Perserikatan Naga Api Jilid 06
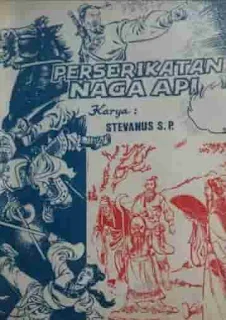
UNTUK sesaat Rahib Hong-tay tercengang oleh permintaan yang mendadak itu. Kemudian ia tertawa dan berkata, “Kenapa nona begitu percaya bahwa aku dapat mendidikmu dalam ilmu silat?”
“Te-cu (murid) percaya bahwa dalam bimbingan Suhu (guru) te-cu akan dapat mempelajari ilmu silat Siau-lim-pay yang terkenal sejak dahulu. Murid sudah melihat sendiri kesaktian dan kebajikan Suhu,” sahut Tong Wi-lian dengan tegas.
Upacara penerimaan murid saja belum terjadi, tetapi gadis itu sudah memanggil “guru” kepada rahib sakti itu, mau tidak mau Hong-tay Hwesio geli dalam hati melihat sikap yang masih agak kekanak-kanakan itu. Namun sekaligus mata batin Hong-tay Hwesio yang tajam itupun dapat melihat semangat dan kekerasan hati yang membaja dari gadis itu. Jauh di hati kecil sang rahib memang sudah timbul rasa sayang kepada gadis yang lugu itu dan ingin mendidiknya sebagai murid.
Tetapi rahib tua itu tidak langsung menyatakan menerima Wi-lian melainkan masih bertanya lagi, “Setelah kau menjadi seorang yang berilmu tinggi lalu kau mau apa?”
Tong Wi-lian agak bingung menjawab pertanyaan itu. Di dalam hatinya bergejolaklah dendam kesumatnya kepada Cia To-bun dan Thio Ban-kiat yang telah menghancurkan ketenteraman hidupnya dan membuat keluarganya jadi tercerai-berai. Tapi hal gejolak dalam hatinya tidak diutarakannya kepada rahib sakti itu.
Tak terduga bahwa mata batin Hong-tay Hwesio ternyata dapat menembus dan menjenguk isi hatinya. Kata Hong-tay Hwesio dengan suara tetap lembut, “Aku melihat hawa dendam menyelubungi air mukamu, pikiranmu pun hanya tertuju kepada pembunuhan dan pembalasan. Kalau benar demikian maka aku tidak dapat menerimamu sebagai muridku. Menurunkan ilmu silat sama dengan memberikan senjata. Aku tidak ingin melihat seorang yang haus darah dan mabuk dendam seperti nona menguasai suatu ilmu silat tinggi. Itu akan sangat membahayakan orang banyak.”
Merah padamlah wajah Tong Wi-lian mendengar kecaman rahib itu, namun gadis itu tetap tidak bangkit dari berlututnya dan wajahnya tertunduk dalam-dalam. Akhirnya ia menyahut juga, “Tetapi bagaimana kalau ada seseorang yang telah membuat keluargaku menjadi porak-poranda? Kami sekeluarga yang tadinya hidup tenteram, berkumpul di bawah satu atap. Kini telah tercerai-berai dan tidak saling mengetahui keberadaan masing-masing?”
Sahut Rahib Hong-tay, “Dalam menghadapi suatu persoalan, kita harus tetap berpikiran jernih dan jangan membiarkan hawa nafsu menguasai pikiran kita. Yang bersalah harus dihukum, biarpun dia merupakan orang yang kita cintai. Dasar penghukuman itu bukan karena kebencian dan pembalasan, namun hanya mencegah agar kepentingan orang banyak tetap terlindungi!”
Hati Tong Wi-lian bergejolak penuh dengan pertentangan batin. Sementara itu Rahib Hong-tay masih terus berkata dengan suaranya yang lembut, “Nona, jika orang yang nona benci itu sudah bertobat, dan tidak lagi merugikan masyarakat, bahkan menjadi orang yang berguna, apakah kau tetap akan membunuhnya?”
Wi-lian tidak dapat langsung menjawab. Ia bertanya kepada diri sendiri, kenapa begitu berhasrat untuk membunuh Cia To-bun? Jawabnya adalah karena Cia To-bun telah menyusahkan keluarganya. Bagaimana kalau kemudian Cia To-bun berubah menjadi seorang yang sangat diperlukan dalam masyarakat? Apakah dia akan tetap membunuhnya meskipun orang banyak akan merasa kehilangan? Apakah dendam keluarganya lebih utama dari kepentingan masyarakat luas?
Namun gadis itu membantah hatinya sendiri, “Bangsat Cia To-bun tidak mungkin berubah menjadi oang baik-baik. Pembunuh-pembunuh bayaran yang baru saja hampir mencelakai aku dan kakakku ini adalah bukti bahwa bangsat itu masih terus memburu kami dan belum puas sebelum keluarga Tong tertumpas habis. Bila tidak ada orang-orang yang menolong kami berdua, mungkin saat inipun kami berdua sudah tidak ada lagi di dunia ini.”
Tengah gadis itu terombang-ambing menemukan jawaban atas masalah yang berkecamuk di dalam hatinya, rahib tua itu telah berkata pula, “Dendam hanya mengotori hati dan pikiran. Pikiran kita yang harusnya jernih, menjadi keruh dan tidak dapat lagi menikmati kehangatan hidup ini. Kita terpencil dari sesama manusia, seperti sebuah pulau di tengah laut. Memang sebagai ahli-ahli silat yang harus mengamalkan ilmunya untuk kepentingan umum, kadang-kadang kami dipaksa melakukan pembunuhan, tetapi hal tu merupakan jalan yang terakhir dan terburuk. Mungkin kita harus membunuh, tapi hal itu karena tidak ada jalan lain, kita terpaksa membunuh seorang atau beberapa orang supaya puluhan atau ratusan orang lainnya tidak menjadi korban. Kau paham asas ini?”
“Te-cu berjanji akan selalu menjunjung tinggi amanat Suhu.”
“Ajaran dari aliran Siau-lim kami mengutamakan welas asih kepada seluruh makhluk hidup. Bukan hanya manusia, bahkan makhluk yang berujud hewan sekalipun. Mengalahkan diri sendiri sebelum menundukkan orang lain. Membunuh atau melukai bukan tujuan, tapi hanya cara untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak. Itupun merupakan cara yang terakhir dan terburuk. Paham?”
Dengan jujur Tong Wi-lian menyahut, “Ajaran seluhur itu terus terang saja masih jauh dari diri te-cu. Namun te-cu berjanji akan berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menjalankan apa yang telah Suhu wejangkan ini.”
Kepala rahib tua yang gundul itu terangguk-angguk sambil tersenyum ketika mendengar ucapan yang terus terang dari Tong Wi-lian. Rahib Hong-tay berkesan bahwa calon muridnya ini seorang yang jujur. Biasanya jika seseorang ditanya tentang kesanggupannya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perguruan.
Maka tanpa pikir panjang dia akan menyatakan kesanggupannya, bahkan dengan kata-kata yang muluk-muluk dan dilengkapi dengan sumpah setia segala, tujuannya tidak lain hanyalah agar cepat diterima dalam perguruan itu. namun tidak sedikit diantara yang melupakan sumpahnya begitu telah lulus dengan bekal ilmu yang tinggi.
Tetapi Rahib Hong-tay yakin akan kejujuran dan ketulusan gadis she Tong itu, maka keluarlah jawaban yang diharapkan Tong Wi-lian sejak tadi, “Baiklah, kau menjadi muridku, meskipun agak janggal nampaknya karena aku seorang rahib dan kau seorang gadis. Asal hati kita bersih dari pikiran busuk, persetan dengan gunjingan orang lain.”
Tak terperikan girangnya gadis itu. Cepat ia menjalankan upacara penghormatan pengangkatan guru, yaitu dengan jalan berlutut dan menyembah sembilan kali di hadapan Suhunya.
Rahib Hong-tay tersenym. Perlahan-lahan ia melangkah ke sebuah pohon yang teduh dan duduk bersila di bawahnya. Katanya, “Sekarang kau tentu tahu apa yang harus kau lakukan, sekaligus aku ingin melihat apakah kau sanggup menunaikan ajaran perguruan atau tidak.” Tanpa menunggu jawaban muridnya lagi, sang rahib lalu memejamkan matanya dan mulai bersemedi.
Tong Wi-lian menjadi heran melihat sikap dan mendengar ucapan gurunya itu. Tanyanya, “Apa yang harus te-cu perbuat?” tetapi pertanyaan itu tidak mendapat jawaban, gurunya telah tenggelam dalam semedinya.
Gadis itu menjadi kebingungan dan menebak-nebak apa yang dimaui oleh gurunya. Dan ketika matanya menyambar sosok-sosok mayat yang bergelimpangan di tempat itu, tiba-tiba terbukalah pikiran Wi-lain. Ia ingat pelajaran welas asih yang baru saja diucapkan gurunya dan telah disanggupinya, dan kini ia harus mewujudkannya dalam perbuatan.
Betapapun jahatnya para berandal suruhan Cia To-bun itu di masa hidupnya, tapi tidak sepatutnya merendahkan hakekat kemanusiaan mereka dengan membiarka tubuh-tubuh mereka tetap bergelimpangan tidak terurus yang akhirnya akan menjadi santapan binatang-binatang liar. Bahkan dalam perang antara dua negara pun ada peraturan-peraturan yang mencoba mempertahankan martabat manusia, meskipun peraturan itu sering dilanggar oleh kedua belah pihak.
Lalu Wi-lian mengambil sebatang golok yang tergeletak diantara mayat-mayat itu dan mulai menggali tanah, membuat sebuah lubang besar untuk menguburkan empatbelas sosok mayat. Pekerjaan itu tentu saja cukup berat buat seorang gadis, meskipun Wi-lian bertubuh kuat dan sudah terdidik ilmu silat sejak kecil, apalagi tanah di pnggir hutan itu ternyata cukup keras pula. Tetapi gadis yang keras hati itu bekerja terus dengan bersemangat dan tanpa mengeluh, bahkan ketika telapak tangannya mulai lecet dan lengannya menjadi pegal, ia tidak berhenti.
Kekuatan cinta kaksih sesama manusia kah yang memberikan kekuatan kepadanya? Atau sekedar ingin mengambil hati calon gurunya supaya mendapat ilmu yang tinggi untuk membalas dendam? Ia sendiri tidak dapat menjawabnya, namun ketika matahari telah tenggelam di sebelah barat maka gadis itu berhasil menguburkan keempatbelas sosok mayat itu secara sederhana tapi layak.
Ketika Tong Wi-lian menoleh ke bawah pohon di mana suhunya duduk, terlihat Rahib Hong-tay telah membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, “Omitohud, muridku yang hebat.”
Sambil mengusap keringatnya, Wi-lian menyahut sambil tersenyum pula, “Sayang, tee-cu agaknya masih belum dapat melakukannya dengan sepenuhnya dilandasi cinta kasih. Tapi lebih banyak didorong maksud untuk menyenangkan hati Suhu saja. Mohon petunjuk Suhu lebih lanjut.”
“Kau cukup jujur dan berani melihat keadaan dirimu secara jujur pula, muridku. Orang yang menyadari bahwa dirinya sedang berjalan di pinggir jurang akan menjadi berhati-hati sehingga tidak terjerumus. Sebaliknya orang yang tidak menyadarinya akan merasa dirinya aman dan dia dengan mudahnya akan terjerumus ke jurang. Tapi jangan buru-buru senang dengan pujianku ini, kau harus berusaha lebih keras lagi untuk membersihkan batinmu.”
Guru dan murid itu kemudian berjalan bersama-sama meninggalkan tempat itu menuju ke arah selatan. Tujuan mereka adalah Gunung Siong-san, tempat letaknya kuil Siau-lim-si yang terkenal itu.
Tiba-tiba Wi-lian bertanya kepada gurunya, “Suhu, aku pernah mendengar berita bahwa kuil Siau-lim punya peraturan keras yang sudah dijalankan selama beratus-ratus tahun, yaitu melarang seorang wanita untuk masuk ke dalam kuil. Benarkah itu, Suhu?”
Rahib Hong-tay menganggukkan kepalanya, “Betul, memang ada peraturan semacam itu. Kaum wanita yang hendak bersembahyang kepada Sang Buddha paling-paling hanya diijinkan masuk sampai ke ruangan sembahyang di bagian depan saja. Sedang bagian dalam kuil merupakan bagian yang tidak dapat dimasuki oleh sembarangan orang, bahkan andaikata dia seorang pria.”
“Kalau tidak dapat masuk ke dalam kuil, bagaimana te-cu bisa belajar ilmu silat?”
Sahut Rahib Hong-tay, “Belajar silat tidak harus di dalam kuil, di udara terbuka malahan lebih segar dan sehat. Di sekitar kuil banyak tempat-tempat sepi yang berpemandangan bagus dan cocok untik tempat berlatih silat. Nanti aku akan memintakan ijin kepada Hong-thio (Ketua Kuil) supaya kau diijinkan tinggal di sekitar kuil. Tergantung kepadamu, apakah kau betah tinggal di tempat sesepi itu sendirian?”
Tanpa pikir panjang lagi Tong Wi-lian menyatakan sanggup hidup dalam kesunyian demi mempelajari ilmu yang tinggi dari rahib sakti itu.
Rahib Hong-tay sebenarnya cukup mengerti bahwa gadis muridnya itu masih memerlukan usaha yang panjang untuk membersihkan batinnya dari sisa-sisa dendam. Maka dalam perjalanannya ke selatan, sengaja diajaknya muridnya itu mengambil jalan memutar, tidak melewati an-yang-shia, supaya muridnya tidak teringat akan dendamnya.
Rahib itu justru mengajak muridnya untuk menyusuri daerah pantai timur. Sepanjang jalan bila ada kesempatan, tidak henti-hentinya Hong-tay Hwesio memberikan wejangan tentang ajaran-ajaran Buddha kepada muridnya. Dan ternyata rahib tua ini bukan cuma pandai mengoceh, melainkan juga memberi contoh dalam perbuatan-perbuatan nyata sepanjang perjalanan.
Dan selama perjalanan itu perlahan-lahan mata batin Tong Wi-lian mulai terbuka dan hatinya semakin tenteram. Sejurus ilmu silatpun ia belum diajari, namun kemajuan batin dan ketenangan yang dicapainya akan sangat berarti dalam melandasi pelajaran ilmu silatnya kelak.
Setelah berjalan beberapa hari, pada suatu hari guru dan murid itu memasuki sebuah kota kecil yang bernama Bun-seng, yang letaknya diperbatasan propinsi Ciat-kang. Kota itu bukan kota besar, luasnya hanya seluas kota An-yang-shia, kota kelahiran Tong Wi-lian. Hanya suasananya agak berbeda. Di kota Bun-seng ini terasa benar suasana kehidupan kaum nelayan.
Tepat ketika Rahib Hong-tay dan Tong Wi-lian memasuki kota nelayan yang kecil itu, kota itu baru saja terguncang hebat oleh suatu peristiwa yang sangat menggangu ketenteraman hidup di kota itu. selama beberapa malam kota Bun-seng berturut-turut telah digemparkan oleh rangkaian pembunuhan yang nekad. Disebut nekad, karena yang dijadikan korban adalah para perwira tentara Kerajaan Beng yang bertugas di kota itu!
Dalam tiga malam berturut-turut, tiga orang perwira telah mati terbunuh, dan mayat mereka dalam keadaan luka arangkranjang telah sengaja “dipamerkan” oleh pembunuh-pembunuhnya dengan diletakkan di tempat-tempat yang ramai!
Kejadian itu merupakan tamparan hebat bagi perwira pemimpin keamanan di kota itu. Segera keluarlah perintahnya untuk menggeledah seluruh kota untuk menemukan pembunuhnya, dan malapetaka buat rakyat kecilpun mulai dari sini. Dalam melakukan penggeledahan, para tentara kerajaan telah menggunakan kesempatan untuk mengisi kantong dengan memeras rakyat, selain itu penggeledahan pun dilakukan secara membabi-buta, sehingga mereka bukan lagi tentara kerajaan tapi lebih tepat disebut perampok-perampok berseragam.
Siapa yang dicurigai langsung diseret keluar dari rumahnya, kecuali yang bisa menyuap prajurit-prajurit itu. Dan celakalah yang tidak bisa menyuap, sebab mereka akan langsung digiring menuju ke penjara kota. Jika sudah begini, maka hanya ada dua kemungkinan buat si korban. Dijebloskan seterusnya dengan tuduhan bersekutu dengan pembunuh setelah melalui sebuah “pengadilan kilat”, dan kemungkinan kedua adalah dibebaskan kembali karena tuduhannya tidak terbukti.
Namun sudah terlanjur kehilangan sebelah mata atau beberapa buah gigi atau cacat lainnya. Dan rakyat tidak bisa menuntut kepada siapapun. Demikianlah gambaran kebobrokan masyarakat di masa pemerintahan Kaisar Cong-ceng. Rakyat tidak punya perlindungan sama sekali. Ibarat domba gemuk yang dikelilingi serigala-serigala kelaparan.
Pada saat Rahib Hong-tay hendak memasuki kota Bun-seng bersama muridnya, merekapun sempat mengalami pemeriksaan oleh beberapa orang tentara kerajaan, untung rahib itu masih punya sisa beberapa tahil perak untuk menyuap tentara-tentara kerajaan itu sehingga bebaslah ia dan muridnya dari segala kerepotan. Tong Wi-lian pun menyamar sebagai laki-laki, sehingga tidak diganggu oleh prajurit- prajurit itu.
Waktu itu adalah tengah hari, di mana matahari tengah bertahta dipuncak langit dan panasnya terasa menyengat kulit. Begitu Rahib Hong-tay masuk ke dalam kota, maka langsung saja mereka menemukan sebuah pemandangan yang menyayat hati. Di tengah jalan raya ada enam orang lelaki yang tengah diseret oleh sepasukan tentara kerajaan. Mereka diseret seperti kambing atau lembu saja layaknya. Dan setiap kali cemeti atau gagang tombak melanda punggung orang-orang celaka itu.
Di belakang rombongan pesakitan itu ada rombongan lain. Mereka adalah sekelompok wanita dan anak-anak yang mengikuti rombongan di depannya sambil meratap tangis. Rupanya mereka adalah anggota keluarga dari orang-orang pesakitan itu. Tapi mereka tidak pernah berhasil mendekati rombongan pesakitan sebab prajurit-prajurit selalu merintangi dengan senjata-senjata mereka, atau dengan kaki-kaki yang ditendangkan.
Sedangkan para pesakitan nampak begitu menderita. Pakaian mereka sudah hancur sehingga terlihatlah punggung mereka yang “dihiasi” jalur-jalur matang biru yang berlumuran darah. Tetapi cambukan-cambukan dan gebukan-gebukan tidak pernah mereda, bahkan semakin gencar mendera punggung orang-orang kecil tersebut. Dan para prajurit pun tertawa-tawa senang, puas, karena berhasil menunjukkan “kegagahan” mereka.
Rahib Hong-tay mengajak muridnya membaurkan diri di antara penduduk kota Bun-seng yang bergerombol di pinggir jalan. Hati Rahib Hong-tay yang penuh welas asih seketika bergetar hebat waktu melihat sesamanya diperlakukan seperti binatang oleh sesama manusia pula. Di dalam hatinya dia berdoa memohon petunjuk Sang Buddha. Tetapi karena rahib itu tidak ingin bertindak sembarangan sebelum mengetahui persoalannya lebih dahulu, maka ia lalu mendekati seorang kakek bongkok di pinggir jalan. Katanya, “Tuan, apakah yang telah terjadi?”
Kakek bongkok itu menarik napas panjang lalu menyahut, “Apakah tay-su belum tahu? Selama beberapa malam berturut-turut ini telah ada tiga orang perwira kerajaan yang dibunuh orang, dan mayat yang dirusak oleh pembunuh-pembunuh itu sengaja diletakkan di tempat-tempat ramai, agaknya memang hendak menentang penguasa. Nah, keenam orang yang sedang diseret oleh prajurit-prajurit itulah yang dituduh sebagai pembunuhnya. Mereka baru saja diadili secara kilat, dan sudah diputuskan hukuman penggal kepala buat mereka. Mereka sedang digiring ke lapangan dekat Tong-mui (gerbang timur) untuk menjalani hukumannya.”
Seorang nenek yang agaknya isteri dari kakek bongkok itu ikut nimbrung dalam percakapan, “Yang kasihan adalah si Ah Beng. Ia baru setahun beristeri dan anaknya pun masih kecil, tetapi sebentar lagi ia akan menjadi setan tanpa kepala. Padahal jelas dia tidak bersalah, tapi sialnya prajurit yang mengeledah rumahnya itu adalah bekas saingan asmaranya dulu. Rupanya prajurit itu masih dendam karena tidak berhasil menggaet perempuan yang sekarang menjadi isteri Ah Beng sehingga kesempatan ini digunakannya untuk menjerumuskan Ah Beng ke dalam kesulitan.”
“Di antara keenam orang itu, yang manakah yang bernama Ah Beng?” tanya Rahib Hong-tay.
Nenek itu agaknya seorang yang suka mengobrol. Dengan bersemangat ia segera menunjukkan jarinya ke arah salah seorang pesakitan sambil berkata, “Yang diseret paling depan itulah. Kemarin dia menyembelih ayam dan lupa membersihkan pisau yang digunakan untuk menyembelih. Tak terduga tadi malam terjadi lagi pembunuhan itu. pisaunya yang berlumuran darah ditemukan oleh prajurit yang menggeledahnya dan segera dijadikan barang bukti. Dasar hakimnya juga malas untuk memeriksa perkara itu secara teliti, maka enak saja diputuskannya hukuman mati buat Ah Beng.”
Mendengar cerita nenek itu, Rahib Hong-tay menarik napas. Semurah itukah nyawa manusia, sehingga dengan seenaknya saja orang dapat dijatuhi hukuman mati tanpa bukti yang kuat? Inikah hukum Kerajaan Beng? Ketika Hong-tay Hwesio menengok ke arah para pesakitan, nampak bahwa Ah Beng itulah yang paling payah keadaannya. Tubuhnya yang selama ini kurus karena hidup dalam kemiskinan, kini babak-belur dihujani deraan para prajurit. Mukanya yang sudah pucat menyeringai menahan kesakitan yang luar biasa.
“Ampunilah aku tuan-tuan,” ratapnya dengan suara lemah. “Aku hanyalah seorang yang lemah dan tidak mengerti ilmu silat, bagaimana aku berani melakukan pembunuhan terhadap para tay-jin? Ampun tuan...”
Seorang tentara kerajaan yang berkumis kaku seperti ijuk segera menggampar muka Ah Beng sehingga kepala Ah Beng bagai disentakkan ke belakang dengan mulut berlumuran darah. Masih belum puas, ia menginjak dada Ah Beng yang kurus kering sambil membentak dengan bengisnya, “Kau kira kau dapat menipu kami?! Jelas di rumahmu ada bukti kuat berupa pisau yang berlumuran darah! Lebih baik kau mengaku saja di mana tempat sembunyinya kawan-kawanmu supaya hukuman matimu dapat dijalankan dengan cepat tanpa siksaan macam-macam!”
Seorang perempuan yang masih cukup muda dan menggendong seorang bayi berumur beberapa bulan segera menerjang maju dan berlutut di depan prajurit yang berkumis kaku itu sambil meratap, “Ciu toako, harap sudilah kau mengingat persahabatan kita di masa lalu. Ah Beng toako benar-benar tidak melakukan pembunuhan, semalam dia berada di dalam rumah terus dan tidak melangkah keluar pintu setapakpun. Aku berani bersumpah tentang hal ini, ampunilah dia...”
Begitu diingatkan akan “persahabatan masa lalu” seketika si prajurit berkumis kaku itu justru semakin tersinggung. Sejenak prajurit itu memandang isteri Ah Beng dengan liarnya. Tiba-tiba dia menyeringai lalu tangannya mengusap dagu perempuan itu sambil berkata,
“A-giok, ternyata kau masih cantik juga meskipun si bangsat buduk ah Beng ini tidak mampu membelikan pakaian bagus untukmu. Kau harus mengerti bahwa meskipun kini kita sama-sama telah berkeluarga tetapi aku masih sering teringat kepadamu. Andaikata dulu kau terima lamaranku, sekarang tentu kau akan mengalami hidup senang dan tidak tersangkut perkara ini. Tapi nanti setelah pelaksanaan hukuman mati ini, kau masih boleh tinggal di rumahku sebagai isteri kedua. Setuju?”
Dan tingkah prajurit yang dipanggil Ciu toako itu kemudian benar-benar tidal peduli bahwa ia sedang berada di tengah jalan raya, dan ada ratusan mata sedang memandangnya. Dengan seenaknya saja ia memegang tubuh isteri Ah Beng, bahkan kemudian memeluk dan menciumi mukanya. Perempuan itu berusaha meronta dan melepaskan dirinya, sedangkan bayi dalam gendongannya menangis keras karena terhimpit oleh tubuh prajurit yang besar dan berbau keringat tersebut.
Prajurit she Ciu itu agaknya merasa sangat terganggu oleh tangisan si bayi. Dengan kasar ia merenggut si bayi dari pelukan ibunya lalu dibantingnya ke tanah! Bayi tak berdosa itu jatuh terbanting dengan kepala mengenai tanah lebih dulu, tak ampun lagi, tangisnya pun berhenti untuk selama-lamanya.
Sang ibu jadi kaget sekali. Ia menubruk mayat bayinya sambil berteriak-teriak dengan kalapnya, bagaikan gila ia memanggil-manggil nama bayinya yang lucu yang sekarang tidak mampu menjawab lagi. Penduduk kota Bun-seng yang melihat kejadian itu segera membuang muka dengan perasaan sangat muak dan pedih. Tetapi tak seorangpun ingin mempertaruhkan nyawa dengan menentang tingkah laku prajurit-prajurit yang kesetanan itu.
Tong Wi-lian yang ikut berjubel diantara kerumunan orang menggertakkan giginya dan mukanya menjadi merah padam karena marah melihat kesewenang-wenangan alat-alat negara itu. Ketika gadis itu menoleh ke arah gurunya, nampaklah wajah Sang guru tidak ada kemarahan sedikitpun, ia hanya memejamkan mata dengan setitik air bening tergantung di sudutnya.
“Suhu, kita harus bertindak, tindakan para prajurit ini benar-benar keterlaluan,” desis Tong Wi-lian sambil menarik tangan gurunya.
Namun Rahib Hong-tay masih juga ragu-ragu untuk turun tangan sebab masih dibebani berbagai pertimbangan. Ia menyadari bahwa daerah itu sudah cukup dekat dengan Gunung Siong-san, tempat berdirinya pusat perguruan Siau-lim-pay yang terkenal. Jika dia memunculkan dirinya di tempat itu dengan jubah paderinya yang mencolok, maka orang akan langsung meghubungkannya dengan Siau-lim-pay, dan itu berarti dia melibatkan seluruh anggota Siau-lim-pay dengan permusuhan melawan pemerintah Kerajaan Beng.
Pertimbangan lainnya adalah bahwa andaikata ia berhasil menyelamatkan sebuah nyawa, tapi tentara kerajaan yang marah itu tentu akan menimbulkan malapetaka yang lebih hebat lagi bagi rakyat banyak. Meskipun hatinya sudah sangat muak melihat kekejaman itu, namun ia masih mampu berfikir panjang dengan memikirkan keselamatan orang banyak. Sedangkan pertimbangan semacam itu tidak ada dalam diri muridnya yang hanya sekedar menuruti perasaan marahnya yang bergejolak.
Dalam pada itu, pesakitan yang bernama Ah Beng timbul keberaniannya setelah melihat keluarganya diperlakukan sewenang-wenang oleh prajurit-prajurit kerajaan. Teriaknya dengan marah, “Anjing-anjing keparat! Kenapa kau bunuh bayi yang sama sekali belum tahu apa-apa! Kalian benar-benar berhati binatang dan berjantung anjing... aaaah!”
Ah Beng sama sekali tidak sempat menyelesaikan kalimat makiannya sebab prajurit she Ciu telah menjadi marah dan tanpa kenal kasihan telah menusukkan tombaknya ke perut bekas saingan asmaranya tersebut. Ah Beng berteriak kesakitan dan roboh disamping tubuh bayinya. Setelah berkelojot sebentar, diapun terdiam untuk selamanya.
Betapapun sabarnya Rahib Hong-tay, dan betapapun macamnya pertimbangan dalam hatinya, akhirnya mendidih juga darah kesatrianya ketika melihat kebiadaban yang berlangsung di depan matanya. Tangannya segera merogoh kantong jubahnya dan menggenggam segenggam uang logam yang siap ditaburkan ke arah prajurit-prajurit tidak berprikemanusiaan itu. Sementara itu Tong Wi-lian pun sudah gatal tangan dan tangannya pun sudah terkepal kencang.
Tetapi sebelum guru dan murid itu bertindak, ternyata sudah ada pihak lain yang mendahului memberi hajaran kepada prajurit-prajurit tersebut. Entah dari mana datangnya, dan hanya terdengar suara berdesing, tahu-tahu sebatang anak panah telah menancap di tenggorokan prajurit she Ciu yang kala itu sedang tertawa-tawa kesenangan.
Mendadak ia nampak melotot kaget dan kesakitan, tangannya mengapai-gapai kian kemari seolah orang yang hendak tenggelam sedang mencari pegangan. Ketika roboh ke tanah ia masih sempat mengeluarkan suara-suara sekarat dari tenggorokannya, lalu nyawanyapun amblas.
Semua orang menjadi terkejut dan panik melihat perkembangan yang tak terduga-duga itu. Tidak terkecuali Rahib Hong-tay dan muridnya meskipun mereka tidak sepanik orang lain. Belum lagi kekegetan orang banyak menjadi reda, sekali lagi seorang tentara kerajaan menjerit keras sambil memegangi dadanya yang tertancap anak panah.
Sebelum roboh ia sempat berteriak ketakutan, “A... ada pem... bu... bunuh gelap...!!”
Penduduk kota kecil yang sedang berjejal di pinggir jalan itupun segera bubar ketakutan seperti gabah ditampi. Mereka harus cepat-cepat meninggalkan tempat itu sebelum ditangkap dan dituduh membunuh prajurit kerajaan, dan kemudian mengalami nasib seburuk Ah Beng.
Sedangkan prajurit-prajurit kerajaan itu telah berpencar sambil berteriak, “Tangkap pembunuh!”
Dalam keadaan sekacau itu, Rahib Hong-tay sempat menyambitkan segenggam uang logam yang telah dipersiapkannya sejak tadi. Namun kini tidak diarahkan kepada para prajurit, melainkan kepada belenggu yang membelenggu para pesakitan. Di sini terlihatlah kepandaian Rahib Hong-tay, sebab uang-uang logam tersebut dengan tepat dapat memutuskan tali-tali yang mengikat para pesakitan tanpa melukai kulit mereka. Dan dalam keadaan hiruk-pikuk seperti itu ternyata incarannya tidak meleset sedikitpun. Para pesakitan itupun tidak melewatkan kesempatan baik dan segera melarikan diri semuanya.
Setelah membebaskan para pesakitan dari jarak jauh, rahib itu segera mengajak muridnya untuk membaurkan diri dengan orang-orang yang sedang panik. Mereka berdua mencari persembunyian yang baik untuk menonton kejadian selanjutnya.
“Bagaimana sekarang sikap kita, Suhu?” tanya Tong Wi-lian sambil berlari-lari mengikuti gurunya.
“Kita tidak perlu menonjolkan diri,” kata gurunya. “Agaknya sudah ada pihak lain yang berniat untuk mencegah kebiadaban prajurit-prajurit itu. Kita hanya akan melihatnya dari kejauhan dan kemudian menentukan langkah kita selanjutnya.”
“Bagaimana kalau kita langsung membantu saja pemanah-pemanah tersembunyi itu?” usul Wi-lian dengan penuh semangat.
“Jangan gegabah, kita belum tahu apakah pemanah-pemanah gelap itu dari pihak yang bermaksud baik atau justru sebaliknya.”
Sebentar saja jalan raya yang terletak membujur di tengah-tengah kota Bun-seng itu telah menjadi sepi. Di tengah jalan kini hanya ada mayat Ah Beng beserta mayat bayinya serta mayat dua orang prajurit yang mati konyol oleh pemanah gelap. Isteri Ah Beng sudah diselamatkan oleh salah seorang penduduk yang baik hati.
Para prajurit yang lain pun tidak nampak lagi di tengah jalan raya, sebab mereka tidak ingin menjadi sasaran empuk para pemanah gelap. Prajurit-prajurit tersebut telah menyusup ke dalam lorong-lorong disekitar tempat kejadian dan berusaha mencari dan menangkap si pemanah gelap. Rahib Hong-tay dan muridnya bersembunyi di balik setumpuk anyaman bambu, dan dengan cermat memperhatikan suasana.
Pada jaman itu memang sudah timbul rasa ketidak-puasan rakyat terhadap pemerintahan Kaisar Cong-ceng yang lemah dan tidak adil. Aliran Siau-lim-pay sebagai perguruan yang terbesar di Tiongkok mau tidak mau pasti akan terlibat setiap perkembangan yang menyangkut rakyat banyak, sebab sudah sejak lama murid-murid Siau-lim-pay dikenal sebagai pendekar-pendekar pembela rakyat yang tertindas. Kini Rahib Hong-tay ingin tahu pihak manakah yang telah berani menentang pihak tentara kerajaan secara terang-terangan tersebut.
Tengah ketegangan mencekam di semua sudut, tiba-tiba dari atas genteng sebuah rumah di pinggir jalan, terlemparlah sebuah benda besar ke tengah-tengah jalan. Setelah jatuh ternyata “benda” itu adalah mayat berseragam prajurit Kerajaan Beng dengan leher yang telah tergorok hampir putus. Ketika Wi-lian memperhatikan dengan seksama, ternyata prajurit itu termasuk kelompok yang menyiksa kaum pesakitan tadi. Rupanya dia mencoba menyelidiki ke atas genteng, tapi di balik wuwungan itu dia dibantai oleh pembunuh gelap yang bersembunyi.
“Celakalah pemilik rumah itu,” desis Wi-lian perlahan. “Pasti besok pagi ia akan dituduh berkomplot dengan penjahat, nasibnya pun akan menjadi sangat buruk.”
Sementara itu prajurit-prajurit lain agaknya masih bersembunyi belum jauh dari tempat itu, dan mereka masih dapat melihat mayat kawan mereka yang dilemparkan dari atas genteng tadi. Diam-diam nyali para prajurit itu mulai menciut. Mereka garang dan galak terhadap rakyat lemah yang tidak bersenjata, namun terhadap pembunuh-pembunuh yang masih belum menampakkan diri, mereka mulai merasa agak gentar.
Seorang prajurit yang bernyali agak kecil berlindung di belakang sebuah tempayan air. Ia sedang memandang mayat kawannya itu dengan lutut gemetar. Dan dia bertambah gemetar ketika melihat sesosok bayangan hitam telah berdiri dibelakangnya. Sesosok tubuh yang berpakaian serba hitam dan mukanya tertutup kedok kain hitam pula. Hanya sepasang matanya yang setajam pisau itu tengah menatap prajurit tersebut.
“Sss... sia... pa... kkk... kau?” tanya prajurit tersebut dengan tergagap sambil mencoba mencabut pedang tang tergantung di pinggangnya. Aneh, biasanya ia cukup tangkas mencabut pedang untuk menggertak dan menakut-nakuti rakyat, namun kini tangannya terasa lemas sehingga sekian lama dia belum juga berhasil mencabut pedangnya.
Orang berkedok itu sama sekali tdak menjawab. Jawabannya adalah menggerakkan pedang pendek yang dipegangnya, dan sekali tusuk saja amblaslah pedangnya di jantung prajurit sial itu. ketika ia menarik kembali pedangnya, prajurit itu langsung roboh dengan sebuah luka menganga di dadanya. Lelaki berkedok segera mencengkeram mayat prajurit tersebut dan melemparkannya ke tengah jalan. Kemudian dia sendiri dengan tenangnya melangkah ke tengah jalan dan berdiri tegak di sana, matanya menyapu ke empat penjuru dengan garangnya.
Melihat si pembunuh telah keluar dari persembunyiannya, para prajurit pun segera berlompatan keluar dari tempat perlindungan masing-masing dan langsung mengurung orang berkedok tersebut.
Orang berkedok itu nampak tenang-tenang saja menghadapi kepungan para prajurit. Tiba-tiba ia menggerakkan pedang pendeknya dengan gerakan seperti orang memberi aba-aba. Begitu gerakan selesai, bermunculanlah belasan orang lelaki berkedok dari tempat persembunyian mereka masing-masing. Mereka muncul dari loteng-loteng di pinggir jalan, lorong lorong sempit di pinggr jalan, dari dalam parit saluran air kotor dan bahkan ada yang muncul dari dalam tumpukan sampah.
Mereka muncul bagaikan hantu-hantu di siang hari dan langsung menyergap ke arah para prajurit. Karena sergapan mendadak ini, para prajurit menjadi panik dan beberapa prajurit langsung menjadi korban sia-sia. Untunglah bahwa para prajurit kerajaan itupun merupakan orang-orang yang cukup terlatih. Salah seorang yang berpangkat paling tinggi segera mengambil pimpinan dan berseru agar kawan-kawannya jangan bingung dan melawan dengan tenang. Teriaknya,
“Semuanya tetap di sini untuk menghadapi para pengacau ini. Salah seorang pergilah ke tangsi untuk memanggil bala bantuan! Cepat!”
Prajurit yang ditunjuk untuk memanggil bala bantuan segera berlari meninggalkan tempat itu. Tetapi ia hanya sempat berlari belasan langkah, sebab seorang berkedok telah muncul dari balik genteng di pinggir jalan dan langsung menembakkan panahnya. Prajurit itu langsung roboh terjungkal dengan punggung tertancap anak panah.
Dalam pada itu gerombolan orang berkedok telah bertempur sengit dengan pasukan kecil prajurit kerajaan. Setelah para tentara kerajaan itu dapat bertempur dengan tenang dan tidak gugup lagi, tampaklah bahwa mereka lebih terlatih dan lebih berpengalaman dibandingkan lawan-lawan mereka. Jumlah tentara kerajaan itu pun hampir tiga kali lipat dari lawan-lawannya sehingga keadaanpun kini berbalik, kini orang-orang berkedoklah yang terkepung dan terjepit.
Kalau pada permulaannya serangan orang-orang berkedok itu berhasil mengurangi beberapa orang tentara kerajaan, hal itu hanyalah disebabkan oleh serangan mereka yang mendadak dan tidak terduga. Tetapi sekarang setelah kedua belah pihak berhadapan dan telah sama-sama siap, terlihatlah bahwa orang-orang berkedok itu tidak terlalu tangguh sehingga mereka mulai terdesak.
Sebagian prajurit memakai senjata pedang dan perisai, sebaliknya orang-orang berkedok itu rata-rata hanya bersenjata belati atau pedang pendek, yaitu jenis-jenis senjata yang mudah disembunyikan dalam baju. Meskipun demikian orang-orang berkedok tersebut melawan dengan gigih. Beberapa prajurit telah roboh tewas atau luka-luka, namun diantara orang berkedok itupun ada yang roboh dan tewas.
Namun ada seorang berkedok yang paling menonjol kepandaiannya, yaitu orang berkedok yang tadi muncul pertama kali ditengah jalan. Ia bertubuh tinggi semampai dan berpundak cukup tegap, meskipun tidak terlalu besar. Ilmu silatnya pun tampak paling lihai, terbukti dengan permainan pedangnya yang lincah dan mantap. Untuk membendung amukan orang ini, pihak tentara kerajaan harus menggabungkan tenaga lima orang prajurit, barulah dapat melawannya dengan seimbang. Tetapi orang itupun melawan dengan garang seperti harimau terluka.
Dari tempat persembunyiannya, Rahib Hong-tay dan muridnya mengawasi jalannya petempuran dengan cermat. Tong Wi-lian semakin lama semakin tertarik melihat permainan pedang si orang berkedok. Ia pun merasa sudah sangat mengenal bentuk tubuh dan gerak-gerik orang itu. Ya, bahkan ia mengenalnya sejak kecil! Karena tidak dapat menahan diri lagi, ia lalu berbisik kepada gurunya,
“Suhu, orang berkedok yang tinggi semampai itu memainkan ilmu pedang Soat-san-pay!”
Rahib Hong-tay mengiakan, “Ya, akupun melihatnya. Tetapi itu bukan hal yang aneh. Soat-san-pay adalah sebuah perguruan yang cukup besar dan mempunyai banyak murid, meskipun letak perguruan itu jauh di perbatasan barat, tapi apa sukarnya jika salah seorang muridnya hendak berkeliaran di daerah Tiong-goan ini?”
“Tetapi te-cu seakan-akan sangat mengenal orang itu,” sahut Wi-lian dengan agak ragu-ragu.
Suara gemerincing senjata beradu bercampur aduk dengan dengus kesakitan atau teriakan perang penuh dendam terdengar makin riuh di tempat itu, semakin lama semakin ribut. Pemanah yang bersembunyi di atas genteng rumah di pinggir jalan kembali telah “menjemput” beberapa nyawa prajurit kerajaan. Basanya yang diincar adalah prajurit yang mencoba meninggalkan tempat pertempuran untuk memanggil bala bantuan. Incarannya ternyata selalu jitu dan tidak pernah meleset.
Tetapi pemanah di atas genteng itu kemudian semakin berani memunculkan dirinya, dan datanglah nasib sialnya. Ketika si pemanah sedang berjongkok di atas genteng untuk menunggu korbannya, seorang prajurit berhasil melemparkan lembing yang tepat menancap di data si pemanah. Sambil menjerit kesakitan, si pemanah itupun roboh dari atas genteng dan terbanting di tanah.
Namun prajurit yang melempar lembing itupun juga mengalami nasib buruk, sebab seorang lawannya berhasil membenamkan sepasang belati ke lambungnya dan merobeknya. Prajurit itupun ambruk ke tanah, menambah jumlah deretan korban yang sudah cukup banyak.
Rahib Hong-tay yang berhati lembut itu hampir-hampir menangis melihat sesama manusia saling bunuh seperti binatang buas di padang liar saja. Bahkan lebih kejam dari binatang, sebab binatang hanya membunuh untuk membela diri atau untuk mengisi perut, namun manusia membunuh hanya semata untuk kepuasan diri sendiri.
Korban yang terluka atau tewas terus bertambah di kedua belah pihak. Tetapi hal tersebut tidak mematahkan kebuasan orang-orang itu, justru malah semakin bertambah buas dan kalap. Kawanan orang berkedok yang tadinya berjumlah belasan orang, kini telah hampir habis. Mereka kini tinggal berempat, termasuk orang berkedok yang memainkan ilmu pedang Soat-san-pay. Merekalah yang masih bertahan dengan gigihnya melawan tekanan tentara-tentara kerajaan.
Sementara itu Rahib Hong-tay mulai mempertimbangkan untuk turun tangan. Tapi ia masih berpikir apakah turut campur dirinya itu akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak atau justru akan menambah jumlah korban? Sebagai manusia biasa, rahib itupun mempunyai perasaan berpihak. Di dalam hatinya ia sudah berpihak kepada orang-orang berkedok, Sebab dengan mata kepalanya sendiri ia telah menyaksikan kekejaman yang memuakkan dari tentara-tentara kerajaan.
Dalam pada itu, orang berkedok yang bertubuh tinggi semampai telah mulai melihat kesulitan yang membayang bagi pihaknya. Ia segera mengeluarkan suitan nyaring, mengisyaratkan kawan-kawannya agar mengundurkan diri dari gelanggang.
Namun prajurit-prajurit yang sudah dirasuk dendam karena telah kehilangan beberapa orang kawan itu tentu saja tidak membiarkan orang-orang berkedok itu kabur begitu saja. Seorang prajurit yang berpangkat paling tinggi segera mengejek dengan suara dingin,
“Hemm, saat ini tidak ada selubang jarumpun yang dapat kalian gunakan untuk menyelamatkan diri. Kalau ingin meraka memang bisa, dan pedangku ini sanggup untuk mengantarkan kalian.”
Tong Wi-lian yang juga punya perasaan berpihak kepada orang-orang berkedok itu, terutama kepada orang yang memainkan ilmu pedang Soat-san-pay, segera membisiki gurunya, “Suhu, cepatlah bertindak sebelum orang-orang berkedok itu tertumpas habis. Mereka bertindak demikian untuk menentang kezaliman.”
Rahib Hong-tay memang sudah memutuskan untuk membantu orang-orang berkedok itu secara diam-diam, karena dianggapnya orang-orang berkedok itu sebagai orang-orang gagah berani yang berani menentang tindakan kejam tentara kerajaan. Tapi rahib itu masih belum berniat untuk membunuh tentara-tentara itu, hanya berniat melumpuhkannya saja. Dengan demikian akan memberi kesempatan kepada orang-orang berkedok itu untuk melarikan diri.
Setelah mengincar sasarannya baik-baik, Rahib Hong-tay lalu menaburkan seraup uang logam yang sudah digenggamnya sedari tadi. Kepingan-kepingan uang logam yang nampaknya ditabur sembarangan itu ternyata dapat “memilih” sasarannya sendiri-sendiri dengan tepat, dan semuanya tepat mengenai lutut para prajurit kerajaan!
Hampir bersamaan para prajurit itu menjerit kesakitan dan roboh serentak ketika uang-uang logam yang disambitkan Hong-tay Hwesio mengenai sambungan lutut mereka. Mereka menjadi kalang-kabut dan sama sekali tidak tahu sebab kaki mereka mendadak menjadi lemas.
Keinginan Hong-tay Hwesio adalah agar supaya orang-orang berkedok itu cepat-cepat melarikan diri sehingga korban yang lebih banyak dapat dikurangi. Namun ternyata keinginan yang mulia itu tidak sesuai dengan kenyataan. Orang-orang berkedok tidak melarikan diri selagi para prajurit roboh, malahan dengan kebencian yang semakin meluap mereka membabat habis prajurit-prajurit kerajaan tanpa kenal ampun.
Terdengar jerit kematian berturut-turut. Dalam sekejap saja, sisa-sisa prajurit kerajaan yang masih hidup telah tertumpas habis tanpa sisa. Jalan raya yang lengang itu kini penuh dengan bangkai manusia yang malang-melintang.
Baik Rahib Hong-tay maupun Tong Wi-lian sama sekali tidak menduga akan sikap orang-orang berkedok yang menyalah-gunakan pertolongan itu. Rahib Hong-tay membantu orang-orang itu karena muak melihat kekejaman tentara kerajaan, tapi ternyata orang-orang berkedok itupun merupakan manusia-manusia yang tak kalah buas dan liarnya denga para tentara kerajaan. Mereka sama sekali tidak membiarkan satupun prajurit hidup.
Rasa simpati yang sempat timbul dalam hati Rahib Hong-tay dan muridnya sirnalah sudah. Namun dalam pada itu Tong Wi-lian merasa semakin mengenal orang berkedok yang tinggi semampai. Ingatannya semakin lama semakin tajam dan mulutnya hampir saja meneriakkan sebuah nama.
Gerombolan orang berkedok yang tinggal empat orang itu berdiri bertolak pinggang di tengah jalan, di antara mayat-mayat lawan mereka, seakan sedang memuaskan diri menikmati kemenangan mereka. Kemudian terdengarlah orang yang bertubuh tinggi semampai itu berkata kepada teman-temannya,
“Kita tinggalkan tempat ini secepatnya sebelum anjing-anjing Kaisar lainnya membanjiri tempat ini!”
Keempatnya segera mengambil kuda-kuda tunggangan mereka yang disembunyikan di lorong-lorong sekitar tempat itu. Tak lama kemudian mereka telah berada di punggung kuda masing-masing dan segera memacunya menuju ke arah barat kota Bun-seng.
Saat itulah Tong Wi-lian tidak ragu lagi akan orang yang bertubuh tinggi semampai itu. Kini dia ingat orang itu, apalagi setelah mendengar suaranya, jika tadi dia masih ragu-ragu itu disebabkan karena orang ini namapak agak kurus dibandingkan dulu. Orang itu tidak lain adalah Tong Wi-siang, kakaknya yang tertua, yang sudah setengah tahun lebih meninggalkan An-yang-shia karena terlibat pembunuhan seorang pejabat hukum dari Pak-khia.
Tanpa dapat menahan diri lagi, Tong Wi-lian segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan mengejar ke arah larinya orang-orang berkuda itu sambil berteriak memanggil nama kakaknya, “A-siang! A-siang!”
Keempat penunggang kuda itu sudah berada belasan tombak jauhnya dari tempat pertempuran, ketika gadis itu memanggil-manggil nama kakaknya. Tapi pemimpin gerombolan yang bertubuh tinggi semampai itu sempat mendengar teriakan Wi-lian dan sempat menolehkan kepala. Ia nampak ragu-ragu sejenak, tapi kemudian ia menggertakkan gigi, mengeraskan hatinya dan lalu memacu kudanya lebih cepat lagi.
Tong Wi-lian yang berlarian mengejar tak dihiraukan lagi. Sebaliknya Wi-lian bagai kalap mengejar kakak tertuanya yang telah lama tak pernah bertemu. Sekuat tenaga ia terus berlari mengejar sambil memanggil “A-siang” berulang kali. Namun mana bisa ia menandingi kecepatan lari kuda? Dalam sekejap saja bayangan keempat ekor kuda itu semakin mengecil, semakin kabur dan akhirnya lenyap dengan hanya meninggalkan debu kuning yang mengepul.
Bagai hilang kesadaran, Wi-lian terus mengejar sampai ke batas kota hingga akhirnya dia putus asa, batinnya telah terpukul begitu hebat hingga iapun jatuh terkulai dan pingsan. Untung Hong-tay Hwesio segera menolongnya, dan dengan bantuan beberapa orang penduduk yang baik hati, mereka berhasil menyadarkan dan menghibur gadis itu.
Sebelum meninggalkan kota Bun-seng, Rahib Hong-tay telah menguras seluruh isi kantongnya hingga tak tersisa sepeserpun, lalu dititipkan kepada salah seorang penduduk Bun-seng agar diserahkan kepada keluarga Ah Beng yang masih hidup.
Setelah Tong Wi-lian sadar kembali, maka guru dan murid itupun melanjutkan perjalanannya menuju Kuil Siau-lim-pay di bukit Siong-san yang sudah tidak jauh lagi.sejak hari itu Tong Wi-lian nampak agak murung dan tidak seriang biasanya. Rupanya dia sangat menyesal karena tidak sempat menemui kakak tertuanya.
Bahkan dia pun menyesal melihat tingkah laku kakaknya yang ada gejala-gejala akan menjadi sesat. Dulu kakaknya sudah cukup bengal dan nakal, dan kini setelah berpisah dengan keluarganya agaknya dia semakin berani membuat kekacauan.
Meskipun hatinya risau, untunglah Wi-lian bukan jenis gadis yang cengeng. Peristiwa yang dialaminya di kota Bun-seng justru semakin mengobarkan semangatnya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dikuil Siau-lim-si. Dan setelah membekal ilmu yang dapat diandalkan, barulah dia akan dengan leluasa mencari keluarganya yang tercerai-berai untuk dikumpulkan kembali.
Empat orang lelaki tegap penunggang kuda tengah berpacu di tengah padang gersang yang tanahnya berwarna kuning kecoklatan. Kota Bun-seng, kota di mana mereka berempat baru saja menimbulkan kegemparan, sudah jauh tertinggal di belakang mereka. Penunggang-penunggang kuda itu adalah para lelaki muda yang semuanya berwajah garang dan tidak terawat. Mereka adalah sisa kelompok yang selalu diburu dan bahkan tidak jarang hampir tertumpas.
Yang berkuda paling depan adalah lelaki bertubuh tinggi semampai yang merupakan pemimpin kelompok. Umurnya baru sekitar 25 tahun tetapi nampak seperti berumur 40 tahun sebab kumis dan jeggotnya yang tidak pernah dicukur itu telah tumbuh serabutan. Wajahnya sebenarnya cukup tampan, namun nampak keruh dan ganas, bahkan sinar matanya menampilkan pula sifat-sifatnya yang liar. Di bukan lain adalah Tong Wi-siang, kakak dari Tong Wi-hong dan Tong Wi-lian, putera tertua mendiang Kiang-se-tay-hiap Tong Tian.
Ketika merasa telah cukup jauh dari kota Bun-seng dan cukup aman, Tong Wi-siang lalu memberi isyarat kepada tiga orang kawannya untuk memperlambat lari kuda mereka. Lalu mereka memperlambat lari kudanya dan berkuda perlahan-lahan sambil membisu seribu bahasa. Wajah mereka masih melukiskan ketegangan yang baru saja mereka alami di Bun-seng.
Bagaimana tidak merasa tegang, kalau menyadari bahwa “permainan” yang baru saja mereka lakukan itu ternyata berakibat sedemkian hebat sehingga belasan orang kawan mereka terpaksa ditinggal sebagai mayat-mayat di Bun-seng. Sedang mereka sendiri pun hampir-hampir tidak bisa lolos dari lubang jarum.
Wi-siang sendiri berkuda paling depan, pandangan matanya yang kosong-melompong menatap ke depan. Anak muda berhati sekeras besi dan kenyang dengan pengalaman-pengalaman berbahaya itu ternyata sedang gundah hati. Tadi sebelum meninggalkan kota Bun-seng telinganya mendengar seorang gadis memanggil-manggil namanya sambil berlarian. Gadis itu adalah adiknya, yang meskipun sering bertengkar dengannya karena sama-sama berwatak keras, namun juga sangat disayanginya.
Tadi, ketika sang adik mengejarnya, alangkah rindunya Tong Wi-siang sehingga berniat untuk melompat turun dari kudanya dan memeluk adiknya, tetapi keadaan telah memaksanya untuk berbuat lain. Wi-siang sadar bahwa jika sampai tempat itu dikepung oleh prajurit-prajurit kerajaan dalam jumlah besar, maka tiada harapan lolos lagi baginya dan bagi kawan-kawannya. Karena itulah dia mengeraskan hati dengan tidak menghiraukan sama sekali seruan adiknya, meskipun saat itu hatinya bagaikan tersayat-sayat.
Dalam hatinya yang sekeras batu ternyata bisa juga timbul rasa penyesalan. Tadinya keluarganya hidup tenteram di An-yang-shia, namun kini telah berantakan dan terpencar-pencar tidak keruan lagi. Tong Wi-siang merasa sangat menyesal karena merasa bahwa dirinyalah yang menyebabkan semua kehancuran itu, sifat bengalnyalah yang menjadi biang keladi semua malapetaka itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur, waktu terus berjalan ke depan, dan Wi-siang tidak akan mampu memutar roda waktu agar balik seperti semula.
Sambil berkuda perlahan, dia mulai melamun membayangkan masa kecil dan masa menjelang dewasanya. Waktu itu dia merupakan pelindung bagi kedua adiknya, meskipun kedua adiknya bukan merupakan anak-anak yang cengeng. Bahkan Tong Wi-siang berani berkelahi dengan siapapun demi melindungi adaik-adiknya. Ketika menginjak masa remaja, mulailah ia mendapatkan kawan-kawan yang bertabiat buruk yang sedikit demi sedikit mulai mempengaruhi sifat-sifat Wi-siang.
Ia mulai menjadi seorang anak yang tidak betah diam di rumah untuk berkumpul bersama keluarga, dia lebih senang bersama dengan kawan-kawannya, bergerombol di tempat-tempat ramai di an-yang-shia. Ia dan kawan-kawannya senang membuat kekacauan yang dianggapnya sebagai tanda “kejantanan” mereka. Berjudi, berkelahi, makan-minum tanpa membayar, dan sebagainya.
Bahkan kemudian ia menjadi yang paling menonjol sehingga diangkat menjadi pemimpin anak-anak bengal itu. Puncak kenakalan mereka adalah ketika mereka memutuskan untuk menyerang serombongan pejabat pemerintah dari Pak-khia karena bujukan salah seorang dari mereka yang ingin membalas dendam sakit hati ayahnya.
Sejak saat itu tertutuplah kemungkinan bagi Wi-siang dan gerombolannya untuk pulang ke An-yang-shia. Mereka menjadi buronan pemerintah kerajaan Beng, berlari dan bersembunyi dari tempat satu ke tempat lainnya. Tidak jarang mereka harus bertempur dengan kelompok-kelompok prajurit kerajaan atau melawan pemburu-pemburu upahan Cia To-bun.
Pada suatu hari, Tong Wi-siang tidak dapat menahan diri lagi dan ingin menjenguk keadaan rumahnya. Teman-temannya pun mendukung rencana itu, sebab teman-teman Wi-siang itupun merupakan anak-anak kelahiran an-yang-shia dan masih punya keluarga di An-yang-shia. Namun alangkah sedih dan murkanya anak-anak muda itu setelah menjumpai rumah mereka dalam keadaan menjadi puing atau sudah kosong. Bahkan ada yang seluruh keluarganya telah ditangkap dan entah dibawa kemana.
Tong Wi-siang sendiri menemui rumahnya dalam keadaan sudah menjadi puing-puing yang dihuni binatang-binatang liar. Agak jauh dari rumahnya ia menemukan segunduk kuburan tanpa nama yang hanya ditandai dengan sebatang pedang, tetapi Wi-siang tahu bahwa kuburan itu adalah kuburan ayahnya sebab ia mengenal pedang ayahnya itu. Di depan makam itulah Tong Wi-siang berlutut dan menangis meluapkan penyesalannya, sekaligus menyulut api dendam buat dirinya sendiri.
Lalu bersama kawan-kawannya yang juga sedang gelap pikiran, anak-anak muda yang nekat itu menyerbu rumah Cia To-bun. Tapi kedatangan mereka bagaikan serombongan serangga yang menubruk nyala api. Bukan saja mereka berhasil diusir oleh pengawal-pengawal Cia To-bun, bahkan gerombolan mereka pun kehilangan separuh dari anggota mereka setelah bertempur dengan para pengawal Cia To-bun.
Rombongan anak-anak muda yang kehilangan pegangan tersebut lalu menjadi liar, bergentayangan dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mencari penyaluran bagi perasaan mereka yang meledak-ledak. Jadilah mereka pengacau di mana-mana, dan setiap kali bertempur dengan pasukan pemerintah, jumlah mereka pun terus berkurang, ada yang terbunuh, tertawan, atau diam-diam melarikan diri untuk melepaskan diri dari gerombolan.
Yang terakhir adalah kekacauan yang mereka perbuat di kota Bun-seng. Di sini gerombolan Wi-siang mengalami pukulan berat, sebab dari limabelas orang, yang hidup hanya empat orang. Selain itu, Tong Wi-siang pribadi pun mengalami sesuatu yang meresahkan hatinya, yaitu pertemuannya dengan adik perempuan yang disayanginya.
Kini keempat orang sisa gerombolan telah melarikan diri puluhan li jaraknya dari kota Bun-seng. Ketiga kawan Wi-siang melihat punggung Tong Wi-siang terguncang-guncang. Mereka mengira bahwa pemimpin mereka terguncang karena larinya kuda, dan mereka sama sekali tidak akan menduga bahwa pemimpin mereka yang garang itu sebenarnya sedang menangis.
“A-siang!” salah seorang dari kawannya memanggil. “Apakah kita tidak akan beristirahat barang sebentar? Kukira kini kita sudah cukup jauh dari Bun-seng, sudah cukup aman, bahkan sebentar lagi kita mungkin akan sampai kota Kiang-leng.”
Wi-siang tidak menoleh sebab tidak ingin air matanya dilihat oleh teman-temannya. Sahutnya tanpa menoleh, “Kita tidak boleh lengah sekejappun, sebab kita berempat adalah buronan pemerintah kerajaan, dan ada tersedia hadiah besar buat batok-batok kepala kita. Jika kita melewati tempat ramai, tentu jejak kita akan tercium oleh anjing-anjing kerajaan itu.”
“Tetapi kuda tunggangan kita sudah mulai kelelahan, sudah beberapa hari kita pakai secara diluar batas,” bantah kawannya. “Bahkan bisa mati kelelahan kalau tidak kita istirahatkan.”
Jawab Wi-siang, “Persetan! Aku tidak ingin tertangkap lalu diarak keliling kota sebelum kepala kita dipisahkan oleh golok algojo. Karena itu kita jalan terus!”
“Tetapi...” Kawannya yang hendak membantah itu terbungkam setelah Wi- siang menyahutnya dengan suara hampir berteriak, “Jangan membantahku lagi, Hong-pin!”
Anak muda kawan Wi-siang itu bernama Hong-pin. Sebenarnya ia masih terlalu muda untuk ikut-ikutan dalam petualangan sekeras itu, umurnya bahkan lebih muda dari adik Wi-siang yang terkecil, yaitu Wi-lian. Lim Hong-pin adalah anak seorang keluarga pedagang hasil bumi yang terhitung kaya-raya untuk ukuran An-yang-shia. Namun sejak Lim Hong-pin terlibat dalam pembunuhan pejabat dari Pak-khia, maka usaha dagang ayahnya ditutup dan rumahnya disegel oleh pemerintah, sedang keluarga Lim Hong-pin sendiri sudah pindah entah kemana.
Demi menyelamatkan diri dari kejaran pemerintah, Lim Hong-pin terpaksa terus bergabung dalam “pasukan” Tong Wi-siang dan ikut mengacau ke mana-mana. Sering juga ia menyesal kenapa dulu tidak menuruti anjuran ayahnya untuk belajar dagang saja, alih-alih malahan bergaul rapat dengan pengacau-pengacau ini, dan akhirnya kini ia harus memetik hasil dari perbuatannya sendiri.
Dua orang teman Wi-siang lainnya masing-masing bernama Siangkoan Hong dan Tan Goan-ciau. Siangkoan Hong ini juga anak seorang kaya, ayahnya adalah seorang pengusaha rumah makan terbesar di An-yang-shia, tapi nasibnya sama dengan Lim Hong-pin, yaitu tidak berani pulang ke rumah karena takut dikirim ke bawah golok algojo. Dalam gerombolan Wi-siang, Siangkoan Hong ini terkenal keberaniannya...
“Te-cu (murid) percaya bahwa dalam bimbingan Suhu (guru) te-cu akan dapat mempelajari ilmu silat Siau-lim-pay yang terkenal sejak dahulu. Murid sudah melihat sendiri kesaktian dan kebajikan Suhu,” sahut Tong Wi-lian dengan tegas.
Upacara penerimaan murid saja belum terjadi, tetapi gadis itu sudah memanggil “guru” kepada rahib sakti itu, mau tidak mau Hong-tay Hwesio geli dalam hati melihat sikap yang masih agak kekanak-kanakan itu. Namun sekaligus mata batin Hong-tay Hwesio yang tajam itupun dapat melihat semangat dan kekerasan hati yang membaja dari gadis itu. Jauh di hati kecil sang rahib memang sudah timbul rasa sayang kepada gadis yang lugu itu dan ingin mendidiknya sebagai murid.
Tetapi rahib tua itu tidak langsung menyatakan menerima Wi-lian melainkan masih bertanya lagi, “Setelah kau menjadi seorang yang berilmu tinggi lalu kau mau apa?”
Tong Wi-lian agak bingung menjawab pertanyaan itu. Di dalam hatinya bergejolaklah dendam kesumatnya kepada Cia To-bun dan Thio Ban-kiat yang telah menghancurkan ketenteraman hidupnya dan membuat keluarganya jadi tercerai-berai. Tapi hal gejolak dalam hatinya tidak diutarakannya kepada rahib sakti itu.
Tak terduga bahwa mata batin Hong-tay Hwesio ternyata dapat menembus dan menjenguk isi hatinya. Kata Hong-tay Hwesio dengan suara tetap lembut, “Aku melihat hawa dendam menyelubungi air mukamu, pikiranmu pun hanya tertuju kepada pembunuhan dan pembalasan. Kalau benar demikian maka aku tidak dapat menerimamu sebagai muridku. Menurunkan ilmu silat sama dengan memberikan senjata. Aku tidak ingin melihat seorang yang haus darah dan mabuk dendam seperti nona menguasai suatu ilmu silat tinggi. Itu akan sangat membahayakan orang banyak.”
Merah padamlah wajah Tong Wi-lian mendengar kecaman rahib itu, namun gadis itu tetap tidak bangkit dari berlututnya dan wajahnya tertunduk dalam-dalam. Akhirnya ia menyahut juga, “Tetapi bagaimana kalau ada seseorang yang telah membuat keluargaku menjadi porak-poranda? Kami sekeluarga yang tadinya hidup tenteram, berkumpul di bawah satu atap. Kini telah tercerai-berai dan tidak saling mengetahui keberadaan masing-masing?”
Sahut Rahib Hong-tay, “Dalam menghadapi suatu persoalan, kita harus tetap berpikiran jernih dan jangan membiarkan hawa nafsu menguasai pikiran kita. Yang bersalah harus dihukum, biarpun dia merupakan orang yang kita cintai. Dasar penghukuman itu bukan karena kebencian dan pembalasan, namun hanya mencegah agar kepentingan orang banyak tetap terlindungi!”
Hati Tong Wi-lian bergejolak penuh dengan pertentangan batin. Sementara itu Rahib Hong-tay masih terus berkata dengan suaranya yang lembut, “Nona, jika orang yang nona benci itu sudah bertobat, dan tidak lagi merugikan masyarakat, bahkan menjadi orang yang berguna, apakah kau tetap akan membunuhnya?”
Wi-lian tidak dapat langsung menjawab. Ia bertanya kepada diri sendiri, kenapa begitu berhasrat untuk membunuh Cia To-bun? Jawabnya adalah karena Cia To-bun telah menyusahkan keluarganya. Bagaimana kalau kemudian Cia To-bun berubah menjadi seorang yang sangat diperlukan dalam masyarakat? Apakah dia akan tetap membunuhnya meskipun orang banyak akan merasa kehilangan? Apakah dendam keluarganya lebih utama dari kepentingan masyarakat luas?
Namun gadis itu membantah hatinya sendiri, “Bangsat Cia To-bun tidak mungkin berubah menjadi oang baik-baik. Pembunuh-pembunuh bayaran yang baru saja hampir mencelakai aku dan kakakku ini adalah bukti bahwa bangsat itu masih terus memburu kami dan belum puas sebelum keluarga Tong tertumpas habis. Bila tidak ada orang-orang yang menolong kami berdua, mungkin saat inipun kami berdua sudah tidak ada lagi di dunia ini.”
Tengah gadis itu terombang-ambing menemukan jawaban atas masalah yang berkecamuk di dalam hatinya, rahib tua itu telah berkata pula, “Dendam hanya mengotori hati dan pikiran. Pikiran kita yang harusnya jernih, menjadi keruh dan tidak dapat lagi menikmati kehangatan hidup ini. Kita terpencil dari sesama manusia, seperti sebuah pulau di tengah laut. Memang sebagai ahli-ahli silat yang harus mengamalkan ilmunya untuk kepentingan umum, kadang-kadang kami dipaksa melakukan pembunuhan, tetapi hal tu merupakan jalan yang terakhir dan terburuk. Mungkin kita harus membunuh, tapi hal itu karena tidak ada jalan lain, kita terpaksa membunuh seorang atau beberapa orang supaya puluhan atau ratusan orang lainnya tidak menjadi korban. Kau paham asas ini?”
“Te-cu berjanji akan selalu menjunjung tinggi amanat Suhu.”
“Ajaran dari aliran Siau-lim kami mengutamakan welas asih kepada seluruh makhluk hidup. Bukan hanya manusia, bahkan makhluk yang berujud hewan sekalipun. Mengalahkan diri sendiri sebelum menundukkan orang lain. Membunuh atau melukai bukan tujuan, tapi hanya cara untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak. Itupun merupakan cara yang terakhir dan terburuk. Paham?”
Dengan jujur Tong Wi-lian menyahut, “Ajaran seluhur itu terus terang saja masih jauh dari diri te-cu. Namun te-cu berjanji akan berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menjalankan apa yang telah Suhu wejangkan ini.”
Kepala rahib tua yang gundul itu terangguk-angguk sambil tersenyum ketika mendengar ucapan yang terus terang dari Tong Wi-lian. Rahib Hong-tay berkesan bahwa calon muridnya ini seorang yang jujur. Biasanya jika seseorang ditanya tentang kesanggupannya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perguruan.
Maka tanpa pikir panjang dia akan menyatakan kesanggupannya, bahkan dengan kata-kata yang muluk-muluk dan dilengkapi dengan sumpah setia segala, tujuannya tidak lain hanyalah agar cepat diterima dalam perguruan itu. namun tidak sedikit diantara yang melupakan sumpahnya begitu telah lulus dengan bekal ilmu yang tinggi.
Tetapi Rahib Hong-tay yakin akan kejujuran dan ketulusan gadis she Tong itu, maka keluarlah jawaban yang diharapkan Tong Wi-lian sejak tadi, “Baiklah, kau menjadi muridku, meskipun agak janggal nampaknya karena aku seorang rahib dan kau seorang gadis. Asal hati kita bersih dari pikiran busuk, persetan dengan gunjingan orang lain.”
Tak terperikan girangnya gadis itu. Cepat ia menjalankan upacara penghormatan pengangkatan guru, yaitu dengan jalan berlutut dan menyembah sembilan kali di hadapan Suhunya.
Rahib Hong-tay tersenym. Perlahan-lahan ia melangkah ke sebuah pohon yang teduh dan duduk bersila di bawahnya. Katanya, “Sekarang kau tentu tahu apa yang harus kau lakukan, sekaligus aku ingin melihat apakah kau sanggup menunaikan ajaran perguruan atau tidak.” Tanpa menunggu jawaban muridnya lagi, sang rahib lalu memejamkan matanya dan mulai bersemedi.
Tong Wi-lian menjadi heran melihat sikap dan mendengar ucapan gurunya itu. Tanyanya, “Apa yang harus te-cu perbuat?” tetapi pertanyaan itu tidak mendapat jawaban, gurunya telah tenggelam dalam semedinya.
Gadis itu menjadi kebingungan dan menebak-nebak apa yang dimaui oleh gurunya. Dan ketika matanya menyambar sosok-sosok mayat yang bergelimpangan di tempat itu, tiba-tiba terbukalah pikiran Wi-lain. Ia ingat pelajaran welas asih yang baru saja diucapkan gurunya dan telah disanggupinya, dan kini ia harus mewujudkannya dalam perbuatan.
Betapapun jahatnya para berandal suruhan Cia To-bun itu di masa hidupnya, tapi tidak sepatutnya merendahkan hakekat kemanusiaan mereka dengan membiarka tubuh-tubuh mereka tetap bergelimpangan tidak terurus yang akhirnya akan menjadi santapan binatang-binatang liar. Bahkan dalam perang antara dua negara pun ada peraturan-peraturan yang mencoba mempertahankan martabat manusia, meskipun peraturan itu sering dilanggar oleh kedua belah pihak.
Lalu Wi-lian mengambil sebatang golok yang tergeletak diantara mayat-mayat itu dan mulai menggali tanah, membuat sebuah lubang besar untuk menguburkan empatbelas sosok mayat. Pekerjaan itu tentu saja cukup berat buat seorang gadis, meskipun Wi-lian bertubuh kuat dan sudah terdidik ilmu silat sejak kecil, apalagi tanah di pnggir hutan itu ternyata cukup keras pula. Tetapi gadis yang keras hati itu bekerja terus dengan bersemangat dan tanpa mengeluh, bahkan ketika telapak tangannya mulai lecet dan lengannya menjadi pegal, ia tidak berhenti.
Kekuatan cinta kaksih sesama manusia kah yang memberikan kekuatan kepadanya? Atau sekedar ingin mengambil hati calon gurunya supaya mendapat ilmu yang tinggi untuk membalas dendam? Ia sendiri tidak dapat menjawabnya, namun ketika matahari telah tenggelam di sebelah barat maka gadis itu berhasil menguburkan keempatbelas sosok mayat itu secara sederhana tapi layak.
Ketika Tong Wi-lian menoleh ke bawah pohon di mana suhunya duduk, terlihat Rahib Hong-tay telah membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, “Omitohud, muridku yang hebat.”
Sambil mengusap keringatnya, Wi-lian menyahut sambil tersenyum pula, “Sayang, tee-cu agaknya masih belum dapat melakukannya dengan sepenuhnya dilandasi cinta kasih. Tapi lebih banyak didorong maksud untuk menyenangkan hati Suhu saja. Mohon petunjuk Suhu lebih lanjut.”
“Kau cukup jujur dan berani melihat keadaan dirimu secara jujur pula, muridku. Orang yang menyadari bahwa dirinya sedang berjalan di pinggir jurang akan menjadi berhati-hati sehingga tidak terjerumus. Sebaliknya orang yang tidak menyadarinya akan merasa dirinya aman dan dia dengan mudahnya akan terjerumus ke jurang. Tapi jangan buru-buru senang dengan pujianku ini, kau harus berusaha lebih keras lagi untuk membersihkan batinmu.”
Guru dan murid itu kemudian berjalan bersama-sama meninggalkan tempat itu menuju ke arah selatan. Tujuan mereka adalah Gunung Siong-san, tempat letaknya kuil Siau-lim-si yang terkenal itu.
Tiba-tiba Wi-lian bertanya kepada gurunya, “Suhu, aku pernah mendengar berita bahwa kuil Siau-lim punya peraturan keras yang sudah dijalankan selama beratus-ratus tahun, yaitu melarang seorang wanita untuk masuk ke dalam kuil. Benarkah itu, Suhu?”
Rahib Hong-tay menganggukkan kepalanya, “Betul, memang ada peraturan semacam itu. Kaum wanita yang hendak bersembahyang kepada Sang Buddha paling-paling hanya diijinkan masuk sampai ke ruangan sembahyang di bagian depan saja. Sedang bagian dalam kuil merupakan bagian yang tidak dapat dimasuki oleh sembarangan orang, bahkan andaikata dia seorang pria.”
“Kalau tidak dapat masuk ke dalam kuil, bagaimana te-cu bisa belajar ilmu silat?”
Sahut Rahib Hong-tay, “Belajar silat tidak harus di dalam kuil, di udara terbuka malahan lebih segar dan sehat. Di sekitar kuil banyak tempat-tempat sepi yang berpemandangan bagus dan cocok untik tempat berlatih silat. Nanti aku akan memintakan ijin kepada Hong-thio (Ketua Kuil) supaya kau diijinkan tinggal di sekitar kuil. Tergantung kepadamu, apakah kau betah tinggal di tempat sesepi itu sendirian?”
Tanpa pikir panjang lagi Tong Wi-lian menyatakan sanggup hidup dalam kesunyian demi mempelajari ilmu yang tinggi dari rahib sakti itu.
* * * * * * *
Rahib Hong-tay sebenarnya cukup mengerti bahwa gadis muridnya itu masih memerlukan usaha yang panjang untuk membersihkan batinnya dari sisa-sisa dendam. Maka dalam perjalanannya ke selatan, sengaja diajaknya muridnya itu mengambil jalan memutar, tidak melewati an-yang-shia, supaya muridnya tidak teringat akan dendamnya.
Rahib itu justru mengajak muridnya untuk menyusuri daerah pantai timur. Sepanjang jalan bila ada kesempatan, tidak henti-hentinya Hong-tay Hwesio memberikan wejangan tentang ajaran-ajaran Buddha kepada muridnya. Dan ternyata rahib tua ini bukan cuma pandai mengoceh, melainkan juga memberi contoh dalam perbuatan-perbuatan nyata sepanjang perjalanan.
Dan selama perjalanan itu perlahan-lahan mata batin Tong Wi-lian mulai terbuka dan hatinya semakin tenteram. Sejurus ilmu silatpun ia belum diajari, namun kemajuan batin dan ketenangan yang dicapainya akan sangat berarti dalam melandasi pelajaran ilmu silatnya kelak.
Setelah berjalan beberapa hari, pada suatu hari guru dan murid itu memasuki sebuah kota kecil yang bernama Bun-seng, yang letaknya diperbatasan propinsi Ciat-kang. Kota itu bukan kota besar, luasnya hanya seluas kota An-yang-shia, kota kelahiran Tong Wi-lian. Hanya suasananya agak berbeda. Di kota Bun-seng ini terasa benar suasana kehidupan kaum nelayan.
Tepat ketika Rahib Hong-tay dan Tong Wi-lian memasuki kota nelayan yang kecil itu, kota itu baru saja terguncang hebat oleh suatu peristiwa yang sangat menggangu ketenteraman hidup di kota itu. selama beberapa malam kota Bun-seng berturut-turut telah digemparkan oleh rangkaian pembunuhan yang nekad. Disebut nekad, karena yang dijadikan korban adalah para perwira tentara Kerajaan Beng yang bertugas di kota itu!
Dalam tiga malam berturut-turut, tiga orang perwira telah mati terbunuh, dan mayat mereka dalam keadaan luka arangkranjang telah sengaja “dipamerkan” oleh pembunuh-pembunuhnya dengan diletakkan di tempat-tempat yang ramai!
Kejadian itu merupakan tamparan hebat bagi perwira pemimpin keamanan di kota itu. Segera keluarlah perintahnya untuk menggeledah seluruh kota untuk menemukan pembunuhnya, dan malapetaka buat rakyat kecilpun mulai dari sini. Dalam melakukan penggeledahan, para tentara kerajaan telah menggunakan kesempatan untuk mengisi kantong dengan memeras rakyat, selain itu penggeledahan pun dilakukan secara membabi-buta, sehingga mereka bukan lagi tentara kerajaan tapi lebih tepat disebut perampok-perampok berseragam.
Siapa yang dicurigai langsung diseret keluar dari rumahnya, kecuali yang bisa menyuap prajurit-prajurit itu. Dan celakalah yang tidak bisa menyuap, sebab mereka akan langsung digiring menuju ke penjara kota. Jika sudah begini, maka hanya ada dua kemungkinan buat si korban. Dijebloskan seterusnya dengan tuduhan bersekutu dengan pembunuh setelah melalui sebuah “pengadilan kilat”, dan kemungkinan kedua adalah dibebaskan kembali karena tuduhannya tidak terbukti.
Namun sudah terlanjur kehilangan sebelah mata atau beberapa buah gigi atau cacat lainnya. Dan rakyat tidak bisa menuntut kepada siapapun. Demikianlah gambaran kebobrokan masyarakat di masa pemerintahan Kaisar Cong-ceng. Rakyat tidak punya perlindungan sama sekali. Ibarat domba gemuk yang dikelilingi serigala-serigala kelaparan.
Pada saat Rahib Hong-tay hendak memasuki kota Bun-seng bersama muridnya, merekapun sempat mengalami pemeriksaan oleh beberapa orang tentara kerajaan, untung rahib itu masih punya sisa beberapa tahil perak untuk menyuap tentara-tentara kerajaan itu sehingga bebaslah ia dan muridnya dari segala kerepotan. Tong Wi-lian pun menyamar sebagai laki-laki, sehingga tidak diganggu oleh prajurit- prajurit itu.
Waktu itu adalah tengah hari, di mana matahari tengah bertahta dipuncak langit dan panasnya terasa menyengat kulit. Begitu Rahib Hong-tay masuk ke dalam kota, maka langsung saja mereka menemukan sebuah pemandangan yang menyayat hati. Di tengah jalan raya ada enam orang lelaki yang tengah diseret oleh sepasukan tentara kerajaan. Mereka diseret seperti kambing atau lembu saja layaknya. Dan setiap kali cemeti atau gagang tombak melanda punggung orang-orang celaka itu.
Di belakang rombongan pesakitan itu ada rombongan lain. Mereka adalah sekelompok wanita dan anak-anak yang mengikuti rombongan di depannya sambil meratap tangis. Rupanya mereka adalah anggota keluarga dari orang-orang pesakitan itu. Tapi mereka tidak pernah berhasil mendekati rombongan pesakitan sebab prajurit-prajurit selalu merintangi dengan senjata-senjata mereka, atau dengan kaki-kaki yang ditendangkan.
Sedangkan para pesakitan nampak begitu menderita. Pakaian mereka sudah hancur sehingga terlihatlah punggung mereka yang “dihiasi” jalur-jalur matang biru yang berlumuran darah. Tetapi cambukan-cambukan dan gebukan-gebukan tidak pernah mereda, bahkan semakin gencar mendera punggung orang-orang kecil tersebut. Dan para prajurit pun tertawa-tawa senang, puas, karena berhasil menunjukkan “kegagahan” mereka.
Rahib Hong-tay mengajak muridnya membaurkan diri di antara penduduk kota Bun-seng yang bergerombol di pinggir jalan. Hati Rahib Hong-tay yang penuh welas asih seketika bergetar hebat waktu melihat sesamanya diperlakukan seperti binatang oleh sesama manusia pula. Di dalam hatinya dia berdoa memohon petunjuk Sang Buddha. Tetapi karena rahib itu tidak ingin bertindak sembarangan sebelum mengetahui persoalannya lebih dahulu, maka ia lalu mendekati seorang kakek bongkok di pinggir jalan. Katanya, “Tuan, apakah yang telah terjadi?”
Kakek bongkok itu menarik napas panjang lalu menyahut, “Apakah tay-su belum tahu? Selama beberapa malam berturut-turut ini telah ada tiga orang perwira kerajaan yang dibunuh orang, dan mayat yang dirusak oleh pembunuh-pembunuh itu sengaja diletakkan di tempat-tempat ramai, agaknya memang hendak menentang penguasa. Nah, keenam orang yang sedang diseret oleh prajurit-prajurit itulah yang dituduh sebagai pembunuhnya. Mereka baru saja diadili secara kilat, dan sudah diputuskan hukuman penggal kepala buat mereka. Mereka sedang digiring ke lapangan dekat Tong-mui (gerbang timur) untuk menjalani hukumannya.”
Seorang nenek yang agaknya isteri dari kakek bongkok itu ikut nimbrung dalam percakapan, “Yang kasihan adalah si Ah Beng. Ia baru setahun beristeri dan anaknya pun masih kecil, tetapi sebentar lagi ia akan menjadi setan tanpa kepala. Padahal jelas dia tidak bersalah, tapi sialnya prajurit yang mengeledah rumahnya itu adalah bekas saingan asmaranya dulu. Rupanya prajurit itu masih dendam karena tidak berhasil menggaet perempuan yang sekarang menjadi isteri Ah Beng sehingga kesempatan ini digunakannya untuk menjerumuskan Ah Beng ke dalam kesulitan.”
“Di antara keenam orang itu, yang manakah yang bernama Ah Beng?” tanya Rahib Hong-tay.
Nenek itu agaknya seorang yang suka mengobrol. Dengan bersemangat ia segera menunjukkan jarinya ke arah salah seorang pesakitan sambil berkata, “Yang diseret paling depan itulah. Kemarin dia menyembelih ayam dan lupa membersihkan pisau yang digunakan untuk menyembelih. Tak terduga tadi malam terjadi lagi pembunuhan itu. pisaunya yang berlumuran darah ditemukan oleh prajurit yang menggeledahnya dan segera dijadikan barang bukti. Dasar hakimnya juga malas untuk memeriksa perkara itu secara teliti, maka enak saja diputuskannya hukuman mati buat Ah Beng.”
Mendengar cerita nenek itu, Rahib Hong-tay menarik napas. Semurah itukah nyawa manusia, sehingga dengan seenaknya saja orang dapat dijatuhi hukuman mati tanpa bukti yang kuat? Inikah hukum Kerajaan Beng? Ketika Hong-tay Hwesio menengok ke arah para pesakitan, nampak bahwa Ah Beng itulah yang paling payah keadaannya. Tubuhnya yang selama ini kurus karena hidup dalam kemiskinan, kini babak-belur dihujani deraan para prajurit. Mukanya yang sudah pucat menyeringai menahan kesakitan yang luar biasa.
“Ampunilah aku tuan-tuan,” ratapnya dengan suara lemah. “Aku hanyalah seorang yang lemah dan tidak mengerti ilmu silat, bagaimana aku berani melakukan pembunuhan terhadap para tay-jin? Ampun tuan...”
Seorang tentara kerajaan yang berkumis kaku seperti ijuk segera menggampar muka Ah Beng sehingga kepala Ah Beng bagai disentakkan ke belakang dengan mulut berlumuran darah. Masih belum puas, ia menginjak dada Ah Beng yang kurus kering sambil membentak dengan bengisnya, “Kau kira kau dapat menipu kami?! Jelas di rumahmu ada bukti kuat berupa pisau yang berlumuran darah! Lebih baik kau mengaku saja di mana tempat sembunyinya kawan-kawanmu supaya hukuman matimu dapat dijalankan dengan cepat tanpa siksaan macam-macam!”
Seorang perempuan yang masih cukup muda dan menggendong seorang bayi berumur beberapa bulan segera menerjang maju dan berlutut di depan prajurit yang berkumis kaku itu sambil meratap, “Ciu toako, harap sudilah kau mengingat persahabatan kita di masa lalu. Ah Beng toako benar-benar tidak melakukan pembunuhan, semalam dia berada di dalam rumah terus dan tidak melangkah keluar pintu setapakpun. Aku berani bersumpah tentang hal ini, ampunilah dia...”
Begitu diingatkan akan “persahabatan masa lalu” seketika si prajurit berkumis kaku itu justru semakin tersinggung. Sejenak prajurit itu memandang isteri Ah Beng dengan liarnya. Tiba-tiba dia menyeringai lalu tangannya mengusap dagu perempuan itu sambil berkata,
“A-giok, ternyata kau masih cantik juga meskipun si bangsat buduk ah Beng ini tidak mampu membelikan pakaian bagus untukmu. Kau harus mengerti bahwa meskipun kini kita sama-sama telah berkeluarga tetapi aku masih sering teringat kepadamu. Andaikata dulu kau terima lamaranku, sekarang tentu kau akan mengalami hidup senang dan tidak tersangkut perkara ini. Tapi nanti setelah pelaksanaan hukuman mati ini, kau masih boleh tinggal di rumahku sebagai isteri kedua. Setuju?”
Dan tingkah prajurit yang dipanggil Ciu toako itu kemudian benar-benar tidal peduli bahwa ia sedang berada di tengah jalan raya, dan ada ratusan mata sedang memandangnya. Dengan seenaknya saja ia memegang tubuh isteri Ah Beng, bahkan kemudian memeluk dan menciumi mukanya. Perempuan itu berusaha meronta dan melepaskan dirinya, sedangkan bayi dalam gendongannya menangis keras karena terhimpit oleh tubuh prajurit yang besar dan berbau keringat tersebut.
Prajurit she Ciu itu agaknya merasa sangat terganggu oleh tangisan si bayi. Dengan kasar ia merenggut si bayi dari pelukan ibunya lalu dibantingnya ke tanah! Bayi tak berdosa itu jatuh terbanting dengan kepala mengenai tanah lebih dulu, tak ampun lagi, tangisnya pun berhenti untuk selama-lamanya.
Sang ibu jadi kaget sekali. Ia menubruk mayat bayinya sambil berteriak-teriak dengan kalapnya, bagaikan gila ia memanggil-manggil nama bayinya yang lucu yang sekarang tidak mampu menjawab lagi. Penduduk kota Bun-seng yang melihat kejadian itu segera membuang muka dengan perasaan sangat muak dan pedih. Tetapi tak seorangpun ingin mempertaruhkan nyawa dengan menentang tingkah laku prajurit-prajurit yang kesetanan itu.
Tong Wi-lian yang ikut berjubel diantara kerumunan orang menggertakkan giginya dan mukanya menjadi merah padam karena marah melihat kesewenang-wenangan alat-alat negara itu. Ketika gadis itu menoleh ke arah gurunya, nampaklah wajah Sang guru tidak ada kemarahan sedikitpun, ia hanya memejamkan mata dengan setitik air bening tergantung di sudutnya.
“Suhu, kita harus bertindak, tindakan para prajurit ini benar-benar keterlaluan,” desis Tong Wi-lian sambil menarik tangan gurunya.
Namun Rahib Hong-tay masih juga ragu-ragu untuk turun tangan sebab masih dibebani berbagai pertimbangan. Ia menyadari bahwa daerah itu sudah cukup dekat dengan Gunung Siong-san, tempat berdirinya pusat perguruan Siau-lim-pay yang terkenal. Jika dia memunculkan dirinya di tempat itu dengan jubah paderinya yang mencolok, maka orang akan langsung meghubungkannya dengan Siau-lim-pay, dan itu berarti dia melibatkan seluruh anggota Siau-lim-pay dengan permusuhan melawan pemerintah Kerajaan Beng.
Pertimbangan lainnya adalah bahwa andaikata ia berhasil menyelamatkan sebuah nyawa, tapi tentara kerajaan yang marah itu tentu akan menimbulkan malapetaka yang lebih hebat lagi bagi rakyat banyak. Meskipun hatinya sudah sangat muak melihat kekejaman itu, namun ia masih mampu berfikir panjang dengan memikirkan keselamatan orang banyak. Sedangkan pertimbangan semacam itu tidak ada dalam diri muridnya yang hanya sekedar menuruti perasaan marahnya yang bergejolak.
Dalam pada itu, pesakitan yang bernama Ah Beng timbul keberaniannya setelah melihat keluarganya diperlakukan sewenang-wenang oleh prajurit-prajurit kerajaan. Teriaknya dengan marah, “Anjing-anjing keparat! Kenapa kau bunuh bayi yang sama sekali belum tahu apa-apa! Kalian benar-benar berhati binatang dan berjantung anjing... aaaah!”
Ah Beng sama sekali tidak sempat menyelesaikan kalimat makiannya sebab prajurit she Ciu telah menjadi marah dan tanpa kenal kasihan telah menusukkan tombaknya ke perut bekas saingan asmaranya tersebut. Ah Beng berteriak kesakitan dan roboh disamping tubuh bayinya. Setelah berkelojot sebentar, diapun terdiam untuk selamanya.
Betapapun sabarnya Rahib Hong-tay, dan betapapun macamnya pertimbangan dalam hatinya, akhirnya mendidih juga darah kesatrianya ketika melihat kebiadaban yang berlangsung di depan matanya. Tangannya segera merogoh kantong jubahnya dan menggenggam segenggam uang logam yang siap ditaburkan ke arah prajurit-prajurit tidak berprikemanusiaan itu. Sementara itu Tong Wi-lian pun sudah gatal tangan dan tangannya pun sudah terkepal kencang.
Tetapi sebelum guru dan murid itu bertindak, ternyata sudah ada pihak lain yang mendahului memberi hajaran kepada prajurit-prajurit tersebut. Entah dari mana datangnya, dan hanya terdengar suara berdesing, tahu-tahu sebatang anak panah telah menancap di tenggorokan prajurit she Ciu yang kala itu sedang tertawa-tawa kesenangan.
Mendadak ia nampak melotot kaget dan kesakitan, tangannya mengapai-gapai kian kemari seolah orang yang hendak tenggelam sedang mencari pegangan. Ketika roboh ke tanah ia masih sempat mengeluarkan suara-suara sekarat dari tenggorokannya, lalu nyawanyapun amblas.
Semua orang menjadi terkejut dan panik melihat perkembangan yang tak terduga-duga itu. Tidak terkecuali Rahib Hong-tay dan muridnya meskipun mereka tidak sepanik orang lain. Belum lagi kekegetan orang banyak menjadi reda, sekali lagi seorang tentara kerajaan menjerit keras sambil memegangi dadanya yang tertancap anak panah.
Sebelum roboh ia sempat berteriak ketakutan, “A... ada pem... bu... bunuh gelap...!!”
Penduduk kota kecil yang sedang berjejal di pinggir jalan itupun segera bubar ketakutan seperti gabah ditampi. Mereka harus cepat-cepat meninggalkan tempat itu sebelum ditangkap dan dituduh membunuh prajurit kerajaan, dan kemudian mengalami nasib seburuk Ah Beng.
Sedangkan prajurit-prajurit kerajaan itu telah berpencar sambil berteriak, “Tangkap pembunuh!”
Dalam keadaan sekacau itu, Rahib Hong-tay sempat menyambitkan segenggam uang logam yang telah dipersiapkannya sejak tadi. Namun kini tidak diarahkan kepada para prajurit, melainkan kepada belenggu yang membelenggu para pesakitan. Di sini terlihatlah kepandaian Rahib Hong-tay, sebab uang-uang logam tersebut dengan tepat dapat memutuskan tali-tali yang mengikat para pesakitan tanpa melukai kulit mereka. Dan dalam keadaan hiruk-pikuk seperti itu ternyata incarannya tidak meleset sedikitpun. Para pesakitan itupun tidak melewatkan kesempatan baik dan segera melarikan diri semuanya.
Setelah membebaskan para pesakitan dari jarak jauh, rahib itu segera mengajak muridnya untuk membaurkan diri dengan orang-orang yang sedang panik. Mereka berdua mencari persembunyian yang baik untuk menonton kejadian selanjutnya.
“Bagaimana sekarang sikap kita, Suhu?” tanya Tong Wi-lian sambil berlari-lari mengikuti gurunya.
“Kita tidak perlu menonjolkan diri,” kata gurunya. “Agaknya sudah ada pihak lain yang berniat untuk mencegah kebiadaban prajurit-prajurit itu. Kita hanya akan melihatnya dari kejauhan dan kemudian menentukan langkah kita selanjutnya.”
“Bagaimana kalau kita langsung membantu saja pemanah-pemanah tersembunyi itu?” usul Wi-lian dengan penuh semangat.
“Jangan gegabah, kita belum tahu apakah pemanah-pemanah gelap itu dari pihak yang bermaksud baik atau justru sebaliknya.”
Sebentar saja jalan raya yang terletak membujur di tengah-tengah kota Bun-seng itu telah menjadi sepi. Di tengah jalan kini hanya ada mayat Ah Beng beserta mayat bayinya serta mayat dua orang prajurit yang mati konyol oleh pemanah gelap. Isteri Ah Beng sudah diselamatkan oleh salah seorang penduduk yang baik hati.
Para prajurit yang lain pun tidak nampak lagi di tengah jalan raya, sebab mereka tidak ingin menjadi sasaran empuk para pemanah gelap. Prajurit-prajurit tersebut telah menyusup ke dalam lorong-lorong disekitar tempat kejadian dan berusaha mencari dan menangkap si pemanah gelap. Rahib Hong-tay dan muridnya bersembunyi di balik setumpuk anyaman bambu, dan dengan cermat memperhatikan suasana.
Pada jaman itu memang sudah timbul rasa ketidak-puasan rakyat terhadap pemerintahan Kaisar Cong-ceng yang lemah dan tidak adil. Aliran Siau-lim-pay sebagai perguruan yang terbesar di Tiongkok mau tidak mau pasti akan terlibat setiap perkembangan yang menyangkut rakyat banyak, sebab sudah sejak lama murid-murid Siau-lim-pay dikenal sebagai pendekar-pendekar pembela rakyat yang tertindas. Kini Rahib Hong-tay ingin tahu pihak manakah yang telah berani menentang pihak tentara kerajaan secara terang-terangan tersebut.
Tengah ketegangan mencekam di semua sudut, tiba-tiba dari atas genteng sebuah rumah di pinggir jalan, terlemparlah sebuah benda besar ke tengah-tengah jalan. Setelah jatuh ternyata “benda” itu adalah mayat berseragam prajurit Kerajaan Beng dengan leher yang telah tergorok hampir putus. Ketika Wi-lian memperhatikan dengan seksama, ternyata prajurit itu termasuk kelompok yang menyiksa kaum pesakitan tadi. Rupanya dia mencoba menyelidiki ke atas genteng, tapi di balik wuwungan itu dia dibantai oleh pembunuh gelap yang bersembunyi.
“Celakalah pemilik rumah itu,” desis Wi-lian perlahan. “Pasti besok pagi ia akan dituduh berkomplot dengan penjahat, nasibnya pun akan menjadi sangat buruk.”
Sementara itu prajurit-prajurit lain agaknya masih bersembunyi belum jauh dari tempat itu, dan mereka masih dapat melihat mayat kawan mereka yang dilemparkan dari atas genteng tadi. Diam-diam nyali para prajurit itu mulai menciut. Mereka garang dan galak terhadap rakyat lemah yang tidak bersenjata, namun terhadap pembunuh-pembunuh yang masih belum menampakkan diri, mereka mulai merasa agak gentar.
Seorang prajurit yang bernyali agak kecil berlindung di belakang sebuah tempayan air. Ia sedang memandang mayat kawannya itu dengan lutut gemetar. Dan dia bertambah gemetar ketika melihat sesosok bayangan hitam telah berdiri dibelakangnya. Sesosok tubuh yang berpakaian serba hitam dan mukanya tertutup kedok kain hitam pula. Hanya sepasang matanya yang setajam pisau itu tengah menatap prajurit tersebut.
“Sss... sia... pa... kkk... kau?” tanya prajurit tersebut dengan tergagap sambil mencoba mencabut pedang tang tergantung di pinggangnya. Aneh, biasanya ia cukup tangkas mencabut pedang untuk menggertak dan menakut-nakuti rakyat, namun kini tangannya terasa lemas sehingga sekian lama dia belum juga berhasil mencabut pedangnya.
Orang berkedok itu sama sekali tdak menjawab. Jawabannya adalah menggerakkan pedang pendek yang dipegangnya, dan sekali tusuk saja amblaslah pedangnya di jantung prajurit sial itu. ketika ia menarik kembali pedangnya, prajurit itu langsung roboh dengan sebuah luka menganga di dadanya. Lelaki berkedok segera mencengkeram mayat prajurit tersebut dan melemparkannya ke tengah jalan. Kemudian dia sendiri dengan tenangnya melangkah ke tengah jalan dan berdiri tegak di sana, matanya menyapu ke empat penjuru dengan garangnya.
Melihat si pembunuh telah keluar dari persembunyiannya, para prajurit pun segera berlompatan keluar dari tempat perlindungan masing-masing dan langsung mengurung orang berkedok tersebut.
Orang berkedok itu nampak tenang-tenang saja menghadapi kepungan para prajurit. Tiba-tiba ia menggerakkan pedang pendeknya dengan gerakan seperti orang memberi aba-aba. Begitu gerakan selesai, bermunculanlah belasan orang lelaki berkedok dari tempat persembunyian mereka masing-masing. Mereka muncul dari loteng-loteng di pinggir jalan, lorong lorong sempit di pinggr jalan, dari dalam parit saluran air kotor dan bahkan ada yang muncul dari dalam tumpukan sampah.
Mereka muncul bagaikan hantu-hantu di siang hari dan langsung menyergap ke arah para prajurit. Karena sergapan mendadak ini, para prajurit menjadi panik dan beberapa prajurit langsung menjadi korban sia-sia. Untunglah bahwa para prajurit kerajaan itupun merupakan orang-orang yang cukup terlatih. Salah seorang yang berpangkat paling tinggi segera mengambil pimpinan dan berseru agar kawan-kawannya jangan bingung dan melawan dengan tenang. Teriaknya,
“Semuanya tetap di sini untuk menghadapi para pengacau ini. Salah seorang pergilah ke tangsi untuk memanggil bala bantuan! Cepat!”
Prajurit yang ditunjuk untuk memanggil bala bantuan segera berlari meninggalkan tempat itu. Tetapi ia hanya sempat berlari belasan langkah, sebab seorang berkedok telah muncul dari balik genteng di pinggir jalan dan langsung menembakkan panahnya. Prajurit itu langsung roboh terjungkal dengan punggung tertancap anak panah.
Dalam pada itu gerombolan orang berkedok telah bertempur sengit dengan pasukan kecil prajurit kerajaan. Setelah para tentara kerajaan itu dapat bertempur dengan tenang dan tidak gugup lagi, tampaklah bahwa mereka lebih terlatih dan lebih berpengalaman dibandingkan lawan-lawan mereka. Jumlah tentara kerajaan itu pun hampir tiga kali lipat dari lawan-lawannya sehingga keadaanpun kini berbalik, kini orang-orang berkedoklah yang terkepung dan terjepit.
Kalau pada permulaannya serangan orang-orang berkedok itu berhasil mengurangi beberapa orang tentara kerajaan, hal itu hanyalah disebabkan oleh serangan mereka yang mendadak dan tidak terduga. Tetapi sekarang setelah kedua belah pihak berhadapan dan telah sama-sama siap, terlihatlah bahwa orang-orang berkedok itu tidak terlalu tangguh sehingga mereka mulai terdesak.
Sebagian prajurit memakai senjata pedang dan perisai, sebaliknya orang-orang berkedok itu rata-rata hanya bersenjata belati atau pedang pendek, yaitu jenis-jenis senjata yang mudah disembunyikan dalam baju. Meskipun demikian orang-orang berkedok tersebut melawan dengan gigih. Beberapa prajurit telah roboh tewas atau luka-luka, namun diantara orang berkedok itupun ada yang roboh dan tewas.
Namun ada seorang berkedok yang paling menonjol kepandaiannya, yaitu orang berkedok yang tadi muncul pertama kali ditengah jalan. Ia bertubuh tinggi semampai dan berpundak cukup tegap, meskipun tidak terlalu besar. Ilmu silatnya pun tampak paling lihai, terbukti dengan permainan pedangnya yang lincah dan mantap. Untuk membendung amukan orang ini, pihak tentara kerajaan harus menggabungkan tenaga lima orang prajurit, barulah dapat melawannya dengan seimbang. Tetapi orang itupun melawan dengan garang seperti harimau terluka.
Dari tempat persembunyiannya, Rahib Hong-tay dan muridnya mengawasi jalannya petempuran dengan cermat. Tong Wi-lian semakin lama semakin tertarik melihat permainan pedang si orang berkedok. Ia pun merasa sudah sangat mengenal bentuk tubuh dan gerak-gerik orang itu. Ya, bahkan ia mengenalnya sejak kecil! Karena tidak dapat menahan diri lagi, ia lalu berbisik kepada gurunya,
“Suhu, orang berkedok yang tinggi semampai itu memainkan ilmu pedang Soat-san-pay!”
Rahib Hong-tay mengiakan, “Ya, akupun melihatnya. Tetapi itu bukan hal yang aneh. Soat-san-pay adalah sebuah perguruan yang cukup besar dan mempunyai banyak murid, meskipun letak perguruan itu jauh di perbatasan barat, tapi apa sukarnya jika salah seorang muridnya hendak berkeliaran di daerah Tiong-goan ini?”
“Tetapi te-cu seakan-akan sangat mengenal orang itu,” sahut Wi-lian dengan agak ragu-ragu.
Suara gemerincing senjata beradu bercampur aduk dengan dengus kesakitan atau teriakan perang penuh dendam terdengar makin riuh di tempat itu, semakin lama semakin ribut. Pemanah yang bersembunyi di atas genteng rumah di pinggir jalan kembali telah “menjemput” beberapa nyawa prajurit kerajaan. Basanya yang diincar adalah prajurit yang mencoba meninggalkan tempat pertempuran untuk memanggil bala bantuan. Incarannya ternyata selalu jitu dan tidak pernah meleset.
Tetapi pemanah di atas genteng itu kemudian semakin berani memunculkan dirinya, dan datanglah nasib sialnya. Ketika si pemanah sedang berjongkok di atas genteng untuk menunggu korbannya, seorang prajurit berhasil melemparkan lembing yang tepat menancap di data si pemanah. Sambil menjerit kesakitan, si pemanah itupun roboh dari atas genteng dan terbanting di tanah.
Namun prajurit yang melempar lembing itupun juga mengalami nasib buruk, sebab seorang lawannya berhasil membenamkan sepasang belati ke lambungnya dan merobeknya. Prajurit itupun ambruk ke tanah, menambah jumlah deretan korban yang sudah cukup banyak.
Rahib Hong-tay yang berhati lembut itu hampir-hampir menangis melihat sesama manusia saling bunuh seperti binatang buas di padang liar saja. Bahkan lebih kejam dari binatang, sebab binatang hanya membunuh untuk membela diri atau untuk mengisi perut, namun manusia membunuh hanya semata untuk kepuasan diri sendiri.
Korban yang terluka atau tewas terus bertambah di kedua belah pihak. Tetapi hal tersebut tidak mematahkan kebuasan orang-orang itu, justru malah semakin bertambah buas dan kalap. Kawanan orang berkedok yang tadinya berjumlah belasan orang, kini telah hampir habis. Mereka kini tinggal berempat, termasuk orang berkedok yang memainkan ilmu pedang Soat-san-pay. Merekalah yang masih bertahan dengan gigihnya melawan tekanan tentara-tentara kerajaan.
Sementara itu Rahib Hong-tay mulai mempertimbangkan untuk turun tangan. Tapi ia masih berpikir apakah turut campur dirinya itu akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak atau justru akan menambah jumlah korban? Sebagai manusia biasa, rahib itupun mempunyai perasaan berpihak. Di dalam hatinya ia sudah berpihak kepada orang-orang berkedok, Sebab dengan mata kepalanya sendiri ia telah menyaksikan kekejaman yang memuakkan dari tentara-tentara kerajaan.
Dalam pada itu, orang berkedok yang bertubuh tinggi semampai telah mulai melihat kesulitan yang membayang bagi pihaknya. Ia segera mengeluarkan suitan nyaring, mengisyaratkan kawan-kawannya agar mengundurkan diri dari gelanggang.
Namun prajurit-prajurit yang sudah dirasuk dendam karena telah kehilangan beberapa orang kawan itu tentu saja tidak membiarkan orang-orang berkedok itu kabur begitu saja. Seorang prajurit yang berpangkat paling tinggi segera mengejek dengan suara dingin,
“Hemm, saat ini tidak ada selubang jarumpun yang dapat kalian gunakan untuk menyelamatkan diri. Kalau ingin meraka memang bisa, dan pedangku ini sanggup untuk mengantarkan kalian.”
Tong Wi-lian yang juga punya perasaan berpihak kepada orang-orang berkedok itu, terutama kepada orang yang memainkan ilmu pedang Soat-san-pay, segera membisiki gurunya, “Suhu, cepatlah bertindak sebelum orang-orang berkedok itu tertumpas habis. Mereka bertindak demikian untuk menentang kezaliman.”
Rahib Hong-tay memang sudah memutuskan untuk membantu orang-orang berkedok itu secara diam-diam, karena dianggapnya orang-orang berkedok itu sebagai orang-orang gagah berani yang berani menentang tindakan kejam tentara kerajaan. Tapi rahib itu masih belum berniat untuk membunuh tentara-tentara itu, hanya berniat melumpuhkannya saja. Dengan demikian akan memberi kesempatan kepada orang-orang berkedok itu untuk melarikan diri.
Setelah mengincar sasarannya baik-baik, Rahib Hong-tay lalu menaburkan seraup uang logam yang sudah digenggamnya sedari tadi. Kepingan-kepingan uang logam yang nampaknya ditabur sembarangan itu ternyata dapat “memilih” sasarannya sendiri-sendiri dengan tepat, dan semuanya tepat mengenai lutut para prajurit kerajaan!
Hampir bersamaan para prajurit itu menjerit kesakitan dan roboh serentak ketika uang-uang logam yang disambitkan Hong-tay Hwesio mengenai sambungan lutut mereka. Mereka menjadi kalang-kabut dan sama sekali tidak tahu sebab kaki mereka mendadak menjadi lemas.
Keinginan Hong-tay Hwesio adalah agar supaya orang-orang berkedok itu cepat-cepat melarikan diri sehingga korban yang lebih banyak dapat dikurangi. Namun ternyata keinginan yang mulia itu tidak sesuai dengan kenyataan. Orang-orang berkedok tidak melarikan diri selagi para prajurit roboh, malahan dengan kebencian yang semakin meluap mereka membabat habis prajurit-prajurit kerajaan tanpa kenal ampun.
Terdengar jerit kematian berturut-turut. Dalam sekejap saja, sisa-sisa prajurit kerajaan yang masih hidup telah tertumpas habis tanpa sisa. Jalan raya yang lengang itu kini penuh dengan bangkai manusia yang malang-melintang.
Baik Rahib Hong-tay maupun Tong Wi-lian sama sekali tidak menduga akan sikap orang-orang berkedok yang menyalah-gunakan pertolongan itu. Rahib Hong-tay membantu orang-orang itu karena muak melihat kekejaman tentara kerajaan, tapi ternyata orang-orang berkedok itupun merupakan manusia-manusia yang tak kalah buas dan liarnya denga para tentara kerajaan. Mereka sama sekali tidak membiarkan satupun prajurit hidup.
Rasa simpati yang sempat timbul dalam hati Rahib Hong-tay dan muridnya sirnalah sudah. Namun dalam pada itu Tong Wi-lian merasa semakin mengenal orang berkedok yang tinggi semampai. Ingatannya semakin lama semakin tajam dan mulutnya hampir saja meneriakkan sebuah nama.
Gerombolan orang berkedok yang tinggal empat orang itu berdiri bertolak pinggang di tengah jalan, di antara mayat-mayat lawan mereka, seakan sedang memuaskan diri menikmati kemenangan mereka. Kemudian terdengarlah orang yang bertubuh tinggi semampai itu berkata kepada teman-temannya,
“Kita tinggalkan tempat ini secepatnya sebelum anjing-anjing Kaisar lainnya membanjiri tempat ini!”
Keempatnya segera mengambil kuda-kuda tunggangan mereka yang disembunyikan di lorong-lorong sekitar tempat itu. Tak lama kemudian mereka telah berada di punggung kuda masing-masing dan segera memacunya menuju ke arah barat kota Bun-seng.
Saat itulah Tong Wi-lian tidak ragu lagi akan orang yang bertubuh tinggi semampai itu. Kini dia ingat orang itu, apalagi setelah mendengar suaranya, jika tadi dia masih ragu-ragu itu disebabkan karena orang ini namapak agak kurus dibandingkan dulu. Orang itu tidak lain adalah Tong Wi-siang, kakaknya yang tertua, yang sudah setengah tahun lebih meninggalkan An-yang-shia karena terlibat pembunuhan seorang pejabat hukum dari Pak-khia.
Tanpa dapat menahan diri lagi, Tong Wi-lian segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan mengejar ke arah larinya orang-orang berkuda itu sambil berteriak memanggil nama kakaknya, “A-siang! A-siang!”
Keempat penunggang kuda itu sudah berada belasan tombak jauhnya dari tempat pertempuran, ketika gadis itu memanggil-manggil nama kakaknya. Tapi pemimpin gerombolan yang bertubuh tinggi semampai itu sempat mendengar teriakan Wi-lian dan sempat menolehkan kepala. Ia nampak ragu-ragu sejenak, tapi kemudian ia menggertakkan gigi, mengeraskan hatinya dan lalu memacu kudanya lebih cepat lagi.
Tong Wi-lian yang berlarian mengejar tak dihiraukan lagi. Sebaliknya Wi-lian bagai kalap mengejar kakak tertuanya yang telah lama tak pernah bertemu. Sekuat tenaga ia terus berlari mengejar sambil memanggil “A-siang” berulang kali. Namun mana bisa ia menandingi kecepatan lari kuda? Dalam sekejap saja bayangan keempat ekor kuda itu semakin mengecil, semakin kabur dan akhirnya lenyap dengan hanya meninggalkan debu kuning yang mengepul.
Bagai hilang kesadaran, Wi-lian terus mengejar sampai ke batas kota hingga akhirnya dia putus asa, batinnya telah terpukul begitu hebat hingga iapun jatuh terkulai dan pingsan. Untung Hong-tay Hwesio segera menolongnya, dan dengan bantuan beberapa orang penduduk yang baik hati, mereka berhasil menyadarkan dan menghibur gadis itu.
Sebelum meninggalkan kota Bun-seng, Rahib Hong-tay telah menguras seluruh isi kantongnya hingga tak tersisa sepeserpun, lalu dititipkan kepada salah seorang penduduk Bun-seng agar diserahkan kepada keluarga Ah Beng yang masih hidup.
Setelah Tong Wi-lian sadar kembali, maka guru dan murid itupun melanjutkan perjalanannya menuju Kuil Siau-lim-pay di bukit Siong-san yang sudah tidak jauh lagi.sejak hari itu Tong Wi-lian nampak agak murung dan tidak seriang biasanya. Rupanya dia sangat menyesal karena tidak sempat menemui kakak tertuanya.
Bahkan dia pun menyesal melihat tingkah laku kakaknya yang ada gejala-gejala akan menjadi sesat. Dulu kakaknya sudah cukup bengal dan nakal, dan kini setelah berpisah dengan keluarganya agaknya dia semakin berani membuat kekacauan.
Meskipun hatinya risau, untunglah Wi-lian bukan jenis gadis yang cengeng. Peristiwa yang dialaminya di kota Bun-seng justru semakin mengobarkan semangatnya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dikuil Siau-lim-si. Dan setelah membekal ilmu yang dapat diandalkan, barulah dia akan dengan leluasa mencari keluarganya yang tercerai-berai untuk dikumpulkan kembali.
* * * * * * *
Empat orang lelaki tegap penunggang kuda tengah berpacu di tengah padang gersang yang tanahnya berwarna kuning kecoklatan. Kota Bun-seng, kota di mana mereka berempat baru saja menimbulkan kegemparan, sudah jauh tertinggal di belakang mereka. Penunggang-penunggang kuda itu adalah para lelaki muda yang semuanya berwajah garang dan tidak terawat. Mereka adalah sisa kelompok yang selalu diburu dan bahkan tidak jarang hampir tertumpas.
Yang berkuda paling depan adalah lelaki bertubuh tinggi semampai yang merupakan pemimpin kelompok. Umurnya baru sekitar 25 tahun tetapi nampak seperti berumur 40 tahun sebab kumis dan jeggotnya yang tidak pernah dicukur itu telah tumbuh serabutan. Wajahnya sebenarnya cukup tampan, namun nampak keruh dan ganas, bahkan sinar matanya menampilkan pula sifat-sifatnya yang liar. Di bukan lain adalah Tong Wi-siang, kakak dari Tong Wi-hong dan Tong Wi-lian, putera tertua mendiang Kiang-se-tay-hiap Tong Tian.
Ketika merasa telah cukup jauh dari kota Bun-seng dan cukup aman, Tong Wi-siang lalu memberi isyarat kepada tiga orang kawannya untuk memperlambat lari kuda mereka. Lalu mereka memperlambat lari kudanya dan berkuda perlahan-lahan sambil membisu seribu bahasa. Wajah mereka masih melukiskan ketegangan yang baru saja mereka alami di Bun-seng.
Bagaimana tidak merasa tegang, kalau menyadari bahwa “permainan” yang baru saja mereka lakukan itu ternyata berakibat sedemkian hebat sehingga belasan orang kawan mereka terpaksa ditinggal sebagai mayat-mayat di Bun-seng. Sedang mereka sendiri pun hampir-hampir tidak bisa lolos dari lubang jarum.
Wi-siang sendiri berkuda paling depan, pandangan matanya yang kosong-melompong menatap ke depan. Anak muda berhati sekeras besi dan kenyang dengan pengalaman-pengalaman berbahaya itu ternyata sedang gundah hati. Tadi sebelum meninggalkan kota Bun-seng telinganya mendengar seorang gadis memanggil-manggil namanya sambil berlarian. Gadis itu adalah adiknya, yang meskipun sering bertengkar dengannya karena sama-sama berwatak keras, namun juga sangat disayanginya.
Tadi, ketika sang adik mengejarnya, alangkah rindunya Tong Wi-siang sehingga berniat untuk melompat turun dari kudanya dan memeluk adiknya, tetapi keadaan telah memaksanya untuk berbuat lain. Wi-siang sadar bahwa jika sampai tempat itu dikepung oleh prajurit-prajurit kerajaan dalam jumlah besar, maka tiada harapan lolos lagi baginya dan bagi kawan-kawannya. Karena itulah dia mengeraskan hati dengan tidak menghiraukan sama sekali seruan adiknya, meskipun saat itu hatinya bagaikan tersayat-sayat.
Dalam hatinya yang sekeras batu ternyata bisa juga timbul rasa penyesalan. Tadinya keluarganya hidup tenteram di An-yang-shia, namun kini telah berantakan dan terpencar-pencar tidak keruan lagi. Tong Wi-siang merasa sangat menyesal karena merasa bahwa dirinyalah yang menyebabkan semua kehancuran itu, sifat bengalnyalah yang menjadi biang keladi semua malapetaka itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur, waktu terus berjalan ke depan, dan Wi-siang tidak akan mampu memutar roda waktu agar balik seperti semula.
Sambil berkuda perlahan, dia mulai melamun membayangkan masa kecil dan masa menjelang dewasanya. Waktu itu dia merupakan pelindung bagi kedua adiknya, meskipun kedua adiknya bukan merupakan anak-anak yang cengeng. Bahkan Tong Wi-siang berani berkelahi dengan siapapun demi melindungi adaik-adiknya. Ketika menginjak masa remaja, mulailah ia mendapatkan kawan-kawan yang bertabiat buruk yang sedikit demi sedikit mulai mempengaruhi sifat-sifat Wi-siang.
Ia mulai menjadi seorang anak yang tidak betah diam di rumah untuk berkumpul bersama keluarga, dia lebih senang bersama dengan kawan-kawannya, bergerombol di tempat-tempat ramai di an-yang-shia. Ia dan kawan-kawannya senang membuat kekacauan yang dianggapnya sebagai tanda “kejantanan” mereka. Berjudi, berkelahi, makan-minum tanpa membayar, dan sebagainya.
Bahkan kemudian ia menjadi yang paling menonjol sehingga diangkat menjadi pemimpin anak-anak bengal itu. Puncak kenakalan mereka adalah ketika mereka memutuskan untuk menyerang serombongan pejabat pemerintah dari Pak-khia karena bujukan salah seorang dari mereka yang ingin membalas dendam sakit hati ayahnya.
Sejak saat itu tertutuplah kemungkinan bagi Wi-siang dan gerombolannya untuk pulang ke An-yang-shia. Mereka menjadi buronan pemerintah kerajaan Beng, berlari dan bersembunyi dari tempat satu ke tempat lainnya. Tidak jarang mereka harus bertempur dengan kelompok-kelompok prajurit kerajaan atau melawan pemburu-pemburu upahan Cia To-bun.
Pada suatu hari, Tong Wi-siang tidak dapat menahan diri lagi dan ingin menjenguk keadaan rumahnya. Teman-temannya pun mendukung rencana itu, sebab teman-teman Wi-siang itupun merupakan anak-anak kelahiran an-yang-shia dan masih punya keluarga di An-yang-shia. Namun alangkah sedih dan murkanya anak-anak muda itu setelah menjumpai rumah mereka dalam keadaan menjadi puing atau sudah kosong. Bahkan ada yang seluruh keluarganya telah ditangkap dan entah dibawa kemana.
Tong Wi-siang sendiri menemui rumahnya dalam keadaan sudah menjadi puing-puing yang dihuni binatang-binatang liar. Agak jauh dari rumahnya ia menemukan segunduk kuburan tanpa nama yang hanya ditandai dengan sebatang pedang, tetapi Wi-siang tahu bahwa kuburan itu adalah kuburan ayahnya sebab ia mengenal pedang ayahnya itu. Di depan makam itulah Tong Wi-siang berlutut dan menangis meluapkan penyesalannya, sekaligus menyulut api dendam buat dirinya sendiri.
Lalu bersama kawan-kawannya yang juga sedang gelap pikiran, anak-anak muda yang nekat itu menyerbu rumah Cia To-bun. Tapi kedatangan mereka bagaikan serombongan serangga yang menubruk nyala api. Bukan saja mereka berhasil diusir oleh pengawal-pengawal Cia To-bun, bahkan gerombolan mereka pun kehilangan separuh dari anggota mereka setelah bertempur dengan para pengawal Cia To-bun.
Rombongan anak-anak muda yang kehilangan pegangan tersebut lalu menjadi liar, bergentayangan dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mencari penyaluran bagi perasaan mereka yang meledak-ledak. Jadilah mereka pengacau di mana-mana, dan setiap kali bertempur dengan pasukan pemerintah, jumlah mereka pun terus berkurang, ada yang terbunuh, tertawan, atau diam-diam melarikan diri untuk melepaskan diri dari gerombolan.
Yang terakhir adalah kekacauan yang mereka perbuat di kota Bun-seng. Di sini gerombolan Wi-siang mengalami pukulan berat, sebab dari limabelas orang, yang hidup hanya empat orang. Selain itu, Tong Wi-siang pribadi pun mengalami sesuatu yang meresahkan hatinya, yaitu pertemuannya dengan adik perempuan yang disayanginya.
Kini keempat orang sisa gerombolan telah melarikan diri puluhan li jaraknya dari kota Bun-seng. Ketiga kawan Wi-siang melihat punggung Tong Wi-siang terguncang-guncang. Mereka mengira bahwa pemimpin mereka terguncang karena larinya kuda, dan mereka sama sekali tidak akan menduga bahwa pemimpin mereka yang garang itu sebenarnya sedang menangis.
“A-siang!” salah seorang dari kawannya memanggil. “Apakah kita tidak akan beristirahat barang sebentar? Kukira kini kita sudah cukup jauh dari Bun-seng, sudah cukup aman, bahkan sebentar lagi kita mungkin akan sampai kota Kiang-leng.”
Wi-siang tidak menoleh sebab tidak ingin air matanya dilihat oleh teman-temannya. Sahutnya tanpa menoleh, “Kita tidak boleh lengah sekejappun, sebab kita berempat adalah buronan pemerintah kerajaan, dan ada tersedia hadiah besar buat batok-batok kepala kita. Jika kita melewati tempat ramai, tentu jejak kita akan tercium oleh anjing-anjing kerajaan itu.”
“Tetapi kuda tunggangan kita sudah mulai kelelahan, sudah beberapa hari kita pakai secara diluar batas,” bantah kawannya. “Bahkan bisa mati kelelahan kalau tidak kita istirahatkan.”
Jawab Wi-siang, “Persetan! Aku tidak ingin tertangkap lalu diarak keliling kota sebelum kepala kita dipisahkan oleh golok algojo. Karena itu kita jalan terus!”
“Tetapi...” Kawannya yang hendak membantah itu terbungkam setelah Wi- siang menyahutnya dengan suara hampir berteriak, “Jangan membantahku lagi, Hong-pin!”
Anak muda kawan Wi-siang itu bernama Hong-pin. Sebenarnya ia masih terlalu muda untuk ikut-ikutan dalam petualangan sekeras itu, umurnya bahkan lebih muda dari adik Wi-siang yang terkecil, yaitu Wi-lian. Lim Hong-pin adalah anak seorang keluarga pedagang hasil bumi yang terhitung kaya-raya untuk ukuran An-yang-shia. Namun sejak Lim Hong-pin terlibat dalam pembunuhan pejabat dari Pak-khia, maka usaha dagang ayahnya ditutup dan rumahnya disegel oleh pemerintah, sedang keluarga Lim Hong-pin sendiri sudah pindah entah kemana.
Demi menyelamatkan diri dari kejaran pemerintah, Lim Hong-pin terpaksa terus bergabung dalam “pasukan” Tong Wi-siang dan ikut mengacau ke mana-mana. Sering juga ia menyesal kenapa dulu tidak menuruti anjuran ayahnya untuk belajar dagang saja, alih-alih malahan bergaul rapat dengan pengacau-pengacau ini, dan akhirnya kini ia harus memetik hasil dari perbuatannya sendiri.
Dua orang teman Wi-siang lainnya masing-masing bernama Siangkoan Hong dan Tan Goan-ciau. Siangkoan Hong ini juga anak seorang kaya, ayahnya adalah seorang pengusaha rumah makan terbesar di An-yang-shia, tapi nasibnya sama dengan Lim Hong-pin, yaitu tidak berani pulang ke rumah karena takut dikirim ke bawah golok algojo. Dalam gerombolan Wi-siang, Siangkoan Hong ini terkenal keberaniannya...
Selanjutnya;