Matahari Senja
Bagian 20
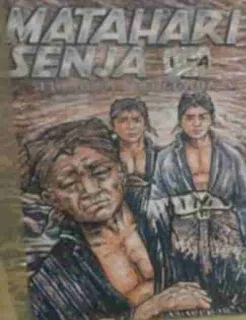
KI LEMAH TELES tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Diperintahkannya, para cantrik yang bersenjata anak panah untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, maka beberapa batang anak panah sendaren telah terlepas dari busurnya. Anak panah yang memberikan isyarat kepada semua kekuatan yang dibawa oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari untuk bergerak serentak.
Ki Lemah Teles yang berada di panggungan pun tanggap akan perintah itu. Ketika ia melihat pasukan itu mulai bergerak, maka Ki Lemah Teles telah memerintahkan membunyikan isyarat dengan memukul bende diatas panggungan itu.
Demikian suara bende itu meraung-raung diatas panggungan, maka para cantrik seisi padepokan itu telah bersiap. Anak-anak muda dari beberapa padukuhan yang telah berada di padepokan itupun telah mendapatkan dirinya pula.
Sebagian dari mereka memang sudah mempunyai sedikit pengalaman, tetapi yang lain sama sekali belum. Namun para pemimpin padepokan itu masih sempat memberikan latihan-latihan kepada mereka meskipun baru landasannya saja sementara lawan mereka adalah orang-orang yang setiap saat selalu bercanda dengan senjata mereka.
Tetapi para cantrik padepokan Kiai Banyu Bening yang mengikuti jejak Ki Warana juga cukup banyak. Merekapun memiliki pengalaman sebagaimana para pengikut Kiai Narawangsa.
Demikianlah, maka sejenak kemudian, seperti arus banjir bandang, para pengikut Kiai Narawangsa telah menyerang padepokan yang telah ditinggalkan oleh Kiai Banyu Bening itu. Mereka menerobos pintu gerbang induk dan pintu-pintu gerbang butulan yang telah menjadi abu. Tetapi demikian mereka mulai bergerak, maka anak panah pun tercurah bagaikan hujan.
Tetapi hal itu memang sudah diperhitungkan oleh Kiai Narawangsa dan para pengikutnya. Karena itu, merekapun tidak terkejut sama sekali. Bahkan mereka telah siap untuk menangkis serangan anak panah yang menghujan itu.
Meskipun demikian, beberapa orang telah terhenti di pintu-pintu gerbang. Anak panah yang menyusup dibawah perisai dan mengenai lutut, telah melumpuhkan beberapa pengikut Kiai Narawangsa. Namun ada pula anak panah yang menembus dada, sehingga orang yang dikenainya terjatuh dan terinjak-injak oleh kawan-kawannya. Mereka untuk selamanya tidak akan pernah bangkit lagi.
Sejenak kemudian, maka banturan kekuatanpun telah terjadi. Tetapi demikian derasnya arus serangan yang mengalir dari luar padepokan, telah memaksa para cantrik untuk bergerak mundur. Tetapi para cantrik itu tidak melepaskan para penyerang untuk begitu saja memasuki padepokan yang telah mereka rebut dari tangan Panembahan Lebdagati itu.
Pertempuran pun segera menyala dengan sengitnya. Senjata yang teracu-acu, berputaran dan terayun-ayun itu, telah saling berbenturan. Suaranya berdentang diantara teriakan-teriakan yang mengguruh dari kedua belah pihak.
Di induk pasukan Kiai Narawangsa bertempur dengan garangnya. Apa saja yang ada didepannya telah disapunya tanpa ampun. Namun langkahnya terhenti ketika dihadapannya berdiri seorang yang sudah berada diusia senjanya.
“Sabarlah sedikit. Kiai Narawangsa. Jangan kau sapu anak-anak seperti menebas batang ilalang. Seharusnya kau mempunyai sedikit harga diri dengan mencari lawan yang seimbang, setidak-tidaknya mampu memberikan sedikit perlawanan.”
“Siapa kau?” bertanya Kiai Narawangsa.
“Namaku Ajar Pangukan.” jawab orang itu.
Kiai Narawangsa menarik nafas dalam-dalam. Katanya ”Namamu tidak dikenal. Minggirlah. Kau sudah terlalu tua untuk berada di medan pertempuran. Aku tidak akan menghancurkanmu sebagaimana orang-orang lain yang berani mendekati aku.”
“Kiai Narawangsa, aku berniat untuk melawanmu apapun yang terjadi.”
“Kau ternyata belum mengenal aku yang sebenarnya.”
“Jika sekarang aku berdiri disini, justru karena aku ingin mengenalmu sebaik-baiknya.”
“Nampaknya kau juga orang berilmu. Tetapi belum terlambat bagimu jika kau ingin menyingkir.”
“Aku akan tetap mencoba menghadapimu. Marilah, aku sudah bersiap sepenuhnya.”
Kiai Narawangsa menggeram. Katanya ”Apaboleh buat jika aku harus membunuhmu.”
“Bukankah didalam perang dapat saja terjadi, membunuh atau dibunuh?”
“Bagus. Kau benar-benar sudah siap maju ke medan pertempuran. Aku senang mendapat seorang lawan yang sedikit dapat menggelitik ilmuku.”
Ki Ajar Pangukan pun kemudian telah bersiap. Kiai Narawangsa telah bergerak selangkah ke samping. Demikian pula Ki Ajar Pangukan sehingga keduanya untuk beberapa saat saling bergeser setapak-setapak.
Sesaat kemudian, maka Kiai Narawangsa yang garang itu mulai meloncat menyerang. Tetapi serangannya yang seakan-akan sekedar untuk menyentuh kulit lawannya itu pun telah dielakkan oleh Ki Ajar Pangukan.
Namun serangan-serangan Kiai Narawangsa berikutnya justru menjadi semakin cepat dan semakin garang. Namun demikian, serangan-serangan itu tidak menyentuh sasarannya. Tetapi Kiai Narawangsa memang belum bersungguh-sungguh. Ia masih ingin mengetahui serba sedikit tentang kemampuan lawannya yang sudah lewat separo baya.
Ki Ajar Pangukan pun masih belum benar-benar bertempur. Seperti Kiai Narawangsa, Ki Ajar Pangukan baru sekedar ingin mengintip kemampuan lawannya. Karena itu, maka keduanya masih belum menapak pada ilmu mereka yang sebenarnya.
Dalam pada itu, yang lebih kasar dari Kiai Narawangsa adalah Ki Gunasraba. Dengan senjata bindi ia menghancurkan apa saja yang ada disekitarnya. Untuk menahan geraknya, maka lima orang cantrik padepokan itu telah mengepungnya. Namun bindi Gunasraba berputaran dengan cepat. Bindi yang besar itu memang sulit untuk ditahan.
Jika terjadi benturan dengan senjata para cantrik, maka senjata-senjata itu harus digenggam erat-erat. Dua orang cantrik telah kehilangan senjata mereka dalam benturan dengan bindi Gunasraba. Untunglah, seorang diantara mereka segera mendapatkan senjata kembali. Sementara cantrik yang lain telah memungut senjata siapa pun juga yang terkapar tidak jauh daripadanya.
Meskipun berlima, ternyata cantrik itu mengalami kesulitan. Yang dapat mereka lakukan adalah sekedar menahan, agar Gunasraba tidak mengacaukan pertahanan para cantrik pemula yang masih belum cukup berpengalaman. Namun diantara riuhnya geram dan teriakan-teriakan, terdengar seseorang berkata,
”Minggirlah. Aku akan mencoba menghadapinya.”
Para cantrik itu memang segera menyibak. Yang muncul adalah Ki Sambi Pitu. Seorang yang rambutnya sudah mulai ubanan. Beberapa lembar yang terjurai dibawah ikat kepalanya, nampak kelabu keputih-putihan.
“Kau mau apa, kakek tua?“ bertanya Gunasraba.
“He, aku belum tua!” jawab Ki Sambi Pitu ”Gigiku masih utuh.”
“Tetapi rambutmu sudah mulai memutih.” sahut Gunasraba.
“Aku dapat menyembunyikan rambutku dibawah ikat kepalaku.”
“Kau cukur sampai gundul pun kau tidak akan dapat menyembunyikan umurmu.”
Ki Sambi Pitu tertawa. Katanya, ”Aku memang sudah tua.”
“Minggirlah. Jangan ganggu aku. Aku akan membinasakan orang-orang yang berani menghalangi jalanku menuju ke pendapa bangunan utama padepokan ini.”
Tetapi Ki Sambi Pitu justru tertawa. Katanya, ”Kau suka yang aneh-aneh, Ki Sanak. Kau kira kami akan mempersilahkan kalian naik ke pendapa dan menyuguhkan hidangan minuman hangat dan makan siang dengan memotong tiga ekor lembu?”
“Setan kau orang tua yang tidak tahu diri. Sekali kau tersentuh senjataku, maka tubuhmu akan segera lumat.”
Tetapi Ki Sambi Pitu tidak bergeser dari tempatnya. Dengan tangkasnya Ki Sambi Pitu telah menggerakkan pedangnya. Namun Ki Sambi Pitu itu sadar, bahwa bindi lawannya yang berat itu merupakan senjata yang berbahaya. Ia harus menghindari benturan langsung sejauh dapat dilakukannya.
Gunasraba yang marah itupun kemudian berkata, ”Jika demikian bersiaplah untuk mati. Tubuhmu akan segera lumat menjadi debu.”
Ki Sambi Pitu tidak menjawab lagi. Tetapi ia benar-benar sudah siap untuk menghadapinya. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit, mereka tidak merasa perlu untuk saling menjajagi. Apalagi tangan Gunasraba sudah terlanjur berkeringat ketika ia menghadapi kelima orang cantrik yang berusaha membatasi geraknya.
Tetapi karena itu, maka Gunasraba pun segera terkejut. Orang tua itu ternyata mampu bergerak dengan tangkas. Tubuhnya bahkan seakan-akan seringan kapas. Sementara itu senjatanya berputaran dengan cepat, sehingga sebilah pedang itu seakan-akan telah berubah menjadi dua atau tiga atau bahkan empat.
“Gila kakek tua ini...” geram Gunasraba. Namun Gunasraba juga bukan orang kebanyakan. Iapun memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan kekuatan Gunasraba ternyata memang melampaui kekuatan orang kebanyakan.
Namun dalam pada itu, demikian pasukan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari memasuki halaman padepokan, maka Nyai Wiji Sari langsung dapat melihat sebuah tugu batu dan sebuah nisan kecil diatasnya sebagaimana pernah dilaporkan oleh orang-orangnya yang pernah datang ke padepokan itu.
Karena itu, maka jantungnya benar-benar telah bergejolak. Demikian pasukannya sempat mendorong pertahanan para cantrik dari padepokan itu mundur, maka Nyai Wiji Sari tidak dapat menahan dirinya. Nyai Wiji Sari pun dengan garangnya telah menerobos menusuk langsung pertahanan lawan. Tiba-tiba saja perempuan itu terlepas dari medan dan berlari langsung ke tugu didepan bangunan utama padepokan itu.
Dengan perasaan yang bergejolak, maka Nyai Wiji Sari pun segera berlutut didepan tugu itu. Dua orang pengawalnya tidak melepaskan Nyai Wiji Sari pergi sendiri. Karena itu, maka keduanya segera memburunya. Demikian Nyai Wiji Sari berlutut didepan tugu dengan nisan kecil diatasnya itu, maka kedua orang pengawalnya itupun telah bersiap untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi.
Beberapa orang cantrik memang siap untuk mengejar mereka. Tetapi seorang yang bongkok telah menahan mereka. “Biarlah aku yang mengurusnya.”
Para cantrik itu mengurungkan niatnya. Namun karena Nyai Wiji Sari dikawal oleh dua orang pengikutnya, maka dua orang cantrik yang semula menjadi pengikut Kiai Banyu Bening telah ikut bersama Ki Pandi. Kedua orang pengawal Nyai Wiji Sari itu pun segera mempersiapkan diri ketika mereka melihat Ki Pandi berjalan mendekat.
Namun nampaknya Ki Pandi tidak akan dengan serta merta menyerang mereka. Sebenarnyalah Ki Pandi melangkah dengan tenang mendekat. Dahinya berkerut ketika ia melihat Nyai Wiji Sari itu mengusap matanya yang basah.
“Maafkan ibumu, anakku” desisnya ”Ibu tidak dapat menjagamu dengan baik, sehingga bencana itu terjadi.”
“Kesalahanmu tidak terletak pada kelengahanmu menjaganya, Nyai.” tiba-tiba saja Ki Pandi menyahut ”Tetapi sumber kesalahan itu adalah karena kau tidak setia.”
Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Ia sudah siap menghadapi perempuan itu jika ia menjadi marah. Tetapi yang tidak terduga itupun terjadi. Nyai Wiji Sari yang garang itu tidak dengan serta-merta bangkit dan menyerang Ki Pandi yang bongkok itu. Tetapi ia justru menjawab, “Kau benar, Ki Sanak. Ketidak-setiaan itu adalah sumber dari bencana ini.”
Nyai Wyi Sari justru menangis. Isaknya telah mengguncang tubuhnya ”Maafkan aku anakku. Ketidak setiaanku itu pula yang membuat Kiai Banyu Bening menjadi gila. Pada mulanya ia bukan orang yang jahat. Tetapi ketika ia melihat seorang laki-laki didalam bilik tidurnya dan bahkan membiarkan anaknya menangis, maka ia menjadi seperti orang gila. Malapetaka itu terjadi. Rumah itu terbakar dan bayi inipun terbakar. Sejak itu, Kiai Banyu Bening telah berubah. Ia menjadi seorang penjahat yang ditakuti. Bahkan menurut pendengaranku, ia benar-benar menjadi gila disini, karena ia berniat mengorbankan bayi-bayi yang dibakar hidup-hidup didalam api. Ia ingin membalas dendam karena kematian bayinya yang terbakar itu. Ia ingin banyak orang mengalami kepahitan sebagaimana dialaminya.”
Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Yang dilihatnya berlutut itu bukan seorang perempuan garang yang terbiasa berpacu diatas punggung kuda, menjelajahi padukuhan dan bulak-bulak panjang dimalam hari. Tetapi yang berlutut itu adalah seorang perempuan yang menyesali jalan hidupnya yang sesat.
“Ki Sanak!” terdengar Nyai Wiji Sari itu berdesis. ”Apakah benar Kiai Banyu Bening telah meninggal?”
“Ya, Nyai,” jawab Ki Pandi ”Kedua orang ini adalah orang yang tinggal bersama Kiai Banyu Bening untuk waktu yang lama.”
“Apakah benar, Panembahan Lebdagati yang telah membunuh Kiai Banyu Bening?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Ya, Nyai...” jawab salah seorang dari kedua orang cantrik itu. ”Kiai Banyu Bening telah terbunuh oleh Panembahan Lebdagati. Padepokan ini pernah diduduki oleh Panembahan Lebdagati yang telah membunuh Kiai Banyu Bening itu.”
“Kenapa Panembahan Lebdagati membunuh Kiai Banyu Bening?”
“Menurut Panembahan Lebdagati, daerah ini, sepanjang lereng Gunung Lawu adalah daerahnya.”
“Apakah itu benar?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Panembahan Lebdagati memang pernah menguasai daerah ini. Tetapi ia pernah terusir oleh beberapa orang berilmu tinggi yang tidak dapat membiarkan kepercayaan sesatnya berkembang. Setiap purnama ia mengorbankan seorang gadis untuk membuat pusakanya menjadi pusaka terbaik di muka bumi.”
Dahi Nyai Wiji Sari berkerut. “Lalu kenapa kalian kemudian dapat tinggal di padepokan ini?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Kami mengambilnya dari tangan Panembahan Lebdagati.”
“Jadi kau juga pengikut Kiai Banyu Bening?“ bertanya Nyai Wiji Sari.
“Tidak, Nyai. Kebetulan tidak. Aku terlibat setelah tempat ini diduduki oleh Panembahan Lebdagati.” jawab Ki Pandi.
Nyai Wiji Sari termangu-mangu sejenak. Tetapi ia masih tetap berlutut. Sementara sekali-sekali tangannya masih mengusap air matanya. Dalam pada itu, seorang pengawalnyalah yang berkata, ”Sudahlah Nyai. Kiai Narawangsa masih terlibat dalam pertempuran yang sengit. Apakah Nyai tidak akan melibatkan diri?”
Tiba-tiba saja Nyai Wiji Sari mengangkat wajahnya. Dipandanginya Ki Pandi dengan tajamnya. Ternyata wajah Nyai Wiji Sari itu berubah. Meskipun pelupuknya masih basah, tetapi mata itu bagaikan telah menyala.
Ki Pandi melihat perubahan itu. Karena itu, maka ia pun telah bersiap kembali untuk menghadapi segala kemungkinan. Agaknya Nyai Wiji Sari itu telah menghentakkan diri dari rintihan nuraninya, kembali ke dalam dunia petualangannya yang garang, yang penuh dengan kekerasan dan kekelaman nalar budi.
“Orang bongkok...!” geram Nyai Wiji Sari kemudian ”Kau tentu salah satu dari orang yang telah mengacaukan segala sesuatunya. Mungkin kau justru yang telah mendalangi agar Panembahan Lebdagati membunuh Kiai Banyu Bening. Namun kemudian kau khianati Panembahan itu. Kau dengan licik telah mengadu kekuatan orang-orang berilmu tinggi. Diatas mayat mereka sekarang kau menari di padepokan ini.”
Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Selangkah ia bergerak surut ketika Nyai Wiji Sari yang telah bangkit berdiri itu melangkah maju sambil memandanginya dengan mata yang membara.
“Tidak, Nyai...“ suara Ki Pandi masih tetap lunak ”Kau kembali terbenam ke alam arus perasaanmu yang kau landasi pengalaman hidupmu yang kelam. Ketika sepercik terang bersinar di hatimu, maka kau dapat menemukan dirimu sendiri. Tetapi jika kelam itu datang menyelimuti kalbumu, maka kau menjadi seorang perempuan yang garang.”
“Cukup. Siapa pun kau dan apapun yang kau katakan, namun aku datang untuk mengambil padepokan ini. Aku akan selalu berada disisi anakku. Ia sendiri disini, apalagi sepeninggal Kiai Banyu Bening.”
“Kaupun harus berpikir bening, Nyai.”
“Cukup. Tengadahkan wajahmu. Aku akan menebas lehermu. Kau akan dikubur disini, dibawah tugu ini. Kau akan menjadi pengawal anakku dan melakukan apa saja yang diinginkannya. Bahkan kau akan menjadi kuda tunggangan yang jinak dan penurut.”
Ki Pandi mengerutkan dahinya. Mata Nyai Wiji Sari justru menjadi liar. Tiba-tiba saja perempuan itu telah mencabut senjatanya, sebilah pedang. Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Perasaan Nyai Wiji Sari yang kacau telah mendorongnya untuk bertempur langsung pada tataran yang menentukan.
Ki Pandi memang tidak dapat mengelak. Ia sadar, bahwa Nyai Wiji Sari itu tentu memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka Ki Pandi tidak ingin menjadi lengah dan kehilangan kesempatan. Demikian Nyai Wiji Sari mulai memutar pedangnya, maka Ki Pandi telah melepas ikat kepalanya dan dibalutkan pada lengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam sebuah seruling yang semula terselip di punggungnya.
Betapapun gelap nalar Nyai Wiji Sari, tetapi ketika ia melihat senjata Ki Pandi, maka Nyai Wiji Sari itupun segera menyadari, bahwa orang bongkok itu bukannya orang kebanyakan. Karena itu, maka Nyai Wiji Sari itupun menjadi sangat berhati-hati menghadapinya. Kedua orang pengawal Nyai Wiji Sari telah bersiap pula. Mereka bergeser di sebelah menyebelah Nyai Wiji Sari.
Ki Pandi masih bergeser surut. Kedua orang cantrik yang menyertai telah bersiap pula. Mereka akan menghadapi kedua orang pengawal Nyai Wiji Sari. “Kau sadari apa yang aku lakukan, Nyai?” bertanya Ki Pandi.
“Kau mulai ketakutan bongkok. Sayang, aku tidak mempunyai perasaan belas kasihan kepada siapa pun juga. Apalagi jika aku sudah terlanjur mencabut pedangku.”
Ki Pandi tidak menjawab. Sementara itu Nyai Wiji Sari telah mengangkat pedangnya sambil berkata lantang, ”Lihat pedangku yang berwarna kehitam-hitaman. Ini adalah warna darah yang membeku di daun pedangku. Aku tidak pernah membersihkannya jika pedangku berlumur darah.”
Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya daun pedang Nyai Wiji Sari yang menyeramkan. Sama sekali tidak berkilat ditimpa cahaya matahari. Warna coklat kehitaman membuat tengkuk Ki Pandi meremang. Tetapi Ki Pandi tidak mempunyai banyak kesempatan untuk merenungi lawannya yang menilik senjatanya, Nyai Wiji Sari benar-benar telah terbenam terlalu dalam di lumpur yang pekat.
Nampaknya dengan caranya Nyai Wiji Sari ingin melupakan kepahitan jalan hidupnya yang bernoda. Bahkan Nyai Wiji Sari juga ingin melupakan perasaan bersalah yang selalu membayanginya kemana saja ia pergi. Dalam pada itu, maka Nyai Wiji Sari pun mulai menggapai tubuh Ki Pandi dengan ujung pedangnya. Namun Ki Pandi bergeser. menghindar.
Nyai Wiji Sari menyadari, bahwa kain ikat kepala Ki Pandi yang dipergunakan untuk membalut lengan kirinya, tentu bukan kebanyakan ikat kepala. Ikat kepala itu tentu selembar ikat kepala yang dibuat secara khusus. Yang liat dan seratserat benangnya tidak mudah terputus oleh tajamnya senjata.
Demikian pula seruling ditangan kanan orang bongkok itu. Tentu bukan seruling yang dibelinya di pasar atau di sebuah keramaian merti desa. Tetapi seruling itu tentu sebuah seruling yang dibuat secara khusus pula.
Demikianlah, maka sejenak kemudian, pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Nyai Wiji Sari ternyata memang seorang perempuan yang tangkas, yang memiliki ilmu yang tinggi. Pedangnya berputaran dengan cepat. Sambaran anginnya bagaikan menusuk-nusuk lubang kulit. Tetapi Nyai Wiji Sari harus melihat kenyataan, bahwa orang bongkok yang buruk itu ternyata benar-benar memiliki ilmu yang tinggi.
Apapun yang dilakukan oleh Nyai Wiji Sari, Ki Pandi mampu mengindarinya atau menangkisnya dengan lengannya yang dibalut dengan ikat kepalanya atau dengan serulingnya. Dengan demikian, maka Nyai Wiji Sari harus meningkatkan ilmunya. Bahkan sampai pada tataran tertinggi.
Dalam pada itu, di pintu-pintu butulan, pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Di pintu butulan sebelah kiri, Manggada dan Laksana telah bertemu dengan dua orang yang pernah berjalan berpapasan di jalan bulak. Sebagaimana Manggada dan Laksana masih mengenali kedua . orang anak muda itu, ternyata keduanya juga masih mengenali Manggada dan Laksana.
“Jadi kau penghuni padepokan ini, he?” bertanya Parung Landung.
Manggada termangu-mangu sejenak. Katanya, “Kita pernah bertemu Ki Sanak.”
“Kalau aku tahu, kau penghuni padepokan ini, maka saat kita berpapasan, kepalamu tentu sudah aku lumatkan.”
Laksana tiba-tiba saja tertawa. Katanya, ”Aku menyesal bahwa kami waktu itu memberikan jalan kepadanya, sehingga kami terpaksa berjalan diatas tanggul parit. Waktu itu, aku memang sudah merencanakan untuk mencabuti kumismu yang jarang itu. Tetapi kakakku mencegahnya.”
“Tutup mulutmu!” Paron Waja menggeram. ”Aku akan menyumbat mulutmu sekarang.”
Laksana masih saja tertawa. Katanya, “Kita mempunyai kesempatan yang sama sekarang. Kawan-kawanmu dan para cantrik di padepokan ini tengah bertempur. Kita pun akan bertempur tanpa orang lain yang akan mengganggu.”
“Bagus. Kita akan bertempur tanpa orang lain yang akan mengganggu kita sampai tuntas,“ jawab Parung Landung.
“Kita bertempur di medan perang. Bukan sedang berperang tanding. Karena itu, kemungkinan datangnya gangguan dapat saja terjadi. Karena itu, persetan dengan istilahnya. Sejauh kita mendapat kesempatan bertempur seorang lawan seorang, maka kita akan melakukannya."
“Nah, kami silahkan kalian memilih lawan.”
Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Tetapi Laksanalah yang berkata, ”Kalian saja yang memilih. Aku harus melawan yang mana, dan kakang Manggada yang mana. Bagi kami siapa pun yang kami hadapi, tidak ada bedanya. Kami sudah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan.”
Paron Waja menggeram. Katanya, “Biarlah aku bungkam mulut anak ini.”
Laksana tertawa pula. Katanya, “Mulut ini ada yang punya. Tentu yang punya akan berkeberatan jika mulut ini akan dibungkam.”
Kemarahan Paron Waja benar-benar sudah membakar jantungnya. Karena itu, tiba-tiba saja ia telah meloncat sambil mengayunkan tangannya ke arah wajah Laksana. Tetapi Laksana sudah bersiap sepenuhnya. Dengan tangkas ia bergeser surut, sehingga tangan Paron Waja tidak menyentuh kulitnya. Namun terasa desir angin menerpa wajah Laksana yang luput dari jangkauan tangan Paron Waja itu. Dengan demikian Laksana menyadari, bahwa kekuatan Paron Waja memang sangat besar.
Sementara itu, ketika Paron Waja mulai menyerang Laksana, maka Manggada tidak menyia-nyiakan waktu. Justru Manggada lah yang lebih dahulu mengambil langkah. Dengan cepat Manggada meloncat sambil menjulurkan kakinya.
Parung Landung melihat serangan itu. Tetapi demikian cepat dan tidak diduga-duga. Karena itu, maka Parung Landung tidak sempat mengelak. Yang dapat dilakukan adalah sekedar menepis serangan kaki Manggada yang kuat itu. Ternyata Parung Landung tidak berhasil sepenuhnya.
Meskipun kaki Manggada itu tidak mengenai sasaran, tetapi kaki itu masih juga mengenai pundak. Tubuh Parung Landung itu terputar. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Tetapi Parung Landung justru telah bergeser beberapa langkah untuk memperbaiki kedudukannya.
Manggada memang tidak memburunya. Ia tidak ingin dianggap curang dan licik. Karena itu, maka Manggada itupun menunggu sejenak, sehingga Parung Landung berdiri tegak dan siap untuk menghadapinya.
Parung Landung itupun menggeram. ”Ternyata kau licik sekali.”
“Tidak. Bukan aku yang licik. Tetapi kau terlalu yakin akan kemampuanmu sehingga kau abaikan aku. Aku memang tidak ingin menentukan akhir dari pertempuran diantara kita dengan serangan yang pertama itu. Aku baru sekedar memperingatkanmu, agar kau berhati-hati.”
“Kau dapat saja membuat seribu macam alasan. Tetapi sekarang, marilah kita buktikan, siapakah diantara kita yang akan dapat keluar dari pertempuran ini utuh. Bukan hanya namanya.”
Manggada menarik nafas dalam-dalam. Lawannya ternyata memang seorang yang sangat yakin akan kemampuannya Karena itu, maka Manggada pun telah bersiap sebaik-baiknya untuk menghadapinya. Demikianlah, Manggada dan Laksana telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Lawan mereka juga masih muda. Tetapi Parung Landung dan Paron Waja agaknya lebih tua dari lawan-lawan mereka.
Pertempuran antara anak-anak muda itupun dengan cepatnya meningkat. Jantung mereka lebih cepat membara dan darah mereka lebih cepat mendidih. Sehingga beberapa saat kemudian, maka pertempuran itu menjadi semakin garang dan segenap kemampuannya dikerahkan.
Parang Landung dan Paron Waja yang terbiasa hidup dalam petualangan, sama sekali tidak merasa canggung. Bahkan mereka pun berusaha dengan cepat untuk mengakhiri lawan lawan mereka, agar mereka segera dapat terlibat dalam pertempuran melawan para cantrik dari padepokan itu. Adalah sangat menggembirakan untuk membantai cantrik-cantrik pemula yang masih belum banyak berpengalaman.
Tetapi ternyata mereka tidak dapat melakukannya semudah yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Kedua anak muda yang mereka hadapi itu ternyata adalah anak-anak muda yang berbekal ilmu sehingga untuk beberapa saat mereka masih mampu mengimbangi ilmu mereka.
Karena itu, setelah bertempur beberapa saat lamanya, Parung Landung justru mengumpat-umpat kasar. Ternyata tangan Manggada sempat menggapai keningnya. Meskipun tidak terlalu keras, namun sentuhan itu sendiri membuat kemarahan Parung Landung semakin memuncak.
Karena itu, maka Parung Landung pun telah menghentakkan kemampuannya pula dengan serangan-serangan beruntun yang sempat mengejutkan Manggada. Karena itu, Manggada telah terdorong surut. Namun serangan Parung Landung masih belum mampu menembus pertahanan Manggada.
Parung Landung menggeram. Ia tidak mau mengalami kenyataan itu. Parung Landung ingin lawannya itu segera dapat diselesaikannya, sehingga dengan wajah tengadah ia dapat menepuk dadanya. ”Aku telah membunuh andalan padepokan ini.”
Tetapi ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Lawannya ternyata sangat liat dan bahkan berilmu tinggi. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit pula.
Paron Waja pun mulai menjadi gelisah, ia menyangka bahwa dalam waktu singkat anak muda itu dapat segera dikalahkannya. Tetapi ternyata bahwa anak muda itu mampu mengimbanginya.
Dalam pada itu, di belakang pintu butulan sebelah kanan, Ki Jagaprana telah menghentikan dua orang yang disangkanya kembar. Kedua orang yang mengamuk seperti sepasang harimau yang terluka.
“Bagus....” Ki Jagaprana mengangguk-angguk ”Apakah memang sudah menjadi kebiasaan kalian bertempur berpasangan?”
“Siapa kau?” bertanya Krendhawa.
“Pertanyaanmu aneh. Seharusnya kau tahu bahwa aku adalah salah satu dari penghuni padepokan ini.”
“Maksudku, siapa namamu?” bentak Krendhawa.
Ki Jagapura tersenyum. Katanya. ”Namaku Jagaprana. Aku mendapat perintah untuk menghentikan kalian berdua. Nah, jika kalian memang terbiasa bertempur berpasangan karena kalian anak kembar, maka aku tidak berkeberatan.”
“Kami bukan saudara kembar.” geram Mingkara ”Umur kami bertaut hitungan tahun.”
“Oh...” Jagaprana mengangguk-angguk ”Tetapi ujud kalian tidak ubahnya dua orang kembar.”
“Agaknya matamu lah yang kabur.” geram Mingkara.
“Aku tidak peduli, apakah kalian kembar atau tidak. Yang penting bagiku, jika kalian terbiasa bertempur berpasangan, marilah. Aku ingin menjajagi kemampuan kalian berdua.”
“Kau terlalu sombong kakek tua. Betapapun tinggi ilmumu, wadagmu sudah tidak membantu. Kau sudah terlalu tua untuk bertempur di medan yang garang menghadapi petualangan yang terbiasa dengan kekerasan. Bahkan seandainya kau matahari yang menyala di langit, kau sudah memasuki masa senjamu.”
Jagaprana tertawa. Katanya, “Sinar matahari senja masih akan mampu membakar bibir mega di langit. Cahaya layung di senja hari masih dapat membuat mata puluhan orang menjadi sakit."
“Iblis kau!” geram Krendhawa ”Suaramu seperti sentuhan welat ditelingaku. Pedih. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Kami ingin menunjukkan, betapa kami mampu bertempur berpasangan melampaui orang kembar sebenarnya.”
Ki Jagaprana masih tertawa. Katanya, ”Marilah, aku sudah siap.”
Mingkara memang tidak sabar lagi. Dengan garangnya, ia pun meloncat menyerang Ki Jagaprana dengan ayunan tangannya. Ki Jagaprana bergeser surut. Tangan itu tidak menyentuh tubuhnya.
Tetapi serangan berikutnya pun segera menyusul. Krendhawa telah menjulurkan kakinya menyerang lambung. Tetapi dengan cepat Ki Jagaprana menggeliat, sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenainya. Bahkan tiba-tiba saja Ki Jagaprana yang tua itu melenting sambil berputar. Kakinya yang terayun mendatar hampir saja menyambar kening Krendhawa.
“Iblis tua!” geram Krendhawa sambil meloncat menjauh.
Ki Jagaprana tertawa pula. Katanya, ”Jangan mengumpat. Umpatanmu tidak akan membantumu mengalahkan aku.”
“Diam kau iblis tua!” teriak Mingkara.
Tetapi Jagaprana tertawa semakin keras. Demikianlah pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Krendhawa dan Mingkara memang bertempur berpasangan. Tetapi ternyata bahwa Ki Jagaprana benar-benar seorang yang berilmu tinggi.
Semakin lama Krendhawa dan Mingkara bertempur melawan orang tua itu, maka mereka pun semakin menyakini akan tingkat kemampuannya, sehingga kedua orang yang dianggap kembar itu harus meningkatkan ilmunya pula.
Pertempuran memang menyala semakin besar. Tidak hanya di belakang pintu-pintu butulan. Tetapi juga di belakang pintu gerbang utama. Agak terpisah, Nyai Wiji Sari tengah bertempur melawan Ki Pandi yang bongkok. Pedang Nyai Wiji Sari yang kehitam-hitaman itu berputar dengan cepat.
Namun Ki Pandi pun telah mengimbanginya. Dengan cepat orang bongkok itu menghindari serangan-serangan Nyai Wiji Sari. Pedang yang terayun-ayun itu tidak segera dapat mengenai tubuh orang bongkok yang mampu bergerak cepat itu.
Namun sebenarnyalah, bahwa serangan-serangan Nyai Wiji Sari tidak cukup membahayakan bagi Ki Pandi. Betapapun garangnya serta tingginya ilmu Nyai Wiji Sari, namun dihadapan Ki Pandi, Nyai Wiji Sari bukan seorang yang mencemaskan. Karena itu, maka hentakan-hentakan serangan Nyai Wiji Sari tidak mampu menembus pertahanan Ki Pandi.
Nyai Wiji Sari mulai menjadi gelisah. Apa pun yang dilakukan, serangan-serangannya tidak mampu menyentuh tubuh orang bongkok itu. Nyai Wiji Sari yang bangga akan kecepatan geraknya, di hadapan Ki Pandi tidak terlalu banyak berarti, karena Ki Pandi itupun mampu bergerak cepat pula meskipun nampaknya orang itu selalu berjalan terbongkok-bongkok.
Semakin lama Nyai Wiji Sari semakin menyadari, bahwa orang bongkok itu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ilmunya. Bahkan Nyai Wiji Sari itupun mulai menyadari, bahwa orang bongkok itu masih belum sampai ke puncak kemampuannya.
Meskipun demikian, Nyai Wiji Sari tidak segera berputus-asa. Perempuan yang garang itu mempunyai pengalaman yang luas sekali. Ia sudah pernah bertempur melawan orang yang memiliki berbagai macam ilmu.
Sementara itu, Nyai Wiji Sari masih merasa mempunyai puncak ilmu yang masih belum ditrapkan. Meskipun Nyai Wiji Sari itu tidak yakin bahwa puncak ilmunya itu akan dapat mengakhiri pertempuran itu, namun ia harus mencobanya.
Nyai Wiji Sari sendiri mencemaskan keragu-raguannya sendiri. Biasanya ia tidak pernah merasa ragu menghadapi lawan yang betapapun garangnya. Bahkan dalam pertempuran yang terjadi diantara mereka yang berebut daerah jelajah. Pertengkaran dan permusuhan yang terjadi diantara orang-orang yang hidupnya berada di bawah permukaan.
Namun dalam pada itu. Nyai Wiji Sari pun merasa heran, bahwa serangan-serangan Ki Pandi pun tidak pernah membahayakannya. Sekali-sekali seruling Ki Pandi memang pernah menyentuh kulitnya, tetapi sama sekali tidak menyakitinya. Seakan-akan Ki Pandi hanya ingin membuktikan, betapa rapuhnya pertahanan Nyai Wiji Sari itu dihadapan Ki Pandi yang bongkok itu.
Meskipun Nyai Wiji Sari masih harus berteka-teki, namun ia masih bertempur terus. Pedangnya masih berputaran dengan garangnya, meskipun serangan-serangannya tidak pernah berhasil. Dalam, keadaan yang gawat itu, maka Nyai Wiji Sari mulai mempertimbangkan untuk mengetrapkan ilmu puncaknya.
Ia sadar, jika ia gagal, maka orang bongkok itu tentu akan menjadi bersungguh-sungguh pula. Mungkin dengan demikian pertahanannya justru benar-benar akan dihancurkannya.
Tetapi akibat yang paling buruk harus dijalaninya, karena sejak semula Nyai Wiji Sari sudah memperhitungkan kemungkinan yang demikian akan dapat terjadi atas dirinya. Tetapi Nyai Wiji Sari memang tidak dengan serta-merta mengetrapkan ilmu puncaknya. Ia masih membuat beberapa pertimbangan dan persiapan.
Sementara itu, dua orang pengawalnya masih juga bertempur dengan sengitnya melawan dua orang cantrik yang datang bersama Ki Pandi. Nampaknya mereka memiliki kesempatan yang sama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang cukup luas dengan landasan ilmu yang cukup.
Sedangkan pertempuran yang terjadi di sekitar pintu-pintu butulan pun telah merambat semakin lebar. Para cantrik tidak dapat membatasi pertempuran di arena yang terbatas. Tetapi para pengikut Kiai Narawangsa berusaha untuk menebar seluas-luasnya di padepokan itu.
Namun ada yang pernah terjadi sebelumnya telah terjadi pula di padepokan itu. Para cantrik dari padepokan itu telah memanfaatkan pengenalan mereka atas medan sebaik-baiknya. Diantara bangunan-bangunan yang ada, para cantrik menyerang lawan-lawannya dengan tiba-tiba. Mereka muncul dari balik sudut-sudut bangunan yang ada. Dari balik pintu dan dari ruang-ruang yang tersebar dalam bangunan-bangunan di padepokan itu.
Para cantrik pemula, yang terdiri dari anak-anak muda yang belum lama berada di padepokan, menyerang lawan-lawan mereka dalam kelompok-kelompok kecil.
Ketika matahari menjadi semakin tinggi menggapai puncak langit, pertempuran telah menyebar hampir di seluruh padepokan. Para cantrik sulit mengendalikan lawan mereka. Dalam pada itu, Ki Lemah Teles dan Ki Warana yang sudah turun dari panggungan, telah menghilang diantara bangunan yang ada di padepokan itu. Bersama beberapa orang cantrik pemula, mereka berusaha menemukan lawan disela-sela bangunan. Ki Lemah Teles kadang-kadang membiarkan para cantrik pemula untuk mendapatkan pengalaman.
Tetapi dalam keadaan yang gawat, maka Ki Lemah Teles telah berusaha untuk mengurangi kekuatan lawan. Seperti sosok hantu diterik cahaya matahari, Ki Lemah Teles telah berhasil menyusut lawan cukup banyak. Tetapi sebenarnyalah Ki Lemah Teles bukan seorang pembunuh. Ia selalu berusaha melumpuhkan lawan-lawannya tanpa membunuhnya.
Dalam pada itu, pertempuran tidak jauh dari pintu gerbang utama masih berlangsung dengan sengitnya. Kiai Narawangsa ternyata tidak segera mengalahkan lawannya yang dianggapnya sudah terlalu tua untuk turun ke medan pertempuran. Lawannya, Ki Ajar Pangukan benar-benar seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga ilmunya sama sekali tidak dapat disusul oleh umurnya yang semakin tua.
Sementara itu, bindi Gunasraba yang berat itu setiap kali saling berbenturan dengan pedang Ki Sambi Pitu. Kekasaran dan tenaga yang besar dari Gunasraba sama sekali tidak banyak berarti bagi Ki Sambi Pitu. Beberapa kali Gunasraba harus meloncat menjauhi lawannya untuk memperbaiki keadaannya.
Namun rasa-rasanya ujung pedang Ki Sambi Pitu selalu memburunya. Meskipun Gunasraba beberapa kali berusaha menjauh, namun Ki Sambi Pitu itu selalu saja lekat dihadapannya. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya.
Namun akhirnya batas kemampuan pertahanan Gunasraba dapat ditembus. Ujung pedang Ki Sambi Pitu mulai menyentuh kulit. Sebuah goresan menyilang di lengan Gunasraba. Gunasraba mengumpat kasar. Kemarahannya semakin membakar ubun-ubunnya. Luka di lengannya itu telah menitikkan darahnya yang hangat.
Tetapi kemarahan, umpatan dan geram tidak cukup untuk menghentikan perlawanan Ki Sambi Pitu. Untuk mengalahkan lawannya diperlukan kemampuan dan ilmu yang tinggi. Gunasraba yang gelisah itu masih memutar bindinya. Justru semakin cepat. Bindi itu terayun-ayun di seputar tubuhnya, sehingga memang sulit bagi Ki Sambi Pitu untuk mendekat.
Tetapi Ki Sambi Pitu bukannya seorang cantrik yang baru mulai berlatih mengenali dasar-dasar ilmu kanuragan. Ki Sambi Pitu adalah seorang yang sudah kenyang menelan pahit manisnya dunia yang keras. Itulah sebabnya, maka putaran bindi Gunasraba yang bahkan seakan-akan merupakan gumpalan awan hitam yang mengelilingi tubuhnya, tidak mampu membentengi serangan Ki Sambi Pitu.
Sebuah serangan yang cepat, menyusup diantara putaran bindi itu, langsung menyentuh pundak Gunasraba. Namun hampir saja bindi itu menghantam kening Ki Sambi Pitu. Ki Sambi Pitu bergerak dengan cepatnya. Sambil merendah, sekali lagi pedangnya terjulur. Ketika sambaran angin yang ditimbulkan oleh ayunan bindi Gunasraba itu menyambar wajahnya, maka pedang Sambi Pitu itu mematuk dengan cepatnya menyusup disela-sela tulang iga Gunasraba.
Terdengar teriakan melengking tinggi. Gunasraba terhuyung-huyung surut. Demikian Ki Sambi Pitu menarik pedangnya, maka darah pun memancar dari luka di dada Gunasraba. Sejenak kemudian, maka Gunasraba itupun jatuh terbanting di tanah seperti sebatang pohon pisang yang rebah.
Kematian Gunasraba menimbulkan kegelisahan yang mencengkam jantung para pengikut Kiai Narawangsa. Ki Gunasraba menurut pengertian mereka adalah seorang yang berilmu tinggi. Ia merupakan kepercayaan Kiai Narawangsa di medan pertempuran. Apalagi Ki Gunasraba adalah adik Kiai Narawangsa yang diharapkan akan menggantikannya memimpin padepokan yang akan ditinggalkan oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.
Ki Sambi Pitu yang berdiri termangu-mangu sambil menggenggam hulu pedangnya yang basah oleh darah tercenung sejenak memandangi tubuh yang terbaring diam. Namun ia tidak mempunyai banyak kesempatan. Beberapa orang pengikut Kiai Narawangsa itupun serentak telah menyerang Ki Sambi Pitu. Ki Sambi Pitu pun dengan cepat berloncatan menghindar.
Sementara itu para cantrik pun tidak membiarkan lawan mereka bergerak leluasa. Tetapi pertanda-pertanda buruk telah nampak pada pasukan Kiai Narawangsa. Ternyata kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih besar dari perhitungan mereka. Bahwa di padepokan itu terdapat beberapa orang berilmu tinggi sebelumnya tidak pernah mereka duga.
Satu-satunya orang yang mereka perhitungkan mempunyai ilmu yang tinggi adalah Kiai Banyu Bening sendiri. Tetapi justru Kiai Banyu Bening itu sudah tidak ada. Yang ada adalah beberapa orang ysng berilmu tinggi.
Kematian Gunasraba merupakan satu pukulan yang berat bagi Kiai Narawangsa. Kecuali Gunasraba adalah adiknya, ia termasuk orang yang cerdik dan berilmu tinggi. Namun di padepokan itu, Gunasraba tidak mampu mempertahankan diri menghadapi lawannya yang sudah menjadi tua itu.
Sementara itu, Kiai Narawangsa sendiri mengalami kesulitan menghadapi Ki Ajar Pangukan. Kiai Narawangsa yang memiliki pengalaman yang sangat luas itu harus menghadapi kenyataan, bahwa di padepokan itu terdapat seorang yang mampu mengimbangi ilmunya.
Sedangkan orang yang lain lagi, masih juga bertempur melawan Nyai Wiji Sari. Nampaknya Nyai Wiji Sari yang bertempur tidak jauh dari sebuah tugu sebagai alas sebuah nisan kecil itu, juga tidak segera dapat mengalahkan lawannya.
“Darimana saja orang-orang berilmu tinggi yang berkumpul di padepokan ini?” bertanya Kiai Narawangsa didalam hatinya...
Ki Lemah Teles yang berada di panggungan pun tanggap akan perintah itu. Ketika ia melihat pasukan itu mulai bergerak, maka Ki Lemah Teles telah memerintahkan membunyikan isyarat dengan memukul bende diatas panggungan itu.
Demikian suara bende itu meraung-raung diatas panggungan, maka para cantrik seisi padepokan itu telah bersiap. Anak-anak muda dari beberapa padukuhan yang telah berada di padepokan itupun telah mendapatkan dirinya pula.
Sebagian dari mereka memang sudah mempunyai sedikit pengalaman, tetapi yang lain sama sekali belum. Namun para pemimpin padepokan itu masih sempat memberikan latihan-latihan kepada mereka meskipun baru landasannya saja sementara lawan mereka adalah orang-orang yang setiap saat selalu bercanda dengan senjata mereka.
Tetapi para cantrik padepokan Kiai Banyu Bening yang mengikuti jejak Ki Warana juga cukup banyak. Merekapun memiliki pengalaman sebagaimana para pengikut Kiai Narawangsa.
Demikianlah, maka sejenak kemudian, seperti arus banjir bandang, para pengikut Kiai Narawangsa telah menyerang padepokan yang telah ditinggalkan oleh Kiai Banyu Bening itu. Mereka menerobos pintu gerbang induk dan pintu-pintu gerbang butulan yang telah menjadi abu. Tetapi demikian mereka mulai bergerak, maka anak panah pun tercurah bagaikan hujan.
Tetapi hal itu memang sudah diperhitungkan oleh Kiai Narawangsa dan para pengikutnya. Karena itu, merekapun tidak terkejut sama sekali. Bahkan mereka telah siap untuk menangkis serangan anak panah yang menghujan itu.
Meskipun demikian, beberapa orang telah terhenti di pintu-pintu gerbang. Anak panah yang menyusup dibawah perisai dan mengenai lutut, telah melumpuhkan beberapa pengikut Kiai Narawangsa. Namun ada pula anak panah yang menembus dada, sehingga orang yang dikenainya terjatuh dan terinjak-injak oleh kawan-kawannya. Mereka untuk selamanya tidak akan pernah bangkit lagi.
Sejenak kemudian, maka banturan kekuatanpun telah terjadi. Tetapi demikian derasnya arus serangan yang mengalir dari luar padepokan, telah memaksa para cantrik untuk bergerak mundur. Tetapi para cantrik itu tidak melepaskan para penyerang untuk begitu saja memasuki padepokan yang telah mereka rebut dari tangan Panembahan Lebdagati itu.
Pertempuran pun segera menyala dengan sengitnya. Senjata yang teracu-acu, berputaran dan terayun-ayun itu, telah saling berbenturan. Suaranya berdentang diantara teriakan-teriakan yang mengguruh dari kedua belah pihak.
Di induk pasukan Kiai Narawangsa bertempur dengan garangnya. Apa saja yang ada didepannya telah disapunya tanpa ampun. Namun langkahnya terhenti ketika dihadapannya berdiri seorang yang sudah berada diusia senjanya.
“Sabarlah sedikit. Kiai Narawangsa. Jangan kau sapu anak-anak seperti menebas batang ilalang. Seharusnya kau mempunyai sedikit harga diri dengan mencari lawan yang seimbang, setidak-tidaknya mampu memberikan sedikit perlawanan.”
“Siapa kau?” bertanya Kiai Narawangsa.
“Namaku Ajar Pangukan.” jawab orang itu.
Kiai Narawangsa menarik nafas dalam-dalam. Katanya ”Namamu tidak dikenal. Minggirlah. Kau sudah terlalu tua untuk berada di medan pertempuran. Aku tidak akan menghancurkanmu sebagaimana orang-orang lain yang berani mendekati aku.”
“Kiai Narawangsa, aku berniat untuk melawanmu apapun yang terjadi.”
“Kau ternyata belum mengenal aku yang sebenarnya.”
“Jika sekarang aku berdiri disini, justru karena aku ingin mengenalmu sebaik-baiknya.”
“Nampaknya kau juga orang berilmu. Tetapi belum terlambat bagimu jika kau ingin menyingkir.”
“Aku akan tetap mencoba menghadapimu. Marilah, aku sudah bersiap sepenuhnya.”
Kiai Narawangsa menggeram. Katanya ”Apaboleh buat jika aku harus membunuhmu.”
“Bukankah didalam perang dapat saja terjadi, membunuh atau dibunuh?”
“Bagus. Kau benar-benar sudah siap maju ke medan pertempuran. Aku senang mendapat seorang lawan yang sedikit dapat menggelitik ilmuku.”
Ki Ajar Pangukan pun kemudian telah bersiap. Kiai Narawangsa telah bergerak selangkah ke samping. Demikian pula Ki Ajar Pangukan sehingga keduanya untuk beberapa saat saling bergeser setapak-setapak.
Sesaat kemudian, maka Kiai Narawangsa yang garang itu mulai meloncat menyerang. Tetapi serangannya yang seakan-akan sekedar untuk menyentuh kulit lawannya itu pun telah dielakkan oleh Ki Ajar Pangukan.
Namun serangan-serangan Kiai Narawangsa berikutnya justru menjadi semakin cepat dan semakin garang. Namun demikian, serangan-serangan itu tidak menyentuh sasarannya. Tetapi Kiai Narawangsa memang belum bersungguh-sungguh. Ia masih ingin mengetahui serba sedikit tentang kemampuan lawannya yang sudah lewat separo baya.
Ki Ajar Pangukan pun masih belum benar-benar bertempur. Seperti Kiai Narawangsa, Ki Ajar Pangukan baru sekedar ingin mengintip kemampuan lawannya. Karena itu, maka keduanya masih belum menapak pada ilmu mereka yang sebenarnya.
Dalam pada itu, yang lebih kasar dari Kiai Narawangsa adalah Ki Gunasraba. Dengan senjata bindi ia menghancurkan apa saja yang ada disekitarnya. Untuk menahan geraknya, maka lima orang cantrik padepokan itu telah mengepungnya. Namun bindi Gunasraba berputaran dengan cepat. Bindi yang besar itu memang sulit untuk ditahan.
Jika terjadi benturan dengan senjata para cantrik, maka senjata-senjata itu harus digenggam erat-erat. Dua orang cantrik telah kehilangan senjata mereka dalam benturan dengan bindi Gunasraba. Untunglah, seorang diantara mereka segera mendapatkan senjata kembali. Sementara cantrik yang lain telah memungut senjata siapa pun juga yang terkapar tidak jauh daripadanya.
Meskipun berlima, ternyata cantrik itu mengalami kesulitan. Yang dapat mereka lakukan adalah sekedar menahan, agar Gunasraba tidak mengacaukan pertahanan para cantrik pemula yang masih belum cukup berpengalaman. Namun diantara riuhnya geram dan teriakan-teriakan, terdengar seseorang berkata,
”Minggirlah. Aku akan mencoba menghadapinya.”
Para cantrik itu memang segera menyibak. Yang muncul adalah Ki Sambi Pitu. Seorang yang rambutnya sudah mulai ubanan. Beberapa lembar yang terjurai dibawah ikat kepalanya, nampak kelabu keputih-putihan.
“Kau mau apa, kakek tua?“ bertanya Gunasraba.
“He, aku belum tua!” jawab Ki Sambi Pitu ”Gigiku masih utuh.”
“Tetapi rambutmu sudah mulai memutih.” sahut Gunasraba.
“Aku dapat menyembunyikan rambutku dibawah ikat kepalaku.”
“Kau cukur sampai gundul pun kau tidak akan dapat menyembunyikan umurmu.”
Ki Sambi Pitu tertawa. Katanya, ”Aku memang sudah tua.”
“Minggirlah. Jangan ganggu aku. Aku akan membinasakan orang-orang yang berani menghalangi jalanku menuju ke pendapa bangunan utama padepokan ini.”
Tetapi Ki Sambi Pitu justru tertawa. Katanya, ”Kau suka yang aneh-aneh, Ki Sanak. Kau kira kami akan mempersilahkan kalian naik ke pendapa dan menyuguhkan hidangan minuman hangat dan makan siang dengan memotong tiga ekor lembu?”
“Setan kau orang tua yang tidak tahu diri. Sekali kau tersentuh senjataku, maka tubuhmu akan segera lumat.”
Tetapi Ki Sambi Pitu tidak bergeser dari tempatnya. Dengan tangkasnya Ki Sambi Pitu telah menggerakkan pedangnya. Namun Ki Sambi Pitu itu sadar, bahwa bindi lawannya yang berat itu merupakan senjata yang berbahaya. Ia harus menghindari benturan langsung sejauh dapat dilakukannya.
Gunasraba yang marah itupun kemudian berkata, ”Jika demikian bersiaplah untuk mati. Tubuhmu akan segera lumat menjadi debu.”
Ki Sambi Pitu tidak menjawab lagi. Tetapi ia benar-benar sudah siap untuk menghadapinya. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit, mereka tidak merasa perlu untuk saling menjajagi. Apalagi tangan Gunasraba sudah terlanjur berkeringat ketika ia menghadapi kelima orang cantrik yang berusaha membatasi geraknya.
Tetapi karena itu, maka Gunasraba pun segera terkejut. Orang tua itu ternyata mampu bergerak dengan tangkas. Tubuhnya bahkan seakan-akan seringan kapas. Sementara itu senjatanya berputaran dengan cepat, sehingga sebilah pedang itu seakan-akan telah berubah menjadi dua atau tiga atau bahkan empat.
“Gila kakek tua ini...” geram Gunasraba. Namun Gunasraba juga bukan orang kebanyakan. Iapun memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan kekuatan Gunasraba ternyata memang melampaui kekuatan orang kebanyakan.
Namun dalam pada itu, demikian pasukan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari memasuki halaman padepokan, maka Nyai Wiji Sari langsung dapat melihat sebuah tugu batu dan sebuah nisan kecil diatasnya sebagaimana pernah dilaporkan oleh orang-orangnya yang pernah datang ke padepokan itu.
Karena itu, maka jantungnya benar-benar telah bergejolak. Demikian pasukannya sempat mendorong pertahanan para cantrik dari padepokan itu mundur, maka Nyai Wiji Sari tidak dapat menahan dirinya. Nyai Wiji Sari pun dengan garangnya telah menerobos menusuk langsung pertahanan lawan. Tiba-tiba saja perempuan itu terlepas dari medan dan berlari langsung ke tugu didepan bangunan utama padepokan itu.
Dengan perasaan yang bergejolak, maka Nyai Wiji Sari pun segera berlutut didepan tugu itu. Dua orang pengawalnya tidak melepaskan Nyai Wiji Sari pergi sendiri. Karena itu, maka keduanya segera memburunya. Demikian Nyai Wiji Sari berlutut didepan tugu dengan nisan kecil diatasnya itu, maka kedua orang pengawalnya itupun telah bersiap untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi.
Beberapa orang cantrik memang siap untuk mengejar mereka. Tetapi seorang yang bongkok telah menahan mereka. “Biarlah aku yang mengurusnya.”
Para cantrik itu mengurungkan niatnya. Namun karena Nyai Wiji Sari dikawal oleh dua orang pengikutnya, maka dua orang cantrik yang semula menjadi pengikut Kiai Banyu Bening telah ikut bersama Ki Pandi. Kedua orang pengawal Nyai Wiji Sari itu pun segera mempersiapkan diri ketika mereka melihat Ki Pandi berjalan mendekat.
Namun nampaknya Ki Pandi tidak akan dengan serta merta menyerang mereka. Sebenarnyalah Ki Pandi melangkah dengan tenang mendekat. Dahinya berkerut ketika ia melihat Nyai Wiji Sari itu mengusap matanya yang basah.
“Maafkan ibumu, anakku” desisnya ”Ibu tidak dapat menjagamu dengan baik, sehingga bencana itu terjadi.”
“Kesalahanmu tidak terletak pada kelengahanmu menjaganya, Nyai.” tiba-tiba saja Ki Pandi menyahut ”Tetapi sumber kesalahan itu adalah karena kau tidak setia.”
Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Ia sudah siap menghadapi perempuan itu jika ia menjadi marah. Tetapi yang tidak terduga itupun terjadi. Nyai Wiji Sari yang garang itu tidak dengan serta-merta bangkit dan menyerang Ki Pandi yang bongkok itu. Tetapi ia justru menjawab, “Kau benar, Ki Sanak. Ketidak-setiaan itu adalah sumber dari bencana ini.”
Nyai Wyi Sari justru menangis. Isaknya telah mengguncang tubuhnya ”Maafkan aku anakku. Ketidak setiaanku itu pula yang membuat Kiai Banyu Bening menjadi gila. Pada mulanya ia bukan orang yang jahat. Tetapi ketika ia melihat seorang laki-laki didalam bilik tidurnya dan bahkan membiarkan anaknya menangis, maka ia menjadi seperti orang gila. Malapetaka itu terjadi. Rumah itu terbakar dan bayi inipun terbakar. Sejak itu, Kiai Banyu Bening telah berubah. Ia menjadi seorang penjahat yang ditakuti. Bahkan menurut pendengaranku, ia benar-benar menjadi gila disini, karena ia berniat mengorbankan bayi-bayi yang dibakar hidup-hidup didalam api. Ia ingin membalas dendam karena kematian bayinya yang terbakar itu. Ia ingin banyak orang mengalami kepahitan sebagaimana dialaminya.”
Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Yang dilihatnya berlutut itu bukan seorang perempuan garang yang terbiasa berpacu diatas punggung kuda, menjelajahi padukuhan dan bulak-bulak panjang dimalam hari. Tetapi yang berlutut itu adalah seorang perempuan yang menyesali jalan hidupnya yang sesat.
“Ki Sanak!” terdengar Nyai Wiji Sari itu berdesis. ”Apakah benar Kiai Banyu Bening telah meninggal?”
“Ya, Nyai,” jawab Ki Pandi ”Kedua orang ini adalah orang yang tinggal bersama Kiai Banyu Bening untuk waktu yang lama.”
“Apakah benar, Panembahan Lebdagati yang telah membunuh Kiai Banyu Bening?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Ya, Nyai...” jawab salah seorang dari kedua orang cantrik itu. ”Kiai Banyu Bening telah terbunuh oleh Panembahan Lebdagati. Padepokan ini pernah diduduki oleh Panembahan Lebdagati yang telah membunuh Kiai Banyu Bening itu.”
“Kenapa Panembahan Lebdagati membunuh Kiai Banyu Bening?”
“Menurut Panembahan Lebdagati, daerah ini, sepanjang lereng Gunung Lawu adalah daerahnya.”
“Apakah itu benar?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Panembahan Lebdagati memang pernah menguasai daerah ini. Tetapi ia pernah terusir oleh beberapa orang berilmu tinggi yang tidak dapat membiarkan kepercayaan sesatnya berkembang. Setiap purnama ia mengorbankan seorang gadis untuk membuat pusakanya menjadi pusaka terbaik di muka bumi.”
Dahi Nyai Wiji Sari berkerut. “Lalu kenapa kalian kemudian dapat tinggal di padepokan ini?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Kami mengambilnya dari tangan Panembahan Lebdagati.”
“Jadi kau juga pengikut Kiai Banyu Bening?“ bertanya Nyai Wiji Sari.
“Tidak, Nyai. Kebetulan tidak. Aku terlibat setelah tempat ini diduduki oleh Panembahan Lebdagati.” jawab Ki Pandi.
Nyai Wiji Sari termangu-mangu sejenak. Tetapi ia masih tetap berlutut. Sementara sekali-sekali tangannya masih mengusap air matanya. Dalam pada itu, seorang pengawalnyalah yang berkata, ”Sudahlah Nyai. Kiai Narawangsa masih terlibat dalam pertempuran yang sengit. Apakah Nyai tidak akan melibatkan diri?”
Tiba-tiba saja Nyai Wiji Sari mengangkat wajahnya. Dipandanginya Ki Pandi dengan tajamnya. Ternyata wajah Nyai Wiji Sari itu berubah. Meskipun pelupuknya masih basah, tetapi mata itu bagaikan telah menyala.
Ki Pandi melihat perubahan itu. Karena itu, maka ia pun telah bersiap kembali untuk menghadapi segala kemungkinan. Agaknya Nyai Wiji Sari itu telah menghentakkan diri dari rintihan nuraninya, kembali ke dalam dunia petualangannya yang garang, yang penuh dengan kekerasan dan kekelaman nalar budi.
“Orang bongkok...!” geram Nyai Wiji Sari kemudian ”Kau tentu salah satu dari orang yang telah mengacaukan segala sesuatunya. Mungkin kau justru yang telah mendalangi agar Panembahan Lebdagati membunuh Kiai Banyu Bening. Namun kemudian kau khianati Panembahan itu. Kau dengan licik telah mengadu kekuatan orang-orang berilmu tinggi. Diatas mayat mereka sekarang kau menari di padepokan ini.”
Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Selangkah ia bergerak surut ketika Nyai Wiji Sari yang telah bangkit berdiri itu melangkah maju sambil memandanginya dengan mata yang membara.
“Tidak, Nyai...“ suara Ki Pandi masih tetap lunak ”Kau kembali terbenam ke alam arus perasaanmu yang kau landasi pengalaman hidupmu yang kelam. Ketika sepercik terang bersinar di hatimu, maka kau dapat menemukan dirimu sendiri. Tetapi jika kelam itu datang menyelimuti kalbumu, maka kau menjadi seorang perempuan yang garang.”
“Cukup. Siapa pun kau dan apapun yang kau katakan, namun aku datang untuk mengambil padepokan ini. Aku akan selalu berada disisi anakku. Ia sendiri disini, apalagi sepeninggal Kiai Banyu Bening.”
“Kaupun harus berpikir bening, Nyai.”
“Cukup. Tengadahkan wajahmu. Aku akan menebas lehermu. Kau akan dikubur disini, dibawah tugu ini. Kau akan menjadi pengawal anakku dan melakukan apa saja yang diinginkannya. Bahkan kau akan menjadi kuda tunggangan yang jinak dan penurut.”
Ki Pandi mengerutkan dahinya. Mata Nyai Wiji Sari justru menjadi liar. Tiba-tiba saja perempuan itu telah mencabut senjatanya, sebilah pedang. Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Perasaan Nyai Wiji Sari yang kacau telah mendorongnya untuk bertempur langsung pada tataran yang menentukan.
Ki Pandi memang tidak dapat mengelak. Ia sadar, bahwa Nyai Wiji Sari itu tentu memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka Ki Pandi tidak ingin menjadi lengah dan kehilangan kesempatan. Demikian Nyai Wiji Sari mulai memutar pedangnya, maka Ki Pandi telah melepas ikat kepalanya dan dibalutkan pada lengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam sebuah seruling yang semula terselip di punggungnya.
Betapapun gelap nalar Nyai Wiji Sari, tetapi ketika ia melihat senjata Ki Pandi, maka Nyai Wiji Sari itupun segera menyadari, bahwa orang bongkok itu bukannya orang kebanyakan. Karena itu, maka Nyai Wiji Sari itupun menjadi sangat berhati-hati menghadapinya. Kedua orang pengawal Nyai Wiji Sari telah bersiap pula. Mereka bergeser di sebelah menyebelah Nyai Wiji Sari.
Ki Pandi masih bergeser surut. Kedua orang cantrik yang menyertai telah bersiap pula. Mereka akan menghadapi kedua orang pengawal Nyai Wiji Sari. “Kau sadari apa yang aku lakukan, Nyai?” bertanya Ki Pandi.
“Kau mulai ketakutan bongkok. Sayang, aku tidak mempunyai perasaan belas kasihan kepada siapa pun juga. Apalagi jika aku sudah terlanjur mencabut pedangku.”
Ki Pandi tidak menjawab. Sementara itu Nyai Wiji Sari telah mengangkat pedangnya sambil berkata lantang, ”Lihat pedangku yang berwarna kehitam-hitaman. Ini adalah warna darah yang membeku di daun pedangku. Aku tidak pernah membersihkannya jika pedangku berlumur darah.”
Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya daun pedang Nyai Wiji Sari yang menyeramkan. Sama sekali tidak berkilat ditimpa cahaya matahari. Warna coklat kehitaman membuat tengkuk Ki Pandi meremang. Tetapi Ki Pandi tidak mempunyai banyak kesempatan untuk merenungi lawannya yang menilik senjatanya, Nyai Wiji Sari benar-benar telah terbenam terlalu dalam di lumpur yang pekat.
Nampaknya dengan caranya Nyai Wiji Sari ingin melupakan kepahitan jalan hidupnya yang bernoda. Bahkan Nyai Wiji Sari juga ingin melupakan perasaan bersalah yang selalu membayanginya kemana saja ia pergi. Dalam pada itu, maka Nyai Wiji Sari pun mulai menggapai tubuh Ki Pandi dengan ujung pedangnya. Namun Ki Pandi bergeser. menghindar.
Nyai Wiji Sari menyadari, bahwa kain ikat kepala Ki Pandi yang dipergunakan untuk membalut lengan kirinya, tentu bukan kebanyakan ikat kepala. Ikat kepala itu tentu selembar ikat kepala yang dibuat secara khusus. Yang liat dan seratserat benangnya tidak mudah terputus oleh tajamnya senjata.
Demikian pula seruling ditangan kanan orang bongkok itu. Tentu bukan seruling yang dibelinya di pasar atau di sebuah keramaian merti desa. Tetapi seruling itu tentu sebuah seruling yang dibuat secara khusus pula.
Demikianlah, maka sejenak kemudian, pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Nyai Wiji Sari ternyata memang seorang perempuan yang tangkas, yang memiliki ilmu yang tinggi. Pedangnya berputaran dengan cepat. Sambaran anginnya bagaikan menusuk-nusuk lubang kulit. Tetapi Nyai Wiji Sari harus melihat kenyataan, bahwa orang bongkok yang buruk itu ternyata benar-benar memiliki ilmu yang tinggi.
Apapun yang dilakukan oleh Nyai Wiji Sari, Ki Pandi mampu mengindarinya atau menangkisnya dengan lengannya yang dibalut dengan ikat kepalanya atau dengan serulingnya. Dengan demikian, maka Nyai Wiji Sari harus meningkatkan ilmunya. Bahkan sampai pada tataran tertinggi.
Dalam pada itu, di pintu-pintu butulan, pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Di pintu butulan sebelah kiri, Manggada dan Laksana telah bertemu dengan dua orang yang pernah berjalan berpapasan di jalan bulak. Sebagaimana Manggada dan Laksana masih mengenali kedua . orang anak muda itu, ternyata keduanya juga masih mengenali Manggada dan Laksana.
“Jadi kau penghuni padepokan ini, he?” bertanya Parung Landung.
Manggada termangu-mangu sejenak. Katanya, “Kita pernah bertemu Ki Sanak.”
“Kalau aku tahu, kau penghuni padepokan ini, maka saat kita berpapasan, kepalamu tentu sudah aku lumatkan.”
Laksana tiba-tiba saja tertawa. Katanya, ”Aku menyesal bahwa kami waktu itu memberikan jalan kepadanya, sehingga kami terpaksa berjalan diatas tanggul parit. Waktu itu, aku memang sudah merencanakan untuk mencabuti kumismu yang jarang itu. Tetapi kakakku mencegahnya.”
“Tutup mulutmu!” Paron Waja menggeram. ”Aku akan menyumbat mulutmu sekarang.”
Laksana masih saja tertawa. Katanya, “Kita mempunyai kesempatan yang sama sekarang. Kawan-kawanmu dan para cantrik di padepokan ini tengah bertempur. Kita pun akan bertempur tanpa orang lain yang akan mengganggu.”
“Bagus. Kita akan bertempur tanpa orang lain yang akan mengganggu kita sampai tuntas,“ jawab Parung Landung.
“Kita bertempur di medan perang. Bukan sedang berperang tanding. Karena itu, kemungkinan datangnya gangguan dapat saja terjadi. Karena itu, persetan dengan istilahnya. Sejauh kita mendapat kesempatan bertempur seorang lawan seorang, maka kita akan melakukannya."
“Nah, kami silahkan kalian memilih lawan.”
Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Tetapi Laksanalah yang berkata, ”Kalian saja yang memilih. Aku harus melawan yang mana, dan kakang Manggada yang mana. Bagi kami siapa pun yang kami hadapi, tidak ada bedanya. Kami sudah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan.”
Paron Waja menggeram. Katanya, “Biarlah aku bungkam mulut anak ini.”
Laksana tertawa pula. Katanya, “Mulut ini ada yang punya. Tentu yang punya akan berkeberatan jika mulut ini akan dibungkam.”
Kemarahan Paron Waja benar-benar sudah membakar jantungnya. Karena itu, tiba-tiba saja ia telah meloncat sambil mengayunkan tangannya ke arah wajah Laksana. Tetapi Laksana sudah bersiap sepenuhnya. Dengan tangkas ia bergeser surut, sehingga tangan Paron Waja tidak menyentuh kulitnya. Namun terasa desir angin menerpa wajah Laksana yang luput dari jangkauan tangan Paron Waja itu. Dengan demikian Laksana menyadari, bahwa kekuatan Paron Waja memang sangat besar.
Sementara itu, ketika Paron Waja mulai menyerang Laksana, maka Manggada tidak menyia-nyiakan waktu. Justru Manggada lah yang lebih dahulu mengambil langkah. Dengan cepat Manggada meloncat sambil menjulurkan kakinya.
Parung Landung melihat serangan itu. Tetapi demikian cepat dan tidak diduga-duga. Karena itu, maka Parung Landung tidak sempat mengelak. Yang dapat dilakukan adalah sekedar menepis serangan kaki Manggada yang kuat itu. Ternyata Parung Landung tidak berhasil sepenuhnya.
Meskipun kaki Manggada itu tidak mengenai sasaran, tetapi kaki itu masih juga mengenai pundak. Tubuh Parung Landung itu terputar. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Tetapi Parung Landung justru telah bergeser beberapa langkah untuk memperbaiki kedudukannya.
Manggada memang tidak memburunya. Ia tidak ingin dianggap curang dan licik. Karena itu, maka Manggada itupun menunggu sejenak, sehingga Parung Landung berdiri tegak dan siap untuk menghadapinya.
Parung Landung itupun menggeram. ”Ternyata kau licik sekali.”
“Tidak. Bukan aku yang licik. Tetapi kau terlalu yakin akan kemampuanmu sehingga kau abaikan aku. Aku memang tidak ingin menentukan akhir dari pertempuran diantara kita dengan serangan yang pertama itu. Aku baru sekedar memperingatkanmu, agar kau berhati-hati.”
“Kau dapat saja membuat seribu macam alasan. Tetapi sekarang, marilah kita buktikan, siapakah diantara kita yang akan dapat keluar dari pertempuran ini utuh. Bukan hanya namanya.”
Manggada menarik nafas dalam-dalam. Lawannya ternyata memang seorang yang sangat yakin akan kemampuannya Karena itu, maka Manggada pun telah bersiap sebaik-baiknya untuk menghadapinya. Demikianlah, Manggada dan Laksana telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Lawan mereka juga masih muda. Tetapi Parung Landung dan Paron Waja agaknya lebih tua dari lawan-lawan mereka.
Pertempuran antara anak-anak muda itupun dengan cepatnya meningkat. Jantung mereka lebih cepat membara dan darah mereka lebih cepat mendidih. Sehingga beberapa saat kemudian, maka pertempuran itu menjadi semakin garang dan segenap kemampuannya dikerahkan.
Parang Landung dan Paron Waja yang terbiasa hidup dalam petualangan, sama sekali tidak merasa canggung. Bahkan mereka pun berusaha dengan cepat untuk mengakhiri lawan lawan mereka, agar mereka segera dapat terlibat dalam pertempuran melawan para cantrik dari padepokan itu. Adalah sangat menggembirakan untuk membantai cantrik-cantrik pemula yang masih belum banyak berpengalaman.
Tetapi ternyata mereka tidak dapat melakukannya semudah yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Kedua anak muda yang mereka hadapi itu ternyata adalah anak-anak muda yang berbekal ilmu sehingga untuk beberapa saat mereka masih mampu mengimbangi ilmu mereka.
Karena itu, setelah bertempur beberapa saat lamanya, Parung Landung justru mengumpat-umpat kasar. Ternyata tangan Manggada sempat menggapai keningnya. Meskipun tidak terlalu keras, namun sentuhan itu sendiri membuat kemarahan Parung Landung semakin memuncak.
Karena itu, maka Parung Landung pun telah menghentakkan kemampuannya pula dengan serangan-serangan beruntun yang sempat mengejutkan Manggada. Karena itu, Manggada telah terdorong surut. Namun serangan Parung Landung masih belum mampu menembus pertahanan Manggada.
Parung Landung menggeram. Ia tidak mau mengalami kenyataan itu. Parung Landung ingin lawannya itu segera dapat diselesaikannya, sehingga dengan wajah tengadah ia dapat menepuk dadanya. ”Aku telah membunuh andalan padepokan ini.”
Tetapi ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Lawannya ternyata sangat liat dan bahkan berilmu tinggi. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit pula.
Paron Waja pun mulai menjadi gelisah, ia menyangka bahwa dalam waktu singkat anak muda itu dapat segera dikalahkannya. Tetapi ternyata bahwa anak muda itu mampu mengimbanginya.
Dalam pada itu, di belakang pintu butulan sebelah kanan, Ki Jagaprana telah menghentikan dua orang yang disangkanya kembar. Kedua orang yang mengamuk seperti sepasang harimau yang terluka.
“Bagus....” Ki Jagaprana mengangguk-angguk ”Apakah memang sudah menjadi kebiasaan kalian bertempur berpasangan?”
“Siapa kau?” bertanya Krendhawa.
“Pertanyaanmu aneh. Seharusnya kau tahu bahwa aku adalah salah satu dari penghuni padepokan ini.”
“Maksudku, siapa namamu?” bentak Krendhawa.
Ki Jagapura tersenyum. Katanya. ”Namaku Jagaprana. Aku mendapat perintah untuk menghentikan kalian berdua. Nah, jika kalian memang terbiasa bertempur berpasangan karena kalian anak kembar, maka aku tidak berkeberatan.”
“Kami bukan saudara kembar.” geram Mingkara ”Umur kami bertaut hitungan tahun.”
“Oh...” Jagaprana mengangguk-angguk ”Tetapi ujud kalian tidak ubahnya dua orang kembar.”
“Agaknya matamu lah yang kabur.” geram Mingkara.
“Aku tidak peduli, apakah kalian kembar atau tidak. Yang penting bagiku, jika kalian terbiasa bertempur berpasangan, marilah. Aku ingin menjajagi kemampuan kalian berdua.”
“Kau terlalu sombong kakek tua. Betapapun tinggi ilmumu, wadagmu sudah tidak membantu. Kau sudah terlalu tua untuk bertempur di medan yang garang menghadapi petualangan yang terbiasa dengan kekerasan. Bahkan seandainya kau matahari yang menyala di langit, kau sudah memasuki masa senjamu.”
Jagaprana tertawa. Katanya, “Sinar matahari senja masih akan mampu membakar bibir mega di langit. Cahaya layung di senja hari masih dapat membuat mata puluhan orang menjadi sakit."
“Iblis kau!” geram Krendhawa ”Suaramu seperti sentuhan welat ditelingaku. Pedih. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Kami ingin menunjukkan, betapa kami mampu bertempur berpasangan melampaui orang kembar sebenarnya.”
Ki Jagaprana masih tertawa. Katanya, ”Marilah, aku sudah siap.”
Mingkara memang tidak sabar lagi. Dengan garangnya, ia pun meloncat menyerang Ki Jagaprana dengan ayunan tangannya. Ki Jagaprana bergeser surut. Tangan itu tidak menyentuh tubuhnya.
Tetapi serangan berikutnya pun segera menyusul. Krendhawa telah menjulurkan kakinya menyerang lambung. Tetapi dengan cepat Ki Jagaprana menggeliat, sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenainya. Bahkan tiba-tiba saja Ki Jagaprana yang tua itu melenting sambil berputar. Kakinya yang terayun mendatar hampir saja menyambar kening Krendhawa.
“Iblis tua!” geram Krendhawa sambil meloncat menjauh.
Ki Jagaprana tertawa pula. Katanya, ”Jangan mengumpat. Umpatanmu tidak akan membantumu mengalahkan aku.”
“Diam kau iblis tua!” teriak Mingkara.
Tetapi Jagaprana tertawa semakin keras. Demikianlah pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Krendhawa dan Mingkara memang bertempur berpasangan. Tetapi ternyata bahwa Ki Jagaprana benar-benar seorang yang berilmu tinggi.
Semakin lama Krendhawa dan Mingkara bertempur melawan orang tua itu, maka mereka pun semakin menyakini akan tingkat kemampuannya, sehingga kedua orang yang dianggap kembar itu harus meningkatkan ilmunya pula.
Pertempuran memang menyala semakin besar. Tidak hanya di belakang pintu-pintu butulan. Tetapi juga di belakang pintu gerbang utama. Agak terpisah, Nyai Wiji Sari tengah bertempur melawan Ki Pandi yang bongkok. Pedang Nyai Wiji Sari yang kehitam-hitaman itu berputar dengan cepat.
Namun Ki Pandi pun telah mengimbanginya. Dengan cepat orang bongkok itu menghindari serangan-serangan Nyai Wiji Sari. Pedang yang terayun-ayun itu tidak segera dapat mengenai tubuh orang bongkok yang mampu bergerak cepat itu.
Namun sebenarnyalah, bahwa serangan-serangan Nyai Wiji Sari tidak cukup membahayakan bagi Ki Pandi. Betapapun garangnya serta tingginya ilmu Nyai Wiji Sari, namun dihadapan Ki Pandi, Nyai Wiji Sari bukan seorang yang mencemaskan. Karena itu, maka hentakan-hentakan serangan Nyai Wiji Sari tidak mampu menembus pertahanan Ki Pandi.
Nyai Wiji Sari mulai menjadi gelisah. Apa pun yang dilakukan, serangan-serangannya tidak mampu menyentuh tubuh orang bongkok itu. Nyai Wiji Sari yang bangga akan kecepatan geraknya, di hadapan Ki Pandi tidak terlalu banyak berarti, karena Ki Pandi itupun mampu bergerak cepat pula meskipun nampaknya orang itu selalu berjalan terbongkok-bongkok.
Semakin lama Nyai Wiji Sari semakin menyadari, bahwa orang bongkok itu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ilmunya. Bahkan Nyai Wiji Sari itupun mulai menyadari, bahwa orang bongkok itu masih belum sampai ke puncak kemampuannya.
Meskipun demikian, Nyai Wiji Sari tidak segera berputus-asa. Perempuan yang garang itu mempunyai pengalaman yang luas sekali. Ia sudah pernah bertempur melawan orang yang memiliki berbagai macam ilmu.
Sementara itu, Nyai Wiji Sari masih merasa mempunyai puncak ilmu yang masih belum ditrapkan. Meskipun Nyai Wiji Sari itu tidak yakin bahwa puncak ilmunya itu akan dapat mengakhiri pertempuran itu, namun ia harus mencobanya.
Nyai Wiji Sari sendiri mencemaskan keragu-raguannya sendiri. Biasanya ia tidak pernah merasa ragu menghadapi lawan yang betapapun garangnya. Bahkan dalam pertempuran yang terjadi diantara mereka yang berebut daerah jelajah. Pertengkaran dan permusuhan yang terjadi diantara orang-orang yang hidupnya berada di bawah permukaan.
Namun dalam pada itu. Nyai Wiji Sari pun merasa heran, bahwa serangan-serangan Ki Pandi pun tidak pernah membahayakannya. Sekali-sekali seruling Ki Pandi memang pernah menyentuh kulitnya, tetapi sama sekali tidak menyakitinya. Seakan-akan Ki Pandi hanya ingin membuktikan, betapa rapuhnya pertahanan Nyai Wiji Sari itu dihadapan Ki Pandi yang bongkok itu.
Meskipun Nyai Wiji Sari masih harus berteka-teki, namun ia masih bertempur terus. Pedangnya masih berputaran dengan garangnya, meskipun serangan-serangannya tidak pernah berhasil. Dalam, keadaan yang gawat itu, maka Nyai Wiji Sari mulai mempertimbangkan untuk mengetrapkan ilmu puncaknya.
Ia sadar, jika ia gagal, maka orang bongkok itu tentu akan menjadi bersungguh-sungguh pula. Mungkin dengan demikian pertahanannya justru benar-benar akan dihancurkannya.
Tetapi akibat yang paling buruk harus dijalaninya, karena sejak semula Nyai Wiji Sari sudah memperhitungkan kemungkinan yang demikian akan dapat terjadi atas dirinya. Tetapi Nyai Wiji Sari memang tidak dengan serta-merta mengetrapkan ilmu puncaknya. Ia masih membuat beberapa pertimbangan dan persiapan.
Sementara itu, dua orang pengawalnya masih juga bertempur dengan sengitnya melawan dua orang cantrik yang datang bersama Ki Pandi. Nampaknya mereka memiliki kesempatan yang sama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang cukup luas dengan landasan ilmu yang cukup.
Sedangkan pertempuran yang terjadi di sekitar pintu-pintu butulan pun telah merambat semakin lebar. Para cantrik tidak dapat membatasi pertempuran di arena yang terbatas. Tetapi para pengikut Kiai Narawangsa berusaha untuk menebar seluas-luasnya di padepokan itu.
Namun ada yang pernah terjadi sebelumnya telah terjadi pula di padepokan itu. Para cantrik dari padepokan itu telah memanfaatkan pengenalan mereka atas medan sebaik-baiknya. Diantara bangunan-bangunan yang ada, para cantrik menyerang lawan-lawannya dengan tiba-tiba. Mereka muncul dari balik sudut-sudut bangunan yang ada. Dari balik pintu dan dari ruang-ruang yang tersebar dalam bangunan-bangunan di padepokan itu.
Para cantrik pemula, yang terdiri dari anak-anak muda yang belum lama berada di padepokan, menyerang lawan-lawan mereka dalam kelompok-kelompok kecil.
Ketika matahari menjadi semakin tinggi menggapai puncak langit, pertempuran telah menyebar hampir di seluruh padepokan. Para cantrik sulit mengendalikan lawan mereka. Dalam pada itu, Ki Lemah Teles dan Ki Warana yang sudah turun dari panggungan, telah menghilang diantara bangunan yang ada di padepokan itu. Bersama beberapa orang cantrik pemula, mereka berusaha menemukan lawan disela-sela bangunan. Ki Lemah Teles kadang-kadang membiarkan para cantrik pemula untuk mendapatkan pengalaman.
Tetapi dalam keadaan yang gawat, maka Ki Lemah Teles telah berusaha untuk mengurangi kekuatan lawan. Seperti sosok hantu diterik cahaya matahari, Ki Lemah Teles telah berhasil menyusut lawan cukup banyak. Tetapi sebenarnyalah Ki Lemah Teles bukan seorang pembunuh. Ia selalu berusaha melumpuhkan lawan-lawannya tanpa membunuhnya.
Dalam pada itu, pertempuran tidak jauh dari pintu gerbang utama masih berlangsung dengan sengitnya. Kiai Narawangsa ternyata tidak segera mengalahkan lawannya yang dianggapnya sudah terlalu tua untuk turun ke medan pertempuran. Lawannya, Ki Ajar Pangukan benar-benar seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga ilmunya sama sekali tidak dapat disusul oleh umurnya yang semakin tua.
Sementara itu, bindi Gunasraba yang berat itu setiap kali saling berbenturan dengan pedang Ki Sambi Pitu. Kekasaran dan tenaga yang besar dari Gunasraba sama sekali tidak banyak berarti bagi Ki Sambi Pitu. Beberapa kali Gunasraba harus meloncat menjauhi lawannya untuk memperbaiki keadaannya.
Namun rasa-rasanya ujung pedang Ki Sambi Pitu selalu memburunya. Meskipun Gunasraba beberapa kali berusaha menjauh, namun Ki Sambi Pitu itu selalu saja lekat dihadapannya. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya.
Namun akhirnya batas kemampuan pertahanan Gunasraba dapat ditembus. Ujung pedang Ki Sambi Pitu mulai menyentuh kulit. Sebuah goresan menyilang di lengan Gunasraba. Gunasraba mengumpat kasar. Kemarahannya semakin membakar ubun-ubunnya. Luka di lengannya itu telah menitikkan darahnya yang hangat.
Tetapi kemarahan, umpatan dan geram tidak cukup untuk menghentikan perlawanan Ki Sambi Pitu. Untuk mengalahkan lawannya diperlukan kemampuan dan ilmu yang tinggi. Gunasraba yang gelisah itu masih memutar bindinya. Justru semakin cepat. Bindi itu terayun-ayun di seputar tubuhnya, sehingga memang sulit bagi Ki Sambi Pitu untuk mendekat.
Tetapi Ki Sambi Pitu bukannya seorang cantrik yang baru mulai berlatih mengenali dasar-dasar ilmu kanuragan. Ki Sambi Pitu adalah seorang yang sudah kenyang menelan pahit manisnya dunia yang keras. Itulah sebabnya, maka putaran bindi Gunasraba yang bahkan seakan-akan merupakan gumpalan awan hitam yang mengelilingi tubuhnya, tidak mampu membentengi serangan Ki Sambi Pitu.
Sebuah serangan yang cepat, menyusup diantara putaran bindi itu, langsung menyentuh pundak Gunasraba. Namun hampir saja bindi itu menghantam kening Ki Sambi Pitu. Ki Sambi Pitu bergerak dengan cepatnya. Sambil merendah, sekali lagi pedangnya terjulur. Ketika sambaran angin yang ditimbulkan oleh ayunan bindi Gunasraba itu menyambar wajahnya, maka pedang Sambi Pitu itu mematuk dengan cepatnya menyusup disela-sela tulang iga Gunasraba.
Terdengar teriakan melengking tinggi. Gunasraba terhuyung-huyung surut. Demikian Ki Sambi Pitu menarik pedangnya, maka darah pun memancar dari luka di dada Gunasraba. Sejenak kemudian, maka Gunasraba itupun jatuh terbanting di tanah seperti sebatang pohon pisang yang rebah.
Kematian Gunasraba menimbulkan kegelisahan yang mencengkam jantung para pengikut Kiai Narawangsa. Ki Gunasraba menurut pengertian mereka adalah seorang yang berilmu tinggi. Ia merupakan kepercayaan Kiai Narawangsa di medan pertempuran. Apalagi Ki Gunasraba adalah adik Kiai Narawangsa yang diharapkan akan menggantikannya memimpin padepokan yang akan ditinggalkan oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.
Ki Sambi Pitu yang berdiri termangu-mangu sambil menggenggam hulu pedangnya yang basah oleh darah tercenung sejenak memandangi tubuh yang terbaring diam. Namun ia tidak mempunyai banyak kesempatan. Beberapa orang pengikut Kiai Narawangsa itupun serentak telah menyerang Ki Sambi Pitu. Ki Sambi Pitu pun dengan cepat berloncatan menghindar.
Sementara itu para cantrik pun tidak membiarkan lawan mereka bergerak leluasa. Tetapi pertanda-pertanda buruk telah nampak pada pasukan Kiai Narawangsa. Ternyata kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih besar dari perhitungan mereka. Bahwa di padepokan itu terdapat beberapa orang berilmu tinggi sebelumnya tidak pernah mereka duga.
Satu-satunya orang yang mereka perhitungkan mempunyai ilmu yang tinggi adalah Kiai Banyu Bening sendiri. Tetapi justru Kiai Banyu Bening itu sudah tidak ada. Yang ada adalah beberapa orang ysng berilmu tinggi.
Kematian Gunasraba merupakan satu pukulan yang berat bagi Kiai Narawangsa. Kecuali Gunasraba adalah adiknya, ia termasuk orang yang cerdik dan berilmu tinggi. Namun di padepokan itu, Gunasraba tidak mampu mempertahankan diri menghadapi lawannya yang sudah menjadi tua itu.
Sementara itu, Kiai Narawangsa sendiri mengalami kesulitan menghadapi Ki Ajar Pangukan. Kiai Narawangsa yang memiliki pengalaman yang sangat luas itu harus menghadapi kenyataan, bahwa di padepokan itu terdapat seorang yang mampu mengimbangi ilmunya.
Sedangkan orang yang lain lagi, masih juga bertempur melawan Nyai Wiji Sari. Nampaknya Nyai Wiji Sari yang bertempur tidak jauh dari sebuah tugu sebagai alas sebuah nisan kecil itu, juga tidak segera dapat mengalahkan lawannya.
“Darimana saja orang-orang berilmu tinggi yang berkumpul di padepokan ini?” bertanya Kiai Narawangsa didalam hatinya...
Selanjutnya,
MATAHARI SENJA BAGIAN 21
MATAHARI SENJA BAGIAN 21