Matahari Senja
KIAI Narawangsa pun bertanya-tanya pula kepada diri sendiri. Bagaimanakah dengan Parung Landung dan Paron Waja serta Krendhawa dan Mingkara. Tetapi Kiai Narawangsa tidak mempunyai banyak waktu untuk merenungi keadaan. Ki Ajar Pangukan telah melibatkan dalam pertempuran yang sengit. Hampir tidak ada waktu sekejap pun untuk memperhatikan keadaan, kecuali jika Kiai Narawangsa itu sengaja mengambil jarak.
Dalam pada itu, Manggada masih bertempur melawan Parung Landung, sedangkan Laksana menghadapi Paron Waja. Mereka adalah anak-anak muda yang jantungnya masih mudah terbakar. Sementara itu mereka adalah anak-anak muda yang memiliki bekal ilmu yang tinggi.
Namun Parung Landung yang bertempur melawan Manggada harus menyadari, bahwa lawannya ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Jika anak muda itu lebih baik menyingkir ketika mereka berpapasan, itu bukan karena mereka tidak mempunyai bekal untuk berkelahi, tetapi agaknya anak muda itu memang menghindari perselisihan yang tidak perlu. Tetapi ketika anak muda itu benar-benar dihadapkan pada satu pertempuran yang tidak dapat dihindari, maka ternyata ia telah menunjukkan kemampuannya yang tinggi.
Sebenarnyalah Manggada mampu bertempur dengan cepat, keras dan garang. Tubuhnya yang liat seakan-akan tidak bertulang lagi. Anak muda itu mempunyai banyak sekali cara untuk menyerang dan bertahan. Kakinya dengan tangkas berloncatan seakan-akan tidak lagi berjejak diatas tanah.
Tetapi Parung Landung yang ditempa dalam lingkungan yang keras dan kasar itupun menjadi keras dan kasar pula. Ketika ia menyadari bahwa lawannya memiliki ilmu yang tinggi, maka Parung Landung itupun telah meningkatkan serangan-serangannya.
Dengan demikian, maka pertempuranpun menjadi semakin sengit. Serangan-serangan Parung Landung menjadi semakin garang. Ketika kemudian ditangannya tergenggam sebuah golok yang besar, maka Manggada pun telah memegang pedangnya pula.
Ternyata keduanya memiliki kemampuan bermain senjata yang tinggi. Golok yang besar di tangan Parung Landung menjadi semakin berbahaya karena kekuatan anak muda itu memang sangat besar. Tetapi tidak kalah berbahayanya pedang di tangan Manggada. Pedang itu berputaran dengan cepatnya. Terayun-ayun mendebarkan.
Sementara itu, Laksana dan Paron Wajapun masih juga bertempur dengan sengitnya pula. Keduanya juga sudah menggenggam senjata. Benturan-benturan telah terjadi dengan kerasnya. Kedua-duanya memiliki kekuatan yang besar.
Namun Laksana yang telah ditempa dalam kehidupan hutan bersama Manggada dan Ki Pandi itu, dengan cepat menyesuaikan diri dengan gaya permainan senjata lawannya. Karena itu, apapun yang dilakukan oleh Mingkara, Laksana dapat mengimbanginya. Justru karena itu, kemarahan Mingkara bagaikan telah menyulut ubun-ubunnya. Dihentakkannya kemampuan dan ilmunya untuk mengatasi ketangkasan lawannya.
Demikianlah, maka dentang senjata yang berbenturan itupun telah memercikkan bunga api. Senjata-senjata yang terbuat dari baja pilihan itu berputaran, menyambar, mematuk dan saling mendera.
Sementara itu, pertempuran antara para pengikut Kiai Narawangsa dan para penghuni padepokan itupun menjadi semakin sengit pula. Satu-satu korban pun berjatuhan. Beberapa orang yang sempat, telah menyingkirkan kawan-kawan mereka yang terluka, agar mereka tidak terlanjur mati terinjak-injak kaki mereka yang sedang bertempur. Ketika matahari melewati puncaknya, maka langit pun bagaikan membara. Panasnya seakan-akan menyusup tubuh dan menghanguskan tulang.
Sementara itu pertempuran masih saja berlangsung dengan sengitnya. Ki Jagaprana memang harus bekerja keras menghadapi dua orang saudara yang semula disangkanya kembar. Kedua orang itu mampu bertempur berpasangan dengan rapat. Saling mengisi dan saling melindungi. Mereka datang menyerang berganti-ganti berurutan seperti gelombang yang didera oleh prahara, bergulung-gulung menghantam tebing.
Tetapi Ki Jagaprana adalah seorang yang mumpuni. Ilmunya yang tinggi benar-benar telah mapan di tempa oleh pengalaman. Meskipun umurnya menjadi semakin tua, tetapi ia masih tetap seorang yang sulit dicari tandingnya.
Sesaat demi sesaat, dua orang kakak beradik itu menjadi semakin berat. Serangan-serangan Ki Jagaprana tidak kalah garangnya dengan serangan-serangan kedua orang lawannya. Meskipun tidak terlalu sering, tetapi beberapa kali membuat kedua orang lawannya itu terkejut dan terpaksa berloncatan menjauhinya.
Namun Ki Jagaprana tidak ingin pertempuran itu menjadi semakin berkepanjangan. Ia hanya seorang diri, sedangkan lawannya bertempur berpasangan. Pada saatnya, maka ia harus memeras tenaga lebih banyak dari lawannya seorang-seorang. Karena, itu, selagi tenaganya masih belum susut, maka ia harus berusaha mengakhiri pertempuran itu.
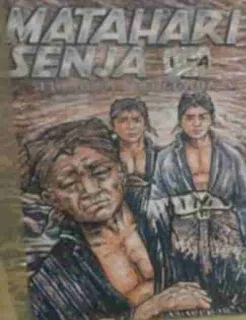
Dalam pada itu, Krendhawa yang sempat mendesak Ki Jagaprana surut berteriak, ”Mati kau orang tua yang sombong.”
Tetapi Ki Jagaprana tidak mati. Ia sempat mengelakkan senjata Krendhawa yang terjulur ke arah dadanya. Namun dalam waktu yang hampir bersamaan Mingkara pun berteriak, ”Mati kau iblis tua.”
Tetapi Jagaprana justru tertawa. Dengan nada tinggi ia berkata, ”Kalian tahu artinya mati?”
“Tutup mulutmu.” bentak Krendhawa.
Ki Jagaprana merendahkan dirinya. Senjata Krendhawa terayun deras di atas kepalanya. Tetapi senjata itu tidak menyentuh kulit Ki Jagaprana. Namun Mingkara itu berteriak, ”Kau tidak akan dapat luput dari tangan kami iblis tua. Kau akan segera jatuh ke tangan kami, apapun yang kau lakukan.”
“Jangan banyak sesumbar...” desis Ki Jagaprana sambil menghindari serangan Krendhawa ”Jika aku memerlukan kawan, maka aku tinggal berteriak saja. Beberapa orang akan segera berdatangan dan membantu aku membantai kalian berdua. Tetapi bukan itu niatku. Aku masih ingin menjajagi kemampuanku, apakah panasku, masih lebih tajam dari panasmu. Apakah panas Matahari senja masih mampu membuat air mendirih atau sekedar mengepulkan asap.”
“Kau memang terlalu banyak berbicara.” geram Krendhawa. Namun kata-kata Krendhawa terputus. Ki Jagaprana memang sudah mulai merasa letih. Ia sadar, bahwa beberapa saat kemudian, maka tenaganya tentu akan menyusut.
“Apakah aku memang sudah tua?” bertanya Ki Jagaprana kepada diri sendiri ”Kenapa aku sekarang menjadi terlalu cepat letih?”
Ki Jagaprana masih menguji dirinya sendiri. Tetapi karena ia harus bertempur melawan dua orang yang berilmu tinggi, maka Ki Jagaprana memang harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Namun dalam pada itu, meskipun Ki Jagaprana telah mulai merasa letih, tenaganya masih belum menyusut justru karena itu, maka ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu sebelum tenaganya benar-benar telah menyusut.
Sementara itu, maka Krendhawa dan Mingkara pun telah berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Mereka pun ingin agar orang tua itu segera dapat diakhiri. Karena itu, maka kedua orang itu telah mengerahkan kemampuan mereka tertinggi. Seperti Gunasraba, maka keduanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan mengandalkan kekuatannya itu, keduanya telah mencoba menghimpit Ki Jagaprana dari dua arah yang berlawanan.
Ki Jagaprana pun mulai merasakan seakan-akan kekuatan kedua orang lawannya itu meningkat. Setiap terjadi benturan, Jagaprana memang merasakan tekanan yang kuat dari kedua orang lawannya. Namun kekuatan yang besar itu tidak menjamin kemenangan dalam pertempuran yang cepat dan keras itu.
Dalam keadaan yang gawat itu, maka Ki Jagaprana telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghentikan pertempuran. Senjata yang sudah berada di tangannya itu mulai menyusup di sela-sela pertahanan senjata lawan-lawannya. Di bawah teriknya sinar matahari, maka kecepatan gerak Ki Jagaprana ternyata menjadi sangat menguntungkan, justru karena lawannya mengandalkan kekuatan mereka.
Ketika senjata Krendhawa terayun dengan derasnya, maka Ki Jagaprana masih sempat untuk merendah. Namun bersamaan dengan itu, Ki Jagaprana telah berputar, sementara tangannya yang menggenggam senjatanya itupun telah terentang. Putaran ujung senjata Ki Jagaprana itu ternyata berhasil menyusup dibawah pertahanan Krendhawa. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar Krendhawa itu berteriak nyaring.
Umpatan-umpatan kasar terdengar meloncat dari mulutnya. Krendhawa itupun kemudian terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Ternyata ujung senjata Ki Jagaprana itu telah mengoyak lambung. Mingkara yang melihat saudaranya terluka, dengan serta merta telah meloncat menyerang Ki Jagaprana. Senjata terayun dengan derasnya mengarah ke kening Ki Jagaprana.
Namun Ki Jagaprana sempat melihat serangan itu. Sekali lagi ia dengan cepat merendah dengan berjongkok diatas satu lututnya, sementara ujung senjatanya terjulur lurus menggapai tubuh lawannya.
Mingkara terkejut. Langkahnya terhenti. Namun ia tidak tahu lagi apa yang telah terjadi. Ujung senjata Ki Jagaprana itu ternyata telah menggapai jantung Mingkara. Ketika kemudian Ki Jagaprana menarik senjatanya, maka Mingkara itu telah jatuh terjerembab. Tubuhnya terbanting di tanah sementara nafasnya telah terputus.
Krendhawa melihat keadaan saudara laki-lakinya itu. Karena itu dengan sisa tenaganya ia berusaha menyerang Ki Jagaprana. Ki Jagaprana melihat serangan itu. Yang dilakukannya kemudian adalah sekedar menghindar. Dengan cepat ia bangkit dan meloncat, kesamping.
Serangan Krendhawa itu tidak menyentuh sasaran. Namun dengan menghentakkan tenaganya, sementara lambungnya sudah terkoyak, maka darah Krendhawa seakan-akan telah diperas keluar. Sejenak Krendhawa itu terhuyung-huyung. Namun demikian banyaknya darah yang terperas, sehingga tubuh itu menjadi sangat lemah.
Perlahan-lahan Krendhawa jatuh berlutut. Namun kemudian tubuhnya itu terguling. Meskipun demikian Krendhawa itu masih sempat mengerang kesakitan.
Ki Jagaprana termangu-mangu sejenak. Dipandanginya tubuh yang terbaring diam. Beberapa langkah dari tubuh Krendhawa itu, tubuh Mingkara pun terbaring diam pula. Ki Jagaprana mengerutkan keningnya ketika ia melihat Krendhawa itu kemudian telah bergerak. Dengan sisa tenaganya, Krendhawa berusaha untuk merangkak mendekati tubuh adiknya yang telah tidak bernafas lagi.
“Bangkitlah Mingkara. Ayo bangkit. Kita bunuh iblis tua itu. Kita adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Segala kemauan kita terjadi.”
Ki Jagaprana memandang tingkah laku Krendhawa itu dengan jantung yang berdebaran. Ketika ia melihat Krendhawa itu mengguncang-guncang tubuh adiknya, maka dada Ki Jagaprana itupun menjadi berdebar-debar. Ternyata Krendhawa tidak mau melihat kenyataan sampai pada saat-saat terakhirnya.
Bahkan kemudian Krendhawa itu berusaha untuk bangkit. Dicobanya untuk mengangkat kepala adiknya sambil berkata dengan suara gemetar, ”Bangkitlah Mingkara. Bangkitlah. Kita tidak punya banyak waktu lagi.”
Tetapi Mingkara sama sekali tidak bergerak lagi.
“Mingkara, Mingkara!” Krendhawa itupun kemudian berteriak ”Kau kenapa he?”
Sementara itu darah dari luka Krendhawa itupun mengalir semakin banyak. Gerak seru teriakan-teriakannya membuat darahnya mengalir bergumpal-gumpal.
Sementara itu pertempuran pun masih berlangsung di mana-mana. Tetapi tidak seorang pun yang sempat mendekati mereka. Para cantrik dari padepokan itu telah semakin menekan para pengikut Kiai Narawangsa. Ketika ada seorang yang akan berlari kearah Krendhawa dan Mingkara, maka seorang cantrik telah menahan mereka dan melihatnya dalam pertempuran.
Ki Jagaprana yang menyaksikan tingkah laku Krendhawa itu pun menjadi iba. Dengan hati-hati iapun telah mendekatinya. Tetapi Krendhawa tidak menghiraukannya. Seakan-akan ia tidak melihat lagi orang-orang lain yang ada di sekitarnya, selain adiknya yang telah terbunuh itu.
“Ki Sanak...” desis Ki Jagaprana ”Jangan terlalu banyak bergerak. Darahmu akan semakin terperas dari tubuhmu. Tenanglah, berbaringlah dengan baik.”
Krendhawa itu mencoba memandang wajah Ki Jagaprana. Tetapi ternyata ia tidak lagi dapat mengenalinya. Selain matanya yang sudah menjadi kabur, nalarnya juga sudah tidak utuh lagi. Sementara itu, matahari di langit membuat pandangannya menjadi silau.
“Siapa kau?” bertanya Krendhawa.
“Siapa pun aku tidak penting bagimu. Tetapi tenanglah. Berbaringlah.”
“Aku sedang membangunkan adikku. Ia sudah terlalu lama tidur. Ia harus bangkit. Perang sudah dimulai.”
“Perang sudah selesai. Biarlah adikmu beristirahat. Ia sangat letih.”
“Perang sudah selesai?” bertanya Krendhawa. Krendhawa itu termangu-mangu sejenak. Tetapi tubuhnya sudah menjadi semakin lemah. Darahnya membasahi tanah. Sementara tubuhnya sendiri juga sudah menjadi merah sebagaimana tubuh Mingkara.
“Perang memang sudah selesai. Beristirahatlah dengan sebaik-baiknya.”
Krendhawa mengerutkan keningnya. Ia mencoba untuk mengamati wajah Ki Jagaprana. Tetapi segala-galanya menjadi semakin kabur. Meskipun demikian, Krendhawa itupun meletakkan kepalanya di tubuh adiknya. Seakan-akan diluar sadarnya ia berkata, '“Aku akan tidur dahulu. Perang sudah selesai.”
Tetapi tiba-tiba Krendhawa itu mengangkat kepalanya sambil bertanya, ”Apakah kita menang?”
“Ya. Kita menang...!”
“Kiai Banyu Bening sudah dibunuh?”
“Ya. Kiai Banyu Bening sudah dibunuh.”
Orang itu tersenyum. Namun kemudian kepalanya itupun diletakkannya kembali. Ia masih akan berbicara lagi. Tetapi terasa pedih dilambungnya. Krendhawa masih mencoba tersenyum karena kemenangan yang telah dicapai oleh Kiai Narawangsa dengan membunuh Kiai Banyu Bening. Namun senyuman itu adalah senyumannya yang terakhir. Krendhawa pun telah mengakhiri hidupnya di medan pertempuran.
Ki Jagaprana menarik nafas, dalam-dalam. Iapun Kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan tubuh dua orang kakak beradik yang semula disangkanya kembar itu.
Pertempuran masih terjadi di sekitarnya. Para cantrik masih belum dapat mengusir lawan-lawannya. Bahkan pertempuran pun telah menjadi semakin meluas dimana-mana.
Ki Jagaprana yang telah kehilangan lawannya itu pun kemudian melangkah mendekati arena. Beberapa orang pengikut yang sempat melihat Ki Jagaprana membunuh Krendhawa dan Mingkara, menjadi berdebar-debar. Tengkuk mereka meremang, seolah-olah senjata Ki Jagaprana itu telah menyentuhnya.
“Siapa yang akan menyerah, menyerahlah...” teriak Ki Jagaprana tiba-tiba.
Ternyata teriakannya itu berpengaruh. Para pengikut Kiai Narawangsa menjadi semakin gelisah. Dengan lantang Ki Jagaprana itu berkata selanjurnya, ”Hanya ada dua pilihan. Menyerah atau mati.”
Beberapa orang pengikut Kiai Narawangsa memang mulai memikirkan untuk menyerah. Namun seorang yang bertubuh tinggi dan besar itu berteriak, ”Hanya ada dua pilihan bagi kami. Menang atau mati.”
“Apakah aku tidak salah dengar?” bertanya Ki Jagaprana ”Menyerah atau mati.”
“Tidak. Menang atau mati.”
Ki Jagaprana menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya orang itu termasuk seorang yang berpengaruh di lingkungan para pengikut Kiai Narawangsa. Sambil berteriak orang itu bertempur melawan dua orang cantrik. Katanya ”Kita sudah berada di ambang kemenangan. Tidak ada orang yang dapat menghalangi kita.”
Jantung Ki Jagaprana mulai tergelitik. Karena itu, maka iapun mendekatinya sambil berkata, ”Kau lihat aku membunuh kedua orang yang semula aku sangka kembar itu?”
”Jangan mengigau. Aku tidak peduli apa yang telah kau lakukan. Tetapi kami tidak akan menyerah.”
Ki Jagaprana yang mulai letih itu memang menjadi mudah tersinggung. Panasnya terik matahari, keringat yang membasahi tubuhnya serta pertempuran yang menjalar kemana-mana membuatnya cepat mengambil keputusan. Orang itu harus dihentikan. Kemudian yang lain akan mudah dikendalikan. Karena itu, maka Ki Jagaprana pun telah mendekatinya sambil berkata, ”Mulutmu memang harus dibungkam.”
“Mulutmu yang akan aku koyakkan jika kau berani mendekat.”
Ki Jagaprana pun melangkah semakin dekat. Kemudian katanya kepada kedua orang yang bertempur melawan orang yang bertubuh tinggi besar itu, ”Minggirlah. Bantu kawan-kawanmu, biarlah aku selesaikan orang ini.”
Kedua orang cantrik yang bertempur melawan orang yang bertubuh tinggi besar itupun segera berloncatan menjauh, sementara Ki Jagaprana telah memasuki medan. Orang yang bertubuh tinggi besar itu menggeram. Ketika Ki Jagaprana melangkah semakin dekat, maka orang yang bertubuh tinggi besar itu telah meloncat menyerangnya.
Kemarahan memang sudah membakar jantung Ki Jagaprana. Karena itu, maka ketika orang itu meloncat menyerang, maka Ki Jagaprana telah bergeser selangkah, sehingga serangan itu tidak mengenai sasarannya. Namun bersamaan dengan itu, senjata Ki Jagaprana telah terayun mendatar.
Segores luka telah menyilang di dada orang itu. Terhuyung-huyung ia terdorong beberapa langkah surut Orang itu masih sempat mengumpat. Tetapi tubuhnya pun segera jatuh terguling. Orang itu memang tidak terbunuh. Namun ia sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk bangkit.
Sejenak Ki Jagaprana berdiri termangu-mangu. Bahwa orang bertubuh tinggi besar itu sudah tidak berdaya, ternyata pengaruhnya memang besar sekali. Para pengikut Kiai Narawangsa yang bertempur di sekitar tempat itu hatinya menjadi semakin kecut.
Dalam pada itu Ki Jagaprana berteriak lagi. “Siapa yang akan menyerah, akan mendapat perlakuan wajar. Tetapi siapa yang tidak menyerah, akan mengalami perlakuan yang buruk.”
Tetapi masih juga ada pengikut Kiai Narawangsa yang setia. Dengan lantang ia berteriak, ”Hanya pengkhianat sajalah yang akan menyerah.”
Tetapi demikian mulutnya terkatup, maka ujung sepucuk tombak pendek telah mematuknya. Orang itu terkejut. Tetapi ia sudah terlambat untuk berbuat sesuatu. Ujung tombak itu telah menghunjam dalam-dalam di dadanya. Ketika orang itu rebah di tanah, maka seorang cantrik dengan tombak di tangan telah bergeser menjauhinya.
Dalam pada itu, sekali lagi Ki Jagaprana berkata lantang. ”Siapa yang akan menyerah? Yang keras kepala seorang demi seorang akan mati di padepokan ini.”
Tidak ada seorang pun yang berani berteriak lagi. Ketika Ki Jagaprana menawarkan kesempatan sekali lagi untuk menyerah, maka beberapa orang dengan serta-merta telah bergeser menjauhi lawan-lawannya sambil meletakkan senjata mereka, ”Aku menyerah...”
Pernyataan beberapa orang itu telah diikuti oleh beberapa orang yang lain lagi. Semakin lama semakin banyak, sehingga akhirnya hampir semua orang yang bertempur di sekitarnya telah menyerah pula. Tetapi mereka yang telah bergeser jauh dari pintu gerbang itu, tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di pintu gerbang itu.
Karena itu, mereka yang tidak mendengar teriakan Ki Jagaprana dengan jelas tidak berbuat sebagaimana dilakukan oleh kawan-kawan mereka. Mereka masih saja bertempur dengan garangnya. Namun akhirnya mereka mengetahuinya pula, kenapa banyak kawan-kawannya yang menghentikan perlawanan.
“Krendhawa dan Mingkara telah mati terbunuh.”
Sementara itu, di pintu butulan yang lain, Manggada dan Laksana masih bertempur dengan sengitnya melawan Parung Landung dan Paron Waja. Anak-anak muda itu telah bertempur habis-habisan. Nampaknya pertempuran itu akan menentukan, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati.
Namun sebenarnyalah kegarangan Parung Landung dan Paron Waja tidak mampu mengimbangi kemampuan ilmu Manggada dan Laksana. Kedua orang anak muda yang sudah ditempa di sanggar oleh ayah Laksana dan yang kemudian dimatangkan oleh pengalaman. Bahkan kemudian mereka telah ditumbuh-besarkah oleh Ki Pandi dengan caranya.
Tubuh Manggada dan Laksana menjadi liat dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang bagaimana pun juga rumitnya. Di hutan mereka menjalani laku yang berat, namun yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu mereka.
Parung Landung yang merasa dirinya mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, semula merasa yakin akan dapat mengalahkan lawannya. Tetapi ternyata kemudian bahwa kemampuannya tidak dapat mengguncang ilmu Manggada. Goloknya yang besar setiap kali terayun tanpa mampu menyentuh sasarannya. Jika terjadi benturan, maka goloknya yang berat itu malah terasa sebagai beban.
Di bawah teriknya matahari, maka ujung pedang Manggada mulai menyusup menembus pertahanan Parung Indung. Betapa kuatnya Parung Landung, namun ketangkasan Manggada ternyata sulit untuk diimbanginya.
Demikianlah maka perlahan-lahan tetapi pasti, Manggada telah mendesak lawannya. Ayunan golok yang berat sama sekali tidak menyulitkannya. Senjata yang lebih kecil justru terasa lebih berarti. Ketika ujungnya sempat menggapai tubuh Parung Landung, maka terdengar Parung Landung itu mengeluh tertahan.
Parung Landung meloncat surut. Ia sempat mengusap bahunya dengan telapak tangannya yang menjadi merah. Ketika Parung Landung dengan geram melangkah maju, terdengar tidak terlalu jauh daripadanya, Paron Waja berteriak kesakitan. Terhuyung-huyung ia melangkah surut. Namun kemudian tidak memberinya kesempatan. Dengan cepat Laksana memburunya. Pedangnya terjulur lurus mengarah ke dada.
Paron Waja masih berusaha menangkis. Tetapi karena keseimbangannya sedang goyah, maka ayunan senjatanya tidak mampu menepis ujung pedang Laksana. Karena itu, maka dalam keadaan yang goyah, ujung pedang Laksana telah terhunjam di dadanya, langsung menyentuh jantungnya. Paron Waja tidak mempunyai kesempatan lagi. Tubuhnya terdorong semakin jauh, sehingga akhirnya jatuh terbanting di tanah.
Parung Landung yang melihat adiknya tertusuk di dadanya berteriak memanggil namanya sambil meloncat menjauhi lawannya, memburu kearah Paron Waja terpelanting jatuh. Tetapi langkahnya terhenti, ketika Laksana pun menghadangnya sambil mengacukan pedangnya. Parung Landung termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya Manggada maju selangkah demi selangkah mendekatinya.
“Menyerahlah...” berkata Manggada ”Kau sudah terluka. Kau tidak akan dapat melawan kami berdua, sementara orang-orangmu tidak akan sempat menyelamatkanmu, karena mereka telah terikat dengan lawannya masing-masing.
Parung Landung menggeram. Ketika ia memandang pertempuran di sekitarnya, maka ia memang tidak dapat mengharapkan para pengikut Kiai Narawangsa membantunya. Setiap orang harus berjuang untuk melindungi dirinya sendiri.
Sementara itu, Manggada dan Laksana telah menjadi semakin dekat. Keduanya telah mengacukan senjata mereka. Parung Landung masih berdiri tegak di tempatnya. Sementara Manggada sekali lagi berkata, ”Jangan melawan lagi. Tidak akan ada gunanya.”
Parung Landung berdiri termangu-mangu. Dari lukanya masih mengembun darahnya yang merah. Namun senjata Parung Landung itu seakan-akan telah terkulai. Ujungnya bahkan telah menyentuh tanah. Kepala anak muda itu tertunduk lesu. Sekali-sekali ia masih berpaling memandang tubuh adiknya yang terkapar.
“Menyerahlah. Letakkan senjatamu.” berkata Manggada kemudian.
Parung Landung itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun mulai membungkuk untuk meletakkan senjatanya. Nampaknya ia tidak ingin melemparkan goloknya yang telah mengawani dalam petualangannya yang panjang.
Laksana melangkah mendekat. Ia berniat untuk memungut senjata itu setelah diletakkan oleh Parung Landung. Namun tiba-tiba saja Manggada berteriak, “Laksana, hati-hati.”
Laksana terkejut. Tetapi yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Parung Landung yang seolah-olah sudah meletakkan senjatanya itu, tiba-tiba telah meloncat menyerang Laksana dengan garangnya sambil berteriak, ”Aku bunuh kau karena kau sudah membunuh saudaraku.”
Laksana memang agak terlambat menangkis serangan itu. Golok yang berat itu terjulur langsung mengarah ke dada Laksana. Serangan itu terjadi demikian cepatnya. Laksana yang menepis golok lawannya itu tidak seluruhnya berhasil. Ujung golok itu ternyata masih sempat mengoyak pundaknya. Tubuh Laksana bagaikan diputar. Anak muda itu benar-benar telah kehilangan keseimbangannya. Dengan derasnya Laksana terlempar jatuh. Pedangnya terlepas dari tangannya dan terpental beberapa langkah daripadanya.
Parung Landung dengan cepat meloncat memburunya. Goloknya yang besar itupun segera terangkat. Dengan geramnya ia mengayunkan goloknya untuk menghabisi anak muda yang telah membunuh saudaranya itu. Laksana tidak dapat berbuat banyak. Yang dapat dilakukan adalah melindungi dahinya dengan lengannya ketika golok itu mengarah kekepalanya.
Tetapi golok itu tidak pernah memecahkan kepala Laksana atau mematahkan lengannya. Demikian golok itu terayun, maka Parung Landung itu terdorong dengan derasnya. Justru dari dadanya tersembul ujung pedang yang ditusukkan dari punggung.
Parung Landung tidak sempat mengaduh. Goloknya yang terayun itu tidak mengenai sasarannya justru ketika Parung Landung itu jatuh tertelungkup. Ketika tubuhnya terdorong maju, maka kakinya sudah menyangkut tubuh Laksana yang terbaring di hadapannya.
Bukan hanya Parung Landung, bahkan Manggada yang telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyelamatkan Laksana telah terdorong dan seperti Parung Landung, kakinya juga terantuk tubuh Laksana. Sejenak kemudian, Manggada pun telah bangkit berdiri. Demikian pula Laksana meski pun harus terdorong tubuh Parung Landung.
Demikian mereka berdiri, maka tubuh Laksana justru telah menjadi merah oleh darah. Kecuali darahnya sendiri yang mengalir dari lukanya di pundaknya, darah Parung Landung telah membasahi tubuhnya pula.
Manggada yang kemudian telah menarik pedangnya, memandangi tubuh kedua orang saudara yang terbaring diam itu. Laksana yang telah memungut senjatanya pula, kemudian berdiri tegak memandangi arena pertempuran yang semakin meluas.
Tetapi kekuatan Kiai Narawangsa sudah menjadi semakin tipis. Mereka bahkan seakan-akan telah kehilangan hubungan yang satu dengan yang lain, sehingga mereka harus menentukan langkah mereka masing-masing.
Manggada dan Laksana pun kemudian telah mendekati arena pertempuran itu. Beberapa sosok tubuh telah terbaring diam. Namun masih ada yang merintih dan mengaduh karena luka-lukanya. Ketika Manggada itu telah berdiri di arena, maka iapun segera berteriak,
”Menyerahlah. Tidak ada gunanya lagi kalian bertempur. Lihat, kedua orang pemimpin kalian telah terbunuh.”
Para pengikut Kiai Narawangsa memang menjadi ragu-ragu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di medan yang lain. Tetapi rasa-rasanya keadaan kawan-kawannya menjadi tidak jauh berbeda. Seandainya mereka mampu mendesak para cantrik dari padepokan itu, maka aliran kemenangan mereka yang memasuki pintu gerbang utama tentu sudah sampai dan memenuhi seisi padepokan. Tetapi mereka belum melihat kelompok-kelompok yang memasuki padepokan itu dari pintu gerbang utama sampai ke tempat itu.
Dalam pada itu, sekali lagi mereka mendengar suara Manggada ”Aku beri kesempatan kepada kalian untuk menyerah. Jika kesempatan ini kalian sia-siakan, maka kalian tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi.”
Para pengikut Kiai Narawangsa itu memang tidak melihat kemungkinan lain. Apalagi sebagian dari mereka rasa-rasanya sudah menjadi berputus-asa. Pertempuran diteriknya panas matahari tanpa melihat harapan. Pemimpin mereka telah terbunuh, sehingga dengan demikian, maka kedua orang anak muda yang telah membunuh pemimpin mereka itu akan dapat membunuh mereka pula tanpa ampun.
Karena itu, selagi masih ada kesempatan, maka beberapa orang diantara mereka yang ketahanan jiwaninya lemah, telah memutuskan untuk menyerah. Tetapi sebagaimana di bagian lain dari kelompok-kelompok pengikut Kiai Narawangsa, maka di kelompok-kelompok itu pun terdapat orang-orang yang setia kepada Kiai Narawangsa. Dengan lantang orang itupun berteriak,
”Jika nanti Kiai Narawangsa mengambil alih padepokan ini, maka siapa yang berkhianat akan digantung.”
Keragu-raguan memang melanda para pengikut Kiai Narawangsa. Untuk meyakinkan mereka, maka Manggada dan Laksana pun benar-benar telah turun kedalam arena pertempuran. Ternyata pedang kedua orang anak muda itu benar-benar membuat bulu tengkuk para pengikut Kiai Narawangsa itu berdiri. Karena itu, maka mereka memang tidak mempunyai pilihan lain.
Ketika sekali lagi Manggada meneriakkan kesempatan untuk menyerah, maka beberapa orang diantara mereka pun langsung melemparkan senjata-senjata mereka. Beberapa orang yang setia kepada Kiai Narawangsa masih berusaha untuk membakar keberanian kawan-kawan mereka Tetapi masih saja ada diantara mereka yang melemparkan senjata mereka.
Pertempuran itu pun kemudian telah mereda. Mereka yang tidak mau menyerahkan dirinya, harus menghadapi kenyataan, bahwa mereka benar-benar akan dihancurkan. Dengan demikian maka pertempuran di beberapa tempat pun sudah menjadi semakin mereda. Sebagian dari para pengikut Kiai Narawangsa sudah menyerah.
Namun di halaman depan padepokan itu, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Apalagi karena Kiai Narawanagsa sendiri masih bertempur melawan Ki Ajar Pangukan. sementara Nyai Wiji Sari bertempur melawan Ki Pandi. Namun kehadiran orang-orang tua yang berilmu tinggi di arena pertempuran itu sangat membatasi gerak para pengikut Kiai Narawangsa.
Ki Sambi Pitu yang telah kehilangan lawannya, telah berada diantara para cantrik pula. Sementara itu Ki Lemah Teles dan Ki Warana bersama-sama para cantrik telah membersihkan para pengikut Kiai Narawangsa yang sudah terlanjur menyusup diantara bangunan-bangunan di padepokan itu.
Dalam pada itu, Kiai Narawangsa sendiri ternyata tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Bahkan Ki Ajar Pangukan itu selalu dapat mengimbangi ilmunya yang selalu ditingkatkannya.
Kiai Narawangsa itu semakin lama menjadi semakin gelisah. Kematian Gunasraba telah membuat hatinya bagaikan terkoyak. Kecuali ia merasa kehilangan, menurut perhitungannya, lawan Gunasraba itu akan dapat dengan semena-mena menghancurkan para pengikutnya. Sedangkan Nyai Wiji Sari masih juga belum dapat melepaskan diri dari lawannya yang bongkok itu.
Sementara itu, Kiai Narawangsa pun mulai dapat menilai kenyataan yang dihadapinya. Para pengikutnya sudah menyusut dengan cepat. Para pemimpin kelompoknya sudah terbunuh di medan. Karena itu, maka satu-satunya harapannya adalah membinasakan lawannya, kemudian menghadapi yang lainnya yang berkeliaran di antara para cantriknya.
Dalam saat-saat yang gawat itu Kiai Narawangsa telah mengerahkan ilmu pamungkasnya. Sejenak ia sempat memusatkan nalar budinya. Kemudian disebutnya sumber-sumber kekuatan dan daerah kelam. Kiai Narawangsa memang mengandalkan ilmunya berdasarkan kekuatan dari kerajaan hitam.
Ketika kemudian Kiai Narawangsa itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, maka rasa-rasanya tubuhnya telah bergetar. Semacam awan yang hitam mulai mengabut di sekitarnya. Semakin lama semakin tebal. Awan itu mulai berputar perlahan-lahan. Tetapi semakin lama menjadi semakin cepat.
Ki Ajar Pangukan yang berpengalaman itupun segera menyadari, bahwa lawannya telah mengetrapkan ilmunya yang sangat berbahaya. Awan yang kehitam-hitaman itu akan dapat melibatnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, kemudian membantingnya ke tanah.
Karena itulah, maka Ki Ajar Pangukan harus menanggapinya. Ia tidak ingin dilibat oleh awan yang akan menjadi semacam angin pusaran itu. Dengan cepat, Ki Ajar Pangukan telah mengambil jarak untuk mendapat kesempatan melawan awan yang berputar itu.
Para cantrik dan bahkan para pengikut Kiai Narawangsa sendiri yang sedang bertempur telah menyibak. Tidak seorang pun yang dapat bertahan jika awan yang kehitam-hitaman itu melibat mereka dan mengangkatnya ke udara. Kemudian membantingnya jatuh di atas tanah. Tubuh mereka tentu akan lumat dan mereka akan kehilangan nyawa mereka.
Ki Ajar Pangukan memperhatikan awan itu dengan dahi yang berkerut. Sementara itu, Ki Sambi Pitu, Ki Lemah Teles serta para cantrik menyaksikan ungkapan ilmu Kiai Narawangsa itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ki Pandi yang sedang bertempur melawan Nyai Wiji Saripun sempat melihat awan yang berputaran itu sejenak.
Sementara itu Nyai Wiji Sari yang melihat kerut di dahi Ki Pandi berkata, ”Nah, bongkok buruk. Apa yang dapat dilakukan oleh kawan-kawanmu untuk melawan kemampuan Kiai Narawangsa. Ilmu itu adalah ilmu yang jarang sekali dipergunakan. Tetapi karena kalian membuatnya sangat marah, maka tidak ada pilihan lain dari Kiai Narawangsa kecuali membinasakan kalian dengan ilmunya.”
Ki Pandi mengangguk-angguk. Tetapi ia tetap memelihara jarak dengan Nyai Wiji Sari, agar tidak terjadi serangan yang tiba-tiba.
“Bongkok buruk. Kenapa kau tidak menghentikan saja perlawananmu? Menyerahlah. Kau akan mendapat hukuman yang ringan.”
“Apakah pengertian hukuman yang ringan itu didalam lingkunganmu?” bertanya Ki Pandi. ”Dipenjara setahun, dua tahun atau harus bekerja paksa di kebun-kebun di bawah teriknya matahari atau justru digantung?”
“Apapun ujudnya, tetapi tentu lebih baik daripada disambar angin pusaran itu.”
Tetapi sikap Ki Pandi itu mengejutkan sekali. Orang bongkok itu justru tersenyum sambil berkata, ”Aku tidak mengira bahwa didalam kalutnya pertempuran yang menentukan ini. Kiai Narawangsa sempat mengajak bermain-main.”
“Gila kau. Ia tidak sedang bermain-main. Ilmu itu benar-benar dapat membunuhmu.”
Tetapi Ki Pandi menggeleng. Katanya sambil tertawa, ”Bagi Ki Ajar Pangukan, maka asap-asapan itu hanya dapat membuatnya sedikit terbatuk-batuk.”
“Tidak!” Nyai Wiji Sari hampir berteriak ”Lihat. Kawanmu itu akan mati dilibat, diangkat dan kemudian dihempaskan diatas batu padas.”
“Nyai keliru!” sahut Ki Pandi ”Permainan itu adalah permainan Ki Ajar Pangukan dimasa kanak-kanaknya.”
“Iblis bongkok. Kau akan melihat, bagaimana tubuh kawanmu itu hancur nanti.”
“Marilah kita bertaruh, Nyai...” desis Ki Pandi.
Nyai Wiji Sari tidak menyahut. Tetapi wajahnya nampak menjadi tegang.
Dalam pada itu, asap yang kehitam-hitaman serta berputar semakin cepat itu telah dilihat pula oleh para pengikut Kiai Narawangsa yang berada di bagian belakang padepokan. Bahkan mereka yang telah menyerah pun menyesali keputusannya yang tergesa. Ilmu yang nggegirisi itu tentu akan sanggup menyelesaikan pekerjaan Kiai Narawangsa yang berat itu.
“Kenapa kita demikian tergesa-gesa menyerah?” desis salah seorang pengikut Kiai Narawangsa.
“Bukan salah kita. Kenapa baru sekarang Kiai Narawangsa melepaskan ilmunya? Kenapa tidak tadi sebelum kita menyerah?”
“Awan yang kehitam-hitaman itu akan dapat menghancurkan kawan-kawan kita sendiri. Agaknya kawan-kawan kita sekarang telah berpencar, sehingga Kiai Narawangsa mendapat kesempatan untuk melepaskan ilmunya itu.”
“Alangkah bodohnya kita disini.”
Tetapi para pengikut Kiai Narawangsa yang sudah terlanjur menyerah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Senjata mereka telah dirampas. Di sekelilingnya para cantrik siap berjaga-jaga dengan senjata telanjang. Namun seorang diantara para pengikut Kiai Narawangsa yang sudah terlanjur menyerah itu bangkit berdiri sambil berteriak,
”Itulah akhir dari segala-galanya. Padepokan ini akan hanyut diterbangkan oleh angin pusaran itu. Kita semuanya pun akan hanyut pula. Kemudian dilepaskan di udara sehingga kita akan mati terbanting di atas tanah ini. Tetapi itu lebih baik bagi kita daripada menjadi tawanan.”
Mulutnya terkatup ketika tiba-tiba saja pangkal landean tombak menyambar mulutnya. Dua giginya tanggal dan mulutnya pun mulai berdarah.
Dalam pada itu, maka angin pusaran itu mulai merayap menuju ke tempat Ki Ajar Pangukan berdiri. Ki Ajar Pangukan menyadari, apa yang sedang dihadapinya itu. Karena itu, maka ia pun telah bersiap sebaik-baiknya. Ki Ajar Pangukan sudah bertekad untuk beradu ilmu, apapun yang akan terjadi atas dirinya. Karena itu, maka Ki Ajar Pangukan itupun segera mempersiapkan dirinya. Dipusatkannya nalar budinya menghadapi ilmu lawannya itu.
Ketika pusaran asap yang kehitam-hitaman itu mendekatinya, maka Ki Ajar Pangukan itupun telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dilandasi dengan segenap kekuatan ilmu dan kemampuannya, maka Ki Ajar Pangukan itu telah meloncat dan mengayunkan tangannya menghantam pusaran kabut yang kehitam-hitaman itu.
Satu benturan ilmu telah terjadi. Kabut yang kehitam-hitaman dan berputar menghampiri Ki Ajar Pangukan itu tiba-tiba telah pecah. Angin pusaran itu bagaikan telah tertiup oleh prahara sehingga pecah bercerai berai.
Kiai Narawangsa terkejut melihat akibat dari benturan ilmu itu. Selangkah ia mundur. Ia hampir tidak percaya, bahwa ilmunya itu telah dipecahkan sehingga tidak berdaya sama sekali.
Dalam pada itu, selagi Kiai Narawangsa itu termangu-mangu, maka Ki Ajar Pangukan telah menghentakkan tangannya sekali lagi mengarah langsung kepada Kiai, Narawangsa. Tangannya sama sekali tidak menyentuh Kiai Narawangsa yang masih berdiri termangu-mangu karena ungkapan ilmunya itu hancur dan kemudian hanyut tidak berbekas.
Namun selagi kabut yang kehitam-hitaman itu menjadi semakin tipis, maka Kiai Narawangsa itu terkejut sekali. Ayunan tangan Ki Ajar Pangukan yang mengarah kepadanya itu, telah menghentakkan kekuatan dan ilmu yang dahsyat sekali. Tetapi Kiai Narawangsa itu terlambat. Kekuatan ilmu Ki Ajar Pangukan itu menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang tidak terlawan.
Tubuh Kiai Narawangsa itupun telah terlempar beberapa langkah surut. Kemudian jatuh terbanting di atas tanah. Sekali Kiai Narawangsa itu menggeliat. Namun kemudian tubuhnya menjadi tidak berdaya sama sekali. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka tidak ada lagi kekuatan yang dapat menggerakkan tubuhnya.
Nyai Wiji Sari pun terkejut pula menyaksikan peristiwa itu. Di luar sadarnya, maka ia pun segera berlari ke arah tubuh Kiai Narawangsa terbaring. Dengan serta-merta Nyai Wiji Sari pun berlutut di sisi tubuh yang menjadi sangat lemah itu.
“Kiai...” suara Nyai Wiji Sari bagaikan tersangkut di kerongkongan.
Kiai Narawangsa masih membuka matanya. Dilihatnya Nyai Wiji Sari yang berlutut di sebelahnya. “Nyai...” suaranya lemah sekali ”Aku tidak dapat lagi membantumu mengambil anakmu.”
“Kiai...” desis Nyai Wiji Sari ”Bangkitlah. Jangan tinggalkan aku sendiri disarang serigala ini.”
Wajah Kiai Narawangsa menjadi merah sesaat. Namun kemudian wajah itu menjadi pucat kembali. Nafasnya menjadi tersengal-sengal. “Nyai, aku tidak kuasa menyeberangi batas ini.”
“Tidak. Kau adalah seorang yang tidak terkalahkan. Kau mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Atasi kesulitan bagian dalam tabuhmu, Kiai.”
Kiai Narawangsa menggeleng lemah. Katanya, ”Siapa pun aku Nyai, ternyata aku juga mempunyai keterbatasan. Hati-hatilah membawa diri Nyai. Kau memang berada di sarang serigala-serigala yang lapar.”
“Kiai, Kiai...” Nyai Wiji Sari menggungcang-guncang tubuh itu. Namun Kiai Narawangsa telah meninggalkannya untuk selama-lamanya.
Nyai Wiji Sari yang garang itu menangis. Kepergian Kiai Narawangsa benar-benar tidak diduganya. Ketika mereka berangkat dari padepokan mereka, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sudah demikian yakin akan keberhasilan mereka. Tetapi ternyata mereka harus menghadapi kekuatan yang tidak mereka duga sebelumnya. Ternyata bahwa Kiai Narawangsa itu telah terbunuh.
Ki Ajar Pangukan berdiri termangu-mangu. Di sebelahnya Ki Pandi mengangguk-angguk kecil. Ki Lemah Teles, Ki Sambi Pitu, Ki Jagaprana bahkan Manggada dan Laksana pun telah berdiri di sekitar tubuh yang terbaring itu.
Pertempuran yang terjadi di halaman itupun dengan cepat menyusut. Tanpa ada yang memberi peringatan atau mengancam, para pengikut Kiai Narawangsa itu telah menyerah.
Namun berbeda dengan mereka, Nyai Wiji Sari itu tiba-tiba telah bangkit. Pedangnya masih berada di tangannya. Bahkan pedang itu pun kemudian telah berputar dengan cepatnya.
Orang-orang yang berdiri di seputarnya berloncatan surut. Mereka tidak menduga bahwa tiba-tiba saja Nyai Wiji Sari telah mengamuk seperti seseorang yang kerasukan iblis. Yang terutama menjadi sasaran serangan-serangannya adalah Ki Pandi, sehingga Ki Pandi itupun berloncatan surut beberapa langkah.
“Nyai...” Ki Pandi mencoba untuk mencegahnya. “Jangan Nyai. Jangan kehilangan akal seperti itu.”
Tetapi Nyai Wiji Sari tidak mendengarnya. Serangan-serangannya datang beruntun. Bahkan kemudian dengan membabi buta. Ki Pandi terpaksa setiap kali berloncatan menghindar, menangkis dan bahkan sekali-sekali membentur senjata Nyai Wiji Sari. Tetapi Ki Pandi sendiri tidak pernah membalas serangan-serangan itu.
Nyai Wiji Sari yang mengetahui bahwa lawannya tidak pernah membalasnya menyerang, berkata lantang, ”Kenapa kau hanya berloncatan menghindar? Kenapa kau tidak membalas menyerang.”
”Sabarlah Nyai. Sebenarnya apa yang kau cari. Jika kau ingin mendapatkan anakmu, itulah anakmu. Tidak seorang pun yang akan menghalangimu. Ambil anakmu dan bawa kemana kau mau.”
“Kau berusaha untuk melemahkan tekadku untuk membunuhmu dan membunuh kawan-kawanmu. Ayo, katakan kepada kawan-kawanmu itu. Kita akan bertempur sampai tuntas. Aku sanggup membunuh semua penghuni padepokan ini.”
“Nyai...” berkata Ki Pandi sambil menghindari serangan-serangannya. ”Cobalah kau pergunakan nalarmu. Berpikirlah dengan tenang. Jangan kau biarkan gejolak perasaanmu itu membakar dadamu.”
Nyai Wiji Sari tidak mendengarkannya sama sekali. Perempuan itu masih saja menyerang Ki Pandi dengan garangnya. Tetapi akhirnya Ki Pandi tidak mencegahnya lagi. Dibiarkannya perempuan itu mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Bahkan Ki Pandi itu justru sekali-sekali mulai menyerang, menyentuh tubuh lawannya dengan serulingnya meskipun tidak menimbulkan akibat apapun juga. Tetapi sentuhan-sentuhan itu telah memancing Nyai Wiji Sari untuk mengerahkan tenaga dan kemampuannya.
Ki Ajar Pangukan, Ki Sambi Pitu, Ki Jagaprana dan Ki Lemah Teles dan beberapa orang yang lain memang dapat mengetahui maksud Ki Pandi. Karena itu, mereka sama sekali tidak mencegahnya. Selangkah demi selangkah Ki Pandi memancing lawannya mendekati tugu kecil di depan pendapa bangunan utama padepokan itu, sehingga akhirnya keduanya telah bertempur hanya beberapa langkah saja dari tugu kecil itu.
Namun betapapun Nyai Wiji Sari mengerahkan kemampuannya, namun ia sama sekali tidak pernah mampu menyentuh tubuh lawannya dengan ujung pedangnya. Tetapi Ki Pandi pun tidak pula pernah menyakiti Nyai Wiji Sari. Betapapun tinggi daya tahan tubuh Nyai Wiji Sari, akhirnya iapun telah sampai pada batas ketahanannya. Semakin bernafsu ia ingin membunuh lawannya, maka tenaganyapun menjadi semakin terperas habis.
Akhirnya, Nyai Wiji Sari itu tidak dapat mengingkari bahwa tenaganya justru mulai menyusut. Kenyataan itulah yang kemudian dihadapi oleh Nyai Wiji Sari. Ketika tenaganya benar-benar sudah terkuras habis, maka serangan-serangannya menjadi tidak berarti lagi. Nyai Wiji Sari setiap kali justru terhuyung-huyung terseret oleh ayunan pedang sendiri. Akhirnya, Nyai Wiji Sari itu pun justru telah terjatuh di sisi tugu kecil itu.
Ki Pandi berdiri termangu-mangu sejenak. Nyai Wiji Sari masih menggenggam pedangnya yang kehitam-hitaman. Meskipun pedangnya tidak mengkilap, tetapi pedang itu tentu tajam sekali.
“Nyai...” suara Ki Pandi lunak ”Sudahlah. Bukankah tidak ada artinya lagi jika Nyai masih saja membiarkan perasaan Nyai bergejolak.”
Nyai Wiji Sari tidak menyahut.
“Nyai, anakmu sudah tidak ada lagi. Kiai Banyu Bening juga sudah tidak ada. Aku tidak tahu, apa yang akan kau lakukan terhadap Kiai Banyu Bening seandainya ia masih ada.”
Nyai Wiji Sari tidak segera menjawab.
”Terakhir, Kiai Narawangsa pun sudah tidak ada pula Nyai.”
Nyai Wiji Sari tidak menjawab. Tetapi yang terdengar kemudian adalah isak tangisnya. Bahkan tiba-tiba dipeluknya tugu itu, seperti ia sedang memeluk anaknya.
Pertempuran pun benar-benar telah selesai, tidak ada perlawanan lagi di seluruh padepokan itu. Semua pengikut Kiai Narawangsa sudah menyerah. Ketika matahari kemudian turun menjelang senja, maka Nyai Wiji Sari itu berdiri di pintu gerbang padepokan. Ki Ajar Pangukan, Ki Pandi, Ki Lemah Teles, Ki Sambi Pitu, Ki Jagaprana bahkan Manggada dan Laksana mengantarnya sampai keluar pintu gerbang.
“Aku akan melihat dunia dari sisi yang lain...” berkata Nyai Wiji Sari ”Aku titip anakku. Aku yakin bahwa ia tidak akan tersia-sia di sini. Aku akan mencari jalan untuk dapat menebus segala dosa dan kesalahanku. Semuanya itu bersumber dari ketidak-setiaanku.”
Ki Ajar Pangukan mengangguk kecil sambil berdesis, ”Hati-hatilah Nyai.”
Nyai Wiji Sari itupun kemudian berjalan meninggalkan padepokan itu sambil berdesis, ”Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan kepadaku.”
Perempuan itupun kemudian melangkah dengan langkah yang tetap menjauhi padepokan itu. Tetapi ia tidak lagi mengenakan pakaian khususnya. Ia mengenakan pakaian sebagaimana seorang perempuan tanpa senjata dilambungnya.
Matahari masih bersinar. Sinarnya tidak lagi menggigit. Tetapi matahari senja itu masih memberikan cahaya kepada Nyai Wiji Sari yang berjalan menjauh. Ia tidak tau kemana ia harus memilih jalan yang lain dari jalan yang pernah ditempuhnya bersama Kiai Narawangsa. Meskipun kemudian langit menjadi semakin suram, tetapi dihati Nyai Wiji Sari, matahari justru memancarkan cahayanya yang terang.
DAFTAR KARYA SH MINTARDJA