Matahari Senja
Bagian 19
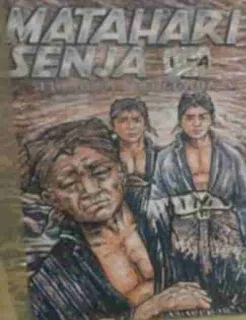
PARUNG Landung dan Paron Waja telah diberinya berbagai macam petunjuk sehingga usaha membakar pintu gerbang itu tidak akan gagal. Bahkan air tidak akan dapat menolong pintu gerbang itu.
Kiai Narawangsa yang telah mendapat laporan Gunasraba bahwa segala sesuatunya sudah siap, telah memberikan isyarat, bahwa mereka akan segera menyerang padepokan itu.
“Besok sehari kita mempersiapkan segala-galanya. Besok lusa, di dini hari, kita akan mulai membakar pintu gerbang. Menurut perhitungan, saat matahari naik, pintu gerbang dan pintu-pintu butulan tentu sudah menjadi abu.”
Perintah itu pun segera menjalar ke setiap telinga. Mereka yang sudah merasa jemu berkeliaran di hutan itu justru menjadi gembira. Saat-saat berburu binatang sudah berakhir. Mereka kemudian akan berburu lawan di padepokan Kiai Banyu Bening.
“Kita sudah terlalu lama tidak membasahi senjata kita,” berkata seorang yang berkepala botak ”mudah-mudahan orang-orang padepokan itu tanggap untuk bermain bersama.”
“Cantrik-cantrik padepokan pada umumnya juga memiliki kemampuan olah kanuragan.”
“Justru itulah yang rnenarik,“ jawab orang botak itu. Keputusan Kiai Narawangsa itu sesaat membuat wajah Nyai Wiji Sari menjadi cerah. Pertempuran akan membuatnya lupa pada kegelisahannya. Perang tidak akan memberinya kesempatan merenungi dirinya sendiri.
Tetapi malam-malam menjelang gerakan yang dilakukan oleh Kiai Narawangsa itu telah dilihat oleh Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi. Dengan sadar, bahwa diantara orang-orang yang berada di hutan itu terdapat orang-orang berilmu tinggi, Ki Ajar Pangukan, Ki Pandi berusaha mengamati kesibukan mereka.
Pada malam menjelang serangan yang akan dilakukan itu, Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi masih belum mengetahui, cara apakah yang akan dipergunakan untuk menghancurkan pintu gerbang.
Kiai Narawangsa dan Gunasraba cukup berhati-hati. Mereka mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan mereka pergunakan untuk membakar pintu gerbang itu ditengah-tengah lingkungan perkemahan mereka, sehingga Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi tidak dapat melihatnya.
Namun yang mereka ketahui, bahwa serangan itu akan berlangsung sejak dini hari. Karena itu, maka kedua orang itupun segera kembali ke padepokan untuk memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan Ki Warana.
Akhirnya saat yang mendebarkan itupun datang. Hari terakhir yang disediakan untuk mempersiapkan segala-galanya telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para pengikut Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari. Sehingga dengan demikian, maka segala persiapan tidak ada lagi yang tercecer.
Di malam terakhir itu, sebagian dari para pengikut sempat beristirahat sebaik-baiknya. Mereka sempat tidur nyenyak dan bahkan mendekur keras. Hanya beberapa orang yang bertugas sajalah yang sibuk mempersiapkan segala-galanya.
Namun demikian, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari berusaha untuk dapat memberi kesempatan kepada orang-orangnya untuk bergantian beristirahat. Namun lewat tengah malam, maka semua orang telah dibangunkan. Mereka harus mulai mempersiapkan diri sebaik-baiknya Mereka harus mengamati senjata mereka masing-masing, agar senjata mereka tidak mengecewakan jika mereka sudah berada di medan pertempuran.
“Semua orang harus bersiap untuk melindungi diri sendiri dari hujan anak panah,“ berkata Kiai Narawangsa “Yang tidak berperisai supaya bersiap sebaik-baiknya agar tidak mati sebelum memasuki pintu gerbang padepokan.”
Demikianlah, setelah segala sesuatunya bersiap, maka sebuah iring-iringan yang cukup besar telah mulai bergerak menuju ke padepokan. Mereka juga sudah makan sekenyang-kenyangnya agar mereka tidak kehabisan tenaga disaat-saat mereka bertempur nanti di padepokan. Sementara itu. orang-orang yang ditugaskan khusus telah menyediakan makanan pula yang dapat dimakan kapan saja menurut kebutuhan. Diantara iring-iringan itu terdapat pula beberapa ekor kuda beban yang mengangkut bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk membakar pintu padepokan.
Pada saat yang demikian Gunasraba telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bersama beberapa orang yang telah terlatih dan berpengalaman, maka Gunasraba duduk diatas punggung kuda masing-masing. Beberapa orang diantaranya memegangi kendali kuda-kuda yang menjadi kuda beban.
Pada saat yang ditentukan, maka beberapa orang berkuda itupun dengan cepat telah berpacu menuju ke pintu gerbang utama dan yang lain ke pintu butulan sebagaimana yang pernah mereka amati sebelumnya.
Semuanya berjalan dengan cepat. Para petugas yang berjaga-jaga diatas panggungan melihat beberapa ekor kuda muncul dari kegelapan. Kuda-kuda itu berlari kencang menuju ke padepokan. Bahkan ada diantaranya kuda-kuda yang tidak berpenumpang.
Mula-mula para petugas itu mengira bahwa orang-orang yang datang berkuda itu, sebagaimana pernah mereka lakukan, hanya akan mengamati keadaan. Tetapi kuda-kuda itu berlari langsung mendekati pintu gerbang utama. Yang lain memencar menuju ke pintu-pintu gerbang butulan.
Para petugas yang sedang berjaga-jaga itu terlambat mengambil sikap. Ketika beberapa orang menyadari keadaan itu, mereka berusaha untuk mencegahnya dengan anak panah. Tetapi para petugas itu memang terlambat memberikan tanggapan terhadap langkah-langkah yang tidak terduga itu.
Orang-orang berkuda itupun segera telah berada di pintu-pintu gerbang. Anak panah yang diluncurkan dari panggungan di belakang dinding memang agak sulit untuk mencapai orang-orang yang berdiri melekat pintu gerbang yang dialasnya terdapat atap ijuk.
Karena itu, maka dua orang diantara mereka pun segera berlari-lari turun untuk memberikan laporan kepada Kiai Lemah Teles yang berada di pendapa bersama Ki Warana.
“Kita benar-benar sudah mulai.” berkata Ki Lemah Teles.
“Aku akan melihat apa yang terjadi, Ki Lemah Teles,“ berkata Ki Warana.
“Aku juga akan pergi. Perintahkan memberitahukan kepada orang-orang yang malas itu.”
Ki Warana dan Ki Lemah Teles pun segera berlari-lari ke panggungan, sementara itu, Ki Warana telah memerintahkan seorang cantrik untuk memberitahukan kepada orang-orang tua yang berilmu tinggi yang sedang berada di belakang.
“Bongkok buruk dan Ki Ajar Pangukan tidak mengigau dengan ceriteranya tentang serangan yang akan dilakukan menjelang fajar hari ini.” berkata Ki Lemah Teles sambil berlari-lari ke panggungan.
Demikian Ki Lemah Teles dan Ki Warana naik ke panggungan disisi kanan pintu gerbang, maka iapun segera menyadari, apa yang akan terjadi. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi pengalaman dan pengetahuan Ki Lemah Teles yang luas segera mengetahui, bahwa orang-orang itu akan membakar pintu gerbang.
Sebenarnyalah Gunasraba telah meletakkan beberapa onggok serat kering di bawah pintu gerbang. Serat kering yang sudah berbaur dengan serbuk biji jarak. Kemudian untuk meyakinkan bahwa api akan berkobar, dituang pula dua bumbung minyak kelapa. Kemudian beberapa kampil biji jarak ditaburkan pula diatasnya. Beberapa saat kemudian, maka Gunasraba pun segera mempersiapkan api dengan batu titikan dan dimik-dimik belerang.
Demikian matangnya persiapan yang dilakukan, sehingga segalanya itu terjadi demikian cepatnya. Gunasraba tidak mempergunakan kayu-kayu kering untuk mengobarkan api, karena serat yang disediakan sudah cukup banyak, sehingga Gunasraba itu yakin, bahwa api akan segera menelan pintu gerbang induk itu.
Sebenarnyalah serat-serat yang kering itu dengan cepat terbakar. Serbuk biji jarak yang mengandung minyak itupun cepat membuat api semakin besar. Demikian pula minyak kelapa yang dituang serta beberapa kampil biji jarak. Untuk beberapa saat lamanya, Gunasraba memang masih harus melindungi apinya yang sedang membesar.
Dalam pada itu, maka didalam dinding padepokan telah terdengar isyarat untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Suara kentongan-kentongan kecil telah melontarkan perintah kepada setiap orang yang ada didalam dinding padepokan.
Gunasraba yang mendengar suara kentongan itu sempat mengumpat. Ternyata orang-orang padepokan itu tidak menjadi gugup dan bingung. Suara kentongan-kentongan kecil, itu tidak membayangkan kegelisahan. Tiga atau ampat kentongan yang mengisyaratkan perintah itu memperdengarkan iramanya yang mapan.
Orang-orang padepokan itu memang tidak menjadi bingung. Sebelumnya mereka sudah mendapat perintah untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Tetapi yang terjadi memang lebih cepat dari yang mereka duga. Mereka memperhitungkan bahwa serangan itu akan datang bersamaan dengan terbitnya matahari. Tetapi ternyata di dini hari kentongan itu sudah harus memberikan isyarat agar mereka bersiap.
Ternyata kentongan itu berbunyi di saat mereka sedang makan. Karena itu, maka mereka pun segera menelan nasi yang masih belum sempat mereka makan. Sedikit terhambat di kerongkongan, sehingga mereka harus minum lebih banyak.
Beberapa saat kemudian para cantrik itupun berlari-larian naik ke panggungan. Sementara yang lain, bersiap-siap ditempat yang sudah ditentukan bagi setiap kelompok. Tetapi terdengar perintah yang lain dari beberapa orang yang berada di belakang pintu gerbang. ”Air. Air.”
Para cantrik yang berada disekitar pintu gerbang utama dan pintu gerbang mereka. Karena itu, maka mereka pun segera berlari-lari mencari air dengan bumbung-bumbung panjang yang sering dipergunakan untuk mengusung air mengisi gentong dan tempayan didapur, atau dengan kelenting. Tetapi bumbung-bumbung yang tersedia tidak cukup banyak untuk mengatasi api yang menyala semakin besar.
Pintu gerbang utama dan butulan yang terbuat dari kayu itu sudah mulai terbakar. Bahkan gawang pintunya juga sudah mulai menyala. Sementara itu, ijuk pada atap pintu gerbang itupun akan sangat mudah terbakar pula.
Para pemimpin padepokan itu memang tidak mengira bahwa Kiai Narawangsa akan mempergunakan cara yang tidak banyak dipergunakan orang untuk memecahkan pintu gerbang utama dari sebuah sasaran. Kiai Narawangsa tidak memecahkan pintu gerbang dengan sebuah balok kayu yang panjang dan besar yang diusung oleh banyak orang. Tidak pula mempergunakan tali-tali yang kuat yang ditarik oleh beberapa ekor kuda. Tetapi Kiai Narawangsa telah mempergunakan api. Bukan untuk memecahkan pintu, tetapi membakar pintu itu sehingga menjadi abu.
Ternyata air memang tidak banyak menolong. Apalagi air itu tidak cukup banyak dibanding dengan nyala api yang membesar. Tidak cukup banyak bumbung-bumbung besar yang dibuat dari bambu petung yang dapat dipergunakan untuk mengangkut air.
Karena itu, maka Ki Lemah Teles akhirnya memerintahkan para cantrik untuk menghentikan usaha mereka memadamkan api. Tetapi para cantrik harus segera bersiap dalam kesiagaan kedua. Mereka harus bersiap untuk bertahan di belakang pintu gerbang yang sudah dapat dipastikan akan terbuka.
Ki Pandi dan Ki Ajar Pangukan yang berdiri di panggungan sebelah kiri itupun menyaksikan api yang menyala itu dengan termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja Ki Pandi itu berkata kepada seorang cantrik. “Siapkan tali, he, kalian punya tampar ijuk?”
“Ada Kiai!“ jawab seseorang cantrik “Sisa tampar ijuk yang kemarin dipergunakan untuk memperbaiki tali-tali ijuk panggungan ini?”
“Masih ada berapa gulung?”
“Masih ada beberapa gulung Kiai.”
Ki Pandi pun kemudian berkata kepada Ki A jar Pangukan. ”Ki Ajar, marilah kita bermain-main dengan orang-orang yang sedang membakar pintu gerbang itu.
Ki Ajar Pangukan pun segera tanggap. Karena itu, maka iapun segera menyahut. ”Marilah. Ajak kedua cucumu itu.”
Manggada dan Laksana yang ada di panggungan itu pula segera menyahut. “Marilah, Ki Ajar. Kami akan ikut bersama Ki Ajar.”
Demikianlah, maka dengan cepat mereka telah mengurai tampar ijuk itu dan menjulurkannya keluar dinding. Disisi lain, diatas panggungan Ki Lemah Teles melihat Ki Pandi menjulurkan tali ijuk. Tidak hanya sehelai, tetapi beberapa helai.
Ki Lemah Teles segera mengetahui apa yang akan dilakukan. Sementara itu Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana juga sudah naik ke panggungan itu pula. Tanpa menunggu, maka Ki Jagaprana dan Ki Sambi Pitu pun segera bersiap. Karena di panggungan itu tidak ada tali ijuk yang dapat mereka pergunakan, maka mereka tidak mempergunakannya. Orang-orang berilmu tinggi itu kemudian meloncat begitu saja dari atas dinding padepokan seperti seekor kucing. Sementara itu, Ki Pandi dan Ki Ajar Pangukan telah turun dengan mempergunakan tali ijuk.
“Kenapa orang-orang itu mempersulit diri dengan tali-tali ijuk?“ desis Ki Sambi Pitu.
“Sebenarnya tali-tali itu tidak untuk mereka.” jawab Ki Jagaprana.
Sebenarnyalah selain kedua orang tua berilmu tinggi itu, Manggada dan Laksana pun telah turun pula menyusuri tali ijuk itu diikuti oleh beberapa orang cantrik.
Gunasraba yang berada di depan pintu menunggui api yang menyala semakin besar itupun terkejut. Ia tidak mengira bahwa ada beberapa orang yang turun dari atas dinding dan berlari-lari mendekatinya.
“Cegah mereka!“ teriak Gunasraba.
Beberapa orang yang datang bersamanya segera bersiap untuk menyongsong orang-orang yang berlari-lari itu. Namun Gunasraba sendiri tidak ikut bersama mereka. Dengan tangkasnya Gunasraba itu meloncat keatas punggung kudanya dan dengan cepat melarikan diri kedalam gelap.
Para pengikutnya memang termangu sejenak. Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan. Dengan geram Manggada dan Laksana telah berloncatan mendekat.
Tetapi Ki Pandi tidak segera menyerang mereka. Dengan lantang iapun berkata ”Menyerahlah. Kalian tidak mempunyai pilihan lain.”
Orang-orang yang datang bersama Gunasraba itu tidak menghiraukan. Jumlah orang yang turun dengan tali itu tidak banyak. Karena itu, maka mereka merasa mampu untuk bertahan sambil menunggu kawan-kawan mereka yang akan segera datang untuk menolong.
Mereka meyakini bahwa Ki Gunasraba sedang menghubungi Kiai Narawangsa untuk mendapatkan bantuan. Karena itu, justru orang-orang itulah yang telah mendahului menyerang mereka yang turun dari dinding padapokan.
Beberapa orang cantrik pun segera terlibat dalam pertempuran. Manggada dan Laksana juga segera terjun langsung melawan orang-orang yang telah membakar pintu gerbang itu.
Namun bagaimana pun juga api yang membakar pintu gerbang itu tidak dapat dipadamkan. Pintu gerbang itu memang terbakar. Yang dilakukan oleh para cantrik kemudian adalah mencegah panggungan disebelah menyebelah pintu gerbang itu ikut terbakar.
Dalam pada itu pertempuran yang terjadi di depan pintu gerbang itu tidak berlangsung lama. Ketika orang-orang tua berilmu tinggi itu melibatkan diri, maka dengan cepat orang-orang yang membakar pintu gerbang itu telah dikuasai.
Bahkan ketika.orang-orang yang membakar pintu-pintu butulan ikut bergabung dengan kawan-kawan mereka, ternyata mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi.
Dalam waktu yang singkat beberapa orang telah terkapar di depan pintu gerbang yang telah terbakar sedangkan yang lain telah menyerah. Para cantrik padepokan itu justru berhasil menguasai beberapa ekor kuda.
Tetapi mereka tidak tahu, bagaimana mereka akan membawa kuda-kuda itu masuk kedalam padepokan, karena pintu gerbang utama dan pintu-pintu butulan telah dibakar. Tetapi tiba-tiba saja seorang cantrik berteriak, “Masih ada satu pintu butulan yang tidak dibakar.”
Ki Pandi yang mendengar teriakan cantrik dari panggungan itu bertanya “Disisi sebelah mana?”
“Pintu butulan kecil yang menghadap ke Timur. Pintu yang hampir tidak pernah dipergunakan.”
Ki Pandi, orang-orang tua yang berilmu tinggi serta Manggada dan Laksana pun telah membawa beberapa ekor kuda yang tertinggal serta para tawanan mengelilingi dinding padepokan menuju ke pintu gerbang yang menghadap kesebelan Timur, yang karena tidak sering dipergunakan, maka telah ditumbuhi oleh batang ilalang dan pohon-pohon perdu.
Namun dalam pada itu, Gunasraba yang melarikan diri diatas punggung kudanya telah sampai ke induk pasukannya. Dengan nafas yang terangah-engah, ia telah melaporkan apa yang terjadi di pintu gerbang utama padepokan Kiai Banyu Bening.
“Orang-orang gila, yang ingin membunuh dirinya sendiri. Baiklah. Marilah kita mendekat. Bukankah sebentar lagi, pintu gerbang utama dan beberapa pintu butulan itu sudah akan menjadi abu?”
“Ya. Pada saat matahari terbit. Tetapi kita harus bersabar sedikit, agar kaki kita tidak menginjak bara yang masih panas.” Orang-orang yang pertama akan memasuki pintu gerbang sudah dipersiapkan. Bukankah mereka telah mengenakan tlumpah kulit kayu?”
“Aku memang sudah memberikan contoh, bagaimana membuat tlumpah kulit kayu untuk melindungi kaki mereka. Mudah-mudahan mereka telah mempersiapkannya.”
“Bukankah kita dapat melihat sekarang?” sahut Nyai Wiji Sari.
Gurasraba pun kemudian memerintahkan Parang Landung dan Paron Waja untuk melihat, apakah orang-orangnya mematuhi perintahnya membuat tlumpah-tlumpah kulit kayu untuk melindungi telapak kaki mereka dari bara yang masih panas. Sementara itu, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Saripun telah mempersiapkan segala-galanya. Sesaat lagi, mereka akan bergerak mendekati padepokan.
“Sayang, kita kehilangan beberapa ekor kuda.” desis Kiai Narawangsa.
“Tidak. Sebentar lagi, kita akan mendapatkannya kembali.” jawab Gunasraba.
Dalam pada itu Paning Landung dan Paron Waja pun telah melaporkan bahwa orang-orang mereka telah membuat tiumpah kulit kayu dengan tali kedebog yang sudah dikeringkan.
“Tidak ada masalah.” berkata Parung Landung “Mereka dapat mengabaikan panasnya bara yang tersisa. Meskipun ada yang membuat dari clumpring, tetapi cukup untuk menahan panasnya sisa-sisa gerbang yang sudah menjadi arang.”
“Tetapi clumpring itu sendiri akan terbakar,“ berkata Gunasraba.
“Bukankah kita tidak akan berdiri tegak diatas bara itu?“ sahut Paron Waja “Bukankah kita hanya akan berlari melintas?”
Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Tetapi Nyai Wiji Sari menyahut “Jangan merendahkan lawan. Mereka akan menahan kita diatas bara api pintu gerbang itu.”
“Kita dapat mengulur waktu sebentar Nyai. Bukankah kita dapat berbicara lebih dahulu dengan Banyu Bening? Ia akan berpikir ulang jika ia melihat kekuatan lata yang besar ini.”
“Aku tidak ingin berbicara dengan Banyu Bening. Aku hanya ingin anakku itu.”
Kiai Narawangsa tidak menjawab lagi. Namun kemudian iapun bertanya kepada Gunasraba, “Marilah. Apakah kita sudah bersiap sepenuhnya?”
“Sudah kakang. Kita sudah dapat bergerak sekarang. Mudah-mudahan kita masih sempat menolong orang-orang yang terjebak saat mereka membakar pintu gerbang.”
Demikianlah, maka Parung Landung dan Paron Wajapun segera memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju ke padepokan. Sementara itu langit telah menjadi merah. Mereka berharap ' bahwa saat matahari terbit, mereka sudah memasuki pintu-pintu gerbang padepokan yang mereka sangka masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening itu.
Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sarilah yang melangkah di paling depan. Kemudian Gunasraba dan dua orang saudara seperguruannya. Dua orang kakak beradik yang sebenarnya tidak kembar, tetapi wajah mereka demikian miripnya, sehingga banyak orang menyangka bahwa mereka adalah dua orang saudara kembar. Sedangkan sebenarnya umur mereka terpaut dua tahun. Krendhawa dan Mingkara.
Demikianlah, maka langkah kaki yang berderap di padang perdu itupun seakan-akan telah menggetarkan bumi. Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari yang berjalan dipaling depan nampak menjadi tegang. Telah berpuluh bahkan beratus kali keduanya turun ke medan pertempuran. Bukan saja saat-saat mereka merampok dan menyamun di bulak-bulak panjang.
Tetapi sudah berapa kali mereka terperosok ke dalam benturan kekuatan diantara mereka yang hidup dalam dunia yang kelam. Bertempur untuk memperebutkan pengaruh dan daerah jelajah, serta kadang-kadang tanpa sebab apa-apa.
Tetapi yang dihadapi oleh Nyai Wiji Sari saat ini adalah orang yang pernah tersangkut dalam perjalanan hidupnya. Bahkan seseorang yang telah memberinya seorang anak yang sekarang dimakamkan di belakang dinding padepokan itu. Anak itulah yang setiap saat seakan-akan memanggil-manggilnya. Mengulurkan tangannya, menggapainya sambil memanggil-manggilnya “Ibu, ibu, aku kedinginan, ibu.”
Nyai Wiji Sari menggeretak-kan giginya. Langkahnya menjadi semakin cepat. Bahkan rasa-rasanya Nyai Wiji Sari itu ingin meloncat langsung memasuki padepokan Kiai Banyu Bening. Tetapi di samping itu, ada semacam keseganan untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening sendiri.
Meskipun setiap kali Nyai Wiji Sari berusaha untuk mengingkarinya, tetapi di dasar hatinya, ia mengakui, betapa ia telah melakukan kesalahan sebagai seorang isteri, karena ia sudah membiarkan Narawangsa masuk ke dalam bilik tidurnya, justru saat ia menidurkan anaknya.
Petaka itu tidak dapat dihindarinya. Nyai Wiji Sari itu tertegun melihat api yang sudah menjadi semakin surut. Pintu gerbang padepokan itu telah runtuh. Tidak ada lagi yang menghalangi langkah mereka memasuki padepokan itu. Tetapi yang terbuka, yang tidak menjadi penghalang lagi, adalah pintu pada gerbang utama dan butulan. Di belakang reruntuhan itu telah bersiap para cantrik dan para pengikut Kiai Banyu Bening.
Nyai Wiji Sari mengerutkan dahinya. Sementara itu, kakinya melangkah semakin panjang. Ada dua dorongan yang bertentangan didalam diri Nyai Wiji Sari. Ia memang ingin lebih cepat sampai di makam anaknya, tetapi ada keseganan di hatinya untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening. Nyai Wiji Sari rasa-rasanya tidak akan berani menatap wajah laki-laki itu. Laki-laki yang pernah menjadi suaminya.
Namun di luar sadar, mereka telah menjadi semakin dekat dengan reruntuhan pintu gerbang utama. Api telah jauh menyusut Meskipun demikian. Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari masih dapat melihat dengan jelas, beberapa sosok tubuh yang terbujur lintang. Mereka adalah orang-orang yang datang bersama Ki Gunasraba untuk membakar pintu gerbang.“Kiai Banyu Bening telah membantai mereka,“ berkata Gunasraba dengan geram.
Tetapi langkah mereka terhenti. Mereka sadari, bahwa diatas panggungan itu beberapa orang cantrik telah mempersiapkan anak-panah dan lembing yang sudah siap mereka lontarkan. Dengan isyarat Kiai Narawangsa telah memanggil beberapa orang yang juga sudah mempersiapkan anak panah mereka.
“Pada saatnya, lindungi kami,“ terdengar suara Kiai Narawangsa yang berat. Tetapi pasukan itu memang berhenti.
“Kita memang harus bersabar.” berkata Gunasraba yang melihat api di pintu gerbang itu hampir padam.
Dalam pada itu, Kiai Narawangsapun segera memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Beberapa kelompok diantara mereka telah pergi mengelilingi padepokan itu. Mereka adalah kelompok-kelompok yang mendapat tugas untuk memasuki padepokan lewat pintu butulan.
Kiai Narawangsa telah berpesan kepada mereka, bahwa kelompok-kelompok itu harus bergerak setelah mereka mendengar isyarat yang akan dilontarkan lewat panah sendaren dari depan pintu gerbang utama. Dalam pada itu, dari atas panggungan para cantrik mengikuti terus gerak-gerik pasukan Kiai Narawangsa. Setiap saat ada.diantara para cantrik itu yang menghubungi dan memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan Ki Warana.
Dalam pada itu, Gunasraba telah membagi kedua orang saudara seperguruannya serta kedua orang anaknya untuk memimpin pasukan yang akan memasuki pintu gerbang butulan. Parang Landung dan Paron Waja, yang dianggapnya sudah memiliki kemampuan yang memadai, akan memasuki padepokan itu lewat pintu butulan sebelah kiri yang juga telah terbakar habis. Sementara kedua orang saudara seperguruannya, Krendhawa dan Mingkara, akan memasuki pintu butulan sebelah kanan. Mereka telah membawa masing-masing pasukan secukupnya.
Dalam pada itu, langit pun menjadi bertambah terang. Manggada dan Laksana yang juga berada di panggungan melihat dua orang anak muda yang bergerak ke kiri dengan beberapa kelompok orang.
“He, kau kenal kedua orang itu?” bertanya Laksana sambil menggamit Manggada.
Manggada mengerutkan dahinya. Dengan ragu ia berkata, ”Kedua anak muda itulah yang telah kita lihat dijalan bulak itu.”
“Ya... yang berpapasan dengan kita berdua. Mereka sama sekali tidak mau menepi, sehingga kita harus berjalan diatas tanggul parit.”
Manggada mengangguk-angguk. Sementara Laksana berkata selanjutnya, “Mereka akan berusaha memasuki pintu butulan sebelah kiri.”
“Kita akan menemui mereka,“ sahut Manggada. Atas ijin Ki Pandi dan Ki Lemah Teles, maka Manggada dan Laksana telah pergi ke pintu butulan sebelah kiri, yang juga sudah terbakar. Mereka segera bergabung dengan para cantrik yang bertugas di tempat itu.
“Aku akan berada diantara kalian “ berkata Manggada.
“Bagaimana dengan pintu gerbang utama?“ bertanya seorang cantrik yang diserahi pimpinan di belakang pintu butulan itu.
“Ki Lemah Teles ada disana. Diluar, dua orang anak muda yang memimpin para pengikut Kiai Narawangsa, nampaknya orang-orang berilmu. Mudah-mudahan bersama kalian, kami ber-dua dapat menahan mereka.”
Para cantrik itu mengangguk-angguk. Mereka memang menjadi mantap dengan kehadiran Manggada dan Laksana, karena para cantrik itu mengetahui, bahwa kedua orang anak muda itu telah memiliki ilmu yang tinggi.
Dalam pada itu, maka Ki Jagapranapun telah diminta untuk berada di butulan sebelah kanan, karena mereka melihat dua orang yang diduga kembar, berada diantara mereka yang akan memasuki padepokan lewat pintu gerbang sebelah kanan.
“Baik” jawab Ki Jagaprana “Aku akan melihat apakah orang kembar itu akan dapat mengejutkan anak-anak padepokan ini.”
“Tetapi berhati-hatilah...” pesan Ki Lemah Teles ”Jika keduanya menunjukkan kelebihannya, biarlah beberapa orang cantrik membantumu, sementara kau panggil salah seorang dari kami. Aku tidak mau kau mati. Kita masih mempunyai persoalan.”
Ki Pandi lah yang menyahut ”Jika kau masih ingin berperang tanding, kenapa tidak kau tantang saja Nyai Wiji Sari.”
“Kenapa tidak kau lakukan sendiri?” bentak Ki Lemah Teles. Ki Pandi tertawa. Katanya ”Jika saja aku tidak bongkok dan tidak berpenampilan buruk.”
“Apakah kau tidak ingat bahwa umurmu sudah berada di senja hari? Seandainya kau tidak bongkok dan buruk, kaupun sudah menjadi pikun.”
Ki Pandi tertawa semakin keras. Orang-orang lain yang mendengarnya ikut tertawa pula.
“Sudahlah pergilah” bentak Ki Lemah Teles ”Orang kembar itu sudah sampai di muka pintu butulan.”
“Api masih sedikit menyala.” jawab Ki Jagaprana ”Mereka tentu akan menunggu bara api itu padam.”
“Lihat. Sebagian besar dari mereka memakai tlumpah.”
Ki Jagaprana mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Dengan tergesa-gesa iapun melangkah menuju ke butulan sebelah kanan. Sebagaimana Manggada dan Laksana, maka Ki Jagaprana pun disambut dengan gembira oleh para cantrik yang bertugas di pintu butulan sebelah kanan yang sudah hampir menjadi abu. Bahkan api pun mulai menjadi padam, meskipun asap masih mengepul.
Diatas panggungan Ki Jagaprana melihat para cantrik siap dengan busur dan anak panah serta lembing-lembing bambu. Tetapi Ki Jagaprana pun kemudian telah memberitahukan beberapa orang cantrik yang bersenjata anak panah untuk bersiap menyambut para pengikut Kiai Narawangsa demikian mereka memasuki pintu butulan yang sudah terbuka itu,
“Kalian harus melumpuhkan lapisan pertama dari orang-orang yang memasuki pintu yang sudah menjadi abu itu. Jika mereka membawa perisai, maka bidiklah kakinya. Jika mungkin lututnya. Jika mereka tidak membawa perisai, maka sasaran kalian adalah dada mereka.”
Demikianlah, maka beberapa orang yang bersenjata busur dan anak panah pun telah bersiap. Mereka telah memasang anak-panahnya pada busurnya. Dilambungnya tergantung bumbung yang berisi anak-panah pula.
Beberapa saat mereka menunggu. Para cantrik yang ada didalam Beberapa saat mereka menunggu. Para cantrik yang ada didalam dinding padepokan itu rasa-rasanya tidak sabar lagi. Terutama mereka yang sudah mengetrapkan anak-panah pada busurnya dan bahkan tali busur itu sudah mulai menegang.
Di depan pintu gerbang padepokan yang sudah terbakar. Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari bersama pasukan induknya telah berhenti. Mereka memang harus menunggu api di gerbang itu agar padam sama sekali. Tetapi sisa-sisa api dan bara tidak akan dapat menahan mereka, karena orang-orang yang sudah siap memasuki padepokan itu mempergunakan alas kaki yang mereka buat dari kulit kayu.
Sementara itu, para penghuni padepokan itupun sudah siap pula untuk menahan serangan yang sebentar lagi akan melanda padepokan itu, Ki Pandi, Ki Ajar Pangukan dan Ki Sambi Pitu telah siap bersama para cantrik dibelakang pintu gerbang yang terbakar. Sementara Ki Lemah Teles dan Ki Warana masih berada di panggungan di sebelah pintu gerbang yang sudah terbakar itu.
“He, Kiai Banyu Bening.” berteriak Kiai Narawangsa ”aku masih memberi kesempatan untuk menyerah. Meskipun kami yakin akan dapat menghancurkan seluruh padepokan ini, bukan hanya pintu gerbanya saja, tetapi kami masih mempunyai belas kasihan. Karena itu, sebaiknya kau menyerah saja.”
Ki Lemah Teles yang berada dipanggungan memandang pasukan yang sudah siap itu dengan jantung yang berdebar-debar. Tetapi Ki Lemah Teles sudah bertekad untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada.
Kawan-kawannya telah menyetujuinya pula. Jika pengakuan itu dapat mencegah pertempuran, maka tidak perlu jatuh korban dari kedua belah pihak, meskipun hal itu sudah terjadi atas sekelompok orang yang telah membakar pintu gerbang, kecuali mereka yang telah menyerah.
“He. Kiai Banyu Bening!” teriak Kiai Narawangsa pula ”jawab pernyataanku ini. Kesempatan untuk menyerah.”
Ki Lemah Teles yang ada diatas panggungan itupun menyahut, ”Kiai Narawangsa, apakah kau tidak dapat melihat kami yang berada diatas panggungan. Cahaya matahari telah nampak di langit. Kami yang ada di panggungan sudah dapat melihat wajah kalian seorang demi seorang.”
Kiai Narawangsa termangu-mangu sejenak. Suara itu bukan suara Kiai Banyu Bening. Meskipun sudah lama ia tidak mendengar suara Banyu Bening, tetapi Kiai Narawangsa masih akan dapat mengenali suara itu. Ketika ia berpaling kepada Nyai Wiji Sari, maka Kiai Narawangsa itupun melihat kening Nyai Wiji Sari berkerut.
“Siapa kau?” tiba-tiba saja suara Nyai Wiji Sari melengking tinggi.
Kiai Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, ”Aku Ki Lemah Teles yang menunggui padepokan ini bersama Ki Warana.”
“Kami ingin berbicara dengan Kiai Banyu Bening.” teriak Kiai Narawangsa kemudian ”Kami tidak akan berbicara dengan orang lain.”
Kiai Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun iapun kemudian berteriak pula, ”Kiai Narawangsa. Ketahuilah, bahwa padepokan ini bukan lagi padepokan yang dipimpin oleh Kiai Banyu Bening. Sekarang akulah yang memimpin padepokan ini setelah padepokan ini ditinggalkan oleh Kiai Banyu Bening beberapa saat yang lalu.”
Jawaban itu sangat mengejutkan. Hampir diluar sadar Nyai Wiji Sari berteriak nyaring, ”Bohong. Kalian tidak usah menyembunyikan Kiai Banyu Bening. Kami datang untuk membuat perhitungan dengan orang itu.”
“Kami berkata sebenarnya Nyai. Kiai Banyu Bening sudah tidak ada. Sesuatu telah terjadi di padepokan ini. Bencana.”
“Jangan melingkar-lingkar.” sahut Kiai Narawangsa. ”Apakah Kiai Banyu Bening sekarang sudah menjadi seorang pengecut, sehingga tidak berani lagi menghadapi kami.”
“Tidak. Kiai Banyu Bening memang bukan pengecut. Itulah sebabnya maka kalian tidak lagi dapat menjumpai Kiai Banyu Bening sekarang.”
Di belakang pintu gerbang yang sudah menjadi abu, Ki Ajar Pangukan menjadi berdebar-debar. Ia pernah menerima utusan Kiai Narawangsa dan mengaku sebagai Kiai Banyu Bening.
“Apa yang sebenarnya telah terjadi disini?” bertanya Nyai Wiji Sari ”Penipuan? Kepura-puraan, atau sebuah permainan yang licik?”
“Tidak ada permainan yang licik. Tetapi ketahuilah, bahwa Kiai Banyu Bening memang sudah tidak ada dalam arti yang sebenarnya. Kiai Banyu Bening telah gugur saat ia mempertahankan padepokan ini.”
“Bohong!” teriak Nyai Wiji Sari dengan serta-merta. Betapa ia dan Kiai Banyu Bening bermusuhan karena kehadiran Kiai Narawangsa, tetapi berita kematian Kiai Banyu Bening sangat mengejutkannya.
“Kami tidak berbohong Nyai.” jawab Kiai Lemah Teles ”Kami dapat menceriterakan urut-urutan peristiwanya.”
“Siapa yang telah membunuh Kiai Banyu Bening?” bertanya Nyai Wiji Sari dengan suara bergetar.
“Panembahan Lebdagati,” jawab Ki Lemah Teles.
“Lebdagati. Jadi iblis itukah yang telah membunuh Kiai Banyu Bening?”
“Ya. Panembahan Lembadagi datang ke padepokan ini dan merebutnya untuk beberapa hari, sebelum kami datang membebaskannya,” sahut Ki Lemah Teles “Kami dapat mengusir Panembahan Lebdagati. Tetapi kami tidak dapat menangkapnya, apalagi membunuhnya.”
Jantung Nyai Wiji Sari terasa berdegup semakin cepat. Darahnya seakan-akan bergejolak didalam dadanya. Rasa-rasanya ia tidak rela mendengar berita kematian Kiai Banyu Bening. Betapa ia terpisah dari orang itu, namun Kiai Banyu Bening pernah menjadi suaminya. Ketika ia mula-mula mengenal sentuhan tangan laki-laki, orang itu adalah Kiai Banyu Bening.
Dalam pada itu, Kiai Narawangsalah yang berteriak, ”Apakah kau justru pengikut Panembahan Lebdagati itu?”
“Tidak. Kami bukan pengikut Panembahan Lebdagati. Kami justru telah bertempur melawannya dan mengusirnya dari padepokan ini.”
Sejenak Kiai Narawangsa menjadi termangu-mangu. Ia mencoba memandang wajah-wajah orang yang berada dipanggungan. Sebenarnyalah bahwa tidak ada orang yang dapat diduganya Kiai Banyu Bening. Tetapi Kiai Banyu Bening memang dapat saja bersembunyi atau melarikan diri sebelumnya. Namun Kiai Banyu Bening memang bukan seorang pengecut yang dapat berbuat seperti itu.
Dalam pada itu, Ki Lemah Teles pun berkata, ”Kiai Narawangsa, apakah sebenarnya yang kalian kehendaki dari Kiai Banyu Bening? Jika kami dapat memenuhinya, maka kami akan mencoba memenuhinya tanpa harus mengorbankan banyak orang.”
“Ki Lemah Teles.” suara Nyai Wiji Sari dengan nada tinggi seakan-akan menggetarkan dinding-dinding padepokan dan bahkan panggungan di sebelah pintu gerbang yang terbakar itu. Gejolak perasaannya benar-benar telah mengguncang dadanya, sehingga getar suara yang dilontarkan bagaikan mengandung tenaga yang sangat besar.
”Apapun yang kau katakan tentang Kiai Banyu Bening, namun kami datang dengan niat yang tidak berubah. Kami menghendaki padepokan ini. Jika benar kau berniat menghindari penumpahan darah, maka tinggalkan padepokan ini. Tidak ada yang boleh kau bawa selain pakaian yang melekat ditubuh kalian. Aku akan tinggal di padepokan ini menunggui anakku yang telah dibawa ke padepokan ini oleh Kiai Banyu Bening.”
Ki Lemah Teles termangu-mangu sebentar. Namun kemudian iapuan bertanya, ”Jadi itukah niat Nyai datang kemari? Nyai akan mengambil kembali anak Nyai? Juga anak Kiai Banyu Bening? Bagaimana mungkin Nyai datang untuk menemui seorang suami dengan membawa kekuatan yang demikian besarnya? Kecuali jika Nyai akan mengambil kembali suami Nyai yang berada ditangan orang lain.”
“Cukup!” teriak Nyai Wiji Sari. Suaranya semakin lantang dan udara pun bergetar semakin keras. Bahkan getar suara perempuan itu telah mulai menyentuh isi dada ”Jadi begitukah caramu mencari penyelesaian tanpa mengorbankan nyawa?”
“Nyai...“ berkata Ki Lemah Teles kemudian ”Jika Nyai ingin mengambil anak Nyai itu, terserah kepada Nyai. Kami tidak akan menghalangi. Ambillah, karena itu memang anak Nyai. Tetapi jangan mengambil padepokan ini. Kami sudah merebutnya dari tangan Panembahan Lebdagati dengan menitikkan keringat dan darah. Bagaimana mungkin kami akan melepaskannya begitu saja.”
“Aku tidak peduli...” sahut Kiai Narawangsa ”Kami akan memberi waktu secukupnya jika kalian memang akan pergi. Kami tidak akan mengganggu kalian yang meninggalkan padepokan ini. Tetapi jika ada diantara kalian yang memilih bergabung dengan kami, kami tidak berkeberatan. Tetapi kalian harus bersedia mematuhi segala paugeran didalam lingkungan kami.”
“Kiai...” jawab Ki Lemah Teles “Kami akan mempertahankan padepokan ini, apapun yang terjadi. Jika kalian memaksakan kehendak kalian, maka kami justru akan menutup kesempatan Nyai Wiji Sari untuk mengambil anaknya. Biarlah anak itu kesepian disini tanpa ayah dan ibunya.”
“Tidak!” teriak Nyai Wiji Sari ”Aku akan menunggui anakku disini.”
“Itu tidak mungkin, Nyai. Karena itu, maka terserah kepada Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari. Apakah kita harus bertempur atau tidak. Seandainya kita harus bertempur, kami pun sudah siap. Para cantrik dari padepokan ini masih menyandang kebanggaan setelah mereka berhasil mengusir Panembahan Lebdagati. Karena itu, maka dengan darah yang masih panas, kami akan menghadapi kalian. Tetapi jika kalian berniat mengambil anak itu dengan cara yang baik, kami tidak akan berkeberatan. Kami akan memberi kesempatan kepada kalian sebaik-baiknya.”
“Cukup!” teriak Kiai Narawangsa ”Kami akan mengusir kalian dengan kekerasan.”
Ki Lemah Teles tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, maka iapun berkata, ”Jika demikian, maka kita akan bertempur. Tetapi dengan demikian maka kalian tidak akan pernah dapat mengambil anak itu lagi dari padepokan ini.”
“Jangan sentuh anak itu.” teriak Nyai Wiji Sari ”Jika kalian melakukannya juga, maka nasib padepokan ini akan menjadi sangat buruk.”
“Aku tidak akan memeras dengan taruhan anakmu itu Nyai, meskipun sebenarnya anakmu itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Kami akan mempertahankan padepokan ini dengan sikap yang wajar.”
“Diam kau,“ bentak Nyai Wiji Sari ”Kau anggap anakku itu sudah tidak berarti apa-apa? Aku rindukan anakku siang dan malam. Aku tidak sampai hati melepaskan anakku dalam kesepian, kedinginan dan kepanasan karena ayahnya tidak memperdulikannya.”
“Ayahnya lebih peduli kepada anak itu daripada kau Nyai...” tiba-tiba Ki Warana menyahut “Aku melayani Kiai Banyu Bening setiap hari jika ia berada disisi anaknya. Sampai akhir hayatnya ia sama sekali tidak pernah berpaling kepada seorang perempuan yang akan dapat menyakiti hati anaknya itu. Tetapi kau, apa yang kau lakukan? Kau tinggalkan anakmu didalam api, sementara kau lari dengan seorang laki-laki saat anakmu masih bayi.”
“Cukup, cukup. Diam kau iblis!” teriak Nyai Wiji Sari dengan suara yang melengking-lengking.
“Kenapa aku harus diam? Kau khianati kesetiaan seorang suami. Kau nodai kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan sekarang, ketika yang tinggal hanya tulang belulang, kau datang untuk mengambilnya. Semua itu omong kosong. Kau yang memanfaatkan anakmu yang telah kau tinggalkan didalam api yang menyala itu untuk menantang Kiai Banyu Bening dan sekaligus berusaha merebut padepokannya.”
“Kau gila. Kau gila!” teriak Nyai Wiji Sari semakin keras.
“Aku adalah orang terdekat dengan Kiai Banyu Bening. Aku melihat bagaimana Kiai Banyu Bening menjadi gila karena tangis anaknya yang ditelan api, sehingga kegilaannya itu telah mewarnai kepercayaannya. Ia ingin seratus orang bayi mau sebagaimana anaknya, menangis didalam api yang menyala.”
“Tidak. Kau bohong!” Kiai Narawangsa lah yang menyahut Banyu Bening mendengar tangis anaknya bagaikan kidung yang mengalun di atas mega di langit biru. Ketika ia merindukan suara kidung itu lagi, maka ia telah memerintahkan untuk membakar seratus orang bayi demi kepuasan batinnya.”
Tetapi Ki Warana menjawab, ”Kau benci akan kesetiaan Kiai Banyu Bening, karena kau telah mengambil isterinya dengan cara yang tidak beradab.”
“Cukup...” teriak Kiai Narawangsa. Tiba-tiba saja Kiai Narawangsa itu mengangkat tangannya sambil berteriak ”Lontarkan anak panah sendaren. Kita koyak mulut-mulut yang memfitnah itu...”
Kiai Narawangsa yang telah mendapat laporan Gunasraba bahwa segala sesuatunya sudah siap, telah memberikan isyarat, bahwa mereka akan segera menyerang padepokan itu.
“Besok sehari kita mempersiapkan segala-galanya. Besok lusa, di dini hari, kita akan mulai membakar pintu gerbang. Menurut perhitungan, saat matahari naik, pintu gerbang dan pintu-pintu butulan tentu sudah menjadi abu.”
Perintah itu pun segera menjalar ke setiap telinga. Mereka yang sudah merasa jemu berkeliaran di hutan itu justru menjadi gembira. Saat-saat berburu binatang sudah berakhir. Mereka kemudian akan berburu lawan di padepokan Kiai Banyu Bening.
“Kita sudah terlalu lama tidak membasahi senjata kita,” berkata seorang yang berkepala botak ”mudah-mudahan orang-orang padepokan itu tanggap untuk bermain bersama.”
“Cantrik-cantrik padepokan pada umumnya juga memiliki kemampuan olah kanuragan.”
“Justru itulah yang rnenarik,“ jawab orang botak itu. Keputusan Kiai Narawangsa itu sesaat membuat wajah Nyai Wiji Sari menjadi cerah. Pertempuran akan membuatnya lupa pada kegelisahannya. Perang tidak akan memberinya kesempatan merenungi dirinya sendiri.
Tetapi malam-malam menjelang gerakan yang dilakukan oleh Kiai Narawangsa itu telah dilihat oleh Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi. Dengan sadar, bahwa diantara orang-orang yang berada di hutan itu terdapat orang-orang berilmu tinggi, Ki Ajar Pangukan, Ki Pandi berusaha mengamati kesibukan mereka.
Pada malam menjelang serangan yang akan dilakukan itu, Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi masih belum mengetahui, cara apakah yang akan dipergunakan untuk menghancurkan pintu gerbang.
Kiai Narawangsa dan Gunasraba cukup berhati-hati. Mereka mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan mereka pergunakan untuk membakar pintu gerbang itu ditengah-tengah lingkungan perkemahan mereka, sehingga Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi tidak dapat melihatnya.
Namun yang mereka ketahui, bahwa serangan itu akan berlangsung sejak dini hari. Karena itu, maka kedua orang itupun segera kembali ke padepokan untuk memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan Ki Warana.
Akhirnya saat yang mendebarkan itupun datang. Hari terakhir yang disediakan untuk mempersiapkan segala-galanya telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para pengikut Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari. Sehingga dengan demikian, maka segala persiapan tidak ada lagi yang tercecer.
Di malam terakhir itu, sebagian dari para pengikut sempat beristirahat sebaik-baiknya. Mereka sempat tidur nyenyak dan bahkan mendekur keras. Hanya beberapa orang yang bertugas sajalah yang sibuk mempersiapkan segala-galanya.
Namun demikian, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari berusaha untuk dapat memberi kesempatan kepada orang-orangnya untuk bergantian beristirahat. Namun lewat tengah malam, maka semua orang telah dibangunkan. Mereka harus mulai mempersiapkan diri sebaik-baiknya Mereka harus mengamati senjata mereka masing-masing, agar senjata mereka tidak mengecewakan jika mereka sudah berada di medan pertempuran.
“Semua orang harus bersiap untuk melindungi diri sendiri dari hujan anak panah,“ berkata Kiai Narawangsa “Yang tidak berperisai supaya bersiap sebaik-baiknya agar tidak mati sebelum memasuki pintu gerbang padepokan.”
Demikianlah, setelah segala sesuatunya bersiap, maka sebuah iring-iringan yang cukup besar telah mulai bergerak menuju ke padepokan. Mereka juga sudah makan sekenyang-kenyangnya agar mereka tidak kehabisan tenaga disaat-saat mereka bertempur nanti di padepokan. Sementara itu. orang-orang yang ditugaskan khusus telah menyediakan makanan pula yang dapat dimakan kapan saja menurut kebutuhan. Diantara iring-iringan itu terdapat pula beberapa ekor kuda beban yang mengangkut bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk membakar pintu padepokan.
Pada saat yang demikian Gunasraba telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bersama beberapa orang yang telah terlatih dan berpengalaman, maka Gunasraba duduk diatas punggung kuda masing-masing. Beberapa orang diantaranya memegangi kendali kuda-kuda yang menjadi kuda beban.
Pada saat yang ditentukan, maka beberapa orang berkuda itupun dengan cepat telah berpacu menuju ke pintu gerbang utama dan yang lain ke pintu butulan sebagaimana yang pernah mereka amati sebelumnya.
Semuanya berjalan dengan cepat. Para petugas yang berjaga-jaga diatas panggungan melihat beberapa ekor kuda muncul dari kegelapan. Kuda-kuda itu berlari kencang menuju ke padepokan. Bahkan ada diantaranya kuda-kuda yang tidak berpenumpang.
Mula-mula para petugas itu mengira bahwa orang-orang yang datang berkuda itu, sebagaimana pernah mereka lakukan, hanya akan mengamati keadaan. Tetapi kuda-kuda itu berlari langsung mendekati pintu gerbang utama. Yang lain memencar menuju ke pintu-pintu gerbang butulan.
Para petugas yang sedang berjaga-jaga itu terlambat mengambil sikap. Ketika beberapa orang menyadari keadaan itu, mereka berusaha untuk mencegahnya dengan anak panah. Tetapi para petugas itu memang terlambat memberikan tanggapan terhadap langkah-langkah yang tidak terduga itu.
Orang-orang berkuda itupun segera telah berada di pintu-pintu gerbang. Anak panah yang diluncurkan dari panggungan di belakang dinding memang agak sulit untuk mencapai orang-orang yang berdiri melekat pintu gerbang yang dialasnya terdapat atap ijuk.
Karena itu, maka dua orang diantara mereka pun segera berlari-lari turun untuk memberikan laporan kepada Kiai Lemah Teles yang berada di pendapa bersama Ki Warana.
“Kita benar-benar sudah mulai.” berkata Ki Lemah Teles.
“Aku akan melihat apa yang terjadi, Ki Lemah Teles,“ berkata Ki Warana.
“Aku juga akan pergi. Perintahkan memberitahukan kepada orang-orang yang malas itu.”
Ki Warana dan Ki Lemah Teles pun segera berlari-lari ke panggungan, sementara itu, Ki Warana telah memerintahkan seorang cantrik untuk memberitahukan kepada orang-orang tua yang berilmu tinggi yang sedang berada di belakang.
“Bongkok buruk dan Ki Ajar Pangukan tidak mengigau dengan ceriteranya tentang serangan yang akan dilakukan menjelang fajar hari ini.” berkata Ki Lemah Teles sambil berlari-lari ke panggungan.
Demikian Ki Lemah Teles dan Ki Warana naik ke panggungan disisi kanan pintu gerbang, maka iapun segera menyadari, apa yang akan terjadi. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi pengalaman dan pengetahuan Ki Lemah Teles yang luas segera mengetahui, bahwa orang-orang itu akan membakar pintu gerbang.
Sebenarnyalah Gunasraba telah meletakkan beberapa onggok serat kering di bawah pintu gerbang. Serat kering yang sudah berbaur dengan serbuk biji jarak. Kemudian untuk meyakinkan bahwa api akan berkobar, dituang pula dua bumbung minyak kelapa. Kemudian beberapa kampil biji jarak ditaburkan pula diatasnya. Beberapa saat kemudian, maka Gunasraba pun segera mempersiapkan api dengan batu titikan dan dimik-dimik belerang.
Demikian matangnya persiapan yang dilakukan, sehingga segalanya itu terjadi demikian cepatnya. Gunasraba tidak mempergunakan kayu-kayu kering untuk mengobarkan api, karena serat yang disediakan sudah cukup banyak, sehingga Gunasraba itu yakin, bahwa api akan segera menelan pintu gerbang induk itu.
Sebenarnyalah serat-serat yang kering itu dengan cepat terbakar. Serbuk biji jarak yang mengandung minyak itupun cepat membuat api semakin besar. Demikian pula minyak kelapa yang dituang serta beberapa kampil biji jarak. Untuk beberapa saat lamanya, Gunasraba memang masih harus melindungi apinya yang sedang membesar.
Dalam pada itu, maka didalam dinding padepokan telah terdengar isyarat untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Suara kentongan-kentongan kecil telah melontarkan perintah kepada setiap orang yang ada didalam dinding padepokan.
Gunasraba yang mendengar suara kentongan itu sempat mengumpat. Ternyata orang-orang padepokan itu tidak menjadi gugup dan bingung. Suara kentongan-kentongan kecil, itu tidak membayangkan kegelisahan. Tiga atau ampat kentongan yang mengisyaratkan perintah itu memperdengarkan iramanya yang mapan.
Orang-orang padepokan itu memang tidak menjadi bingung. Sebelumnya mereka sudah mendapat perintah untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Tetapi yang terjadi memang lebih cepat dari yang mereka duga. Mereka memperhitungkan bahwa serangan itu akan datang bersamaan dengan terbitnya matahari. Tetapi ternyata di dini hari kentongan itu sudah harus memberikan isyarat agar mereka bersiap.
Ternyata kentongan itu berbunyi di saat mereka sedang makan. Karena itu, maka mereka pun segera menelan nasi yang masih belum sempat mereka makan. Sedikit terhambat di kerongkongan, sehingga mereka harus minum lebih banyak.
Beberapa saat kemudian para cantrik itupun berlari-larian naik ke panggungan. Sementara yang lain, bersiap-siap ditempat yang sudah ditentukan bagi setiap kelompok. Tetapi terdengar perintah yang lain dari beberapa orang yang berada di belakang pintu gerbang. ”Air. Air.”
Para cantrik yang berada disekitar pintu gerbang utama dan pintu gerbang mereka. Karena itu, maka mereka pun segera berlari-lari mencari air dengan bumbung-bumbung panjang yang sering dipergunakan untuk mengusung air mengisi gentong dan tempayan didapur, atau dengan kelenting. Tetapi bumbung-bumbung yang tersedia tidak cukup banyak untuk mengatasi api yang menyala semakin besar.
Pintu gerbang utama dan butulan yang terbuat dari kayu itu sudah mulai terbakar. Bahkan gawang pintunya juga sudah mulai menyala. Sementara itu, ijuk pada atap pintu gerbang itupun akan sangat mudah terbakar pula.
Para pemimpin padepokan itu memang tidak mengira bahwa Kiai Narawangsa akan mempergunakan cara yang tidak banyak dipergunakan orang untuk memecahkan pintu gerbang utama dari sebuah sasaran. Kiai Narawangsa tidak memecahkan pintu gerbang dengan sebuah balok kayu yang panjang dan besar yang diusung oleh banyak orang. Tidak pula mempergunakan tali-tali yang kuat yang ditarik oleh beberapa ekor kuda. Tetapi Kiai Narawangsa telah mempergunakan api. Bukan untuk memecahkan pintu, tetapi membakar pintu itu sehingga menjadi abu.
Ternyata air memang tidak banyak menolong. Apalagi air itu tidak cukup banyak dibanding dengan nyala api yang membesar. Tidak cukup banyak bumbung-bumbung besar yang dibuat dari bambu petung yang dapat dipergunakan untuk mengangkut air.
Karena itu, maka Ki Lemah Teles akhirnya memerintahkan para cantrik untuk menghentikan usaha mereka memadamkan api. Tetapi para cantrik harus segera bersiap dalam kesiagaan kedua. Mereka harus bersiap untuk bertahan di belakang pintu gerbang yang sudah dapat dipastikan akan terbuka.
Ki Pandi dan Ki Ajar Pangukan yang berdiri di panggungan sebelah kiri itupun menyaksikan api yang menyala itu dengan termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja Ki Pandi itu berkata kepada seorang cantrik. “Siapkan tali, he, kalian punya tampar ijuk?”
“Ada Kiai!“ jawab seseorang cantrik “Sisa tampar ijuk yang kemarin dipergunakan untuk memperbaiki tali-tali ijuk panggungan ini?”
“Masih ada berapa gulung?”
“Masih ada beberapa gulung Kiai.”
Ki Pandi pun kemudian berkata kepada Ki A jar Pangukan. ”Ki Ajar, marilah kita bermain-main dengan orang-orang yang sedang membakar pintu gerbang itu.
Ki Ajar Pangukan pun segera tanggap. Karena itu, maka iapun segera menyahut. ”Marilah. Ajak kedua cucumu itu.”
Manggada dan Laksana yang ada di panggungan itu pula segera menyahut. “Marilah, Ki Ajar. Kami akan ikut bersama Ki Ajar.”
Demikianlah, maka dengan cepat mereka telah mengurai tampar ijuk itu dan menjulurkannya keluar dinding. Disisi lain, diatas panggungan Ki Lemah Teles melihat Ki Pandi menjulurkan tali ijuk. Tidak hanya sehelai, tetapi beberapa helai.
Ki Lemah Teles segera mengetahui apa yang akan dilakukan. Sementara itu Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana juga sudah naik ke panggungan itu pula. Tanpa menunggu, maka Ki Jagaprana dan Ki Sambi Pitu pun segera bersiap. Karena di panggungan itu tidak ada tali ijuk yang dapat mereka pergunakan, maka mereka tidak mempergunakannya. Orang-orang berilmu tinggi itu kemudian meloncat begitu saja dari atas dinding padepokan seperti seekor kucing. Sementara itu, Ki Pandi dan Ki Ajar Pangukan telah turun dengan mempergunakan tali ijuk.
“Kenapa orang-orang itu mempersulit diri dengan tali-tali ijuk?“ desis Ki Sambi Pitu.
“Sebenarnya tali-tali itu tidak untuk mereka.” jawab Ki Jagaprana.
Sebenarnyalah selain kedua orang tua berilmu tinggi itu, Manggada dan Laksana pun telah turun pula menyusuri tali ijuk itu diikuti oleh beberapa orang cantrik.
Gunasraba yang berada di depan pintu menunggui api yang menyala semakin besar itupun terkejut. Ia tidak mengira bahwa ada beberapa orang yang turun dari atas dinding dan berlari-lari mendekatinya.
“Cegah mereka!“ teriak Gunasraba.
Beberapa orang yang datang bersamanya segera bersiap untuk menyongsong orang-orang yang berlari-lari itu. Namun Gunasraba sendiri tidak ikut bersama mereka. Dengan tangkasnya Gunasraba itu meloncat keatas punggung kudanya dan dengan cepat melarikan diri kedalam gelap.
Para pengikutnya memang termangu sejenak. Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan. Dengan geram Manggada dan Laksana telah berloncatan mendekat.
Tetapi Ki Pandi tidak segera menyerang mereka. Dengan lantang iapun berkata ”Menyerahlah. Kalian tidak mempunyai pilihan lain.”
Orang-orang yang datang bersama Gunasraba itu tidak menghiraukan. Jumlah orang yang turun dengan tali itu tidak banyak. Karena itu, maka mereka merasa mampu untuk bertahan sambil menunggu kawan-kawan mereka yang akan segera datang untuk menolong.
Mereka meyakini bahwa Ki Gunasraba sedang menghubungi Kiai Narawangsa untuk mendapatkan bantuan. Karena itu, justru orang-orang itulah yang telah mendahului menyerang mereka yang turun dari dinding padapokan.
Beberapa orang cantrik pun segera terlibat dalam pertempuran. Manggada dan Laksana juga segera terjun langsung melawan orang-orang yang telah membakar pintu gerbang itu.
Namun bagaimana pun juga api yang membakar pintu gerbang itu tidak dapat dipadamkan. Pintu gerbang itu memang terbakar. Yang dilakukan oleh para cantrik kemudian adalah mencegah panggungan disebelah menyebelah pintu gerbang itu ikut terbakar.
Dalam pada itu pertempuran yang terjadi di depan pintu gerbang itu tidak berlangsung lama. Ketika orang-orang tua berilmu tinggi itu melibatkan diri, maka dengan cepat orang-orang yang membakar pintu gerbang itu telah dikuasai.
Bahkan ketika.orang-orang yang membakar pintu-pintu butulan ikut bergabung dengan kawan-kawan mereka, ternyata mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi.
Dalam waktu yang singkat beberapa orang telah terkapar di depan pintu gerbang yang telah terbakar sedangkan yang lain telah menyerah. Para cantrik padepokan itu justru berhasil menguasai beberapa ekor kuda.
Tetapi mereka tidak tahu, bagaimana mereka akan membawa kuda-kuda itu masuk kedalam padepokan, karena pintu gerbang utama dan pintu-pintu butulan telah dibakar. Tetapi tiba-tiba saja seorang cantrik berteriak, “Masih ada satu pintu butulan yang tidak dibakar.”
Ki Pandi yang mendengar teriakan cantrik dari panggungan itu bertanya “Disisi sebelah mana?”
“Pintu butulan kecil yang menghadap ke Timur. Pintu yang hampir tidak pernah dipergunakan.”
Ki Pandi, orang-orang tua yang berilmu tinggi serta Manggada dan Laksana pun telah membawa beberapa ekor kuda yang tertinggal serta para tawanan mengelilingi dinding padepokan menuju ke pintu gerbang yang menghadap kesebelan Timur, yang karena tidak sering dipergunakan, maka telah ditumbuhi oleh batang ilalang dan pohon-pohon perdu.
Namun dalam pada itu, Gunasraba yang melarikan diri diatas punggung kudanya telah sampai ke induk pasukannya. Dengan nafas yang terangah-engah, ia telah melaporkan apa yang terjadi di pintu gerbang utama padepokan Kiai Banyu Bening.
“Orang-orang gila, yang ingin membunuh dirinya sendiri. Baiklah. Marilah kita mendekat. Bukankah sebentar lagi, pintu gerbang utama dan beberapa pintu butulan itu sudah akan menjadi abu?”
“Ya. Pada saat matahari terbit. Tetapi kita harus bersabar sedikit, agar kaki kita tidak menginjak bara yang masih panas.” Orang-orang yang pertama akan memasuki pintu gerbang sudah dipersiapkan. Bukankah mereka telah mengenakan tlumpah kulit kayu?”
“Aku memang sudah memberikan contoh, bagaimana membuat tlumpah kulit kayu untuk melindungi kaki mereka. Mudah-mudahan mereka telah mempersiapkannya.”
“Bukankah kita dapat melihat sekarang?” sahut Nyai Wiji Sari.
Gurasraba pun kemudian memerintahkan Parang Landung dan Paron Waja untuk melihat, apakah orang-orangnya mematuhi perintahnya membuat tlumpah-tlumpah kulit kayu untuk melindungi telapak kaki mereka dari bara yang masih panas. Sementara itu, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Saripun telah mempersiapkan segala-galanya. Sesaat lagi, mereka akan bergerak mendekati padepokan.
“Sayang, kita kehilangan beberapa ekor kuda.” desis Kiai Narawangsa.
“Tidak. Sebentar lagi, kita akan mendapatkannya kembali.” jawab Gunasraba.
Dalam pada itu Paning Landung dan Paron Waja pun telah melaporkan bahwa orang-orang mereka telah membuat tiumpah kulit kayu dengan tali kedebog yang sudah dikeringkan.
“Tidak ada masalah.” berkata Parung Landung “Mereka dapat mengabaikan panasnya bara yang tersisa. Meskipun ada yang membuat dari clumpring, tetapi cukup untuk menahan panasnya sisa-sisa gerbang yang sudah menjadi arang.”
“Tetapi clumpring itu sendiri akan terbakar,“ berkata Gunasraba.
“Bukankah kita tidak akan berdiri tegak diatas bara itu?“ sahut Paron Waja “Bukankah kita hanya akan berlari melintas?”
Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Tetapi Nyai Wiji Sari menyahut “Jangan merendahkan lawan. Mereka akan menahan kita diatas bara api pintu gerbang itu.”
“Kita dapat mengulur waktu sebentar Nyai. Bukankah kita dapat berbicara lebih dahulu dengan Banyu Bening? Ia akan berpikir ulang jika ia melihat kekuatan lata yang besar ini.”
“Aku tidak ingin berbicara dengan Banyu Bening. Aku hanya ingin anakku itu.”
Kiai Narawangsa tidak menjawab lagi. Namun kemudian iapun bertanya kepada Gunasraba, “Marilah. Apakah kita sudah bersiap sepenuhnya?”
“Sudah kakang. Kita sudah dapat bergerak sekarang. Mudah-mudahan kita masih sempat menolong orang-orang yang terjebak saat mereka membakar pintu gerbang.”
Demikianlah, maka Parung Landung dan Paron Wajapun segera memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju ke padepokan. Sementara itu langit telah menjadi merah. Mereka berharap ' bahwa saat matahari terbit, mereka sudah memasuki pintu-pintu gerbang padepokan yang mereka sangka masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening itu.
Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sarilah yang melangkah di paling depan. Kemudian Gunasraba dan dua orang saudara seperguruannya. Dua orang kakak beradik yang sebenarnya tidak kembar, tetapi wajah mereka demikian miripnya, sehingga banyak orang menyangka bahwa mereka adalah dua orang saudara kembar. Sedangkan sebenarnya umur mereka terpaut dua tahun. Krendhawa dan Mingkara.
Demikianlah, maka langkah kaki yang berderap di padang perdu itupun seakan-akan telah menggetarkan bumi. Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari yang berjalan dipaling depan nampak menjadi tegang. Telah berpuluh bahkan beratus kali keduanya turun ke medan pertempuran. Bukan saja saat-saat mereka merampok dan menyamun di bulak-bulak panjang.
Tetapi sudah berapa kali mereka terperosok ke dalam benturan kekuatan diantara mereka yang hidup dalam dunia yang kelam. Bertempur untuk memperebutkan pengaruh dan daerah jelajah, serta kadang-kadang tanpa sebab apa-apa.
Tetapi yang dihadapi oleh Nyai Wiji Sari saat ini adalah orang yang pernah tersangkut dalam perjalanan hidupnya. Bahkan seseorang yang telah memberinya seorang anak yang sekarang dimakamkan di belakang dinding padepokan itu. Anak itulah yang setiap saat seakan-akan memanggil-manggilnya. Mengulurkan tangannya, menggapainya sambil memanggil-manggilnya “Ibu, ibu, aku kedinginan, ibu.”
Nyai Wiji Sari menggeretak-kan giginya. Langkahnya menjadi semakin cepat. Bahkan rasa-rasanya Nyai Wiji Sari itu ingin meloncat langsung memasuki padepokan Kiai Banyu Bening. Tetapi di samping itu, ada semacam keseganan untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening sendiri.
Meskipun setiap kali Nyai Wiji Sari berusaha untuk mengingkarinya, tetapi di dasar hatinya, ia mengakui, betapa ia telah melakukan kesalahan sebagai seorang isteri, karena ia sudah membiarkan Narawangsa masuk ke dalam bilik tidurnya, justru saat ia menidurkan anaknya.
Petaka itu tidak dapat dihindarinya. Nyai Wiji Sari itu tertegun melihat api yang sudah menjadi semakin surut. Pintu gerbang padepokan itu telah runtuh. Tidak ada lagi yang menghalangi langkah mereka memasuki padepokan itu. Tetapi yang terbuka, yang tidak menjadi penghalang lagi, adalah pintu pada gerbang utama dan butulan. Di belakang reruntuhan itu telah bersiap para cantrik dan para pengikut Kiai Banyu Bening.
Nyai Wiji Sari mengerutkan dahinya. Sementara itu, kakinya melangkah semakin panjang. Ada dua dorongan yang bertentangan didalam diri Nyai Wiji Sari. Ia memang ingin lebih cepat sampai di makam anaknya, tetapi ada keseganan di hatinya untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening. Nyai Wiji Sari rasa-rasanya tidak akan berani menatap wajah laki-laki itu. Laki-laki yang pernah menjadi suaminya.
Namun di luar sadar, mereka telah menjadi semakin dekat dengan reruntuhan pintu gerbang utama. Api telah jauh menyusut Meskipun demikian. Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari masih dapat melihat dengan jelas, beberapa sosok tubuh yang terbujur lintang. Mereka adalah orang-orang yang datang bersama Ki Gunasraba untuk membakar pintu gerbang.“Kiai Banyu Bening telah membantai mereka,“ berkata Gunasraba dengan geram.
Tetapi langkah mereka terhenti. Mereka sadari, bahwa diatas panggungan itu beberapa orang cantrik telah mempersiapkan anak-panah dan lembing yang sudah siap mereka lontarkan. Dengan isyarat Kiai Narawangsa telah memanggil beberapa orang yang juga sudah mempersiapkan anak panah mereka.
“Pada saatnya, lindungi kami,“ terdengar suara Kiai Narawangsa yang berat. Tetapi pasukan itu memang berhenti.
“Kita memang harus bersabar.” berkata Gunasraba yang melihat api di pintu gerbang itu hampir padam.
Dalam pada itu, Kiai Narawangsapun segera memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Beberapa kelompok diantara mereka telah pergi mengelilingi padepokan itu. Mereka adalah kelompok-kelompok yang mendapat tugas untuk memasuki padepokan lewat pintu butulan.
Kiai Narawangsa telah berpesan kepada mereka, bahwa kelompok-kelompok itu harus bergerak setelah mereka mendengar isyarat yang akan dilontarkan lewat panah sendaren dari depan pintu gerbang utama. Dalam pada itu, dari atas panggungan para cantrik mengikuti terus gerak-gerik pasukan Kiai Narawangsa. Setiap saat ada.diantara para cantrik itu yang menghubungi dan memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan Ki Warana.
Dalam pada itu, Gunasraba telah membagi kedua orang saudara seperguruannya serta kedua orang anaknya untuk memimpin pasukan yang akan memasuki pintu gerbang butulan. Parang Landung dan Paron Waja, yang dianggapnya sudah memiliki kemampuan yang memadai, akan memasuki padepokan itu lewat pintu butulan sebelah kiri yang juga telah terbakar habis. Sementara kedua orang saudara seperguruannya, Krendhawa dan Mingkara, akan memasuki pintu butulan sebelah kanan. Mereka telah membawa masing-masing pasukan secukupnya.
Dalam pada itu, langit pun menjadi bertambah terang. Manggada dan Laksana yang juga berada di panggungan melihat dua orang anak muda yang bergerak ke kiri dengan beberapa kelompok orang.
“He, kau kenal kedua orang itu?” bertanya Laksana sambil menggamit Manggada.
Manggada mengerutkan dahinya. Dengan ragu ia berkata, ”Kedua anak muda itulah yang telah kita lihat dijalan bulak itu.”
“Ya... yang berpapasan dengan kita berdua. Mereka sama sekali tidak mau menepi, sehingga kita harus berjalan diatas tanggul parit.”
Manggada mengangguk-angguk. Sementara Laksana berkata selanjutnya, “Mereka akan berusaha memasuki pintu butulan sebelah kiri.”
“Kita akan menemui mereka,“ sahut Manggada. Atas ijin Ki Pandi dan Ki Lemah Teles, maka Manggada dan Laksana telah pergi ke pintu butulan sebelah kiri, yang juga sudah terbakar. Mereka segera bergabung dengan para cantrik yang bertugas di tempat itu.
“Aku akan berada diantara kalian “ berkata Manggada.
“Bagaimana dengan pintu gerbang utama?“ bertanya seorang cantrik yang diserahi pimpinan di belakang pintu butulan itu.
“Ki Lemah Teles ada disana. Diluar, dua orang anak muda yang memimpin para pengikut Kiai Narawangsa, nampaknya orang-orang berilmu. Mudah-mudahan bersama kalian, kami ber-dua dapat menahan mereka.”
Para cantrik itu mengangguk-angguk. Mereka memang menjadi mantap dengan kehadiran Manggada dan Laksana, karena para cantrik itu mengetahui, bahwa kedua orang anak muda itu telah memiliki ilmu yang tinggi.
Dalam pada itu, maka Ki Jagapranapun telah diminta untuk berada di butulan sebelah kanan, karena mereka melihat dua orang yang diduga kembar, berada diantara mereka yang akan memasuki padepokan lewat pintu gerbang sebelah kanan.
“Baik” jawab Ki Jagaprana “Aku akan melihat apakah orang kembar itu akan dapat mengejutkan anak-anak padepokan ini.”
“Tetapi berhati-hatilah...” pesan Ki Lemah Teles ”Jika keduanya menunjukkan kelebihannya, biarlah beberapa orang cantrik membantumu, sementara kau panggil salah seorang dari kami. Aku tidak mau kau mati. Kita masih mempunyai persoalan.”
Ki Pandi lah yang menyahut ”Jika kau masih ingin berperang tanding, kenapa tidak kau tantang saja Nyai Wiji Sari.”
“Kenapa tidak kau lakukan sendiri?” bentak Ki Lemah Teles. Ki Pandi tertawa. Katanya ”Jika saja aku tidak bongkok dan tidak berpenampilan buruk.”
“Apakah kau tidak ingat bahwa umurmu sudah berada di senja hari? Seandainya kau tidak bongkok dan buruk, kaupun sudah menjadi pikun.”
Ki Pandi tertawa semakin keras. Orang-orang lain yang mendengarnya ikut tertawa pula.
“Sudahlah pergilah” bentak Ki Lemah Teles ”Orang kembar itu sudah sampai di muka pintu butulan.”
“Api masih sedikit menyala.” jawab Ki Jagaprana ”Mereka tentu akan menunggu bara api itu padam.”
“Lihat. Sebagian besar dari mereka memakai tlumpah.”
Ki Jagaprana mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Dengan tergesa-gesa iapun melangkah menuju ke butulan sebelah kanan. Sebagaimana Manggada dan Laksana, maka Ki Jagaprana pun disambut dengan gembira oleh para cantrik yang bertugas di pintu butulan sebelah kanan yang sudah hampir menjadi abu. Bahkan api pun mulai menjadi padam, meskipun asap masih mengepul.
Diatas panggungan Ki Jagaprana melihat para cantrik siap dengan busur dan anak panah serta lembing-lembing bambu. Tetapi Ki Jagaprana pun kemudian telah memberitahukan beberapa orang cantrik yang bersenjata anak panah untuk bersiap menyambut para pengikut Kiai Narawangsa demikian mereka memasuki pintu butulan yang sudah terbuka itu,
“Kalian harus melumpuhkan lapisan pertama dari orang-orang yang memasuki pintu yang sudah menjadi abu itu. Jika mereka membawa perisai, maka bidiklah kakinya. Jika mungkin lututnya. Jika mereka tidak membawa perisai, maka sasaran kalian adalah dada mereka.”
Demikianlah, maka beberapa orang yang bersenjata busur dan anak panah pun telah bersiap. Mereka telah memasang anak-panahnya pada busurnya. Dilambungnya tergantung bumbung yang berisi anak-panah pula.
Beberapa saat mereka menunggu. Para cantrik yang ada didalam Beberapa saat mereka menunggu. Para cantrik yang ada didalam dinding padepokan itu rasa-rasanya tidak sabar lagi. Terutama mereka yang sudah mengetrapkan anak-panah pada busurnya dan bahkan tali busur itu sudah mulai menegang.
Di depan pintu gerbang padepokan yang sudah terbakar. Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari bersama pasukan induknya telah berhenti. Mereka memang harus menunggu api di gerbang itu agar padam sama sekali. Tetapi sisa-sisa api dan bara tidak akan dapat menahan mereka, karena orang-orang yang sudah siap memasuki padepokan itu mempergunakan alas kaki yang mereka buat dari kulit kayu.
Sementara itu, para penghuni padepokan itupun sudah siap pula untuk menahan serangan yang sebentar lagi akan melanda padepokan itu, Ki Pandi, Ki Ajar Pangukan dan Ki Sambi Pitu telah siap bersama para cantrik dibelakang pintu gerbang yang terbakar. Sementara Ki Lemah Teles dan Ki Warana masih berada di panggungan di sebelah pintu gerbang yang sudah terbakar itu.
“He, Kiai Banyu Bening.” berteriak Kiai Narawangsa ”aku masih memberi kesempatan untuk menyerah. Meskipun kami yakin akan dapat menghancurkan seluruh padepokan ini, bukan hanya pintu gerbanya saja, tetapi kami masih mempunyai belas kasihan. Karena itu, sebaiknya kau menyerah saja.”
Ki Lemah Teles yang berada dipanggungan memandang pasukan yang sudah siap itu dengan jantung yang berdebar-debar. Tetapi Ki Lemah Teles sudah bertekad untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada.
Kawan-kawannya telah menyetujuinya pula. Jika pengakuan itu dapat mencegah pertempuran, maka tidak perlu jatuh korban dari kedua belah pihak, meskipun hal itu sudah terjadi atas sekelompok orang yang telah membakar pintu gerbang, kecuali mereka yang telah menyerah.
“He. Kiai Banyu Bening!” teriak Kiai Narawangsa pula ”jawab pernyataanku ini. Kesempatan untuk menyerah.”
Ki Lemah Teles yang ada diatas panggungan itupun menyahut, ”Kiai Narawangsa, apakah kau tidak dapat melihat kami yang berada diatas panggungan. Cahaya matahari telah nampak di langit. Kami yang ada di panggungan sudah dapat melihat wajah kalian seorang demi seorang.”
Kiai Narawangsa termangu-mangu sejenak. Suara itu bukan suara Kiai Banyu Bening. Meskipun sudah lama ia tidak mendengar suara Banyu Bening, tetapi Kiai Narawangsa masih akan dapat mengenali suara itu. Ketika ia berpaling kepada Nyai Wiji Sari, maka Kiai Narawangsa itupun melihat kening Nyai Wiji Sari berkerut.
“Siapa kau?” tiba-tiba saja suara Nyai Wiji Sari melengking tinggi.
Kiai Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, ”Aku Ki Lemah Teles yang menunggui padepokan ini bersama Ki Warana.”
“Kami ingin berbicara dengan Kiai Banyu Bening.” teriak Kiai Narawangsa kemudian ”Kami tidak akan berbicara dengan orang lain.”
Kiai Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun iapun kemudian berteriak pula, ”Kiai Narawangsa. Ketahuilah, bahwa padepokan ini bukan lagi padepokan yang dipimpin oleh Kiai Banyu Bening. Sekarang akulah yang memimpin padepokan ini setelah padepokan ini ditinggalkan oleh Kiai Banyu Bening beberapa saat yang lalu.”
Jawaban itu sangat mengejutkan. Hampir diluar sadar Nyai Wiji Sari berteriak nyaring, ”Bohong. Kalian tidak usah menyembunyikan Kiai Banyu Bening. Kami datang untuk membuat perhitungan dengan orang itu.”
“Kami berkata sebenarnya Nyai. Kiai Banyu Bening sudah tidak ada. Sesuatu telah terjadi di padepokan ini. Bencana.”
“Jangan melingkar-lingkar.” sahut Kiai Narawangsa. ”Apakah Kiai Banyu Bening sekarang sudah menjadi seorang pengecut, sehingga tidak berani lagi menghadapi kami.”
“Tidak. Kiai Banyu Bening memang bukan pengecut. Itulah sebabnya maka kalian tidak lagi dapat menjumpai Kiai Banyu Bening sekarang.”
Di belakang pintu gerbang yang sudah menjadi abu, Ki Ajar Pangukan menjadi berdebar-debar. Ia pernah menerima utusan Kiai Narawangsa dan mengaku sebagai Kiai Banyu Bening.
“Apa yang sebenarnya telah terjadi disini?” bertanya Nyai Wiji Sari ”Penipuan? Kepura-puraan, atau sebuah permainan yang licik?”
“Tidak ada permainan yang licik. Tetapi ketahuilah, bahwa Kiai Banyu Bening memang sudah tidak ada dalam arti yang sebenarnya. Kiai Banyu Bening telah gugur saat ia mempertahankan padepokan ini.”
“Bohong!” teriak Nyai Wiji Sari dengan serta-merta. Betapa ia dan Kiai Banyu Bening bermusuhan karena kehadiran Kiai Narawangsa, tetapi berita kematian Kiai Banyu Bening sangat mengejutkannya.
“Kami tidak berbohong Nyai.” jawab Kiai Lemah Teles ”Kami dapat menceriterakan urut-urutan peristiwanya.”
“Siapa yang telah membunuh Kiai Banyu Bening?” bertanya Nyai Wiji Sari dengan suara bergetar.
“Panembahan Lebdagati,” jawab Ki Lemah Teles.
“Lebdagati. Jadi iblis itukah yang telah membunuh Kiai Banyu Bening?”
“Ya. Panembahan Lembadagi datang ke padepokan ini dan merebutnya untuk beberapa hari, sebelum kami datang membebaskannya,” sahut Ki Lemah Teles “Kami dapat mengusir Panembahan Lebdagati. Tetapi kami tidak dapat menangkapnya, apalagi membunuhnya.”
Jantung Nyai Wiji Sari terasa berdegup semakin cepat. Darahnya seakan-akan bergejolak didalam dadanya. Rasa-rasanya ia tidak rela mendengar berita kematian Kiai Banyu Bening. Betapa ia terpisah dari orang itu, namun Kiai Banyu Bening pernah menjadi suaminya. Ketika ia mula-mula mengenal sentuhan tangan laki-laki, orang itu adalah Kiai Banyu Bening.
Dalam pada itu, Kiai Narawangsalah yang berteriak, ”Apakah kau justru pengikut Panembahan Lebdagati itu?”
“Tidak. Kami bukan pengikut Panembahan Lebdagati. Kami justru telah bertempur melawannya dan mengusirnya dari padepokan ini.”
Sejenak Kiai Narawangsa menjadi termangu-mangu. Ia mencoba memandang wajah-wajah orang yang berada dipanggungan. Sebenarnyalah bahwa tidak ada orang yang dapat diduganya Kiai Banyu Bening. Tetapi Kiai Banyu Bening memang dapat saja bersembunyi atau melarikan diri sebelumnya. Namun Kiai Banyu Bening memang bukan seorang pengecut yang dapat berbuat seperti itu.
Dalam pada itu, Ki Lemah Teles pun berkata, ”Kiai Narawangsa, apakah sebenarnya yang kalian kehendaki dari Kiai Banyu Bening? Jika kami dapat memenuhinya, maka kami akan mencoba memenuhinya tanpa harus mengorbankan banyak orang.”
“Ki Lemah Teles.” suara Nyai Wiji Sari dengan nada tinggi seakan-akan menggetarkan dinding-dinding padepokan dan bahkan panggungan di sebelah pintu gerbang yang terbakar itu. Gejolak perasaannya benar-benar telah mengguncang dadanya, sehingga getar suara yang dilontarkan bagaikan mengandung tenaga yang sangat besar.
”Apapun yang kau katakan tentang Kiai Banyu Bening, namun kami datang dengan niat yang tidak berubah. Kami menghendaki padepokan ini. Jika benar kau berniat menghindari penumpahan darah, maka tinggalkan padepokan ini. Tidak ada yang boleh kau bawa selain pakaian yang melekat ditubuh kalian. Aku akan tinggal di padepokan ini menunggui anakku yang telah dibawa ke padepokan ini oleh Kiai Banyu Bening.”
Ki Lemah Teles termangu-mangu sebentar. Namun kemudian iapuan bertanya, ”Jadi itukah niat Nyai datang kemari? Nyai akan mengambil kembali anak Nyai? Juga anak Kiai Banyu Bening? Bagaimana mungkin Nyai datang untuk menemui seorang suami dengan membawa kekuatan yang demikian besarnya? Kecuali jika Nyai akan mengambil kembali suami Nyai yang berada ditangan orang lain.”
“Cukup!” teriak Nyai Wiji Sari. Suaranya semakin lantang dan udara pun bergetar semakin keras. Bahkan getar suara perempuan itu telah mulai menyentuh isi dada ”Jadi begitukah caramu mencari penyelesaian tanpa mengorbankan nyawa?”
“Nyai...“ berkata Ki Lemah Teles kemudian ”Jika Nyai ingin mengambil anak Nyai itu, terserah kepada Nyai. Kami tidak akan menghalangi. Ambillah, karena itu memang anak Nyai. Tetapi jangan mengambil padepokan ini. Kami sudah merebutnya dari tangan Panembahan Lebdagati dengan menitikkan keringat dan darah. Bagaimana mungkin kami akan melepaskannya begitu saja.”
“Aku tidak peduli...” sahut Kiai Narawangsa ”Kami akan memberi waktu secukupnya jika kalian memang akan pergi. Kami tidak akan mengganggu kalian yang meninggalkan padepokan ini. Tetapi jika ada diantara kalian yang memilih bergabung dengan kami, kami tidak berkeberatan. Tetapi kalian harus bersedia mematuhi segala paugeran didalam lingkungan kami.”
“Kiai...” jawab Ki Lemah Teles “Kami akan mempertahankan padepokan ini, apapun yang terjadi. Jika kalian memaksakan kehendak kalian, maka kami justru akan menutup kesempatan Nyai Wiji Sari untuk mengambil anaknya. Biarlah anak itu kesepian disini tanpa ayah dan ibunya.”
“Tidak!” teriak Nyai Wiji Sari ”Aku akan menunggui anakku disini.”
“Itu tidak mungkin, Nyai. Karena itu, maka terserah kepada Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari. Apakah kita harus bertempur atau tidak. Seandainya kita harus bertempur, kami pun sudah siap. Para cantrik dari padepokan ini masih menyandang kebanggaan setelah mereka berhasil mengusir Panembahan Lebdagati. Karena itu, maka dengan darah yang masih panas, kami akan menghadapi kalian. Tetapi jika kalian berniat mengambil anak itu dengan cara yang baik, kami tidak akan berkeberatan. Kami akan memberi kesempatan kepada kalian sebaik-baiknya.”
“Cukup!” teriak Kiai Narawangsa ”Kami akan mengusir kalian dengan kekerasan.”
Ki Lemah Teles tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, maka iapun berkata, ”Jika demikian, maka kita akan bertempur. Tetapi dengan demikian maka kalian tidak akan pernah dapat mengambil anak itu lagi dari padepokan ini.”
“Jangan sentuh anak itu.” teriak Nyai Wiji Sari ”Jika kalian melakukannya juga, maka nasib padepokan ini akan menjadi sangat buruk.”
“Aku tidak akan memeras dengan taruhan anakmu itu Nyai, meskipun sebenarnya anakmu itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Kami akan mempertahankan padepokan ini dengan sikap yang wajar.”
“Diam kau,“ bentak Nyai Wiji Sari ”Kau anggap anakku itu sudah tidak berarti apa-apa? Aku rindukan anakku siang dan malam. Aku tidak sampai hati melepaskan anakku dalam kesepian, kedinginan dan kepanasan karena ayahnya tidak memperdulikannya.”
“Ayahnya lebih peduli kepada anak itu daripada kau Nyai...” tiba-tiba Ki Warana menyahut “Aku melayani Kiai Banyu Bening setiap hari jika ia berada disisi anaknya. Sampai akhir hayatnya ia sama sekali tidak pernah berpaling kepada seorang perempuan yang akan dapat menyakiti hati anaknya itu. Tetapi kau, apa yang kau lakukan? Kau tinggalkan anakmu didalam api, sementara kau lari dengan seorang laki-laki saat anakmu masih bayi.”
“Cukup, cukup. Diam kau iblis!” teriak Nyai Wiji Sari dengan suara yang melengking-lengking.
“Kenapa aku harus diam? Kau khianati kesetiaan seorang suami. Kau nodai kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan sekarang, ketika yang tinggal hanya tulang belulang, kau datang untuk mengambilnya. Semua itu omong kosong. Kau yang memanfaatkan anakmu yang telah kau tinggalkan didalam api yang menyala itu untuk menantang Kiai Banyu Bening dan sekaligus berusaha merebut padepokannya.”
“Kau gila. Kau gila!” teriak Nyai Wiji Sari semakin keras.
“Aku adalah orang terdekat dengan Kiai Banyu Bening. Aku melihat bagaimana Kiai Banyu Bening menjadi gila karena tangis anaknya yang ditelan api, sehingga kegilaannya itu telah mewarnai kepercayaannya. Ia ingin seratus orang bayi mau sebagaimana anaknya, menangis didalam api yang menyala.”
“Tidak. Kau bohong!” Kiai Narawangsa lah yang menyahut Banyu Bening mendengar tangis anaknya bagaikan kidung yang mengalun di atas mega di langit biru. Ketika ia merindukan suara kidung itu lagi, maka ia telah memerintahkan untuk membakar seratus orang bayi demi kepuasan batinnya.”
Tetapi Ki Warana menjawab, ”Kau benci akan kesetiaan Kiai Banyu Bening, karena kau telah mengambil isterinya dengan cara yang tidak beradab.”
“Cukup...” teriak Kiai Narawangsa. Tiba-tiba saja Kiai Narawangsa itu mengangkat tangannya sambil berteriak ”Lontarkan anak panah sendaren. Kita koyak mulut-mulut yang memfitnah itu...”
Selanjutnya,
MATAHARI SENJA BAGIAN 20
MATAHARI SENJA BAGIAN 20