Matahari Senja
Bagian 18
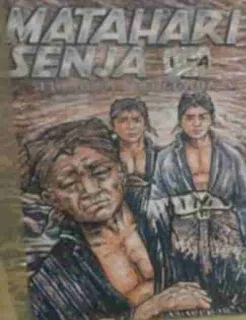
KI AJAR PANGUKAN tertawa. Katanya ”Sekarang sudah ada pimpinan baru di padepokan ini. Karena itu, biarlah pemimpin baru itu bekerja. Kita justru akan menguji, apakah pemimpin yang baru ini menjadi lebih baik atau tidak.”
“Baiklah.” berkata Ki Lemah Teles ”Jika ternyata pimpinan yang baru ini lebih buruk, biarlah ia dicampakkan keluar dari padepokan ini.”
“Jangan merajuk!” desis Ki Pandi ”Jika kurang baik, justru harus diperbaiki.”
“Kenapa bukan kau saja yang menjadi pemimpin disini, bongkok buruk.”
Ki Pandi pun tertawa pula. Demikian pula Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana. Tetapi mereka tidak menyahut lagi.
Demikianlah yang dilakukan oleh para cantrik dan anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu sehari-hari adalah menempa diri dalam olah kanuragan. Anak-anak muda yang berlatih bersama Manggada dan Laksana itupun serba sedikit telah memiliki pengetahuan, bagaimana mereka harus bermain dengan senjata, meskipun senjata utama mereka adalah tombak pendek dan pedang.
Namun dengan tombak pendek dan pedang, mereka telah berlatih mempergunakannya untuk melawan jenis-jenis senjata-senjata yang lain. Mereka telah belajar, bagaimana mereka mempergunakan senjata mereka untuk melawan yang kadang-kadang aneh.
Dalam pada itu dimalam berikutnya, Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana telah kembali melihat-lihat orang-orang yang berada di hutan itu. Seperti yang diduga oleh Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana, maka orang-orang itu sudah mendirikan sebuah gubug. Tidak terlalu dekat dengan bibir hutan. Tetapi sedikit ke tengah sehingga terlindung oleh pepohonan dan pohon-pohon perdu.
Bahkan Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana sempat mendengar orang-orang yang memanasi tubuh mereka dengan perapian itu berbincang dengan dua orang yang agaknya baru datang dari padepokan Kiai Narawangsa. Dari mulut mereka, Ki Sambi Pitu dan Jagaprana mendengar, bahwa Kiai Narawangsa akan segera datang.
“Jika mereka sudah ada di gubug itu, maka tugas kita menjadi bertambah berat, karena Kiai Narawangsa dan Nyi Wiji Sari tentu memiliki ketajaman pendengaran dan penglihatan."
“Penglihatan kita sudah cukup. Kita tinggal menghitung, berapa besar jumlah mereka, sehingga akan dapat kita pergunakan sebagai perbandingan.”
Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. Tetapi iapun kemudian berkata, ”Kita akan berusaha melihat sebuah iring-iringan yang memasuki hutan itu. Bukankah itu lebih mudah daripada kita datang ketempat ini pada saat Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sudah berada disini?”
“Siang malam kita mengamati tempat ini ?”
“Di siang hari kita dapat berada dan bekerja di sawah. Tetapi di malam hari kita memang harus menyediakan waktu yang khusus.” jawab Ki Sambi Pitu.
Ki Jayaraga mengangguk-augguk. Katanya ”Kita dapat melakukannya bergantian.”
“Di siang hari biarlah para cantrik yang bekerja di sawah melakukannya. Tetapi Ki Warana harus memilih cantrik yang terbaik.”
Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Warana dan Ki Lemah Teles, maka mereka pun, menyepakatinya. Sejak hari itu, maka tidak semua cantrik dibenarkan pergi ke sawah didekat hutan yang menjadi landasan kekuatan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.
“Jika aku yang melakukannya.” berkata Ki Lemah Teles ”aku akan memilih tempat yang agak jauh. Bibir hutan itu terlalu dekat dengan sasaran mereka.”
“Yang melakukan bukan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sendiri. Tetapi para cantriknya yang tentu mempunyai wawasan yang lebih sempit dari keduanya.” sahut Ki Jagaprana.
Dengan demikian, maka ketegangan menjadi semakin meningkat di padepokan Ki Lemah Teles itu. Setiap orang benar-benar harus bersiap menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun.
Pada hari-hari terakhir, anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu telah berlatih mempergunakan busur dan anak panah. Mereka harus mempergunakan ketika orang-orang yang menyerang padepokan itu mulai mendekat.
Jika disiang hari para cantrik yang bekerja di sawah dipilih cantrik yang terbaik, karena mereka bertugas mengamati landasan bagi orang-orang Kiai Narawangsa, maka dimalam hari, pengawasan itu dilakukan berganti-ganti oleh orang-orang tua yang berilmu tinggi di padepokan itu.
Akhirnya, yang mereka tunggu-tunggu itupun datang. Justru dimalam hari ketika Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana bertugas melakukan pengawasan. “Kita pula yang mendapat kesempatan melihatnya pertama kali kehadiran orang-orang itu.
Dengan tegang, dari balik gerumbul-gerumbul perdu, kedua orang itu melihat sebuah iring-iringan yang datang menuju ke hutan yang sudah dipersiapkan oleh beberapa orang yang mendahuluinya. Iring-iringan yang panjang itu berjalan menyusuri jalan setapak dalam gelapnya malam.
“Nampaknya mereka hanya bergerak di malam hari.” berkata Ki Sambi Pitu.
“Ya. Tetapi aku yakin, mereka membagi orang-orangnya menjadi beberapa kelompok.”
“Ya. Tentu tidak hanya sejumlah itu. Jika hanya sejumlah itu, maka mereka akan dapat dengan mudah kita hancurkan. Tidak usah menunggu mereka menyerang.” sahut Ki Sambi Pitu. Namun tiba-tiba iapun berbisik ”Bagaimana jika mereka kita hancurkan esok pagi. Selanjutnya kita menunggu iring-iringan berikutnya dan berikutnya?”
“Begitu mudahnya?” sahut Ki Jagaprana. ”Seandainya hal itu kita lakukan, pada serangan terhadap kelompok pertama, belum tentu jika kita menemui Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari ada didalamnya. Sementara itu jika ada seorang saja yang lolos, maka iring-iringan berikutnya tidak akan pernah datang lagi. Tetapi Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari itu akan menjadi seperti api didalam sekam di waktu-waktu mendatang. Justru pada saat kita sudah tidak berada di padepokan itu, mereka datang dengan membawa orang yang lebih banyak.”
Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. Dalam iring-iringan yang mereka lihat didalam gelapnya malam dari tempat yang tidak terlalu dekat itu, keduanya memang tidak dapat melihat, apakah didalam iring-iringan itu terdapat seorang perempuan.
Menurut dugaan kedua orang itu, maka Nyai Wiji Sari tentu mengenakan pakaian yang sama dengan laki-laki yang ada didalam pasukannya. Kedua orang itupun kemudian telah menunggui jalan yang dilalui iring-iringan itu sampai pagi. Tetapi malam itu tidak ada lagi iring-iringan yang memasuki hutan itu.
“Biarlah malam nanti orang lain yang mengawasinya” berkata Ki Sambi Pitu.
“Mungkin sebagian dari mereka akan datang siang hari.”
“Mungkin.” Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk ”Tetapi agaknya menurut perhitungan mereka, perjalanan siang hari untuk sebuah iring-iringan yang besar akan sangat menarik perhatian.”
Kedua orang itu tidak menunggu matahari terbit agar mereka justru tidak terjebak oleh para pengamat yang tentu juga dipasang oleh orang-orang Narawangsa itu. Selagi langit masih gelap, mereka sudah bergerak meninggalkan persembunyiannya kembali ke padepokan.
Setelah berbenah diri, maka Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana segera minta Ki Warana dan orang-orang yang berilmu tinggi di padepokan itu berkumpul. Pada umumnya mereka juga bangun pagi-pagi sekali. Dengan singkat Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana telah melaporkan apa yang dapat mereka lihat malam itu.
“Nanti malam harus ada orang lain yang mengawasi jalan itu, sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih lengkap tentang mereka.”
Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Kepada Ki Warana ia berkata, ”Jika demikian, jangan ijinkan para cantrik pergi ke sawah. Sangat berbahaya bagi mereka. Orang-orang itu tentu akan mencari keterangan tentang padepokan ini. Jika mereka tahu bahwa sawah tidak jauh dari hutan itu adalah sawah padepokan ini, maka. mereka segera mengetahuinya, bahwa orang yang berada disawah itu adalah cantrik dari padepokan ini.”
Ki Warana mengangguk. Tetapi iapun kemudian bertanya, “Apakah kita tidak perlu mengawasinya di siang hari? Aku kira mereka tidak akan tergesa-gesa membuka benturan kekerasan dengan padepokan ini. Bukankah mereka memerlukan waktu untuk bersiap-siap menghadapi benturan yang lebih besar.”
“Mungkin demikian, Ki Warana. Tetapi mungkin juga tidak. Mungkin mereka sengaja menangkap cantrik itu sebagai tantangan yang terbuka. Bukankah mereka sudah dengan berterus terang menantang kita semuanya dengan mengirimkan utusan sampai dua kali berturut-turut. Aku kira mereka masih akan mengirimkan utusan lagi untuk meyakinkan, bahwa kita benar-benar menolak permintaan mereka.”
Ki Warana mengangguk-angguk. Katanya ”Baiklah. Aku akan memerintahkan agar para cantrik tidak pergi ke sawah, terutama yang terdekat dengan sisi hutan yang dipergunakan sebagai landasan oleh Kiai Narawangsa itu.”
Namun dalam pada itu, Ki Lemah Teles itupun berkata ”Tetapi biarlah aku sendiri yang akan pergi ke sawah itu.”
“Sendiri?” bertanya Ki Warana.
“Ya, kenapa?”
“Aku akan pergi bersama Ki Lemah Teles. Mungkin aku tidak berarti apa-apa dalam olah kanuragan. Tetapi aku kira aku dapat berlari lebih cepat dari orang lain.”
Orang-orang tua yang berilmu tinggi itu tersenyum. Ki Ajar Pangukan itupun berkata, ”Bukankah aku juga dapat pergi ke sawah itu?”
“Jangan kau dan jangan si bongkok buruk. Kalian berdua sudah dikenali oleh utusan Kiai Narawangsa. Sementara itu, Ki Warana juga sudah dikenali pula. Karena itu, biarlah aku pergi sendiri. Yakinlah, tidak akan ada persoalan apa-apa.”
Tetapi Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana tidak mau membiarkan Ki Lemah Teles pergi sendiri. Karena itu, maka Ki Sambi Pitu itupun berkata ”Baiklah. Biarlah aku dan Ki Jagaprana yang ikut pergi ke sawah. Tetapi janji, tidak lebih sampai tengah hari. Semalam kami berdua semalam suntuk tidak memejamkan mata.”
“Bukankah sudah terbiasa bagi kalian berdua,” desis Ki Lemah Teles.
Ki Sambi Pitu tersenyum. Namun katanya, ”Tetapi aku akan menolak jika di tengah sawah nanti aku ditantang berperang tanding.”
“Persetan kau!” geram Ki Lemah Teles ”Aku tidak akan menantangmu. Tetapi aku ingin langsung menebas lehermu dengan cangkul.”
Yang mendengarnya justru tertawa.
“Baiklah” berkata Ki Lemah Teles ”Biarlah aku berbenah diri. Disaat matahari naik, aku akan pergi ke sawah bersama Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana.”
Tetapi selama ketiga orang itu bekerja di sawah, mereka tidak melihat iring-iringan yang datang dan menuju ke arah sisi hutan yang sudah dipersiapkan itu. Malam berikutnya, Ki Pandi dan Ki Ajar Pangukan lah yang mendapat giliran untuk mengamati sisi hutan itu. Seperti malam sebelumnya, maka keduanya memang melihat sebuah iring-iringan yang berjalan menuju ke landasan bagi orang pengikut Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari itu. Bahkan pada malam ketiga, masih juga datang iring-iringan berikutnya.
“Mereka membawa beberapa ekor kuda tunggangan dan beberapa ekor kuda beban. Agaknya banyak barang dan barangkali persediaan makanan yang mereka bawa.”
“Ya. Segala sesuatunya yang akan terjadi sebaiknya segera terjadi. Semakin cepat semakin baik.” berkata Ki Ajar Pangukan ”Kehadiran orang sebanyak itu akan dapat mempengaruhi tatanan kehidupan di padukuhan-padukuhan disekitar tempat ini. Jika persediaan makan mereka habis, maka mereka tentu akan lari ke padukuhan. Kecuali keadaan padukuhan itu akan menjadi resah dan bahkan lebih dari itu, maka mereka akan mendengar bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada lagi.”
Ketika hal itu kemudian dibicarakan di padepokan, maka Laksana yang ikut mendengarkannya menjadi gelisah. “Kenapa kau. Laksana?” bertanya Manggada.
“Kehadiran sekian banyak laki-laki di daerah ini akan sangat berbahaya bagi gadis-gadis. Mereka tidak boleh lagi mandi dan mencuci di tepian.”
“Terutama Delima!” desis Manggada.
“Bukan hanya Delima!” sahut Laksana ”Juga kawan-kawannya. Mereka harus tahu itu.”
Manggada memang berniat untuk mengganggu Laksana. Tetapi ia melihat kebenaran pendapat Laksana. Apalagi peristiwa yang tidak diinginkan itu hampir saja terjadi justru atas Delima. Karena itu, ketika Laksana mengajak Manggada menemui Delima, Manggada tidak berkeberatan.
“Tetapi berhati-hatilah.” pesan Ki Pandi ketika Manggada dan Laksana itu minta diri ”Ketahui sajalah, bahwa sisi hutan itu sekarang menjadi landasan para pengikut Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.”
“Arah yang akan kami tempuh justru berlawanan, Ki Pandi.”
“Ya, aku tahu. Tetapi bukan berarti bahwa kalian tidak mungkin akan bertemu dengan pengikut Kiai Narawangsa yang berkeliaran disekitar padepokan ini.”
“Ya, Ki Pandi.”
Sementara itu Ki Lemah Teles pun berpesan, ”Jangan terlalu lama. Kita masih belum tahu cara apakah yang akan mereka pergunakan. Mungkin mereka justru akan membangun perkemahan di sekitar padepokan ini untuk menutup hubungan padepokan ini dengan dunia disekitarnya. Cara ini banyak dilakukan untuk memaksa orang yang mereka kepung itu kehabisan persediaan pangan, sehingga mereka akan menyerah.”
“Baik Ki Lemah Teles!” jawab Manggada dan Laksana hampir bersamaan.
Dengan hati-hati, maka Manggada dan Laksana itupun telah pergi menemui Delima. Kedatangan Manggada dan Laksana memang mengejutkan. Namun kedua orang anak muda itu sama sekali tidak menunjukkan sikap yang gelisah.
“TidaK ada apa-apa. Paman Krawangan,” berkata Manggada, “Kami hanya ingin sekedar singgah.”
“Kalian bawa pesan dari Warana?”
“Tidak secara khusus, Ki Krawangan. Tetapi kami ingin memberitahukan persoalan yang harus mendapat perhatian dari Delima dan kawan-kawannya.”
“Delima?” bertanya Ki Krawangan.
“Ya, paman. Kami membawa pesan bagi Delima.” Sahut Laksana.
Manggada menarik nafas panjang. Ia sudah akan membuka mulutnya untuk mengucapkan peringatan bagi Delima dan kawan-kawannya itu lewat Ki Krawangan. Tetapi agaknya Laksana ingin menyampaikannya langsung kepada Delima.
Tetapi Ki Krawangan itu memang bangkit berdiri untuk memanggil Delima. Ternyata Delima pun kemudian dengan wajah yang terang bersama ayahnya, ikut menemui Manggada dan Laksana, meskipun wajah itu harus terap menunduk.
Laksana lah yang kemudian menceriterakan kepada Ki Krawangan dan Delima bahwa telah datang ke lingkungan itu, sebuah gerombolan yang mungkin akan dapat membahayakan Delima dan kawan-kawannya.
“Untuk sementara kalian tidak usah pergi ke tepian untuk mandi dan mencuci,” berkata Laksana selanjutnya. Delima mengangguk-angguk. Demikian pula Ki Krawangan.
“Terima kasih.” desis Ki Krawangan kemudian ”Apakah agaknya masih akan terjadi benturan kekerasan?”
“Mungkin, paman.” jawab Manggada. Namun kemudian anak muda itupun berkata ”Tetapi aku mohon paman dan Delima tidak mengabarkan kepada siapapun, bahwa kami sudah mengetahui kedatangan gerombolan itu. Ki Warana sampai sekarang masih mengambil jarak dari gerombolan itu. Ki Warana masih berusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan gerombolan itu.”
Ki Krawangan mengangguk-angguk. Katanya, ”Baiklah. Aku akan memperhatikan pesan itu. Mudah-mudahan Warana dapat menempatkan dirinya dalam satu tatanan baru yang terjadi di padepokan itu.”
Manggada lah yang kemudian menyampaikan kepada Ki Krawangan, bahwa sampai saat terakhir, Ki Warana masih menyatakan kepada orang-orang dari gerombolan itu bahwa Kiai Banyu Bening masih hidup.
“Apakah Warana sudah berhubungan dengan mereka?” bertanya Ki Krawangan.
“Mereka telah mengirimkan utusan ke padepokan. Mereka adalah orang-orang yang mendendam Kiai Banyu Bening.”
“Aku tidak mengerti maksud Warana. Seandainya ia mengatakan bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada lagi, bukankah tidak akan terjadi permusuhan lagi.”
“Tetapi mereka tidak hanya mendendam kepada Kiai Banyu Bening. Tetapi mereka ingin mengambil padepokan itu.”
Ki Krawangan mengangguk-angguk. Sementara itu Manggada pun berkata, ”Tetapi sekali lagi kami berpesan, Biarlah persoalan itu menjadi persoalan Ki Warana dengan orang-orang gerombolan itu.”
Ki Krawangan masih mengangguk-angguk. Sementara Manggada merasa bahwa ia tidak akan dapat menceriterakan semuanya kepada Ki Krawangan dalam waktu yang singkat.
Ketika Manggada menggamit Laksana untuk minta diri, ternyata Laksana tidak menanggapinya. Ia masih saja berbicara tentang kemungkinan buruk yang dapat terjadi, jika Delima dan kawan-kawannya turun ke tepian.
Namun dalam pada itu, Ki Krawangan pun berkata kepada Delima ”Delima. Kau dapat membuat minuman untuk tamu-tamumu.”
“Tidak usah, paman. Tidak usah.” sahut Laksana dengan serta merta ”Masih ada beberapa pesan lagi buat Delima.”
Ki Krawangan tersenyum. Katanya ”Biarlah nanti setelah menghidangkan minuman, Delima mendengarkan pesan-pesan itu lagi.”
Ternyata Manggada dan Laksana berada di rumah Ki Krawangan untuk waktu yang agak lama. Mereka menunggu minuman menjadi dingin. Kemudian menghirupnya dengan gula kelapa, dan bahkan kemudian telah dihidangkan pula beberapa potong makanan.
Namun Manggada lah yang menjadi gelisah. Ketika ia mendapat kesempatan, iapun berbisik, “Kita harus segera kembali. Kita akan masuk kedalam sanggar bersama anak-anak muda itu.”
Tetapi Laksana berdesis, ”Sekali-sekali kita dapat melepaskan ketegangan-ketegangan yang setiap hari memburu kita. Sebelum kita benar-benar harus bertempur, sebaiknya kita beristirahat barang satu hari.”
Manggada hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat memaksa Laksana untuk segera kembali ke padepokan. Baru setelah beberapa kali Manggada memperingatkan, maka akhirnya Laksana pun bersedia pula meninggalkan rumah Delima itu.
Di perjalanan kembali, Manggada masih saja bersungut-sungut. Mereka telah kehilangan waktu beberapa lama. Seharusnya mereka sudah berada diantara anak-anak muda yang sedang dengan bersungguh-sungguh menempa diri itu. Tetapi Laksana hanya tersenyum-senyum saja menanggapi sikap kakak sepupunya itu.
Keduanya sempat menjadi berdebar-debar ketika mereka di tengah-tengah bulak bertemu dengan dua orang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Menilik sikap dan cara mereka mengenakan pakaiannya, maka keduanya tentu bukan orang yang tinggal disisi Barat kaki Gunung Lawu itu. Tetapi Manggada dan Laksana tidak ingin membuat persoalan. Karena itu, maka ketika mereka berpapasan dengan kedua orang itu, keduanya lebih baik menepi.
Kedua orang yang berpapasan dengan Manggada dan Laksana itu juga masih muda sebagaimana Manggada dan Laksana. Nampaknya keduanya merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang pantas dihormati. Ketika mereka berpapasan dengan Manggada dan Laksana, keduanya sama sekali tidak mau bergeser menepi sedikitpun, sehingga Manggada dan Laksana lah yang harus minggir sehingga keduanya melipir tanggul parit yang membujur sepanjang jalan itu.
“Gila.” geram Laksana ”Jika saja padepokan itu tidak sedang dalam ketegangan.”
“Lalu, mau kau apakan mereka?” bertanya Manggada.
“Aku akan memilin leher mereka.”
Manggada tertawa. Katanya ”Sudahlah. Saat ini kita memang harus memusatkan perhatian kita kepada gerombolan yang dipimpin oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari itu.”
“Keduanya tentu para pengikut Kiai Narawangsa itu pula.”
“Aku juga menduga demikian” sahut Manggada.
“Bagaimana jika kita tantang saja mereka, mumpung tidak nampak ada orang disawah.”
“Kiai Lemah Teles dan Ki Warana belum membunyikan pertanda perang. Kita harus bersabar.”
“Apapun yang terjadi jika kita menantang kedua orang itu, tidak akan mempengaruhi persoalan yang tumbuh antara para pengikut Kiai Narawangsa dengan orang-orang padepokan.”
“Biarlah segalanya tertimbun pada benturan yang tentu akan terjadi pada satu hari. Mungkin besok, lusa atau mungkin sepekan lagi. Tetapi tentu tidak akan terlalu lama.”
Tiba-tiba saja Laksana itu berhenti. Ketika ia berpaling, punggung kedua orang anak muda itu masih nampak.
“Apakah mereka akan pergi ke rumah Delima?”
“Kau jangan menjadi gila seperti itu” desis Manggada. Lalu katanya ”Bahkan aku ingin memperingatkanmu, agar kau tidak terlalu dekat dengan Delima.”
“Kenapa?” bertanya Manggada.
“Mungkin tidak apa-apa bagimu sendiri. Tetapi sudah berapa kali terjadi kau memuji kecantikan seorang gadis. Nah, bukankah akhirnya kau terus pergi meninggalkan mereka itu?”
Laksana mengerutkan dahinya.
“Jika pada suatu saat tumbuh perasaan yang mendalam di hati seorang gadis, sedangkan pada satu saat kita harus melanjutkan perjalanan pengembaraan ini sebelum kita benar-benar pulang, kau dapat mengira-ngirakan, apa yang akan terjadi dengan gadis itu selanjutnya.”
Laksana tidak menjawab. Tetapi kata-kata Manggada itu menyentuh hatinya pula. Sementara itu, Manggada pun berkata pula, ”Kecuali jika kau sudah jemu mengembara dan ingin menetap disatu tempat.”
Laksana menarik nafas dalam-dalam. Memang tidak terbersit dihatinya, bahwa ia ingin segera menghentikan pengembaraannya. Namun Manggada tidak ingin memperpanjang persoalan itu. Ia menyerahkan segala sesuatunya kepada Laksana, karena ia tahu, bahwa Laksana pun sudah menjadi dewasa. Laksana mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab.
Demikianlah, mereka berdua pun kemudian berjalan semakin cepat menuju ke padepokan. Ketika keduanya kemudian memasuki regol padepokan, Ki Pandi yang duduk di pendapa bangunan utama padepokan itu menarik nafas dalam-dalam. Iapun kemudian bangkit berdiri menyongsong kedua orang anak muda itu.
“Aku sudah berdebar-debar. Rasa-rasanya kalian pergi terlalu lama. Kami disini terpengaruh oleh ketegangan suasana dengan kedatangan para pengikut Kiai Narawangsa itu. Dan bahkan mungkin Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sendiri juga sudah ada ditempat itu.”
“Maaf, Ki Pandi.” Laksana lah yang menjawab ”Ki Krawangan telah menghidangkan makanan dan minuman, sehingga kami tidak dapat meninggalkannya begitu saja.”
“Sudahlah. Tidak apa-apa. Hanya kecemasan seorang tua.”
Kedua orang anak muda itupun kemudian langsung pergi menemui kelompok-kelompok yang berlatih di bawah bimbingan mereka. Tetapi keduanya tertegun, karena anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu sedang berlatih bersama orang-orang tua yang berilmu tinggi di padepokan itu. Ki Sambi Pitu, Ki Jagaprana, Ki Lemah Teles dan Ki Ajar Pangukan sedang sibuk menjajagi kemampuan anak-anak muda yang untuk waktu yang sangat singkat mencoba untuk menyadap ilmu kanuragan dari Manggada dan Laksana.
Ternyata orang-orang tua itu merasa puas dengan kemajuan yang telah mereka capai. Dengan tombak dan pedang dengan perisai atau tidak dengan perisai, anak-anak muda itu sudah mampu mempertanankan diri melawan berbagai macam senjata. Untuk beberapa lama penjajagan itu berlangsung. Manggada dan Laksana serta Ki Pandi berdiri saja mengamatinya.
“Sama sekali tidak mengecewakan.” desis Ki Pandi ”Jika jiwa kalian tidak dibakar oleh kemudaan kalian, mungkin anak-anak itu masih belum mampu mencapai tataran sebagaimana sekarang ini. Mereka telah bekerja dengan sangat keras untuk dapat menyesuaikan diri dengan keinginan kalian.”
Manggada dan Laksana tidak menjawab.
“Manggada dan Laksana!” berkata Ki Pandi kemudian ”Justru menjelang hari-hari yang gawat, yang tentu akan memaksa kita semua bekerja sangat-sangat keras, maka kalian harus mengurangi beban anak-anak itu. Biarlah mereka sempat beristirahat."
Manggada dan Laksana mengangguk-angguk.
Sementara Ki Pandi berkata selanjutnya ”Dari hari ke hari mereka nampak menjadi semakin kurus. Meskipun mereka tidak mengeluh, tetapi biarlah tubuh mereka menjadi semakin segar menjelang hari-hari yang mendebarkan itu.”
“Baiklah, Ki Pandi ” desis Manggada kemudian.
“Yang harus kalian pertahankan, adalah latihan-latihan ketahanan tubuh setiap mereka bangun pagi. Kemudian latihan-latihan olah senjata, setidak-tidaknya untuk mempertahankan tataran yang telah mereka capai. Kalian harus memberikan waktu beristirahat lebih banyak. Memberi kesempatan mereka untuk berbuat sesuatu sebagaimana anak-anak muda yang lain. Tidak semuanya dapat kalian ukur sebagaimana kalian sendiri.”
“Baik, Ki Pandi.” jawab Manggada dan Laksana.
Dalam pada itu, maka orang-orang tua yang berilmu tinggi di padepokan itu menganggap bahwa tingkat kemampuan anak-anak muda yang belum lama berada di padepokan itu sudah cukup memadai diukur dari waktu yang mereka pergunakan untuk belajar dan berlatih. Apalagi yang memimpin mereka juga anak muda yang umurnya tidak terpaut banyak dengan mereka.
Beberapa saat kemudian, maka latihan latihan itupun berakhir. Semuanya menganggap bahwa latihan yang telah mereka lakukan sangat baik. Kemampuan mereka sudah memadai, apalagi dilihat dari sisi waktu. Namun semuanya telah memberikan saran yang sama, bahwa anak-anak muda itu harus mendapat kesempatan untuk beristirahat lebih banyak tanpa mengabaikan latihan-latihan yang harus mereka lakukan untuk mengasah tajamnya kemampuan yang telah mereka miliki.
Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Orang-orang tua itu tentu memiliki pengalaman yang jauh lebih luas dari Manggada dan Laksana. Ketika kemudian Manggada dan Laksana berada diantara anak-anak muda itu, maka Manggada dan Laksana pun telah mengatakan kepada mereka, untuk mendapatkan tenaga yang sebesar-besarnya menjelang saat-saat yang paling gawat, maka kesempatan untuk beristirahat pun akan diberikan lebih banyak.
Namun keduanya masih menambahkan, bahwa hal itu bukan berarti bahwa latihan-latihan yang berat dan kerja yang keras sudah berakhir.
“Sementara itu di hutan tua, Kiai Natawangsa dan Nyai Wiji Sari telah bersiap menerkam kita.” berkata Manggada kepada anak-anak muda itu.
Sebenarnyalah saat itu Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari telah berada diantara para pengikutnya di hutan yang sebelumnya memang telah dipersiapkan. Ternyata keduanya tidak mempunyai pendirian sebagaimana orang yang berilmu tinggi di padepokan, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari tidak menganggap landasan yang dibangun itu terlalu dekat dengan padepokan yang akan menjadi sasaran mereka.
Bahkan Kiai Narawangsa berkata, ”Kalian memang memiliki ketajaman penalaran. Tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk meloncat ke padepokan itu. Tidak terlalu jauh dan cukup terlindung dari penglihatan orang-orang padepokan.”
“Bukankah kita tidak berniat untuk berlindung.” berkata Nyai Wiji Sari ”Kita justru akan datang ke padepokan itu dan menuntut agar padepokan itu diserahkan kepada kita.”
“Tetapi kita tidak boleh tergesa-gesa Nyai.” jawab Kiai Narawangsa ”segala sesuatunya harus diperhitungkan sebaik-baiknya, agar kita dapat mencapai hasil sebagaimana kita kehendaki.”
“Apalagi yang harus diperhitungkan?” Nyai Wiji Sari memang tidak sabar lagi ”Kita datangi padepokan itu. Kita hancurkan pintu-pintunya. Kemudian kita menyerbu masuk.”
“Bagaimana dengan rencana kita untuk datang menemui Banyu Bening?”
“Apakah ada gunanya?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Mudah-mudahan masih ada gunanya. Jika Banyu Bening dapat mencegah pertempuran, maka ia akan mendapat kesempatan untuk hidup beberapa lama lagi.”
“Apakah ukurannya waktu yang kau katakan tidak lama lagi itu?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Sampai kita menjadi jemu dan kemudian membunuhnya,” jawab Narawangsa.
“Akhirnya sama saja. Kenapa tidak kita bunuh sekarang?”
“Jika ia dapat mencegah perang, bukankah orang-orang kita tidak banyak yang akan mati? Sementara itu, kita akan menangkap Banyu Bening dan terserahlah kepada kita. Tetapi para pengikutnya tentu sudah terpecah bercerai berai dan tidak akan mampu menyusun kekuatan lagi untuk melawan kita.”
Nyai Wiji Sari merenung sejenak. Namun ada sesuatu yang terasa bergejolak dihatinya. Nyai Wiji Sari sendiri tidak tahu, apakah yang mengekang perasaannya untuk datang menemui Kiai Banyu Bening dan berbicara dengan laki-laki itu. Bagi Nyai Wiji Sari, datang dengan pasukan dan bertempur, akan lebih baik daripada harus datang menemuinya dan berbicara dengannya.
“Aku muak melihat laki-laki itu.” geram Nyai Wiji Sari.
Tetapi kata-kata yang terlontar disela-sela bibirnya itu tidak meyakinkan dirinya sendiri. Bahkan didalam lubuk hatinya telah timbul pertanyaan, ”Apakah bukan karena sebab lain?”
Nyai Wiji Sari menggeretakkan giginya. Ia mencoba mengusir sentuhan-sentuhan perasaan yang dianggapnya sebagai satu kelemahan justru karena ia seorang perempuan. Bagaimanapun juga Kiai Banyu Bening adalah bekas suaminya dan yang pernah memberinya seorang anak. Tetapi anak itu meninggal, justru karena terbakar.
Kiai Narawangsa melihat keragu-raguan yang sangat di wajah Nyai Wiji Sari. Tetapi menurut tanggapan Kiai Narawangsa justru karena Wiji Sari itu sangat membenci suaminya. Ketika Nyai Wiji Sari itu masih menjadi istri Lembu Wirid, ia sudah membencinya. Apalagi kemudian setelah anaknya terbunuh didalam lidah api yang menyala menelan rumahnya.
“Terserah kepadamu.” berkata Kiai Narawangsa ”Jika kau berkeberatan, maka aku akan menurut, mana yang kau anggap lebih baik. Jika aku berniat untuk datang menemuinya, itu karena kita pernah merencanakannya.”
“Tidak. Aku tidak mau menemui laki-laki keparat itu.” geram Nyai Wiji Sari. Hampir berteriak iapun berkata ”Tidak. Aku muak. Muak sekali.”
“Baik. Baik.” berkata Kiai Narawangsa ”Kita akan langsung datang ke padepokan itu dengan seluruh kekuatan kita. Kita akan membakar pintu-pintunya dan menerobos masuk kedalamnya.”
“Aku sudah menyiapkan beberapa bakul biji jarak. Beberapa bakul yang lain sudah dihancurkan menjadi bubuk kasar yang dicampur dengan serat yang sudah dikeringkan.“
“Apakah serbuk dan biji jarak itu cukup banyak untuk membakar pintu gerbang dan pintu butulan?”
“Tentu. Kita akan menimbun kayu-kayu kering diluar pintu itu untuk mempercepat nyala api. Jika daun pintu gerbang itu terbakar, maka kita akan segera dapat menerobos masuk.”
“Baiklah. Kita harus menyiapkan gerobak-gerobak kecil untuk mengusung kayu, serbuk biji jarak dan biji jarak itu.”
“Besok kita akan melihat pintu gerbang itu,” berkata Kiai Narawangsa.
Sebenarnyalah dihari berikutnya, Kiai Narawangsa dan Gunasraba berserta beberapa orang pengiringnya telah mendatangi padepokan. Berkuda mereka tanpa ragu-ragu mendekati rintu gerbang padepokan itu dari arah depan. Beberapa puluh langkah mereka menghentikan kuda mereka. Para petugas di panggungan disebelah menyebelah pintu gerbang itu melihat kedatangan beberapa orang berkuda.
Namun mereka mengerti, bahwa serangan yang sebenarnya masih belum datang, karena jumlah orang berkuda itu tidak lebih dari sepuluh orang. Meskipun demikian, para petugas itu telah memberikan laporan langsung kepada Ki Lemah Teles tanpa membunyikan kentongan.
Orang-orang tua yang berilmu tinggi, yang ada di padepokan itu telah memanjat panggungan yang ada disebelah menyebelah pintu gerbang itu. Tetapi merekapun berpendapat, bahwa orang-orang itu masih belum akan berbuat sesuatu.
“Mungkin mereka akan menemui orang yang bernama Kiai Banyu Bening itu” berkata Ki Lemah Teles.
Tetapi ternyata tidak. Ternyata mereka tidak menyatakan maksudnya itu. Beberapa orang itu hanya berkeliaran hilir mudik diatas punggung kuda mereka sambil mengamat-amati pintu gerbang.
“Mereka sedang memperhitungkan kemungkinan untuk merusak pintu gerbang itu.” desis Ki Ajar Pangukan.
“Ya. Tetapi mereka tidak dapat menghitung ketebalan daun pintu gerbang itu. Mereka juga tidak dapat menduga, seberapa besarnya selarak pintu itu.”
Namun diluar, Kiai Narawangsa berkata, ”Pintu itu dibuat dari kayu.”
“Kita akan dapat membakarnya.” berkata Gunasraba.
“Kau yakin biji jarakmu itu cukup untuk menyalakan pintu gerbang itu?”
“Tentu kakang.” jawab Gunasraba ”Pintu gerbang itu akan menjadi abu. Dan kita akan dapat dengan leluasa masuk kedalamnya. Kita bukan orang dungu yang mau membuang-buang waktu dan bahkan nyawa dengan memanggul balok kayi yang besar untuk menghantam dan merobohkan pintu gerbang itu. Selama kita hilir mudik mengambil ancang-ancang, maka anak panah orang-orang diatas panggungan itu sudah menghujani kita.”
“Jika kita membakar pintu itu, bukankah mereka juga dapat membunuh kita dengan anak panahnya?”
“Tetapi kita tidak memerlukan banyak orang. Empat orang menaburkan serbuk yang bercampur serat itu serta biji jarak sementara lima atau enam orang melindunginya dengan perisai. Sementara itu, orang-orang kita akan melontarkan serangan anak panah pula dari tempat kita ini untuk mengurangi tekanan mereka terhadap orang-orang kita yang sedang membakar pintu gerbang itu."
Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Iapun yakin bahwa rencana adiknya itu tentu akan dapat dilakukan. Biji jarak memang mengandung minyak yang dapat dipergunakan sebagai oncor di malam hari.
Sementara itu, orang-orang yang berada dipanggungan di sebelah-menyebelah pintu gerbang itu memperhatikan orang-orang berkuda itu dengan saksama. Tetapi mereka tidak dapat mengerti, apa yang akan mereka lakukan. Mereka hanya melihat orang-orang itu menunjuk kearah pintu gerbang, kearah panggungan disebelah-menyebelah pintu gerbang itu serta sekali-sekali memperhatikan keadaan di sekitarnya.
Tetapi orang-orang itu tidak hanya memperhatikan pintu gerbang utama. Ternyata mereka juga memperhatikan pintu-pintu butulan. Kuda-kuda itu berlari-lari melingkari padepokan yang terhitung luas itu.
“Mereka sedang mencari cara yang paling baik untuk merusak pintu.” berkata Ki Ajar Pangukan.
“Kita akan melayani, cara apa saja yang akan mereka pergunakan.” desis Ki Sambi Pitu.
Ki Lemah Teles dan Ki Warana memperhatikan orang-orang itu dengan saksama. Beberapa saat lamanya beberapa orang berkuda itu hilir mudik di sekitar padepokan. Namun akhirnya kuda-kuda itu berlari meninggalkan padepokan itu.
Orang-orang tua yang berilmu tinggi, yang melihat beberapa orang berkuda itupun menyadari, bahwa Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari ternyata cukup berhati-hati. Mereka tidak langsung datang menyerang, tetapi mereka telah mencoba untuk melihat sasaran untuk membuat perhitungan yang lebih mantap.
“Seorang diantara mereka itu adalah Kiai Narawangsa sendiri.” desis Ki Warana.
“Ya!” Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk ”menurut utusannya yang terdahulu, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi.”
“Yang manakah diantara mereka yang kau maksud Ki Narawangsa itu?” bertanya Ki Lemah Teles.
“Yang bertubuh raksasa. Yang tidak mengenakan ikat kepalanya, tetapi hanya disangkutkan dilehernya sedang jika kita sempat melihat lebih dekat, maka kita akan melihat segores luka diwajahnya.”
Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Seorang diantara orang-orang berkuda itu adalah seorang yang bertubuh raksasa. Ikat kepalanya disangkutkan dibahunya, sementara itu rambutnya yang ikal dan panjang itu disanggulnya agak tinggi. Kiai Narawangsa ditilik dari ujud lahiriahnya memang sangat meyakinkan. Jika ia kemudian datang untuk menantang Kiai Banyu Bening, Kiai Narawangsa itu tentu memiliki keyakinan diri yang tinggi.
Kehadiran orang-orang berkuda itu, telah memperingatkan kepada Ki Lemah Teles, Ki Warana dan orang-orang tua yang berilmu tinggi, agar mereka menjadi lebih berhati-hati menghadapi lawan yang membuat perhitungan-perhitungan yang cermat.
Ketika sekelompok orang berkuda itu telah hilang dari penglihatan mereka, maka Ki Warana dan orang-orang tua yang berilmu tinggi itupun duduk di pendapa bangunan induk padepokan itu untuk berbincang tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
Seorang cantrik yang bertugas di panggungan itu bertanya kepada kawannya ”Apa kira-kira yang akan mereka lakukan?"
“Mereka tentu merencanakan untuk memecahkan pintu gerbang itu.” jawab kawannya.
“Aku tahu. Tetapi bagaimana caranya?” kawannya membentak.
Cantrik itu tertawa. Katanya ”Kenapa kau tiba-tiba menjadi uring-uringan?”
Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya bertanya lagi.
Dipendapa, orang-orang berilmu tinggi itu juga menduga-duga. Cara apakah yang akan ditempuh oleh Kiai Narawangsa untuk membuka pintu gerbang padepokan itu. Tetapi yang mereka sebutkan adalah cara-cara yang sering dipergunakan untuk memecahkan pintu. Tidak seorangpun diantara mereka yang menduga, bahwa Kiai Narawangsa akan memecahkan pintu gerbang itu dengan cara yang lain. Api.
Sementara itu, di dalam hutan tempat Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari menunggu kesempatan, Gunasraba telah mempersiapkan segala-galanya. Seonggok serat kulit kayu yang kering, telah dicampur serbuk biji jarak. Selain itu telah dipersiapkan pula biji jarak yang cukup banyak. Untuk meyakinkan diri, maka Gunasraba itu pun telah menyediakan minyak kelapa yang cukup, yang akan dituang pada onggokan-onggokan serat kayu yang Kering itu.
“Pintu gerbang itu tentu akan terbakar.” geram Gunasraba.
“Bukankah kau akan membakar semua pintu,” bertanya Kia Narawangsa.
“Ya. Semua pintu. Gerbang utama dan gerbang-gerbang butulan. Seperti yang kita ketahui, ada empat pintu butulan."
Cara yang dipilih oleh Gunasraba itu memang tidak dapat dilakukan dengan serta-merta. Tetapi mereka harus menunggu api yang dinyalakan itu menjadi besar. Baru kemudian api itu akan membakar pintu gerbang yang terbuat dari kayu itu.
“Kita memang harus sedikit bersabar!” berkata Gunasraba ”tetapi cara ini adalah cara yang akan menelan korban paling sedikit.
Namun dalam pada itu, Nyai Wiji Sari nampaknya menjadi semakin tidak sabar. Perempuan itu menjadi semakin banyak merenung. Wajahnya nampak muram dan tingkah lakunya yang gelisah. “Aku tidak dapat duduk disini berhari-hari tanpa berbuat apa-apa berkata Nyai Wiji Sari itu.
“Kami sedang mempersiapkan segala-galanya Nyai” jawab Kiai Narawangsa, ”kami tidak ingin gagal.”
“Apa sebenarnya yang mencemaskan kita? Kita akan menghancurkan Lembu Wirid itu. Jika orang itu mati, maka para pengikutnya tentu akan segera menyerah.”
“Aku mengerti.” jawab Kiai Narawangsa ”Tetapi bukankah kita perlu memikirkan cara agar kita dapat masuk dan berhadapan dengan Kiai Banyu Bening?”
Nyai Wiji Sari tidak menyahut lagi. Namun wajah masih saja nampak gelap. Sebenarnya semakin lama Nyai Wiji Sari berada di hutan itu, kegelisahan terasa semakin mencengkamnya. Rasara-sanya ia sudah mendengar tangis anaknya yang melengking-lengking dibalik dinding padepokan itu.
Tetapi Nyai Wiji Sari rasa-rasanya juga selalu dibayangi oleh wajah Lembu Wirid. Wajah yang keras seorang laki-laki. Dalam kegelisahannya itu, kadang-kadang masih juga timbul pertanyaan, kenapa waktu itu ia telah tergelincir untuk menerima Narawangsa memasuki lingkungan dinding ruang tidurnya.
“Itulah awal bencana ini” Nyai Wiji Sari merintih didalam hatinya.
Tetapi hati Nyai Wiji Sari yang gelap itu tidak melihat jalan penyelesaian yang terbaik yang dapat ditempuhnya. Ketika kerinduannya kepada seorang anak memuncak, maka perempuan itu telah menyalurkan gejolak perasaannya itu dengan caranya yang keras dan kasar, sebagaimana cara hidup yang dijalaninya.
“Tetapi bukan aku yang ingin membunuh Lembu Wirid” perasaan Nyai Wiji Sari melonjak ”Aku hanya ingin mengambil apa yang masih tersisa dari anakku.”
Tetapi Nyai Wiji Sari tidak dapat mengatakannya kepada Kiai Narawangsa. Jika hal itu dikatakannya, maka Kiai Narawangsa akan dapat menjadi salah paham. Sementara itu, Nyai Wiji Sari tidak ingin merusak hidup kekeluargaannya sekali lagi. Meskipun selama itu ia berada dijalan kehidupan yang gelap serta membina keluarga yang kelam pula, namun Nyai Wiji Sari itu ingin mempertahankannya.
Dalam pada itu, segala persiapan pun telah dilakukan. Gunasraba telah yakin, bahwa ia akan dapat membuka pintu, gerbang itu dengan caranya...
“Baiklah.” berkata Ki Lemah Teles ”Jika ternyata pimpinan yang baru ini lebih buruk, biarlah ia dicampakkan keluar dari padepokan ini.”
“Jangan merajuk!” desis Ki Pandi ”Jika kurang baik, justru harus diperbaiki.”
“Kenapa bukan kau saja yang menjadi pemimpin disini, bongkok buruk.”
Ki Pandi pun tertawa pula. Demikian pula Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana. Tetapi mereka tidak menyahut lagi.
Demikianlah yang dilakukan oleh para cantrik dan anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu sehari-hari adalah menempa diri dalam olah kanuragan. Anak-anak muda yang berlatih bersama Manggada dan Laksana itupun serba sedikit telah memiliki pengetahuan, bagaimana mereka harus bermain dengan senjata, meskipun senjata utama mereka adalah tombak pendek dan pedang.
Namun dengan tombak pendek dan pedang, mereka telah berlatih mempergunakannya untuk melawan jenis-jenis senjata-senjata yang lain. Mereka telah belajar, bagaimana mereka mempergunakan senjata mereka untuk melawan yang kadang-kadang aneh.
Dalam pada itu dimalam berikutnya, Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana telah kembali melihat-lihat orang-orang yang berada di hutan itu. Seperti yang diduga oleh Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana, maka orang-orang itu sudah mendirikan sebuah gubug. Tidak terlalu dekat dengan bibir hutan. Tetapi sedikit ke tengah sehingga terlindung oleh pepohonan dan pohon-pohon perdu.
Bahkan Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana sempat mendengar orang-orang yang memanasi tubuh mereka dengan perapian itu berbincang dengan dua orang yang agaknya baru datang dari padepokan Kiai Narawangsa. Dari mulut mereka, Ki Sambi Pitu dan Jagaprana mendengar, bahwa Kiai Narawangsa akan segera datang.
“Jika mereka sudah ada di gubug itu, maka tugas kita menjadi bertambah berat, karena Kiai Narawangsa dan Nyi Wiji Sari tentu memiliki ketajaman pendengaran dan penglihatan."
“Penglihatan kita sudah cukup. Kita tinggal menghitung, berapa besar jumlah mereka, sehingga akan dapat kita pergunakan sebagai perbandingan.”
Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. Tetapi iapun kemudian berkata, ”Kita akan berusaha melihat sebuah iring-iringan yang memasuki hutan itu. Bukankah itu lebih mudah daripada kita datang ketempat ini pada saat Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sudah berada disini?”
“Siang malam kita mengamati tempat ini ?”
“Di siang hari kita dapat berada dan bekerja di sawah. Tetapi di malam hari kita memang harus menyediakan waktu yang khusus.” jawab Ki Sambi Pitu.
Ki Jayaraga mengangguk-augguk. Katanya ”Kita dapat melakukannya bergantian.”
“Di siang hari biarlah para cantrik yang bekerja di sawah melakukannya. Tetapi Ki Warana harus memilih cantrik yang terbaik.”
Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Warana dan Ki Lemah Teles, maka mereka pun, menyepakatinya. Sejak hari itu, maka tidak semua cantrik dibenarkan pergi ke sawah didekat hutan yang menjadi landasan kekuatan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.
“Jika aku yang melakukannya.” berkata Ki Lemah Teles ”aku akan memilih tempat yang agak jauh. Bibir hutan itu terlalu dekat dengan sasaran mereka.”
“Yang melakukan bukan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sendiri. Tetapi para cantriknya yang tentu mempunyai wawasan yang lebih sempit dari keduanya.” sahut Ki Jagaprana.
Dengan demikian, maka ketegangan menjadi semakin meningkat di padepokan Ki Lemah Teles itu. Setiap orang benar-benar harus bersiap menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun.
Pada hari-hari terakhir, anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu telah berlatih mempergunakan busur dan anak panah. Mereka harus mempergunakan ketika orang-orang yang menyerang padepokan itu mulai mendekat.
Jika disiang hari para cantrik yang bekerja di sawah dipilih cantrik yang terbaik, karena mereka bertugas mengamati landasan bagi orang-orang Kiai Narawangsa, maka dimalam hari, pengawasan itu dilakukan berganti-ganti oleh orang-orang tua yang berilmu tinggi di padepokan itu.
Akhirnya, yang mereka tunggu-tunggu itupun datang. Justru dimalam hari ketika Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana bertugas melakukan pengawasan. “Kita pula yang mendapat kesempatan melihatnya pertama kali kehadiran orang-orang itu.
Dengan tegang, dari balik gerumbul-gerumbul perdu, kedua orang itu melihat sebuah iring-iringan yang datang menuju ke hutan yang sudah dipersiapkan oleh beberapa orang yang mendahuluinya. Iring-iringan yang panjang itu berjalan menyusuri jalan setapak dalam gelapnya malam.
“Nampaknya mereka hanya bergerak di malam hari.” berkata Ki Sambi Pitu.
“Ya. Tetapi aku yakin, mereka membagi orang-orangnya menjadi beberapa kelompok.”
“Ya. Tentu tidak hanya sejumlah itu. Jika hanya sejumlah itu, maka mereka akan dapat dengan mudah kita hancurkan. Tidak usah menunggu mereka menyerang.” sahut Ki Sambi Pitu. Namun tiba-tiba iapun berbisik ”Bagaimana jika mereka kita hancurkan esok pagi. Selanjutnya kita menunggu iring-iringan berikutnya dan berikutnya?”
“Begitu mudahnya?” sahut Ki Jagaprana. ”Seandainya hal itu kita lakukan, pada serangan terhadap kelompok pertama, belum tentu jika kita menemui Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari ada didalamnya. Sementara itu jika ada seorang saja yang lolos, maka iring-iringan berikutnya tidak akan pernah datang lagi. Tetapi Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari itu akan menjadi seperti api didalam sekam di waktu-waktu mendatang. Justru pada saat kita sudah tidak berada di padepokan itu, mereka datang dengan membawa orang yang lebih banyak.”
Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. Dalam iring-iringan yang mereka lihat didalam gelapnya malam dari tempat yang tidak terlalu dekat itu, keduanya memang tidak dapat melihat, apakah didalam iring-iringan itu terdapat seorang perempuan.
Menurut dugaan kedua orang itu, maka Nyai Wiji Sari tentu mengenakan pakaian yang sama dengan laki-laki yang ada didalam pasukannya. Kedua orang itupun kemudian telah menunggui jalan yang dilalui iring-iringan itu sampai pagi. Tetapi malam itu tidak ada lagi iring-iringan yang memasuki hutan itu.
“Biarlah malam nanti orang lain yang mengawasinya” berkata Ki Sambi Pitu.
“Mungkin sebagian dari mereka akan datang siang hari.”
“Mungkin.” Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk ”Tetapi agaknya menurut perhitungan mereka, perjalanan siang hari untuk sebuah iring-iringan yang besar akan sangat menarik perhatian.”
Kedua orang itu tidak menunggu matahari terbit agar mereka justru tidak terjebak oleh para pengamat yang tentu juga dipasang oleh orang-orang Narawangsa itu. Selagi langit masih gelap, mereka sudah bergerak meninggalkan persembunyiannya kembali ke padepokan.
Setelah berbenah diri, maka Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana segera minta Ki Warana dan orang-orang yang berilmu tinggi di padepokan itu berkumpul. Pada umumnya mereka juga bangun pagi-pagi sekali. Dengan singkat Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana telah melaporkan apa yang dapat mereka lihat malam itu.
“Nanti malam harus ada orang lain yang mengawasi jalan itu, sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih lengkap tentang mereka.”
Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Kepada Ki Warana ia berkata, ”Jika demikian, jangan ijinkan para cantrik pergi ke sawah. Sangat berbahaya bagi mereka. Orang-orang itu tentu akan mencari keterangan tentang padepokan ini. Jika mereka tahu bahwa sawah tidak jauh dari hutan itu adalah sawah padepokan ini, maka. mereka segera mengetahuinya, bahwa orang yang berada disawah itu adalah cantrik dari padepokan ini.”
Ki Warana mengangguk. Tetapi iapun kemudian bertanya, “Apakah kita tidak perlu mengawasinya di siang hari? Aku kira mereka tidak akan tergesa-gesa membuka benturan kekerasan dengan padepokan ini. Bukankah mereka memerlukan waktu untuk bersiap-siap menghadapi benturan yang lebih besar.”
“Mungkin demikian, Ki Warana. Tetapi mungkin juga tidak. Mungkin mereka sengaja menangkap cantrik itu sebagai tantangan yang terbuka. Bukankah mereka sudah dengan berterus terang menantang kita semuanya dengan mengirimkan utusan sampai dua kali berturut-turut. Aku kira mereka masih akan mengirimkan utusan lagi untuk meyakinkan, bahwa kita benar-benar menolak permintaan mereka.”
Ki Warana mengangguk-angguk. Katanya ”Baiklah. Aku akan memerintahkan agar para cantrik tidak pergi ke sawah, terutama yang terdekat dengan sisi hutan yang dipergunakan sebagai landasan oleh Kiai Narawangsa itu.”
Namun dalam pada itu, Ki Lemah Teles itupun berkata ”Tetapi biarlah aku sendiri yang akan pergi ke sawah itu.”
“Sendiri?” bertanya Ki Warana.
“Ya, kenapa?”
“Aku akan pergi bersama Ki Lemah Teles. Mungkin aku tidak berarti apa-apa dalam olah kanuragan. Tetapi aku kira aku dapat berlari lebih cepat dari orang lain.”
Orang-orang tua yang berilmu tinggi itu tersenyum. Ki Ajar Pangukan itupun berkata, ”Bukankah aku juga dapat pergi ke sawah itu?”
“Jangan kau dan jangan si bongkok buruk. Kalian berdua sudah dikenali oleh utusan Kiai Narawangsa. Sementara itu, Ki Warana juga sudah dikenali pula. Karena itu, biarlah aku pergi sendiri. Yakinlah, tidak akan ada persoalan apa-apa.”
Tetapi Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana tidak mau membiarkan Ki Lemah Teles pergi sendiri. Karena itu, maka Ki Sambi Pitu itupun berkata ”Baiklah. Biarlah aku dan Ki Jagaprana yang ikut pergi ke sawah. Tetapi janji, tidak lebih sampai tengah hari. Semalam kami berdua semalam suntuk tidak memejamkan mata.”
“Bukankah sudah terbiasa bagi kalian berdua,” desis Ki Lemah Teles.
Ki Sambi Pitu tersenyum. Namun katanya, ”Tetapi aku akan menolak jika di tengah sawah nanti aku ditantang berperang tanding.”
“Persetan kau!” geram Ki Lemah Teles ”Aku tidak akan menantangmu. Tetapi aku ingin langsung menebas lehermu dengan cangkul.”
Yang mendengarnya justru tertawa.
“Baiklah” berkata Ki Lemah Teles ”Biarlah aku berbenah diri. Disaat matahari naik, aku akan pergi ke sawah bersama Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana.”
Tetapi selama ketiga orang itu bekerja di sawah, mereka tidak melihat iring-iringan yang datang dan menuju ke arah sisi hutan yang sudah dipersiapkan itu. Malam berikutnya, Ki Pandi dan Ki Ajar Pangukan lah yang mendapat giliran untuk mengamati sisi hutan itu. Seperti malam sebelumnya, maka keduanya memang melihat sebuah iring-iringan yang berjalan menuju ke landasan bagi orang pengikut Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari itu. Bahkan pada malam ketiga, masih juga datang iring-iringan berikutnya.
“Mereka membawa beberapa ekor kuda tunggangan dan beberapa ekor kuda beban. Agaknya banyak barang dan barangkali persediaan makanan yang mereka bawa.”
“Ya. Segala sesuatunya yang akan terjadi sebaiknya segera terjadi. Semakin cepat semakin baik.” berkata Ki Ajar Pangukan ”Kehadiran orang sebanyak itu akan dapat mempengaruhi tatanan kehidupan di padukuhan-padukuhan disekitar tempat ini. Jika persediaan makan mereka habis, maka mereka tentu akan lari ke padukuhan. Kecuali keadaan padukuhan itu akan menjadi resah dan bahkan lebih dari itu, maka mereka akan mendengar bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada lagi.”
Ketika hal itu kemudian dibicarakan di padepokan, maka Laksana yang ikut mendengarkannya menjadi gelisah. “Kenapa kau. Laksana?” bertanya Manggada.
“Kehadiran sekian banyak laki-laki di daerah ini akan sangat berbahaya bagi gadis-gadis. Mereka tidak boleh lagi mandi dan mencuci di tepian.”
“Terutama Delima!” desis Manggada.
“Bukan hanya Delima!” sahut Laksana ”Juga kawan-kawannya. Mereka harus tahu itu.”
Manggada memang berniat untuk mengganggu Laksana. Tetapi ia melihat kebenaran pendapat Laksana. Apalagi peristiwa yang tidak diinginkan itu hampir saja terjadi justru atas Delima. Karena itu, ketika Laksana mengajak Manggada menemui Delima, Manggada tidak berkeberatan.
“Tetapi berhati-hatilah.” pesan Ki Pandi ketika Manggada dan Laksana itu minta diri ”Ketahui sajalah, bahwa sisi hutan itu sekarang menjadi landasan para pengikut Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.”
“Arah yang akan kami tempuh justru berlawanan, Ki Pandi.”
“Ya, aku tahu. Tetapi bukan berarti bahwa kalian tidak mungkin akan bertemu dengan pengikut Kiai Narawangsa yang berkeliaran disekitar padepokan ini.”
“Ya, Ki Pandi.”
Sementara itu Ki Lemah Teles pun berpesan, ”Jangan terlalu lama. Kita masih belum tahu cara apakah yang akan mereka pergunakan. Mungkin mereka justru akan membangun perkemahan di sekitar padepokan ini untuk menutup hubungan padepokan ini dengan dunia disekitarnya. Cara ini banyak dilakukan untuk memaksa orang yang mereka kepung itu kehabisan persediaan pangan, sehingga mereka akan menyerah.”
“Baik Ki Lemah Teles!” jawab Manggada dan Laksana hampir bersamaan.
Dengan hati-hati, maka Manggada dan Laksana itupun telah pergi menemui Delima. Kedatangan Manggada dan Laksana memang mengejutkan. Namun kedua orang anak muda itu sama sekali tidak menunjukkan sikap yang gelisah.
“TidaK ada apa-apa. Paman Krawangan,” berkata Manggada, “Kami hanya ingin sekedar singgah.”
“Kalian bawa pesan dari Warana?”
“Tidak secara khusus, Ki Krawangan. Tetapi kami ingin memberitahukan persoalan yang harus mendapat perhatian dari Delima dan kawan-kawannya.”
“Delima?” bertanya Ki Krawangan.
“Ya, paman. Kami membawa pesan bagi Delima.” Sahut Laksana.
Manggada menarik nafas panjang. Ia sudah akan membuka mulutnya untuk mengucapkan peringatan bagi Delima dan kawan-kawannya itu lewat Ki Krawangan. Tetapi agaknya Laksana ingin menyampaikannya langsung kepada Delima.
Tetapi Ki Krawangan itu memang bangkit berdiri untuk memanggil Delima. Ternyata Delima pun kemudian dengan wajah yang terang bersama ayahnya, ikut menemui Manggada dan Laksana, meskipun wajah itu harus terap menunduk.
Laksana lah yang kemudian menceriterakan kepada Ki Krawangan dan Delima bahwa telah datang ke lingkungan itu, sebuah gerombolan yang mungkin akan dapat membahayakan Delima dan kawan-kawannya.
“Untuk sementara kalian tidak usah pergi ke tepian untuk mandi dan mencuci,” berkata Laksana selanjutnya. Delima mengangguk-angguk. Demikian pula Ki Krawangan.
“Terima kasih.” desis Ki Krawangan kemudian ”Apakah agaknya masih akan terjadi benturan kekerasan?”
“Mungkin, paman.” jawab Manggada. Namun kemudian anak muda itupun berkata ”Tetapi aku mohon paman dan Delima tidak mengabarkan kepada siapapun, bahwa kami sudah mengetahui kedatangan gerombolan itu. Ki Warana sampai sekarang masih mengambil jarak dari gerombolan itu. Ki Warana masih berusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan gerombolan itu.”
Ki Krawangan mengangguk-angguk. Katanya, ”Baiklah. Aku akan memperhatikan pesan itu. Mudah-mudahan Warana dapat menempatkan dirinya dalam satu tatanan baru yang terjadi di padepokan itu.”
Manggada lah yang kemudian menyampaikan kepada Ki Krawangan, bahwa sampai saat terakhir, Ki Warana masih menyatakan kepada orang-orang dari gerombolan itu bahwa Kiai Banyu Bening masih hidup.
“Apakah Warana sudah berhubungan dengan mereka?” bertanya Ki Krawangan.
“Mereka telah mengirimkan utusan ke padepokan. Mereka adalah orang-orang yang mendendam Kiai Banyu Bening.”
“Aku tidak mengerti maksud Warana. Seandainya ia mengatakan bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada lagi, bukankah tidak akan terjadi permusuhan lagi.”
“Tetapi mereka tidak hanya mendendam kepada Kiai Banyu Bening. Tetapi mereka ingin mengambil padepokan itu.”
Ki Krawangan mengangguk-angguk. Sementara itu Manggada pun berkata, ”Tetapi sekali lagi kami berpesan, Biarlah persoalan itu menjadi persoalan Ki Warana dengan orang-orang gerombolan itu.”
Ki Krawangan masih mengangguk-angguk. Sementara Manggada merasa bahwa ia tidak akan dapat menceriterakan semuanya kepada Ki Krawangan dalam waktu yang singkat.
Ketika Manggada menggamit Laksana untuk minta diri, ternyata Laksana tidak menanggapinya. Ia masih saja berbicara tentang kemungkinan buruk yang dapat terjadi, jika Delima dan kawan-kawannya turun ke tepian.
Namun dalam pada itu, Ki Krawangan pun berkata kepada Delima ”Delima. Kau dapat membuat minuman untuk tamu-tamumu.”
“Tidak usah, paman. Tidak usah.” sahut Laksana dengan serta merta ”Masih ada beberapa pesan lagi buat Delima.”
Ki Krawangan tersenyum. Katanya ”Biarlah nanti setelah menghidangkan minuman, Delima mendengarkan pesan-pesan itu lagi.”
Ternyata Manggada dan Laksana berada di rumah Ki Krawangan untuk waktu yang agak lama. Mereka menunggu minuman menjadi dingin. Kemudian menghirupnya dengan gula kelapa, dan bahkan kemudian telah dihidangkan pula beberapa potong makanan.
Namun Manggada lah yang menjadi gelisah. Ketika ia mendapat kesempatan, iapun berbisik, “Kita harus segera kembali. Kita akan masuk kedalam sanggar bersama anak-anak muda itu.”
Tetapi Laksana berdesis, ”Sekali-sekali kita dapat melepaskan ketegangan-ketegangan yang setiap hari memburu kita. Sebelum kita benar-benar harus bertempur, sebaiknya kita beristirahat barang satu hari.”
Manggada hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat memaksa Laksana untuk segera kembali ke padepokan. Baru setelah beberapa kali Manggada memperingatkan, maka akhirnya Laksana pun bersedia pula meninggalkan rumah Delima itu.
Di perjalanan kembali, Manggada masih saja bersungut-sungut. Mereka telah kehilangan waktu beberapa lama. Seharusnya mereka sudah berada diantara anak-anak muda yang sedang dengan bersungguh-sungguh menempa diri itu. Tetapi Laksana hanya tersenyum-senyum saja menanggapi sikap kakak sepupunya itu.
Keduanya sempat menjadi berdebar-debar ketika mereka di tengah-tengah bulak bertemu dengan dua orang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Menilik sikap dan cara mereka mengenakan pakaiannya, maka keduanya tentu bukan orang yang tinggal disisi Barat kaki Gunung Lawu itu. Tetapi Manggada dan Laksana tidak ingin membuat persoalan. Karena itu, maka ketika mereka berpapasan dengan kedua orang itu, keduanya lebih baik menepi.
Kedua orang yang berpapasan dengan Manggada dan Laksana itu juga masih muda sebagaimana Manggada dan Laksana. Nampaknya keduanya merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang pantas dihormati. Ketika mereka berpapasan dengan Manggada dan Laksana, keduanya sama sekali tidak mau bergeser menepi sedikitpun, sehingga Manggada dan Laksana lah yang harus minggir sehingga keduanya melipir tanggul parit yang membujur sepanjang jalan itu.
“Gila.” geram Laksana ”Jika saja padepokan itu tidak sedang dalam ketegangan.”
“Lalu, mau kau apakan mereka?” bertanya Manggada.
“Aku akan memilin leher mereka.”
Manggada tertawa. Katanya ”Sudahlah. Saat ini kita memang harus memusatkan perhatian kita kepada gerombolan yang dipimpin oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari itu.”
“Keduanya tentu para pengikut Kiai Narawangsa itu pula.”
“Aku juga menduga demikian” sahut Manggada.
“Bagaimana jika kita tantang saja mereka, mumpung tidak nampak ada orang disawah.”
“Kiai Lemah Teles dan Ki Warana belum membunyikan pertanda perang. Kita harus bersabar.”
“Apapun yang terjadi jika kita menantang kedua orang itu, tidak akan mempengaruhi persoalan yang tumbuh antara para pengikut Kiai Narawangsa dengan orang-orang padepokan.”
“Biarlah segalanya tertimbun pada benturan yang tentu akan terjadi pada satu hari. Mungkin besok, lusa atau mungkin sepekan lagi. Tetapi tentu tidak akan terlalu lama.”
Tiba-tiba saja Laksana itu berhenti. Ketika ia berpaling, punggung kedua orang anak muda itu masih nampak.
“Apakah mereka akan pergi ke rumah Delima?”
“Kau jangan menjadi gila seperti itu” desis Manggada. Lalu katanya ”Bahkan aku ingin memperingatkanmu, agar kau tidak terlalu dekat dengan Delima.”
“Kenapa?” bertanya Manggada.
“Mungkin tidak apa-apa bagimu sendiri. Tetapi sudah berapa kali terjadi kau memuji kecantikan seorang gadis. Nah, bukankah akhirnya kau terus pergi meninggalkan mereka itu?”
Laksana mengerutkan dahinya.
“Jika pada suatu saat tumbuh perasaan yang mendalam di hati seorang gadis, sedangkan pada satu saat kita harus melanjutkan perjalanan pengembaraan ini sebelum kita benar-benar pulang, kau dapat mengira-ngirakan, apa yang akan terjadi dengan gadis itu selanjutnya.”
Laksana tidak menjawab. Tetapi kata-kata Manggada itu menyentuh hatinya pula. Sementara itu, Manggada pun berkata pula, ”Kecuali jika kau sudah jemu mengembara dan ingin menetap disatu tempat.”
Laksana menarik nafas dalam-dalam. Memang tidak terbersit dihatinya, bahwa ia ingin segera menghentikan pengembaraannya. Namun Manggada tidak ingin memperpanjang persoalan itu. Ia menyerahkan segala sesuatunya kepada Laksana, karena ia tahu, bahwa Laksana pun sudah menjadi dewasa. Laksana mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab.
Demikianlah, mereka berdua pun kemudian berjalan semakin cepat menuju ke padepokan. Ketika keduanya kemudian memasuki regol padepokan, Ki Pandi yang duduk di pendapa bangunan utama padepokan itu menarik nafas dalam-dalam. Iapun kemudian bangkit berdiri menyongsong kedua orang anak muda itu.
“Aku sudah berdebar-debar. Rasa-rasanya kalian pergi terlalu lama. Kami disini terpengaruh oleh ketegangan suasana dengan kedatangan para pengikut Kiai Narawangsa itu. Dan bahkan mungkin Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sendiri juga sudah ada ditempat itu.”
“Maaf, Ki Pandi.” Laksana lah yang menjawab ”Ki Krawangan telah menghidangkan makanan dan minuman, sehingga kami tidak dapat meninggalkannya begitu saja.”
“Sudahlah. Tidak apa-apa. Hanya kecemasan seorang tua.”
Kedua orang anak muda itupun kemudian langsung pergi menemui kelompok-kelompok yang berlatih di bawah bimbingan mereka. Tetapi keduanya tertegun, karena anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu sedang berlatih bersama orang-orang tua yang berilmu tinggi di padepokan itu. Ki Sambi Pitu, Ki Jagaprana, Ki Lemah Teles dan Ki Ajar Pangukan sedang sibuk menjajagi kemampuan anak-anak muda yang untuk waktu yang sangat singkat mencoba untuk menyadap ilmu kanuragan dari Manggada dan Laksana.
Ternyata orang-orang tua itu merasa puas dengan kemajuan yang telah mereka capai. Dengan tombak dan pedang dengan perisai atau tidak dengan perisai, anak-anak muda itu sudah mampu mempertanankan diri melawan berbagai macam senjata. Untuk beberapa lama penjajagan itu berlangsung. Manggada dan Laksana serta Ki Pandi berdiri saja mengamatinya.
“Sama sekali tidak mengecewakan.” desis Ki Pandi ”Jika jiwa kalian tidak dibakar oleh kemudaan kalian, mungkin anak-anak itu masih belum mampu mencapai tataran sebagaimana sekarang ini. Mereka telah bekerja dengan sangat keras untuk dapat menyesuaikan diri dengan keinginan kalian.”
Manggada dan Laksana tidak menjawab.
“Manggada dan Laksana!” berkata Ki Pandi kemudian ”Justru menjelang hari-hari yang gawat, yang tentu akan memaksa kita semua bekerja sangat-sangat keras, maka kalian harus mengurangi beban anak-anak itu. Biarlah mereka sempat beristirahat."
Manggada dan Laksana mengangguk-angguk.
Sementara Ki Pandi berkata selanjutnya ”Dari hari ke hari mereka nampak menjadi semakin kurus. Meskipun mereka tidak mengeluh, tetapi biarlah tubuh mereka menjadi semakin segar menjelang hari-hari yang mendebarkan itu.”
“Baiklah, Ki Pandi ” desis Manggada kemudian.
“Yang harus kalian pertahankan, adalah latihan-latihan ketahanan tubuh setiap mereka bangun pagi. Kemudian latihan-latihan olah senjata, setidak-tidaknya untuk mempertahankan tataran yang telah mereka capai. Kalian harus memberikan waktu beristirahat lebih banyak. Memberi kesempatan mereka untuk berbuat sesuatu sebagaimana anak-anak muda yang lain. Tidak semuanya dapat kalian ukur sebagaimana kalian sendiri.”
“Baik, Ki Pandi.” jawab Manggada dan Laksana.
Dalam pada itu, maka orang-orang tua yang berilmu tinggi di padepokan itu menganggap bahwa tingkat kemampuan anak-anak muda yang belum lama berada di padepokan itu sudah cukup memadai diukur dari waktu yang mereka pergunakan untuk belajar dan berlatih. Apalagi yang memimpin mereka juga anak muda yang umurnya tidak terpaut banyak dengan mereka.
Beberapa saat kemudian, maka latihan latihan itupun berakhir. Semuanya menganggap bahwa latihan yang telah mereka lakukan sangat baik. Kemampuan mereka sudah memadai, apalagi dilihat dari sisi waktu. Namun semuanya telah memberikan saran yang sama, bahwa anak-anak muda itu harus mendapat kesempatan untuk beristirahat lebih banyak tanpa mengabaikan latihan-latihan yang harus mereka lakukan untuk mengasah tajamnya kemampuan yang telah mereka miliki.
Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Orang-orang tua itu tentu memiliki pengalaman yang jauh lebih luas dari Manggada dan Laksana. Ketika kemudian Manggada dan Laksana berada diantara anak-anak muda itu, maka Manggada dan Laksana pun telah mengatakan kepada mereka, untuk mendapatkan tenaga yang sebesar-besarnya menjelang saat-saat yang paling gawat, maka kesempatan untuk beristirahat pun akan diberikan lebih banyak.
Namun keduanya masih menambahkan, bahwa hal itu bukan berarti bahwa latihan-latihan yang berat dan kerja yang keras sudah berakhir.
“Sementara itu di hutan tua, Kiai Natawangsa dan Nyai Wiji Sari telah bersiap menerkam kita.” berkata Manggada kepada anak-anak muda itu.
Sebenarnyalah saat itu Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari telah berada diantara para pengikutnya di hutan yang sebelumnya memang telah dipersiapkan. Ternyata keduanya tidak mempunyai pendirian sebagaimana orang yang berilmu tinggi di padepokan, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari tidak menganggap landasan yang dibangun itu terlalu dekat dengan padepokan yang akan menjadi sasaran mereka.
Bahkan Kiai Narawangsa berkata, ”Kalian memang memiliki ketajaman penalaran. Tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk meloncat ke padepokan itu. Tidak terlalu jauh dan cukup terlindung dari penglihatan orang-orang padepokan.”
“Bukankah kita tidak berniat untuk berlindung.” berkata Nyai Wiji Sari ”Kita justru akan datang ke padepokan itu dan menuntut agar padepokan itu diserahkan kepada kita.”
“Tetapi kita tidak boleh tergesa-gesa Nyai.” jawab Kiai Narawangsa ”segala sesuatunya harus diperhitungkan sebaik-baiknya, agar kita dapat mencapai hasil sebagaimana kita kehendaki.”
“Apalagi yang harus diperhitungkan?” Nyai Wiji Sari memang tidak sabar lagi ”Kita datangi padepokan itu. Kita hancurkan pintu-pintunya. Kemudian kita menyerbu masuk.”
“Bagaimana dengan rencana kita untuk datang menemui Banyu Bening?”
“Apakah ada gunanya?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Mudah-mudahan masih ada gunanya. Jika Banyu Bening dapat mencegah pertempuran, maka ia akan mendapat kesempatan untuk hidup beberapa lama lagi.”
“Apakah ukurannya waktu yang kau katakan tidak lama lagi itu?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Sampai kita menjadi jemu dan kemudian membunuhnya,” jawab Narawangsa.
“Akhirnya sama saja. Kenapa tidak kita bunuh sekarang?”
“Jika ia dapat mencegah perang, bukankah orang-orang kita tidak banyak yang akan mati? Sementara itu, kita akan menangkap Banyu Bening dan terserahlah kepada kita. Tetapi para pengikutnya tentu sudah terpecah bercerai berai dan tidak akan mampu menyusun kekuatan lagi untuk melawan kita.”
Nyai Wiji Sari merenung sejenak. Namun ada sesuatu yang terasa bergejolak dihatinya. Nyai Wiji Sari sendiri tidak tahu, apakah yang mengekang perasaannya untuk datang menemui Kiai Banyu Bening dan berbicara dengan laki-laki itu. Bagi Nyai Wiji Sari, datang dengan pasukan dan bertempur, akan lebih baik daripada harus datang menemuinya dan berbicara dengannya.
“Aku muak melihat laki-laki itu.” geram Nyai Wiji Sari.
Tetapi kata-kata yang terlontar disela-sela bibirnya itu tidak meyakinkan dirinya sendiri. Bahkan didalam lubuk hatinya telah timbul pertanyaan, ”Apakah bukan karena sebab lain?”
Nyai Wiji Sari menggeretakkan giginya. Ia mencoba mengusir sentuhan-sentuhan perasaan yang dianggapnya sebagai satu kelemahan justru karena ia seorang perempuan. Bagaimanapun juga Kiai Banyu Bening adalah bekas suaminya dan yang pernah memberinya seorang anak. Tetapi anak itu meninggal, justru karena terbakar.
Kiai Narawangsa melihat keragu-raguan yang sangat di wajah Nyai Wiji Sari. Tetapi menurut tanggapan Kiai Narawangsa justru karena Wiji Sari itu sangat membenci suaminya. Ketika Nyai Wiji Sari itu masih menjadi istri Lembu Wirid, ia sudah membencinya. Apalagi kemudian setelah anaknya terbunuh didalam lidah api yang menyala menelan rumahnya.
“Terserah kepadamu.” berkata Kiai Narawangsa ”Jika kau berkeberatan, maka aku akan menurut, mana yang kau anggap lebih baik. Jika aku berniat untuk datang menemuinya, itu karena kita pernah merencanakannya.”
“Tidak. Aku tidak mau menemui laki-laki keparat itu.” geram Nyai Wiji Sari. Hampir berteriak iapun berkata ”Tidak. Aku muak. Muak sekali.”
“Baik. Baik.” berkata Kiai Narawangsa ”Kita akan langsung datang ke padepokan itu dengan seluruh kekuatan kita. Kita akan membakar pintu-pintunya dan menerobos masuk kedalamnya.”
“Aku sudah menyiapkan beberapa bakul biji jarak. Beberapa bakul yang lain sudah dihancurkan menjadi bubuk kasar yang dicampur dengan serat yang sudah dikeringkan.“
“Apakah serbuk dan biji jarak itu cukup banyak untuk membakar pintu gerbang dan pintu butulan?”
“Tentu. Kita akan menimbun kayu-kayu kering diluar pintu itu untuk mempercepat nyala api. Jika daun pintu gerbang itu terbakar, maka kita akan segera dapat menerobos masuk.”
“Baiklah. Kita harus menyiapkan gerobak-gerobak kecil untuk mengusung kayu, serbuk biji jarak dan biji jarak itu.”
“Besok kita akan melihat pintu gerbang itu,” berkata Kiai Narawangsa.
Sebenarnyalah dihari berikutnya, Kiai Narawangsa dan Gunasraba berserta beberapa orang pengiringnya telah mendatangi padepokan. Berkuda mereka tanpa ragu-ragu mendekati rintu gerbang padepokan itu dari arah depan. Beberapa puluh langkah mereka menghentikan kuda mereka. Para petugas di panggungan disebelah menyebelah pintu gerbang itu melihat kedatangan beberapa orang berkuda.
Namun mereka mengerti, bahwa serangan yang sebenarnya masih belum datang, karena jumlah orang berkuda itu tidak lebih dari sepuluh orang. Meskipun demikian, para petugas itu telah memberikan laporan langsung kepada Ki Lemah Teles tanpa membunyikan kentongan.
Orang-orang tua yang berilmu tinggi, yang ada di padepokan itu telah memanjat panggungan yang ada disebelah menyebelah pintu gerbang itu. Tetapi merekapun berpendapat, bahwa orang-orang itu masih belum akan berbuat sesuatu.
“Mungkin mereka akan menemui orang yang bernama Kiai Banyu Bening itu” berkata Ki Lemah Teles.
Tetapi ternyata tidak. Ternyata mereka tidak menyatakan maksudnya itu. Beberapa orang itu hanya berkeliaran hilir mudik diatas punggung kuda mereka sambil mengamat-amati pintu gerbang.
“Mereka sedang memperhitungkan kemungkinan untuk merusak pintu gerbang itu.” desis Ki Ajar Pangukan.
“Ya. Tetapi mereka tidak dapat menghitung ketebalan daun pintu gerbang itu. Mereka juga tidak dapat menduga, seberapa besarnya selarak pintu itu.”
Namun diluar, Kiai Narawangsa berkata, ”Pintu itu dibuat dari kayu.”
“Kita akan dapat membakarnya.” berkata Gunasraba.
“Kau yakin biji jarakmu itu cukup untuk menyalakan pintu gerbang itu?”
“Tentu kakang.” jawab Gunasraba ”Pintu gerbang itu akan menjadi abu. Dan kita akan dapat dengan leluasa masuk kedalamnya. Kita bukan orang dungu yang mau membuang-buang waktu dan bahkan nyawa dengan memanggul balok kayi yang besar untuk menghantam dan merobohkan pintu gerbang itu. Selama kita hilir mudik mengambil ancang-ancang, maka anak panah orang-orang diatas panggungan itu sudah menghujani kita.”
“Jika kita membakar pintu itu, bukankah mereka juga dapat membunuh kita dengan anak panahnya?”
“Tetapi kita tidak memerlukan banyak orang. Empat orang menaburkan serbuk yang bercampur serat itu serta biji jarak sementara lima atau enam orang melindunginya dengan perisai. Sementara itu, orang-orang kita akan melontarkan serangan anak panah pula dari tempat kita ini untuk mengurangi tekanan mereka terhadap orang-orang kita yang sedang membakar pintu gerbang itu."
Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Iapun yakin bahwa rencana adiknya itu tentu akan dapat dilakukan. Biji jarak memang mengandung minyak yang dapat dipergunakan sebagai oncor di malam hari.
Sementara itu, orang-orang yang berada dipanggungan di sebelah-menyebelah pintu gerbang itu memperhatikan orang-orang berkuda itu dengan saksama. Tetapi mereka tidak dapat mengerti, apa yang akan mereka lakukan. Mereka hanya melihat orang-orang itu menunjuk kearah pintu gerbang, kearah panggungan disebelah-menyebelah pintu gerbang itu serta sekali-sekali memperhatikan keadaan di sekitarnya.
Tetapi orang-orang itu tidak hanya memperhatikan pintu gerbang utama. Ternyata mereka juga memperhatikan pintu-pintu butulan. Kuda-kuda itu berlari-lari melingkari padepokan yang terhitung luas itu.
“Mereka sedang mencari cara yang paling baik untuk merusak pintu.” berkata Ki Ajar Pangukan.
“Kita akan melayani, cara apa saja yang akan mereka pergunakan.” desis Ki Sambi Pitu.
Ki Lemah Teles dan Ki Warana memperhatikan orang-orang itu dengan saksama. Beberapa saat lamanya beberapa orang berkuda itu hilir mudik di sekitar padepokan. Namun akhirnya kuda-kuda itu berlari meninggalkan padepokan itu.
Orang-orang tua yang berilmu tinggi, yang melihat beberapa orang berkuda itupun menyadari, bahwa Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari ternyata cukup berhati-hati. Mereka tidak langsung datang menyerang, tetapi mereka telah mencoba untuk melihat sasaran untuk membuat perhitungan yang lebih mantap.
“Seorang diantara mereka itu adalah Kiai Narawangsa sendiri.” desis Ki Warana.
“Ya!” Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk ”menurut utusannya yang terdahulu, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi.”
“Yang manakah diantara mereka yang kau maksud Ki Narawangsa itu?” bertanya Ki Lemah Teles.
“Yang bertubuh raksasa. Yang tidak mengenakan ikat kepalanya, tetapi hanya disangkutkan dilehernya sedang jika kita sempat melihat lebih dekat, maka kita akan melihat segores luka diwajahnya.”
Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Seorang diantara orang-orang berkuda itu adalah seorang yang bertubuh raksasa. Ikat kepalanya disangkutkan dibahunya, sementara itu rambutnya yang ikal dan panjang itu disanggulnya agak tinggi. Kiai Narawangsa ditilik dari ujud lahiriahnya memang sangat meyakinkan. Jika ia kemudian datang untuk menantang Kiai Banyu Bening, Kiai Narawangsa itu tentu memiliki keyakinan diri yang tinggi.
Kehadiran orang-orang berkuda itu, telah memperingatkan kepada Ki Lemah Teles, Ki Warana dan orang-orang tua yang berilmu tinggi, agar mereka menjadi lebih berhati-hati menghadapi lawan yang membuat perhitungan-perhitungan yang cermat.
Ketika sekelompok orang berkuda itu telah hilang dari penglihatan mereka, maka Ki Warana dan orang-orang tua yang berilmu tinggi itupun duduk di pendapa bangunan induk padepokan itu untuk berbincang tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
Seorang cantrik yang bertugas di panggungan itu bertanya kepada kawannya ”Apa kira-kira yang akan mereka lakukan?"
“Mereka tentu merencanakan untuk memecahkan pintu gerbang itu.” jawab kawannya.
“Aku tahu. Tetapi bagaimana caranya?” kawannya membentak.
Cantrik itu tertawa. Katanya ”Kenapa kau tiba-tiba menjadi uring-uringan?”
Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya bertanya lagi.
Dipendapa, orang-orang berilmu tinggi itu juga menduga-duga. Cara apakah yang akan ditempuh oleh Kiai Narawangsa untuk membuka pintu gerbang padepokan itu. Tetapi yang mereka sebutkan adalah cara-cara yang sering dipergunakan untuk memecahkan pintu. Tidak seorangpun diantara mereka yang menduga, bahwa Kiai Narawangsa akan memecahkan pintu gerbang itu dengan cara yang lain. Api.
Sementara itu, di dalam hutan tempat Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari menunggu kesempatan, Gunasraba telah mempersiapkan segala-galanya. Seonggok serat kulit kayu yang kering, telah dicampur serbuk biji jarak. Selain itu telah dipersiapkan pula biji jarak yang cukup banyak. Untuk meyakinkan diri, maka Gunasraba itu pun telah menyediakan minyak kelapa yang cukup, yang akan dituang pada onggokan-onggokan serat kayu yang Kering itu.
“Pintu gerbang itu tentu akan terbakar.” geram Gunasraba.
“Bukankah kau akan membakar semua pintu,” bertanya Kia Narawangsa.
“Ya. Semua pintu. Gerbang utama dan gerbang-gerbang butulan. Seperti yang kita ketahui, ada empat pintu butulan."
Cara yang dipilih oleh Gunasraba itu memang tidak dapat dilakukan dengan serta-merta. Tetapi mereka harus menunggu api yang dinyalakan itu menjadi besar. Baru kemudian api itu akan membakar pintu gerbang yang terbuat dari kayu itu.
“Kita memang harus sedikit bersabar!” berkata Gunasraba ”tetapi cara ini adalah cara yang akan menelan korban paling sedikit.
Namun dalam pada itu, Nyai Wiji Sari nampaknya menjadi semakin tidak sabar. Perempuan itu menjadi semakin banyak merenung. Wajahnya nampak muram dan tingkah lakunya yang gelisah. “Aku tidak dapat duduk disini berhari-hari tanpa berbuat apa-apa berkata Nyai Wiji Sari itu.
“Kami sedang mempersiapkan segala-galanya Nyai” jawab Kiai Narawangsa, ”kami tidak ingin gagal.”
“Apa sebenarnya yang mencemaskan kita? Kita akan menghancurkan Lembu Wirid itu. Jika orang itu mati, maka para pengikutnya tentu akan segera menyerah.”
“Aku mengerti.” jawab Kiai Narawangsa ”Tetapi bukankah kita perlu memikirkan cara agar kita dapat masuk dan berhadapan dengan Kiai Banyu Bening?”
Nyai Wiji Sari tidak menyahut lagi. Namun wajah masih saja nampak gelap. Sebenarnya semakin lama Nyai Wiji Sari berada di hutan itu, kegelisahan terasa semakin mencengkamnya. Rasara-sanya ia sudah mendengar tangis anaknya yang melengking-lengking dibalik dinding padepokan itu.
Tetapi Nyai Wiji Sari rasa-rasanya juga selalu dibayangi oleh wajah Lembu Wirid. Wajah yang keras seorang laki-laki. Dalam kegelisahannya itu, kadang-kadang masih juga timbul pertanyaan, kenapa waktu itu ia telah tergelincir untuk menerima Narawangsa memasuki lingkungan dinding ruang tidurnya.
“Itulah awal bencana ini” Nyai Wiji Sari merintih didalam hatinya.
Tetapi hati Nyai Wiji Sari yang gelap itu tidak melihat jalan penyelesaian yang terbaik yang dapat ditempuhnya. Ketika kerinduannya kepada seorang anak memuncak, maka perempuan itu telah menyalurkan gejolak perasaannya itu dengan caranya yang keras dan kasar, sebagaimana cara hidup yang dijalaninya.
“Tetapi bukan aku yang ingin membunuh Lembu Wirid” perasaan Nyai Wiji Sari melonjak ”Aku hanya ingin mengambil apa yang masih tersisa dari anakku.”
Tetapi Nyai Wiji Sari tidak dapat mengatakannya kepada Kiai Narawangsa. Jika hal itu dikatakannya, maka Kiai Narawangsa akan dapat menjadi salah paham. Sementara itu, Nyai Wiji Sari tidak ingin merusak hidup kekeluargaannya sekali lagi. Meskipun selama itu ia berada dijalan kehidupan yang gelap serta membina keluarga yang kelam pula, namun Nyai Wiji Sari itu ingin mempertahankannya.
Dalam pada itu, segala persiapan pun telah dilakukan. Gunasraba telah yakin, bahwa ia akan dapat membuka pintu, gerbang itu dengan caranya...
Selanjutnya,
MATAHARI SENJA BAGIAN 19
MATAHARI SENJA BAGIAN 19