Matahari Senja
Bagian 17
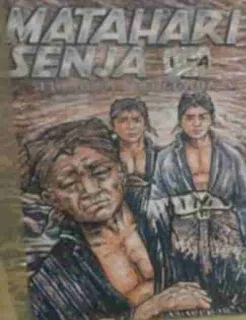
KELIMA orang itu menempuh perjalanan yang jauh. Tetapi perjalanan mereka tidak banyak dibayangi bahaya, karena mereka tidak mempunyai tugas lain kecuali melihat-lihat padepokan di kaki Gunung Lawu itu.
Dalam pada itu. orang-orang yang berada di padepokan di kaki Gunung Lawu itu masih saja menempa diri. Mereka memanfaatkan waktu degan sebaik-baiknya. Mereka yang tidak pergi ke sawah, telah masuk kedalam sanggar. Mungkin sanggar tertutup, mungkin sanggar terbuka. Orang-orang yang umurnya sudah menjelang senja itu dengan tekun membimbing mereka pula.
“Apa yang dapat kita lakukan harus kita lakukan pada masa-masa senja ini” berkata Ki A jar Pangukan.
Ki Lemah Teles tertawa. Katanya ”Meskipun menjelang senja, kita tetap matahari.”
“Ya” Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. ”Sinar matahari senja masih dapat membakar langit.”
Ki Pandi tertawa pula. Katanya ”Jangan takut kehilangan panas jika api kalian telah menyalakan sebukit karang sehingga membara.”
“Tidak cukup!” teriak Ki Lemah Teles ”Panas cahaya matahari senjamu harus membuat bulan, bintang dan semua langit membara sampai saatnya terbit matahari baru.”
Ki Jagaprana tertawa berkepanjangan. Katanya ”Apakah matahari-matahari kini pandai bermimpi.”
“Bukan mimpi...” teriak Ki Lemah Teles ”Apimu lah yang akan segera padam didalam mimpi burukmu.”
“Kau akan menantang berperang tanding?” bertanya Ki Pandi.
“Bongkok edan!” geram Ki Lemah Teles. Mereka pun tertawa. Sementara Ki Lemah Teles melangkah meninggalkan mereka.
Tetapi langkahnya terhenti ketika Ki Pandi berkata, ”He, kau akan kemana? Berilah perintah-perintah. Kau sekarang memimpin padepokan ini bersama Ki Warana.”
“Perintah apa yang dapat aku berikan kepada matahari yang mulai redup sebelum senja?”
Ki Lemah Teles tidak menghiraukan orang-orang tua itu tertawa berkepanjangan. Ki Warana menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin dapat berbuat sebagaimana orang-orang tua itu. Sempat tertawa dan memandang kehidupan tanpa dibebani oleh berbagai macam persoalan yang menekan. Tetapi ia tidak dapat ingkar, bahwa ia harus bekerja keras untuk menyusun kembali tatanan kerja dan hubungan di padepokan itu.
Dari hari ke hari, kesibukan di padepokan itu menjadi semakin meningkat. Beberapa orang anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu justru menyatakan diri untuk ikut menimba ilmu di padepokan itu. Mereka dan orang-orang tua mereka kemudian mengetahui, bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar di padepokan itu.
Ki Warana telah menyatakan, bahwa sanggar-sanggar yang terdapat di padukuhan-padukuhan tidak mempunyai arti lagi. “Jika sanggar itu ingin tetap ada di padukuhan, maka gunanya sudah berbeda sama sekali.”
Perubahan-perubahan yang meyakinkan itulah, yang membuat orang-orang padukuhan mempercayakan beberapa orang anak muda mereka menyatakan diri untuk tinggal di padepokan. Mereka bukan saja ingin mendapatkan tuntunan dalam olah kanuragan. Tetapi di padepokan mereka juga ingin menyadap pengetahuan tentang bercocok tanam, berternak dan mengenali musim. Mereka juga ingin dapat membaca huruf-huruf serta menangkap maksudnya.
Tetapi Ki Warana telah memberitahukan kepada mereka dan orang tua mereka, bahwa, padepokan itu masih berada dalam keadaan bahaya. “Aku tidak ingin mereka terbakar dalam api permusuhan begitu mereka memasuki padepokan kami,” berkata Ki Warana kepada anak-anak muda itu serta orang tua mereka.
Beberapa orang memang menjadi ragu-ragu. Tetapi beberapa orang yang lain berkata, ”Kami siap menjalani tugas apapun juga.”
Ki Warana justru menjadi terharu. Ia merasakan sambutan yang hangat dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu, setelah berhasil merombak alasnya sampai ke dasar. Ketika hal itu dibicarakannya dengan Ki Lemah Teles, maka Ki Lemah Teles pada dasarnya sejalan dengan pikiran Ki Warana. Sebaiknya anak-anak muda itu tidak memasuki padepokan justru pada saat yang gawat.
“Mereka belum mempunyai bekal apa-apa” berkata Ki Lemah Teles.
Tetapi ternyata beberapa orang anak muda justru bersedia mengalami akibat apapun. Terutama dari padukuhan terdekat yang telah menjadi landasan perlawanan Ki Warana terhadap Panembahan Lebdagati dan Lembu Palang.
“Kami sudah mempunyai pengalaman.” berkata beberapa orang anak muda itu.
Ki Warana memang tidak dapat menolak mereka. Jika Ki Warana tidak mau menerima mereka, maka akan dapat terjadi salah paham, seakan-akan setelah Ki Warana merebut kembali padepokannya, maka ia telah menolak kehadiran anak-anak muda itu di padepokannya.
“Apa boleh buat.” berkata Ki Lemah Teles. ”Mereka memang sudah mempunyai sedikit pengalaman.”
“Tetapi dengan demikian, kita tidak akan dapat menolak kehadiran anak-anak muda dari padukuhan yang lain.”
Ki Lemah Teles menarik nafas dalam-dalam. Katanya ”Anak-anak yang baru sama sekali itu justru akan dapat menjadi beban.”
“Tetapi mereka akan menganggap kita menjauhi sebuah padukuhan tetapi mendekati padukuhan yang lain.”
“Ki Warana!” berkata Ki Lemah Teles ”Beri mereka penjelasan sekali lagi, bahwa padepokan ini masih dibayangi oleh pertentangan dan perselisihan. Sehingga dengan demikian kita dapat membagi tanggung-jawab.”
Ki Warana mengangguk-angguk. Katanya ”Baik, Ki Lemah Teles. Aku akan menjelaskan kepada anak-anak muda itu serta orang tuanya, bahwa pertentangan dan perselisihan itu akan dapat membuahkan kematian.”
Dengan penjelasan itu, memang ada beberapa orang anak muda yang mengurungkan niatnya, tetapi ada pula diantara mereka yang dengan tekad bulat bergabung dengan para cantrik dari padepokan yang telah memperbaharui pijakannya itu.
“Kami akan membuka kesempatan seluas-luasnya setelah keadaan benar-benar menjadi tenang.” berkata Ki Warana.
Namun mereka yang tidak menunda keinginannya untuk bergabung dengan para cantrik di padepokan itu, Ki Warana telah menaruh perhatian lebih besar daripada para cantrik yang lain.
“Kami serahkan mereka kepada kalian berdua ngger.” berkata Ki Warana kepada Manggada dan Laksana.
“Tetapi apa yang dapat kami berikan kepada mereka?” bertanya Manggada ”Pengetahuan dan ilmuku masih terlalu dangkal.”
“Tidak. Ilmu dan pengetahuan kalian jauh lebih baik dari ilmu dan pengetahuanku. Karena itu, aku serahkan mereka kepada angger berdua untuk dapat meletakkan dasar-dasar secara umum. Pada perkembangannya nanti, biarlah Ki Lemah Teles yang mengatur mereka.”
Manggada dan Laksana tidak dapat menolak. Ketika hal itu dikatakan kepada Ki Pandi, ternyata Ki Pandi sependapat. Katanya, ”Kalian tentu dapat melakukannya.”
Tetapi Ki Pandi menasehatkan, agar semua latihan dilakukan didalam padepokan. “Mungkin para pengikut Kiai Narawangsa selalu mengamati padepokan ini. Karena itu, maka mereka jangan melihat persiapan-persiapan yang dilakukan di padepokan ini.”
Sesuai dengan tugas yang diserahkan kepada Manggada dan Laksana, maka kedua anak muda itupun segera mulai melakukannya. Anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu mendapat kesempatan terbanyak untuk melakukan latihan-latihan. Mereka tidak segera diserahi tugas untuk ikut memelihara sawah dan pategalan. Yang penting bagi mereka adalah menempa diri dalam olah kanuragan.
Apalagi keadaan padepokan yang masih selalu dibayangi oleh perselisihan yang berkepanjangan Setiap hari. Manggada dan Laksana memasuki sanggar terbuka bergantian. Keduanya telah membagi anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu menjadi dua kelompok yang besar. Kemudian kelompok-kelompok itu dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil.
Setiap hari, di dini hari, anak-anak muda itu harus sudah bangun. Setelah berbenah diri. mereka segera memasuki latihan-latihan pagi. Mereka memanasi tubuh mereka dengan gerakan-gerakan yang khusus. Kemudian berlari-lari memutari halaman dan kebun padepokan. Jika kelompok yang dipimpin oleh Manggada berlatih disanggar terbuka, maka Laksana melakukannya di halaman. Demikian sebaliknya.
Setelah sepekan mereka melakukan latihan-latihan gerak dasar, maka Manggada dan Laksana mulai mengajari mereka cara memegang berbagai jenis senjata. Mula-mula anak-anak muda itu berlatih memegang tombak dan melakukan gerak-gerak dasar. Kemudian mereka mulai berlatih memegang pedang dan perisai.
Untuk memburu waktu yang sempit, maka Manggada dan Laksana menekankan kemampuan anak-anak muda yang menjadi penghuni baru dari padepokan itu bermain dengan tombak pendek dan pedang dengan perisainya.
“Kalian tidak perlu menjelajahi berbagai macam senjata. Yang penting dalam waktu yang pendek ini kalian mampu mempergunakan tombak pendek dan pedang dengan perisainya,” berkata Manggada dan Laksana kepada anak-anak muda itu.
Namun anak-anak muda itu juga diajarinya mempergunakan tombak pendek dan pedang untuk melawan berbagai macam senjata. Mereka berlatih melawan orang yang bersenjata kapak. Berlatih melawan orang yang mempergunakan trisula, canggah, bindi atau cambuk.
Latihan-latihan yang dilakukan oleh para penghuni padepokan itu memang tidak dapat dilihat dari luar. Baik anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu, maupun mereka yang sudah berada di padepokan itu sejak padepokan itu dipimpin oleh Kiai Banyu Bening.
Jika ada empat atau lima orang penghuni padepokan itu yang pergi keluar, mereka tentu membawa cangkul atau bajak atau garu dengan sepasang kerbau untuk dipekerjakan di sawah. atau pategalan di seputar padepokan itu.
Dalam pada itu, ternyata Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari juga tidak segera mendatangi padepokan yang dipimpin oleh Ki Lemah Teles itu. Kecuali mereka juga ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mereka masih merasa sayang untuk meninggalkan lingkungannya. Rasa-rasanya mereka masih memerlukan waktu beberapa lama untuk menguras harta-benda yang ada di lingkungannya yang cukup luas itu.
Namun dalam pada itu, orang-orang yang ditugaskan oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sudah berada di kaki Gunung Lawu. Mereka mencoba mengamati padepokan yang mereka sangka masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening itu. Justru karena mereka menganggap bahwa padepokan itu memang masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening.
Maka mereka sama sekali tidak berusaha lagi untuk meyakinkannya lagi. Bahkan kelima orang itu sama sekali tidak mencoba berhubungan dengan orang-orang padukuhan. Jika mereka melakukannya, maka mungkin sekali kedatangan mereka akhirnya diketahui oleh orang-orang padepokan.
Karena itu, maka mereka hanya sekedar melakukan pengamatan dari kejauhan. Meskipun kelima orang itu tidak melihat kekuatan padepokan itu yang sebenarnya, tetapi mereka memang melihat kesiagaan yang mantap. Mereka melihat para cantrik yang mengawasi keadaan di sekeliling padepokan dari atas panggung dibelakang dinding. Bahkan mereka juga melihat, dua orang cantrik dengan tombak ditangan mengawal sebuah pedati yang penuh berisi hasil bumi yang dipetik di pategalan.
“Ternyata Kiai Banyu Bening adalah seorang yang sangat berhati-hati...” berkata salah seorang diantara mereka.
Setelah beberapa hari kelima orang itu mengadakan pengamatan, maka mereka mengambil kesimpulan, bahwa padepokan Kiai Banyu Bening adalah padepokan yang cukup tertib. Pemimpin kelompok itu pada hari-hari terakhir dari tugasnya ternyata atas gagasan sendiri ingin memasuki padepokan Kiai Banyu Bening itu.
“Apakah tidak akan membahayakan jiwa kita?” bertanya salah seorang dari mereka.
“Mungkin...” jawab pemimpin kelompok itu ”Tetapi dengan demikian, aku akan dapat melihat serba sedikit isi dari padepokan itu untuk menyesuaikan laporan kawan kita terdahulu, yang juga pernah datang menghadap Kiai Banyu Bening.”
“Tetapi menurut kawan kita itu, Kiai Banyu Bening adalah seorang yang tidak dapat diduga sifatnya. Namun ia adalah seorang yang mempunyai wibawa yang tinggi.”
“Jika aku tidak kembali setelah matahari sampai di puncak, sebaiknya kalian menyingkir dari tempat ini.” Berkata pemimpin kelompok itu.
“Apa yang akan kau katakan kepada Kiai Banyu Bening?” bertanya seorang kawannya.
“Aku akan memberikan peringatan, bahwa Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari dalam waktu dekat akan segera datang.”
“Hanya itu?”
“Ya. Hanya itu. Bukankah ini penting sekali bagi mereka?”
“Tetapi apakah hal itu dibenarkan oleh Kiai Narawangsa. Jika karena itu, Kiai Banyu Bening menyingkir, bukankah Kiai Narawangsa terutama, akan menjadi sangat marah, karena ia ingin membunuh saja Kiai Banyu Bening itu?”
“Kiai Banyu Bening menurut perhitunganku, tidak akan melarikan diri.”
Pemimpin kelompok itu kemudian memutuskan untuk benar-benar pergi ke padepokan. Ia mengajak salah seorang dari kawan-kawannya itu yang pernah datang ke tempat itu sebelumnya, meskipun orang itu juga tidak ikut memasuki padepokan pada waktu itu.
Dengan kesadaran yang tinggi atas akibat yang mungkin terjadi atas diri mereka, maka pemimpin kelompok itupun telah pergi ke padepokan bersama dengan seorang kawannya. Namun bagaimana pun juga orang itu merasa jantungnya berdetak lebih cepat.
Pemimpin kelompok yang orangnya berbeda dengan pemimpin kelompok yang datang terdahulu ke padepokan itu, memang seorang yang berani. Meskipun demikian, ketika ia melangkah menuju ke pintu gerbang, orang itu menjadi berdebar-debar pula.
Para petugas yang berada di panggungan di sebelah pintu gerbang itu telah melihat kedatangannya. Karena itu, maka petugas itupun kemudian berteriak bertanya, ”He, siapakah kalian dan untuk apa kalian datang kemari.”
Pemimpin kelompok itu memandang para petugas diatas panggungan itu. Dengan lantang ia justru bertanya ”Apakah aku harus berteriak pula?”
Petugas itu termangu-mangu sejenak. Nampaknya orang yang datang itu bukan orang-orang padukuhan atau orang-orang yang telah terbiasa dengan padepokan itu. Karena itu, maka para petugas itupun menjadi lebih berhati-hati. Seorang dari para petugas itupun telah menjawab, ”Ya. Berteriaklah.”
“Inikah cara padepokan ini menerima tamu?”
“Ya!” jawab petugas itu.
Pemimpin kelompok nu mulai merasa tersinggung. Tetapi ia harus menahan diri. Dengan lantang pula ia berkata ”Aku ingin menghadap Kiai Banyu Bening.”
Petugas itu ragu-ragu sejenak. Namun kemudian iapun berkata ”Tunggulah, aku akan melaporkannya. Tetapi kalian harus menjawab, siapakah kalian dan kalian datang dari mana.”
“Aku utusan dari Kiai Narawangsa.” jawab orang itu tanpa ragu-ragu. Bahkan ia mengucapkan nama itu dengan kebanggaan yang melonjak didalam dadanya. Menurut pendapatnya, nama Kiai Narawangsa akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi Kiai Banyu Bening.”
Nama itu memang menggetarkan dada petugas di panggungan. Karena itu, salah seorang petugas dipanggungan itu telah turun untuk melaporkan kedatangan utusan Kiai Narawangsa itu. Sementara petugas yang lain masih bertanya ”Kau datang untuk apa?”
“Aku akan bertemu dengan Kiai Banyu Bening.” “Keperluanmu apa?” bertanya petugas itu pula.
“Aku akan menyampaikan sendiri kepada Kiai Banyu Bening.”
“Aku tidak tahu, apakah Kiai Banyu Bening dapat menerimamu atau tidak.” jawab petugas itu. Ia sudah mengerti, bahwa Ki Ajar Pangukan lah yang telah berperan menjadi Kiai Banyu Bening ketika utusan Kiai Narawangsa yang terdahulu datang ke padepokan itu.
Namun orang yang berada di muka regol itu berteriak “Katakan kepada Kiai Banyu Bening bahwa aku utusan Kiai Narawangsa ingin bertemu.”
Petugas pintu jaga menemui Ki Warana untuk melaporkan kehadiran dua orang yang mengaku utusan dari Kiai Narawangsa. Ki Warana pun segera menemui Ki Lemah Teles dan Ki Ajar Pangukan untuk minta pertimbangan apakah yang sebaiknya dilakukan terhadap utusan itu.
“Mereka bukan orang-orang yang pernah datang kemari,” berkata Ki Warana, ”Para petugas itu tentu masih dapat mengenali kedua orang utusan Kiai Narawangsa yang terdahulu, karena kebetulan waktu itu mereka melihat langsung kedatangan kedua orang utusan itu.”
“Katakan, bahwa Kiai Banyu Bening baru beristirahat. Ia tidak dapat menerima kedua utusan itu. Tanyakan saja kepadanya, apakah keperluan mereka datang. Agaknya kita sudah dapat menebak, apa yang akan mereka katakan.”
Ki Waranapun mengangguk-angguk.
“Temuilah mereka!” berkata Ki Ajar Pangukan.
Ki Warana lah yang kemudian memerintahkan membuka regol depan setelah memerintahkan para penghuni padepokan yang tidak berkepentingan untuk menyingkir. Demikian pula anak-anak muda yang sedang berlatih bersama Manggada di halaman samping.
“Biarlah mereka melihat padepokan ini tidak terlalu ramai.” berkata Ki Warana.
Baru kemudian, setelah suasana di padepokan itu nampak lengang seperti yang dikehendaki oleh Ki Warana, para cantrik membuka pintu gerbang padepokan.
Sementara itu, kedua orang yang datang dari padepokan Kiai Narawangsa itu sudah menjadi tidak sabar. “Kenapa kalian mempermainkan kami?” bertanya yang tertua diantara kedua orang itu demikian pintu terbuka.
Tetapi orang yang membuka pintu itu mengerti, bahwa utusan Kiai Narawangsa itu ingin menggertaknya, sehingga karena itu, maka iapun justru bertanya, ”Apakah kami mempermainkan kalian?”
“Kalian sengaja tidak segera membuka pintu dan memaksa kami menunggu di depan regol seperti pengemis yang menunggu belas kasihan.”
Jawaban orang yang membuka pintu itu ternyata tidak kalah kerasnya dengan pernyataan kedua orang itu, ”Jika kalian memang tidak menunggu belas kasihan, kenapa kalian tidak pergi saja?”
Wajah kedua orang itu menjadi merah. Yang tertua diantara mereka berkata, ”Aku utusan Kiai Narawangsa. Jika kau menghina aku, sama artinya kau telah menghina Kiai Narawangsa.”
Tetapi orang yang membuka pintu itu menjawab, ”Padepokan ini adalah padepokan Kiai Banyu Bening. Siapapun yang berhubungan dengan padepokan ini harus tunduk kepada tatanan yang berlaku di sini.”
Kemarahan yang memuncak hampir saja membuat kedua orang itu kehilangan kendali. Tetapi mereka sadari, bahwa mereka berdiri didepan regol sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka orang yang tertua itupun berkata, ”Sekarang, bawa aku bertemu dengan Kiai Banyu Bening.”
Ki Warana yang melihat gelagat yang kurang baik di depan gerbang padepokan itupun telah mendekat. Ki Warana itu mendengar ketika orang yang mengaku utusan Kiai Narawangsa itu minta untuk dibawa menghadap Kiai Banyu Bening. Karena itu, justru Ki Warana lah yang menjawab, ”Kiai Banyu Bening sedang beristirahat.”
Kedua orang yang mengaku utusan Kiai Narawangsa itu memandang Ki Warana yang melangkah semakin dekat. Dengan nada tinggi, yang muda diantara kedua orang itu berkata, ”Kami utusan Kiai Narawangsa.”
“Kenapa Kiai Narawangsa itu tidak datang sendiri?”
“Pada saatnya Kiai akan datang. Sekarang, biarlah aku berbicara dengan Kiai Banyu Bening.”
“Kiai Banyu Bening baru beristirahat.”
“Aku utusan Kiai Narawangsa.”
Ki Warana tertawa. Katanya, ”Jika Kiai Narawangsa itu datang sekarang, maka Kiai Banyu Bening tentu akan menemuinya. Karena itu pergilah, katakan kepada Kiai Narawangsa, agar ia datang sendiri agar Kiai Banyu Bening bersedia menemuinya.”
“Kalian akan menyesal telah mempermainkan utusan Kiai Narawangsa.”
“Pergilah. Jika Kiai Narawangsa berkeberatan, kenapa tidak Nyai Wiji Sari saja yang datang kemari? Mungkin Nyai Wiji Sari akan sempat mengenang kembali masa-masa lalunya bersama Kiai Banyu Bening. He, apakah Kiai Narawangsa akan cemburu?”
Orang itu menggeram. Tetapi keduanya memang tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka kehilangan kendali, maka mereka justru akan terjerumus ke tangan orang-orang sepadepokan. Sebenarnyalah mereka datang ke padepokan itu sekedar untuk melihat kesibukan di padepokan itu. Serba sedikit mereka ingin mendapat gambaran, apa yang ada didalam padepokan itu untuk kemudian disesuaikan dengan laporan pemimpin kelompok yang pernah datang terdahulu.
Karena itu, bertemu dengan Kiai Banyu Bening atau tidak bertemu, sebenarnya tidak ada bedanya, dari pintu gerbang padepokan yang terbuka, mereka telah melihat kedalam padepokan itu. Sehingga tidak perlu memaksakan keinginan untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening. Akan tetapi untuk mengelabui para penghuni cantrik, maka ia harus berpura-pura.
Maka dengan nada tinggi, orang yang tertua diantara kedua orang yang mengaku utusan Kiai Narawanmgsa itu berkata, ”Ki Sanak. Kalian telah memperlakukan utusan Kiai Narawangsa dengan cara yang tidak baik. Pada suatu saat Kiai Narawangsa akan datang, menghukum kalian dan seisi padepokan ini. Kiai Narawangsa akan datang dengan kekuatan yang tidak akan dapat kalian bendung, melanda padepokan kalian. Tetapi selanjutnya, Kiai Narawangsa tidak akan pernah meninggalkan padepokan ini. Apalagi Nyai Wiji Sari. Ia akan tinggal disini, bersama anaknya yang telah dibunuh oleh ayahnya sendiri. Justru dibakar didalam api.”
Ki Warana justru menunjuk pada tugu di depan pendapa bangunan utama dengan batu nisan kecil diatasnya. ”Itulah makam anak Kiai Banyu Bening. Makam itu sangat dihormatinya. Kiai Banyu Bening memang sangat mendendam kepada isterinya yang sudah menyebabkan anaknya terbakar sehingga meninggal.”
“Itu salah Kiai Banyu Bening.”
“Salah Nyai Wiji Sari.”
Orang yang muda masih akan menyahut. Tetapi Ki Warana telah membentaknya ”Jika kau sebut lagi, bahwa Kiai Banyu Bening yang bersalah, maka kalian tidak akan pernah kembali ke padepokan Kiai Narawangsa. Membunuh atau tidak membunuh kalian, bagi kami sama saja. Kami harus mempertahankan padepokan ini dengan ujung senjata. Karena itu pergilah, sebelum kalian akan dibantai disini. Aku tidak main-main. Aku dapat menjatuhkan perintah itu.”
Kedua orang itu memang menjadi cemas. Karena itu, maka yang tertua diantara mereka berkata, ”Aku akan pergi sekarang, tetapi dalam waktu dekat aku akan kembali lagi."
Kiai Warana memandang orang itu dengan tajamnya. Katanya ”Cepat pergi, sebelum aku melepaskan sekelompok cantrik-cantrik dari padepokan ini untuk membantaimu. Kami sama sekali tidak takut kepada Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.”
Kedua orang itupun kemudian beringsut meninggalkan pintu gerbang padepokan itu. Mereka ternyata tidak berhasil menggertak orang-orang padepokan itu. Merekapun tidak berhasil menemui Kiai Banyu Bening. Tetapi mereka sudah berhasil melihat serba sedikit keadaan di dalam padepokan itu.
Ketika mereka berkumpul kembali dengan kawan-kawannya, maka orang itupun berkata, ”Kita tidak melihat sesuatu yang pantas dicemaskan di dalam padepokan itu. Meskipun penjagaan di panggungan-panggungan nampaknya sangat ketat, tetapi nampaknya padepokan itu rapuh didalam. Kami tidak melihat sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus.”
“Apakah kita akan segera kembali dan memberikan laporan kepada Kiai Narawangsa.”
“Ya. Kita akan segera kembali.”
Kelima orang itu tidak menunggu hari berikutnya. Di sisa hari itu mereka mulai berangkat menempuh perjalanan jauh. Tetapi seperti saat mereka berangkat, mereka tidak banyak mengalami rintangan diperjalanan pulang.
Dalam pada itu, Nyai Wiji Sari merasa sudah terlalu lama menunggu kesempatan untuk dapat pergi ke kaki Gunung Lawu. Apalagi ketika rasa-rasanya sudah tidak ada lagi rumah yang pantas diketuk pintunya. Ternyata betapa pun kerasnya jalan kehidupan yang di tempuh oleh Nyai Wiji Sari, namun kerinduan yang hampir tidak tertahankan telah mencengkam jantungnya. Namun ia tidak dapat mengingkari satu kenyataan, bahwa anaknya memang sudah meninggal, terbakar bersama rumahnya dan seisinya.
Nyai Wiji Sari memang menganggap bahwa kematian anaknya itu disebabkan oleh kesalahan suaminya. Jika saja waktu itu suaminya tidak cepat dibakar oleh perasaan marahnya, maka persoalannya akan menjadi lain. Meskipun demikian, di hati kecilnya, Nyai Wiji Sari juga melihat bahwa dirinya juga bersalah. Seharusnya ia tidak membawa Narawangsa kerumahnya. Saat itu ia mengira bahwa Lembu Wirid tidak akan pulang sampai matahari terbit.
Namun sebelum tengah malam suaminya sudah pulang. Karena suaminya dan Narawangsa memang memiliki ilmu yang tinggi, maka perkelahian diantara mereka tidak dapat dihindari. Nyai Wiji Sari tidak dapat menyesali peristiwa yang telah terjadi itu. Karena bagaimana pun juga ia menyesal, yang terjadi itu memang sudah terjadi.
Seakan-akan terbayang kembali, apa yang telah dilakukannya. Ternyata ia telah membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Ketika Narawangsa terdesak, maka ia justru membantu laki-laki itu untuk melawan suaminya. Ketika rumahnya terbakar, dan jerit tangis anaknya melengking, Wiji Sari tidak tahan mendengarnya, sementara ia tidak lagi dapat menerobos api untuk menolongnya
Namun dalam keadaan yang sangat bingung tangannya telah ditarik oleh Narawangsa karena api telah membakar hampir seluruh bagian rumahnya. Demikian ia bergeser, maka langit-langit pun telah runtuh. Nyai Wiji Sari tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh suaminya. Hampir diluar kesadarannva. Nyai Wiji Sari tidak menolak ketika tangannya ditarik terus menjauhi api yang menjadi semakin gemuruh menelan rumahnya dan isinya, termasuk bayinya.
Namun akhirnya Nyai Wiji Sari mengetahui, bahwa dihari berikutnya suaminya telah mengambil tubuh anaknya yang hangus dan dibawanya pergi. Orang-orang yang menyaksikannya tidak dapat berbuat banyak. Menurut keterangan tetangga-tetangganya, Lembu Wirid yang juga mengalami luka bakar itu, sama sekali tidak mau berbicara sepatah kata pun.
Baru kemudian, ketika ia memerintahkan beberapa orang anak buahnya menelusuri kepergian Lembu Wirid, maka orang-orangnya itupun menemukan Lembu Wirid itu di kaki Gunung Lawu dan bergelar Kiai Banyu Bening.
Namun laporan dari pengikutnya yang telah pergi ke kaki Gunung Lawu yang terdahulu, mengatakan bahwa anaknya yang meninggal itu telah dibuatkan sebuah tugu dan diatasnya diletakkan batu nisan kecil oleh bekas suaminya, Lembu Wirid.
Nyai Wiji Sari menarik nafas dalam-dalam. Jika hal itu benar, maka agaknya Lembu Wirid juga merasa getir karena kematian anaknya. Bahkan seperti yang dilaporkan oleh pengikutnya itu, bahwa Kiai Banyu Bening telah membuat satu upacara yang gila. Upacara dengan mengorbankan bayi yang sebenarnya.
“Ia memang, gila!” desis Nyai Wiji Sari.
Namun setelah peristiwa itu lama sekali terjadi, Nyai Wiji Sari itu dapat melihat dengan lebih baik dari jarak yang cukup jauh. Namun setiap kali terbersit penyesalan didalam hatinya, maka Nyai Wiji Sari tentu menghibur dirinya bahwa peristiwa yang memang akan terjadi itu tentu akan terjadi juga.
Dalam pada itu, Kiai Narawangsa yang melihat Nyai Wiji Sari selalu merenung, tidak terlalu sering menegur. Namun beberapa kali ia mengatakan, bahwa mereka akan segera berangkat ke kaki Gunung Lawu untuk melihat dan sekaligus memiliki padepokan tempat anaknya itu dikuburkan. Tetapi Kiai Narawangsa tidak tahu, bahwa yang direnungkan oleh Nyai Wiji Sari tidak sekedar kerinduannya kepada anaknya yang sudah tidak ada serta keinginannya merambah daerah baru.
Tetapi peristiwa yang telah terjadi itu justru selalu membayanginya. Hatinya. Lembu Wirid memang seorang yang sering membohonginya. Ia sering berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya. Tetapi bukan seharusnya Wiji Sari itu menyakiti hatinya terlalu dalam. Bahwa ia membawa Narawangsa ke rumahnya itu sama artinya bahwa ia telah menikam punggung Lembu Wirid.
Ketika sekelompok orang yang ditugaskan pergi ke kaki Gunung Lawu untuk yang kedua kalinya datang, maka Nyai Wiji Sari pun segera memanggil mereka. Bersama Kiai Narawangsa maka Nyai Wiji Sari telah menerima kelima orang yang baru datang dari kaki Gunung Lawu itu.
“Apa yang kalian lihat dan apa yang telah kalian dengar?” bertanya Kiai Narawangsa.
Orang tertua yang memimpin kelompok itu telah memberikan laporan tentang perjalanannya. Iapun telah melaporkan pula, bahwa ia telah melihat keadaan serta isi padepokan itu.
“Kau masuk ke padepokan?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Ya Nyai. Meskipun kami berdua waktu itu tidak berhasil menemui Kiai Banyu Bening.”
“Kau lihat sebuah tugu yang diatasnya terdapat batu nisan kecil?” bertanya Nyai Wiji Sari pula.
“Ya, Nyai. Tugu dan nisan kecil itu masih ada di halaman.”
Nyai Wiji Sari menarik nafas dalam-dalam. Setelah kematian bayinya itu, Nyai Wiji Sari tidak lagi mempunyai keturunan. “Kematian anakku itu adalah kutukan bagiku sebagai seorang perempuan.” berkata Nyai Wiji Sari didalam hatinya.
Namun untuk beberapa lama Nyai Wiji Sari dapat menyembunyikan kegelisahannya itu. Ia telah memasuki satu dunia yang hitam dan gelap. Berkuda di malam hari melalui jalan-jalan panjang, padang-padang rumput dan padang perdu yang luas. Jalan-jalan sempit di pinggir hutan.
Sudah berapa kali ujang pedangnya menikam dada orang yang tidak mau menyerahkan harta bendanya. Sudah berapa kali tajam pedangnya menebas leher orang yang mengadakan perlawanan ketika ia merampok bersama Kiai Narawangsa yang kemudian dianggapnya sebagai suaminya.
Tetapi bagaimanapun juga hidup tanpa keturunan adalah seperti sebatang pohon yang tidak berbuah. Kering. Keterangan pemimpin kelompok yang pergi ke kaki Gunung Lawu itu seakan-akan telah mendesak Nyai Wiji sari untuk segera berangkat mengambil padepokan itu. Rasa-rasanya anaknya itu sudah terlalu lama merengek sambil menjulurkan kedua tangannya.
“Baik, baik. Aku akan segera datang ngger.” Nyai Wiji Sari berkata didalam hatinya.
Keterangan pemimpin kelompok pertama dan kelompok kedua yang hampir bersamaan itu, telah mendorong Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari untuk segera berangkat.
Ketika segala persiapan sudah dianggap cukup, maka Kiai Narawangsa telah memerintahkan sekelompok orang untuk pergi mendahului ke kaki Gunung Lawu. Mereka harus membangunkan landasan bagi seluruh kekuatan yang akan pergi dan kemudian mengambil padepokan di kaki Gunung Lawu itu.
Tetapi Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari tidak pergi berdua saja bersama-sama dengan para pengikutnya. Kiai Narawangsa telah mengajak adiknya serta beberapa orang saudara seperguruannya. Dua orang anak adiknya itu, yang seakan-akan telah diangkatnya menjadi anaknya, akan ikut pula bersama mereka. Dua orang anak muda yang telah ditempa dengan keras sehingga keduanya telah menjadi anak muda yang berilmu tinggi.
“Gunasraba!” berkata Kiai Narawangsa kepada adiknya ”Jika aku sudah mendapat daerah baru, maka aku serahkan padepokan ini kepadamu. Karena itu, aku minta bantuanmu untuk menemukan daerah baru itu.”
“Kenapa kakang tinggalkan padepokan yang telah mapan ini?”
“Di padepokan yang berada di kaki Gunung Lawu itu terdapat makam anak Nyai Wiji Sari. Ia merindukannya dan ingin selalu dekat dengan anaknya itu.”
“Bagaimana dengan pemimpin padepokan itu?” bertanya Gunasraba.
“Namanya Kiai Banyu Bening. Ia adalah bekas suami Wiji Sari, yang dahulu namanya Lembu Wirid. Kita harus merebut padepokan itu dan sekaligus membunuhnya.”
Gunasraba mengangguk-angguk. Katanya, ”Baik kakang, jika itu yang kau maui. Aku akan mengajak dua orang saudara seperguruanku. Anak-anak dan beberapa orang sahabat dan kepercayaanku. Jika kelak aku memimpin padepokan ini, maka setidak-tidaknya mereka akan dapat menumpang tidur dan makan disini disela-sela petualangan mereka.”
“Kau sendiri, sudah waktunya untuk menghentikan petualanganmu dan menetap di sebuah padepokan. Nah, sebentar lagi kau akan mendapat kesempatan.”
Gunasraba tertawa. Katanya, ”Mudah-mudahan aku kerasan tinggal disatu tempat untuk waktu yang lama.”
“Kau harus mencobanya.” berkata Kiai Narawangsa. Gunasraba tertawa semakin keras. Katanya ”Padepokan ini akan menjadi sarang serigala yang ganas. Padepokan ini akan menjadi semakin menakutkan.”
“Terserah saja kepadamu nanti.” sahut Kiai Narawangsa. Di hari-hari terakhir, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari menjadi semakin sibuk mempersiapkan diri.
“Kita tinggal menunggu laporan dari orang-orang yang sedang membuat landasan sebelum kita menyerang padepokan yang dipimpin oleh Kiai Banyu Bening itu.” berkata Kiai Narawangsa kepada adiknya itu.
Nyai Wiji Sari hampir tidak dapat menahan diri lagi untuk menunggu laporan dari sekelompok orang-orangnya yang telah lebih dahulu pergi ke kaki Gunung Lawu. Ia mulai mendesak Kiai Narawangsa untuk berangkat tanpa menunggu lebih lama lagi.
“Kita akan dapat berselisih jalan dengan orang yang akan memberikan laporan kepada kita. Selain itu, kita memang memerlukan seseorang yang akan menuntun perjalanan kita agar tidak diketahui lebih dahulu oleh orang-orang Banyu Bening.”
Nyai Wiji Sari masih mencoba bersabar untuk beberapa hari. Namun akhirnya orang yang ditunggunya itupun datang juga. Dua orang diantara beberapa orang lebih dahulu.
“Kami membuat landasan dipinggir hutan,” berkata salah seorang dari kedua orang itu.
Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari mendengarkan laporan kedua orang itu dengan saksama. Bahkan Kiai Narawangsa minta agar adiknya ikut mendengarkannya pula, agar ia dapat memberikah pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan.
“Ternyata semuanya telah mendukung rencana kita.” berkata Kiai Narawangsa ”Keadaan padepokan Kiai Banyu Bening itu sendiri akan memberikan kesempatan kepada kita untuk dengan cepat menguasainya.”
“Tetapi mereka mengawasi keadaan di seputar padepokan mereka dengan ketat.” berkata salah seorang dari kedua orang itu.
“Apa arti pengawasan yang ketat jika keadaan didalam padepokan itu rapuh?” bertanya Kiai Narawangsa.
“Kami tidak melihat kekuatan yang akan dapat mencegah kita,” berkata orang itu pula.
“Pekan ini kita akan berangkat.” berkata Kiai Narawangsa. Lalu katanya kepada adiknya ”Sebagian dari barang-barang kami akan kami tinggal. Pada kesempatan lain, kami akan mengambilnya.”
Gunasraba mengangguk-angguk. Katanya, ”Baiklah. Sementara kita pergi, biarlah dua orang kepercayaanku menunggui padepokan ini. Mereka akan dapat mencari kawan yang akan dapat dipercaya pula.”
“Baiklah.” berkata Kiai Narawangsa ”Dengan demikian, maka segala persiapan sudah selesai.”
“Semuanya tinggal menunggu perintah kakang.”
“Aku ingin berbicara dengan kedua orang anakmu.” berkata Kiai Narawangsa.
Dua orang anak muda yang bertubuh tegar telah menemui Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari. Dengan nada berat Kiai Narawangsa itupun berkata, ”Aku dan ibumu ingin mengajakmu bertamasya ke kaki Gunung Lawu.”
“Kami sudah menunggu, kapan kita akan berangkat?”
“Aku juga sudah hampir tidak tahan.” berkata Nyai Wiji Sari. “Tetapi aku ingin berpesan kepada kalian, bahwa kita akan memasuki daerah berbahaya di kaki Gunung Lawu itu.”
Kedua orang anak muda itu tertawa. Parung Landung, yang tertua diantara mereka tertawa lebih keras. Katanya ”Bukankah kita ditempa untuk memasuki lingkaran-lingkaran yang paling berbahaya?”
Sementara itu, adiknya, Paron Waja berkata lantang, “Kami sudah siap paman. Apakah paman masih meragukan kami berdua?”
“Tidak. Kami sama sekali tidak meragukan kalian. Kami hanya ingin memperingatkan kalian, agar kalian berhati-hati.”
“Kami akan berhati-hati paman.” sahut Parung Landung. Dalam pada itu maka persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sudah sampai ke puncaknya. Mereka tinggal menunggu saat yang terbaik untuk berangkat ke kaki Gunung Lawu.
Sementara itu, anak-anak muda yang baru memasuki lingkungan padepokan yang dipimpin oleh Ki Lemah Teles dan Ki Warana itu telah berlatih semakin keras. Apalagi dua orang cantrik yang sedang berada disawah melihat dua orang yang nampak mencurigakan. Dua orang yang agaknya sedang mengamati padepokan yang sedang mengalami perubahan landasan dan tatanan itu.
Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Warana, maka Ki Warana itupun berdesis, ”Tidak mustahil bahwa keduanya adalah para pengikut Kiai Narawangsa yang sedang mengamati padepokan kita.”
“Kami juga menyangka demikian, Ki Warana.”
“Baiklah. Kita memang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Meskipun kita tinggal menunggu, tetapi justru karena itu, kita akan selalu berada dalam ketegangan.”
“Kami akan berusaha untuk mengamati orang-orang yang mencurigakan itu Ki Warana.”
“Baiklah. Tetapi berhati-hatilah. Seandainya kita menemukan isyarat bahwa mereka memang para pengikut Kiai Narawangsa, kita tidak harus dengan serta-merta bertindak. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Segala sesuatunya harus diperhitungkan dengan cermat sehingga kita tidak justru terjebak.”
“Ya, Ki Warana.” jawab kedua cantrik itu.
“Baiklah. Aku akan memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan kawan-kawannya itu.”
Ki Lemah Teles yang mendapat laporan itupun kemudian telah membicarakannya dengan Ki Ajar Pangukan, Ki Sambi Pitu, Ki Jagaprana dan Ki Pandi.
“Kita harus mengetahui siapakah mereka itu,” berkata Ki Pandi.
“Jika benar mereka adalah pengikut Kiai Nalawangsa, maka mereka tentu mempunyai tempat persembunyian di sekitar padepokan ini.”
“Aku akan mencarinya,” berkata Kiai Jagaprana.
“Aku ikut.” sahut Ki Sambi Pitu ”Biariah aku mendapat peranan disini. Tanpa peranan yang berarti, maka aku akan menjadi matahari yang redup sebelum senja.”
Ki Ajar Pangukan tertawa. Katanya ”Aku sudah mendapat peranan. Justru peranan terbesar di padepokan ini.”
Namun dalam pertemuan itu telah disepakati, bahwa Ki Jagaprana dan Ki Sambi Pitu akan mengamati orang-orang yang mencurigakan itu.
“Jangan Ki Pandi.” berkata Ki Ajar Pangukan ”Ketika dua orang utusan Kiai Narawangsa menemui Kiai Banyu Bening Ki Pandi duduk bersamaku.”
Ki Pandi tertawa pendek. Katanya ”Orang-orang seperti aku ini tentu akan dapat dengan mudah dikenali orang.”
“Kau sendiri yang mengatakannya Ki Bongkok.” sahut Ki Ajar Pangukan.
Sementara itu, Ki Jagaprana pun berkata, ”Nanti malam, aku akan mulai.”
Tetapi keduanya tidak dapat dengan serta-merta melakukannya. Mereka harus berbicara dahulu dengan dua orang cantrik yang pernah melihat kedua orang yang mencurigakan itu ketika keduanya berada di sawah. Darimana mereka datang dan kemana mereka pergi.
Dengan bahan itu, maka keduanya akan dapat memperkirakan arah yang akan mereka datangi malam nanti. Tugas-yang berbahaya itu memang tidak dapat diserahkan kepada para cantrik. Untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya maka tugas itu memang harus dilakukan oleh orang yang berilmu tinggi. Apalagi jika Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sudah berada diantara mereka. Maka untuk dapat mendekat, diperlukan kemampuan yang tinggi.
Untuk mendapat hasil yang sebaik-baiknya, maka Ki Sambi Pitu dan Jagaprana tidak dengan tergesa-gesa mencari tempat persembunyian orang-orang itu. Tetapi dihari berikutnya, mereka telah ikut pergi ke sawah. Dengan memanggul cangkul serta memakai caping bambu mereka bersama dua orang cantrik telah pergi ke sawah. Dibawah panasnya matahari yang memanjat semakin tinggi, mereka berendam di air berlumpur sambil mengayunkan cangkul mereka.
Sebenarnya, mereka melihat dua orang yang mencurigakan lewat meniti pematang. Mereka memang hanya berjalan melintas. Tetapi keduanya mengamati padepokan itu dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana memperhatikan arah kemana mereka pergi. Tidak terlalu jauh dari padepokan mereka berjalan melingkar. Juga masih meniti pematang. Mereka berjalan menjauh, kemudian memutar kembali kearah hutan kaki pegunungan.
“Kita akan melihat malam nanti, apa yang ada dihutan itu,” desis Ki Jagaprana.
“Kita sudah dapat menduga, dimana mereka bersembunyi” berkata Ki Sambi Pitu.
“Ya. Asap itu.”
“Ternyata mereka memang dungu.”
“Atau kita yang dungu, jika kita begitu saja percaya, bahwa mereka memang berada disekitar perapian itu.”
Keduanya mengangguk-angguk. Ki Sambi Pitu lah yang kemudian berkata ”Baiklah. Biarlah malam nanti kita akan membuktikannya.”
Seperti yang direncanakan oleh kedua orang itu, maka ketika senja turun, keduanya pun telah bersiap. Demikian gelap menyelimuti padepokan itu, maka mereka berdua telah keluar lewat regol butulan untuk melihat-lihat hutan lebat di kaki Gunung Lawu itu. Dengan hau-hati keduanya kemudian menyusuri pinggir hutan. Yang menjadi sasaran utama adalah arah asap yang mereka lihat mengepul itu.
Ternyata orang-orang itu memang kurang berhati-hati. Malam itu mereka juga membuat perapian untuk melawan dingin meskipun tidak begitu besar. Mereka memang sudah berusaha untuk melindungi nyala api perapian itu dengan bebatuan. Namun warna merah yang menapak pada batang-batang pepohonan masih juga dapat dilihat oleh Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana.
“Ternyata tidak terlalu sulit.” desis Ki Jagaprana.
Ki Sambi Pitu tidak menjawab. Namun mereka telah merayap semakin mendekati orang-orang yang berada di sekitar perapian. Namun yang dilihat oleh kedua orang itu bukan sekedar perapian. Ternyata mereka melihat berbagai macam bahan dan peralatan yang teronggok tidak terlalu jauh dari tempat mereka membuat perapian.
Ki Sambi Pitu memberi isyarat kepada Ki Jagaprana untuk melihat benda-benda yang teronggok diantara pepohonan hutan itu. Keduanya mengangguk-angguk meskipun mereka tidak saling berbicara. Mereka melihat potongan-potongan dan anyaman bambu. Tali ijuk dan seonggok batang ilalang. Didalam hati mereka berkata, ”Orang-orang ini tentu akan membuat gubug yang cukup besar.”
Apalagi, mereka juga melihat sebidang tanah yang sudah dibersihkan, siap untuk membangun sebuah gubug. Beberapa saat kedua orang itu mengamati lingkungan itu. Baru kemudian, Ki Sambi Pitu telah memberikan isyarat, agar mereka meninggalkan tempat itu. Demikian keduanya menjauhi tempat itu, maka Ki Sambi Pitu pun berkata,
”Nampaknya mereka akan membuat sebuan pesanggrahan.”
“Ya!” Ki Jagaprana mengangguk-angguk.
“Tentu bagi Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari. Sedangkan yang lain akan dapat berada disembarang tempat.”
Ki Jagaprana mengangguk-angguk. Katanya, ”Menilik tempat yang dipersiapkan, tentu banyak orang yang akan datang.”
“Tentu akan meriah.” desis Ki Sambi Pitu.
“Mudah-mudahan kerajaan Ki Lemah Teles tidak segera berakhir.”
Demikian mereka sampai di padepokan, maka keduanya pun segera menceriterakan kepada orang-orang tua yang berilmu tinggi, yang memang menunggu kedatangan Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana.
“Menarik sekali.” desis Ki Ajar Pangukan ”Karena itu, maka kita harus benar-benar bersiap untuk menyambut kehadiran mereka. Kita tidak tahu pasti, berapa besar kekuatan mereka, sehingga karena itu, maka yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan kekuatan penuh untuk menyambut mereka.”
“Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari tentu sudah bersiap-siap pula. Besok mereka tentu sudah akan mendirikan gubug itu. Sehingga dalam dua tiga hari lagi, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari tentu sudah akan datang.”
“Baiklah.” berkata Ki Lemah Teles ”Kita akan bersiap untuk menyongsong kehadiran tamu-tamu Kiai Bayu Bening itu. Karena itu, sebaiknya penyambutan itu dipimpin oleh Kiai Banyu Bening sendiri...”
Dalam pada itu. orang-orang yang berada di padepokan di kaki Gunung Lawu itu masih saja menempa diri. Mereka memanfaatkan waktu degan sebaik-baiknya. Mereka yang tidak pergi ke sawah, telah masuk kedalam sanggar. Mungkin sanggar tertutup, mungkin sanggar terbuka. Orang-orang yang umurnya sudah menjelang senja itu dengan tekun membimbing mereka pula.
“Apa yang dapat kita lakukan harus kita lakukan pada masa-masa senja ini” berkata Ki A jar Pangukan.
Ki Lemah Teles tertawa. Katanya ”Meskipun menjelang senja, kita tetap matahari.”
“Ya” Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. ”Sinar matahari senja masih dapat membakar langit.”
Ki Pandi tertawa pula. Katanya ”Jangan takut kehilangan panas jika api kalian telah menyalakan sebukit karang sehingga membara.”
“Tidak cukup!” teriak Ki Lemah Teles ”Panas cahaya matahari senjamu harus membuat bulan, bintang dan semua langit membara sampai saatnya terbit matahari baru.”
Ki Jagaprana tertawa berkepanjangan. Katanya ”Apakah matahari-matahari kini pandai bermimpi.”
“Bukan mimpi...” teriak Ki Lemah Teles ”Apimu lah yang akan segera padam didalam mimpi burukmu.”
“Kau akan menantang berperang tanding?” bertanya Ki Pandi.
“Bongkok edan!” geram Ki Lemah Teles. Mereka pun tertawa. Sementara Ki Lemah Teles melangkah meninggalkan mereka.
Tetapi langkahnya terhenti ketika Ki Pandi berkata, ”He, kau akan kemana? Berilah perintah-perintah. Kau sekarang memimpin padepokan ini bersama Ki Warana.”
“Perintah apa yang dapat aku berikan kepada matahari yang mulai redup sebelum senja?”
Ki Lemah Teles tidak menghiraukan orang-orang tua itu tertawa berkepanjangan. Ki Warana menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin dapat berbuat sebagaimana orang-orang tua itu. Sempat tertawa dan memandang kehidupan tanpa dibebani oleh berbagai macam persoalan yang menekan. Tetapi ia tidak dapat ingkar, bahwa ia harus bekerja keras untuk menyusun kembali tatanan kerja dan hubungan di padepokan itu.
Dari hari ke hari, kesibukan di padepokan itu menjadi semakin meningkat. Beberapa orang anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu justru menyatakan diri untuk ikut menimba ilmu di padepokan itu. Mereka dan orang-orang tua mereka kemudian mengetahui, bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar di padepokan itu.
Ki Warana telah menyatakan, bahwa sanggar-sanggar yang terdapat di padukuhan-padukuhan tidak mempunyai arti lagi. “Jika sanggar itu ingin tetap ada di padukuhan, maka gunanya sudah berbeda sama sekali.”
Perubahan-perubahan yang meyakinkan itulah, yang membuat orang-orang padukuhan mempercayakan beberapa orang anak muda mereka menyatakan diri untuk tinggal di padepokan. Mereka bukan saja ingin mendapatkan tuntunan dalam olah kanuragan. Tetapi di padepokan mereka juga ingin menyadap pengetahuan tentang bercocok tanam, berternak dan mengenali musim. Mereka juga ingin dapat membaca huruf-huruf serta menangkap maksudnya.
Tetapi Ki Warana telah memberitahukan kepada mereka dan orang tua mereka, bahwa, padepokan itu masih berada dalam keadaan bahaya. “Aku tidak ingin mereka terbakar dalam api permusuhan begitu mereka memasuki padepokan kami,” berkata Ki Warana kepada anak-anak muda itu serta orang tua mereka.
Beberapa orang memang menjadi ragu-ragu. Tetapi beberapa orang yang lain berkata, ”Kami siap menjalani tugas apapun juga.”
Ki Warana justru menjadi terharu. Ia merasakan sambutan yang hangat dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu, setelah berhasil merombak alasnya sampai ke dasar. Ketika hal itu dibicarakannya dengan Ki Lemah Teles, maka Ki Lemah Teles pada dasarnya sejalan dengan pikiran Ki Warana. Sebaiknya anak-anak muda itu tidak memasuki padepokan justru pada saat yang gawat.
“Mereka belum mempunyai bekal apa-apa” berkata Ki Lemah Teles.
Tetapi ternyata beberapa orang anak muda justru bersedia mengalami akibat apapun. Terutama dari padukuhan terdekat yang telah menjadi landasan perlawanan Ki Warana terhadap Panembahan Lebdagati dan Lembu Palang.
“Kami sudah mempunyai pengalaman.” berkata beberapa orang anak muda itu.
Ki Warana memang tidak dapat menolak mereka. Jika Ki Warana tidak mau menerima mereka, maka akan dapat terjadi salah paham, seakan-akan setelah Ki Warana merebut kembali padepokannya, maka ia telah menolak kehadiran anak-anak muda itu di padepokannya.
“Apa boleh buat.” berkata Ki Lemah Teles. ”Mereka memang sudah mempunyai sedikit pengalaman.”
“Tetapi dengan demikian, kita tidak akan dapat menolak kehadiran anak-anak muda dari padukuhan yang lain.”
Ki Lemah Teles menarik nafas dalam-dalam. Katanya ”Anak-anak yang baru sama sekali itu justru akan dapat menjadi beban.”
“Tetapi mereka akan menganggap kita menjauhi sebuah padukuhan tetapi mendekati padukuhan yang lain.”
“Ki Warana!” berkata Ki Lemah Teles ”Beri mereka penjelasan sekali lagi, bahwa padepokan ini masih dibayangi oleh pertentangan dan perselisihan. Sehingga dengan demikian kita dapat membagi tanggung-jawab.”
Ki Warana mengangguk-angguk. Katanya ”Baik, Ki Lemah Teles. Aku akan menjelaskan kepada anak-anak muda itu serta orang tuanya, bahwa pertentangan dan perselisihan itu akan dapat membuahkan kematian.”
Dengan penjelasan itu, memang ada beberapa orang anak muda yang mengurungkan niatnya, tetapi ada pula diantara mereka yang dengan tekad bulat bergabung dengan para cantrik dari padepokan yang telah memperbaharui pijakannya itu.
“Kami akan membuka kesempatan seluas-luasnya setelah keadaan benar-benar menjadi tenang.” berkata Ki Warana.
Namun mereka yang tidak menunda keinginannya untuk bergabung dengan para cantrik di padepokan itu, Ki Warana telah menaruh perhatian lebih besar daripada para cantrik yang lain.
“Kami serahkan mereka kepada kalian berdua ngger.” berkata Ki Warana kepada Manggada dan Laksana.
“Tetapi apa yang dapat kami berikan kepada mereka?” bertanya Manggada ”Pengetahuan dan ilmuku masih terlalu dangkal.”
“Tidak. Ilmu dan pengetahuan kalian jauh lebih baik dari ilmu dan pengetahuanku. Karena itu, aku serahkan mereka kepada angger berdua untuk dapat meletakkan dasar-dasar secara umum. Pada perkembangannya nanti, biarlah Ki Lemah Teles yang mengatur mereka.”
Manggada dan Laksana tidak dapat menolak. Ketika hal itu dikatakan kepada Ki Pandi, ternyata Ki Pandi sependapat. Katanya, ”Kalian tentu dapat melakukannya.”
Tetapi Ki Pandi menasehatkan, agar semua latihan dilakukan didalam padepokan. “Mungkin para pengikut Kiai Narawangsa selalu mengamati padepokan ini. Karena itu, maka mereka jangan melihat persiapan-persiapan yang dilakukan di padepokan ini.”
Sesuai dengan tugas yang diserahkan kepada Manggada dan Laksana, maka kedua anak muda itupun segera mulai melakukannya. Anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu mendapat kesempatan terbanyak untuk melakukan latihan-latihan. Mereka tidak segera diserahi tugas untuk ikut memelihara sawah dan pategalan. Yang penting bagi mereka adalah menempa diri dalam olah kanuragan.
Apalagi keadaan padepokan yang masih selalu dibayangi oleh perselisihan yang berkepanjangan Setiap hari. Manggada dan Laksana memasuki sanggar terbuka bergantian. Keduanya telah membagi anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu menjadi dua kelompok yang besar. Kemudian kelompok-kelompok itu dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil.
Setiap hari, di dini hari, anak-anak muda itu harus sudah bangun. Setelah berbenah diri. mereka segera memasuki latihan-latihan pagi. Mereka memanasi tubuh mereka dengan gerakan-gerakan yang khusus. Kemudian berlari-lari memutari halaman dan kebun padepokan. Jika kelompok yang dipimpin oleh Manggada berlatih disanggar terbuka, maka Laksana melakukannya di halaman. Demikian sebaliknya.
Setelah sepekan mereka melakukan latihan-latihan gerak dasar, maka Manggada dan Laksana mulai mengajari mereka cara memegang berbagai jenis senjata. Mula-mula anak-anak muda itu berlatih memegang tombak dan melakukan gerak-gerak dasar. Kemudian mereka mulai berlatih memegang pedang dan perisai.
Untuk memburu waktu yang sempit, maka Manggada dan Laksana menekankan kemampuan anak-anak muda yang menjadi penghuni baru dari padepokan itu bermain dengan tombak pendek dan pedang dengan perisainya.
“Kalian tidak perlu menjelajahi berbagai macam senjata. Yang penting dalam waktu yang pendek ini kalian mampu mempergunakan tombak pendek dan pedang dengan perisainya,” berkata Manggada dan Laksana kepada anak-anak muda itu.
Namun anak-anak muda itu juga diajarinya mempergunakan tombak pendek dan pedang untuk melawan berbagai macam senjata. Mereka berlatih melawan orang yang bersenjata kapak. Berlatih melawan orang yang mempergunakan trisula, canggah, bindi atau cambuk.
Latihan-latihan yang dilakukan oleh para penghuni padepokan itu memang tidak dapat dilihat dari luar. Baik anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu, maupun mereka yang sudah berada di padepokan itu sejak padepokan itu dipimpin oleh Kiai Banyu Bening.
Jika ada empat atau lima orang penghuni padepokan itu yang pergi keluar, mereka tentu membawa cangkul atau bajak atau garu dengan sepasang kerbau untuk dipekerjakan di sawah. atau pategalan di seputar padepokan itu.
Dalam pada itu, ternyata Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari juga tidak segera mendatangi padepokan yang dipimpin oleh Ki Lemah Teles itu. Kecuali mereka juga ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mereka masih merasa sayang untuk meninggalkan lingkungannya. Rasa-rasanya mereka masih memerlukan waktu beberapa lama untuk menguras harta-benda yang ada di lingkungannya yang cukup luas itu.
Namun dalam pada itu, orang-orang yang ditugaskan oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sudah berada di kaki Gunung Lawu. Mereka mencoba mengamati padepokan yang mereka sangka masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening itu. Justru karena mereka menganggap bahwa padepokan itu memang masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening.
Maka mereka sama sekali tidak berusaha lagi untuk meyakinkannya lagi. Bahkan kelima orang itu sama sekali tidak mencoba berhubungan dengan orang-orang padukuhan. Jika mereka melakukannya, maka mungkin sekali kedatangan mereka akhirnya diketahui oleh orang-orang padepokan.
Karena itu, maka mereka hanya sekedar melakukan pengamatan dari kejauhan. Meskipun kelima orang itu tidak melihat kekuatan padepokan itu yang sebenarnya, tetapi mereka memang melihat kesiagaan yang mantap. Mereka melihat para cantrik yang mengawasi keadaan di sekeliling padepokan dari atas panggung dibelakang dinding. Bahkan mereka juga melihat, dua orang cantrik dengan tombak ditangan mengawal sebuah pedati yang penuh berisi hasil bumi yang dipetik di pategalan.
“Ternyata Kiai Banyu Bening adalah seorang yang sangat berhati-hati...” berkata salah seorang diantara mereka.
Setelah beberapa hari kelima orang itu mengadakan pengamatan, maka mereka mengambil kesimpulan, bahwa padepokan Kiai Banyu Bening adalah padepokan yang cukup tertib. Pemimpin kelompok itu pada hari-hari terakhir dari tugasnya ternyata atas gagasan sendiri ingin memasuki padepokan Kiai Banyu Bening itu.
“Apakah tidak akan membahayakan jiwa kita?” bertanya salah seorang dari mereka.
“Mungkin...” jawab pemimpin kelompok itu ”Tetapi dengan demikian, aku akan dapat melihat serba sedikit isi dari padepokan itu untuk menyesuaikan laporan kawan kita terdahulu, yang juga pernah datang menghadap Kiai Banyu Bening.”
“Tetapi menurut kawan kita itu, Kiai Banyu Bening adalah seorang yang tidak dapat diduga sifatnya. Namun ia adalah seorang yang mempunyai wibawa yang tinggi.”
“Jika aku tidak kembali setelah matahari sampai di puncak, sebaiknya kalian menyingkir dari tempat ini.” Berkata pemimpin kelompok itu.
“Apa yang akan kau katakan kepada Kiai Banyu Bening?” bertanya seorang kawannya.
“Aku akan memberikan peringatan, bahwa Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari dalam waktu dekat akan segera datang.”
“Hanya itu?”
“Ya. Hanya itu. Bukankah ini penting sekali bagi mereka?”
“Tetapi apakah hal itu dibenarkan oleh Kiai Narawangsa. Jika karena itu, Kiai Banyu Bening menyingkir, bukankah Kiai Narawangsa terutama, akan menjadi sangat marah, karena ia ingin membunuh saja Kiai Banyu Bening itu?”
“Kiai Banyu Bening menurut perhitunganku, tidak akan melarikan diri.”
Pemimpin kelompok itu kemudian memutuskan untuk benar-benar pergi ke padepokan. Ia mengajak salah seorang dari kawan-kawannya itu yang pernah datang ke tempat itu sebelumnya, meskipun orang itu juga tidak ikut memasuki padepokan pada waktu itu.
Dengan kesadaran yang tinggi atas akibat yang mungkin terjadi atas diri mereka, maka pemimpin kelompok itupun telah pergi ke padepokan bersama dengan seorang kawannya. Namun bagaimana pun juga orang itu merasa jantungnya berdetak lebih cepat.
Pemimpin kelompok yang orangnya berbeda dengan pemimpin kelompok yang datang terdahulu ke padepokan itu, memang seorang yang berani. Meskipun demikian, ketika ia melangkah menuju ke pintu gerbang, orang itu menjadi berdebar-debar pula.
Para petugas yang berada di panggungan di sebelah pintu gerbang itu telah melihat kedatangannya. Karena itu, maka petugas itupun kemudian berteriak bertanya, ”He, siapakah kalian dan untuk apa kalian datang kemari.”
Pemimpin kelompok itu memandang para petugas diatas panggungan itu. Dengan lantang ia justru bertanya ”Apakah aku harus berteriak pula?”
Petugas itu termangu-mangu sejenak. Nampaknya orang yang datang itu bukan orang-orang padukuhan atau orang-orang yang telah terbiasa dengan padepokan itu. Karena itu, maka para petugas itupun menjadi lebih berhati-hati. Seorang dari para petugas itupun telah menjawab, ”Ya. Berteriaklah.”
“Inikah cara padepokan ini menerima tamu?”
“Ya!” jawab petugas itu.
Pemimpin kelompok nu mulai merasa tersinggung. Tetapi ia harus menahan diri. Dengan lantang pula ia berkata ”Aku ingin menghadap Kiai Banyu Bening.”
Petugas itu ragu-ragu sejenak. Namun kemudian iapun berkata ”Tunggulah, aku akan melaporkannya. Tetapi kalian harus menjawab, siapakah kalian dan kalian datang dari mana.”
“Aku utusan dari Kiai Narawangsa.” jawab orang itu tanpa ragu-ragu. Bahkan ia mengucapkan nama itu dengan kebanggaan yang melonjak didalam dadanya. Menurut pendapatnya, nama Kiai Narawangsa akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi Kiai Banyu Bening.”
Nama itu memang menggetarkan dada petugas di panggungan. Karena itu, salah seorang petugas dipanggungan itu telah turun untuk melaporkan kedatangan utusan Kiai Narawangsa itu. Sementara petugas yang lain masih bertanya ”Kau datang untuk apa?”
“Aku akan bertemu dengan Kiai Banyu Bening.” “Keperluanmu apa?” bertanya petugas itu pula.
“Aku akan menyampaikan sendiri kepada Kiai Banyu Bening.”
“Aku tidak tahu, apakah Kiai Banyu Bening dapat menerimamu atau tidak.” jawab petugas itu. Ia sudah mengerti, bahwa Ki Ajar Pangukan lah yang telah berperan menjadi Kiai Banyu Bening ketika utusan Kiai Narawangsa yang terdahulu datang ke padepokan itu.
Namun orang yang berada di muka regol itu berteriak “Katakan kepada Kiai Banyu Bening bahwa aku utusan Kiai Narawangsa ingin bertemu.”
Petugas pintu jaga menemui Ki Warana untuk melaporkan kehadiran dua orang yang mengaku utusan dari Kiai Narawangsa. Ki Warana pun segera menemui Ki Lemah Teles dan Ki Ajar Pangukan untuk minta pertimbangan apakah yang sebaiknya dilakukan terhadap utusan itu.
“Mereka bukan orang-orang yang pernah datang kemari,” berkata Ki Warana, ”Para petugas itu tentu masih dapat mengenali kedua orang utusan Kiai Narawangsa yang terdahulu, karena kebetulan waktu itu mereka melihat langsung kedatangan kedua orang utusan itu.”
“Katakan, bahwa Kiai Banyu Bening baru beristirahat. Ia tidak dapat menerima kedua utusan itu. Tanyakan saja kepadanya, apakah keperluan mereka datang. Agaknya kita sudah dapat menebak, apa yang akan mereka katakan.”
Ki Waranapun mengangguk-angguk.
“Temuilah mereka!” berkata Ki Ajar Pangukan.
Ki Warana lah yang kemudian memerintahkan membuka regol depan setelah memerintahkan para penghuni padepokan yang tidak berkepentingan untuk menyingkir. Demikian pula anak-anak muda yang sedang berlatih bersama Manggada di halaman samping.
“Biarlah mereka melihat padepokan ini tidak terlalu ramai.” berkata Ki Warana.
Baru kemudian, setelah suasana di padepokan itu nampak lengang seperti yang dikehendaki oleh Ki Warana, para cantrik membuka pintu gerbang padepokan.
Sementara itu, kedua orang yang datang dari padepokan Kiai Narawangsa itu sudah menjadi tidak sabar. “Kenapa kalian mempermainkan kami?” bertanya yang tertua diantara kedua orang itu demikian pintu terbuka.
Tetapi orang yang membuka pintu itu mengerti, bahwa utusan Kiai Narawangsa itu ingin menggertaknya, sehingga karena itu, maka iapun justru bertanya, ”Apakah kami mempermainkan kalian?”
“Kalian sengaja tidak segera membuka pintu dan memaksa kami menunggu di depan regol seperti pengemis yang menunggu belas kasihan.”
Jawaban orang yang membuka pintu itu ternyata tidak kalah kerasnya dengan pernyataan kedua orang itu, ”Jika kalian memang tidak menunggu belas kasihan, kenapa kalian tidak pergi saja?”
Wajah kedua orang itu menjadi merah. Yang tertua diantara mereka berkata, ”Aku utusan Kiai Narawangsa. Jika kau menghina aku, sama artinya kau telah menghina Kiai Narawangsa.”
Tetapi orang yang membuka pintu itu menjawab, ”Padepokan ini adalah padepokan Kiai Banyu Bening. Siapapun yang berhubungan dengan padepokan ini harus tunduk kepada tatanan yang berlaku di sini.”
Kemarahan yang memuncak hampir saja membuat kedua orang itu kehilangan kendali. Tetapi mereka sadari, bahwa mereka berdiri didepan regol sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka orang yang tertua itupun berkata, ”Sekarang, bawa aku bertemu dengan Kiai Banyu Bening.”
Ki Warana yang melihat gelagat yang kurang baik di depan gerbang padepokan itupun telah mendekat. Ki Warana itu mendengar ketika orang yang mengaku utusan Kiai Narawangsa itu minta untuk dibawa menghadap Kiai Banyu Bening. Karena itu, justru Ki Warana lah yang menjawab, ”Kiai Banyu Bening sedang beristirahat.”
Kedua orang yang mengaku utusan Kiai Narawangsa itu memandang Ki Warana yang melangkah semakin dekat. Dengan nada tinggi, yang muda diantara kedua orang itu berkata, ”Kami utusan Kiai Narawangsa.”
“Kenapa Kiai Narawangsa itu tidak datang sendiri?”
“Pada saatnya Kiai akan datang. Sekarang, biarlah aku berbicara dengan Kiai Banyu Bening.”
“Kiai Banyu Bening baru beristirahat.”
“Aku utusan Kiai Narawangsa.”
Ki Warana tertawa. Katanya, ”Jika Kiai Narawangsa itu datang sekarang, maka Kiai Banyu Bening tentu akan menemuinya. Karena itu pergilah, katakan kepada Kiai Narawangsa, agar ia datang sendiri agar Kiai Banyu Bening bersedia menemuinya.”
“Kalian akan menyesal telah mempermainkan utusan Kiai Narawangsa.”
“Pergilah. Jika Kiai Narawangsa berkeberatan, kenapa tidak Nyai Wiji Sari saja yang datang kemari? Mungkin Nyai Wiji Sari akan sempat mengenang kembali masa-masa lalunya bersama Kiai Banyu Bening. He, apakah Kiai Narawangsa akan cemburu?”
Orang itu menggeram. Tetapi keduanya memang tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka kehilangan kendali, maka mereka justru akan terjerumus ke tangan orang-orang sepadepokan. Sebenarnyalah mereka datang ke padepokan itu sekedar untuk melihat kesibukan di padepokan itu. Serba sedikit mereka ingin mendapat gambaran, apa yang ada didalam padepokan itu untuk kemudian disesuaikan dengan laporan pemimpin kelompok yang pernah datang terdahulu.
Karena itu, bertemu dengan Kiai Banyu Bening atau tidak bertemu, sebenarnya tidak ada bedanya, dari pintu gerbang padepokan yang terbuka, mereka telah melihat kedalam padepokan itu. Sehingga tidak perlu memaksakan keinginan untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening. Akan tetapi untuk mengelabui para penghuni cantrik, maka ia harus berpura-pura.
Maka dengan nada tinggi, orang yang tertua diantara kedua orang yang mengaku utusan Kiai Narawanmgsa itu berkata, ”Ki Sanak. Kalian telah memperlakukan utusan Kiai Narawangsa dengan cara yang tidak baik. Pada suatu saat Kiai Narawangsa akan datang, menghukum kalian dan seisi padepokan ini. Kiai Narawangsa akan datang dengan kekuatan yang tidak akan dapat kalian bendung, melanda padepokan kalian. Tetapi selanjutnya, Kiai Narawangsa tidak akan pernah meninggalkan padepokan ini. Apalagi Nyai Wiji Sari. Ia akan tinggal disini, bersama anaknya yang telah dibunuh oleh ayahnya sendiri. Justru dibakar didalam api.”
Ki Warana justru menunjuk pada tugu di depan pendapa bangunan utama dengan batu nisan kecil diatasnya. ”Itulah makam anak Kiai Banyu Bening. Makam itu sangat dihormatinya. Kiai Banyu Bening memang sangat mendendam kepada isterinya yang sudah menyebabkan anaknya terbakar sehingga meninggal.”
“Itu salah Kiai Banyu Bening.”
“Salah Nyai Wiji Sari.”
Orang yang muda masih akan menyahut. Tetapi Ki Warana telah membentaknya ”Jika kau sebut lagi, bahwa Kiai Banyu Bening yang bersalah, maka kalian tidak akan pernah kembali ke padepokan Kiai Narawangsa. Membunuh atau tidak membunuh kalian, bagi kami sama saja. Kami harus mempertahankan padepokan ini dengan ujung senjata. Karena itu pergilah, sebelum kalian akan dibantai disini. Aku tidak main-main. Aku dapat menjatuhkan perintah itu.”
Kedua orang itu memang menjadi cemas. Karena itu, maka yang tertua diantara mereka berkata, ”Aku akan pergi sekarang, tetapi dalam waktu dekat aku akan kembali lagi."
Kiai Warana memandang orang itu dengan tajamnya. Katanya ”Cepat pergi, sebelum aku melepaskan sekelompok cantrik-cantrik dari padepokan ini untuk membantaimu. Kami sama sekali tidak takut kepada Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.”
Kedua orang itupun kemudian beringsut meninggalkan pintu gerbang padepokan itu. Mereka ternyata tidak berhasil menggertak orang-orang padepokan itu. Merekapun tidak berhasil menemui Kiai Banyu Bening. Tetapi mereka sudah berhasil melihat serba sedikit keadaan di dalam padepokan itu.
Ketika mereka berkumpul kembali dengan kawan-kawannya, maka orang itupun berkata, ”Kita tidak melihat sesuatu yang pantas dicemaskan di dalam padepokan itu. Meskipun penjagaan di panggungan-panggungan nampaknya sangat ketat, tetapi nampaknya padepokan itu rapuh didalam. Kami tidak melihat sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus.”
“Apakah kita akan segera kembali dan memberikan laporan kepada Kiai Narawangsa.”
“Ya. Kita akan segera kembali.”
Kelima orang itu tidak menunggu hari berikutnya. Di sisa hari itu mereka mulai berangkat menempuh perjalanan jauh. Tetapi seperti saat mereka berangkat, mereka tidak banyak mengalami rintangan diperjalanan pulang.
Dalam pada itu, Nyai Wiji Sari merasa sudah terlalu lama menunggu kesempatan untuk dapat pergi ke kaki Gunung Lawu. Apalagi ketika rasa-rasanya sudah tidak ada lagi rumah yang pantas diketuk pintunya. Ternyata betapa pun kerasnya jalan kehidupan yang di tempuh oleh Nyai Wiji Sari, namun kerinduan yang hampir tidak tertahankan telah mencengkam jantungnya. Namun ia tidak dapat mengingkari satu kenyataan, bahwa anaknya memang sudah meninggal, terbakar bersama rumahnya dan seisinya.
Nyai Wiji Sari memang menganggap bahwa kematian anaknya itu disebabkan oleh kesalahan suaminya. Jika saja waktu itu suaminya tidak cepat dibakar oleh perasaan marahnya, maka persoalannya akan menjadi lain. Meskipun demikian, di hati kecilnya, Nyai Wiji Sari juga melihat bahwa dirinya juga bersalah. Seharusnya ia tidak membawa Narawangsa kerumahnya. Saat itu ia mengira bahwa Lembu Wirid tidak akan pulang sampai matahari terbit.
Namun sebelum tengah malam suaminya sudah pulang. Karena suaminya dan Narawangsa memang memiliki ilmu yang tinggi, maka perkelahian diantara mereka tidak dapat dihindari. Nyai Wiji Sari tidak dapat menyesali peristiwa yang telah terjadi itu. Karena bagaimana pun juga ia menyesal, yang terjadi itu memang sudah terjadi.
Seakan-akan terbayang kembali, apa yang telah dilakukannya. Ternyata ia telah membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Ketika Narawangsa terdesak, maka ia justru membantu laki-laki itu untuk melawan suaminya. Ketika rumahnya terbakar, dan jerit tangis anaknya melengking, Wiji Sari tidak tahan mendengarnya, sementara ia tidak lagi dapat menerobos api untuk menolongnya
Namun dalam keadaan yang sangat bingung tangannya telah ditarik oleh Narawangsa karena api telah membakar hampir seluruh bagian rumahnya. Demikian ia bergeser, maka langit-langit pun telah runtuh. Nyai Wiji Sari tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh suaminya. Hampir diluar kesadarannva. Nyai Wiji Sari tidak menolak ketika tangannya ditarik terus menjauhi api yang menjadi semakin gemuruh menelan rumahnya dan isinya, termasuk bayinya.
Namun akhirnya Nyai Wiji Sari mengetahui, bahwa dihari berikutnya suaminya telah mengambil tubuh anaknya yang hangus dan dibawanya pergi. Orang-orang yang menyaksikannya tidak dapat berbuat banyak. Menurut keterangan tetangga-tetangganya, Lembu Wirid yang juga mengalami luka bakar itu, sama sekali tidak mau berbicara sepatah kata pun.
Baru kemudian, ketika ia memerintahkan beberapa orang anak buahnya menelusuri kepergian Lembu Wirid, maka orang-orangnya itupun menemukan Lembu Wirid itu di kaki Gunung Lawu dan bergelar Kiai Banyu Bening.
Namun laporan dari pengikutnya yang telah pergi ke kaki Gunung Lawu yang terdahulu, mengatakan bahwa anaknya yang meninggal itu telah dibuatkan sebuah tugu dan diatasnya diletakkan batu nisan kecil oleh bekas suaminya, Lembu Wirid.
Nyai Wiji Sari menarik nafas dalam-dalam. Jika hal itu benar, maka agaknya Lembu Wirid juga merasa getir karena kematian anaknya. Bahkan seperti yang dilaporkan oleh pengikutnya itu, bahwa Kiai Banyu Bening telah membuat satu upacara yang gila. Upacara dengan mengorbankan bayi yang sebenarnya.
“Ia memang, gila!” desis Nyai Wiji Sari.
Namun setelah peristiwa itu lama sekali terjadi, Nyai Wiji Sari itu dapat melihat dengan lebih baik dari jarak yang cukup jauh. Namun setiap kali terbersit penyesalan didalam hatinya, maka Nyai Wiji Sari tentu menghibur dirinya bahwa peristiwa yang memang akan terjadi itu tentu akan terjadi juga.
Dalam pada itu, Kiai Narawangsa yang melihat Nyai Wiji Sari selalu merenung, tidak terlalu sering menegur. Namun beberapa kali ia mengatakan, bahwa mereka akan segera berangkat ke kaki Gunung Lawu untuk melihat dan sekaligus memiliki padepokan tempat anaknya itu dikuburkan. Tetapi Kiai Narawangsa tidak tahu, bahwa yang direnungkan oleh Nyai Wiji Sari tidak sekedar kerinduannya kepada anaknya yang sudah tidak ada serta keinginannya merambah daerah baru.
Tetapi peristiwa yang telah terjadi itu justru selalu membayanginya. Hatinya. Lembu Wirid memang seorang yang sering membohonginya. Ia sering berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya. Tetapi bukan seharusnya Wiji Sari itu menyakiti hatinya terlalu dalam. Bahwa ia membawa Narawangsa ke rumahnya itu sama artinya bahwa ia telah menikam punggung Lembu Wirid.
Ketika sekelompok orang yang ditugaskan pergi ke kaki Gunung Lawu untuk yang kedua kalinya datang, maka Nyai Wiji Sari pun segera memanggil mereka. Bersama Kiai Narawangsa maka Nyai Wiji Sari telah menerima kelima orang yang baru datang dari kaki Gunung Lawu itu.
“Apa yang kalian lihat dan apa yang telah kalian dengar?” bertanya Kiai Narawangsa.
Orang tertua yang memimpin kelompok itu telah memberikan laporan tentang perjalanannya. Iapun telah melaporkan pula, bahwa ia telah melihat keadaan serta isi padepokan itu.
“Kau masuk ke padepokan?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Ya Nyai. Meskipun kami berdua waktu itu tidak berhasil menemui Kiai Banyu Bening.”
“Kau lihat sebuah tugu yang diatasnya terdapat batu nisan kecil?” bertanya Nyai Wiji Sari pula.
“Ya, Nyai. Tugu dan nisan kecil itu masih ada di halaman.”
Nyai Wiji Sari menarik nafas dalam-dalam. Setelah kematian bayinya itu, Nyai Wiji Sari tidak lagi mempunyai keturunan. “Kematian anakku itu adalah kutukan bagiku sebagai seorang perempuan.” berkata Nyai Wiji Sari didalam hatinya.
Namun untuk beberapa lama Nyai Wiji Sari dapat menyembunyikan kegelisahannya itu. Ia telah memasuki satu dunia yang hitam dan gelap. Berkuda di malam hari melalui jalan-jalan panjang, padang-padang rumput dan padang perdu yang luas. Jalan-jalan sempit di pinggir hutan.
Sudah berapa kali ujang pedangnya menikam dada orang yang tidak mau menyerahkan harta bendanya. Sudah berapa kali tajam pedangnya menebas leher orang yang mengadakan perlawanan ketika ia merampok bersama Kiai Narawangsa yang kemudian dianggapnya sebagai suaminya.
Tetapi bagaimanapun juga hidup tanpa keturunan adalah seperti sebatang pohon yang tidak berbuah. Kering. Keterangan pemimpin kelompok yang pergi ke kaki Gunung Lawu itu seakan-akan telah mendesak Nyai Wiji sari untuk segera berangkat mengambil padepokan itu. Rasa-rasanya anaknya itu sudah terlalu lama merengek sambil menjulurkan kedua tangannya.
“Baik, baik. Aku akan segera datang ngger.” Nyai Wiji Sari berkata didalam hatinya.
Keterangan pemimpin kelompok pertama dan kelompok kedua yang hampir bersamaan itu, telah mendorong Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari untuk segera berangkat.
Ketika segala persiapan sudah dianggap cukup, maka Kiai Narawangsa telah memerintahkan sekelompok orang untuk pergi mendahului ke kaki Gunung Lawu. Mereka harus membangunkan landasan bagi seluruh kekuatan yang akan pergi dan kemudian mengambil padepokan di kaki Gunung Lawu itu.
Tetapi Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari tidak pergi berdua saja bersama-sama dengan para pengikutnya. Kiai Narawangsa telah mengajak adiknya serta beberapa orang saudara seperguruannya. Dua orang anak adiknya itu, yang seakan-akan telah diangkatnya menjadi anaknya, akan ikut pula bersama mereka. Dua orang anak muda yang telah ditempa dengan keras sehingga keduanya telah menjadi anak muda yang berilmu tinggi.
“Gunasraba!” berkata Kiai Narawangsa kepada adiknya ”Jika aku sudah mendapat daerah baru, maka aku serahkan padepokan ini kepadamu. Karena itu, aku minta bantuanmu untuk menemukan daerah baru itu.”
“Kenapa kakang tinggalkan padepokan yang telah mapan ini?”
“Di padepokan yang berada di kaki Gunung Lawu itu terdapat makam anak Nyai Wiji Sari. Ia merindukannya dan ingin selalu dekat dengan anaknya itu.”
“Bagaimana dengan pemimpin padepokan itu?” bertanya Gunasraba.
“Namanya Kiai Banyu Bening. Ia adalah bekas suami Wiji Sari, yang dahulu namanya Lembu Wirid. Kita harus merebut padepokan itu dan sekaligus membunuhnya.”
Gunasraba mengangguk-angguk. Katanya, ”Baik kakang, jika itu yang kau maui. Aku akan mengajak dua orang saudara seperguruanku. Anak-anak dan beberapa orang sahabat dan kepercayaanku. Jika kelak aku memimpin padepokan ini, maka setidak-tidaknya mereka akan dapat menumpang tidur dan makan disini disela-sela petualangan mereka.”
“Kau sendiri, sudah waktunya untuk menghentikan petualanganmu dan menetap di sebuah padepokan. Nah, sebentar lagi kau akan mendapat kesempatan.”
Gunasraba tertawa. Katanya, ”Mudah-mudahan aku kerasan tinggal disatu tempat untuk waktu yang lama.”
“Kau harus mencobanya.” berkata Kiai Narawangsa. Gunasraba tertawa semakin keras. Katanya ”Padepokan ini akan menjadi sarang serigala yang ganas. Padepokan ini akan menjadi semakin menakutkan.”
“Terserah saja kepadamu nanti.” sahut Kiai Narawangsa. Di hari-hari terakhir, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari menjadi semakin sibuk mempersiapkan diri.
“Kita tinggal menunggu laporan dari orang-orang yang sedang membuat landasan sebelum kita menyerang padepokan yang dipimpin oleh Kiai Banyu Bening itu.” berkata Kiai Narawangsa kepada adiknya itu.
Nyai Wiji Sari hampir tidak dapat menahan diri lagi untuk menunggu laporan dari sekelompok orang-orangnya yang telah lebih dahulu pergi ke kaki Gunung Lawu. Ia mulai mendesak Kiai Narawangsa untuk berangkat tanpa menunggu lebih lama lagi.
“Kita akan dapat berselisih jalan dengan orang yang akan memberikan laporan kepada kita. Selain itu, kita memang memerlukan seseorang yang akan menuntun perjalanan kita agar tidak diketahui lebih dahulu oleh orang-orang Banyu Bening.”
Nyai Wiji Sari masih mencoba bersabar untuk beberapa hari. Namun akhirnya orang yang ditunggunya itupun datang juga. Dua orang diantara beberapa orang lebih dahulu.
“Kami membuat landasan dipinggir hutan,” berkata salah seorang dari kedua orang itu.
Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari mendengarkan laporan kedua orang itu dengan saksama. Bahkan Kiai Narawangsa minta agar adiknya ikut mendengarkannya pula, agar ia dapat memberikah pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan.
“Ternyata semuanya telah mendukung rencana kita.” berkata Kiai Narawangsa ”Keadaan padepokan Kiai Banyu Bening itu sendiri akan memberikan kesempatan kepada kita untuk dengan cepat menguasainya.”
“Tetapi mereka mengawasi keadaan di seputar padepokan mereka dengan ketat.” berkata salah seorang dari kedua orang itu.
“Apa arti pengawasan yang ketat jika keadaan didalam padepokan itu rapuh?” bertanya Kiai Narawangsa.
“Kami tidak melihat kekuatan yang akan dapat mencegah kita,” berkata orang itu pula.
“Pekan ini kita akan berangkat.” berkata Kiai Narawangsa. Lalu katanya kepada adiknya ”Sebagian dari barang-barang kami akan kami tinggal. Pada kesempatan lain, kami akan mengambilnya.”
Gunasraba mengangguk-angguk. Katanya, ”Baiklah. Sementara kita pergi, biarlah dua orang kepercayaanku menunggui padepokan ini. Mereka akan dapat mencari kawan yang akan dapat dipercaya pula.”
“Baiklah.” berkata Kiai Narawangsa ”Dengan demikian, maka segala persiapan sudah selesai.”
“Semuanya tinggal menunggu perintah kakang.”
“Aku ingin berbicara dengan kedua orang anakmu.” berkata Kiai Narawangsa.
Dua orang anak muda yang bertubuh tegar telah menemui Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari. Dengan nada berat Kiai Narawangsa itupun berkata, ”Aku dan ibumu ingin mengajakmu bertamasya ke kaki Gunung Lawu.”
“Kami sudah menunggu, kapan kita akan berangkat?”
“Aku juga sudah hampir tidak tahan.” berkata Nyai Wiji Sari. “Tetapi aku ingin berpesan kepada kalian, bahwa kita akan memasuki daerah berbahaya di kaki Gunung Lawu itu.”
Kedua orang anak muda itu tertawa. Parung Landung, yang tertua diantara mereka tertawa lebih keras. Katanya ”Bukankah kita ditempa untuk memasuki lingkaran-lingkaran yang paling berbahaya?”
Sementara itu, adiknya, Paron Waja berkata lantang, “Kami sudah siap paman. Apakah paman masih meragukan kami berdua?”
“Tidak. Kami sama sekali tidak meragukan kalian. Kami hanya ingin memperingatkan kalian, agar kalian berhati-hati.”
“Kami akan berhati-hati paman.” sahut Parung Landung. Dalam pada itu maka persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sudah sampai ke puncaknya. Mereka tinggal menunggu saat yang terbaik untuk berangkat ke kaki Gunung Lawu.
Sementara itu, anak-anak muda yang baru memasuki lingkungan padepokan yang dipimpin oleh Ki Lemah Teles dan Ki Warana itu telah berlatih semakin keras. Apalagi dua orang cantrik yang sedang berada disawah melihat dua orang yang nampak mencurigakan. Dua orang yang agaknya sedang mengamati padepokan yang sedang mengalami perubahan landasan dan tatanan itu.
Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Warana, maka Ki Warana itupun berdesis, ”Tidak mustahil bahwa keduanya adalah para pengikut Kiai Narawangsa yang sedang mengamati padepokan kita.”
“Kami juga menyangka demikian, Ki Warana.”
“Baiklah. Kita memang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Meskipun kita tinggal menunggu, tetapi justru karena itu, kita akan selalu berada dalam ketegangan.”
“Kami akan berusaha untuk mengamati orang-orang yang mencurigakan itu Ki Warana.”
“Baiklah. Tetapi berhati-hatilah. Seandainya kita menemukan isyarat bahwa mereka memang para pengikut Kiai Narawangsa, kita tidak harus dengan serta-merta bertindak. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Segala sesuatunya harus diperhitungkan dengan cermat sehingga kita tidak justru terjebak.”
“Ya, Ki Warana.” jawab kedua cantrik itu.
“Baiklah. Aku akan memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan kawan-kawannya itu.”
Ki Lemah Teles yang mendapat laporan itupun kemudian telah membicarakannya dengan Ki Ajar Pangukan, Ki Sambi Pitu, Ki Jagaprana dan Ki Pandi.
“Kita harus mengetahui siapakah mereka itu,” berkata Ki Pandi.
“Jika benar mereka adalah pengikut Kiai Nalawangsa, maka mereka tentu mempunyai tempat persembunyian di sekitar padepokan ini.”
“Aku akan mencarinya,” berkata Kiai Jagaprana.
“Aku ikut.” sahut Ki Sambi Pitu ”Biariah aku mendapat peranan disini. Tanpa peranan yang berarti, maka aku akan menjadi matahari yang redup sebelum senja.”
Ki Ajar Pangukan tertawa. Katanya ”Aku sudah mendapat peranan. Justru peranan terbesar di padepokan ini.”
Namun dalam pertemuan itu telah disepakati, bahwa Ki Jagaprana dan Ki Sambi Pitu akan mengamati orang-orang yang mencurigakan itu.
“Jangan Ki Pandi.” berkata Ki Ajar Pangukan ”Ketika dua orang utusan Kiai Narawangsa menemui Kiai Banyu Bening Ki Pandi duduk bersamaku.”
Ki Pandi tertawa pendek. Katanya ”Orang-orang seperti aku ini tentu akan dapat dengan mudah dikenali orang.”
“Kau sendiri yang mengatakannya Ki Bongkok.” sahut Ki Ajar Pangukan.
Sementara itu, Ki Jagaprana pun berkata, ”Nanti malam, aku akan mulai.”
Tetapi keduanya tidak dapat dengan serta-merta melakukannya. Mereka harus berbicara dahulu dengan dua orang cantrik yang pernah melihat kedua orang yang mencurigakan itu ketika keduanya berada di sawah. Darimana mereka datang dan kemana mereka pergi.
Dengan bahan itu, maka keduanya akan dapat memperkirakan arah yang akan mereka datangi malam nanti. Tugas-yang berbahaya itu memang tidak dapat diserahkan kepada para cantrik. Untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya maka tugas itu memang harus dilakukan oleh orang yang berilmu tinggi. Apalagi jika Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sudah berada diantara mereka. Maka untuk dapat mendekat, diperlukan kemampuan yang tinggi.
Untuk mendapat hasil yang sebaik-baiknya, maka Ki Sambi Pitu dan Jagaprana tidak dengan tergesa-gesa mencari tempat persembunyian orang-orang itu. Tetapi dihari berikutnya, mereka telah ikut pergi ke sawah. Dengan memanggul cangkul serta memakai caping bambu mereka bersama dua orang cantrik telah pergi ke sawah. Dibawah panasnya matahari yang memanjat semakin tinggi, mereka berendam di air berlumpur sambil mengayunkan cangkul mereka.
Sebenarnya, mereka melihat dua orang yang mencurigakan lewat meniti pematang. Mereka memang hanya berjalan melintas. Tetapi keduanya mengamati padepokan itu dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana memperhatikan arah kemana mereka pergi. Tidak terlalu jauh dari padepokan mereka berjalan melingkar. Juga masih meniti pematang. Mereka berjalan menjauh, kemudian memutar kembali kearah hutan kaki pegunungan.
“Kita akan melihat malam nanti, apa yang ada dihutan itu,” desis Ki Jagaprana.
“Kita sudah dapat menduga, dimana mereka bersembunyi” berkata Ki Sambi Pitu.
“Ya. Asap itu.”
“Ternyata mereka memang dungu.”
“Atau kita yang dungu, jika kita begitu saja percaya, bahwa mereka memang berada disekitar perapian itu.”
Keduanya mengangguk-angguk. Ki Sambi Pitu lah yang kemudian berkata ”Baiklah. Biarlah malam nanti kita akan membuktikannya.”
Seperti yang direncanakan oleh kedua orang itu, maka ketika senja turun, keduanya pun telah bersiap. Demikian gelap menyelimuti padepokan itu, maka mereka berdua telah keluar lewat regol butulan untuk melihat-lihat hutan lebat di kaki Gunung Lawu itu. Dengan hau-hati keduanya kemudian menyusuri pinggir hutan. Yang menjadi sasaran utama adalah arah asap yang mereka lihat mengepul itu.
Ternyata orang-orang itu memang kurang berhati-hati. Malam itu mereka juga membuat perapian untuk melawan dingin meskipun tidak begitu besar. Mereka memang sudah berusaha untuk melindungi nyala api perapian itu dengan bebatuan. Namun warna merah yang menapak pada batang-batang pepohonan masih juga dapat dilihat oleh Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana.
“Ternyata tidak terlalu sulit.” desis Ki Jagaprana.
Ki Sambi Pitu tidak menjawab. Namun mereka telah merayap semakin mendekati orang-orang yang berada di sekitar perapian. Namun yang dilihat oleh kedua orang itu bukan sekedar perapian. Ternyata mereka melihat berbagai macam bahan dan peralatan yang teronggok tidak terlalu jauh dari tempat mereka membuat perapian.
Ki Sambi Pitu memberi isyarat kepada Ki Jagaprana untuk melihat benda-benda yang teronggok diantara pepohonan hutan itu. Keduanya mengangguk-angguk meskipun mereka tidak saling berbicara. Mereka melihat potongan-potongan dan anyaman bambu. Tali ijuk dan seonggok batang ilalang. Didalam hati mereka berkata, ”Orang-orang ini tentu akan membuat gubug yang cukup besar.”
Apalagi, mereka juga melihat sebidang tanah yang sudah dibersihkan, siap untuk membangun sebuah gubug. Beberapa saat kedua orang itu mengamati lingkungan itu. Baru kemudian, Ki Sambi Pitu telah memberikan isyarat, agar mereka meninggalkan tempat itu. Demikian keduanya menjauhi tempat itu, maka Ki Sambi Pitu pun berkata,
”Nampaknya mereka akan membuat sebuan pesanggrahan.”
“Ya!” Ki Jagaprana mengangguk-angguk.
“Tentu bagi Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari. Sedangkan yang lain akan dapat berada disembarang tempat.”
Ki Jagaprana mengangguk-angguk. Katanya, ”Menilik tempat yang dipersiapkan, tentu banyak orang yang akan datang.”
“Tentu akan meriah.” desis Ki Sambi Pitu.
“Mudah-mudahan kerajaan Ki Lemah Teles tidak segera berakhir.”
Demikian mereka sampai di padepokan, maka keduanya pun segera menceriterakan kepada orang-orang tua yang berilmu tinggi, yang memang menunggu kedatangan Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana.
“Menarik sekali.” desis Ki Ajar Pangukan ”Karena itu, maka kita harus benar-benar bersiap untuk menyambut kehadiran mereka. Kita tidak tahu pasti, berapa besar kekuatan mereka, sehingga karena itu, maka yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan kekuatan penuh untuk menyambut mereka.”
“Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari tentu sudah bersiap-siap pula. Besok mereka tentu sudah akan mendirikan gubug itu. Sehingga dalam dua tiga hari lagi, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari tentu sudah akan datang.”
“Baiklah.” berkata Ki Lemah Teles ”Kita akan bersiap untuk menyongsong kehadiran tamu-tamu Kiai Bayu Bening itu. Karena itu, sebaiknya penyambutan itu dipimpin oleh Kiai Banyu Bening sendiri...”
Selanjutnya,
MATAHARI SENJA BAGIAN 18
MATAHARI SENJA BAGIAN 18