Matahari Senja
Bagian 16
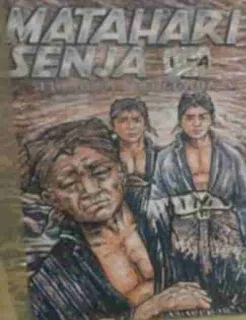
KEDUA orang itu terkejut. Mereka saling berpandangan sejenak, sementara Ki Warana berkata selanjutnya ”Mungkin kalian pernah melihat sepuluh tahun yang lalu atau bahkan lebih, sehingga kalian tidak dapat mengenalinya lagi. Sepeninggal anak bayinya, perubahan itu terlalu cepat terjadi, sehingga Ki Banyu Bening menjadi cepat nampak tua.”
Kedua orang itu nampak ragu-ragu. Sementara itu sambil memandang Ki Ajar Pangukan orang itu berkata ”Apakah kau dapat mengenalinya?”
Kedua orang itu memandang Ki Ajar Pangukan dengan penuh keragu-raguan. Sementara itu, Ki Ajar Pangukan sendiri agak terkejut mendengar pernyataan Ki Warana itu. Tetapi Ki Ajar Pangukan tidak dapat mengelak dari permainan itu. Karena itu maka iapun kemudian berkata,
”Ki Sanak. Jika kalian pernah mengenal aku sebelumnya, tolong beritahu aku, siapakah kalian. Aku sudah menjadi pikun sekarang. Banyak sekali hal yang telah aku lupakan. Aku juga sudah tidak lagi dapat mengenali orang-orang yang pernah tidur dan makan bersama. Sejak anakku meninggal didalam api, segala-galanya seakan-akan telah larut dari duniaku. Yang aku ingat hanyalah tugu dan batu nisan kecil itu serta tulang-tulang yang hangus yang ada didalamnya.”
Yang tertua diantara kedua orang itupun kemudian berkata sambil menarik nafas dalam-dalam, ”Kiai Banyu Bening. Kami mohon maaf, bahwa kami mengaku telah mengenal Kiai. Sebenarnyalah kami memang belum pernah mengenal. Yang kami ketahui adalah sekedar ancar-ancar. Ternyata Kiai sama sekali berbeda dengan ancar-ancar yang telah kami terima.”
Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk. Katanya, ”Bagiku, apakah kalian pernah mengenal aku atau tidak, sama sekali tidak ada bedanya. Seandainya kita pernah berhubungan, maka aku tidak akan pernah ingat, siapakah kalian?”
“Kenapa Kiai cepat menjadi pikun?” bertanya yang termuda diantara kedua orang itu.
Ki Ajar Pangukan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ”Aku tidak tahu. Tetapi sepeninggal anakku, rasa-rasanya masa laluku ikut hilang pula terkubur dibawah batu nisan kecil itu.”
“Kiai sangat menyesal atas kematian anak Kiai itu?”
Wajah Ki Ajar Pangukan menjadi tegang. Dengan lantang ia berkata, ”Kenapa kau bertanya seperti itu? Kau telah menyinggung perasaanku. Ingat, meskipun aku pikun, tetapi aku masih tetap menguasai ilmuku dengan baik. Selama tugu dan nisan itu ada disitu, maka ilmuku tidak akan pudar. Aku tinggal memerlukan beberapa hari lagi untuk mencapai puncak kejayaan ilmuku. Setelah itu, maka apapun yang terjadi, bahkan seandainya gempa mengguncang dan membuat tanah ini menganga sehingga tugu dan nisan itu tenggelam, maka ilmuku sudah tidak akan mungkin goyah lagi.”
Kedua orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Ajar Pangukan itupun bertanya, ”Nah, sekarang katakan, untuk apa kalian datang kemari?”
“Kiai...” berkata yang tertua diantara keduanya. ”Kami datang untuk menyampaikan pesan dari pemimpin kami.”
“Siapa? Apakah aku pernah mengenalnya dahulu?”
“Tentu, Kiai. Kiai pernah mengenalnya dahulu. Aku tidak tahu, apakah kiai masih dapat mengingatnya atau tidak.”
“Sudah aku katakan. Masa laluku sudah terkubur bersama tulang-tulang yang hangus dibawah nisan kecil itu. Semuanya gelap sama sekali. Tetapi katakan, barangkali aku dapat mengingatnya.”
”Kiai tentu ingat. Pemimpin kami adalah Kiai Narawangsa.”
“Narawangsa. Narawangsa. Aku pernah mendengar nama itu.”
“Bukan hanya pernah mendengar tetapi Kiai tentu akan teringat kepada orang itu.”
Ki Ajar Pangukan memandang Ki Warana sejenak, seakan-akan ingin menuntutnya, bahwa ia sudah menjerumuskannya kedalam kesulitan.
Namun Ki Warana lah yang kemudian menyahut, ”Kiai. Mungkin Kiai telah melupakannya. Tetapi Kiai pernah berceritera kepadaku dahulu, bahwa orang yang bernama Kiai Narawangsa itu adalah orang yang pernah berhubungan dengan isteri Kiai. Perkelahian antara Kiai dan Kiai Narawangsa itulah, ini menurut ceritera Kiai yang pernah aku dengar, menyebabkan rumah Kiai terbakar. Kiai sempat menghindari api, sementara Kiai Narawangsa dan isteri Kiai melarikan diri. Tetapi bayi itu tertinggal didalam api.”
“O...” Ki Ajar Pangukan menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Katanya “Ya. Narawangsa. Orang gila itu.”
Ki Pandi lah yang harus menahan tertawa yang seakan-akan hendak meledak didalam dadanya. Untunglah bahwa ia mampu melarutkan diri kedalam permainan itu.
“Terkutuklah orang itu!” desis Ki Ajar Pangukan ”Meskipun aku sudah pikun, aku tidak dapat melupakan nama itu. Tetapi aku tidak yakin bahwa aku masih dapat mengenali wajahnya.”
“Kiai Narawangsa mudah sekali dikenal, Kiai. Tubuhnya seperti raksasa. Kiai ingat? Ia tidak pernah mengenakan ikat kepala sewajarnya. Ikat kepalanya lebih banyak disangkutkan di lehernya daripada dipakai di kepalanya. Di wajahnya terdapat cacat karena goresan pedang.”
“Aku ingat itu. Tetapi wajahnya tidak cacat pada waktu itu.”
“Kiai benar!” jawab yang tertua diantara kedua orang itu ”Tentu Kiai tidak pernah melihat wajahnya terluka, karena luka itu terjadi pada saat Kiai Narawangsa bertempur melawan Kiai Banyu Bening saat itu. Saat api menyala dan menelan rumah beserta bayi itu.”
“Kenapa aku tidak mengoyak lehernya pada waktu itu.” desis Ki Ajar Pangukan.
“Ternyata usia Kiai Narawangsa masih panjang.”
“Terkutuklah orang itu. Terkutuklah orang itu!” berkata Ki Ajar Pangukan dengan lantang.
Ki Pandi yang mendengarnya bergeser ke samping. Kemudian duduk dengan kepala menunduk sehingga dahinya hampir menyentuh tikar pandan tempatnya duduk. Ki Pandi tidak ingin wajahnya dilihat oleh kedua orang tamu yang telah dikelabui oleh Ki Warangka itu.
Dengan lantang Ki Ajar Pangukan itupun kemudian bertanya, ”Sekarang, apa yang ingin kalian katakan kepadaku. Nama itu telah membuat darahku mendidih. Sebelum aku berbuat sesuatu diluar kendali nalarku. Katakan apa yang harus kalian katakan.”
“Kiai...” nampaknya kedua orang itu terpengaruh melihat sikap Ki Ajar Pangukan ”Kami hanyalah sekedar utusan. Jika tidak berkenan di hati Kiai, janganlah menjadi murka kepada kami.”
“Katakan!” geram Ki Ajar Pangukan.
“Kiai...” desis yang tertua diantara mereka ”Kiai Narawangsa ingin minta agar Kiai memberinya kesempatan untuk merawat dan memakamkan kembali bayi itu dengan upacara khusus.”
“Gila...” suara Ki Ajar Pangukan menggelegar, sehingga kedua orang itu mundur setapak ”Kau menghina aku, he?”
“Bukan kami Kiai, Bukan kami.”
”Mulutmulah yang mengucapkannya.”
“Tetapi kami adalah sekedar utusan.”
“Katakan.” suara Ki Ajar Pangukan menurun.
“Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari...”
“Jangan sebut nama Nyai Banyu Bening itu. Kiai Banyu Bening tidak mau mendengar lagi nama isterinya.” potong Ki Warana.
“Terkutuklah semuanya, terkutuklah.” geram Ki Ajar Pangukan. Sebenarnya ia bingung mendengar nama Nyai Wiji Sari. Tetapi Ki Warana pun tangkas berpikir sehingga ia telah memberi tahukan kepada Ki Ajar Pangukan, siapakah Nyai Wiji Sari itu.
“Ampun, Kiai.” desis yang tertua.
“Katakan.” desis Ki Ajar Pangukan ”Tetapi jangan sebut nama itu. Aku telah mengutuk diriku sendiri. Jika aku melupakan masa laluku, kenapa nama itu tidak pernah dapat aku lupakan.”
“Baik, baik, Kiai.” sahut yang tertua itu ”Sebenarnyalah mereka berdua ingin memakamkan kembali di halaman ini pula dan untuk selanjutnya ingin merawatnya.”
“He, kau sadar apa yang kau katakan?”
“Bukan aku, Kiai. Tetapi aku sekedar menyampaikan pesan Kiai Narawangsa.”
“Katakan, katakan!” Ki Ajar Pangukan hampir berteriak.
“Keduanya ingin tinggal di padepokan ini untuk menunggui dan merawat makam bayi itu. Sementara itu mereka mohon Kiai Banyu Bening dan para cantrik yang ada disini untuk meninggalkan padepokan ini,”
Mata Ki Ajar Pangukan terbelalak. Dari sorot matanya memancar api kemerahan. Dengan suara lantang Ki Ajar Pangukan itu berkata, ”pergi. Pergi. Jika kalian tidak segera pergi, aku pancung kau dibawah tugu dan batu nisan itu.”
“Bukan kehendak kami, Kiai.”
“Pergi, kau dengar!” bentak Ki Ajar Pangukan. Lalu katanya kepada Ki Warana ”Antar kedua orang ini keluar dari padepokan.”
Ki Waranapun segera bangkit dan berkata, ”Marilah Ki Sanak. Cepatlah sedikit.”
Kedua orang itupun kemudian bangkit pula sambil berdesis ”Kami mohon diri, Kiai.”
“Cepat pergi. Kalian telah menyakiti mataku, telingaku dan hatiku.”
“Cepat sedikit,” desis Ki Warana, “ Jika darahnya naik sampai ke kepala, hati-hatilah kalian tak akan pernah keluar dari padepokan ini.”
Kedua orang iiu tiba-tiba saja kehilangan segala kegarangan dan keberanian mereka. Keduanya pun melangkah dengan cepat melintasi halaman diantar oleh Ki Warana.
Para cantrik yang berada diregol pun telah membuka selarak pintu regol itu dan membukanya. Demikian keduanya keluar dari regol halaman, Ki Warana pun berkata, ”Itulah sosok orang yang kalian cari Ki Sanak. Kalian harus dapat menempatkan diri kalian, jika kalian menyampaikan jawaban Kiai Banyu Bening agar pemimpin kalian tidak terbakar hatinya.”
Ketika kedua orang itu merasa sudah berada diluar padepokan, maka keberanian mereka telah menyala kembali didalam dada mereka, sehingga yang muda diantara merekapun menjawab, ”Kami tidak akan mengulas keterangan Kiai Banyu Bening, Ki Sanak. Kami justru akan membakar hati Kiai Narawangsa. Dengan demikian padepokan inipun akan terbakar habis menjadi abu sebagaimana rumah Nyai Wiji Sari serta anaknya. Kau jangan mengira bahwa Nyai Wiji Sari tidak tersiksa oleh kematian anaknya itu.”
“Tetapi ia tidak menjadi gila seperti Kiai Banyu Bening. Jika kau sempat mendatangi padukuhan-padukuhan, maka dipadukuhan-padukuhan itu telah dibangun sanggar-sanggar khusus untuk menyerahkan korban. Mula-mula hanya buah-buahan. Kemudian anak seekor binatang yang dipersembahkan hidup-hidup, dibakar diatas lantai yang khusus dibuat untuk itu. Pada saat terakhir, Kiai Banyu Bening telah memerintahkan, yang dipersembahkan adalah bayi-bayi yang masih hidup untuk dibakar. Kiai Banyu Bening akan mendapat kepuasan batin tertinggi jika ia mendengar jerit bayi yang terbakar itu. Dendamnya karena kematian bayinya telah menjadikannya gila.”
Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Hampir diluar sadarnya ia berkata, ”Jadi korban yang dituntut oleh Kiai Banyu Bening itu membakar bayi hidup-hidup.”
“Ya...!”
Keduanya saling berpandangan sejenak. Namun kemudian iapun berkata ”Semuanya akan kami katakan kepada Kiai Narawangsa. Tetapi kau harus mengatakannya kepada Kiai Banyu Bening, bahwa Kiai Narawangsa adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Demikian pula isterinya, Nyai Wiji Sari. Karena itu, jika keduanya datang kemari dan memaksakan kehendaknya, maka itu akan menjadi pertanda buruk bagi Kiai Banyu Bening.”
“Terserah kepadamu. Apakah kau akan berusaha mencegah pemimpinmu agar tidak datang kemari atau tidak. Jika kau tidak mencegahnya dengan cara apapun juga, maka sepanjang hidupmu, kau akan dibebani penyesalan, karena keduanya akan mati disini.”
Yang termuda diantara keduanya itu menyahut, ”Jangan berusaha menakut-nakuti kami. Kami bukan pengecut.”
“Baiklah. Datanglah kemari. Bawa Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari. Kami akan segera menyiapkan batu nisan bagi mereka berdua. Mayat mereka akan dikubur disebelah-menyebelah tugu itu, karena didunia langgeng, mereka akan menjadi hamba dari bayi yang meninggal karena terbakar itu.”
“Impian gila.” geram yang muda.
Namun Ki Warana malah berkata, ”Tetapi kematian yang paling buruk yang dapat terjadi atas Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari adalah, bahwa keduanya juga akan menjadi persembahan yang akan dibakar hidup-hidup.”
“Satu gagasan yang baik.” geram yang tertua ”Kiai Narawangsa akan memperlakukan Kiai Banyu Bening seperti itu.”
Ki Warana tertawa. Katanya ”Pulanglah sebelum Kiai Banyu Bening memerintahkan para cantrik menangkapmu dan menyeretmu kembali ke pendapa. Kalian tentu melihat tonggak besi yang sudah menjadi hitam di sebelah pendapa itu. Kalian tentu dapat membayangkan gunanya.”
Keduanya pun kemudian meninggalkan padepokan itu. Disepanjang jalan mereka masih saja berbincang tentang orang-orang padepokan itu. Namun mereka pun mengakui, betapa besarnya wibawa Kiai Banyu Bening, sehingga dihadapannya, keduanya seakan-akan telah dihadapkan pada sebuah pengadilan yang sedang mengadili mereka.
“Kiai Narawangsa akan membuat Kiai Banyu Bening itu menundukkan kepalanya” berkata yang tertua diantara keduanya.
Yang muda itupun mengangguk-angguk sambil berkata, ”Aku tidak mengira, bahwa Kiai Banyu Bening adalah seorang yang luar biasa. Gambaranku tentang Kiai Banyu Bening sebagaimana sering aku dengar dari pembicaraan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sama sekali berbeda. Aku tidak membayangkan bahwa Kiai Banyu Bening itu mempunyai wibawa yang begitu tinggi.”
“Apa yang dikatakan oleh Kiai Narawangsa itu adalah Kiai Banyu Bening dimasa lampau. Demikian ia kehilangan anaknya, maka Kiai Banyu Bening nampaknya telah menghabiskan waktunya untuk memperdalam ilmunya, sehingga ia hampir lupa segala-galanya.”
Kawannya mengangguk-angguk. Bagaimana pun juga, diluar sadar, setiap kali mereka mengatakan bahwa Kiai Banyu Bening adalah seseorang yang mumpuni. Dalam pada itu, ketika kedua orang itu melangkah pergi, maka Ki Warana pun segera kembali ke pendapa. Ia termangu-mangu sejenak, melihat Ki Pandi tertawa. Bahkan kemudian katanya,
”Perutku terasa sakit karena aku harus menahan tertawa. Tetapi Ki Ajar Pangukan benar-benar seorang yang mampu mengelabuhi orang lain. Ki Ajar benar-benar mampu menjadi Kiai Banyu Bening.”
Ki Warana pun tertawa pula. Namun Ki Ajar itupun berkata ”Ki Warana mengejutkan aku. Tiba-tiba saja sebelum kita berbicara lebih dahulu, aku ditunjuknya langsung menjadi Kiai Banyu Bening.”
“Aku sudah tidak mempunyai waktu lagi.” berkata Ki Warana.
“Tetapi apakah keberatannya jika kita katakan berterus-terang tentang padepokan ini.”
“Aku kira apapun alasannya, namun agaknya mereka akan tetap menuntut tanah ini, tanah yang diatasnya terdapat sebuah padepokan yang sudah berada di tangan kita.”
“Jika tanah dan padepokan ini bukan lagi milik Kiai Banyu Bening, apakah mereka juga akan menuntut? Sedangkan sebelumnya kita tidak saling mengenal dengan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.” desis Ki Ajar Pangukan.
“Kita masih belum tahu benar, apakah yang sebenarnya mereka kehendaki. Apakah Nyai Wiji Sari dengan jujur ingin mendapatkan kembali anaknya yang telah lama meninggal atau alasan-alasan lainnya. Karena itu, selagi Ki Ajar, Ki Pandi dan yang lain ada disini, biarlah persoalannya diselesaikan dengan tuntas.”
Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk. Ia mengerti kecemasan yang mencengkam jantung Ki Warana yang merasa bahwa ilmunya masih belum memadai. Karena itu, maka Ki Warana memerlukan perlindungan dari beberapa orang yang berilmu tinggi.
Namun dalam pada itu, maka Ki Ajar Pangukan itupun berkata ”Ki Warana, dengan pengakuan ini, maka kemungkinan terbesar, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari tentu akan datang ke padepokan ini. Karena itu, maka Ki Warana sebaiknya mempersiapkan orang-orang yang kini masih berada di padepokan ini. Kekuatan padepokan ini telah menyusut jauh dibandingkan pada saat Kiai Banyu Bening masih berada di padepokan ini.”
“Benar Ki Ajar. Tetapi yang tinggal sekarang adalah orang-orang yang lebih mapan. Mereka mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi atas diri mereka disaat Kiai Banyu Bening masih memimpin padepokan ini. Sedangkan sekarang mereka berada disini karena satu keyakinan yang lebih dewasa.”
Ki Ajar Pangukan itupun berkata ”Baiklah. Kita akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kiai Narawangsa. Tetapi kita tidak boleh sekedar berpangku tangan.”
Demikianlah, maka Ki Ajar Pangukan pun telah memanggil beberapa orang tua yang ada di padepokan itu. Dengan singkat Ki Ajar telah menceriterakan apa yang telah dibicarakan dengan kedua orang yang mengaku utusan Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari.
“Seharusnys Ki Lemah Teles lah yang harusmengaku sebagai Kiai Banyu Bening” berkata Ki Ajar Pangukan.
“Kenapa aku?” bertanya Ki Lemah Teles.
“Bukankah kita sudah sepakat, bahwa Ki Lemah Teles akan berada di padepokan ini untuk seterusnya?”
Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Tetapi kemudian iapun berkata ”Tetapi biarlah kali ini Ki Ajar Pangukan yang akan berperan sebagai Kiai Banyu Bening.”
Ki Pandi pun tertawa sambil berkata ”Ki Ajar telah memainkan peranannya dengan baik sekali. Tetapi jika Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari yang datang kemari, maka mereka akan merasa bahwa mereka telah dikelabui oleh orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal.”
Dengan demikian, maka orang-orang tua itu berpendapat, bahwa padepokan itu harus mempersiapkan diri menghadapi orang yang menyebut dirinya Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari, yang telah bertahun-tahun mencari orang yang bernama Kiai Banyu Bening itu.
Dalam pada itu, Ki Ajar Pangukan pun berkata kepada Ki Warana ”Aku memerlukan pengenalan lebih jauh tentang pribadi Kiai Banyu Bening serta kehidupan yang mengelilinginya.”
“Sejauh aku ketahui, Ki Ajar.” jawab Ki Warana.
“Tetapi darimana Ki Warana mengetahui kehidupan Kiai Banyu Bening yang tidak bening itu?” bertanya Ki Pandi.
“Kiai Banyu Bening memang sering berbicara tentang dirinya. Jika ia mulai dibayangi oleh kehidupan masa lampaunya, maka ia memerlukan seseorang yang mau mendengarkan ceriteranya. Bukan hanya aku yang pernah mendengarnya, tetapi beberapa orang yang lainpun pernah mendengarnya. Ceritera-ceritera itulah yang membuat aku semakin lama semakin ragu akan kepemimpinannya. Aku memang mendengar dan merasakan, bahwa apa yang dilakukannya itu tidak lebih dari ungkapan dendam yang mencengkam hatinya.”
“Baiklah” berkata Ki Ajar ”Jita tidak boleh membuang waktu. Kita siapkan apa yang ada untuk mempertahankan tanah dan padepokan ini dari siapapun juga.”
Ki Warana pun kemudian telah menemui beberapa orang pemimpin kelompok di padepokannya. Mereka mendapat penjelasan tentang kemungkinan yang dapat terjadi atas padepokan itu.
“Kita belum sempat menyusun padepokan ini dan membuat tatanan baru yang lebih baik, kita sudah dihadapkan pada satu persoalan baru yang lebih baik, kita sudah dihadapkan pada satu persoalan baru. Tetapi kita harus tegar menghadapinya. Orang-orang tua yang berilmu tinggi itu masih tetap berada disini. Mereka bukan saja akan membimbing kita untuk mempertahankan padepokan ini, tetapi merekapun akan dapat membimbing kita menempuh jalan kehidupan yang baru. Kita akan lebih mengenali diri kita dan mengenali sumber hidup kita.”
Para pemimpin kelompok orang-orang padepokan yang semula adalah pengikut Kiai Banyu Bening itu mengangguk-angguk. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan mendatang.
Namun dalam pada itu, niat orang-orang tua yang berada di padepokan itu membongkar tugu dan menempatkan nisan kecil itu ke tempat yang lebih wajar, terpaksa ditunda. Meskipun keberadaan tugu itu tidak lagi mempunyai arti sebagaimana sebelumnya, tetapi mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari dengan anaknya yang telah meninggal itu.
Seperti yang dikehendaki oleh Ki Warana, maka orang-orang yang berada di padepokan itupun telah mulai mempersiapkan diri. Mereka telah memperbaiki panggungan-panggungan yang telah rusak di belakang dinding padepokan. Mereka pun telah mulai berlatih pula dengan sebaik-baiknya. Bahkan orang-orang tua yang berilmu tinggi, telah ikut terjun langsung didalamnya.
Namun orang-orang tua yang berilmu tinggi itu mempunyai cara tersendiri. Disamping memberikan latihan-latihan kepada semua orang yang ada di padepokan, mereka telah memilih beberapa orang untuk mendapat latihan-latihan khusus. Orang-orang tua yang berilmu tinggi itu masing-masing memilih empat atau lima orang untuk ditempa menjadi orang-orang terbaik di padepokan itu. Dalam benturan kekuatan mereka akan menjadi kekuatan yang harus mampu menembus pertahanan lawan dan mengoyaknya.
Sementara itu, Manggada dan Laksanapun mempunyai kawan-kawan berlatih yang khusus pula. Kelebihan Manggada dan Laksana mampu mengangkat orang-orang yang mereka pilih ke tataran yang lebih tinggi. Kedua orang anak muda itu telah mempergunakan waktu sebaik-baiknya, karena mereka mengetahui bahwa waktu memang sangat sempit.
Meskipun demikian, Manggada dan Laksana sendiri tidak mengabaikan latihan-latihan untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Dengan alat-alat yang ada di dalam sanggar di padepokan itu, keduanya dengan sungguh-sungguh telah menempa diri mereka sendiri pula.
Ternyata usaha itu tidak sia-sia. Empat atau lima orang yang ditangani langsung oleh orang-orang berilmu tinggi itu telah meningkat lebih cepat. Ki Warana sendiri telah bekerja dengan tanpa mengenal lelah untuk menyadap ilmu kanuragan. Ia merasa masih jauh ketinggalan sehingga untuk mencapai tataran yang lebih baik, maka ia harus berbuat sejauh dapat dilakukannya.
Sementara itu, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari selalu menunggu laporan dari orang-orang yang diperintahkannya mencari dan menemui Kiai Banyu Bening. Dua orang yang datang ke padepokan yang semula memang dihuni oleh Kiai Banyu Bening itu telah meninggalkan lereng Gunung Lawu bersama sekelompok kawan-kawannya.
Mereka akan memberikan laporan tentang perjalanan mereka untuk mencari dan menemui Kiai Banyu Bening. Orang itu harus menempuh perjalanan yang panjang untuk sampai ke sebuah padepokan yang dipimpin oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.
Sekelompok orang itu menyusuri Kali Grompol untuk beberapa lama. Kemudian mereka berbelok meninggalkan Kali Grompol menyilang sampai kesebuah tempuran. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri Kali Regunung yang panjang.
Perjalanan mereka memang bukan perjalanan yang ringan. Mereka sekali-sekali harus menyusup di lebatnya hutan belukar, sekali-sekali mereka harus menembus padang perdu yang panjang. Mereka harus melewati pegunungan gundul dan dibakar teriknya sinar matahari.
Sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu tidak dapat mencapai padepokan mereka dalam sehari. Mereka harus berhenti dan bermalam diperjalanan. Untuk mendapatkan makan, mereka harus berburu di hutan yang lebat sehingga dengan demikian maka perjalanan mereka menjadi semakin terhambat.
Sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu maju dengan sangat lamban. Karena itu, untuk mencapai padepokannya, mereka memerlukan waktu yang panjang. Bahkan ternyata mereka masih belum mencapai Kiai Narawangsa yang terletak tidak terlalu jauh dari Kademangan Susukan ditepi Kali Gandu, ketika malam turun di hari kedua.
Meskipun mereka tahu, bahwa padepokan mereka sudah tidak terlalu jauh lagi, tetapi mereka tidak melanjutkan perjalanan. Jalan yang mereka, lalui adalah jalan pintas yang rumpil, yang kadang-kadang melewati tebing yang curam, naik lereng bukit-bukit dan menuruni lembah yang ditumbuhi belukar.
Karena itu mereka lebih senang memilih untuk bermalam dipadang perdu yang tidak terlalu luas. Bergantian orang-orang itu berjaga-jaga. Mungkin binatang buas dari hutan yang tidak terlalu jauh dari padang perdu itu sedang kelaparan karena mereka tidak berhasil menangkap kijang.
Menjelang matahari terbit, mereka telah melanjutkan perjalanan mereka menuju ke padepokan mereka yang berada di tepi Kali Gandu. Sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu mendekati regol padepokan mereka sebelum matahari mencapai puncak langit. Orang tertua diantara mereka menjadi berdebar-debar. Hampir diluar sadarnya ia bertanya kepada kawan-kawannya,
”Bukankah perjalanan kita ini dapat dikatakan berhasil?”
“Ya. Kita sudah berhasil melaksanakan perintah Kiai Narawangsa dengan baik. Kita sudah menemukan padepokan Kiai Banyu Bening. Kita telah menemukan pula makam anak Nyai Wiji Sari. Bukankah menemukan makam itu termasuk salah satu tugas kita yang penting?”
“Untunglah bahwa makam kecil itu berada didalam padepokan, sehingga kita tidak harus mencarinya lagi. Bahkan seandainya makam itu tidak berada di padepokan, maka Kiai Banyu Bening tentu tidak akan bersedia memberitahukannya."
“Karena itu, kita akan memasuki regol halaman padepokan kita dengan dada tengadah. Kita akan dapat membanggakan diri, bahwa akhirnya kitalah yang berhasil menemukan apa yang dicari Kiai Narawangsa untuk waktu yang lama itu setelah beberapa kali kelompok-kelompok yang lain mengalami kegagalan.”
Namun seorang diantara mereka menjawab, ”Meskipun gagal, tetapi kelompok-kelompok yang lain telah mengumpulkan banyak keterangan sehingga kita dapat langsung mencari padepokan itu di kaki Gunung Lawu.”
Orang tertua yang memimpin sekelompok orang itu memandanginya dengan tajamnya, Namun kemudian iapun berkata, ”Kau pernah ikut-ikut dalam kelompok-kelompok sebelum kita pergi ke Gunung Lawu.”
“Ya.” jawab orang itu.
Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Katanya ”Kami tidak akan mengingkari petunjuk-petunjuk itu.”
Mereka pun kemudian terdiam. Langkah mereka semakin mendekati regol padepokan. Beberapa saat kemudian maka sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu telah berdiri di depan regol. Orang yang tertua diantara mereka, yang memimpin sekelompok orang itu, telah mengetuk pintu regol padepokan. Sejenak kemudian, maka sebuah lubang persegi ampat di pintu padepokan itu terbuka. Nampak sebuah wajah di lubang segi empat itu memandang ke luar.
“Bukalah pintunya!” berkata orang tertua yang memimpin kelompok itu.
“He, kau kakang” terdengar orang yang menjengukkan wajahnya itu menyahut.
“Buka pintunya.”
“Baik, baik kakang” jawab orang yang berada didalam.
Demikianlah, maka sejenak kemudian pintu regol itupun telah terbuka. Dua orang cantrik berdiri di belakang pintu itu. Dengan wajah yang cerah mereka telah mempersilahkan sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu masuk.
“Kiai ada dirumah?” bertanya orang tertua itu.
“Kiai dan Nyai baru saja pergi, kakang. Tetapi tentu tidak lama.”
“Kemana?”
“Aku tidak tahu. Tetapi mereka akan segera kembali. Mereka hanya membawa dua orang pengiring.”
Orang tertua yang memimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Sementara penjaga regol itu berkata ”Sambil menunggu, kakang sempat beristirahat barang sejenak. Mungkin kakang akan mandi dan makan dahulu.”
Orang tertua yang memimpin sekelompok orang untuk mencari padepokan Kiai Banyu Bening itu mengangguk-angguk. Katanya kepada kawan-kawannya yang menyertainya ”Marilah. Kita akan sempat beristirahat. Tetapi kita tidak wajib menceriterakan perjalanan kita sebelum kita memberikan laporan kepada Kiai Narawangsa.”
Kawan-kawannya pun mengerti maksud pemimpinnya itu. Karena itu, maka mereka pun harus tetap menyimpan ceritera perjalanan mereka. Kedatangan sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu disambut hangat oleh kawan-kawannya. Namun tidak seorang pun diantara mereka yang mau menceriterakan pengalaman perjalanan mereka.
“Kami belum memberikan laporan kepada Kiai Narawangsa.” berkata salah seorang diantara mereka.
“Apa salahnya? Jika kau centerakan kepada kami, bukankah laporanmu masih utuh?” desak kawannya.
Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, ”Kiai Narawangsa akan merasa dilampaui jika ia tahu, bahwa aku telah berceritera lebih dahulu tentang perjalanan kami.”
Kawannya tidak memaksa. Jika Kiai Narawangsa benar-benar merasa dilampaui sehingga ia menjadi marah, maka persoalannya akan menjadi gawat. Dalam pada itu, sekelompok orang yang baru pulang dari kaki Gunung Lawu itu sempat mandi, makan dan sedikit beristirahat. Ketika matahari menjadi semakin rendah di sisi Barat, maka Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari dan kedua pengiringnya telah kembali ke padepokan.
Ketika mereka mendapat laporan tentang sekelompok orang-orangnya yang telah kembali, maka Nyai Wiji Sari dengan tergesa-gesa memerintahkan untuk memanggilnya. Beberapa saat kemudian, maka Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari duduk di pendapa bangunan utama padepokannya dihadap oleh orang-orang yang baru pulang dari Kaki Gunung Lawu itu.
“Apakah kalian dapat menemukan padepokan Lembu Wirid yang kemudian bergelar Kiai Banyu Bening itu?”
“Ya, Kiai” jawab orang tertua yang memimpin kelompok itu.
“Kau bertemu dengan Kiai Banyu Bening itu sendiri?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Ya, Nyai.” jawab pemimpin kelompok itu ”Dua orang diantara kami telah memasuki padepokan itu dan menemui Kiai Banyu Bening.”
“Kau bertanya tentang makam anakku kepada Kiai Banyu Bening itu?” Nyai Wiji Sari agaknya segera ingin mengetahuinya.
“Ya, Nyai.” jawab orang tertua itu.
“Apa kata Kiai Banyu Bening?” desak Nyai Wiji Sari.
Orang tertua itupun segera menceriterakan kunjungannya di padepokan itu. Diceriterakannya pula, bahwa didepan pendapa bangunan utama padepokan itu terdapat sebuah tugu yang diatasnya terdapat sebuah nisan kecil. Makam anak itu mendapat tempat yang sangat baik didalam padepokan Kiai Banyu Bening.
“Tetapi itu tidak lebih dari satu kepura-puraan.” geram Nyai Wiji Sari.
Orang-orang yang telah pergi ke kaki Gunung Lawu itu termangu-mangu. Mereka melihat bagaimana Kiai Banyu Bening menghormati anaknya yang telah meninggal itu.
“Kalian tidak usah heran!” berkata Nyai Wiji Sari ”Lembu Wirid memang seorang pembohong yang tidak ada duanya. Tidak seorangpun dapat membedakan, yang mana yang sebenarnya dan yang mana yang sekedar pura-pura atau sekedar tipuan untuk mengelabui orang lain.”
Orang tertua yang memimpin kelompok yang pergi ke kaki Gunung Lawu itu menarik nafas dalam-dalam. Didalam hatinya ia berkata ”Itulah sebabnya, bahwa tingkah laku Kiai Banyu Bening itu nampak agak aneh. Agaknya ia hanya sekedar berpura-pura melupakan masa lalunya.”
“Jadi apa yang akan kita lakukan?” bertanya Kiai Narawangsa.”
“Kita datang untuk menemuinya. Aku akan memindahkan makam anakku itu. Aku akan melepaskan anakku dari cengkeraman orang yang tidak tahu diri itu.”
“Kematian anakmu itu sudah berlangsung lama sekali.”
“Akhir-akhir ini aku selalu diganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Rasa-rasanya anakku itu menangis memanggilku. Ia merasa kesepian dan sendiri."
“Apakah kau menganggap banwa mimpimu itu mempunyai arti tertentu?”
“Lembu Wirid tentu sudah tidak menghiraukannya lagi. “Bukan mimpi itu yang memberikan isyarat kepadamu. Tetapi karena kau selalu memikirkannya, maka kau mulai dibayangi oleh mimpi-mimpi itu.”
“Mungkin sekali. Tetapi aku ingin mengambilnya dari tangan Kiai Banyu Bening.”
“Nyai...” berkata orang tertua yang pergi ke kaki Gunung lawu itu ”Mungkin aku dapat menceriterakan sesuai dengan keterangan salah seorang murid Kiai Banyu Bening, bahwa Kiai Banyu Bening telah melakukan satu perbuatan yang sangat gila."
“Apa yang telah dilakukan?” bertanya Nyai Wiji Sari.
Pemimpin kelompok itupun kemudian telah menceriterakan apa yang telah didengarnya dari Ki Warana. Rencana Kiai Banyu Bening untuk menyerahkan korban-korban bayi yang harus dibakar hidup-hidup.
“Aku percaya bahwa gagasan seperti itu muncul di kepala Lembu Wirid.” sahut Nyai Wiji Sari ”Tetapi itu bukan pertanda bahwa Lembu Wirid mencintai anaknya. Ia sekedar mencari kepuasan justru karena ia mendapat kepuasan ketika ia mendengar anaknya menangis melengking-lengking dipanggang panasnya api.”
Orang tertua itu mengerutkan dahinya. Namun Nyai Wiji Sari itu berkata ”Sudahlah. Aku tidak mau mendengar lagi ceritera ngeri itu. Yang penting aku akan pergi ke padepokan Banyu Bening untuk mengambil anakku.”
“Kenapa kita harus mengambil anakmu dari padepokan itu? Bukankah masih ada cara yang lebih baik?” berkata Kiai Narawangsa.
“Cara yang bagaimana?” berkata Nyai Wiji Sari.
“Kita tidak usah membawa anakmu, pergi. Tetapi seperti rencana kita semula, kita akan tinggal di kaki Gunung Lawu. Kita ambil padepokan itu dari tangan Banyu Bening.”
”Lalu, bagaimana dengan Banyu Bening itu sendiri?”
“Kita akan membunuhnya atau mengusirnya. Bukankah begitu?”
Nyai Wiji Sari termangu-mangu sejenak. Ia nampak menjadi ragu-ragu. Sementara Kiai Narawangsa berkata ”Kau" masih merasa sayang, kehilangan Banyu Bening.”
Nyai Wiji Saripun berpaling. Nampak kerut yang dalam di dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata, ”Kenapa kau bertanya begitu?”
“Jadi kenapa kau ragu-ragu membunuhnya?” justru Kiai Narawangsa lah yang bertanya.
“Tidak. Aku tidak ragu-ragu.” desisnya.
Kiai Narawangsa itulah yang kemudian bertanya kepada pemimpin kelompok itu. ”Menurut pendapatmu manakah yang lebih baik. Padukuhan Banyu Bening atau padukuhan kita disini?”
Orang itu ragu-ragu sejenak. Katanya ”Padukuhan kita ini adalah padukuhan yang paling menyenangkan. Kita sudah lama tinggal disini.”
“Jawab yang sebenarnya!” Kiai Narawangsa itupun membentak ”Manakah yang lebih baik? Kita akan memilih, justru karena anak Nyai Wiji Sari itu berada disana.”
“Jika aku boleh mengatakan yang sebenarnya, Kiai,” suara pemimpin kelompok itu nampak ragu ”Padepokan Kiai Banyu Bening nampaknya lebih besar dari padepokan kita disini. Nampaknya padepokan itu berada diatas tanah yang subur. Sawah yang berada di seputar padepokan itu juga nampak subur. Aku kira sawah itu adalah sawah garapan para cantrik dari padepokan Kiai Banyu Bening. Hasilnya tentu cukup memadai. Tidak terlalu jauh dari padepokan itu masih terbentang hutan kaki pegunungan yang lebat. Padang perdu yang akan dapat menjadi cadangan masa depan. Bahkan padang perdu yang berbatu padas itupun selalu basah, karena ada seribu mata air yang dapat disalurkan dan ditampung menjadi parit-parit yang dapat mengaliri tanah yang luas.”
“Kau sempat meneliti keadaan di sekitar padepokan itu?” bertanya Kiai Narawangsa.
“Ketika aku berdua memasuki padepokan, maka kawan-kawan yang lain menunggu di padang yang sempat mendapat perhatian mereka.”
Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Katanya kepada Nyai Wiji Sari. ”Nah, bukankah menarik untuk berada di padepokan itu? Disini kita tidak dapat berkembang. Meskipun kita tinggal di tepi sungai, namun tanahnya terasa semakin sempit. Kita tidak dapat mendesak orang padukuhan yang memang sudah berdiri dijarak yang jauh. Kita juga tidak dapat menebas hutan menurut keperluan. Kita memang dapat menakut-nakuti orang-orang Susukan. Tetapi dengan demikian, maka kita menjadi orang yang hidup terpencil. Meskipun kita tidak memerlukan mereka, namun ada baiknya kita dapat berhubungan dengan orang-orang padukuhan sekitar kita."
Nyai Wiji Sari pun mengangguk-angguk pula.
“Nah, kita akan datang dan menyingkirkan Kiai Banyu Bening. Kita akan berada di satu daerah yang baru dengan harapan-harapan baru.”
“Tetapi kita memerlukan persiapan yang baik, Kiai” berkata pemimpin kelompok ”meskipun nampaknya tidak terlalu banyak, tetapi aku melihat kesiagaan yang tinggi dari para cantrik di padepokan Kiai Banyu Bening itu.”
“Apakah kau kira selama ini kita tidak menempa diri? He, bagaimana dengan kau sendiri? Apakah kau dibayangi oleh ketakutan untuk mengambil padepokan itu?”
“Tidak, Kiai. Bahkan aku telah mengatakannya kepada Kiai Banyu Bening, bahwa Kiai dan Nyai akan datang untuk merawat dan memakamkan kembali anak itu di padepokan itu pula dan mempersilahkan Kiai Banyu Bening untuk pergi.”
“Kita akan membunuhnya.” geram Kiai Narawangsa.
“Aku tidak dapat mengatakannya seperti itu pada waktu aku menghadap Kiai Banyu Bening.”
“Aku mengerti.” Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Lalu katanya ”Kita akan membuat persiapan sebaik-baiknya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan pergi ke lereng Gunung Lawu.”
“Kami menempuh perjalanan kembali dari kaki Gunung Lawu dalam dua hari lebih sedikit. Kami bermalam dua malam diperjalanan.”
“Apakah perjalanan itu cukup berat?”
“Ya, Kiai. Perjalanan yang berat. Apalagi jika kita berangkat dengan seluruh isi padepokan ini.”
“Kita tidak akan berangkat bersama-sama. Kita akan mengirimkan beberapa orang lebih dahulu untuk membuat landasan tidak terlalu jauh dari padepokan itu. Mungkin di pinggir hutan yang dapat memberikan dukungan persediaan makan bagi kita. Tentu ada diantara kita yang memiliki kemampuan berburu. Padukuhan-padukuhan disekitar padepokan itu tentu juga akan dapat menjadi sumber bahan makanan bagi kita.”
“Dengan demikian, hubungan yang buruk akan terulang kembali di tempat yang baru itu.” potong Nyai Wiji Sari.
“Kita akan dapat menyebut nama Kiai Banyu Bening.”
Nyai Wiji Sari mengangguk-angguk. Meskipun demikian ia pun berkata ”Persiapan kita harus meyakinkan. Tetapi yang penting bagiku, aku akan mengambil dan merawat anakku yang selalu hadir didalam mimpi-mimpiku.”
Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Katanya, ”Aku mengerti.”
Beberapa saat kemudian, maka sekelompok orang yang baru datang dari kaki Gunung Lawu itupun diperkenankan untuk beristirahat. Namun Kiai Narawangsa itupun berkata, ”Mulai besok kita akan berkemas.”
“Aku tidak ingin persiapan kita berkepanjangan” berkata Nyai Wiji Sari ”Aku rindukan anak itu.”
Perintah untuk mempersiapkan diri itupun kemudian telah sampai ke setiap telinga. Seorang yang rambutnya sudah ubanan berbisik kepada kawannya, ”Langkah yang kurang bijaksana. Tempat ini merupakan tempat yang paling baik. Jika kita berada di daerah baru, apakah kita dapat dengan segera mendapatkan lahan yang subur.”
“Kawan-kawan kita sudah sempat melihat-lihat. Tanah di sekitar padepokan di kaki gunung Lawu itu sangat subur. Banyak cadangan tanah yang masih terbuka.”
“Kau memang dungu!” geram orang yang rambutnya sudah ubanan itu ”Bukan lahan yang akan kita tanami padi dan jagung.”
“Maksud paman?”
“Lahan yang dapat menyediakan uang, emas dan permata. He, bukankah disamping bercocok tanam kita juga selalu menuai benda-benda berharga itu? Kita tinggal mengambilnya dan membawanya ke padepokan.”
“O” orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya lagi ”Bukankah dimana-mana ada orang kaya?”
“Sudah, sudah!” potong orang yang rambutnya ubanan ”kau memang dungu.”
Orang yang berambut ubanan itupun kemudian telah bangkit dan melangkah pergi. Sejak hari berikutnya, maka Kiai Narawangsa telah memerintahkan orang-orangnya untuk berlatih. Disela-sela kerja mereka disawah dan pategalan, mereka telah menyelenggarakan latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan mereka lebih dari biasanya.
Disamping latihan-latihan yang meningkat, maka Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari juga meningkatkan kegiatan mereka di malam hari. Sebelum mereka meninggalkan padepokan mereka, maka Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari berniat untuk mengurus benda-benda berharga yang ada di daerah jangkauan mereka.
Hampir setiap malam, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari telah keluar dari padepokan mereka. Sekali-sekali mereka berpacu di bulak-bulak panjang di atas punggung kuda bersama ampat atau lima orang pengikutnya. Tetapi pada kesempatan, lain, mereka berjalan menyusuri pematang dan bahkan padang-padang perdu untuk mengumpulkan benda-benda berharga.
Sementara itu di siang hari beberapa orang pengikutnya berkeliaran untuk mencari sasaran serta melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada sasaran itu. Dengan demikian, maka pada lingkungan yang terhitung luas di sekitar padepokan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari itu, keadaannya menjadi semakin memburuk.
Seakan-akan tidak ada kekuatan yang dapat membendung perampokan-perampokan yang semakin sering terjadi. Padukuhan-padukuhan besar dan kecil selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Gardu-gardu peronda justru menjadi kosong, karena para peronda berapapun jumlahnya tidak akan mampu menghentikan perampokan-perampokan itu.
Ketika pada suatu saat, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari menemui sebuah gardu yang ditunggui oleh lima orang peronda. maka nasib kelima orang peronda itu menjadi sangat buruk. Bahkan mereka masih juga sempat mengancam, jika masih ada yang meronda di malam-malam mendatang, maka mereka akan dihabisi. Dengan demikian, maka ketakutan pun semakin tersebar di daerah yang luas di sekitar padepokan itu. Tetapi tidak ada yang mampu mengatasinya.
Disamping kegiatan yang meningkat itu, maka latihan-latihan pun berlangsung semakin meningkat. Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari telah menjadi semakin mantap. Daerah perburuan benda-benda berharga di lingkungan yang terasa menjadi semakin tua itu, telah menjadi semakin kering pula. Sehingga karena itu, maka mereka mengharapkan daerah baru yang masih subur.
Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari juga memperhitungkan kemungkinan, bahwa daerah di sekitar kaki Gunung Lawu itu juga sudah dikuras habis oleh Kiai Banyu Bening. Namun jika mereka dapat menduduki padepokan Kiai Banyu Bening, maka benda-benda yang tersimpan di padepokan itu akan jatuh ketangan mereka pula. Namun Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari ternyata cukup berhati-hati. Mereka telah mengirimkan beberapa orang untuk mengamati padepokan itu dalam beberapa hari.
“Kalian harus mengetahui, seberapa kekuatan yang tersimpan di padepokan itu, sehingga kedatangan kita tidak sekedar menyurukkan kepala kita kedalam api.”
Dengan demikian, maka lima orang telah diperintahkan untuk berangkat menuju ke kaki Gunung Lawu. Dua diantara mereka adalah orang-orang yang pernah pergi ke padepokan Kiai Banyu Bening, sementara yang lain adalah urang-orang baru. Diharapkan bahwa orang-orang baru itu akan dapat memberikan pertimbangan yang lebih lengkap setelah mereka melihat padepokan Kiai Banyu Bening dan lingkungan disekitarnya...
Kedua orang itu nampak ragu-ragu. Sementara itu sambil memandang Ki Ajar Pangukan orang itu berkata ”Apakah kau dapat mengenalinya?”
Kedua orang itu memandang Ki Ajar Pangukan dengan penuh keragu-raguan. Sementara itu, Ki Ajar Pangukan sendiri agak terkejut mendengar pernyataan Ki Warana itu. Tetapi Ki Ajar Pangukan tidak dapat mengelak dari permainan itu. Karena itu maka iapun kemudian berkata,
”Ki Sanak. Jika kalian pernah mengenal aku sebelumnya, tolong beritahu aku, siapakah kalian. Aku sudah menjadi pikun sekarang. Banyak sekali hal yang telah aku lupakan. Aku juga sudah tidak lagi dapat mengenali orang-orang yang pernah tidur dan makan bersama. Sejak anakku meninggal didalam api, segala-galanya seakan-akan telah larut dari duniaku. Yang aku ingat hanyalah tugu dan batu nisan kecil itu serta tulang-tulang yang hangus yang ada didalamnya.”
Yang tertua diantara kedua orang itupun kemudian berkata sambil menarik nafas dalam-dalam, ”Kiai Banyu Bening. Kami mohon maaf, bahwa kami mengaku telah mengenal Kiai. Sebenarnyalah kami memang belum pernah mengenal. Yang kami ketahui adalah sekedar ancar-ancar. Ternyata Kiai sama sekali berbeda dengan ancar-ancar yang telah kami terima.”
Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk. Katanya, ”Bagiku, apakah kalian pernah mengenal aku atau tidak, sama sekali tidak ada bedanya. Seandainya kita pernah berhubungan, maka aku tidak akan pernah ingat, siapakah kalian?”
“Kenapa Kiai cepat menjadi pikun?” bertanya yang termuda diantara kedua orang itu.
Ki Ajar Pangukan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ”Aku tidak tahu. Tetapi sepeninggal anakku, rasa-rasanya masa laluku ikut hilang pula terkubur dibawah batu nisan kecil itu.”
“Kiai sangat menyesal atas kematian anak Kiai itu?”
Wajah Ki Ajar Pangukan menjadi tegang. Dengan lantang ia berkata, ”Kenapa kau bertanya seperti itu? Kau telah menyinggung perasaanku. Ingat, meskipun aku pikun, tetapi aku masih tetap menguasai ilmuku dengan baik. Selama tugu dan nisan itu ada disitu, maka ilmuku tidak akan pudar. Aku tinggal memerlukan beberapa hari lagi untuk mencapai puncak kejayaan ilmuku. Setelah itu, maka apapun yang terjadi, bahkan seandainya gempa mengguncang dan membuat tanah ini menganga sehingga tugu dan nisan itu tenggelam, maka ilmuku sudah tidak akan mungkin goyah lagi.”
Kedua orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Ajar Pangukan itupun bertanya, ”Nah, sekarang katakan, untuk apa kalian datang kemari?”
“Kiai...” berkata yang tertua diantara keduanya. ”Kami datang untuk menyampaikan pesan dari pemimpin kami.”
“Siapa? Apakah aku pernah mengenalnya dahulu?”
“Tentu, Kiai. Kiai pernah mengenalnya dahulu. Aku tidak tahu, apakah kiai masih dapat mengingatnya atau tidak.”
“Sudah aku katakan. Masa laluku sudah terkubur bersama tulang-tulang yang hangus dibawah nisan kecil itu. Semuanya gelap sama sekali. Tetapi katakan, barangkali aku dapat mengingatnya.”
”Kiai tentu ingat. Pemimpin kami adalah Kiai Narawangsa.”
“Narawangsa. Narawangsa. Aku pernah mendengar nama itu.”
“Bukan hanya pernah mendengar tetapi Kiai tentu akan teringat kepada orang itu.”
Ki Ajar Pangukan memandang Ki Warana sejenak, seakan-akan ingin menuntutnya, bahwa ia sudah menjerumuskannya kedalam kesulitan.
Namun Ki Warana lah yang kemudian menyahut, ”Kiai. Mungkin Kiai telah melupakannya. Tetapi Kiai pernah berceritera kepadaku dahulu, bahwa orang yang bernama Kiai Narawangsa itu adalah orang yang pernah berhubungan dengan isteri Kiai. Perkelahian antara Kiai dan Kiai Narawangsa itulah, ini menurut ceritera Kiai yang pernah aku dengar, menyebabkan rumah Kiai terbakar. Kiai sempat menghindari api, sementara Kiai Narawangsa dan isteri Kiai melarikan diri. Tetapi bayi itu tertinggal didalam api.”
“O...” Ki Ajar Pangukan menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Katanya “Ya. Narawangsa. Orang gila itu.”
Ki Pandi lah yang harus menahan tertawa yang seakan-akan hendak meledak didalam dadanya. Untunglah bahwa ia mampu melarutkan diri kedalam permainan itu.
“Terkutuklah orang itu!” desis Ki Ajar Pangukan ”Meskipun aku sudah pikun, aku tidak dapat melupakan nama itu. Tetapi aku tidak yakin bahwa aku masih dapat mengenali wajahnya.”
“Kiai Narawangsa mudah sekali dikenal, Kiai. Tubuhnya seperti raksasa. Kiai ingat? Ia tidak pernah mengenakan ikat kepala sewajarnya. Ikat kepalanya lebih banyak disangkutkan di lehernya daripada dipakai di kepalanya. Di wajahnya terdapat cacat karena goresan pedang.”
“Aku ingat itu. Tetapi wajahnya tidak cacat pada waktu itu.”
“Kiai benar!” jawab yang tertua diantara kedua orang itu ”Tentu Kiai tidak pernah melihat wajahnya terluka, karena luka itu terjadi pada saat Kiai Narawangsa bertempur melawan Kiai Banyu Bening saat itu. Saat api menyala dan menelan rumah beserta bayi itu.”
“Kenapa aku tidak mengoyak lehernya pada waktu itu.” desis Ki Ajar Pangukan.
“Ternyata usia Kiai Narawangsa masih panjang.”
“Terkutuklah orang itu. Terkutuklah orang itu!” berkata Ki Ajar Pangukan dengan lantang.
Ki Pandi yang mendengarnya bergeser ke samping. Kemudian duduk dengan kepala menunduk sehingga dahinya hampir menyentuh tikar pandan tempatnya duduk. Ki Pandi tidak ingin wajahnya dilihat oleh kedua orang tamu yang telah dikelabui oleh Ki Warangka itu.
Dengan lantang Ki Ajar Pangukan itupun kemudian bertanya, ”Sekarang, apa yang ingin kalian katakan kepadaku. Nama itu telah membuat darahku mendidih. Sebelum aku berbuat sesuatu diluar kendali nalarku. Katakan apa yang harus kalian katakan.”
“Kiai...” nampaknya kedua orang itu terpengaruh melihat sikap Ki Ajar Pangukan ”Kami hanyalah sekedar utusan. Jika tidak berkenan di hati Kiai, janganlah menjadi murka kepada kami.”
“Katakan!” geram Ki Ajar Pangukan.
“Kiai...” desis yang tertua diantara mereka ”Kiai Narawangsa ingin minta agar Kiai memberinya kesempatan untuk merawat dan memakamkan kembali bayi itu dengan upacara khusus.”
“Gila...” suara Ki Ajar Pangukan menggelegar, sehingga kedua orang itu mundur setapak ”Kau menghina aku, he?”
“Bukan kami Kiai, Bukan kami.”
”Mulutmulah yang mengucapkannya.”
“Tetapi kami adalah sekedar utusan.”
“Katakan.” suara Ki Ajar Pangukan menurun.
“Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari...”
“Jangan sebut nama Nyai Banyu Bening itu. Kiai Banyu Bening tidak mau mendengar lagi nama isterinya.” potong Ki Warana.
“Terkutuklah semuanya, terkutuklah.” geram Ki Ajar Pangukan. Sebenarnya ia bingung mendengar nama Nyai Wiji Sari. Tetapi Ki Warana pun tangkas berpikir sehingga ia telah memberi tahukan kepada Ki Ajar Pangukan, siapakah Nyai Wiji Sari itu.
“Ampun, Kiai.” desis yang tertua.
“Katakan.” desis Ki Ajar Pangukan ”Tetapi jangan sebut nama itu. Aku telah mengutuk diriku sendiri. Jika aku melupakan masa laluku, kenapa nama itu tidak pernah dapat aku lupakan.”
“Baik, baik, Kiai.” sahut yang tertua itu ”Sebenarnyalah mereka berdua ingin memakamkan kembali di halaman ini pula dan untuk selanjutnya ingin merawatnya.”
“He, kau sadar apa yang kau katakan?”
“Bukan aku, Kiai. Tetapi aku sekedar menyampaikan pesan Kiai Narawangsa.”
“Katakan, katakan!” Ki Ajar Pangukan hampir berteriak.
“Keduanya ingin tinggal di padepokan ini untuk menunggui dan merawat makam bayi itu. Sementara itu mereka mohon Kiai Banyu Bening dan para cantrik yang ada disini untuk meninggalkan padepokan ini,”
Mata Ki Ajar Pangukan terbelalak. Dari sorot matanya memancar api kemerahan. Dengan suara lantang Ki Ajar Pangukan itu berkata, ”pergi. Pergi. Jika kalian tidak segera pergi, aku pancung kau dibawah tugu dan batu nisan itu.”
“Bukan kehendak kami, Kiai.”
“Pergi, kau dengar!” bentak Ki Ajar Pangukan. Lalu katanya kepada Ki Warana ”Antar kedua orang ini keluar dari padepokan.”
Ki Waranapun segera bangkit dan berkata, ”Marilah Ki Sanak. Cepatlah sedikit.”
Kedua orang itupun kemudian bangkit pula sambil berdesis ”Kami mohon diri, Kiai.”
“Cepat pergi. Kalian telah menyakiti mataku, telingaku dan hatiku.”
“Cepat sedikit,” desis Ki Warana, “ Jika darahnya naik sampai ke kepala, hati-hatilah kalian tak akan pernah keluar dari padepokan ini.”
Kedua orang iiu tiba-tiba saja kehilangan segala kegarangan dan keberanian mereka. Keduanya pun melangkah dengan cepat melintasi halaman diantar oleh Ki Warana.
Para cantrik yang berada diregol pun telah membuka selarak pintu regol itu dan membukanya. Demikian keduanya keluar dari regol halaman, Ki Warana pun berkata, ”Itulah sosok orang yang kalian cari Ki Sanak. Kalian harus dapat menempatkan diri kalian, jika kalian menyampaikan jawaban Kiai Banyu Bening agar pemimpin kalian tidak terbakar hatinya.”
Ketika kedua orang itu merasa sudah berada diluar padepokan, maka keberanian mereka telah menyala kembali didalam dada mereka, sehingga yang muda diantara merekapun menjawab, ”Kami tidak akan mengulas keterangan Kiai Banyu Bening, Ki Sanak. Kami justru akan membakar hati Kiai Narawangsa. Dengan demikian padepokan inipun akan terbakar habis menjadi abu sebagaimana rumah Nyai Wiji Sari serta anaknya. Kau jangan mengira bahwa Nyai Wiji Sari tidak tersiksa oleh kematian anaknya itu.”
“Tetapi ia tidak menjadi gila seperti Kiai Banyu Bening. Jika kau sempat mendatangi padukuhan-padukuhan, maka dipadukuhan-padukuhan itu telah dibangun sanggar-sanggar khusus untuk menyerahkan korban. Mula-mula hanya buah-buahan. Kemudian anak seekor binatang yang dipersembahkan hidup-hidup, dibakar diatas lantai yang khusus dibuat untuk itu. Pada saat terakhir, Kiai Banyu Bening telah memerintahkan, yang dipersembahkan adalah bayi-bayi yang masih hidup untuk dibakar. Kiai Banyu Bening akan mendapat kepuasan batin tertinggi jika ia mendengar jerit bayi yang terbakar itu. Dendamnya karena kematian bayinya telah menjadikannya gila.”
Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Hampir diluar sadarnya ia berkata, ”Jadi korban yang dituntut oleh Kiai Banyu Bening itu membakar bayi hidup-hidup.”
“Ya...!”
Keduanya saling berpandangan sejenak. Namun kemudian iapun berkata ”Semuanya akan kami katakan kepada Kiai Narawangsa. Tetapi kau harus mengatakannya kepada Kiai Banyu Bening, bahwa Kiai Narawangsa adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Demikian pula isterinya, Nyai Wiji Sari. Karena itu, jika keduanya datang kemari dan memaksakan kehendaknya, maka itu akan menjadi pertanda buruk bagi Kiai Banyu Bening.”
“Terserah kepadamu. Apakah kau akan berusaha mencegah pemimpinmu agar tidak datang kemari atau tidak. Jika kau tidak mencegahnya dengan cara apapun juga, maka sepanjang hidupmu, kau akan dibebani penyesalan, karena keduanya akan mati disini.”
Yang termuda diantara keduanya itu menyahut, ”Jangan berusaha menakut-nakuti kami. Kami bukan pengecut.”
“Baiklah. Datanglah kemari. Bawa Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari. Kami akan segera menyiapkan batu nisan bagi mereka berdua. Mayat mereka akan dikubur disebelah-menyebelah tugu itu, karena didunia langgeng, mereka akan menjadi hamba dari bayi yang meninggal karena terbakar itu.”
“Impian gila.” geram yang muda.
Namun Ki Warana malah berkata, ”Tetapi kematian yang paling buruk yang dapat terjadi atas Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari adalah, bahwa keduanya juga akan menjadi persembahan yang akan dibakar hidup-hidup.”
“Satu gagasan yang baik.” geram yang tertua ”Kiai Narawangsa akan memperlakukan Kiai Banyu Bening seperti itu.”
Ki Warana tertawa. Katanya ”Pulanglah sebelum Kiai Banyu Bening memerintahkan para cantrik menangkapmu dan menyeretmu kembali ke pendapa. Kalian tentu melihat tonggak besi yang sudah menjadi hitam di sebelah pendapa itu. Kalian tentu dapat membayangkan gunanya.”
Keduanya pun kemudian meninggalkan padepokan itu. Disepanjang jalan mereka masih saja berbincang tentang orang-orang padepokan itu. Namun mereka pun mengakui, betapa besarnya wibawa Kiai Banyu Bening, sehingga dihadapannya, keduanya seakan-akan telah dihadapkan pada sebuah pengadilan yang sedang mengadili mereka.
“Kiai Narawangsa akan membuat Kiai Banyu Bening itu menundukkan kepalanya” berkata yang tertua diantara keduanya.
Yang muda itupun mengangguk-angguk sambil berkata, ”Aku tidak mengira, bahwa Kiai Banyu Bening adalah seorang yang luar biasa. Gambaranku tentang Kiai Banyu Bening sebagaimana sering aku dengar dari pembicaraan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari sama sekali berbeda. Aku tidak membayangkan bahwa Kiai Banyu Bening itu mempunyai wibawa yang begitu tinggi.”
“Apa yang dikatakan oleh Kiai Narawangsa itu adalah Kiai Banyu Bening dimasa lampau. Demikian ia kehilangan anaknya, maka Kiai Banyu Bening nampaknya telah menghabiskan waktunya untuk memperdalam ilmunya, sehingga ia hampir lupa segala-galanya.”
Kawannya mengangguk-angguk. Bagaimana pun juga, diluar sadar, setiap kali mereka mengatakan bahwa Kiai Banyu Bening adalah seseorang yang mumpuni. Dalam pada itu, ketika kedua orang itu melangkah pergi, maka Ki Warana pun segera kembali ke pendapa. Ia termangu-mangu sejenak, melihat Ki Pandi tertawa. Bahkan kemudian katanya,
”Perutku terasa sakit karena aku harus menahan tertawa. Tetapi Ki Ajar Pangukan benar-benar seorang yang mampu mengelabuhi orang lain. Ki Ajar benar-benar mampu menjadi Kiai Banyu Bening.”
Ki Warana pun tertawa pula. Namun Ki Ajar itupun berkata ”Ki Warana mengejutkan aku. Tiba-tiba saja sebelum kita berbicara lebih dahulu, aku ditunjuknya langsung menjadi Kiai Banyu Bening.”
“Aku sudah tidak mempunyai waktu lagi.” berkata Ki Warana.
“Tetapi apakah keberatannya jika kita katakan berterus-terang tentang padepokan ini.”
“Aku kira apapun alasannya, namun agaknya mereka akan tetap menuntut tanah ini, tanah yang diatasnya terdapat sebuah padepokan yang sudah berada di tangan kita.”
“Jika tanah dan padepokan ini bukan lagi milik Kiai Banyu Bening, apakah mereka juga akan menuntut? Sedangkan sebelumnya kita tidak saling mengenal dengan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.” desis Ki Ajar Pangukan.
“Kita masih belum tahu benar, apakah yang sebenarnya mereka kehendaki. Apakah Nyai Wiji Sari dengan jujur ingin mendapatkan kembali anaknya yang telah lama meninggal atau alasan-alasan lainnya. Karena itu, selagi Ki Ajar, Ki Pandi dan yang lain ada disini, biarlah persoalannya diselesaikan dengan tuntas.”
Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk. Ia mengerti kecemasan yang mencengkam jantung Ki Warana yang merasa bahwa ilmunya masih belum memadai. Karena itu, maka Ki Warana memerlukan perlindungan dari beberapa orang yang berilmu tinggi.
Namun dalam pada itu, maka Ki Ajar Pangukan itupun berkata ”Ki Warana, dengan pengakuan ini, maka kemungkinan terbesar, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari tentu akan datang ke padepokan ini. Karena itu, maka Ki Warana sebaiknya mempersiapkan orang-orang yang kini masih berada di padepokan ini. Kekuatan padepokan ini telah menyusut jauh dibandingkan pada saat Kiai Banyu Bening masih berada di padepokan ini.”
“Benar Ki Ajar. Tetapi yang tinggal sekarang adalah orang-orang yang lebih mapan. Mereka mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi atas diri mereka disaat Kiai Banyu Bening masih memimpin padepokan ini. Sedangkan sekarang mereka berada disini karena satu keyakinan yang lebih dewasa.”
Ki Ajar Pangukan itupun berkata ”Baiklah. Kita akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kiai Narawangsa. Tetapi kita tidak boleh sekedar berpangku tangan.”
Demikianlah, maka Ki Ajar Pangukan pun telah memanggil beberapa orang tua yang ada di padepokan itu. Dengan singkat Ki Ajar telah menceriterakan apa yang telah dibicarakan dengan kedua orang yang mengaku utusan Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari.
“Seharusnys Ki Lemah Teles lah yang harusmengaku sebagai Kiai Banyu Bening” berkata Ki Ajar Pangukan.
“Kenapa aku?” bertanya Ki Lemah Teles.
“Bukankah kita sudah sepakat, bahwa Ki Lemah Teles akan berada di padepokan ini untuk seterusnya?”
Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Tetapi kemudian iapun berkata ”Tetapi biarlah kali ini Ki Ajar Pangukan yang akan berperan sebagai Kiai Banyu Bening.”
Ki Pandi pun tertawa sambil berkata ”Ki Ajar telah memainkan peranannya dengan baik sekali. Tetapi jika Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari yang datang kemari, maka mereka akan merasa bahwa mereka telah dikelabui oleh orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal.”
Dengan demikian, maka orang-orang tua itu berpendapat, bahwa padepokan itu harus mempersiapkan diri menghadapi orang yang menyebut dirinya Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari, yang telah bertahun-tahun mencari orang yang bernama Kiai Banyu Bening itu.
Dalam pada itu, Ki Ajar Pangukan pun berkata kepada Ki Warana ”Aku memerlukan pengenalan lebih jauh tentang pribadi Kiai Banyu Bening serta kehidupan yang mengelilinginya.”
“Sejauh aku ketahui, Ki Ajar.” jawab Ki Warana.
“Tetapi darimana Ki Warana mengetahui kehidupan Kiai Banyu Bening yang tidak bening itu?” bertanya Ki Pandi.
“Kiai Banyu Bening memang sering berbicara tentang dirinya. Jika ia mulai dibayangi oleh kehidupan masa lampaunya, maka ia memerlukan seseorang yang mau mendengarkan ceriteranya. Bukan hanya aku yang pernah mendengarnya, tetapi beberapa orang yang lainpun pernah mendengarnya. Ceritera-ceritera itulah yang membuat aku semakin lama semakin ragu akan kepemimpinannya. Aku memang mendengar dan merasakan, bahwa apa yang dilakukannya itu tidak lebih dari ungkapan dendam yang mencengkam hatinya.”
“Baiklah” berkata Ki Ajar ”Jita tidak boleh membuang waktu. Kita siapkan apa yang ada untuk mempertahankan tanah dan padepokan ini dari siapapun juga.”
Ki Warana pun kemudian telah menemui beberapa orang pemimpin kelompok di padepokannya. Mereka mendapat penjelasan tentang kemungkinan yang dapat terjadi atas padepokan itu.
“Kita belum sempat menyusun padepokan ini dan membuat tatanan baru yang lebih baik, kita sudah dihadapkan pada satu persoalan baru yang lebih baik, kita sudah dihadapkan pada satu persoalan baru. Tetapi kita harus tegar menghadapinya. Orang-orang tua yang berilmu tinggi itu masih tetap berada disini. Mereka bukan saja akan membimbing kita untuk mempertahankan padepokan ini, tetapi merekapun akan dapat membimbing kita menempuh jalan kehidupan yang baru. Kita akan lebih mengenali diri kita dan mengenali sumber hidup kita.”
Para pemimpin kelompok orang-orang padepokan yang semula adalah pengikut Kiai Banyu Bening itu mengangguk-angguk. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan mendatang.
Namun dalam pada itu, niat orang-orang tua yang berada di padepokan itu membongkar tugu dan menempatkan nisan kecil itu ke tempat yang lebih wajar, terpaksa ditunda. Meskipun keberadaan tugu itu tidak lagi mempunyai arti sebagaimana sebelumnya, tetapi mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari dengan anaknya yang telah meninggal itu.
Seperti yang dikehendaki oleh Ki Warana, maka orang-orang yang berada di padepokan itupun telah mulai mempersiapkan diri. Mereka telah memperbaiki panggungan-panggungan yang telah rusak di belakang dinding padepokan. Mereka pun telah mulai berlatih pula dengan sebaik-baiknya. Bahkan orang-orang tua yang berilmu tinggi, telah ikut terjun langsung didalamnya.
Namun orang-orang tua yang berilmu tinggi itu mempunyai cara tersendiri. Disamping memberikan latihan-latihan kepada semua orang yang ada di padepokan, mereka telah memilih beberapa orang untuk mendapat latihan-latihan khusus. Orang-orang tua yang berilmu tinggi itu masing-masing memilih empat atau lima orang untuk ditempa menjadi orang-orang terbaik di padepokan itu. Dalam benturan kekuatan mereka akan menjadi kekuatan yang harus mampu menembus pertahanan lawan dan mengoyaknya.
Sementara itu, Manggada dan Laksanapun mempunyai kawan-kawan berlatih yang khusus pula. Kelebihan Manggada dan Laksana mampu mengangkat orang-orang yang mereka pilih ke tataran yang lebih tinggi. Kedua orang anak muda itu telah mempergunakan waktu sebaik-baiknya, karena mereka mengetahui bahwa waktu memang sangat sempit.
Meskipun demikian, Manggada dan Laksana sendiri tidak mengabaikan latihan-latihan untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Dengan alat-alat yang ada di dalam sanggar di padepokan itu, keduanya dengan sungguh-sungguh telah menempa diri mereka sendiri pula.
Ternyata usaha itu tidak sia-sia. Empat atau lima orang yang ditangani langsung oleh orang-orang berilmu tinggi itu telah meningkat lebih cepat. Ki Warana sendiri telah bekerja dengan tanpa mengenal lelah untuk menyadap ilmu kanuragan. Ia merasa masih jauh ketinggalan sehingga untuk mencapai tataran yang lebih baik, maka ia harus berbuat sejauh dapat dilakukannya.
Sementara itu, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari selalu menunggu laporan dari orang-orang yang diperintahkannya mencari dan menemui Kiai Banyu Bening. Dua orang yang datang ke padepokan yang semula memang dihuni oleh Kiai Banyu Bening itu telah meninggalkan lereng Gunung Lawu bersama sekelompok kawan-kawannya.
Mereka akan memberikan laporan tentang perjalanan mereka untuk mencari dan menemui Kiai Banyu Bening. Orang itu harus menempuh perjalanan yang panjang untuk sampai ke sebuah padepokan yang dipimpin oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari.
Sekelompok orang itu menyusuri Kali Grompol untuk beberapa lama. Kemudian mereka berbelok meninggalkan Kali Grompol menyilang sampai kesebuah tempuran. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri Kali Regunung yang panjang.
Perjalanan mereka memang bukan perjalanan yang ringan. Mereka sekali-sekali harus menyusup di lebatnya hutan belukar, sekali-sekali mereka harus menembus padang perdu yang panjang. Mereka harus melewati pegunungan gundul dan dibakar teriknya sinar matahari.
Sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu tidak dapat mencapai padepokan mereka dalam sehari. Mereka harus berhenti dan bermalam diperjalanan. Untuk mendapatkan makan, mereka harus berburu di hutan yang lebat sehingga dengan demikian maka perjalanan mereka menjadi semakin terhambat.
Sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu maju dengan sangat lamban. Karena itu, untuk mencapai padepokannya, mereka memerlukan waktu yang panjang. Bahkan ternyata mereka masih belum mencapai Kiai Narawangsa yang terletak tidak terlalu jauh dari Kademangan Susukan ditepi Kali Gandu, ketika malam turun di hari kedua.
Meskipun mereka tahu, bahwa padepokan mereka sudah tidak terlalu jauh lagi, tetapi mereka tidak melanjutkan perjalanan. Jalan yang mereka, lalui adalah jalan pintas yang rumpil, yang kadang-kadang melewati tebing yang curam, naik lereng bukit-bukit dan menuruni lembah yang ditumbuhi belukar.
Karena itu mereka lebih senang memilih untuk bermalam dipadang perdu yang tidak terlalu luas. Bergantian orang-orang itu berjaga-jaga. Mungkin binatang buas dari hutan yang tidak terlalu jauh dari padang perdu itu sedang kelaparan karena mereka tidak berhasil menangkap kijang.
Menjelang matahari terbit, mereka telah melanjutkan perjalanan mereka menuju ke padepokan mereka yang berada di tepi Kali Gandu. Sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu mendekati regol padepokan mereka sebelum matahari mencapai puncak langit. Orang tertua diantara mereka menjadi berdebar-debar. Hampir diluar sadarnya ia bertanya kepada kawan-kawannya,
”Bukankah perjalanan kita ini dapat dikatakan berhasil?”
“Ya. Kita sudah berhasil melaksanakan perintah Kiai Narawangsa dengan baik. Kita sudah menemukan padepokan Kiai Banyu Bening. Kita telah menemukan pula makam anak Nyai Wiji Sari. Bukankah menemukan makam itu termasuk salah satu tugas kita yang penting?”
“Untunglah bahwa makam kecil itu berada didalam padepokan, sehingga kita tidak harus mencarinya lagi. Bahkan seandainya makam itu tidak berada di padepokan, maka Kiai Banyu Bening tentu tidak akan bersedia memberitahukannya."
“Karena itu, kita akan memasuki regol halaman padepokan kita dengan dada tengadah. Kita akan dapat membanggakan diri, bahwa akhirnya kitalah yang berhasil menemukan apa yang dicari Kiai Narawangsa untuk waktu yang lama itu setelah beberapa kali kelompok-kelompok yang lain mengalami kegagalan.”
Namun seorang diantara mereka menjawab, ”Meskipun gagal, tetapi kelompok-kelompok yang lain telah mengumpulkan banyak keterangan sehingga kita dapat langsung mencari padepokan itu di kaki Gunung Lawu.”
Orang tertua yang memimpin sekelompok orang itu memandanginya dengan tajamnya, Namun kemudian iapun berkata, ”Kau pernah ikut-ikut dalam kelompok-kelompok sebelum kita pergi ke Gunung Lawu.”
“Ya.” jawab orang itu.
Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Katanya ”Kami tidak akan mengingkari petunjuk-petunjuk itu.”
Mereka pun kemudian terdiam. Langkah mereka semakin mendekati regol padepokan. Beberapa saat kemudian maka sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu telah berdiri di depan regol. Orang yang tertua diantara mereka, yang memimpin sekelompok orang itu, telah mengetuk pintu regol padepokan. Sejenak kemudian, maka sebuah lubang persegi ampat di pintu padepokan itu terbuka. Nampak sebuah wajah di lubang segi empat itu memandang ke luar.
“Bukalah pintunya!” berkata orang tertua yang memimpin kelompok itu.
“He, kau kakang” terdengar orang yang menjengukkan wajahnya itu menyahut.
“Buka pintunya.”
“Baik, baik kakang” jawab orang yang berada didalam.
Demikianlah, maka sejenak kemudian pintu regol itupun telah terbuka. Dua orang cantrik berdiri di belakang pintu itu. Dengan wajah yang cerah mereka telah mempersilahkan sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu masuk.
“Kiai ada dirumah?” bertanya orang tertua itu.
“Kiai dan Nyai baru saja pergi, kakang. Tetapi tentu tidak lama.”
“Kemana?”
“Aku tidak tahu. Tetapi mereka akan segera kembali. Mereka hanya membawa dua orang pengiring.”
Orang tertua yang memimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Sementara penjaga regol itu berkata ”Sambil menunggu, kakang sempat beristirahat barang sejenak. Mungkin kakang akan mandi dan makan dahulu.”
Orang tertua yang memimpin sekelompok orang untuk mencari padepokan Kiai Banyu Bening itu mengangguk-angguk. Katanya kepada kawan-kawannya yang menyertainya ”Marilah. Kita akan sempat beristirahat. Tetapi kita tidak wajib menceriterakan perjalanan kita sebelum kita memberikan laporan kepada Kiai Narawangsa.”
Kawan-kawannya pun mengerti maksud pemimpinnya itu. Karena itu, maka mereka pun harus tetap menyimpan ceritera perjalanan mereka. Kedatangan sekelompok pengikut Kiai Narawangsa itu disambut hangat oleh kawan-kawannya. Namun tidak seorang pun diantara mereka yang mau menceriterakan pengalaman perjalanan mereka.
“Kami belum memberikan laporan kepada Kiai Narawangsa.” berkata salah seorang diantara mereka.
“Apa salahnya? Jika kau centerakan kepada kami, bukankah laporanmu masih utuh?” desak kawannya.
Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, ”Kiai Narawangsa akan merasa dilampaui jika ia tahu, bahwa aku telah berceritera lebih dahulu tentang perjalanan kami.”
Kawannya tidak memaksa. Jika Kiai Narawangsa benar-benar merasa dilampaui sehingga ia menjadi marah, maka persoalannya akan menjadi gawat. Dalam pada itu, sekelompok orang yang baru pulang dari kaki Gunung Lawu itu sempat mandi, makan dan sedikit beristirahat. Ketika matahari menjadi semakin rendah di sisi Barat, maka Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari dan kedua pengiringnya telah kembali ke padepokan.
Ketika mereka mendapat laporan tentang sekelompok orang-orangnya yang telah kembali, maka Nyai Wiji Sari dengan tergesa-gesa memerintahkan untuk memanggilnya. Beberapa saat kemudian, maka Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari duduk di pendapa bangunan utama padepokannya dihadap oleh orang-orang yang baru pulang dari Kaki Gunung Lawu itu.
“Apakah kalian dapat menemukan padepokan Lembu Wirid yang kemudian bergelar Kiai Banyu Bening itu?”
“Ya, Kiai” jawab orang tertua yang memimpin kelompok itu.
“Kau bertemu dengan Kiai Banyu Bening itu sendiri?” bertanya Nyai Wiji Sari.
“Ya, Nyai.” jawab pemimpin kelompok itu ”Dua orang diantara kami telah memasuki padepokan itu dan menemui Kiai Banyu Bening.”
“Kau bertanya tentang makam anakku kepada Kiai Banyu Bening itu?” Nyai Wiji Sari agaknya segera ingin mengetahuinya.
“Ya, Nyai.” jawab orang tertua itu.
“Apa kata Kiai Banyu Bening?” desak Nyai Wiji Sari.
Orang tertua itupun segera menceriterakan kunjungannya di padepokan itu. Diceriterakannya pula, bahwa didepan pendapa bangunan utama padepokan itu terdapat sebuah tugu yang diatasnya terdapat sebuah nisan kecil. Makam anak itu mendapat tempat yang sangat baik didalam padepokan Kiai Banyu Bening.
“Tetapi itu tidak lebih dari satu kepura-puraan.” geram Nyai Wiji Sari.
Orang-orang yang telah pergi ke kaki Gunung Lawu itu termangu-mangu. Mereka melihat bagaimana Kiai Banyu Bening menghormati anaknya yang telah meninggal itu.
“Kalian tidak usah heran!” berkata Nyai Wiji Sari ”Lembu Wirid memang seorang pembohong yang tidak ada duanya. Tidak seorangpun dapat membedakan, yang mana yang sebenarnya dan yang mana yang sekedar pura-pura atau sekedar tipuan untuk mengelabui orang lain.”
Orang tertua yang memimpin kelompok yang pergi ke kaki Gunung Lawu itu menarik nafas dalam-dalam. Didalam hatinya ia berkata ”Itulah sebabnya, bahwa tingkah laku Kiai Banyu Bening itu nampak agak aneh. Agaknya ia hanya sekedar berpura-pura melupakan masa lalunya.”
“Jadi apa yang akan kita lakukan?” bertanya Kiai Narawangsa.”
“Kita datang untuk menemuinya. Aku akan memindahkan makam anakku itu. Aku akan melepaskan anakku dari cengkeraman orang yang tidak tahu diri itu.”
“Kematian anakmu itu sudah berlangsung lama sekali.”
“Akhir-akhir ini aku selalu diganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Rasa-rasanya anakku itu menangis memanggilku. Ia merasa kesepian dan sendiri."
“Apakah kau menganggap banwa mimpimu itu mempunyai arti tertentu?”
“Lembu Wirid tentu sudah tidak menghiraukannya lagi. “Bukan mimpi itu yang memberikan isyarat kepadamu. Tetapi karena kau selalu memikirkannya, maka kau mulai dibayangi oleh mimpi-mimpi itu.”
“Mungkin sekali. Tetapi aku ingin mengambilnya dari tangan Kiai Banyu Bening.”
“Nyai...” berkata orang tertua yang pergi ke kaki Gunung lawu itu ”Mungkin aku dapat menceriterakan sesuai dengan keterangan salah seorang murid Kiai Banyu Bening, bahwa Kiai Banyu Bening telah melakukan satu perbuatan yang sangat gila."
“Apa yang telah dilakukan?” bertanya Nyai Wiji Sari.
Pemimpin kelompok itupun kemudian telah menceriterakan apa yang telah didengarnya dari Ki Warana. Rencana Kiai Banyu Bening untuk menyerahkan korban-korban bayi yang harus dibakar hidup-hidup.
“Aku percaya bahwa gagasan seperti itu muncul di kepala Lembu Wirid.” sahut Nyai Wiji Sari ”Tetapi itu bukan pertanda bahwa Lembu Wirid mencintai anaknya. Ia sekedar mencari kepuasan justru karena ia mendapat kepuasan ketika ia mendengar anaknya menangis melengking-lengking dipanggang panasnya api.”
Orang tertua itu mengerutkan dahinya. Namun Nyai Wiji Sari itu berkata ”Sudahlah. Aku tidak mau mendengar lagi ceritera ngeri itu. Yang penting aku akan pergi ke padepokan Banyu Bening untuk mengambil anakku.”
“Kenapa kita harus mengambil anakmu dari padepokan itu? Bukankah masih ada cara yang lebih baik?” berkata Kiai Narawangsa.
“Cara yang bagaimana?” berkata Nyai Wiji Sari.
“Kita tidak usah membawa anakmu, pergi. Tetapi seperti rencana kita semula, kita akan tinggal di kaki Gunung Lawu. Kita ambil padepokan itu dari tangan Banyu Bening.”
”Lalu, bagaimana dengan Banyu Bening itu sendiri?”
“Kita akan membunuhnya atau mengusirnya. Bukankah begitu?”
Nyai Wiji Sari termangu-mangu sejenak. Ia nampak menjadi ragu-ragu. Sementara Kiai Narawangsa berkata ”Kau" masih merasa sayang, kehilangan Banyu Bening.”
Nyai Wiji Saripun berpaling. Nampak kerut yang dalam di dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata, ”Kenapa kau bertanya begitu?”
“Jadi kenapa kau ragu-ragu membunuhnya?” justru Kiai Narawangsa lah yang bertanya.
“Tidak. Aku tidak ragu-ragu.” desisnya.
Kiai Narawangsa itulah yang kemudian bertanya kepada pemimpin kelompok itu. ”Menurut pendapatmu manakah yang lebih baik. Padukuhan Banyu Bening atau padukuhan kita disini?”
Orang itu ragu-ragu sejenak. Katanya ”Padukuhan kita ini adalah padukuhan yang paling menyenangkan. Kita sudah lama tinggal disini.”
“Jawab yang sebenarnya!” Kiai Narawangsa itupun membentak ”Manakah yang lebih baik? Kita akan memilih, justru karena anak Nyai Wiji Sari itu berada disana.”
“Jika aku boleh mengatakan yang sebenarnya, Kiai,” suara pemimpin kelompok itu nampak ragu ”Padepokan Kiai Banyu Bening nampaknya lebih besar dari padepokan kita disini. Nampaknya padepokan itu berada diatas tanah yang subur. Sawah yang berada di seputar padepokan itu juga nampak subur. Aku kira sawah itu adalah sawah garapan para cantrik dari padepokan Kiai Banyu Bening. Hasilnya tentu cukup memadai. Tidak terlalu jauh dari padepokan itu masih terbentang hutan kaki pegunungan yang lebat. Padang perdu yang akan dapat menjadi cadangan masa depan. Bahkan padang perdu yang berbatu padas itupun selalu basah, karena ada seribu mata air yang dapat disalurkan dan ditampung menjadi parit-parit yang dapat mengaliri tanah yang luas.”
“Kau sempat meneliti keadaan di sekitar padepokan itu?” bertanya Kiai Narawangsa.
“Ketika aku berdua memasuki padepokan, maka kawan-kawan yang lain menunggu di padang yang sempat mendapat perhatian mereka.”
Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Katanya kepada Nyai Wiji Sari. ”Nah, bukankah menarik untuk berada di padepokan itu? Disini kita tidak dapat berkembang. Meskipun kita tinggal di tepi sungai, namun tanahnya terasa semakin sempit. Kita tidak dapat mendesak orang padukuhan yang memang sudah berdiri dijarak yang jauh. Kita juga tidak dapat menebas hutan menurut keperluan. Kita memang dapat menakut-nakuti orang-orang Susukan. Tetapi dengan demikian, maka kita menjadi orang yang hidup terpencil. Meskipun kita tidak memerlukan mereka, namun ada baiknya kita dapat berhubungan dengan orang-orang padukuhan sekitar kita."
Nyai Wiji Sari pun mengangguk-angguk pula.
“Nah, kita akan datang dan menyingkirkan Kiai Banyu Bening. Kita akan berada di satu daerah yang baru dengan harapan-harapan baru.”
“Tetapi kita memerlukan persiapan yang baik, Kiai” berkata pemimpin kelompok ”meskipun nampaknya tidak terlalu banyak, tetapi aku melihat kesiagaan yang tinggi dari para cantrik di padepokan Kiai Banyu Bening itu.”
“Apakah kau kira selama ini kita tidak menempa diri? He, bagaimana dengan kau sendiri? Apakah kau dibayangi oleh ketakutan untuk mengambil padepokan itu?”
“Tidak, Kiai. Bahkan aku telah mengatakannya kepada Kiai Banyu Bening, bahwa Kiai dan Nyai akan datang untuk merawat dan memakamkan kembali anak itu di padepokan itu pula dan mempersilahkan Kiai Banyu Bening untuk pergi.”
“Kita akan membunuhnya.” geram Kiai Narawangsa.
“Aku tidak dapat mengatakannya seperti itu pada waktu aku menghadap Kiai Banyu Bening.”
“Aku mengerti.” Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Lalu katanya ”Kita akan membuat persiapan sebaik-baiknya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan pergi ke lereng Gunung Lawu.”
“Kami menempuh perjalanan kembali dari kaki Gunung Lawu dalam dua hari lebih sedikit. Kami bermalam dua malam diperjalanan.”
“Apakah perjalanan itu cukup berat?”
“Ya, Kiai. Perjalanan yang berat. Apalagi jika kita berangkat dengan seluruh isi padepokan ini.”
“Kita tidak akan berangkat bersama-sama. Kita akan mengirimkan beberapa orang lebih dahulu untuk membuat landasan tidak terlalu jauh dari padepokan itu. Mungkin di pinggir hutan yang dapat memberikan dukungan persediaan makan bagi kita. Tentu ada diantara kita yang memiliki kemampuan berburu. Padukuhan-padukuhan disekitar padepokan itu tentu juga akan dapat menjadi sumber bahan makanan bagi kita.”
“Dengan demikian, hubungan yang buruk akan terulang kembali di tempat yang baru itu.” potong Nyai Wiji Sari.
“Kita akan dapat menyebut nama Kiai Banyu Bening.”
Nyai Wiji Sari mengangguk-angguk. Meskipun demikian ia pun berkata ”Persiapan kita harus meyakinkan. Tetapi yang penting bagiku, aku akan mengambil dan merawat anakku yang selalu hadir didalam mimpi-mimpiku.”
Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Katanya, ”Aku mengerti.”
Beberapa saat kemudian, maka sekelompok orang yang baru datang dari kaki Gunung Lawu itupun diperkenankan untuk beristirahat. Namun Kiai Narawangsa itupun berkata, ”Mulai besok kita akan berkemas.”
“Aku tidak ingin persiapan kita berkepanjangan” berkata Nyai Wiji Sari ”Aku rindukan anak itu.”
Perintah untuk mempersiapkan diri itupun kemudian telah sampai ke setiap telinga. Seorang yang rambutnya sudah ubanan berbisik kepada kawannya, ”Langkah yang kurang bijaksana. Tempat ini merupakan tempat yang paling baik. Jika kita berada di daerah baru, apakah kita dapat dengan segera mendapatkan lahan yang subur.”
“Kawan-kawan kita sudah sempat melihat-lihat. Tanah di sekitar padepokan di kaki gunung Lawu itu sangat subur. Banyak cadangan tanah yang masih terbuka.”
“Kau memang dungu!” geram orang yang rambutnya sudah ubanan itu ”Bukan lahan yang akan kita tanami padi dan jagung.”
“Maksud paman?”
“Lahan yang dapat menyediakan uang, emas dan permata. He, bukankah disamping bercocok tanam kita juga selalu menuai benda-benda berharga itu? Kita tinggal mengambilnya dan membawanya ke padepokan.”
“O” orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya lagi ”Bukankah dimana-mana ada orang kaya?”
“Sudah, sudah!” potong orang yang rambutnya ubanan ”kau memang dungu.”
Orang yang berambut ubanan itupun kemudian telah bangkit dan melangkah pergi. Sejak hari berikutnya, maka Kiai Narawangsa telah memerintahkan orang-orangnya untuk berlatih. Disela-sela kerja mereka disawah dan pategalan, mereka telah menyelenggarakan latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan mereka lebih dari biasanya.
Disamping latihan-latihan yang meningkat, maka Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari juga meningkatkan kegiatan mereka di malam hari. Sebelum mereka meninggalkan padepokan mereka, maka Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari berniat untuk mengurus benda-benda berharga yang ada di daerah jangkauan mereka.
Hampir setiap malam, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari telah keluar dari padepokan mereka. Sekali-sekali mereka berpacu di bulak-bulak panjang di atas punggung kuda bersama ampat atau lima orang pengikutnya. Tetapi pada kesempatan, lain, mereka berjalan menyusuri pematang dan bahkan padang-padang perdu untuk mengumpulkan benda-benda berharga.
Sementara itu di siang hari beberapa orang pengikutnya berkeliaran untuk mencari sasaran serta melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada sasaran itu. Dengan demikian, maka pada lingkungan yang terhitung luas di sekitar padepokan Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari itu, keadaannya menjadi semakin memburuk.
Seakan-akan tidak ada kekuatan yang dapat membendung perampokan-perampokan yang semakin sering terjadi. Padukuhan-padukuhan besar dan kecil selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Gardu-gardu peronda justru menjadi kosong, karena para peronda berapapun jumlahnya tidak akan mampu menghentikan perampokan-perampokan itu.
Ketika pada suatu saat, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari menemui sebuah gardu yang ditunggui oleh lima orang peronda. maka nasib kelima orang peronda itu menjadi sangat buruk. Bahkan mereka masih juga sempat mengancam, jika masih ada yang meronda di malam-malam mendatang, maka mereka akan dihabisi. Dengan demikian, maka ketakutan pun semakin tersebar di daerah yang luas di sekitar padepokan itu. Tetapi tidak ada yang mampu mengatasinya.
Disamping kegiatan yang meningkat itu, maka latihan-latihan pun berlangsung semakin meningkat. Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari telah menjadi semakin mantap. Daerah perburuan benda-benda berharga di lingkungan yang terasa menjadi semakin tua itu, telah menjadi semakin kering pula. Sehingga karena itu, maka mereka mengharapkan daerah baru yang masih subur.
Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari juga memperhitungkan kemungkinan, bahwa daerah di sekitar kaki Gunung Lawu itu juga sudah dikuras habis oleh Kiai Banyu Bening. Namun jika mereka dapat menduduki padepokan Kiai Banyu Bening, maka benda-benda yang tersimpan di padepokan itu akan jatuh ketangan mereka pula. Namun Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari ternyata cukup berhati-hati. Mereka telah mengirimkan beberapa orang untuk mengamati padepokan itu dalam beberapa hari.
“Kalian harus mengetahui, seberapa kekuatan yang tersimpan di padepokan itu, sehingga kedatangan kita tidak sekedar menyurukkan kepala kita kedalam api.”
Dengan demikian, maka lima orang telah diperintahkan untuk berangkat menuju ke kaki Gunung Lawu. Dua diantara mereka adalah orang-orang yang pernah pergi ke padepokan Kiai Banyu Bening, sementara yang lain adalah urang-orang baru. Diharapkan bahwa orang-orang baru itu akan dapat memberikan pertimbangan yang lebih lengkap setelah mereka melihat padepokan Kiai Banyu Bening dan lingkungan disekitarnya...
Selanjutnya,
MATAHARI SENJA BAGIAN 17
MATAHARI SENJA BAGIAN 17