Serial Pendekar Pulau Neraka
Episode Lambang Kematian
Karya Teguh S
Penerbit Cintamedia, Jakarta
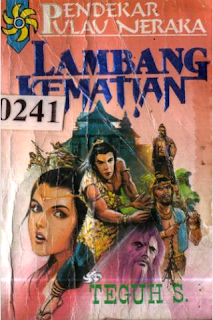
SATU
SEEKOR kuda putih tampak tengah dipacu dengan cepat memasuki daerah perbatasan Kadipaten Jati Anom. Penunggangnya seorang laki‐laki berusia sekitar lima puluh tahun. Dia berpakaian indah yang terbuat dari bahan sutra halus dan bersulam benang emas. Rambutnya panjang tergelung ke atas, dengan anak-anak rambut yang meriap tertiup angin.
"Heya Heya..."
Laki‐laki itu menggebah kudanya lebih kencang lagi. Sementara debu‐debu yang mengepul oleh kaki‐kaki kuda itu bertambah banyak beterbangan. Tidak sedikit pun dia memperlambat lari kudanya meskipun sudah memasuki pusat kota yang ramai. Hal itu tentu saja menarik perhatian semua orang yang memadati jalan utama Kadipaten Jati Anom. Tapi nampaknya tidak seorang pun yang berani menegur, apalagi sampai menghentikannya.
"Cepat buka pintu" seru laki‐laki itu ketika hampir sampai ke pintu gerbang sebuah bangunan besar dan berpagar tembok batu tebal yang tinggi dan kokoh. Sebentar saja dua orang penjaga pintu gerbang segera membuka pintu yang terbuat dari kayu jati yang tebal dan keras. Bunyi bergerit terdengar saat pintu gerbang itu terkuak. Dan tanpa memperlambat lari kudanya, laki‐laki berpakaian indah itu langsung menerobos masuk. Sedangkan dua orang penjaga pintu gerbang hanya bisa menggeleng‐gelengkan kepalanya saja.
"Hooop..."
Laki‐laki berusia sekitar lima puluh tahun itu langsung melompat turun dari punggung kuda putihnya, begitu sampai di depan tangga yang menuju ke serambi depan dari bangunan itu. Tampak beberapa orang yang berseragam dan membawa tombak panjang langsung berdiri berbaris dan memberi hormat. Laki‐laki itu terus melangkah dengan tergesa‐gesa menaiki anak‐anak tangga yang menuju serambi depan yang luas dengan pilar‐pilar besar menyangga atap.
Langkahnya terus terayun melintasi serambi yang berlantai batu pualam putih berkilat. Seorang laki‐laki tua yang memakai jubah warna kuning dengan kepala botak menyambutnya dengan membungkukkan badan. Tangannya tidak berhenti mengelus‐elus janggut putih yang panjang menutupi lehernya.
"Di mana Adipati Rakondah?" tanya laki‐laki itu dengan napas tersengal memburu.
"Gusti Adipati berada di taman belakang, Gusti Panglima," sahut laki‐laki berjubah kuning itu.
Dan tanpa berkata apa‐apa lagi, laki‐laki berbaju indah itu langsung melangkah ke dalam. Langkahnya tetap lebar dan tergesa‐gesa melintasi ruangan dalam yang lebar dan luas. Sepertinya dia sudah tidak asing lagi dengan keadaan bangunan itu. Tak lama kemudian dia disambut oleh beberapa orang berpakaian seragam yang berjaga‐jaga di sekitar bangunan itu.
"Kakang Panglima Bantaraji..."
Satu seruan terkejut dan gembira terdengar saat laki-laki setengah baya itu memasuki sebuah taman yang ditata indah di belakang bangunan istana itu. Tampak seorang laki laki yang berwajah tampan dengan rambut berwarna dua segera menyongsongnya dengan tangan yang terbuka lebar. Laki‐laki berusia setengah baya yang ternyata adalah seorang panglima bernama Bantaraji itu hanya berdiri tegak dengan bibir mengulas senyuman tipis.
"Kau tidak keberatan kalau aku akan mengganggu sebentar, Adik Adipati Rakondah?"
Laki‐laki tampan yang usianya sebaya dengan Panglima Bantaraji itu hanya tersenyum. Kemudian dia mempersilakan tamunya itu untuk duduk di sebuah bangku taman yang terbuat dari kayu jati berukir indah.
Sejenak Panglima Bantaraji mengedarkan pandangannya berkeliling, menyapu beberapa wanita cantik dan beberapa orang pengawal yang berseragam prajurit dengan senjata tombak panjang di tangan.
Hanya ada satu orang yang masih tinggal. Seorang gadis cantik mengenakan baju biru masih duduk di pinggir kolam.
"Anakku, Intan Delima, Kakang," kata Adipati Rakondah, ketika melihat tatapan mata Panglima Bantaraji terarah ke dekat kolam.
"Kau bisa meminta Intan Delima untuk meninggalkan taman ini?" pinta Panglima Bantaraji.
"Kenapa? Apakah berita yang kau bawa begitu rahasia, sehingga keponakanmu sendiri tidak boleh mendengar?" Adipati Rakondah tampak keberatan.
"Sebaiknya memang begitu. Soalnya hal ini menyangkut masa lalumu," agak berbisik suara Panglima Bantaraji.
"Intan...," panggil Adipati Rakondah.
"Ya, Ayah," lembut dan merdu sekali suara gadis itu menyahut.
"Kau bisa pergi sebentar? Ayah ingin bicara dengan pamanmu," kata Adipati Rakondah.
Intan Delima memandang Panglima Bantaraji sebentar. Lalu dia bangkit berdiri, dan mengangguk ke arah pamannya yang baru datang. Kemudian dia melangkah pergi tanpa membantah sedikit pun. Langkah kakinya gemulai dan sedap dipandang mata. Panglima Bantaraji menunggu sampai gadis itu lenyap di balik pintu.
"Berita apa yang kau bawa?" tanya Adipati Rakondah langsung.
"Kau ingat dengan Rengganis?"
Adipati Rakondah langsung berubah raut wajahnya. Nama Rengganis sudah begitu dikenalnya. Dan hampir setiap tahun, wanita cantik itu selalu mengundangnya untuk datang ke pesta yang selalu diadakan di atas sebuah kapal layar besar dan mewah di Pesisir Pantai Selatan. Makanya dia tahu betul siapa Rengganis itu. Orang tuanya adalah seorang patih kerajaan, namun kemudian berkhianat hendak menggulingkan Raja Kandaka yang sekarang sudah mangkat dan digantikan oleh putranya.
Di samping itu dia juga pernah membantu Rengganis untuk menghancurkan Padepokan Teratai Putih yang diketuai oleh Dewa Pedang, bekas seorang panglima yang mengundurkan ciri setelah menunaikan tugas berat. Hal itu dilakukannya karena Adipati Rakondah merasa berhutang budi pada orang tua Rengganis. Dan dia memang punya dendam pribadi dengan Dewa Pedang.
"Aku tidak akan pernah melupakannya, Kakang. Memang tahun ini aku tidak bisa memenuhi undangannya, karena aku tidak bisa meninggalkan putriku yang baru pulang dari padepokan pamannya di Gunung Rangkas," kata Adipati Rakondah.
"Kalau waktu itu kau ada di sana, tentu aku tidak perlu repot‐repot datang ke sini, Adik Rakondah," sungut Panglima Bantaraji.
"Kau datang ke sana? Apa ada sesuatu yang terjadi, Kakang?" tanya Adipati Rakondah mengerutkan keningnya.
"Mungkin kau tidak akan percaya kalau aku mengatakan bahwa pesta itu berantakan, dan kapal Rengganis hancur," sahut Panglima Bantaraji.
"Apa...?" Adipati Rakondah tersentak tidak percaya. "Jangan bicara main‐main, Kakang. Mereka yang diundang bukan orang‐orang sembarangan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi?"
"Sudah aku katakan tadi, ini adalah peristiwa lama dan ada hubungannya dengan masa lalumu."
Sejenak Adipati Rakondah menggeser duduknya untuk lebih mendekat. Sedangkan bola matanya berputar mengedar berkeliling. Seolah‐olah dia takut kalau pembicaraan ini ada yang mendengar. "Siapa yang telah melakukan itu?" tanya Adipati Rakondah setengah berbisik.
"Kau pasti akan lebih terkejut kalau mendengarnya."
"Katakan, siapa?" desak Adipati Rakondah tak sabar.
"Putra Dewa Pedang, sekarang dia memakai nama julukan Pendekar Pulau Neraka..."
Adipati Rakondah tidak bisa lagi berkata‐kata. Mulutnya ternganga lebar, dan kedua bola matanya berputar‐putar. Sedangkan raut wajahnya berubah kemerahan, dan sebentar kemudian pucat‐pasi. Dia seperti tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Rasanya mustahil kalau Bayu masih hidup. Apalagi sampai muncul lagi dengan nama julukan Pendekar Pulau Neraka. Waktu itu dia menyaksikan sendiri, bagaimana Badar, murid utama Padepokan Teratai Putih membawa lari seorang bayi yang berumur beberapa hari menuju Pulau Neraka. Sebuah pulau yang sangat ditakuti dan tak ada seorang pun yang mau menginjakkan kakinya ke sana. Dan sampai sekarang belum pernah ada seorang pun yang bisa keluar dengan selamat kalau sudah masuk ke sana
(Untuk lebih jelasnya, baca serial Pendekar Pulau Neraka dalam episode perdananya yang berjudul Geger Rimba Persilatan)
"Mustahil..." Adipati Rakondah menggeleng‐gelengkan kepalanya tidak percaya.
"Kau akan percaya kalau sudah melihatnya, Adik Rakondah," kata Panglima Bantaraji.
Adipati Rakondah jadi terdiam lagi.
"Aku yakin, sekarang Pendekar Pulau Neraka sedang mencari orang‐orang yang waktu itu mendukung Rengganis untuk menghancurkan Padepokan Teratai Putih," lanjut Panglima Bantaraji.
Sejenak Adipati Rakondah mengangkat kepalanya. Dia menatap tajam pada laki‐laki gagah yang duduk di sampingnya itu. Kini otaknya tiba‐tiba jadi buntu, tidak mampu lagi untuk dipakai berpikir. Berita yang dibawa oleh Panglima Bantaraji benar‐benar mengejutkannya, bahkan seperti berita datangnya kiamat. Kabar yang dibawa oleh Panglima Bantaraji sudah jelas. Dan dia bisa menebak bahwa Rengganis tewas di tangan seorang pemuda yang mengaku bernama Pendekar Pulau Neraka itu. Beberapa saat kemudian Adipati Rakondah bangkit dari duduknya dan berjalan mondar‐mandir dengan kening berkerut dalam. Sementara Panglima Bantaraji tetap duduk sambil memperhatikan.
********************
Sejak mendapat berita dari kakaknya, Panglima Bantaraji, Adipati Rakondah selalu tampak gelisah. Dia jadi lebih senang menyendiri dan melamun. Hanya kalau malam hari saja dia pergi ke kaki Gunung Panjaran untuk memperdalam ilmu‐ilmu olah kanuragannya. Seperti malam ini, dia tampak sudah berada di sekitar kaki gunung itu.
"Hiyaaa..."
Glarrr!
Malam yang sunyi sepi tiba‐tiba pecah oleh suara ledakan dan gemuruh bebatuan yang hancur berkeping-keping. Tampak Adipati Rakondah berdiri tegak dengan kedua telapak tangan masih terbuka dan menjulur ke depan. Sedangkan matanya dengan tajam menatap reruntuhan batu yang berada sekitar sepuluh depa di depannya. Kepulan debu masih membayang di udara. Sedangkan pecahan‐pecahan batu juga masih ber-hamburan turun bagai hujan.
"Bagus..." tiba‐tiba terdengar suara diiringi tepuk tangan.
Adipati Rakondah langsung berbalik. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Panglima Bantaraji tiba‐tiba sudah berada di belakangnya. Panglima Kerajaan Banyu Biru itu kemudian melangkah pelahan‐lahan menghampirinya. Tampak bibirnya yang tipis dengan kumis tebal di atasnya menyunggingkan senyuman cerah.
"Jurus 'Tapak Sakti'mu benar‐benar luar biasa" puji Panglima Bantaraji sambil geleng‐geleng kepala perlahan.
"Jangan memperolokku, Kakang," rungut Adipati Kakondah.
"Aku yakin dengan jurus itu kau akan mampu menandingi Pendekar Pulau Neraka."
"Aku justru merasa sebaliknya, Kakang. Jurus ‘Tapak Sakti ku memang seimbang dengan jurus ‘Kipas Maut' Nyai Rengganis. Tapi aku baru bisa menguasainya di bawah jurus 'Kipas Maut'. Rasanya aku belum mampu, Kakang," nada suara Adipati Rakondah terdengar mengeluh.
"Jangan berkecil hati dulu, Adik Rakondah. Meskipun aku tahu bahwa kau salah, tapi aku tidak akan tinggal diam begitu saja. Aku sudah mengirim utusan ke kerajaan, dan meminta prajurit‐prajurit pilihanku untuk datang ke sini."
"Untuk apa? Kakang hanya membuang‐buang waktu dan nyawa sia‐sia," Adipati Rakondah menyesalkan.
"Jangan berpikir yang bukan‐bukan dulu, Adik Rakondah. Aku melakukan semua itu hanya untuk sekedar berjaga‐jaga. Aku dengar sudah beberapa tokoh sakti yang dulu ikut menghancurkan Padepokan Teratai Putih tewas di tangannya. Tindakan pendekar itu kejam dan tidak kenal ampun. Siapa saja yang mencoba menghalangi maksudnya, tidak diberi kesempatan hidup lagi. Aku harap kau bisa mengerti, Adik Rakondah. Aku hanya menjaga kemungkinan, kalau‐kalau dia akan berbuat kejam. Bagaimanapun juga keselamatan Kadipaten Jati Anom adalah tanggung jawabku juga," Panglima Bantaraji mencoba menjelaskan.
"Terima kasih, Kakang," ucap Adipati Rakondah terharu.
"Hanya satu pesanku, Adik Rakondah," lanjut Panglima Bantaraji. Adipati Rakondah menatap lurus ingin tahu. "Kau harus hati‐hati terhadap senjatanya."
"Maksudmu, Kakang?"
"Senjata Pendekar Pulau Neraka berbentuk cakra bersegi enam. Senjata itu dapat melayang seperti memiliki mata. Dan sampai saat ini belum ada satu senjata pun yang mampu menandinginya. Bahkan Tongkat Sakti Jantara pun sudah dibabat buntung"
"Kakang...? Apakah Kakang Jantara juga ikut tewas?" Adipati Rakondah terkejut.
"Benar."
"Bagaimana Kakang bisa tahu semuanya?" tanya Adipati Rakondah seperti menyelidik.
"Aku mengikuti semua kejadian dengan sembunyi-sembunyi. Dan aku melihat semua kejadian yang dilakukan oleh Pendekar Pulau Neraka itu. Aku sendiri tidak tahu, apakah pendekar itu mengetahui kehadiranku atau tidak. Yang jelas, aku selalu menguntit ke mana pendekar itu pergi untuk mencari orang‐orang yang telah bersekutu menghancurkan Padepokan Teratai Putih," kembali Panglima Bantaraji menjelaskan.
"Dan sekarang Kakang tiba‐tiba berada di sini, apakah Pendekar Pulau Neraka itu juga ada di sekitar sini?" tebak Adipati Rakondah mulai bisa mengerti.
"Entahlah, dia sudah sampai atau belum. Tapi yang jelas arah perjalanannya menuju Kadipaten Jati Anom ini."
Kembali Adipati Rakondah terdiam.
"Malam sudah terlalu larut, sebaiknya sekarang kau pulang saja. Dan aku akan terus berusaha menjauhkan pendekar itu dari Kadipaten Jati Anom," kata Panglima Bantaraji.
"Apa yang akan kau lakukan, Kakang?" tanya Adipati Rakondah.
Panglima Bantaraji hanya tersenyum. Kemudian Iangkahnya terayun. Sedangkan Adipati Rakondah juga ikut melangkah di belakang laki‐laki setengah baya yang masih kelihatan gagah itu. Mereka terus berjalan tanpa banyak bicara lagi. Sementara malam terus merayap semakin larut. Dan angin malam yang dingin menebarkan titik‐titik embun, menambah suasana semakin sunyi dan dingin.
********************
DUA
Pagi ini awan hitam tampak menggantung dan berarak di angkasa. Sementara cahaya matahari seperti tak sanggup untuk menembus kepekatan awan yang menyelimuti seluruh langit di atas Kadipatan Jati Anom. Sedangkan hembusan angin yang bertiup kencang menebarkan udara dingin seperti menusuk sampai ke tulang. Tampak daun‐daun berguguran, dan debu‐debu berkepulan tersapu angin. Seluruh kota kadipaten itu tampak sepi, hanya sesekali terlihat satu dua orang yang melintasi jalan utama kota itu.
Dari arah pintu gerbang perbatasan kadipaten sebelah Utara, tampak seorang laki‐laki gagah sedang melangkah ringan mendekati pintu gerbang. Sampai di depan pintu gerbang, pemuda itu hanya melirik pada dua penjaga yang memandanginya denga tatapan mata penuh selidik. Hingga pemuda itu berlalu, kedua penjaga itu masih tetap memperhatikannya. Kadipaten Jati Anom memang sering kedatangan tamu, baik yang hanya singgah maupun yang ingin menetap, sehingga setiap kali ada pendatang baru para penjaga pintu gerbang perbatasan tidak pernah menegur atau bertanya.
"Orang itu tampaknya mencurigakan, ya...?" bisik salah seorang penjaga.
"Hm...," gumam satunya lagi tidak jelas, namun matanya terus mengamati pemuda yang sudah jauh berjalan.
"Ciri‐cirinya seperti yang pernah dikatakan oleh Panglima Bantaraji," kata penjaga itu lagi.
"Benar" seru yang satunya. Dan tanpa berkata apa‐apa lagi, kedua penjaga pintu gerbang perbatasan itu langsung berlari kencang memburu pemuda tadi.
"Berhenti..."
Pemuda gagah itu segera menghentikan langkahnya. Namun sedikit pun dia tidak berbalik atau menoleh. Dia tetap berdiri tegak dengan pandiangan lurus ke depan. Kedua penjaga itu terus menghampiri dan mencegatnya.
"Maaf, Kisanak. Kami harus memeriksa Anda dulu," kata salah seorang penjaga dengan sopan.
"Bukankah kota ini bebas untuk didatangi oleh pendatang?"
"Benar, tapi sekarang Gusti Adipati dan Gusti Panglima telah memerintahkan kami untuk memeriksa setiap pendatang baru."
"Sejak kapan peraturan itu berlaku?"
"Tujuh hari yang lalu."
"Kalau aku menolak...?"
Sejenak kedua penjaga itu saling berpandangan. Kata‐kata pemuda gagah itu terdengar dingin dan kaku. Sedangkan sinar matanya tampak tajam, seakan‐akan mampu membuat siapa saja yang memandangnya bergidik tanpa sebab. Maka seperti dikomando saja, kedua penjaga itu segera melangkah mundur dua tindak. Sementara tangannya menggenggam tombak dengan lebih erat.
"Maaf, Kisanak. Sebenarnya kami juga enggan untuk memeriksa setiap orang yang datang ke kota ini, tapi kami hanya menjalankan tugas," kata salah seorang penjaga masih bersikap sopan, meskipun sudah waspada.
"Katakan pada Gusti‐mu, aku tidak akan lama di sini. Dan aku akan segera meninggalkan kota ini setelah urusanku selesai" lantang dan tegas kata‐kata pemuda itu. Dan tanpa menghiraukan kebingungan kedua penjaga itu, dia segera mengayunkan langkahnya kembali. Ayunan kakinya tampak ringan dan tenang. Tapi kemudian, kedua penjaga itu langsung melompat dan kembali menghadang. Kali ini ujung tombaknya sudah terhunus.
"Maaf, kami terpaksa menahanmu, Kisanak," kata salah seorang penjaga.
"Hm..." Pemuda itu tidak mempedulikan. Dia terus saja mengayunkan kakinya.
"Berhenti"
Tapi pemuda itu tetap tidak menghiraukan, dia terus melangkah maju. Sementara kedua penjaga itu saling pandang, lalu dengan cepat salah seorang dari mereka menggerakkan tombaknya ke arah perut pemuda itu. Namun hanya dengan mengegoskan tubuhnya sedikit ke samping, pemuda itu luput dari serangan. Bahkan tanpa diduga sama sekali, tangan pemuda itu bergerak cepat dan mengempit batang tombak itu di ketiaknya. Sedangkan tangan satunya lagi berhasil mematahkan tombak itu. Dan belum lagi penjaga itu sempat menguasai keadaan, sebuah ayunan kaki yang bergerak bagai kilat, langsung menghantam dadanya yang keras.
"Hugh" penjaga itu mengeluh pendek. Tubuhnya sampai terjajar ke belakang beberapa depa.
Melihat keadaan itu, penjaga yang satunya lagi segera mengibaskan tombaknya ke arah leher. Namun dengan cepat pemuda itu menarik kepalanya ke belakang, dan tangan kanannya terangkat ke atas menangkap tombak itu. Lalu dengan satu kali hantaman tangan kiri, tombak itu kembali patah jadi dua bagian.
"Akh..."
Kedua penjaga itu terkejut bukan main. Dalam sekejap saja kedua tombak mereka sudah patah jadi dua bagian. Sementara pemuda itu masih tetap berdiri tegak tanpa menggeser kakinya sedikit pun. Sebentar mereka saling pandang, lalu....
Sret
Hampir bersamaan kedua penjaga itu mencabut pedang yang tergantung di pinggang. Kedua pedang penjaga itu berukuran panjang dan berwarna keperakan berkilat. Tampak pemuda gagah itu hanya menatap dengan bibir yang mengulas senyum sinis.
"Sayang sekali, nama kalian tidak tercantum dalam daftarku...," kata pemuda gagah itu bergumam. Setelah berkata demikian, pemuda itu langsung melesat pergi bagai kilat melewati kepala kedua penjaga itu. Tentu saja hal itu membuat kedua penjaga itu melongo seperti melihat dewa baru turun dari kahyangan. Dan saat mereka membalikkan tubuh pemuda gagah itu sudah tidak terlihat lagi bayangannya.
"Siapa dia, ya...?" salah seorang penjaga bergumam sambil memasukkan pedangnya kembali ke dalam warangkanya.
"Kau tunggu dulu di sini, aku akan melaporkan hal ini pada Gusti Adipati," kata seorang lagi.
"Cepatlah, tidak enak berjaga sendirian. "
"Sebentar saja aku pasti sudah kembali, kalau tidak... Paling‐paling juga mampir di rumah janda sebelah"
"Sialan"
********************
Adipati Rakondah segera berdiri begitu melihat seorang berpakaian prajurit penjaga datang dengan tergopoh‐gopoh. Prajurit itu langsung berlutut memberi hormat. Tampak tubuhnya bersimbah peluh, sementara debu menempel di wajah dan bajunya. Napasnya masih terengah‐engah seperti baru saja menempuh perjalanan jauh dan melelahkan.
"Ada apa? Bukankah kau seharusnya masih menjaga di pintu gerbang perbatasan sebelah Utara kota?" tanya Adipati Rakondah sedikit terkejut.
"Ampun, Gusti. Hamba sengaja datang ke sini karena ada sesuatu hal yang harus segera hamba laporkan," sahut prajurit penjaga perbatasan itu.
"Katakan cepat, apa yang akan kau laporkan?"
"Baru saja ada seorang pemuda yang mencurigakan melewati pintu gerbang, Gusti. Hamba sudah berusaha untuk menahan dan memeriksanya, tapi pemuda itu malah melawan. Ilmu olah kanuragannya sangat tinggi, Gusti. Hanya sekali gebrak saja, hamba dan teman hamba terkecoh dan dia berhasil kabur," lapor prajurit penjaga itu.
Sejenak Adipati Rakondah memalingkan mukanya dan menatap pada Panglima Bantaraji yang tetap duduk di kursinya. Di sebelah Panglima Bantaraji, duduk seorang gadis cantik yang mengenakan baju ungu yang terbuat dan bahan sutra halus yang indah. Gadis itu adalah putri tunggal Adipati Rakondah yang bernama Intan Delima.
"Bagaimana ciri‐cirinya?" tanya Panglima Bantaraji.
"Dia mengenakan baju yang terbuat dari kulit harimau, Gusti Panglima," sahut prajurit penjaga perbatasan itu.
"Kau tidak salah lihat, Prajurit?" Panglima Bantaraji bangkit dari duduknya.
"Tidak, Gusti."
"Ada apa, Kakang? Kau kenal?" tanya Adipati Rakondah. "Tidak salah lagi. Pasti dialah orangnya..." gumam Panglima Bantaraji pelan.
"Maksudmu...?"
"Pendekar Pulau Neraka selalu memakai baju dari kulit harimau. Hm..., tapi...."
"Kenapa, Kakang?" tanya Adipati Rakondah tak sabar.
Panglima Bantaraji tidak segera menyahut. Di malah melangkah menghampiri prajurit penjaga pintu gerbang perbatasan itu. Matanya tajam menatap prajurit yang duduk bersimpuh dengan kepala tertunduk dalam itu.
"Prajurit"
"Hamba, Gusti Panglima."
"Kau sempat bertarung dengannya?" tanya Panglima Bantaraji.
"Benar, Gusti. Tapi hanya sekali gebrakan saja."
"Apa dia mengeluarkan senjatanya?"
"Tidak, Gusti."
Panglima Bantaraji kemudian berbalik dan menghadap Adipati Rakondah yang sudah duduk kembali di kursinya. Sementara putrinya tetap diam sejak tadi, seperti tidak mau peduli sama sekali dengan pembicaraan itu. Namun dari keningnya yang sedikit berkerut, bisa dipastikan kalau gadis itu sedang berpikir juga.
"Adik Rakondah. Sebaiknya mulai sekarang kau melipatgandakan penjagaan. Aku akan segera menyelidiki orang itu," kata Panglima Bantaraji.
"Hati‐hati, Kakang," hanya itu yang bisa diucapkan Adipati Rakondah.
Kemudian Panglima Bantaraji segera berbalik dan melangkah meninggalkan ruangan balai agung Kadipaten Jati Anom itu. Sedangkan Adipati Rakondah segera memerintahkan pada prajurit penjaga itu untuk kembali bertugas. Dia juga memerintahkan untuk melipatgandakan penjagaan di pintu gerbang masuk batas kota kadipaten.
"Apa yang sebenarnya terjadi, Ayah?" tanya Intan Delima setelah lama berdiam diri.
"Tidak apa‐apa, hanya sedikit persoalan kecil," sahut Adipati Rakondah.
"Siapa orang itu, Ayah?" desak Intan Delima.
Adipati Rakondah tidak menjawab. Dia hanya tersenyum, dan melangkah meninggalkan ruangan besar itu. Sementara Intan Delima nampak masih diliputi oleh rasa penasaran, tapi dia tidak berani mendesak ayahnya untuk berkata terus terang. Kemudian gadis itu hanya mengangkat bahunya saja dan berlalu dari ruangan itu.
********************
Keadaan di Istana Kadipaten Jati Anom sekarang telah berubah. Dari siang sampai malam para prajurit kadipaten tampak selalu bersiaga dengan senjata lengkap seperti mau diserang musuh saja. Adipati Rakondah memang telah memerintahkan untuk melipat‐gandakan penjagaan di sekitar istana itu.
Sementara itu Intan Delima yang belum memahami betul akan situasi dan persoalan yang sedang dihadapi ayahnya, makin bertambah penasaran melihat keadaan itu. Kini Kadipaten Jati Anom benar‐benar seperti mau perang saja. Bukan hanya di sekitar istana kadipaten saja yang dijaga ketat, tapi juga hampir seluruh pelosok kota kadipaten.
"Aku tidak percaya kalau hal ini hanya karena persoalan kecil...," gumam Intan Delima yang pagi itu sedang berjalan‐jalan mengelilingi istana kadipaten.
"Mungkin ada musuh yang akan menyerang, Gusti Ayu," celetuk seorang emban pengasuh yang mendampinginya.
"Tidak, Bibi Emban. Aku sudah mendengar sedikit pembicaraan. Aku jadi penasaran, siapa sebenarnya pemuda yang begitu ditakuti oleh Ayah dan Paman Panglima?" Intan Delima seperti bicara pada dirinya sendiri.
Dua orang emban yang mengikutinya tidak membuka suara. Mereka terus saja berjalan pelan‐pelan menuju taman samping. Beberapa saat kemudian, Intan Delima menghenyakkan tubuhnya di kursi panjang yang terbuat dari bambu di dekat kolam yang diisi dengan berbagai jenis ikan.
"Bibi Emban, tolong katakan pada pengurus kuda agar segera menyiapkan seekor kuda untukku sekarang," perintah Intan Delima.
"Gusti Ayu hendak ke mana?" tanya salah seorang emban yang bertubuh gemuk.
"Laksanakan saja perintahku" sentak Intan Delima.
"Baik, Gusti Ayu." Perempuan bertubuh gemuk itu pun bergegas menuju istal.
Sedangkan Intan Delima kembali berdiri dan melangkah menuju ke bagian depan. Ayunan kakinya lebar‐lebar, dan bibirnya terkatup rapat. Sementara seorang emban lagi terus menguntitnya dengan wajah dipenuhi tanda tanya.
"Gusti Ayu...," Emban itu memberanikan diri membuka suara.
"Ada apa?" tanya Intan Delima sambil terus melangkah.
"Gusti Adipati menyatakan bahwa seluruh kadipaten dalam keadaan gawat, sebaiknya Gusti Ayu membawa beberapa orang prajurit pengawal," saran limban itu.
Namun Intan Delima tidak menanggapi. Dia berhenti melangkah pada saat ada seorang laki‐laki tua yang datang menghampirinya dengan menuntun seekor kuda putih dengan kaki‐kakinya belang hitam. Di belakangnya tampak seorang wanita gemuk mengikuti Kuda sudah siap dengan pelana dari kain tebal yang bersulamkan benang emas. Dan tanpa banyak bicara lagi, Intan Delima langsung melompat naik ke punggung kuda. Dan saal itu juga Intan Delima segera menggebah kudanya menuju ke pintu gerbang istana kadipaten yang dijaga tidak kurang dari sepuluh prajurit.
Kuda putih dengan belang hitam pada kakinya itu terus dipacu cepat meninggalkan kepulan debu di belakangnya. Dua orang penjaga pintu gerbang bergegas membuka pintu dengan raut wajah yang diliputi berbagai macam perasaan. Sepertinya mereka tidak ingin membukakan pintu, tapi begitu melihat yang menunggang kuda adalah putri Adipati Jati Anom, mereka segera membuka pintu gerbang itu. Intan Delima terus menggebah kudanya dengan kencang ke luar dari lingkungan benteng istana kadipaten. Sementara penjaga pintu gerbang segera menutup kembali pintunya setelah kuda yang di-tunggangi Intan Delima ke luar.
"Hiya Hiya " Intan Delima terus menggebah kudanya dengan cepat melintasi jalan utama Kadipaten Jati Anom. Beberapa orang penduduk kota yang berpapasan dengannya, langsung membungkukkan badannya. Intan Delima terus memacu kudanya menuju perbatasan Utara kadipaten.
"Hooop..." Intan Delima segera menghentikan lari kudanya tepat di depan pintu gerbang perbatasan yang terbuat dari batu ukir di kanan kiri jalan. Enam orang prajurit penjaga yang ada langsung membungkukkan badan memberi hormat. Intan Delima menatap salah seorang prajurit penjaga yang berdiri paling pinggir.
"Kau, ke sini"
"Hamba, Gusti Ayu," sahut prajurit penjaga itu segera menghampiri.
"Kau yang melapor kemarin?"
"Benar, Gusti Ayu."
"Aku minta agar kau berkata jujur dan terus terang. Siapa pemuda yang berbaju kulit harimau itu?" tegas nada suara Intan Delima.
"Maksud, Gusti Ayu?"
'Yang kau laporkan kemarin. Goblok"
"Maaf, Gusti Ayu. Hamba‐..., hamba hanya mendapat perintah untuk menjaga pintu gerbang perbatasan Utara saja, Gusti. Hamba...."
"Jangan banyak alasan. Cepat katakan, siapa nama pemuda itu?" potong Intan Delima gusar.
Prajurit itu jadi kebingungan. Sejenak bola matanya berputar melirik pada temannya yang bungkam saja sejak tadi. Dia seperti sedang berpikir keras dan menimbang‐nimbang permintaan putri tunggal junjungannya ini. Rasanya sulit bagi dia untuk mengatakan yang sebenarnya, karena Adipati Rakondah sendiri sudah berpesan padanya untuk tidak mengatakan hal ini pada Intan Delima. Adipati Rakondah tidak ingin putrinya itu terlibat, dan menjadi korban dari kekejaman Pendekar Pulau Neraka yang kini hatinya sedang tersulut oleh api dendam.
Lama kelamaan Intan Delima jadi geregetan juga melihat sikap prajurit itu. Kemudian gadis itu melompat turun dari atas punggung kudanya, dan mendarat manis tepat di depan prajurit itu. "Katakan, siapa nama pemuda yang berbaju kulit harimau itu?" dingin dan datar suara Intan Delima.
"Ampunkan hamba, Gusti Ayu. Hamba..., hamba sudah dipesan untuk..."
"Tidak mengatakan padaku, begitu?" sentak Intan Delima semakin gusar.
Prajurit penjaga itu hanya diam tertunduk.
"Siapa yang telah memerintahmu begitu? Paman Panglima...? Ayah?" berondong Intan Delima.
"Gusti Adipati Rakondah sendiri, Gusti Ayu," pelan jawaban prajurit penjaga itu.
"Dengar kalian semua! Siapa saja yang berani buka mulut bahwa aku telah mengorek keterangan, akan berhadapan langsung denganku" lantang suara Intan Delima.
Enam orang prajurit penjaga tersebut langsung diam sambil menundukkan kepala. Tidak ada seorang pun yang bisa menentang gadis itu. Selain karena dia adalah putri tunggal junjungan mereka, Intan Delima juga memiliki ilmu olah kanuragan yang cukup tinggi. Sementara itu Intan Delima terus memandangi para prajurit itu satu persatu dengan tatapan tajam.
"Cepat katakan, siapa nama pemuda itu? Dan apa maksudnya datang ke sini?" tanya Intan Delima dingin.
"Tapi, Gusti Ayu..., hamba..."
"Kau tidak perlu takut, juga yang lainnya. Kalau sampai Ayahanda Adipati tahu, aku yang akan membela kalian" janji Intan Delima.
Serentak enam orang prajurit tersebut saling berpandangan. Kemudian yang lima orang meng-anggukkan kepala pada kawannya yang ada di depan Intan Delima. Sejenak prajurit itu menarik napas dan menelan ludahnya untuk membasahi tenggorokan yang mendadak kering.
"Cepat katakan," desak Intan Delima tidak sabaran.
"Ampun, Gusti Ayu. Pemuda yang berbaju kulit harimau itu bernama Pendekar Pulau Neraka. Dia datang ke Kadipaten Jati Anom ini untuk mencari Gusti Adipati. Dia ingin membalas dendam, Gusti Ayu," kata prajurit itu menjelaskan dengan suara gemetaran.
"Dendam...?" Intan Delima mengerutkan keningnya.
"Dendam apa?"
"Hamba tidak tahu persis, Gusti. Yang tahu hanya Gusti Panglima dan Gusti Adipati sendiri."
"Apakah orang itu sangat tangguh dan berbahaya, sehingga harus memperkuat penjagaan dengan prajurit-prajurit pilihan kerajaan?"
"Hamba tidak tahu pasti, Gusti Ayu. Tapi yang hamba sempat dengar, Pendekar Pulau Neraka sangat kejam. Dia selalu membunuh setiap orang yang ditujunya, bahkan mereka yang mencoba melindungi juga dibunuh. Mungkin itulah sebabnya, kenapa Gusti Adipati Rakondah tidak ingin Gusti Ayu mengetahui persoalannya," kata prajurit itu sudah tenang suaranya
"Bagaimana tingkat kepandaiannya?"
"Tidak tahu, Gusti Ayu. Tapi kemarin dia melumpuhkan hamba dan teman hamba hanya dalam sekali gebrak saja. Dia juga bisa hilang, Gusti Ayu."
"Hm...," Intan Delima mengerutkan keningnya. Keterangan yang sedikit diperoleh itu sudah bisa membuat Intan Delima mengerti. Seseorang yang bisa menghilang dalam pandangan orang berilmu olah kanuragan rendah, sudah dapat dipastikan kalau orang itu memiliki tingkat kepandaian yang sulit diukur dan dicari tandingannya.
Dan tanpa berkata apa‐apa lagi, Intan Delima langsung berbalik dan melompat naik ke punggung kudanya. Gerakannya begitu ringan dan indah, pertanda ilmu meringankan tubuhnya sudah cukup tinggi. Gadis itu menggebah kudanya pelahan‐lahan meninggalkan perbatasan Utara Kadipaten Jati Anom. Dia kembali masuk ke kota. Sepanjang jalan keningnya terus berkerenyut memikirkan setiap kata yang barusan diucapkan oleh prajurit penjaga itu.
********************
TIGA
Keadaan di dalam kola Kadipaten Jati Anom benar-benar seperti mau perang. Suasana seperti itu tentu saja membuat penduduk jadi bertanya‐tanya dalam hati, namun tidak pernah menemukan jawaban yang tepat. Keadaan seperti itu sudah berjalan lima hari di dalam kota Kadipaten Jati Anom, namun belum berubah juga.
Sementara itu Intan Delima yang sedang mencari tahu orang yang bernama Pendekar Pulau Neraka, setiap hari terus mengelilingi kota kadipaten. Sebenarnya dia ingin menanyakan langsung peristiwa yang sebenarnya pada ayahnya, tapi setiap kali dia mau bicara, selalu tertunda dan dibatalkan. Intan Delima sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan keterangan apa‐apa dari ayahnya. Bisa‐bisa ayahnya malah memperketat pengawalan pada dirinya. Hal itulah yang selalu dihindarkan Intan Delima.
Sejak pagi sampai tengah hari, Intan Delima berada di atas punggung kudanya. Hari ini adalah hari yang ketiga bagi Intan Delima mencari orang yang berjuluk Pendekar Pulau Neraka. Sudah seluruh pelosok kota dia jelajahi, tapi sampai saat ini belum juga berhasil. Memang tidak mudah untuk mencari seseorang di tengah‐tengah begitu banyak orang. Apalagi belum pernah berjumpa sekali pun
"Huh Udara siang ini panas sekali..." keluh Intan Delima seraya menyeka keringat yang meleleh lehernya yang jenjang. Intan Delima kemudian menghentikan langkah kaki kudanya di pinggir sebuah sungai kecil yang berair jernih. Sebentar dia mengedarkan pandangannya berkeliling sebelum turun dari punggung kudanya. Tidak terlihat seorang pun di sekitar tempat itu, karena daerah ini memang sudah jauh masuk ke hutan perbatasan sebelah Selatan. Intan Delima tertegun sejenak begitu matanya memandang seonggok batu cadas yang berdiri menjulang dari gerumbul pepohonan.
Batu cadas itu seperti diukir oleh tangan ahli, berbentuk seperti seekor ular raksasa yang melingkar di tengah‐tengah hutan melibat sebatang pohon raksasa. Benar‐benar suatu pemandangan yang indah. Sayang tak seorang pun yang berani mendekatinya. Banyak legenda yang menceritakan tentang batu dan hutan itu. Tapi semuanya hanya berupa legenda yang diseram-seramkan. Belum ada bukti dan kebenarannya.
"Hutan Naga... Hhh... Mudah‐mudahan tidak ada apa‐apa. Aku hanya singgah sebentar," desah Intan Delima menenangkan diri.
Kemudian gadis itu menuntun kudanya dan mendekati sungai kecil berair jernih yang mengalir tenang dari hutan yang membukit itu. Lalu dia berlutut di tepian sungai itu dan dengan kedua tangannya dia menyiduk air dan membasuh mukanya. Terasa sejuk dan segar begitu air sungai menyentuh wajahnya yang putih kemerahan dan berkulit halus lembut bagai sutra.
Dan ketika tangannya hendak menciduk air lagi, mendadak gerakannya terhenti. Di permukaan air sungai yang bening terbayang seseorang sedang berdiri di seberang. Buru buru Intan Delima mengangkat kepalanya. Dan tampaklah seorang pemuda gagah sudah berdiri di seberang sungai. Pemuda itu berwajah tampan, namun terlihat garis‐garis kekerasannya. Kemudian dengan pelahan‐lahan, Intan Delima bangkit lari jongkoknya. Matanya terus menatap tajam memperhatikan laki-laki muda itu. Dari ujung kepala hingga ke ujung kaki dia perhatikan dengan seksama. Sejenak Intan Delima melangkah mundur dua tindak.
"Apakah dia orangnya? Ciri‐cirinya sama persis seperti yang dikatakan oleh prajurit penjaga perbatasan. Masih muda, gagah dan bajunya terbuat dari kulit harimau. Tapi.... Ah Rasanya tidak mungkin. Dia tidak kelihatan kejam dan jahat. Malah...," Intan Delima tidak melanjutkan kata‐kata yang terlintas di hatinya.
"Tuan siapa? Dan kenapa ada di tempat yang angker ini?" tanya Intan Delima menegur lebih dulu setelah menenangkan pikirannya.
"Kau sendiri, kenapa juga berada di sini?" pemuda itu balik bertanya.
"He... Aku yang bertanya padamu" bentak Intan Delima.
"Aku tidak pernah memberitahu siapa diriku lebih dahulu, sebelum orang lain memperkenalkan diri," kata pemuda itu tenang, namun nada suaranya terdengar tegas.
"Hm..., rupanya kau orang asing di sini, sehingga tidak tahu dengan siapa kau sedang berhadapan."
"Siapa pun kau, aku tidak peduli"
Intan Delima berkerenyut keningnya. Belum pernah ada seorang pun yang berani bicara kasar seperti itu padanya. Dia adalah seorang putri adipati yan sangat dihormati dan berilmu tinggi Dan semua orang selalu membungkuk hormat bila berhadapan dengannya, tapi pemuda ini. Sedikit pun tidak memandang sebelah mata padanya
"Sikapmu bisa menyulitkan dirimu sendiri...," gumam Intan Delima setengah mengancam.
"Aku memang terlahir penuh kesulitan, jadi apapun bentuknya kesulitan itu tidak pernah merubah sikapku," tegas jawaban pemuda gagah itu.
"Kurang ajar Kau benar‐benar tidak memandangku sebelah mata. Kau tahu siapa aku, heh?" bentak Intan Delima langsung mendidih darahnya.
"Aku tahu, kau adalah seorang gadis yang manja dan mudah marah. Tapi kau sangat cantik, dan...."
“Setan" merah padam seluruh wajah Intan Delima. Gadis itu tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Dan bagaikan seekor burung elang, dia menggenjot tubuhnya menyeberangi sungai. Kemudian tanpa banyak bicara lagi, gadis itu langsung mengirimkan pukulan mautnya yang bertenaga dalam cukup tinggi kearah pemuda itu.
"Eit" Pemuda itu hanya berkelit sedikit ke samhping, dan tangan kanannya memukul ke arah dada Intan Delima. Untung saja gadis itu cepat cepat menarik mundur tubuhnya, dan langsung melayangkan kakinya ke arah perut.
"Kau hebat, tapi sayang... uts" Pemuda itu segera menggeser kakinya dua tindak ke belakang, dan tendangan Intan Delima pun tidak sampai mengenai perutnya.
Tapi Intan Delima tidak lagi memberi kesempatan. Dia segera menyerang lagi dengan jurus‐jurus yang mengandung tenaga dalam tinggi, sehingga membuat pemuda itu hanya bisa berkelit dan berlompatan ke sana kemari menghindari serangan Intan Delima yang dahsyat dan mematikan itu. Pertarungan antara Intan Delima dan pemuda berbaju kulit harimau itu terus berlangsung semakin sengit. Dan keadaan di sekitar pertarungan itu sudah porak‐poranda seperti diamuk oleh puluhan ekor gajah. Namun sampai pertarungan berjalan lebih dari dua puluh jurus, belum sedikit pun pemuda itu melakukan serangan balasan.
"Kau telah mempermainkan aku, Pemuda Setan! Kau harus mati di tangan Intan Delima, putri tunggal Adipati Jati Anom" bentak Intan Delima, tanpa sadar dia telah membuka rahasia dirinya sendiri.
"Heh..." pemuda berbaju kulit harimau itu tampak terkejut. Buru‐buru dia melompat mundur dan menghindar dari pertarungan.
"Kenapa kau mundur? Takut...?" dengus Intan Delima sinis.
"Tidak kusangka, ternyata adipati pembunuh licik hanya mampu mengirim gadis bau kencur" geram pemuda itu sambil menatap tajam ke bola mata Intan Delima.
"Setan jelek! Kau telah menghina ayahku...” Intan Delima menggeram hebat.
"Bukan itu saja, aku sengaja datang ke kota ini untuk berurusan dengan pembunuh licik yang berkedok jadi adipati"
"Eh, jadi..." Intan Delima menggerinjang kaget.
"Kau.... Kau Pendekar Pulau Neraka...?"
"Ya, akulah Pendekar Pulau Neraka yang akan membuat perhitungan dengan Rakondah" tegas jawaban pemuda itu.
Sejenak Intan Delima memandangi pemuda yang memakai baju kulit harimau itu dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin, seorang pemuda yang usianya paling‐paling dua puluh lima tahun sudah begitu kondang namanya. Sampai‐sampai membuat tokoh-tokoh tua rimba persilatan gempar. Tak terkecuali Adipati Rakondah dan Panglima Bantaraji yang terkenal memiliki ilmu olah kanuragan yang tinggi. Itu baru mendengar namanya saja. belum berhadapan langsung dengan orangnya yang... Intan Delima sukar untuk mempercayai kalau pemuda tampan dan angkuh itu yang telah membuat gempar seluruh rimba persilatan.
"Kenapa wajahmu tiba tiba pucat, Gadis Manja? Apakah kau juga gentar seperti ayahmu?" ejek pemuda yang nama lengkapnya Bayu Hanggara itu.
"Jangan besar kepala dulu, Setan jelek! Kau sendiri tidak akan mampu untuk menandingiku, apalagi berhadapan dengan ayahku, yang sekarang dibantu oleh Panglima Bantaraji" balas Intan Delima menggertak.
"Bagus! Berarti tanganku akan lebih banyak lagi berlumur darah. Seluruh penduduk Kadipaten Jati Anom boleh berlindung di belakang tikus pengecut itu, biar aku lebih puas mengadakan pesta darah dan mayat" Bayu tersenyum lebar.
Bergidik juga hati Intan Delima mendengarnya. sungguh jauh berbeda kata‐kata yang mengalir lancar lengan wajah dan penampilannya. Rasanya semua orang juga tidak akan percaya kalau pemuda ini ternyata berhati kejam dan selalu berlumuran darah dalam hidupnya. Wajah dan bentuk tubuhnya tidak sedikit pun mencerminkan kekejaman. Tapi kata‐katanya barusan... Semua orang pasti bergidik mendengarnya
"Sebaiknya sekarang kau pulang saja, dan segera berlindung di bawah ketiak ayahmu. Katakan padanya kalau saat kematiannya sudah dekat" dengus Bayu.
"Heh..."
Baru saja Intan Delima ingin mengatakan sesua tiba-tiba saja pemuda itu sudah mencelat cepat. Begitu cepatnya, tahu‐tahu dia sudah lenyap dari pandangan mata. Tampak Intan Delima celingukan mencari‐cari. Meskipun gadis itu sudah terlatih dalam berbagai ilmu olah kanuragan, tapi dia benar‐benar tercengang melihat tingginya ilmu yang dimiliki oleh Pendekar Pulau Neraka. Sulit diukur, sampai di mana tingkat kepandaian Pendekar Pulau Neraka itu
"Hhh, rasanya tadi dia tidak melayaniku dengan sungguh‐sungguh. Apakah Ayah dan Paman Panglima akan mampu menandinginya Ilmunya benar‐benar luar biasa...," Intan Delima bergumam sendiri sambil menggeleng‐gelengkan kepala. Beberapa saat lamanya gadis itu masih berdiri saja di tempatnya. Dia tampak tertegun dengan kejadian yang barusan dialaminya.
********************
Sejak pertemuannya dengan Pendekar Pulau Neraka, Intan Delima jadi tampak lebih banyak melamun dan berdiam diri di dalam kamar. Kegagahan dan ketampanan pemuda itu telah menggores dalam di hatinya. Dia jadi sangsi akan kemampuan Ayah dan Pamannya. Mampukah mereka menandingi Pendekar Pulau Neraka? Sedangkan dia sendiri yang sempat bentrok belum mampu untuk mengukur, sampai di mana tingkat kepandaian pendekar muda itu.
Intan Delima juga memikirkan tentang peristiwa yang menyangkut ayahnya dengan Pendekar Pulau Neraka itu, hingga sampai menyulut api dendam yang begitu parah dan harus diselesaikan dengan pertumpahan darah. Beberapa saat kemudian, Intan Delima bangkit dari pembaringan, dan melangkah menuju jendela. Sudah setengah harian dia berada di dalam kamar itu, namun belum juga bisa menemukan jawaban dari pertanyaan‐pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Dan pertanyaan yang paling pokok, dendam apa yang telah bersemayam di dada Pendekar Pulau Neraka?
"Rasanya tidak mungkin kalau dia mencari Ayah tanpa sebab," gumam Intan Delima pelahan. Sejenak gadis itu mengedarkan pandangannya berkeliling melalui jendela kamarnya yang terbuka. Dan matanya langsung terpaku pada pohon beringin yang tumbuh dekat tembok. Tampak seseorang sedang berada di atas pohon itu sambil mengawasi. Dan Intan Delima semakin membeliakkan matanya begitu mengenali siapa orang itu. Maka tanpa pikir panjang lagi, dia langsung melompat ke luar. Dan begitu ujung dari kakinya menyentuh tanah, dia kembali melentingkan tubuhnya ke udara menuju pohon itu.
Slap
"Hey..."
Intan Delima terkejut begitu kakinya menjejak lahan, orang itu langsung melesat kabur. Dan dengan cepat Intan Delima kembali melenting dan mengejar orang yang mencurigakan itu. Tubuhnya bergerak ringan bagai kapas. Kejar‐kejaran pun terjadi. Sedikit pun Intan Delima tidak melepaskan pandangannya dari orang yang berlompatan jauh di depannya.
"Huh Ilmu meringankan tubuhnya sungguh hebat. Tidak mungkin aku bisa mengejarnya tanpa ilmu 'Sayiti Angin'," dengus Intan Delima. Gadis itu tampak semakin cepat berlari setelah dia mengerahkan ilmu 'Sayiti Angin'nya. Dan jarak dengan orang yang ada di depannya pun semakin pendek, dan akhirnya...
"Hiyaaa..."
Intan Delima segera melentingkan tubuhnya dan melompati kepala orang yang dikejarnya itu. Lalu dengan manis dia mendarat di depannya, dan langsung berbalik.
"Berhenti" bentak Intan Delima.
"Hebat... Ternyata kau mampu juga menyusulku," puji orang itu yang ternyata adalah seorang pemuda gagah yang memakai baju dari kulit harimau.
"Mau apa kau mengintai rumahku, Pendekar Pulau Neraka?" Intan Delima bertanya sinis.
Bayu hanya tersenyum saja. Lalu dia mengayunkan kakinya mendekati sebongkah batu hitam sebesar kerbau, dan dengan enak dia duduk di sana. Tampak bibirnya yang tipis masih menyunggingkan senyum. Sedangkan matanya tidak lepas dari wajah cantik yang tidak mencerminkan persahabatan itu. Intan Delima merasa jengah juga dipandangi sedemikian rupa. Buru‐buru dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Entah kenapa, mendadak saja dadanya jadi bergemuruh. Detak jantungnya juga semakin cepat bekerja. Tatapan mata Pendekar Pulau Neraka itu demikian menusuk, dan langsung menuju lubuk hatinya yang paling dalam. Tanpa disadari, wajahnya menyemburat merah dadu.
"Uh Tatapan matanya. , tapi... Ah, tidak Dia adalah musuh ayahku, aku tidak boleh ter... Eh Apa yang sedang kupikirkan? Gila" Intan Delima jadi berperang sendiri dengan batinnya. Gadis itu semakin tidak menentu saja perasaannya, saat dia melirik, dan langsung bertemu pandang dengan pemuda itu. Gadis itu terus merutuki dirinya sendiri. Secara jujur, dia memang mengakui kalau pemuda itu benar‐benar gagah dan tampan. Tatapan matanya mengandung daya tarik yang luar biasa. Intan Delima merasa tidak sanggup lagi untuk mengusir gemuruh yang semakin deras melanda dadanya.
Sebenarnya perasaan itu sudah ada sejak pertama kali mereka bertemu. Namun dia masih sanggup untuk mengenyahkan, tapi sekarang..., rasanya makin sulit untuk menghalau perasaan itu dari hatinya. Kini Intan Delima jadi tidak mengerti, kenapa tiba‐tiba saja dia mempunyai perasaan yang sulit untuk dimengerti? Suatu perasaan yang belum pernah dia alami sebelum nya. Apakah ini yang dinamakan.... Tidak Intan Delima buru‐buru membantah kata hatinya. Lama juga mereka hanya saling berdiam diri dengan hati dan perasaan yang berbicara masing‐masing. Intan Delima merasa, semakin lama dia berada di tempat itu, semakin gelisah perasaan hatinya.
Sementara Pendekar Pulau Neraka masih duduk diam dengan pandangan tidak berkedip pada wajah cantik yang sebentar‐sebentar berubah warnanya. Sementara Intan Delima sendiri semakin diliputi oleh suatu perasaan yang dia sendiri tidak tahu apa artinya.
"Mau ke mana kau?" tanya Bayu begitu melihat Intan Delima mau pergi.
Sejenak Intan Delima mengurungkan niatnya. Dan seperti ada satu kekuatan yang amat dahsyat, dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke bola mata Bayu. Seketika hatinya bergetar hebat begitu matanya bertemu pada satu titik. Dengan sekuat tenaga Intan Delima menguatkan diri dan berusaha untuk tetap terlihat tegar.
"Sebenarnya mau apa kau mengintai rumahku?" tanya Intan Delima setelah menarik napas dalam‐dalam.
"Siapa bilang aku mengintai rumahmu?" Bayu malah balik bertanya.
"He... Kau ada di pohon dekat rumah. Untuk apa lagi kalau bukan untuk mengintai?"
"O..., itu. Sengaja, aku memang sengaja memancingmu," tenang sekali jawaban Bayu.
"Memangnya aku ikan" rungut Intan Delima, geli juga dia.
"Bisa kita bicara baik‐baik? Sebenarnya di antara kita tidak terjadi apa‐apa. Aku memang mencari ayahmu, tapi aku tidak mau melibatkanmu. Kau tidak bersalah apa‐apa padaku," kata‐kata Bayu terdengar serius.
"Kau sepertinya menganggap ayahku adalah orang yang paling berdosa di dunia. Apa kau pikir dirimu paling suci?" ketus nada suara Intan Delima.
"Tidak ada satu pun manusia yang suci di dunia ini. Tapi aku tidak akan berhenti untuk menimbun dosa sebelum semua orang yang telah membunuh keluargaku dengan kejam, habis"
"Kau.... Jadi...," Intan Delima jadi tersekat.
"Seharusnya aku tidak mengatakan persoalan ini padamu. Tapi rasanya kau perlu tahu persoalan sebenarnya. Dan aku harap kau bisa memahaminya," Bayu Hanggara berusaha memberikan pengertian.
"Terus terang, aku juga ingin tahu persoalan yang sebenarnya. Katakan saja, apa sebabnya kau ingin membunuh ayahku?" Intan Delima berusaha keras menenangkan diri.
"Sebenarnya peristiwa itu sudah terjadi dua puluh lima tahun lalu, saat itu aku baru saja lahir. Ayahku memimpin sebuah padepokan yang bernama Padepokan Teratai Putih. Kemudian pada waktu pesta pemberian namaku, tiba‐tiba padepokan itu diserang oleh gerombolan yang digerakkan ibu tiriku. Ayahku tewas, juga ibu kandungku. Dan aku hidup sebatang kara sejak masih berumur beberapa hari. Kau bisa merasakan, betapa beratnya hidup yang harus kujalani di sebuah pulau yang terpencil hanya dengan seorang laki‐laki tua yang buntung dan buta. Apakah kau juga akan menyalahkan, jika aku membalas dendam? Seandainya hal itu terjadi padamu, apa yang akan kamu lakukan? Mencari pembunuh keluargamu, atau kamu hanya diam saja dan melupakan semuanya? Tentu saja tidak..." Bayu menggeleng‐gelengkan kepalanya beberapa kali.
Sementara Intan Delima jadi bungkam. Dia bisa memahami persoalan yang sedang dihadapi pemuda itu. Sebagai seorang anak, memang sudah menjadi kewajiban untuk membela dan mempertahankan nama baik orang tuanya. Namun Intan Delima belum dapat untuk memutuskan saat ini, siapa yang bersalah, dan siapa yang harus dibela? Dua kutub yang begitu berat seperti sedang menarik dirinya.
Sebagai orang yang baru selesai mengikuti gemblengan di sebuah padepokan, dia memang harus membela kebenaran. Sejak kecil ia sudah dididik untuk menjadi seorang pendekar wanita yang tangguh dan digdaya. Tapi sebagai seorang anak yang berbakti, rasanya sulit kalau hanya berdiam diri saja melihat ayahnya sedang menghadapi suatu persoalan berat yang mempertaruhkan nyawa. Intan Delima memang tidak menyalahkan Bayu yang memburu ayahnya, tapi dia juga tidak bisa melihat ayahnya mati begitu saja.
"Mungkin kau akan menganggapku mengada‐ada saja, Adik...."
"Intan. Namaku Intan Delima," potong Intan Delima cepat.
"Hm..., kau bisa memanggilku Bayu."
"Maaf, aku tidak bisa begitu saja percaya. Aku juga harus mendengar sendiri dari ayahku," kata Intan Delima tegas.
"Memang begitu seharusnya, dan aku harap kau tidak ikut campur setelah mengetahui persoalan yang sebenarnya. Tapi kalau kau juga ingin membela ayahmu, jangan anggap aku kejam. Aku sudah bersumpah, akan membunuh siapa saja yang membela orang yang telah membunuh keluargaku," Bayu memperingatkan.
"Mungkin kita akan berhadapan, Bayu. Entah sebagai kawan atau lawan..."
"Ternyata kau berjiwa seorang pendekar juga, Adik Intan," puji Bayu tulus.
"Terima kasih," Intan Delima tersipu. Sesaat mereka kembali terdiam. Sementara itu matahari semakin condong ke arah Barat. Sinarnya yang semula terik, kini sudah tidak terasa lagi. Kabut pun tampak telah mulai kelihatan turun. Beberapa saat kemudian, Intan Delima berpamitan ingin kembali, tapi Bayu buru‐buru mencegah.
"Ada apa lagi?" tanya Intan Delima.
"Katakan pada Pamanmu, Panglima Bantaraji. Agar jangan mencampuri urusan ini. Aku tidak mau orang jujur, baik dan ksatria seperti dia mati sia‐sia," pesan Bayu.
"Baiklah, tapi aku tidak janji," sahut Intan Delima
"Terima kasih, dan yang lebih penting, aku minta agar kau juga tidak ikut campur. Aku akan menghadapi secara ksatria dengan sedikit permainan."
"Apa yang akan kau lakukan?"
Bayu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum saja sembari bangkit dari duduknya. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Pendekar Pulau Neraka itu langsung melesat pergi. Begitu cepatnya, sehingga seperti menghilang saja. Sejenak Intan Delima menarik napas panjang, kemudian kakinya terayun menuju ke istana kadipaten kembal.
********************
EMPAT
Malam baru saja menjelang. Dan kegelapan segera menyelimuti seluruh bumi di sekitar Kadipaten Jati Anom. Tampak Intan Delima ke luar dari kamarnya, dan langsung menuju taman belakang. Langkahnya ringan dan anggun. Namun keningnya terlihat berkerut tipis, pertanda kalau dia tengah menghadapi satu persoalan yang sangat serius. Gadis itu berhenti melangkah begitu sampai di taman belakang. Di sana tampak Adipati Rakondah sedang duduk sendirian di kursi taman yang terbuat dari bambu yang diukir indah dan halus.
"Ayah...."
Adipati Rakondah segera mengangkat kepalanya. Dan langsung tersenyum begitu melihat anak gadisnya itu sudah berdiri di dekatnya. Sementara Intan Delima segera duduk di samping ayahnya.
"Ada apa? Kelihatannya serius sekali," tegur Adipati Rakondah seraya memperhatikan wajah putrinya.
"Ya...," desah Intan Delima.
"Katakan saja, Anakku."
"Ayah tidak akan marah?"
Adipati Rakondah tersenyum dan geleng-gelengkan kepalanya. Tangannya mengusap‐usap rambut Intan Delima dengan penuh kasih. "Kenapa Ayah harus marah? Katakan saja," lembut suara Adipati Rakondah.
Sejenak Intan Delima berpikir. Sepertinya dia berat untuk mengucapkannya. Beberapa kali dia hanya menarik napas panjang, dan menghembuskannya dengan kuat.
"Ayah tahu, kau pasti ingin menanyakan persoalan yang sedang Ayah hadapi, kan?" tebak Adipa Rakondah.
Intan Delima terperanjat. Sungguh dia tidak menyangka kalau ayahnya bisa menebak demikian tepat.
"Kau memang sudah besar, Anakku. Berapa usiamu sekarang?"
"Delapan belas, Ayah."
"Tidak kusangka, kau sudah begitu dewasa. Sudah pantas kau mengetahui persoalan dunia," Adipati Rakondah seperti bicara untuk dirinya sendiri.
"Ayah, apa sebenarnya yang sedang terjadi?" tanya Intan Delima langsung menjurus ke pokok persoalannya. Dia tidak ingin ayahnya mengingat‐ingat kembali masa‐masa lalu. Lebih‐lebih kalau sudah mengenang istrinya. Intan Delima jadi teringat dengan ibunya. Seorang wanita yang lembut dan selalu menerima apa adanya, sebagaimana kodratnya sebagai wanita. Masa‐masa yang indah dan tidak bisa terlupakan begitu saja. Namun sayang, rupanya Tuhan menghendaki lain. Ibunya meninggal saat Intan Delima baru menginjak usia tujuh tahun.
"Intan, persoalan yang sedang Ayah hadapi memang cukup serius. Suatu persoalan yang menyangkut hidup dan matiku...," Adipati Rakondah mulai bercerita.
Tampak Intan Delima mendengarkan dengan serius. Sedikit pun dia tidak menyelak kata‐kata ayahnya, meskipun laki‐laki setengah baya itu terdiam untuk beberapa saat.
"Aku memang bukan seorang Ayah yang baik. Masa laluku dilumuri dengan dosa dan darah. Ilmuku memang tangguh, dan sukar dicari tandingannya. Tapi aku salah menggunakannya. Aku selalu menuruti hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Hingga satu saat...," Adipati Rakondah kembali menghentikan kata‐katanya.
"Teruskan, Ayah," pinta Intan Delima tidak dapat lagi menahan diri.
"Dalam pengembaraanku, di sebuah desa aku bertemu dengan seorang wanita. Aku tahu, kalau wanita itu sudah bersuami, tapi kecantikannya membuatku mata gelap dan ingin memilikinya. Kemudian aku memaksakan kehendakku, dan hampir memperkosa wanita itu, tapi seorang pendekar berhasil menyelamatkannya. Dia mengalahkanku, Intan. Aku dendam dan berjanji akan menghancurkannya kelak. Kau tahu, Intan. Siapa nama pendekar itu? Dialah Pendekar Dewa Pedang, Ayah dari Bayu si Pendekar Pulau Neraka."
"Jadi, Ayah telah membunuhnya?" Intan Delima seperti tidak percaya.
"Bukan aku saja, Intan. Banyak tokoh‐tokoh lain yang ikut membunuh dan menghancurkan padepokan yang dipimpinnya. Dan semua itu juga berkat istri muda Dewa Pedang yang berhasil kami hasut dengan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya."
Intan Delima memandangi ayahnya tidak percaya. Sungguh dia sulit untuk percaya kalau ayahnya bisa sekejam itu. Semula dia sudah berharap bahwa ayahnya akan membantah semua cerita Pendekar Pulau Neraka, tapi yang didapatnya sekarang benar‐benar di luar dugaannya sama sekali. Ternyata masa lalu Adipati Rakondah begitu kelam dan penuh dengan dosa.
"Tidak... Tidak mungkin..." Intan Delima menggeleng‐gelengkan kepalanya seraya bangkit dari duduknya. Tatapan matanya mengandung ketidak-percayaan dengan apa yang barusan didengarnya. Gadis itu kemudian melangkah mundur pelahan‐lahan.
"Intan...," suara Adipati Rakondah tersekat di tenggorokannya.
"Tidak... Katakan padaku, Ayah. Kau tidak melakukan itu. Kau tidak tahu apa‐apa. Katakan, Ayah Katakan kalau kau telah berdusta" mendadak Intan Delima jadi histeris.
"Aku tidak dusta, Anakku. Memang pahit, tapi semua itu sudah berlalu, dan aku sudah melupakan semuanya, Intan. Kalaupun sekarang muncul putra Dewa Pedang, dan ingin membalas dendam, aku harus menghadapinya secara ksatria."
"Oh, tidak...," lirih suara Intan Delima.
"Intan..."
Namun Intan Delima sudah keburu berbalik, dan langsung berlari masuk ke dalam bangunan besar yang indah itu. Sedangkan Adipati Rakondah hanya bisa tertunduk lemas. Ada sedikit rasa penyesalan di hatinya, tapi hal itu memang harus dia lakukan. Cepat atau lambat, Intan Delima pasti tahu.
"Maafkan ayahmu, Intan...," desah Adipati Rakondah.
********************
Malam terus merayap semakin larut. Suasana di Istana Kadipaten Jati Anom semakin sepi. Hanya beberapa penjaga yang masih tampak terlihat di tempat‐tempat yang terlindung dari cahaya bulan dan lampu pelita. Dan di taman belakang, Adipati Rakondah juga masih terlihat duduk di kursi panjang yang terbuat dari bambu. Beberapa kali terdengar tarikan napasnya yang panjang dan dalam. Tampaknya dia masih merenungi sikap putrinya yang langsung berubah begitu dia menceritakan masa lalunya itu. Tapi, bagaimanapun juga dia tidak bisa menyalahkan Intan Delima kalau gadis itu sampai membencinya. Adipati Rakondah sadar, bahwa dirinya memang patut untuk dibenci. Memang penyesalan datangnya selalu belakangan.
Tepat ketika Adipati Rakondah bangkit dari duduknya, tiba‐tiba secercah cahaya keperakan melesat cepat bagai kilat mengarah dirinya. Dan dengan satu gerakan refleks, adipati itu memiringkan tubuhnya sedikit ke kanan. Dan cahaya keperakan itu lewat sedikit di depan dadanya. Namun belum juga dia sempat menarik tubuhnya kembali, mendadak satu cahaya keperakan kembali meluncur deras mengancam nyawanya.
"Uts"
Untung saja Adipati Rakondah kembali berhasil mengelak dengan menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Dan matanya yang tajam sempat menangkap berkelebatnya satu sosok bayangan yang melompati tembok benteng bagian belakang.
"Pengawal..." teriak Adipati Rakondah keras. Setelah berkata begitu, secepat kilat dia melentingkan tubuhnya mengejar sosok bayangan tadi. Dan pada saat yang sama, enam orang prajurit pengawal sudah berdatangan. Mereka sempat melihat bayangan Adipati Rakondah melompati tembok. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka langsung mengejar. Dari cara berlari dan melompati tembok, sudah dapat dilihat kalau enam orang prajurit itu memiliki ilmu olah kanuragan yang tidak rendah. Mereka adalah para prajurit pilihan yang sengaja didatangkan oleh Panglima Bantaraji dari kerajaan.
Sementara itu Adipati Rakondah masih tetap berdiri di balik tembok belakang. Dia telah kehilangan jejak. Bayangan yang dilihatnya tadi langsung hilang ditelan kegelapan malam. Tak lama kemudian enam orang pengawal kadipaten sudah berada di belakangnya.
"Cepat kalian cari di sekitar benteng" perintah Adipati Rakondah.
"Baik, Gusti," sahut enam orang prajurit pilihan itu serentak. Sedangkan Adipati Rakondah segera melentingkan tubuhnya melewati tembok. Dan pada saat kakinya menjejak tanah, di depannya sudah berdiri Panglima Bantaraji yang didampingi sekitar sepuluh orang prajurit dengan pedang terhunus.
"Ada apa?" tanya Panglima Bantaraji bernada cemas.
"Dia sempat datang, tapi langsung kabur," sahut Adipati Rakondah seraya melangkah.
Panglima Bantaraji pun segera memerintahkan pada sepuluh orang prajuritnya untuk mencari orang yang dilihat Adipati Kakondah. Kemudian dia melangkah mengikuti Adipati Jati Anom itu. Mereka lalu berhenti di depan sebuah pilar yang terbuat dari kayu jati bulat yang berukir. Adipati Rakondah segera menjulurkan tangannya dan mencabut dua buah logam berwarna keperakan yang menancap di pilar itu. Dua benda itu berbentuk bintang bersegi enam.
"Pendekar Pulau Neraka...," desis Panglima Bantaraji begitu melihat benda tersebut. Sejenak Adipati Rakondah berbalik dan menatap Panglima Bantaraji. Kemudian tatapannya beralih pada benda‐benda yang kini di dalam genggamannya.
"Berapa buah yang dia lontarkan?" tanya Panglima Bantaraji.
"Dua," sahut Adipati Rakondah pelahan.
"Hm..., itu berarti dua hari lagi," gumam Panglima Bantaraji.
Adipati Rakondah menatap tajam ke bola mata Panglima Bantaraji. Dia seperti meminta penjelasan.
"Pendekar Pulau Neraka selalu memberi tanda kedatangannya dengan mengirimkan bintang perak bersegi enam. Dan hari yang ditentukan berjumlah sama dengan bintang yang dilemparkan," Panglima Bantaraji seperti mengerti tatapan mata itu.
"Hm, jadi dia akan datang menantangku dua hari lagi?"
"Tidak."
"Maksudmu?”
"Mulai melakukan tekanan dan teror dua hari lagi.”
"Aku..., aku tidak mengerti maksudmu, Kakang?"
"Pendekar Pulau Neraka selalu membuat teror untuk melemahkan lawannya."
"Apa yang akan dia lakukan?"
"Entahlah, tapi kau harus lebih berhati‐hati dan jangan terpancing. Terutama sekali pada anakmu, aku merasa Intan Delima akan diperalat untuk melemahkan kepercayaanmu."
"Phuih... Cara apa itu? Pengecut" dengus Adipati Rakondah. Adipati Rakondah terus bersungut‐sungut sambil melangkah ke dalam istananya.
Sementara Panglima Bantaraji segera mengikutinya dari belakang. Dia yang selama ini selalu mengikuti sepak terjang Pendekar Pulau Neraka, sudah bisa mengetahui, kalau kejadian barusan adalah merupakan suatu tanda akan datangnya sebuah malapetaka di Kadipaten Jati Anom ini. Suatu tanda sebagai lambang kematian bagi adik kandungnya.
********************
Dua hari dilalui dengan cepat dan penuh ketegangan. Sudah berapa kali Panglima Bantaraji memperingatkan adiknya agar bisa mengendalikan diri dan jangan terpancing Tapi rasanya sulit bagi Adipati Rakondah, apalagi sekarang sikap Intan Delima padanya jadi lain. Gadis itu tidak mau lagi berbicara padanya. Hatinya sudah terluka menghadapi kenyataan pahit ini. Suatu kenyataan yang tidak diduganya sama sekali. Laki‐laki yang sangat dihormati dan dianggap yang terbaik selama ini ternyata mempunyai masa lalu yang sangat buruk. Masa lalu yang memalukan untuk dikenang. Intan Delima benar‐benar kecewa. Luka yang menggores hatinya begitu dalam, rasanya sulit untuk disembuhkan lagi.
Hari ini adalah hari ketiga setelah terlontarnya bintang sebagai tanda dimulainya suasana berselimut maut. Dan selama tiga hari ini juga Intan Delima terus mengurung diri di dalam kamarnya. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk. Pintu kamar itu selalu tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Tapi sampai tiga hari dilalui, belum ada tanda‐tanda kalau Pendekar Pulau Neraka mulai melakukan tekanan.
"Intan..." Adipati Rakondah memanggil sambil mengetuk pintu kamar anaknya. Tidak ada sahutan dari dalam. Adipati Rakondah terus mengetuk pintu sambil memanggil‐manggil. Mendadak perasaannya jadi tidak enak, karena dari dalam kamar anaknya itu tidak terdengar suara sedikit pun. Maka tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung mendobrak pintu kamar itu. Seketika tubuhnya melesat masuk ke kamar bersamaan dengan hancurnya daun pintu.
"Intan..." seru Adipati Rakondah mulai cemas. Tak ada seorang pun di dalam kamar itu. Buru‐buru Adipati Rakondah berlari ke arah jendela yang terbuka lebar. Dan kedua matanya langsung membeliak begitu mendapati sebuah bintang berwarna keperakan, dan bersegi enam tertancap pada dinding dekat jendela.
"Intan..." teriak Adipati Rakondah panik. Tentu saja suara gaduh itu mengundang beberapa prajurit berdatangan. Begitu pula dengan Panglima Bantaraji, dia langsung berlari masuk ke kamar.
"Ada apa...?" tanya Panglima Bantaraji terkejut.
Adipati Rakondah tidak menjawab. Dia hanya terduduk lemas di tepi tempat tidur yang berantakan. Matanya beredar berkeliling. Keadaan kamar itu seperti baru saja terjadi pertarungan. Tampak pecahan guci berserakan di lantai. Dan meja kursi juga berantakan. Panglima Bantaraji segera mencabut senjata yang berbentuk bintang bersegi enam berwarna perak dari dinding. Sejenak dia mengamati benda yang kini berada di tangannya itu, lalu tatapannya beralih pada Adipati Rakondah yang masih terduduk lemas di tepi pembaringan.
"Cepat geledah seluruh pelosok kadipaten Tanyai semua orang" perintah Panglima Bantaraji.
Dan tanpa menunggu perintah dua kali, para prajurit yang berada di kamar itu langsung pergi melaksanakan perintah itu. Sedangkan Panglima Bantaraji menghampiri adiknya dan ikut duduk di sampingnya. Tidak sedikit pun Adipati Rakondah mengangkat kepalanya Berbagai macam perasaan kini tengah berkecamuk di dalam dadanya.
"Aku sudah peringatkan padamu, Adik Rakondah. Sekarang semua sudah terjadi, dan kita hanya bisa berharap agar Intan Delima bisa selamat dari maut," kata Panglima Bantaraji pelan.
"Ini semua memang salahku, Kakang. Seharusnya aku tidak menceritakan semuanya...," keluh Adipati Rakondah lirih.
Seketika Panglima Bantaraji menatap tajam pada adiknya itu. Dia sepertinya tidak percaya dengan pendengarannya barusan. "Adik Rakondah, apa yang kau katakan tadi?"
"Maafkan aku, Kakang. Aku terpaksa menceritakan semuanya pada Intan. Dan aku tidak menyangka kalau akan begini jadinya."
Panglima Bantaraji bangkit dari duduknya. Kemudian dia melangkah pelan‐pelan dengan kepala tertunduk. Dan ketika sampai di ambang pintu, dia berbalik. Tepat pada saat itu Adipati Rakondah tengah menatapnya. Sejenak mereka saling berpandangan.
"Jadi itulah sebabnya Intan Delima mengurung diri di kamar, Adik Rakondah?" Panglima Bantaraji ingin penjelasan.
"Ya," sahut Adipati Rakondah mendesah.
"Hhh..." Panglima Bantaraji menarik napas panjang. Kemudian dia berbalik lagi.
"Kakang...," pelan suara Adipati Rakondah.
"Ada apa lagi?" Panglima Bantaraji tidak berbalik lagi.
"Terus terang, aku tidak tahu lagi, apa yang harus kulakukan...?" keluh Adipati Rakondah.
Panglima Bantaraji tidak menjawab. Dia terus mengayunkan kakinya meninggalkan kamar itu. Dia sendiri tidak tahu, apa yang harus dilakukan. Sampai saat ini, tindakan Pendekar Pulau Neraka memang sulit untuk ditebak dan dimengerti. Tindakannya sangat ganjil Melakukan tekanan, membuat lawan jadi lemah mentalnya dan kehilangan kepercayaan diri. Kemudian muncul dengan didahului suatu tanda yang aneh dan mengejutkan.
Panglima Bantaraji benar‐benar merasakan suatu suasana yang membingungkan. Sepertinya dia tengah berada pada satu lingkungan yang terkepung oleh makhluk‐makhluk haus darah. Kini keadaannya benar‐ benar seperti di dalam neraka. Apa pun yang dilakukan, sepertinya Pendekar Pulau Neraka bisa mengetahui, dan menciptakan neraka baru yang lebih mengerikan dan menyakitkan.
********************
LIMA
Benarkah Intan Delima telah diculik oleh Pendekar Pulau Neraka? Sebenarnya, Intan Delima memang sengaja meninggalkan istana kadipaten Dia pergi dengan membawa kehancuran dan rasa kecewa yang sangat dalam di hatinya. Kepergian gadis itu diketahui oleh Bayu si Pendekar Pulau Neraka, yang selalu mengamati suasana di sekitar Istana Kadipaten Jati Anom. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan itu dengan menyusup ke dalam kamar gadis itu, dan membuatnya seolah‐olah seperti telah terjadi pertarungan dengan meninggalkan sebuah bintang keperakan bersegi enam.
Lalu, ke mana sebenarnya Intan Delima pergi? Tak ada seorang pun yang tahu, kecuali Bayu. Sekarang Intan Delima berada di sebuah goa kecil di Lereng Gunung Panjaran. Setiap waktu dihabiskannya di dalam goa. Dan dia baru ke luar dari dalam goa kalau merasakan perutnya lapar. Rasa kecewa yang dalam terhadap ayahnya telah membuat gadis itu seperti ingin menghilang dari dunia ramai.
Pagi itu Intan Delima baru saja ke luar dari mulut goa tempatnya mengasingkan diri. Langkah kakinya langsung terhenti ketika tiba‐tiba di depannya sudah berdiri seorang laki‐laki muda berwajah tampan dengan tubuh tinggi tegap. Laki‐laki itu mengenakan baju dari kulit harimau. Kedua tangannya melipat di depan dada.
"Mau apa kau datang ke sini?" ketus suara Intan Delima.
Pemuda gagah itu hanya tersenyum saja, kemudian dia melangkah mendekati. Dan dengan enak dia lalu duduk di atas akar pohon yang menyembul dari dalam tanah. Sedangkan Intan Delima hanya memandanginya saja dengan wajah tidak menunjukkan persahabatan.
"Terus terang, aku heran denganmu. Keadaan Kadipaten Jati Anom kini sedang kacau, kau malah enak-enakan menyendiri di sini," kata pemuda itu kalem. Sepertinya dia tidak tahu‐menahu dengan suasana yang ditimbulkannya.
"Itu semua gara‐gara kau" bentak Intan Delima.
"Tidak juga, kalau ayahmu tidak membuat persoalan lebih dulu," pemuda itu mengelak.
"Jangan bersilat lidah. Katakan saja terus terang, apa maumu datang ke sini?"
"Hanya ingin melihatmu."
"Huh" Intan Delima mencibirkan bibirnya seraya memalingkan wajahnya. Namun dia merasakan wajahnya jadi panas. Kata-kata yang meluncur dari mulut pemuda gagah itu membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Intan Delima tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia sudah terpikat sejak pertemuannya yang pertama kali di Hutan Naga. Rasa simpatinya semakin menebal setelah mengetahui persoalan dan kemelut hidup pemuda yang bernama Bayu itu. Tapi kalau mengingat persoalan yang sedang terjadi antara Bayu dengan Adipati Rakondah, Intan Delima seperti terjepit pada dua sisi yang menyulitkan.
Di satu pihak, dia begitu menyayangi dan mencintai ayahnya. Meskipun hatinya sempat terluka dan kecewa. Dan di pihak lain, hatinya sudah terukir suatu kata‐kata yang sulit untuk dihapuskan kembali. Kini Intan Delima tidak tahu lagi, apa yang harus dilakukan. Rasanya tidak mungkin lagi dia untuk membujuk Bayu agar memadamkan api dendamnya. Dia bisa mengerti dan memahami dendam yang sudah bersemayam kuat di dalam dada pemuda itu Tapi dia juga tidak mungkin berdiam diri melihat nyawa ayahnya terancam oleh Pendekar Pulau Neraka ini.
"Adik Intan...," lembut suara Bayu.
"He Kau..., kau memanggilku adik...?" Intan Delima terperangah setengah tidak percaya. Dia sampai berbalik dan menatap tajam ke bola mata pemuda itu, namun cepat‐cepat dialihkan pandangannya ke arah lain.
"Kenapa? Apakah aku tidak pantas menyebutmu adik?"
"Tidak Eh..., boleh..., boleh," Intan Delima jadi gugup.
"Antara aku dan ayahmu memang saling bermusuhan, tapi aku tidak mau kau ikut memusuhiku. Di dunia ini aku hidup sendiri, tanpa teman dan kerabat. Semua orang memandangku dengan benci, sepertinya kehadiranku hanya akan menimbulkan malapetaka saja. Yah..., mungkin memang sudah takdirku harus hidup sendiri tanpa seorang pun yang mau menjadi teman bicara," Bayu mengeluh.
Kata‐kata Bayu yang bernada keluhan itu membuat hati Intan Delima tergerak. Dia kemudian kembali menatap dalam ke bola mata pemuda itu, seakan‐akan ingin mencari kebenaran pada sinar matanya. Dan gadis itu sedikit tersentak begitu melihat sepasang bola mata itu berkaca‐kaca. Dan tanpa sadar, dia segera menghampiri dan berlutut di depannya.
"Kau benar‐benar cantik, Adik Intan. Aku memang seorang yang tidak tahu diri, terlalu banyak berharap untuk bisa berteman denganmu. Terlalu jauh perbedaan yang ada, terlalu dalam jurang pemisah di antara kita. Maaf, tidak seharusnya aku berharap bisa berteman denganmu," pelan dan lirih suara Bayu.
Intan Delima tidak lagi bisa berkata‐kata. Sebenarnya banyak yang ingin dia ucapkan, tapi tenggorokannya serasa tersekat, sulit untuk mengucapkan satu kata pun. Hanya sinar matanya saja yang memberikan banyak perasaan yang tak bisa dilukiskan. Pelahan‐lahan Bayu bangkit seraya mendesah panjang. Kemudian kakinya terayun pelan meninggalkan gadis itu. Sementara Intan Delima juga ikut berdiri. Rasanya dia ingin ikut melangkah, tapi kakinya seperti terpaku, sulit untuk digerakkan.
"Kakang...," ke luar satu kata dari bibirnya yang bergetar.
Bayu segera menghentikan langkahnya. Dia membalikkan tubuhnya dan menghadap pada gadis itu. Sesaat mereka hanya berdiam diri saling tatap. Namun teriihat kepala pemuda itu menggeleng‐geleng lemah, dan tanpa berkata apa‐apa lagi, tubuhnya langsung melenting cepat dan lenyap ditelan oleh lebatnya pepohonan di Lereng Gunung Panjaran itu.
"Oh.... Kasihan kau, Kakang. Ternyata nasibmu lebih buruk dariku," desah Intan Delima lirih. Gadis itu tetap berdiri terpaku dengan pandangan mata lurus ke arah kepergian Pendekar Pulau Neraka. Lama juga Intan Delima berdiri di depan goa. Hingga sampai matahari berada tepat di atas kepala, baru dia melangkah meninggalkan tempat itu. Perutnya sudah berkeruyuk minta diisi. Kemudian Intan Delima berjalan gontai menembus kelebatan hutan di Lereng Gunung Panjaran.
********************
Sementara itu suasana di Kadipaten Jati Anom semakin tidak menentu. Di seluruh pelosok kota, penjagaan semakin ditingkatkan. Namun sampai saat ini tidak ada yang bisa mengetahui tempat persembunyian Pendekar Pulau Neraka. Dan keadaan semakin bertambah parah, ketika satu persatu para prajurit yang didatangkan dari kerajaan, tewas dengan dada tertembus senjata yang berbentuk bintang perak bersegi enam.
Hal itu tentu saja makin membuat Adipati Rakondah dan Panglima Bantaraji kalang‐kabut. Lebih‐lebih Adipati Rakondah, kepercayaan pada dirinya sendiri semakin goyah. Emosinya sudah tidak terkontrol lagi. Perang urat syaraf yang ditimbulkan oleh sepak‐terjang Pendekar Pulau Neraka benar‐benar telah membuat Adipati Rakondah dan Panglima Bantaraji seperti kehilangan diri.
"Gila Ini benar benar gila" geram Adipati Rakondah ketika pagi itu dia mendapat laporan bahwa seluruh kuda‐kuda di istal hilang. Adipati Rakondah yang selalu didampingi kakaknya, Panglima Bantaraji segera melihat istal yang sudah kosong tanpa seekor kuda pun di dalamnya. Dia langsung menggerutu sendiri, mencaci‐maki tidak karuan. Perang urat syaraf yang dilontarkan Pendekar Pulau Neraka benar‐benar menyakitkan. Setegar apa pun jiwa seseorang, pasti akan rapuh juga jika terus-menerus dilanda teror tanpa mampu untuk berbuat sesuatu.
"Kendalikan dirimu, Adik Rakondah," kata Panglima Bantaraji berusaha menenangkan, padahal di dalam dadanya sendiri juga bergemuruh.
"Bagaimana aku bisa tenang, Kakang. Dia sudah mengambil anakku, kemudian disusul dengan tewasnya sebagian prajurit‐prajurit kita Sedangkan apa yang sudah kita lakukan? Diam... Diam terus" Adipati Rakondah jadi semakin berang.
"Lalu apa yang akan kau lakukan? Mengobrak‐abrik seluruh kadipaten?" Panglima Bantaraji juga jadi gusar.
"Aku akan mencari sendiri bajingan itu"
"Rakondah..."
Peringatan Panglima Bantaraji tidak digubris lagi. Adipati Rakondah bergegas meninggalkan istal yang sudah kosong itu. Hatinya benar‐benar panas, tidak tahan lagi menghadapi tekanan yang datang secara beruntun. Rasanya tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, selain mencari pendekar itu dan menantangnya untuk bertarung sampai salah satu di antara mereka ada yang tewas
"Rakondah" Panglima Bantaraji menyentakkan bahu adiknya hingga adipati itu berbalik dan menghadangnya. Sejenak Adipati Rakondah menatap tajam pada kakaknya itu. Kini mereka tidak peduli lagi dengan jabatan yang disandang masing‐masing. Mereka terus saling tatap dengan tajam, seperti dua orang musuh yang sudah siap mengadu nyawa.
"Bagaimanapun juga kau harus bisa mengendalikan diri, Adik Rakondah. Aku sudah menyebarkan puluhan telik sandi terpercaya untuk menemukan tempat persembunyian Pendekar Pulau Neraka," kata Panglima Bantaraji terus berusaha menenangkan adiknya.
"Percuma, Kakang. Lebih baik segera kau tarik kembali para prajuritmu untuk pulang. Aku tidak mau lagi lebih banyak korban berjatuhan," sahut Adipati Rakondah bernada putus asa.
"Kau sepertinya tidak mempercayai kemampuanku, Rakondah."
"Maaf, Kakang. Pendekar itu hanya menginginkan diriku. Rasanya sia‐sia saja meskipun kau datangkan seluruh prajurit pilihan kerajaan. Dia sangat licik dan punya siasat yang kejam. Maaf, aku harus segera mengambil tindakan sebelum terlambat," tegas kata‐kata Adipati Rakondah.
"Apa yang akan kau lakukan?" tanya Panglima Bantaraji.
"Mengosongkan istana."
"Gila Apa kau mau bunuh diri, Rakondah? Pendekar Pulau Neraka sukar dicari tandingannya. Kita berdua saja belum tentu mampu menghadapinya' Panglima Bantaraji terkejut setengah mati.
"Tapi itu lebih baik. Kakang. Daripada semakin banyak orang yang tidak berdosa tewas di tangannya. Aku akan semakin merasa berdosa jika membiarkan orang‐orang tidak berdosa ikut tewas karena membela ku. "
"Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, Rakondah. Ingat, masih ada aku, masih banyak sahabat-sahabat kita yang memiliki ilmu tinggi. Kalau kita mau menghubungi, mereka pasti mau membantumu," kata Panglima Bantaraji.
Adipati Rakondah segera menggeleng‐gelengkan kepalanya. "Sudah terlambat, Kakang. Rasanya tidak ada lagi yang harus jadi korban. Kini semuanya benar‐benar sudah terlambat. Hidup pun tidak ada gunanya lagi bagiku. Terima kasih, kau telah berkorban banyak untuk membelaku, Kakang. Sebaiknya kau segera kembali saja ke kerajaan, dan bawa semua prajuritmu," kata Adipati Rakondah tetap pada pendiriannya.
"Adik Rakondah..."
"Maaf, aku tidak bisa lagi menerima bantuanmu. terima kasih, Kakang," tegas kata‐kata Adipati Rakondah.
Panglima Bantaraji tidak bisa lagi menahan kepergian adiknya. Dia sudah tahu betul akan watak adiknya itu. Keras dan teguh pada pendiriannya Ada rasa ke-kaguman pada hatinya melihat sikap adiknya yang berjiwa ksatria itu. Benar benar sudah jauh berbeda lengan masa‐masa lalunya. Kini Panglima Bantaraji hanya bisa memandangi Adipati Rakondah yang melangkah gontai menuju istana.
"Kasihan kau, Adikku," desah Panglima Bantaraji pelan. "Kau harus menanggung semua akibat perbuatanmu sendiri."
Dan dengan langkah pelan, Panglima Bantaraji juga meninggalkan halaman depan istal yang sepi itu. Tampak pengurus kuda tengah duduk melamun di samping pintu istal Kini tidak ada lagi yang bisa dia kerjakan. Semua kuda kuda telah lenyap semalam, tanpa sisa satu ekor pun. Suatu kejadian yang aneh, dan baru pertama kali terjadi. Semua orang seperti kena sirep, tidur lelap dan tidak mendengar suara apa pun.
********************
Meskipun sudah berkali‐kali disuruh pulang, tapi Panglima Bantaraji tetap tidak mau meninggalkan Kadipaten Jati Anom. Bagaimanapun juga, dia tidak tega untuk meninggalkan adik kandung satu‐satunya menghadapi maut seorang diri. Meskipun sudah jelas bahwa adiknya yang bersalah. Adipati Rakondah sendiri kini sudah mengosongkan istananya. Semua pelayan dan abdi setianya sudah disuruh meninggalkan istana. Bahkan para pejabat kadipaten tidak diperbolehkan datang lagi. Tidak ada seorang pun yang berani membantah, mereka seperti sudah mengerti dengan semua persoalan yang sedang dihadapi junjungannya itu.
Sekarang yang masih tinggal di lingkungan Istana Kadipaten, hanya Adipati Rakondah sendiri dengan Panglima Bantaraji dan dua puluh orang prajurit pilihan dari kerajaan. Suasana di istana kadipaten benar benar sudah sunyi. Suatu kesunyian yang mencekam dan berselimut maut. Sejak sore, Adipati Rakondah duduk merenung diberanda depan istananya. Di sampingnya duduk pula Panglima Bantaraji. Sementara empat orang prajurit yang bersenjata pedang di pinggang berdiri di belakang mereka. Tak ada yang bicara sedikit pun sejak senja tadi. Masing‐masing sibuk dengan pikirannya. Sedangkan di bagian halaman depan, tampak enam belas prajurit berjaga‐jaga dengan senjata yang sudah terhunus di tangan.
"Huh Seperti sedang menunggu mati saja" dengus Panglima Bantaraji mengeluh. Sejenak Adipati Rakondah menoleh dan sayu pada kakaknya.
"Sudah dua malam kita duduk di sini. Mau sampai kapan lagi begini terus...?" lagi‐lagi Panglima Bantaraji mengeluh.
"Jangan mengeluh terus, Kakang. Aku sudah memintamu untuk meninggalkan Kadipaten Jati Anom," rungut Adipati Rakondah
"Meninggalkanmu sendirian dicincang”
"Kalaupun aku harus mati, ini adalah kesempatanku untuk mati secara ksatria, Kakang."
Kini Panglima Bantaraji menatap tajam pada adiknya. Selama ini dia belum pernah mendengar kata‐kata seperti itu ke luar dari mulut adiknya itu. Dia seperti tidak percaya, bahwa adiknya yang selama ini berada di jalan hitam sudah benar‐benar berubah. Apakah Adipati Rakondah sudah putus asa? Atau memang dia sudah bertobat dan ingin menebus segala dosa‐dosanya di masa lalu? Tidak ada seorang pun yang tahu.
Sementara malam terus merayap semakin larut. Kedua bersaudara itu terus berbincang‐bincang mengenang kembali masa masa lalu. Di mana mereka terkenal sebagai tokoh yang sangat disegani di rimba persilatan, dengan julukan Sepasang Gagak Hitam dari Utara. Dan meskipun mereka selalu bersama‐sama mengarungi keganasan rimba persilatan, namun watak dan tindakan mereka selalu bertentangan. Yang satu selalu mementingkan orang lain dan membela kebenaran, sedangkan satunya lagi selalu bertindak sangat bertentangan, namun anehnya mereka bisa bersatu seiring sejalan.
Hal itu tentu saja membuat tokoh-tokoh sakti rimba persilatan jadi bingung menentukan mereka berada dalam golongan mana. Satu hari mereka memberantas kejahatan bersama-sama, tapi pada hari berikutnya mereka bisa bentrok dengan pendekar golongan putih. Mereka berdua memang bisa saling bantu dan mendukung satu sama lainnya, tapi untuk kepentingan pribadi tidak mau saling mencampuri.
"Kakang, awas..." tiba‐tiba Adipati Rakondah berseru nyaring sambil melompat dan menubruk kakaknya.
Dan pada saat yang bersamaan, secercah cahaya keperakan meluncur deras bagai kilat. Kakak beradik itu jatuh bergulingan, dan sinar keperakan itu langsung menghantam seorang prajurit yang tengah berdiri tepat di belakang Panglima Bantaraji. Jeritan melengking terdengar disusul dengan ambruknya prajurit itu. Panglima Bantaraji bergegas melompat dan menghampiri prajurit yang malang itu. Dan kemudian dia segera mencabut benda berbentuk bintang berwarna keperakan dari dada prajurit itu.
Wut, wut, wut...
Belum lagi rasa terkejut mereka hilang, tiba‐tiba tiga buah benda bercahaya keperakan kembali meluncur dan menancap berjajar pada daun pintu. Seketika Adipati Rakondah dan Paglima Bantaraji melompat begitu mereka melihat berkelebatnya sebuah bayangan melompati tembok.
"Hey... Berhenti..." seru Adipati Rakondah lantang. Namun begitu kakinya hinggap di atas tembok benteng yang tinggi dan tebal, bayangan itu sudah lenyap tak berbekas. Sejenak Adipati Rakondah mengedarkan pandangannya berkeliling, menembus kegelapan malam. Sedangkan Panglima Bantaraji tetap menunggu di bawah.
"Huh... Sial..." rutuk Adipati Rakondah menggeram seraya meluncur ke bawah. Dan dengan manis sekali kakinya segera hinggap di tanah, tepat di depan Panglima Bantaraji. Tampak di beranda depan, dua orang prajurit tengah menggotong seorang prajurit yang tewas tertembus bintang perak bersegi enam. Sesaat Adipati Rakondah dan Panglima Bantaraji saling berpandangan.
"Apa maksudnya dia mengirimkan senjata itu, Kakang?" tanya Adipati Rakondah tetap memandang ke bola mata kakaknya.
"Hari penentuan," sahut Panglima Bantaraji setengah mendesah.
"Aku tidak mengerti maksudmu, Kakang?"
"Berapa yang dia lemparkan?" Panglima Bantaraji malah balik bertanya.
"Empat, dan satu berhasil menewaskan seorang prajuritmu," sahut Adipati Rakondah.
"Berarti tiga buah, dan itu tandanya tiga hari lagi dia akan datang menantangmu. Satu lontaran yang pertama tadi merupakan peringatan," Panglima Bantaraji menjelaskan.
Adipati Rakondah segera terdiam mendengar penjelasan itu. Dan dengan kepala tertunduk lesu, dia melangkah kembali ke beranda depan istananya. Sementara Panglima Bantaraji segera mengatur sisa para prajuritnya untuk tetap berjaga‐jaga dari segala mungkinan yang ada.
********************
Tanpa seorang pun yang mengetahui, sesosok tubuh berada di kerimbunan pepohonan yang tidak jauh dari benteng bagian Barat Istana Kadipaten Jati Anom. Sepasang matanya yang bening bercahaya, menatap tajam mengawasi sekitar bangunan besar dan megah itu. Dan tatapannya langsung terpaku pada seorang laki-laki setengah baya yang mengenakan pakaian indah seorang panglima. Sosok tubuh itu terus mengamati setiap gerak‐gerik Panglima Bantaraji. Tampak Panglima Bantaraji melangkah menuju ke bagian belakang bangunan megah itu. Tak ada seorang prajurit pun yang terlihat di sana. Semua prajurit dikhususkan untuk menjaga bagian depan.
Beberapa saat kemudian, sosok tubuh itu melenting ringan ke bawah tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Lalu kembali dia melentingkan tubuhnya, dan hinggap di atas atap. Dan hanya dengan menginjakkan sedikit ujung jari kakinya, sosok tubuh itu meluruk turun dan langsung mendarat di depan Panglima Bantaraji
"Heh" Panglima Bantaraji terkejut, langsung melompat mundur dua tindak. Sosok tubuh itu ternyata seorang pemuda gagah berwajah tampan. Badannya yang tegap berisi, teringkus baju dari kulit harimau. Tangannya tampak melipat di depan dada. Tampak di pergelangan tangan kanannya menempel sebuah lempengan logam yang berwarna keperakan. Benda itu berkilauan tertimpa oleh cahaya bulan yang mengintip dari balik awan hitam. Tatapan matanya tajam menembus langsung ke bola mata Panglima Bantaraji.
"Pendekar Pulau Neraka ," desis Panglima Bantaraji.
"Kau pasti Panglima Bantaraji," dingin dan datar suara pemuda gagah itu yang ternyata adalah Bayu si Pendekar Pulau Neraka.
"Benar! Akulah Panglima Bantaraji" sahut Panglima Bantaraji sudah bisa mengendalikan dirinya dengan tenang.
"Di antara kita tidak pernah punya persoalan. Maka aku minta padamu, agar jangan mencampuri urusanku, Panglima Bantaraji," tegas kata‐kata Bayu.
"Aku sudah tahu persoalan yang kau bawa ke sini, tapi kau juga harus tahu, bahwa antara aku dan Adipati Rakondah tidak dapat dipisahkan. Kami adalah dua bersaudara yang berjuluk Sepasang Gagak Hitam dari Utara" tegas juga jawaban Panglima Bantaraji.
"Hm..., mereka memang benar. Aku tidak mungkin bisa memberi peringatan padamu," gumam Bayu.
"Apa yang kau katakan, Pendekar Pulau Neraka?"
"Ketahuilah, Panglima Bantaraji. Sebagian prajurit Kadipaten Jati Anom ini masih sayang pada nyawanya. Dan mereka mau menuruti kehendakmu. Tapi prajurit-prajurit yang kau bawa itu sikapnya tidak jauh berbeda denganmu. Keras kepala. Maaf aku harus menyingkirkan semua yang menjadi penghalangku"
"Jadi...?" Panglima Bantaraji terperangah.
"Tidak satu pun penduduk maupun prajurit kadipaten yang berpihak lagi pada Adipati Rakondah. Mereka semua sudah tahu, siapa sebenarnya manusia iblis yang berkedok adipati itu"
"Pengecut! Kau hasut mereka untuk memberontak, heh" geram Panglima Bantaraji.
"Mereka manusia‐manusia yang masih mempunyai pikiran wajar, Panglima. Mereka tidak akan memberontak, mereka telah menyerahkan segalanya padaku. Dan mereka menyesal telah mengabdi pada manusia iblis itu. Nah, Panglima Bantaraji. Kalau kau masih punya otak waras, ikuti jejak mereka. Sedangkan anaknya sendiri tidak mau lagi bertemu dia"
"Keparat... Tidak kusangka, nama Pendekar Pulau Neraka yang begitu terkenal ternyata seorang manusia pengecut dan licik"
"Tidak jauh berbeda dengan cara kalian memperoleh jabatan, Panglima. Kau dan adikmu juga menggunakan akal licik dan pengecut. Menjilat Gusti Prabu, dan menyingkirkan orang‐orang yang tidak menyukai kalian dengan cara kotor dan keji"
"Heh..." Panglima Bantaraji tersentak kaget. Benar-benar di luar dugaan, kalau pemuda gagah yang kondang namanya ini mengetahui seluruhnya tentang kehidupan masa lalu diri mereka. Kini Panglima Bantaraji benar‐benar dibuat tidak berkutik lagi. Kedoknya sudah terbuka lebar di hadapan pemuda ini.
"Panglima, sekali lagi aku memintamu untuk tidak ikut campur, karena aku sudah tahu siapa kau. Jika kau mau menuruti kata‐kataku, hidupmu akan bisa lebih panjang lagi, dan kau bisa tenang berada di keraton memimpin ribuan prajurit," kata Bayu lagi.
"Phuih! Kau bocah kemarin sore berani mengaturku" dengus Panglima Bantaraji.
Bagi Panglima Bantaraji, memang tidak ada pilihan lagi. Dia sudah kepalang basah, dan tidak akan mundur setapak pun juga, meskipun nyawa sebagai taruhannya. Lagi pula, dia memang tidak mungkin meninggalkan adiknya menantang maut seorang diri. Mereka sudah dikenal sebagai sepasang tokoh yang tangguh, dan sudah kenyang mengenyam pahit getirnya kehidupan rimba persilatan selama puluhan tahun.
"Hm..., rupanya benar kata mereka, kau benar‐benar seorang yang keras kepala. Sebenarnya aku enggan berhadapan denganmu, Panglima. Tapi karena kau memaksaku juga, apa boleh buat, kita terpaksa bertemu dalam arena pertarungan nanti." Setelah berkata begitu, Bayu langsung melentingkan tubuhnya bagai kilat meninggalkan tampat itu.
"Hey, tunggu .." sentak Panglima Bantaraji.
Namun begitu Panglima Bantaraji menggenjot tubuhnya, bayangan Pendekar Pulau Neraka itu sudah tidak terlihat lagi. Pendekar itu bagaikan hilang ditelan kepekatan malam. Sementara Panglima Bantaraji hanya bisa mengeluh pendek, dan tidak jadi mengejar.
Malam terus merayap semakin larut, suasana di Kadipaten Jati Anom benar‐benar sepi. Tak ada seorang penduduk pun yang terlihat berada di luar rumah. Mereka semua sudah mengetahui persoalan yang kini sedang dihadapi oleh Adipati Rakondah, dan mereka juga sudah mengetahui, siapa sebenarnya adipati itu. Hal ini semua karena pekerjaan Pendekar Pula Neraka.
Meskipun segala tindakannya dapat dikatakan kejam, namun kekejaman itu hanya ditujukan pada orang‐orang yang memang harus diberi tindakan begitu. Pendekar Pulau Neraka tidak akan pernah melukai atau menyakiti orang yang tidak mempunyai urusan dengannya, kecuali mereka yang benar‐benar keras kepala dan menghalangi tindakannya.
"Benar‐benar hebat dia. Aku jadi sangsi, apakah mampu untuk menandinginya...?" desah Panglima Bantaraji bimbang.
Panglima Bantaraji kemudian melangkah pelan memasuki bangunan istana Kadipatan Jati Anom itu. Di benaknya terus berputar dan dipenuhi oleh kata‐kata Pendekar Pulau Neraka barusan. Dalam hati kecilnya, dia tidak membantah kalau kata‐kata pemuda itu memang benar. Selama hidupnya, dia memang berada di jalur yang tidak bisa ditentukan. Dia sendiri sebenarnya tidak pernah menyetujui dan membenarkan tindakan adiknya, tapi mengingat Adipati Rakondah adalah adik kandung satu-satunya, dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja.
Dan sekarang mereka sedang menghadapi suatu persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Lawan mereka kali, ini bukan lawan sembarangan. Dia ialah seorang pendekar yang selalu bertindak kejam. Mengingat semua itu, Panglima Bantaraji jadi bergidik. Dia jadi ingat akan nasib yang telah dialami Jantara, si Tongkat Samber Nyawa. Kedua kakinya dibuntungi dan matanya dibutakan, persis seperti ketika Jantara nembuntungi dan membutakan Gardika.
"Hhh..., apakah Adik Rakondah juga akan dicincang seperti dia mencincang Dewa Pedang...?" kembali Panglima Bantaraji mendesah lirih.
********************
ENAM
Pagi hari itu di Lereng Gunung Panjaran, Intan Delima tengah duduk merenung di atas akar sebuah pohon besar yang menyembul dari dalam tanah. Jari‐jari tangannya yang lentik dan halus menyentil‐nyentilkan batu kerikil ke sungai kecil di depannya. Wajahnya kelihatan murung, dan sinar matanya redup menatap lurus ke arah sungai kecil yang berair jernih depannya. Gadis itu sama sekali tidak menyadari kalau sejak tadi ada sepasang mata yang memperhatikannya.
Sepasang mata yang bening itu memancarkan cahaya penuh ketegasan dan kekerasan hati. Pelahan‐lahan pemilik sepasang mata itu menghampirinya. Mendadak gadis itu tersentak begitu mendengar suara batuk keluar dari belakangnya. Dia langsung menoleh, dan menggeser duduknya begitu melihat pemuda gagah suda berdiri di belakangnya. Pemuda itu kemudian mengambil tempat, dan duduk di rerumputan di depan Inta Delima.
"Sudah tiga hari ini kau kelihatan murung. Ada apa, Adik Intan?" tanya pemuda gagah itu. Suaranya lembut, dan sinar matanya juga lembut menata langsung ke bola mata gadis itu.
"Entahlah, Kakang Bayu. Aku sendiri tidak tahu,” sahut Intan Delima mendesah lirih.
"Kau rindu dengan ayahmu?" tebak Bayu.
Intan Delima tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap pemuda itu dengan sinar mata yang sulit untuk diartikan. Sebenarnya dia memang rindu dengan ayahnya, tapi mengingat kekecewaan hatinya yang sudah demikian mendalam, kerinduannya itu pupus. Dan Intan Delima membiarkan saja ketika tangan Bayu mulai menggenggam tangannya. Dia juga tak bergeming saat pemuda itu pindah duduk di sampingnya.
"Maafkan aku, Intan Seharusnya kita tidak bertemu dalam suasana seperti ini," lembut suara Bayu.
"Kakang...," suara Intan Delima terputus. Kepalanya tampak menggeleng‐geleng lemah. Sedangkan tatapan matanya mengandung sejuta kata‐kata yang sulit untuk diucapkan.
"Kau ingin mengatakan sesuatu, Intan? Katakanlah, apa pun yang akan kau katakan, aku akan mendengarkan," kata Bayu tetap lembut.
"Kau tidak akan marah?"
Bayu menggeleng dan tersenyum manis.
"Juga tidak akan membenciku?"
Tidak ada alasan untuk membencimu, Intan."
"Kakang, aku. , aku...," Intan Delima sepertinya sulit untuk berkata. Pelahan‐lahan dia kemudian menundukkan kepalanya.
Sementara Bayu terus memperhatikan wajah gadis itu. Dan dengan pelahan‐lahan dia lalu mengangkat kepala Intan Delima dengan ujung jarinya. Sesaat mereka saling bertatapan. Tanpa kata, tanpa suara. Mereka terus bertatapan dengan sejuta kata yang terpancar dari sinar mata. Pelahan‐lahan sekali Bayu mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu. Napasnya yang hangat menerpa langsung membuat paras wajah Intan Delima bersemu merah dadu.
Namun belum sempat gadis itu menyadari apa yang akan dilakukan Bayu, mendadak tubuhnya menggeletar bagi tersengat ribuan lebah. Intan Delima merasakan tubuhnya seperti melayang, jauh menembus mega. Napasnya pun jadi terasa sesak, sedangkan dadanya berdebar keras bagai genderang yang dipukul bertalu-talu. Bibirnya bergetar hebat dalam kuluman bibir Bayu Hanggara.
Intan Delima langsung menundukkan kepalanya begitu Bayu melepaskan pagutannya. Merah sudah seluruh wajahnya. Berbagai perasaan kini berkecamuk di dalam dadanya. Entah dia menyukai semua itu, atau malah membencinya. Belum pernah sekali pun dia melakukan hal itu. Namun Intan Delima seolah ingin merasakannya lagi, dan lagi Pagutan Pendekar Pulau Neraka itu benar‐benar menghanyutkan. Indah, dan...
"Ah... Kau cantik sekali, Intan...," bisik Bayu lembut dan lirih di telinga Intan Delima.
"Kakang...," desah Intan Delima tidak mampu lagi untuk mengatakan sesuatu. Kembali Intan Delima tidak mampu menolak saat tangan yang kekar itu merengkuh dan memeluknya dengan erat. Gadis itu hanya mampu mendesah dan mengeluh lirih. Kepalanya menengadah ke atas dengan mata yang terpejam. Bibirnya dia gigit sekuat‐kuatnya menahan sesuatu yang begitu kuat mendesak dirinya. Ciuman‐ciuman yang hangat di lehernya benar‐benar telah membuat gadis itu lupa diri.
"Oh, ahhh..., Kakang. ," desis Intan Delima lirih. Gadis itu menggelinjangkan tubuhnya saat jari‐jenari tangan Bayu mulai menjelajahi tubuhnya. Kembali gadis itu tidak mampu menolak, saat Bayu membimbingnya ke bawah sebuah pphon besar dan rindang. Intan Delima menurut saja ketika dirinya dibaringkan di atas rerumputan di bawah pohon itu. Sementara cahaya matahari pagi hanya mampu nengintip malu dari balik kerimbunan daun.
Ciuman‐ciuman hangat, elusan lembut jari‐jari, dan bisikan halus dari Pendekar Pulau Neraka membuat Intan Delima bagai terbang ke suatu tempat indah yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Gadis itu hanya bisa mengeluh dan merintih lirih dalam dekapan Bayu Hanggara. Keangkuhan dan ketegarannya luruh hari itu juga. Intan Delima bagaikan seekor anak ayam yang pasrah berada di tangan serigala.
"Kakang, akh..." pekikan tertahan terdengar. Bersamaan dengan mengejangnya tubuh di dalam dekapan Bayu.
"Ohhh..."
********************
Intan Delima segera merapikan pakaiannya. Wajahnya tampak pucat, dan setirik air bening menggulir jatuh di pipinya yang putih kemerahan. Sejenak melirik pada Bayu yang rebah di sampingnya. Tampak keringat membasahi tubuh mereka. Bayu mengangkat tubuhnya dan duduk di samping Intan Delima. Dengan lembut dia kembali merengkuh tubuh gadis itu ke dalam pelukannya. Kini Intan Delima tidak mampu lagi menahan air matanya. Air bening langsung mengucur deras jatuh menimpa dada Bayu yang masih telanjang. Sedangkan pemuda itu hanya bisa memeluk dan mengusap‐usap punggung Intan Delima yang terbuka. Pakaian gadis itu belum seluruhnya rapi. Punggungnya masih terlihat terbuka lebar, menampakkan kulit punggung yang putih mulus tanpa cacat.
"Kau menyesal, Intan?" bisik Bayu lembut.
Intan Delima merenggangkan tubuhnya, dan bergegas merapikan pakaiannya. Dan dengan punggung tangannya dia menghapus air mata yang membasahi pipinya. Gadis itu tidak tahu lagi, apa yang harus dia katakan. Dia juga tidak tahu, perasaan apa yang dialaminya saat ini. Apakah dia bahagia? Sedih? Kehilangan? Atau... Entahlah. Yang jelas semuanya sudah terjadi tanpa ada paksaan. Penyesalan juga tidak ada gunanya lagi, sesuatu yang sudah hilang tidak akan bisa kembali lagi. Dan tanpa berkata sedikit pun, Intan Delima berdiri dan berjalan meninggalkan pemuda itu. Sementara Bayu juga bergegas mengenakan pakaiannya, lalu bangkit dan mengejar gadis itu. Dia mensejajarkan langkahnya di samping Intan Delima. Mereka terus berjalan pelan‐pelan tanpa berkata‐kata.
"Intan..."
Intan Delima menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan menatap langsung ke bola mata Bayu. Bibirnya yang selalu merah, tampak bergetar. Sedangkan sepasang bola matanya juga masih merembang, namun tidak setitik pun air bening yang memenuhi kelopak matanya itu jatuh.
"Maafkan aku, Intan. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi," kata Bayu menyesal.
"Kau harus menikahiku, Kakang. Kau harus menemui ayahku, dan melamarku," kata Intan Delima agak tersendat suaranya.
"Mustahil Tidak mungkin, Intan. Masih banyak pekerjaanku yang belum selesai. Lagi pula aku tidak mungkin menarik kembali kata‐kataku. Aku sudah memberikan waktu pertarungan. Aku atau ayahmu yang harus mati" kata Bayu mantap.
"Aku mencintaimu, Kakang. Dan aku tidak mau kehilanganmu, juga ayahku. Hentikan semua dendam mu, Kakang." Intan Delima setengah merengek.
Kini Bayu hanya bisa menggeleng‐gelengkan kepalanya. Baginya tidak mungkin untuk mencabut kembali ucapannya. Dia memang menyukai gadis itu, tapi dendamnya pada ayah gadis itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Seperti apa pun rintangan yang menghadang, Bayu tetap bertekad untuk melaksanakan dendam itu.
"Aku mohon padamu, Kakang. Kita bisa hidup tenang dan bahagia, tanpa harus dibebani dengan segala macam dendam. Aku bisa meminta pada Paman Panglima Bantaraji agar kau diberi kedudukan yang tinggi di kerajaan," bujuk Intan Delima.
Bayu diam saja.
"Ayah pasti mau memaafkan dan menerimamu Kakang. Aku yakin, Ayah pasti akan menyesali perbuatannya yang telah lalu," sambung Intan Delima tetap membujuk.
"Maaf, Intan. Aku benar‐benar tidak bisa menuruti permintaanmu. Hari pertarungan sudah ditentukan dan aku sudah memberikan tanda sebagai lambang kematian baginya"" kata Bayu tegas.
"Kakang..." suara Intan Delima tercekat.
"Jangan membujuk lagi, Intan," tegas kata‐ka Bayu.
Kini Intan Delima tidak kuasa lagi membendung air matanya. Dan dia hanya bisa berdiri terpaku dengan bibir bergetar. Sementara Bayu mulai melangkah meninggalkannya. Pertentangan batin melanda di gadis itu. Hatinya judah terpaut kuat oleh ketampanan dan kegagahan pendekar muda itu, tapi dia juga mencintai ayahnya. Tidak mungkin membiarkan ayahnya tewas di tangan orang yang sudah menggoreskan tinta merah di hatinya.
"Kakang..." teriak Intan Delima memanggil.
Namun Bayu tetap melangkah meninggalkannya. Sedikit pun dia tidak menoleh ke belakang. Buru‐buru Intan Delima berlari mengejar sambil memanggil-manggil. Dia melewati Pendekar Pulau Neraka itu, dan langsung berdiri menghadangnya. Di tangannya kini sudah tergenggam sebilah pedang yang berkilat tertimpa cahaya matahari. Tentu saja Bayu tersentak melihat Intan Delima telah menghunus pedangnya.
"Jangan main‐main, Intan. Masukkan kembali pedangmu" sentak Bayu keras.
"Tidak..Sebelum kau berjanji tidak akan bertarung dengan ayahku, aku akan tetap menghadang-mu" suara Intan Delima terdengar bergetar.
"Intan Apa‐apaan kamu?" sentak Bayu.
"Aku mohon padamu, Kakang. Batalkan pertarungan itu. Aku benar‐benar mencintaimu...," rengek Intan Delima. Air matanya berderai tak terbendung lagi.
"Jangan main‐main, Intan. Masukkan kembali pedangmu"
"Tidak! Sebelum kau berjanji tidak akan bertarung dengan ayahku" suara Intan Delima agak bergetar.
"Mengertilah, Intan. Aku...."
"Kau tidak mencintaiku, Kakang?" potong Intan Delima cepat.
"Intan...," Bayu jadi kebingungan juga.
"Kau kejam, Kakang. Kau hanya bermaksud mempermainkan aku" tangis Intan Delima meledak Hatinya benar‐benar serasa hancur begitu menyadari kalau pemuda yang telah merenggut segala‐galanya itu tidak mencintainya.
"Aku..., aku menyukaimu, Intan," suara Bayu lembut.
"Tidak Kau hanya menginginkan tubuhku Kau tidak mencintaiku Kau kejam, Kakang... Kejam..." Intan Delima jadi histeris.
"Intan..." Bayu tidak mampu lagi melanjutkan ucapannya.
Intan Delima sudah keburu mengibaskan pedangnya dengan cepat. Untung saja Pendekar Pulau Neraka itu cepat‐cepat menarik tubuhnya ke belakang, sehingga ujung pedang Intan Delima lewat beberapa helai rambut di depan dadanya. Dan belum lagi Bayu sempat menyadarkan gadis itu, mendadak Intan Delima sudah kembali menyerangnya dengan ganas. Tampaknya gadis itu sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Rasa kecewa yang bertumpuk membuat jiwanya terguncang hebat. Baginya lebih baik mati, atau pemuda itu tewas di tangannya daripada hidup menanggung malu dan kekecewaan.
"Intan Hentikan, dengarkan aku dulu..., uts"
Buru‐buru Bayu menarik kepalanya ke belakang begitu ujung pedang Intan Delima hampir membabat lehernya. Pendekar Pulau Neraka itu benar‐benar tidak diberi kesempatan sama sekali. Jangankan untuk membalas menyerang, untuk bicara saja dia tidak punya kesempatan lagi Serangan‐serangan yang dilancarkan Intan Delima benar‐benar dahsyat dan mengarah pada bagian‐bagian tubuh yang mematikan. Rasa cinta, kecewa dan marah telah menggulung dirinya menjadi satu Hilang sudah kelembutan dan kemanisan di wajahnya yang kini memerah kaku bagai seekor singa betina yang kehilangan anaknya.
"Huh Gadis ini benar‐benar ingin membunuhku" keluh Bayu dalam hati.
Serangan‐serangan Intan Delima benar‐benar berbahaya, dan Bayu tidak punya pilihan lain lagi. Begitu pedang Intan Delima mejuruk deras ke arah dadanya, dengan cepat Pendekar Pulau Neraka itu mengegoskan tubuhnya ke samping, dan bagaikan seekor ular marah, tangannya bergerak cepat menepuk punggung tangan gadis itu.
"Akh" Intan Delima memekik tertahan. Tepukan yang disertai pengerahan tenaga dalam tinggi itu membuat pegangan pedang gadis itu terlepas. Dan tanpa dapat dicegah lagi, pedang bercahaya keperakan itu meluncur dan menancap pada sebatang pohon cemara. Belum lagi Intan Delima menyadari apa yang terjadi, satu totokan lembut sudah bersarang di pundak kirinya. Dan disusul satu totokan lagi mendarat di dada kanan. Maka tanpa ampun lagi gadis itu ambruk dengan tubuh lemas tertotok jalan darahnya. Bayu segera memburu dan berlutut di samping gadis itu.
"Intan...."
"Bunuhlah aku, Kakang. Ayo bunuhlah aku..." jerit Intan Delima histeris. Air matanya yang sudah kering kembali mengalir deras.
"Maafkan aku Intan. Aku menyukaimu, tapi...."
"Kau kejam, Kakang Kejam..." jerit Intan Delima memotong cepat. Kepalanya menggeleng‐geleng.
Bayu menarik napas panjang. Kemudian jari‐jari tangannya bergerak lembut ke beberapa bagian tubuh Intan Delima. Setelah itu dia bangkit berdiri. Sejenak, dipandanginya wajah gadis itu, kemudian melangkah mundur. Intan Delima menatapnya tajam dengan sinar, mata yang penuh dengan perasaan cinta, benci dan kecewa yang bercampur menjadi satu.
"Sebentar lagi pengaruh totokanku hilang. Maaf, aku harus segera pergi," kata Bayu dengan nada suara agak tertahan. Setelah berkata begitu, Bayu segera melompat pergi, dan langsung lenyap ditelan kerimbunan pepohonan di Lereng Gunung Panjaran ini.
Memang benar, tidak lama kemudian Intan Delima sudah bisa bangun lagi. Namun dia masih terduduk lemas, dan menangis tersedu‐sedu. Hancur sudah seluruh hatinya. Laki‐laki yang sangat dicintainya telah pergi meninggalkannya dengan luka yang tergores di hati.
"Aku mencintaimu, Kakang Bayu.... Ketahuilah, Kakang. Aku tidak ingin kau tewas di tangan Ayah, aku juga tidak ingin Ayah tewas di tanganmu. Oh, Tuhan..., kenapa Kau pertemukan kami dalam keadaan seperti ini?" Intan Delima merintih lirih. Air matanya semakin banyak berlinang.
Seluruh Lereng Gunung Panjaran seperti mendengar rintihan gadis itu. Angin serasa berhenti berhembus, dan matahari pun meredupkan cahayanya. Rintihan Intan Delima begitu menyayat, terucap dari lubuk hatinya yang paling dalam. Lama Intan Delima duduk bersimpuh dan merintih lirih. Kemudian pelahan‐lahan dia bangkit berdiri. Kemudian dipungutnya pedang yang tertancap di pohon cemara, lalu dimasukkan ke dalam sarungnya kembali di pinggang.
Sebentar dia menarik napas panjang dan dalam. Dan dengan punggung tangannya, dia menyusut air matanya. Kemudian pelahan‐lahan kakinya terayun kembali menuruni Lereng Gunung Panjaran yang sepi itu. Lesu dan gontai langkahnya terayun. Sesekali masih terdengar isaknya yang lirih. Sementara anginpun kembali berhembus, dan matahari kembali menyorotkan sinar-nya dengan terik. Intan Delima telah melangkah gontai dengan membawa berbagai macam perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya.
********************
Hari terus berganti seiring dengan bergulirnya sang waktu. Matahari pun terus berputar sejalan dengan peredarannya. Siang berganti senja, dan senja pun kemudian lenyap digantikan malam. Tugas matahari sepanjang siang telah berganti dengan sang dewi malam dengan cahayanya yang lembut menyirami bumi. Kabut tipis sudah sejak tadi menyelimuti seluruh kawasan Kadipaten Jati Anom, yang berada Kaki Lereng Gunung Panjaran. Kesunyian yang tengah menyelimuti seluruh pelosok Lereng Gunung Panjaran dan Kadipaten Jati Anom, tidak menghalangi sebuah bayangan putih yang berkelebatan cepat menyelinap dari rumah‐rumah penduduk.
Bayangan putih itu jelas bergerak menuju Istana Kadipaten Jati Anom yang kini hanya dijaga oleh tidak lebih dari dua puluh orang prajurit. Dari gerakannya, yang ringan saat melompati tembok benteng istana itu, jelaslah kalau orang itu memiliki tingkat kepandaian yang sangat tinggi. Dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun, sosok bayangan putih itu segera hinggap di atas genting bangunan megah itu. Hanya sekejap dia berada di atas atap, lalu dengan ringan tubuhnya kembali meluruk ke bawah, dan langsung mendarat di beranda depan. Lima orang prajurit yang tengah menjaga tempat itu, terkejut dan langsung mengepung dengan senjata terhunus.
"Tahan" terdengar suara bentakan keras dari arah dalam.
Tidak lama kemudian, keluarlah Adipati Rakondah yang diikuti oleh Panglima Bantaraji. Mereka langsung berlutut di depan orang berjubah putih dengan rambut dan janggut juga putih semua. Bibirnya hampir tertutup oleh kumis panjang yang menyatu dengan janggutnya. Sementara lima orang prajurit yang sudah mengepung, langsung menyimpan kembali senjatanya, dan segera berlutut mengikuti junjungan mereka.
"Bangunlah, anak‐anakku," lembut dan berwibawa suara laki‐laki berjubah putih yang usianya hampir mencapai seratus tahun itu. Kemudian Adipati Rakondah dan Panglima Bantaraji bangkit pelahan. Panglima Bantaraji memberi isyarat kepada lima orang prajurit agar segera pergi. Setelah memberi hormat, kelima prajurit itu pun segera meninggalkan beranda.
"Ah, kedatangan Eyang Guru benar‐benar mengejutkan," kata Adipati Rakondah seraya mempersilakan laki-laki tua yang dipanggil Eyang Guru itu masuk. Laki‐laki tua itu pun segera melangkah ringan memasuki bagian dalam istana itu. Mereka bertiga kemudian duduk di kursi berukir yang terbuat dari kayu jati, dan mengelilingi sebuah meja bundar yang juga berukir dengan batu puatern putih di atasnya.
"Maaf, Eyang. Ada maksud apakah sehingga Eyang Guru Watuagung datang secara tiba‐tiba? tanya Adipati Rakondah hormat. Laki‐laki tua berusia hampir seratus tahun itu tidak segera menjawab. Matanya yang bening dan tajam memandangi sekitamya, kemudian satu persatu dipandanginya Adipati Rakondah dan Panglima Bantaraji secara bergantian.
"Ketahuilah, anak‐anakku. Aku datang karena mendengar bahwa kalian tengah mendapat musibah yang cukup serius. Aku memang sudah mendengar banyak, meskipun tempat tinggalku jauh dari sini. Tapi aku ingin mendengar langsung dari kalian berdua,” tetap lembut dan berwibawa nada suara Eyang Watuagung.
Sejenak Adipati Rakondah memandang Panglima Bantaraji, lalu dia menceritakan keadaan sebenarnya dengan singkat namun jelas. Sedangkan laki‐laki tua berjubah putih itu mengangguk‐anggukkan kepalanya beberapa kali. Sementara jari‐jari tangannya yang kecil dan berkeriput terus mengelus‐elus janggutnya.
"Maafkan kami, Eyang. Bukannya kami tidak mau memberitahukan perihal ini padamu. Kami merasa, bahwa hal ini adalah tanggung jawab kami berdua, terutama aku, Eyang," kata Adipati Rakondah setelah selesai bercerita.
"Hm..., jadi benar anakmu telah diculik oleh seorang pemuda yang mengaku bernama Pendeka Pulau Neraka itu?" Eyang Watuagung seperti ingin kejelasan.
"Benar, Eyang," sahut Adipati Rakondah.
"Maaf Eyang," Panglima Bantaraji menyelak. "Dari mana Eyang tahu semua tentang keadaan di ini?"
"Beberapa prajuritmu yang meninggalkan kadipaten ini telah datang ke tempatku. Bahkan para pelayan dan abdi‐abdimu juga datang. Mereka semua menceritakan perihal keadaan di sini. Kemudian aku memutuskan untuk mengetahui kebenarannya secara langsung."
“Tapi, Eyang..."
"Kau tidak usah cemas Rakondah. Kalian adalah anak‐anakku, murid‐murid utamaku yang sudah berhasil. Aku merasa bangga pada kalian berdua. Tapi aku juga menyesalkan setiap langkah dan tindakanmu, Rakondah. Sejak kecil watakmu memang sudah begitu, dan aku tidak bisa menyalahkanmu. Sebagai orang tua yang mengasuh dan mendidikmu, aku juga merasa bertanggung jawab atas segala akibat perbuatanmu, Rakondah."
"Maafkan aku, Eyang," pelan suara Adipati Rakondah.
"Sudahlah, semuanya telah terjadi. Aku datang justru untuk meluruskan jalan. Mudah‐mudahan pertumpahan darah tidak sampai terjadi. Tapi...," kata‐kata Eyang Watuagung tertunda.
"Ada apa, Eyang...?"
"Ada apa, Eyang?" tanya Panglima Bantaraji setelah Eyang Watuagung tidak segera menjawab. Dia kembali duduk di kursinya dengan pandangan mata lurus ke luar jendela. Keningnya yang memang sudah banyak kerutannya, tampak semakin dalam berkerut. Sementara Adipati Rakondah dan Panglima Bantaraji hanya bisa saling berpandangan tidak mengerti.
Saat itu, tiba‐tiba secercah sinar berwarna keperakan meluncur deras ke arah mereka. Seketika Eyang Watuagung mengegoskan kepalanya sedikit, dan segera mengebutkan tangan kanannya. Sinar keperakan itu langsung lenyap di dalam genggaman tangannya. Dan begitu tangan itu terbuka, tampaklah sebuah logam yang berbentuk bintang dan berwarna keperakan bersegi enam. Ada secarik kain merah yang tergulung di tengah‐tengah benda itu. Eyang Watuagung segera mencopot kain itu dan membuka lipatannya.
Tampak beberapa baris tulisan yang tertera dengan tinta emas. Hanya ada satu kalimat, tapi mampu untuk membuat mata laki‐laki yang berusia hampir seratus tahun itu membeliak lebar. Kemudian Panglima Bantaraji segera merebut kain itu dari tangan Eyang Watuagung.
"Jangan campuri urusanku jika kau tidak ingin mati" desis Panglima Bantaraji membaca sebaris kalimat di kain merah itu.
"Gila" geram Adipati Rakondah.
"Ini benar‐benar, sudah keterlaluan. Berani-beraninya dia menghina Eyang Guru..." desis Panglima Bantaraji menahan geram.
Sedangkan Eyang Watuagung hanya berdiam diri dengan pandangan mata yang tetap lurus ke depan, menembus kepekatan malam melalui jendela yang terbuka lebar. Tampak Gunung Panjaran berdiri megah melatarbelakangi Kadipaten Jati Anom ini. Sebuah gunung yang selalu berselimut kabut pada puncaknya.
"Eyang, penghinaan ini harus dibalas" kata Adipati Rakondah geram. Hatinya benar‐benar tak rela, karena laki‐laki tua yang menjadi gurunya dan mendidiknya sejak kecil mendapat penghinaan seperti itu.
Memang hanya sebuah kalimat yang tertulis pada sehelai kain merah, tapi kalimat itu benar‐benar menyakitkan. Tidak memandang sebelah mata pun pada seorang yang paling dihormati dan diseganinya. Baginya, perbuatan Pendekar Pulau Neraka benar‐benar sudah melampaui batas. Selama ini dia masih bisa menahan diri karena memang merasa bersalah. Tapi kalau sampai penghinaan pada guru dan orang tua angkatnya itu.... Rasanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa tinggal diam memperoleh perlakuan seperti itu.
"Benar, Eyang. Aku rela mati demi membalas penghinaan ini" sambung Panglima Bantaraji.
"Tenangkan diri kalian" sentak Eyang Watuagung.
"Dia benar, aku memang tidak boleh mencampuri urusan ini."
"Tapi, Eyang," Adipati Rakondah ingin membantah.
"Aku tahu, kalian memang tidak rela dengan penghinaan pada diriku. Tapi dia tidak juga salah kalau memintaku untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Meskipun aku tidak menyukai caranya, tapi aku bisa memaklumi," Eyang Watuagung langsung memutus ucapan Adipati Rakondah.
Suasana jadi hening sesaat.
"Dan kau, Bantaraji. Tidak sepatutnya kau mengorbankan orang‐orang yang tidak bersalah dan tida tahu‐menahu mengenai masalah ini. Terus terang, aku tidak setuju dengan caramu," tajam tatapan mata Eyang Watuagung kepada Panglima Rakondah.
"Eyang, aku hanya...."
"Aku tahu, Bantaraji. Kau memang seorang kakak yang baik. Meskipun kau tahu kalau adikmu berada di pihak yang salah, kau tetap rela berkorban untuk membela. Tapi seharusnya kau tidak perlu membawa-bawa orang lain. Besok, aku tidak mau lagi melihat prajurit‐prajurit itu masih ada di sini. Kau mengerti, Bantaraji?" tegas kata‐kata Eyang Watuagung.
"Ya, Eyang," tidak ada pilihan lagi buat Panglima Bantaraji. Meskipun berat, dia harus mematuhi kata-kata gurunya yang juga ayah angkatnya ini.
"Kapan Pendekar Pulau Neraka itu akan datang menantangmu?" tanya Eyang Watuagung beralih menatap pada Adipati Rakondah.
"Besok, tengah malam," sahut Adipati Rakondah.
"Kau harus menghadapinya secara ksatria, Rakondah. Aku akan tersenyum melihat kau mati dengan cara seorang pendekar sejati "
Adipati Rakondah hanya diam menunduk.
"Dan kau, Bantaraji. Aku tidak mau lagi melihatmu berlaku bodoh! Kau paham, Bantaraji?"
"Paham, Eyang."
"Mulai besok, pagi‐pagi sekali, seluruh prajuritmu harus sudah meninggalkan Kadipaten Jadi Anom. Aku tidak mau lagi melihat darah sia‐sia mengalir di bumi Jati Anom ini," sambung Kyang Watuagung lagi.
"Aku mengerti, Eyang," sahut Panglima Bantaraji.
Tak lama kemudian Eyang Watuagung bangkit dari duduknya, dan melangkah ke luar. Sedangkan Adipati Rakondah dan Panglima Bantaraji masih tetap duduk di kursinya. Di satu sisi mereka memang senang dengan kedatangan gurunya, tapi di sisi lain membuat gelisah dengan keputusan‐keputusannya yang benar‐benar di luar dugaan itu. Dari dulu mereka memang telah dididik untuk menjadi seorang pendekar tangguh yang membela kebenaran dan keadilan, tapi jalan hidup manusia memang tidak bisa diduga sebelumnya.
********************
TUJUH
Hari masih pagi sekali. Matahari pun belum menampakkan diri. Sementara kabut yang masih menyelimuti sekitar Lereng Gunung Panjaran, menyebarkan hawa dingin serasa menusuk kulit. Namun keadaan yang demikian itu tidak menghalangi sesosok bayangan putih mendaki lereng gunung itu. Langkahnya ringan dan cepat, bagaikan berjalan di atas angin.
Kemudian ia berhenti di sebuah sungai kecil dengan airnya yang mengalir jernih. Sejenak laki‐laki tua berjubah putih yang tidak lain adalah Eyang Watuagung itu mengedarkan pandangannya berkeliling. Daun telinganya bergerak‐gerak pertanda bahwa dia tengah mendengarkan suara‐suara yang ada di sekitar tempat itu. Dan pada saat pandangannya mengarah ke sebelah kiri, tampaklah seorang pemuda tampan dan gagah sudah berdiri membelakangi sebongkah batu besar.
"Aku tahu kalau kau ada di sekitar sini, Anak Muda," kata Eyang Watuagung. Suaranya terdengar tenang, namun berwibawa.
Pemuda gagah yang berbaju dari kulit harimau itu kemudian melangkah mendekat. Dia berhenti setelah jaraknya dengan laki‐laki tua berusia hampir seratus tahun itu tinggal dua batang tombak lagi. Tangannya tetap melipat di depan dada, memperlihatkan sebentuk logam pipih yang bergerigi enam buah di pergelangan tangannya. Pemuda itu tak lain adalah Pendekar Pulau Neraka.
"Hebat Kau bisa mengetahui tempatku, Orang Tua," kata Bayu memuji.
"Aku sudah tahu sejak kau muncul di istana kadipaten...."
"Dan aku juga sudah tahu kedatanganmu," balas Bayu.
"Kau salah kalau menyangka aku akan membela muridku, Anak Muda. Aku justru datang untuk menyadarkannya, dan mencegah terjadinya pertumpahan darah di antara kalian," masih tenang kata-kata Eyang Watuagung.
"Terlambat..." kata Bayu tegas.
"Tidak ada kata terlambat kalau kau mau memikirkan kembali. Aku tahu semua persoalan yang kau bawa, dan aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Tapi menurutku, dendam bukanlah suatu penyelesaian yang baik. Apalagi harus diakhiri dengan mengadu jiwa"
"Aku kagum padamu, Orang Tua. Ternyata kau adalah seorang yang bijaksana. Tapi sebagai seorang pendekar ksatria, aku pantang menarik kembali kata-kataku yang sudah terucap. Saat pertarungan sudah ditentukan, dan aku tidak mungkin lagi menarik keputusanku. Kau pasti bisa lebih paham dari aku, yang masih belum berpengalaman dalam mengarungi rimba persilatan."
Eyang Watuagung mengangguk‐anggukkan kepalanya. Dalam hati dia memuji dan mengagumi sikap ksatria yang dimiliki oleh anak muda ini. Tapi sebagai seorang guru dan orang tua angkat Adipati Rakondah, Eyang Watuagung rasanya tidak akan bisa membiarkan muridnya tewas di tangan Pendekar Pulau Neraka. Meskipun dia merasa senang melihat muridnya itu bisa bersikap ksatria, namun dalam hati kecilnya tidak rela jika muridnya harus kalah di depan matanya. Lebih-lebih oleh seorang pemuda yang baru saja terjun dalam kancah rimba persilatan. Nama besarnya sebagai tokoh tua yang banyak melahirkan pendekar tangguh bisa tercemar.
"Baiklah, Anak Muda. Aku tidak akan mencampuri urusanmu dengan Rakondah. Tapi aku minta agar kau kembalikan cucuku, Intan Delima. Jangan kau peralat dia jadi sanderamu hanya untuk melemahkan jiwa lawan," kata Eyang Watuagung memohon.
"Aku tidak pernah menculik dan menyandera Intan Delima. Aku tidak tahu di mana kini dia berada. Dia pergi karena malu mempunyai orang tua yang berhati busuk dan kerdil"
"Kata‐katamu benar‐benar menyakitkan, Anak Muda" desis Eyang Watuagung merasa tersinggung muridnya dikatakan berhati busuk. Kalau muridnya berhati busuk, tentu gurunya lebih busuk lagi Eyang Watuagung bisa menangkap arti dari kata‐kata itu.
"Maaf, aku sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggungmu. Tapi semua yang kukatakan itu adalah kenyataan. Aku tidak keberatan jika kau membelanya, tapi kau harus berhadapan denganku" kata Bayu tegas.
"Hm..., kau menantangku, Pendekar Pulau Neraka?"
"Terserah apa tanggapanmu. Yang jelas, tujuanku hanya satu. Dan aku tidak peduli siapa saja yang ada di belakangnya. Bagiku, penghalang tetap penghalang, dan harus aku hadapi" tegas kata‐kata Bayu.
Eyang Watuagung berdecak. Rasa kagumnya semakin bertambah, namun dia juga tidak menyukai sifat yang congkak, angkuh dan menganggap dirinya lebih dari orang lain. Di matanya, Pendekar Pulau Neraka adalah seorang pendekar angkuh yang tidak pernah memandang sebelah mata pun pada siapa saja. Kata‐katanya selalu tegas, dan meluncur deras bagai tak pernah dipikirkan sebelumnya. Eyang Watuagung yang sudah kenyang makan asam garamnya dunia persilatan, tidak terkejut lagi menghadapi orang seperti Bayu Hanggara ini. Sehingga dia tetap bisa bersikap tenang.
"Maaf, aku tidak punya banyak waktu lagi," kata Bayu.
"Tunggu" buru buru Eyang Watuagung mencegah.
"Ada apa lagi?" Bayu mengurungkan niatnya.
"Kau belum menjawab satu pertanyaanku, Anak Muda."
"Pertanyaan yang mana?"
"Di mana kau sembunyikan Intan Delima?"
"Sudah kukatakan, aku tidak tahu. Dia pergi sendiri karena malu dengan kelakuan ayahnya. Apa itu tidak cukup jelas?" agak kasar kata kata Bayu.
"Nada suaramu menyembunyikan sesuatu, Anak Muda...," gumam Eyang Watuagung tidak percaya.
"Terserah" sahut Bayu agak terkejut juga. Sebelum dia lebih jauh didesak, dengan cepat Pendekar Pulau Neraka itu melesat meninggalkan orang tua itu.
Sedangkan Eyang Watuagung tidak mau mengejar lagi. Dia hanya berdiri memandang ke arah kepergian Bayu. Sebentar dia mendesah pendek, kemudian berbalik dan melangkah menuruni lereng kembali. Namun baru beberapa langkah dia berjalan, mendadak tubuhnya berbalik dengan cepat. Dan tangan kanannya berkelebat bersamaan dengan berbaliknya tubuhnya.
"Jangan..."
"Heh..." Eyang Watuagung buru‐buru merentangkan tangannya ke samping, dan dari balik lengan jubahnya yang longgar, meluncurlah tiga buah benda kecil bagai jarum. Benda yang berwarna kuning keemasan itu, meluncur bagai kilat dan menghantam pohon tua yang tidak jauh di samping kanannya. Dan tiga buah benda kecil itu langsung menembus pohon itu. Aneh Pohon itu, langsung kering dan tumbang bagai terhempas satu kekuatan yang amat dahsyat.
"Intan..." seru Eyang Watuagung tersentak kaget.
"Eyang..."
Intan Delima yang muncul dari gerumbul semak, langsung berlari dan memeluk kaki laki‐laki tua itu. Sedangkan Eyang Watuagung segera memegang bahu gadis itu dan membawanya berdiri. Sejenak dia memandangi wajah cucunya yang tampak murung itu. Tampak setitik air bening menggulir di pipinya yang halus kemerahan.
"Apa yang telah terjadi padamu, Cucuku?" tanya Eyang Watuagung sambil menuntun Intan Delima dan membawanya duduk pada sebatang pohon yang telah tumbang.
Intan Delima tidak langsung menjawab. Dia malah menangis di pangkuan laki‐laki tua itu. Sulit baginya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat mencintai pemuda itu, tapi sekaligus juga membencinya, karena laki‐laki yang dicintainya itu ternyata hanya menginginkan tubuhnya saja.
Untuk beberapa saat lamanya, Eyang Watuagung membiarkan saja gadis itu menumpahkan tangisnya. Dia hanya membelai belai rambut yang hitam pekat dengan lembut. Agak lama juga Intan Delima menumpahkan perasaan dalam tangisnya. Kini setelah isaknya agak reda, dia kembali mengangkat kepalanya. Sisa‐sisa air matanya segera dihapusnya dengan ujung baju. Sejenak gadis itu mencoba menenangkan diri.
"Apa yang telah terjadi padamu, Intan?" tanya Eyang Watuagung lagi. ,
"Eyang..., dia..., dia telah...," Intan Delima serasa tidak sanggup lagi meneruskan.
Tiba‐tiba saja perasaan malu menghinggapi dirinya. Tidak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Dia memang telah menyerahkan tubuhnya tanpa paksaan. Dia merelakan semuanya dengan rasa cinta, karena menganggap Bayu Hanggara juga mencintainya dan mau melupakan semua dendamnya. Tapi semua itu ternyata malah terbalik, dan membuatnya kecewa serta sakit hati. Kini kekecewaan yang dalam di hatinya tak mungkin bisa dihapuskan begitu saja. Luka di hatinya sudah begitu parah, tidak mungkin lagi bisa terobati. Namun Intan juga tidak bisa membohongi dirinya. Bagaimanapun juga dia masih mencintai dan mengharapkan Bayu Hanggara.
"Apa yang telah dia lakukan padamu?" agak dikit ditekan suara Eyang Watuagung.
"Eyang... Aku..., aku malu. Aku tidak kuasa untuk menolaknya, Eyang... Aku malu...," kembali Intan Delima menangis.
Kembali Eyang Watuagung menarik napas panjang dan dalam. Meskipun Intan Delima belum mengatakannya dengan terus terang, namun dia sudah bisa menangkap maksudnya. Entah apa yang ada dalam hatinya saat ini, dan jelas wajahnya jadi memerah, dam gerahamnya bergemeletuk hebat.
"Tolong aku, Eyang...," rintih Intan Delima setelah reda tangisnya.
"Katakan, apa yang bisa aku lakukan?"
"Jangan katakan hal ini pada Ayah. Tolong Eyang. Aku..., aku tidak sanggup lagi bertemu dengan Ayah. Aku malu...."
"Kenapa kau harus malu? Itu semua bukan karena salahmu. Kau hanya jadi korban dari kebiadaban manusia yang berhati iblis" agak menggeram suara yang Watuagung.
"Tapi...," Intan Delima menggigit bibirnya. Hampir aja dia keterlepasan bicara. Hatinya tetap tidak rela kalau Bayu dikatakan demikian.
"Aku mengerti perasaanmu. Intan. Sekarang pulanglah, dan tenangkan dirimu. Aku akan mencari setan keparat itu. Dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya," kata Eyang Watuagung.
"Aku tidak mau pulang, Eyang," tolak Intan Delima.
"Lalu, kau mau ke mana?"
Intan Delima tidak segera menjawab. Dia sendiri juga bingung mau pergi ke mana lagi. Untuk kembali kepada ayahnya, rasanya tidak mungkin. Hatinya sudah telanjur kecewa dengan kelakuan ayahnya, dan dia juga malu untuk bertemu lagi, mengingat dirinya kini sudah bukan seorang gadis suci lagi.
"Baiklah, sebaiknya kau kembali saja ke Gunung Rangkas. Katakan pada pamanmu di sana, bahwa aku akan segera datang menjemputmu. Kau akan menjadi murid terakhirku," kata Eyang Watuagung.
"Oh, Eyang...," Intan Delima tidak bisa lagi mengucapkan sesuatu. Sudah lama dia ingin memperoleh ilmu‐ilmu yang dimiliki kakeknya ini. Kini Intan Delima berlutut dan memeluk kaki laki‐laki tua itu. Kemudian pelahan‐lahan dia bangkit dan menjura hormat. Sedangkan Eyang Watuagung hanya tersenyum, namun senyumnya itu terasa getir.
"Eyang, apakah Eyang akan membunuh Pendekar Pulau Neraka?" tanya Intan Delima ragu‐ragu.
"Kalau dia mau berjanji dan bertanggung jawab atas perbuatannya, mungkin tidak. Tergantung nanti saja, Intan," sahut Eyang Watuagung berusaha bersikap bijaksana.
"Terima kasih, Eyang."
"Kenapa kau tanyakan itu, Intan?" tanya Eyang Watuagung dengan tatapan curiga.
"Ah, tidak..., tidak.. Aku hanya ingin dia mati di tanganku," sahut Intan Delima tergagap.
"Hhh..., dendam. Rupanya bumi belum berhenti tersiram oleh darah," desah Eyang Watuagung berat.
Beberapa saat kemudian, Eyang Watuagung meminta agar Intan Delima segera meninggalkan Kadipaten Jati Anom. Dia tidak lagi mendesak agar gadis itu mau menemui ayahnya dulu. Sedangkan Intan Delima sendiri sebenarnya rindu, tapi kerinduannya dia tekan dalam‐dalam. Gadis itu terus melangkah menuruni Lereng Gunung Panjaran dengan hati membawa cinta, dendam, benci dan rasa kecewa yang bertumpuk menjadi satu.
Sementara Eyang Watuagung masih saja berdiri sambil memandangi kepergian Intan Delima. Dan setelah bayangan gadis itu tidak terlihat lagi, barulah laki‐laki tua berjubah putih itu mengayunkan kakinya. Arahnya menuju tempat di mana Pendekar Pulau Neraka tadi pergi. Jelas kalau dia bermaksud mencari pendekar muda itu.
********************
Bayu Hanggara tampak berdiri tegak sambil memandang ke arah Kadipaten Jati Anom yang tampak sepi. Dari tempat ketinggian seperti itu, dia bisa memandang luas ke arah kadipaten itu. Tampak pintu gerbang bentengnya tertutup rapat tanpa satu orang pun prajurit yang menjaganya. Sejenak Bayu tersenyum melihat keadaan Kadipaten Jati Anom yang sudah terpengaruhi oleh kedatangannya.
"Tidak lama lagi, Rakondah. Bersiap‐siaplah menjemput ajalmu," desah Bayu.
"Kau juga harus bersiap siap, Pendekar Pulau Neraka"
Bayu langsung tersentak kaget begitu mendengar suara dari arah belakangnya. Buru‐buru dia membalikkan tubuhnya, dan tampaklah di depannya, seorang laki‐laki tua mengenakan jubah putih yang longgar. "Kau lagi, Orang Tua. Mau apa kau mengikutiku?" nada suara Bayu terdengar ketus.
"Kali ini aku datang untuk meminta tanggung jawabmu, Anak Muda" tegas kata‐kata yang terucap dari bibir Eyang Watuagung.
"Hm...," Bayu mengerutkan keningnya.
"Apa yang telah kau lakukan pada cucuku Intan Delima?" agak bergetar suara Eyang Watuagung.
"O..., rupanya kau telah bertemu dengan gadis itu?" Bayu langsung menebak.
"Semula aku bisa memahamimu, Anak Muda. Tapi perbuatanmu pada Intan Delima..., rasanya aku tidak bisa lagi memaafkanmu, kecuali kau mau tanggung jawab" dingin suara Eyang Watuagung.
"Pasti dia mengadu yang bukan‐bukan," desis Bayu. "Asal kau tahu saja, Orang Tua. Intan Delima datang sendiri padaku dengan sukarela. Aku tidak memaksanya, dia sendiri yang menginginkannya."
"Biadab Pandai sekali kau memutarbalikkan lidah" geram Eyang Watuagung membentak. "Seharusnya aku memang tahu, bahwa kau tidak mungkin mau bertanggung jawab. Kau memang laki‐laki iblis. Tidak ada gunanya aku bersilat lidah padamu"
"Ah..., tidak kusangka. Ternyata aku juga harus berhadapan dengan manusia‐manusia yang culas licik," kata‐kata Bayu masih terdengar tenang.
"Kurang ajar! Kelakuanmu sudah kelewat batas. Anak Muda... Aku tidak pernah marah seperti ini, tapi kau telah memaksaku untuk menurunkan tangan,” Eyang Watuagung benar‐benar tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya.
"Sudah kuduga, kau pasti akan mencari‐cari alasan untuk menjadi penghalangku," kata Bayu kalem.
"Bersiaplah, Anak Muda Intan Delima akan senang melihat kepalamu tanpa leher" ancam Eyang Watuagung.
"Sadis..."
Eyang Watuagung menggeram hebat, lalu dengan cepat dia mengebutkan tangan kanannya ke depan. Seketika itu juga tampaklah tiga buah benda kecil bagai jarum yang berwarna keperakan, meluncur deras ke luar dari lengan bajunya yang longgar.
"Hup" Bayu segera memutar tangan kanannya ke depan, lan menyambut senjata‐senjata kecil itu tanpa menggeser kakinya sedikit pun.
Tring
Tiga buah jarum keemasan itu rontok begitu mem-bentur pergelangan tangan kanan Bayu yang menempel sebuah cakra bersegi enam berwarna keperakan. Pendekar Pulau Neraka itu berdiri tegak dengan tangan melipat di depan dada. Bibirnya menyunggingkan senyum bagai mengejek.
"Jangan besar kepala dulu, Anak Muda Tahan seranganku" bentak Eyang Watuagung. Laki‐laki tua berjubah putih itu langsung melompat, dan memberikan beberapa pukulan bertenaga dalam tinggi. Belum juga pukulannya sampai, namun anginnya sudah terasa menyengat. Bayu bergegas menggeser kakinya ke samping, dan memiringkan tubuhnya sedikit sambil mengibaskan tangannya dan nemapak serangan itu.
"Ikh" Eyang Watuagung tersentak kaget. Buru‐buru dia menarik kembali tangannya yang mendadak jadi kesemutan begitu beradu dengan tangan Pendekar Pulau Neraka. Bersamaan dengan itu Bayu juga melompat mundur dua tindak. Dia juga merasakan tangannya seperti remuk begitu berbenturan dengan tangan laki‐laki tua itu.
"Huh... Tenaga dalamnya benar‐benar luar biasa" dengus Eyang Watuagung mengeluh. Kini Eyang Watuagung tidak mau lagi gegabah. Dia kembali menyerang dengan penuh perhitungan dan hati‐hati.
Sedangkan Bayu sendiri segera melayaninya dengan sikap waspada. Dia sudah merasakan kalau tenaga dalam lawannya kali ini sangat dahsyat. Dan sebentar saja pertempuran di Kaki Lereng Gunung Panjaran itu sudah berlangsung dengan sengit. Masing-masing mengeluarkan jurus‐jurus andalannya.
DELAPAN
Pertarungan antara Bayu Hanggara dengan Eyang Watuagung terus berlangsung dengan sengit. Bagi Bayu, pertarungan dengan jarak dekat seperti ini, tidak memungkinkan untuk melontarkan senjata andalannya, yaitu cakra bersegi enam dan berwarna keperakan. Sedangkan Eyang Watuagung sudah mengeluarkan senjatanya yang berupa pedang pendek bercabang tiga. Menghadapi senjata genggam itu, Bayu terpaksa memegang Cakra Maut nya di tangan kanan. Sudah berpuluh‐puluh jurus yang telah mereka keluarkan namun belum ada tanda‐tanda mana yang bakal terdesak. Sedangkan tempat di sekitar pertarungan sudah porak‐poranda. Bahkan meluas sampai ke daerah yang berjurang serta berbatu‐batu cadas yang besar dan tajam.
Tring
Mendadak satu benturan senjata keras terjadi udara. Tampak percikan bunga api memijar. Dua orang yang tengah bertarung itu saling terpental ke belakang, dan jatuh bergulingan di tanah. Namun dengan cepat mereka segera bangkit, dan kembali berlompatan saling menyerang.
"Hup Hiaaa..." Tiba‐tiba dengan satu teriakan nyaring melengking, Bayu melontarkan senjata Cakra Maut‐nya sambil melompat dan mengirimkan dua buah pukulan dahsyat yang bertenaga dalam sangat tinggi.
"Ikh" Buru‐buru Eyang Watuagung memiringkan tubuhnya menghindari serangan yang bertubi‐tubi itu. Dan dia berhasil mengelakkan senjata yang meluncur deras bagai memiliki mata itu. Namun satu gebrakan dari pukulan yang bertenaga dalam, tidak bisa dihindarkan. Seketika Eyang Watuagung terlontar sejauh tiga batang tombak. Namun dia masih sempat mengibaskan pedangnya yang bercabang tiga.
"Hugh"
"Akh..."
Bayu Hanggara terhuyung tiga langkah ke belakang. Darah mengucur deras dari bahu kirinya yang sobek tersambar ujung pedang Eyang Watuagung. Namun dengan cepat dia mengangkat tangan kanannya, dan menangkap senjata Cakra Maut nya yang kembali berbalik
"Hiya..." Dan bagaikan kilat, Pendekar Pulau Neraka itu melemparkan kembali senjata mautnya di saat tubuh Eyang Watuagung sedang limbung. Tak pelak lagi, lontaran yang cepat disertai pengerahan tenaga dalam sempurna, tidak dapat dihindarkan lagi. Perut orang tua itu sobek tergores ujung cakra yang melayang bagaikan kilat itu.
"Akh..." Eyang Watuagung menjerit keras. Tubuh tua itu terhuyung‐huyung beberapa langkah ke belakang. Untunglah dengan cepat dia mampu menguasai tubuhnya kembali. Dan tanpa mempedulikan darah yang mengucur dari perutnya, Eyang Watuagung segera menghentakkan kedua tangannya ke depan. Seketika itu juga satu desiran angin yang amat dahsyat meluncur bagai topan, dan menghajar tubuh Pendekar Pulau Neraka yang baru saja menangkap senjatanya kembali
"Hiya... Hiyaaa"
Buru‐buru Bayu Hanggara melentingkan tubuhnya sambil membalas dengan dua kali pukulan jarak jauh bertenaga dahsyat. Namun deburan angin topan yang menggemuruh dahsyat sudah keburu menghantam tubuhnya. Kini tubuh Pendekar Pulau Neraka terpelanting deras ke udara, lalu dengan cepat meluruk ke bawah dan langsung masuk ke dalam jurang yang menganga lebar.
"Aaakh..." Jeritan melengking terdengar menyayat bersamaan dengan meluncurnya tubuh Bayu ke dalam jurang yang besar dan dalam itu. Eyang Watuagung bergegas memburu, dan berdiri di tepi jurang. Tangan kirinya terus menekap perutnya yang sobek dan mengucurkan darah segar.
"Hhh... Luar biasa anak itu. Entah apa yang akan terjadi pada dunia persilatan kalau dia masih hidup," Eyang Watuagung mengeluh dalam hari. Sejenak laki‐laki berjubah putih itu menjulurkan kepalanya ke dalam jurang. Tak tampak apa pun di dalam sana. Seluruh permukaan jurang itu tertutup kabut tebal yarig menghalangi pandangan mata.
"Ugh Hoaaak..." Eyang Watuagung memuntahkan darah kental kehitaman. Buru‐buru dia merobek baju bagian dalamnya. Mendadak kedua matanya membeliak lebar begitu melihat gambar tapak tangan hitam tertera di dadanya. "Pukulan Racun Hitam... " desisnya terkejut. "Ugh Ada hubungan apa dia dengan Gardika. .?"
Eyang Watuagung buru‐buru duduk bersila. Sebentar kemudian matanya terpejam. Tampak keringat sebesar-besar butiran jagung menitik di keningnya. Lalu dia membuka matanya kembali. Lagi‐lagi dia memuntahkan darah kental kehitaman.
"Aku harus segera kembali ke Pesanggrahan. Racun hitam ini bisa membunuhku secara pelahan‐lahan. Gila Kenapa aku tidak menyadari kalau jurus‐jurusnya sama dengan Gardika si Cakra Maut Dan lagi..., senjata itu... Huh! Untung saja aku berhasil membunuhnya, kalau dia sampai masih hidup beberapa tahun lagi..., aku tidak tahu lagi, bagaimana keadaan dunia persilatan. Sulit mencari tandingan jurus‐jurus si Cakra Maut. Ugh... Ugh"
Eyang Watuagung segera bangkit dari duduknya, kemudian melangkah cepat dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah mencapai taraf kesempurnaan. Beberapa kali dia masih menyemburkan darah kental kehitaman dari mulutnya. Namun semua itu tidak dihiraukan lagi. Hanya satu yang kini ada dalam pikirannya, dia harus segera sampai ke pesanggrahannya, dan mengurangi pengaruh racun hitam. Paling tidak, hidupnya bisa diperpanjang lagi sampai dia bisa mewariskan seluruh ilmunya pada Intan Delima.
********************
Tapi, benarkah Bayu Hanggara atau Pendekar Pulau Neraka tewas di dasar jurang yang dalam itu? Yang Kuasa rupanya belum menginginkan Pendekar Pulau Neraka meninggalkan dunia. Tubuhnya tidak langsung jatuh ke dasar jurang. Sebatang akar pohon besar yang menyembul dari dalam tanah di bibir jurang, menyanggah tubuhnya. Beberapa saat lamanya Bayu tidak sadarkan diri. Dan begitu dia siuman, seluruh tubuhnya terasa nyeri dan tulang‐tulangnya seperti mau rontok semua.
Bayu tampak terkejut begitu menyadari tubuhnya tersangkut pada sebatang akar yang cukup besar dan kuat. Dan sambil menahan nyeri pada seluruh tubuhnya, dia kemudian merayap dan berusaha mencapai tepi tebing jurang ini. Sejenak kepalanya menengadah ke atas. Tak terlihat apa pun, hanya kabut tebal yan menghalangi pandangan matanya.
"Huh..." Bayu mendengus sambil menghembuskan napasnya. Lalu dia duduk pada pangkal pohon yang berongga besar. Kembali matanya memandang berkeliling. Sepanjang matanya memandang, yang tampak hanya kabut dengan bayang bayang pohon menyemaki tebing jurang. Pemuda itu kemudian mengatur duduknya untuk bersemadi menyalurkan hawa murni ke seluruh aliran darahnya. Dia berusaha membuka jalan darahnya agar sempurna. Kini rasa hangat mulai menjalari tubuhnya, dan rasa nyeri serta pegal‐pegal berangsur hilang. Namun bibirnya menyeringai dan mendesis. Bayu segera menyobek kain merah yang membelit pinggangnya. Dan dengan kain itu dia kemudian membalut luka di bahunya. Jari‐jari tangannya bergerak lincah di sekitar luka, menghentikan aliran darahnya. Sejenak dia menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya lagi dengan kuat.
"Hhh Orang tua itu benar‐benar hebat. Apakah muridnya juga setangguh dia?" Bayu bergumam sendiri. "Aku harus segera ke luar dari jurang ini. Tengah malam nanti adalah saatnya pertarungan. Uh Luka ini..."
Pelahan‐lahan Bayu ke luar dari rongga pohon itu. Kemudian mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Pendekar Pulau Neraka itu mulai merayap mendaki tebing jurang. Kabut tebal masih menghalangi pandangannya, ditambah dengan hembusan angin kencang yang membuat usahanya itu agak terhambat. Sedikit demi sedikit dia mulai merayap mendaki, hingga akhirnya sampailah dia di bibir jurang.
Saat itu hari sudah menjelang senja. Di ufuk Barat matahari hampir tenggelam, berganti dengan kegelapan. Sementara udara di sekitar Lereng Gunung Panjaran itu juga sudah terasa dingin. Bayu menggelimpangkan tubuhnya ke atas rerumputan yang sudah basah oleh embun. Penat dan letih melanda tubuhnya. Sejenak dia memejamkan matanya sebelum bangkit berdiri.
"Seandainya aku harus bentrok lagi dengan orang tua itu, aku pasti akan bisa mengalahkannya. Racun hitam yang kulepaskan sudah pasti merasuk ke dalam darahnya. Hhh..., 'Pukulan Angin Badainya benar‐benar luar biasa," lagi lagi Bayu bergumam sendiri. Perlahan‐lahan Pendekar Pulau Neraka itu melangkah menuruni Lereng Gunung Panjaran.
"Masih ada sedikit waktu, aku harus bersemadi dulu untuk memulihkan kekuatan," gumam Bayu.
Kemudian Pendekar Pulau Neraka itu memilih tempat di antara dua buah batu besar yang agak tersembunyi. Kemudian dia duduk bersila dengan sikap bersemadi. Kakinya terlipat dengan kedua telapak tangan menempel pada lutut. Pelahan‐lahan napasnya mulai diatur bersamaan dengan menutupnya kedua kedua kelopak matanya. Bagi dunia kependekaran, cara memulihkan kondisi tubuh dengan bersemadi bukanlah hal yang aneh lagi. Dan inilah yang tengah dilakukan oleh Bayu Hanggara.
********************
Malam terus merayap semakin larut. Suasana di Istana Kadipaten Jati Anom tampak sunyi senyap. Hanya ada dua orang yang teriihat duduk di bagian depan bangunan istana itu. Mereka adalah Adipati Rakondah dan Panglima Bantaraji Sejak matahari tenggelam tadi mereka sudah berada di sana. Sejak tadi mereka hanya diam. Masing‐masing sibuk dengan pikirannya. Semakin larut malam, kesunyian semakin terasa mencekam. Detak jantung mereka semakin jelas terdengar berdegup kencang.
"Apa kau tidak salah lihat siang tadi, Kakang?" tanya Adipati Rakondah memecah kesunyian
"Maksudmu?" Panglima Bantaraji balik bertanya.
"Yang kau lihat di Lereng Gunung Panjaran."
"Tidak... Jelas sekali aku lihat Pendekar Pulau Neraka jatuh ke dalam jurang setelah kena 'Pukulan Angin Badai' Eyang Guru," kata Panglima Bantaraji yakin.
"Hm..., malam sudah larut. Kalau dia tidak datang, berarti tamat sudah riwayatnya," gumam Adipati Rakondah.
"Ya, mudah‐mudahan dia tewas di dasar jurang," sambut Panglima Bantaraji.
"Sebenarnya aku tidak tega melepas Eyang Guru pulang sendirian, Kakang. Beliau dalam keadaan terluka cukup parah. Aku benar‐benar menyesali semua ini," nada suara Adipati Rakondah seolah mengeluh.
"Sudahlah, Adik Rakondah. Saat ini kita hanya bisa berharap, semoga ..." Kata‐kata Panglima Bantaraji terputus.
Saat itu terdengar suara siulan nyaring melengking menyakitkan telinga. Siulan itu menggema seolah‐olah datang dari segala penjuru mata angin. Jelas kalau suara itu dikeluarkan dengan disertai penyaluran tenaga dalam yang sangat sempurna.
Adipati Rakondah dan Panglima Bantaraji langsung melompat ke luar. Dan hanya dengan sekali lentingan tubuh saja, mereka sudah berada di tengah‐tengah halaman depan yang luas dan sunyi. Sementara suara siulan itu semakin jelas dan menyakitkan telinga. Kedua laki‐laki bersaudara itu segera mengerahkan hawa murni, dan menyalurkannya ke seluruh aliran jalan darah. Terutama menutup gendang telinga mereka.
"Dia datang...," desis Panglima Bantaraji.
Adipati Rakondah menatap kakaknya dengan tajam. Dan belum lagi mereka sempat melakukan sesuatu, tiba‐tiba sebuah bayangan berkelebat cepat bagai kilat melewati tembok benteng Istana Kadipaten Jati Anom.
"Pendekar Pulau Neraka..." sentak kedua laki‐laki itu hampir berbarengan.
Kini di depan mereka telah berdiri seorang laki‐laki muda, gagah dan tampan. Laki‐laki yang ternyata adalah Bayu itu berdiri tegak dengan tangan melipat di depan dada. Tatapan matanya tajam, langsung menusuk ke bola mata Adipati Rakondah. Sekejap saja ketegangan menyelimuti mereka semua.
"Engkau pasti sudah memahami tanda dariku, Adipati Rakondah. Tanda itu boleh kau anggap sebagai lambang kematian bagimu. Kini saatnya sudah tiba, bersiaplah menuju ke neraka..." dingin dan datar suara Bayu Hanggara.
"Kakang, menyingkirlah," kata Adipati Rakondah tanpa menoleh sedikit pun.
"Hati‐hati, Adik Rakondah," kata Panglima Bantaraji seraya melangkah mundur beberapa tindak.
"Pendekar Pulau Neraka. Mari kita mulai. Hait...!"
"Hup..."
Srettt!
Adipati Rakondah mencabut pedangnya seraya melompat menerjang. Gerakannya sangat cepat dan ringan, sedangkan kibasan pedangnya menimbulkan suara angin yang amat dahsyat.
Sejenak Bayu menunggu, lalu dengan cepat dia menghentakkan tangannya ke depan. Seketika secercah cahaya keperakan melesat dari pergelangan tangan kanannya. Begitu cepatnya, sehingga Adipati Rakondah tidak sempat lagi untuk menarik pedangnya. Dan....
Tring!
"Ah..." Adipati Rakondah terkejut bukan main.
Satu benturan keras langsung terjadi antara dua logam, sampai menimbulkan percikan api. Tampak pedang di tangan Adipati Rakondah bergetar hebat. Untung dia cepat‐cepat menekan ujung pedangnya ke tanah, sehinga pegangannya tidak terlepas.
Kini Bayu kembali melompat sambil menjulurkan tangan kanannya ke atas. Dan benda pipih bergerigi enam yang berwarna keperakan itu menempel kembali di pergelangan tangan kanannya. Dengan manis sekali kakinya kembali menjejak tanah. Tapi tiba‐tiba dia mengebutkan tangannya lagi ke depan.
"Awas..." Panglima Bantaraji berteriak nyaring. Dan secepat kilat dia merogoh ke balik bajunya, dan melontarkan sebilah pisau kecil ke arah cakra itu.
Sedangkan Adipati Rakondah yang belum hilang rasa terkejutnya, jadi terperangah. Satu jengkal lagi cakra itu pasti menembus dadanya. Namun beruntung pisau yang dilemparkan oleh Panglima Bantaraji mematahkan serangan Pendekar Pulau Neraka itu. Dan cakra keperakan bergerigi enam itu kembali berputar balik pada pemiliknya.
"Huh" dengus Bayu kesal.
Panglima Bantaraji melompat ke samping adiknya. Tampak di tangan kirinya sudah tergenggam seutas rantai baja hitam dengan ujungnya terpaut lima buah pisau kecil. Dia juga sudah melepaskan baju luarnya. Tampak di seputar pinggang dan dadanya dipenuhi oleh pisau‐pisau kecil yang menempel pada kulit binatang.
"Kau tidak akan mampu menghadapinya sendiri, Adik Rakondah. Senjatanya sangat berbahaya," kata Panglima Bantaraji berbisik.
"Bagus! Aku bisa mengirim kalian ke neraka sekaligus" dengus Bayu.
Adipati Rakondah melemparkan pedangnya. Kemudian dia membuka baju luarnya. Bayu agak terkejut juga melihat kedua lawannya memiliki senjata yang sama persis. Tubuh mereka penuh tertempel pisau‐pisau kecil. Dan di tangan mereka juga tergenggam senjata rantai baja dengan lima pisau di ujungnya. Sebuah rantai hitam yang panjangnya hanya satu hasta.
"Seribu Pisau Terbang..." seru Panglima Bantaraji. Secepat dia berteriak, secepat itu pula tubuhnya melenting ke udara, dan tahu‐tahu sudah berada di belakang Pendekar Pulau Neraka. Dan belum lagi Bayu sempat menyadari, kedua laki‐laki itu sudah mengibaskan tangannya dengan cepat. Tampak puluhan pisau-pisau kecil bertebaran mengarah ke tubuhnya.
"Hup Hiyaaa..." teriak Bayu nyaring. Seketika Pendekar Pulau Neraka itu memutar tubuhnya dengan cepat. Dan senjata Cakra Maut andalannya yang sudah tergenggam di tangan kanan, dia lepaskan untuk menghalau pisau‐pisau yang meluncur deras ke arah tubuhnya. Tampak kedua kakinya juga bergerak lincah, berlompatan, dan tubuhnya meliuk‐liuk bagai belut menghindari hujan pisau dari dua jurusan itu. Bayu sempat menggeram begitu melihat lawannya bergerak memutari tubuhnya. Dan anehnya lagi, mereka bisa saling bertukar senjata yang terlontar hanya dengan menjentikkan ujung jarinya saja. Pisau-pisau itu benar‐benar bagaikan berjumlah ribuan, bertebaran di sekitar tubuh Pendekar Pulau Neraka itu.
"Hhh Serangan mereka hanya satu arah. Aku harus bisa membuatnya pincang," dengus Bayu dalam hati. Matanya yang tajam dan sudah terlatih, langsung dapat melihat kelemahan lawannya. Dan tanpa membuang‐buang waktu lagi, tubuhnya segera melenting ke udara. Lalu dengan cepat tangan kanannya mengibas ke arah Adipati Rakondah. Seketika itu juga senjata cakra bergerigi enam meluruk deras.
Adipati Rakondah terkesiap sesaat, dan serangannya jadi tidak beraturan. Bayu tidak menyia‐nyiakan kesempatan itu, dengan cepat dia meluruk turun ke arah Panglima Bantaraji. Kedua tangannya bergerak cepat dan melontarkan 'Pukulan Rancun Hitam'. Tentu saja hal itu membuat Panglima Bantaraji jadi terkejut setengah mati. Buru-buru dia menjatuhkan dirinya dan bergulingan di tanah.
Sementara itu Adipati Rakondah tengah sibuk menghalau Cakra Maut Pendekar Pulau Neraka yang bergerak sendiri seperti memiliki mata. Dan Bayu kini terus mencecar Panglima Bantaraji dengan serangan-serangan mautnya. Mendadak tangan kanannya terangkat ke atas, menerima senjatanya yang berbalik, kembali, lalu dengan cepat dia segera menghentakkannya ke arah Adipati Rakondah.
"Awas kepala" tiba‐tiba Bayu berteriak nyaring.
"Uts" Buru‐buru Panglima Bantaraji merundukkan kepalanya sedikit begitu melihat tangan kanan Bayu meluruk ke arah kepalanya. Namun tanpa diduga sama sekali, kaki kiri Pendekar Pulau Neraka sudah terangkat naik, dan dengan kecepatan penuh menghentak ke arah perut.
"Hugh" Panglima Bantaraji mengeluh pendek. Tubuhnya membungkuk menahan mual pada perutnya. Dan pada saat itu senjata cakra yang menyerang Adipati Rakondah segera berbalik dan berputar pada pemiliknya. Dengan cepat Bayu menangkap senjata itu, dan secepat itu pula dia melontarkannya kembali ke arah Panglima Bantaraji.
"Aaakh..." Panglima Bantaraji menjerit melengking. Ujung‐ujung Cakra Maut itu langsung menggorok lehernya hingga hampir buntung. Dan hanya dengan satu kali tendangan keras, tubuh Panglima Bantaraji terjungkal dengan leher berlumuran darah seperti ayam yang disembelih
"Kakang..." pekik Adipati Rakondah terkesiap.
"Sekarang giliranmu, Adipati Rakondah" dengus Bayu.
"Setan! Kau harus bayar mahal nyawa Kakang Bantaraji" geram Adipati Rakondah. "Hiyaaa..."
"Pukulan Racun Hitam... Hup, yeaaah..."
"Akh" Adipati Rakondah memekik tertahan, tubuhnya limbung dengan tangan menekan dada.
Sementara itu Bayu juga langsung melompat mundur dua tindak kebelakang. Tangan kirinya menekan lambung. Dan darah mengucur deras dari lambungnya. Ternyata ujung senjata Adipati Rakondah berhasil merobek lambung Pendekar Pulau Neraka itu, tapi 'Pukulan Racun Hitam' juga bersarang di dada Adipati Rakondah.
"Hugh. Hoaaak..." Adipati Rakondah memuntahkan darah kental kehitaman.
"Ah..." Bayu mengeluh sedikit.
Mendadak Pendekar Pulau Neraka itu merasakan tubuhnya jadi panas bagai terpanggang. Sedangkan matanya agak menyipit begitu melihat darah yang mengucur dari lambungnya berwarna kehitaman. Dia sadar kalau senjata Adipati Rakondah mengandung racun yang sangat berbahaya. Sejenak dia memandang lawannya yang sedang berusaha menguasai diri dari pengaruh 'Pukulan Racun Hitam'.
"Mampus kau, Adipati Rakondah" bentak Bayu lantang. Dan bagaikan seekor singa yang terluka, secepat kilat Bayu berlari sambil mengerahkan seluruh tenaga dalamnya pada telapak tangan.
Sesaat Adipati Rakondah terkesiap namun dengan cepat dia melentingkan tubuhnya ke atas. Tapi sungguh di luar dugaan, tubuh Bayu juga langsung melenting. Dan secepat kilat tangan kanannya mengibas ke depan. Secercah cahaya keperakan meluncar deras ke arah tubuh Adipati Rakondah.
Tring!
Adipati Rakondah berhasil menghalau senjata cakra itu, namun dia tidak sempat berkelit dari pukulan tangan kiri Pendekar Pulau Neraka. Dan sambil meraung keras, tubuh adipati itu meluruk jatuh ke tanah. Tepat pada saat itu Bayu menangkap senjatanya yang balik lagi, dan dengan cepat dia melontarkannya kembali ke arah lawan.
"Hiyaaa..."
"Aaakh..." Kembali jeritan melengking tinggi terdengar menyayat. Cakra Maut Pendekar Pulau Neraka itu tertanam dalam di dada Adipati Rakondah. Dan bersamaan dengan mendaratnya Bayu di tanah, tubuh Adipati Rakondah tampak mengejang kaku tanpa nyawa lagi.
"Ayah, Ibu..., satu lagi musuhmu telah terbalaskan," desah Bayu seraya mencabut senjatanya dari dada Adipati Rakondah. Kemudian Bayu memasang kembali senjatanya di pergelangan tangan kanan, setelah membersihkannya, dari noda‐noda darah. Untuk beberapa saat, pemuda itu masih berdiri sambil memandangi Adipati Rakondah yang terbujur kaku tanpa nyawa lagi.
Bayu tidak menyadari kalau ada sepasang mata bening memperhatikannya sejak tadi. Pendekar Pulau Neraka itu terus berjalan pelan‐pelan menuju ke arah Timur.
"Eyang Watuagung harus tahu...," terdengar gumaman pelan setelah bayangan tubuh Bayu lenyap dari pandangan.
Nah, bagaimana sikap Eyang Watuagung setelah mengetahui muridnya tewas? Percayakah dia kalau Pendekar Pulau Neraka masih hidup? Lalu bagaimana pula sikap Intan Delima pada pemuda yang telah membunuh orang tuanya dan sekaligus telah merenggut kegadisannya? Untuk lebih jelas, ikutilah kisah Pendekar Pulau Neraka dalam episode Cinta Berlumur Darah.
S E L E S A I
