TEROR TOPENG MERAH
SATU
BEBERAPA anak muda tengah bergelak ria di penginapan dan kedai Bunga Nirwana yang terletak di pusat kota Kadipaten Lawang. Di meja merah, tersaji beberapa bumbung arak dan ayam bakar. Salah seorang yang paling menonjol adalah pemuda berbaju sutera warna biru. Dia duduk dikelilingi empat orang pemuda lain yang rata-rata berusia sebaya. Agaknya, pemuda berbaju biru itu yang membayari seluruh makanan dan minuman yang tersaji di meja.
“Ayo Jliteng, Jenar, Bagus, dan kau Ragil! Kita minum sampai puas!” teriak pemuda berpakaian biru sambil mengacungkan cawan. Dan seketika ditenggaknya arak sampai tandas.
Perbuatan pemuda itu diikuti keempat kawannya. Kemudian mereka tergelak-gelak bersama-sama. Dan kembali menenggak arak entah yang keberapa kali.
Belum habis gelak tawa mereka, seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun yang sejak tadi berada di luar mendadak masuk ke dalam. Dan dia langsung berdiri di belakang pemuda berbaju biru dengan wajah cemas.
“Den Kamajaya telah banyak minum. Sebaiknya berhenti dulu. Kalau sampai mabuk, tentu Juragan Prajawasita akan menyalahkanku,” kata laki-laki di belakang pemuda berbaju biru, sambil mendekatkan kepalanya.
“Diam kau, Sompak!” bentak pemuda berbaju biru yang bernama Kamajaya, membuat laki-laki yang dipanggil Sompak terjingkat mundur. “Beraninya kau mengurusi aku? Tempatmu di luar sana! Pergilah! Aku bukan anak kecil yang harus terus diawasi!”
“Tapi, Den....”
Kamajaya menoleh, lalu.... “Pergi kataku!” bentak Kamajaya lagi dengan mata melotot lebar.
Kali ini pemuda berbaju biru itu betul-betul marah. Dan Sompak tidak berani lagi mengganggunya. Dengan tubuh gemetar ketakutan dan wajah pucat, buru-buru dia angkat kaki dari sisi majikannya.
“Ayo, lanjutkan kawan-kawan! Kita minum sampai pagi!” teriak Kamajaya sambil mengajak bersulang.
Keempat laki-laki yang menemani Kamajaya langsung menyambut dengan sulangan pula, disertai tawa terkekeh lebar. Seakan-akan mereka sudah tak peduli dengan sekitarnya. Sehingga tanpa disadari, seseorang telah berkelebat dari pintu kedai, lalu berdiri tegak tanpa berkata apa-apa di belakang Kamajaya.
“Kau cucu si Jayeng Rono?” usik sosok yang berdiri di belakang Kamajaya.
“Heh?!” Kamajaya tersentak. Dia tersinggung bukan main, karena ada orang seenaknya saja memanggil kakeknya tanpa sebutan penghormatan. Padahal semua orang di Lawang amat menghormati kakeknya. Mereka memperlakukannya seperti seorang raja kecil. Maka dengan mendelik gusar, pemuda berbaju biru ini menoleh.
“Hei?!” Alangkah gelinya Kamajaya melihat orang yang tegak berdiri di dekatnya ternyata memakai topeng merah terbuat dari kayu. Bentuk topeng itu demikian garang dan sedikit menakutkan, tapi bagi Kamajaya justru menggelikan. Sehingga tanpa sadar bibirnya melebar tersenyum-senyum.
“Kisanak! Kukira tadi kau sungguh-sungguh akan membuat ribut. Tapi, siapa sangka kau ternyata hanya seorang badut. He he he...! Duduklah! Aku senang ditemani orang sepertimu!” ujar Kamajaya.
Sulit dilihat, bagaimana tampang orang bertopeng itu. Tapi untuk sesaat dia diam saja tak menjawab. “Siapa sudi minum bersama keturunan pengecut sepertimu!” ucap orang bertopeng itu dingin, begitu tawa Kamajaya terhenti.
“He, apa maksud kata-katamu?!” sentak Kamajaya.
“Tidak usah berpura-pura, Tolol! Kaulah yang kumaksud!” tuding orang bertopeng merah itu.
Mendengar tuduhan itu, wajah manis Kamajaya kembali berubah geram. Amarahnya berkobar cepat Dan seketika dia berdiri dengan sikap digagah-gagahkan, meski kepalanya berdenyut sakit akibat menenggak arak terlalu banyak.
“Kurang ajar kau! Berani benar kau menyebutku keturunan pengecut?!” bentak Kamajaya garang, seraya mengibaskan tangan kanannya.
Wut!
Kamajaya sebenarnya bukanlah pemuda yang tidak tahu apa-apa soal ilmu silat. Dia cucu tertua Ki Jayeng Rono yang di kalangan rimba persilatan bergelar Macan Terbang. Dan selama ini Kamajaya cukup mendapat gemblengan dari kedua orangtua serta kakeknya. Meski dalam keadaan mabuk, rasanya masih sanggup menghadapi lima pemuda sebayanya.
Tapi, kali ini Kamajaya kena batunya. Orang bertopeng itu hanya sedikit berkelit ke samping, maka pukulannya menghantam angin. Dan tahu-tahu, pukulan balasan menghajar perutnya.
Desss...!
“Aaakh...!” Kamajaya terjungkal ke belakang, langsung menghantam meja lain yang tengah dipakai orang.
“Keparat!” umpat Kamajaya tak karuan, seraya bangkit berdiri.
Sementara empat orang kawan Kamajaya juga kelihatan gusar. Mereka tahu betul, siapa Kamajaya. Dia adalah anak keluarga terhormat. Dan menurut mereka, perlakuan orang bertopeng merah itu sungguh kelewatan.
“Bangsat tak tahu diri! Apa yang telah kau lakukan terhadap cucu orang paling terhormat di daerah ini?!” bentak Jliteng sambil menuding sinis.
“Monyet buduk! Jangan ikut campur urusan ini! Lebih baik tutup mulut. Dan pergilah kalian sebelum mendapat hajaran serupa!” balas orang bertopeng itu tidak kalah garang.
Mendengar sahutan yang membuat merah telinga, bukan main geramnya Jliteng. Maka tanpa basa-basi lagi segera goloknya yang terselip di pinggang dicabut.
Sret!
“Manusia tak tahu diri memang perlu sesekali mendapat hajaran supaya mengerti bagaimana bersikap sopan!” bentak Jliteng seraya melompat sambil menebas leher.
Tapi orang bertopeng itu kelihatan tenang-tenang saja. Bahkan memperdengarkan tawa mengejek. Namun ketika beberapa rambut lagi mata golok yang berkilatan itu mendarat di sasaran, dia memiringkan tubuhnya sedikit Maka, tebasan golok Jliteng hanya mengenai tempat kosong. Dan tiba-tiba orang bertopeng itu menghajar pergelangan tangan Jliteng.
Tak!
“Aaakh...!” Jliteng kontan menjerit tertahan. Pergelangan tangannya yang terpapak tadi terasa sakit bukan main. Mungkin tulangnya patah. Goloknya terlepas dari genggaman. Dan belum juga dia bisa berbuat apa-apa, satu tendangan menyamping berisi tenaga dalam tinggi telah meluncur deras. Lalu....
Begkh!
“Aaakh...!” Disertai jeritan kesakitan, Jliteng terjungkal kesamping, menabrak meja makan lainnya.
“Huh! Penjilat busuk! Apa kau kira harga dirimu akan terangkat dengan cara menjilat? Kau hanya seekor anjing. Dan meski berkawan dengan seekor menjangan, tetap saja anjing!” dengus orang bertopeng itu.
Melihat Jliteng jatuh terjungkal, tiga pemuda yang lain tidak mau tinggal diam. Serentak mereka menghunus golok dengan wajah garang.
“Bangsat terkutuk! Berani benar kau menghajar kawan kami!” bentak Jenar.
“Apa?! Kalian pun mau ikut-ikutan? Boleh! Ayo! Maju ke sini, anjing-anjing buduk. Biar kuberi pelajaran, betapa tidak enaknya menjadi penjilat!” hardik orang bertopeng itu, tersenyum dingin.
Kelihatannya orang bertopeng itu begitu memandang enteng. Sebaliknya ketiga pemuda itu tidak mau gegabah. Jliteng adalah orang yang paling tinggi kepandaiannya diantara mereka. Kalau sampai dijatuhkan dengan mudah, maka apalah artinya mereka? Tapi ketiganya masih bisa berbesar hati dengan jumlah yang lebih banyak. Maka Jenar segera mengatur Bagus dan Ragil untuk menyergap dari samping kiri dan kanan.
“Yeaaa...!” Disertai bentakan nyaring dari Jenar sebagai isyarat penyerangan, mereka bertiga melompat menerkam.
Namun gerakan yang ditunjukkan orang bertopeng merah itu sungguh menakjubkan. Seperti terangkat, tubuhnya melesat ke atas sambil menendang silih berganti ke arah ketiga lawannya.
Dess! Dess! Desss!
“Aaakh...!”
Kembali terdengar tiga jeritan berturut-turut, yang diikuti ambruknya Jenar, Bagus, dan Ragil.
Melihat lawan-lawannya terjungkal, orang bertopeng itu tenang-tenang saja melangkah meninggalkan rumah makan ini. Sementara melihat hal ini, mana mau Kamajaya mendiamkannya saja. Dia yang masih terduduk bangkit. Langsung dikejarnya orang bertopeng itu, walaupun masih sempoyongan.
“Mau pergi ke mana kau, Keparat?! Tinggalkan kepalamu baru boleh pergi seenak perutmu!” bentak pemuda itu.
Orang bertopeng itu melompat beberapa kali sehingga semakin menjauhi penginapan dan kedai Bunga Nirwana. Orang-orang yang melihat mendecah kagum, namun tidak ada yang berani menolong Kamajaya. Bahkan Jenar, Bagus, Ragil, dan Jliteng agaknya jera juga setelah mendapat hajaran dari orang bertopeng. Mereka hanya memperhatikan kepergian orang bertopeng.
Namun, ternyata orang bertopeng itu tidak benar-benar pergi. Sekitar sepuluh tombak dari penginapan itu, dia berhenti dan berdiri tegak seperti menanti Kamajaya yang mengejar.
Melihat orang bertopeng itu berhenti, Kamajaya mendengus dingin. Matanya memandang penuh kemarahan. Bukannya tampak garang, justru Kamajaya malah seperti orang mengantuk akibat terlalu banyak menenggak arak.
“Akhirnya kau menyerah juga, he? He he he...! Bagus! Kau mengerti kalau aku tidak bisa dibuat main-main, bukan?” kata Kamajaya, begitu berada sekitar dua tombak di depan orang bertopeng merah ini.
Orang bertopeng itu sama sekali tidak menggubris ocehan Kamajaya. Tapi ketika pemuda berbaju biru ini telah mendekat, sebelah kakinya bergerak cepat menyapu pinggang. Cepat bagai kilat, Kamajaya mengibaskan tangannya, menangkis.
Plak!
Tangan Kamajaya yang berhasil menangkis terhempas. Dan tanpa diduga, kaki orang bertopeng itu bergerak ke pelipis.
Diegkh...!
“Aaakh...!” Pemuda berbaju biru itu terjungkal ke samping sambil mengeluh kesakitan. Pelipisnya yang jadi sasaran, biru dan membengkak akibat tendangan yang cukup keras tadi.
“Kurang ajar! Huh! Kau akan menyesal karenanya!” maki Kamajaya seraya bangkit perlahan-lahan.
“Huh! Apa yang mesti kutakutkan darimu, Bocah Busuk? Bahkan kakek moyangmu sekalipun, aku tidak takut! Kau akan menjadi pelajaran serta peringatan terbaik bagi kakekmu!” dengus orang bertopeng itu, siap hendak menghajar kembali.
“Yeaaa...!” Kamajaya membentak sambil berkelebat. Pedangnya yang sudah tercabut langsung diputar-putar ke arah orang bertopeng. Meski bagaimanapun, anak muda ini hidup bergelimang harta dan betul-betul menikmatinya. Kerjanya hanya berfoya-foya serta mengejar-ngejar anak gadis orang. Lalu, berkumpul bersama kawan-kawannya yang mempunyai kesenangan sejenis. Sehingga perhatiannya terhadap ilmu olah kanuragan tidak begitu sungguh-sungguh. Maka, serangannya sama sekali tidak berarti bagi orang bertopeng itu.
“Hup!”
Begitu pedang yang berkilatan tertimpa sinar-sinar obor yang terpancang di tiap sudut penginapan itu mendekat, orang bertopeng ini cepat melenting ke atas. Dan tiba-tiba, tubuhnya meluruk turun seraya melepaskan tendangan dahsyat ke dada Kamajaya.
Duk!
“Aaakh...!” Kembali hajaran orang bertopeng itu telah menghantam dada Kamajaya yang kontan menjerit kesakitan. Dadanya seperti remuk mendapat tendangan keras tadi. Pemuda itu langsung terjungkal ke belakang.
“Ayo bangkit lagi, Bocah! Tunjukkan padaku kehebatan ilmu olah kanuragan keluargamu!” dengus orang bertopeng ini.
“Bangsat!”
Sebetulnya, Kamajaya sudah tidak kuat lagi untuk bertarung kembali. Kepalanya berdenyut-denyut karena kebanyakan menenggak arak. Tenaganya pun lemas sehingga tidak terlalu mampu bertarung dengan baik. Ditambah lagi, orang yang dihadapi agaknya bukan tokoh sembarangan. Paling tidak dengan cara melenting, akan kelihatan kalau orang bertopeng itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup hebat.
Namun Kamajaya sendiri amat tersinggung karena diejek sedemikian rupa. Selama ini, dia merasa mampu berbuat apa pun. Dengan pengaruh kakeknya ataupun dengan kemampuan ilmu olah kanuragan yang pas-pasan, tidak jarang dia melepaskan tangan kasar pada orang-orang yang tak disukainya. Hanya saja mereka yang menjadi korbannya merasa lebih baik tutup mulut kalau tidak ingin menderita yang lebih parah lagi kelak.
Sementara itu melihat majikannya jatuh bangun dihajar orang bertopeng, Sompak buru-buru menghampiri. Dia langsung berlutut, di hadapan orang bertopeng itu.
“Kisanak, ampunilah majikanku! Mungkin dia suka usil, tapi sesungguhnya bukan orang jahat...!” ratap Sompak.
“Minggir kau, Sompak!” dengus Kamajaya yang sudah bangkit berdiri dan berjalan ke arah Sompak. Bahkan tiba-tiba kakinya terayun kearah Sompak.
Dess...!
“Aaakh...!” Sompak mengeluh kesakitan dihajar majikannya yang tengah kalap.
“Huh! Kau mewarisi watak tidak berbudi dari kakekmu!” dengus orang bertopeng itu.
“Aku tidak peduli khotbahmu! Yang kuinginkan hanya kepalamu!” desis Kamajaya seraya melepas tendangan ke dada.
Orang bertopeng itu bergerak ke kanan. Tubuhnya langsung berputar cepat, lalu melayangkan sodokan keras ke dada dan muka.
Begkh! Des! Duk!
“Aaakh...!”
Tiga kali berturut-turut hantaman orang bertopeng menghajar dada, lalu pipi kiri dan kanan, membuat Kamajaya terpekik. Tubuhnya terjungkal roboh tak berdaya dengan darah segar muncrat dari mulut.
“Ini peringatan bagi kakekmu! Katakan padanya, dia akan mendapat kunjungan saudara angkatnya nanti!” dengus orang bertopeng itu, lalu berkelebat meninggalkan Kamajaya.
********************
DUA
Semua orang yang tinggal di Kadipaten Lawang tahu, di lereng Gunung Arjuna pada bagian sebelah timur terdapat dataran yang agak luas, terdapat sebuah perkampungan yang dihuni sanak saudara Ki Jayeng Rono. Seorang tokoh silat dengan kepandaian cukup tinggi.
Orang tua yang tahun ini genap berusia tujuh puluh tahun ini dalam rimba persilatan dikenal berjuluk si Macan Terbang. Namun belakangan ini namanya dikenal sebagai hartawan kaya raya di seluruh Kadipaten Lawang. Bahkan sebagian orang merasa yakin kalau Ki Jayeng Rono merupakan orang terkaya di kadipaten ini.
Hari ini, di rumah Ki Jayeng Rono yang tampak megah, terlihat kesibukan yang lumayan besar. Pasalnya, laki-laki tua itu hendak mengadakan hajat perkawinan cucunya yang bernama Rajapadmi, dengan cucu seorang tokoh terkenal dan disegani di dunia persilatan. Konon nama pemuda itu Jaka Tawang, cucu Ki Sendrogowo yang di rimba persilatan dikenal sebagai Serigala Berbulu Hitam.
Kali ini Ki Jayeng Rono yang semula begitu gembira menyambut pesta perkawinan ini, apalagi beliau yang menjodohkan, kelihatan bersedih selama dua hari belakangan ini. Orang tua itu lebih suka mengurung diri di kamarnya, sementara yang lain menyiapkan segala sesuatu untuk kelangsungan hajat Dan ini, agaknya tidak luput dari perhatian Rajapadmi.
“Ada apa, Rajapadmi?” tanya Ki Jayeng Rono, ketika seorang gadis cantik berambut panjang memasuki kamar ini.
Gadis bernama Rajapadmi tidak langsung menjawab. Dia tampak ragu-ragu, dan sesekali memandang wajah eyangnya.
“Aku justru hendak menanyakan itu pada Eyang...,” kata Rajapadmi, lirih.
“Apa maksudmu?”
“Kulihat telah dua hari ini Eyang selalu mengurung diri di kamar. Ada apa, Eyang? Apakah kau hendak membatalkan perkawinan ini?”
“Kenapa berpikir begitu, Padmi? Tentu saja tidak!” sahut laki-laki tua itu seraya tertawa lebar.
“Lalu, kenapa Eyang mesti mengurung diri?” cecar Rajapadmi.
Ki Jayeng Rono tidak mampu menjawabnya secara langsung. Wajahnya yang sempat berseri-seri, kembali murung seperti diliputi kabut tebal.
“Ada apa, Eyang? Apa yang membuat kau kelihatan bersedih?”
Ki Jayeng Rono menarik napas panjang, lalu bangkit berdiri dan membelakangi cucunya. “Entahlah. Belakangan ini aku mimpi buruk. Dan itu selalu membayangi. Seolah-olah, mimpi itu seperti kenyataan...,” tutur Ki Jayeng Rono.
“Mimpi apa, Eyang?”
“Perkampungan kita ini diliputi awan hitam. Dan di beberapa bagian, terlihat nyala api berkobar-kobar. Eyang berusaha memadamkannya, namun kedua kaki ini seperti terpaku di tempat. Jerit tangis bersahut-sahutan. Dan....”
Ki Jayeng Rono tak kuasa melanjutkan ceritanya. Orang tua itu terdiam. Matanya kosong, memandang ke depan melewati jeruji jendela.
“Mimpi hanya sekadar kembang tidur, Eyang. Kenapa kau begitu merisaukannya?” bujuk Rajapadmi, seraya menghampiri orang tua itu.
“Aku takut hal-hal dulu menghantui....”
Ki Jayeng Rono tidak melanjutkan kata-katanya. Agaknya dia sadar kalau kenangan masa mudanya yang buruk tidak boleh diketahui anak cucunya. Selama ini, sosok Ki Jayeng Rono dikenal sebagai seorang dermawan. Bertingkah laku arif, bijaksana, serta santun. Dari mulutnya pun sering terdengar wejangan-wejangan yang welas asih.
“Apa maksud Eyang? Apakah ketika muda kau pernah melakukan hal-hal buruk?” tanya Rajapadmi curiga.
“Bicara apa kau? Tentu saja tidak! Kita keluarga terhormat. Jadi mana mungkin aku melakukan perbuatan-perbuatan buruk!” tangkis orang tua itu cepat.
“Kalau demikian tidak ada yang perlu dikhawatirkan!” tandas Rajapadmi.
“Ya, ya! Sebenarnya memang begitu...,” sahut Ki Jayeng Rono mengangguk cepat, untuk menghilangkan kecurigaan cucunya.
Sikap itulah yang selama ini ditunjukkannya kepada seluruh penghuni perkampungan ini. Sosok tegar yang tidak tergoyahkan oleh badai apa pun!
“Kalau demikian hilangkanlah pikiran-pikiran buruk itu. Tenanglah. Dan, jangan terlalu dimasukkan ke hati mimpi-mimpi buruk itu!” ujar Rajapadmi, sedikit menasihati. “Tunjukkanlah pada orang-orang bahwa sesungguhnya Eyang bergembira menyambut hari perkawinanku!”
“Ya, ya. Kau benar, Rajapadmi!”
Gadis yang baru saja memasuki usia tujuh belas tahun itu tersenyum lebar. Digamitnya lengan laki-laki tua itu untuk diajaknya keluar dan berbaur dengan yang lain. Tapi pada saat yang sama seorang laki-laki setengah baya masuk ke dalam ruangan.
“Sompak, ada apa?!” tanya Rajapadmi heran.
Orang yang baru datang memang Sompak pembantu setia Kamajaya yang juga saudara sepupu Rajapadmi. Dan gadis itu tidak perlu bertanya lebih lanjut ketika melihat Kamajaya mengerang-ngerang kesakitan dipapah dua orang pembantu lain ke ruangan ini. Mukanya lembab dan biru seperti dikeroyok orang sekampung. Demikian pula sekujur tubuhnya.
“Astaga! Kakang Kamajaya! Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau jadi begini?” seru Rajapadmi kaget.
“Kamajaya, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau jadi begini?!” timpal Ki Jayeng Rono.
Laki-laki tua itu geram bukan main. Hampir seluruh orang di Kadipaten Lawang kenal padanya. Bahkan tidak akan berani mengganggu orang-orang perkampungannya. Apalagi cucunya. Lagi pula kalau sekadar menghadapi pemuda sebayanya sampai berjumlah lima orang, Kamajaya masih mampu merobohkan. Tapi melihat keadaannya demikian, pastilah yang menghajarnya bukan orang sembarangan. Mungkin sengaja mau cari gara-gara dengannya.
“Oh, sakit...! Sakit sekali...!” keluh pemuda itu merintih-rintih.
“Rajapadmi! Bawa dia pada Paman Teja untuk mendapat perawatan sebaik-baiknya!” ujar Ki Jayeng Rono dengan wajah tidak sedap dipandang.
Orang yang disebut Paman Teja adalah seorang tabib andalan perkampungan ini. Ramuan-ramuan obatnya selalu mujarab. Dan selama ini, tak pernah gagal mengobati penyakit apa pun.
“Kau di sini. Dan ceritakan padaku, apa yang telah menimpa Kamajaya!” ujar Ki Jayeng Rono ketika melihat Sompak hendak mengekor Rajapadmi yang telah keluar ruangan bersama Kamajaya yang dipapah dua orang pembantunya.
“Eh, iya!” Sompak segera berlutut dan menundukkan kepala.
“Siapa yang menghajarnya?!” tanya Ki Jayeng Rono dengan suara agak keras mengagetkan.
“Hamba tidak tahu orangnya, Ki. Dia..., dia memakai topeng merah terbuat dari kayu,” sahut Sompak, tergagap.
“Dia tidak menyebutkan nama?” kejar Ki Jayeng Rono.
“Tidak, Ki.”
Laki-laki itu terdiam untuk beberapa saat. Kemudian kembali dipandangnya tajam-tajam ke arah Sompak. “Apa yang menyebabkan orang bertopeng itu menghajar Kamajaya?” tanya Ki Jayeng Rono lagi.
“Dia datang begitu saja, lalu membuat Den Kamajaya marah dan berusaha menamparnya. Orang bertopeng itu cukup gesit mengelak. Bahkan balas menghajar, sampai Den Kamajaya tidak bisa menguasai diri,” jelas Sompak.
“Apa yang mereka percakapkan sehingga Kamajaya marah padanya?” cecar Ki Jayeng Rono.
“Entahlah, Ki. Saat itu hamba berada di luar. Tapi lapat-lapat hamba mendengar, orang bertopeng itu menyebut Den Kamajaya sebagai turunan pengecut. Padahal, Den Kamajaya telah bersikap sopan mengajaknya untuk minum bersama.”
Ki Jayeng Rono kembali terdiam memikirkan penjelasan barusan. Dicoba-cobanya untuk menerka, siapa sebenarnya orang bertopeng merah itu. “Dia menyebut Kamajaya sebagai turunan pengecut? Siapa orang itu?” gumam Ki Jayeng Rono.
“Tapi orang bertopeng itu kelihatannya cukup hebat, Ki. Rasanya, meski Den Kamajaya tidak mabuk pun, akan sulit mengalahkannya,” lanjut Sompak.
“Kenapa kau begitu yakin?”
“Empat kawan Den Kamajaya yang ingin membantu menghajar orang bertopeng itu, dibuat babak belur tak berdaya dengan sekali pukul!” jelas Sompak lagi penuh semangat.
“Hm, apakah dia hanya seorang?”
“Kelihatannya begitu, Ki.”
“Coba kau ingat-ingat, Sompak. Apakah ada sesuatu dari omongannya yang menarik perhatianmu?”
“Ng.... apa ya? Ah, iya! Aku ingat!” seru Sompak.
“Apa itu?”
“Dia memberi peringatan kepada Ki Jayeng!”
“Peringatan apa yang kau maksudkan?” tanya Ki Jayeng Rono dengan alis berkerut.
“Katanya, Ki Jayeng akan mendapat kunjungan saudara angkat,” jelas Sompak.
“Hm...!” Wajah Ki Jayeng semakin berkerut seperti tengah berpikir keras untuk mengingat-ingat, siapa saudara angkatnya.
“Apakah Ki Jayeng punya saudara angkat?” tanya Sompak dengan wajah lugu.
“Aku tidak punya saudara angkat sejahat itu,” tegas laki-laki tua ini.
“Ya, aku pun percaya. Orang itu pasti membual!” dengus Sompak geram.
“Apakah dia mengatakan kapan akan datang?”
“Tidak, Ki. Tapi, kurasa dia tidak akan berani menunjukkan batang hidungnya disini, setelah menghajar Den Kamajaya. Apalagi orang itu memang pengecut. Kalau tidak pengecut, tentu tidak akan menyembunyikan wajahnya di balik topeng!” lanjut pembantu itu lagi, masih menyisakan kegeraman hatinya.
“Ya, sudah. Kau kembali ke tempatmu. Dan, jaga baik-baik majikanmu!” ujar Ki Jayeng Rono.
“Baik, Ki!” Setelah menjura hormat, Sompak bangkit. Tubuhnya berbalik, lalu melangkah pergi.
Sepeninggal Sompak, Ki Jayeng Rono kembali merenung. Sebentar-sebentar dia mondar-mandir, kemudian berdiri tertegun sambil memandang keluar lewat jeruji jendela.
“Apakah mereka?” gumam Ki Jayeng Rono. “Mustahil! Mereka pasti sudah mati!”
Tok! Tok! Tok!
“Heh?!” Ki Jayeng Rono sedikit kaget ketika mendengar ketukan dari luar pintu. Kakinya segera melangkah, dan segera membuka pintu.
“Ayah! Apa yang terjadi pada Kamajaya? Siapa yang melakukannya?” tanya seorang laki-laki setengah baya dengan wajah merah padam, ketika Ki Jayeng Rono membuka pintu lebar-lebar.
Laki-laki setengah baya berpakaian indah dari sutera berwarna kuning itu langsung saja menerobos masuk ruangan ini, ditemani seorang wanita berusia sekitar empat puluh tahun.
“Tenanglah, Dilaga. Jangan terpancing amarah begitu...,” ujar Ki Jayeng Rono, berusaha menenangkan laki-laki setengah baya yang dipanggil Dilaga.
“Tapi, Ayah. Kamajaya babak belur. Dan kita tidak bisa mendiamkannya begitu saja. Orang itu mesti ditangkap untuk mendapat pembalasan setimpal!” timpal wanita disamping Dilaga dengan sikap tidak kalah garang.
“Tenanglah kataku! Kemarahan kalian tidak akan menyelesaikan persoalan!” seru Ki Jayeng Rono agak keras.
Mendengar bentakan, dua orang yang agaknya adalah suami istri ini terdiam meski masih menyiratkan amarah pada wajah masing-masing.
“Nah, begitu lebih baik...!” lanjut orang tua itu. Ki Jayeng Rono menarik napas panjang lebih dulu, sebelum melanjutkan kata-katanya.
“Aku telah mendapat keterangan bahwa yang menghajar Kamajaya adalah seorang tokoh memakai topeng merah agar wajahnya tidak dikenali. Aku tidak kenal dengannya. Dan seperti kalian ketahui, aku pun tidak bermusuhan dengan siapa pun. Jadi jelaslah dengan peristiwa itu, dia sengaja menciptakan permusuhan. Apalagi menjelang hajat perkawinan Rajapadmi. Aku khawatir orang itu akan semakin mengacaukan hajat itu. Oleh sebab itu, maka perintahkan semua orang diperkampungan ini untuk waspada,” papar Ki Jayeng Rono.
“Tapi, Ayah. Apakah mungkin dia akan kesini? Hanya orang sinting yang berani mengacau. Di sini berkumpul beberapa tokoh persilatan yang berilmu tinggi, seperti kakak iparku Ki Sabda Kalaka yang bergelar Kelelawar Hitam. Lalu, ada besan si Joyologo yaitu Ki Sukatan Jember, yang bergelar Pendekar Tongkat Maut. Serta, ada juga Ki Danang Rejo yang menjadi Ketua Perguruan Tapak Buana. Di perkampungan ini pun tidak kurang jago-jago lainnya dari keluarga kita sendiri!” tukas Dilaga, yang merupakan putra pertama Ki Jayeng Rono.
“Orang-orang Topeng Merah itu tidak bisa dipandang sebelah mata, Dilaga.”
“Hei?! Ayah kenal mereka rupanya?”
“Tidak. Ayah hanya menduga-duga. Belakangan ini ada komplotan yang menamakan diri mereka Gerombolan Topeng Merah. Ciri-ciri mereka yang mudah dikenali adalah topeng merah selalu dikenakan,” jelas Ki Jayeng Rono.
“Apakah sebelumnya kita pernah berurusan dengan mereka Ayah?” tanya Dilaga sedikit curiga.
“Apa keuntungan kita berurusan dengan mereka? Gerombolan Topeng Merah melakukan apa saja yang mereka suka. Membunuh, merampok, serta perbuatan-perbuatan keji lainnya. Mereka tidak perlu alasan untuk melakukan hal itu.”
Dilaga terdiam sesaat lamanya. Demikian pula istrinya. “Tapi kita tidak bisa mendiamkan perbuatan mereka begitu saja, Ayah!” lanjut Dilaga masih dengan wajah penasaran.
“Apa yang bisa kita lakukan? Mereka adalah gerombolan kuat yang rata-rata berilmu tinggi. Dan lagi pula, tidak ada seorang pun yang mengetahui, di mana sarang mereka. Orang-orang itu datang dan pergi bagai angin. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah waspada!”
Dilaga dan istrinya tidak banyak bicara lagi. Mereka bermaksud hendak meninggalkan ruangan ini, namun mendadak terdengar ribut-ribut dari luar. Tak lama, seorang pelayan masuk. Dia langsung berlutut hormat di hadapan Ki Jayeng Rono.
“Maaf, Ki. Hamba terpaksa masuk untuk melaporkan sesuatu!” ucap pelayan itu.
“Ada apa?” tanya Ki Jayeng Rono.
“Seseorang tengah mengacau di tembok sebelah barat. Saat ini, Den Ayu Sri Dewi dan Den Sukasrana tengah berusaha menghalaunya!”
“Kurang ajar! Ingin kulihat, bagaimana tampang pengacau itu!” dengus Dilaga.
Seperti mendapat pelampiasan dari kekesalan hatinya, Dilaga bergegas meninggalkan ayahnya diikuti istrinya. Sementara Ki Jayeng Rono mengikuti dengan langkah lambat.
Setiba di tempat kejadian, Ki Jayeng Rono, Dilaga, dan istrinya, hanya menemukan beberapa pelayan yang telah roboh jadi mayat. Sementara Sri Dewi dan Sukasrana kelihatan berkerut wajahnya menahan rasa sakit hebat. Sedangkan beberapa pelayan masih berdiri di tempat itu.
“Mana pengacau itu?!” tanya Dilaga, membentak.
“Sudah pergi, Ki!” sahut seorang pelayan.
“Kurang ajar! Kenapa kalian tidak menahannya?! Dasar goblok! Tolol! Apa kerja kalian semua, he?!” bentak Dilaga kalap.
Tak seorang pun yang berani menyahut. Semuanya diam tertunduk, diam seribu bahasa.
“Dilaga! Kau tidak sepatutnya bicara sekasar itu pada mereka. Orang-orang itu telah berusaha sekuat tenaga, bahkan telah jatuh korban di pihak kita. Tapi kemampuan lawan memang tinggi. Mestinya kau harus menghargai usaha mereka,” ujar Ki Jayeng Rono, menasihati.
Dilaga yang tengah kalap karena kejadian yang menimpa Kamajaya putranya, agaknya tidak bisa menerima wejangan begitu saja. Setelah memberi hormat pada orang tua itu, dia segera berlalu dengan wajah gusar.
Ki Jayeng Rono menghela napas panjang, membiarkan saja putranya berlalu. Kemudian didekatinya Sri Dewi dan Sukasrana. “Kalian tidak apa-apa?” tanya Ki Jayeng Rono.
“Hanya sedikit luka, Eyang,” sahut Sri Dewi.
Gadis berusia enam belas tahun ini adalah adik Kamajaya, anak nomor dua Dilaga. Sedangkan Sukasrana yang usianya sebaya dengannya, adalah adik Rajapadmi.
Ki Jayeng Rono memeriksa sebentar. Dan mereka hanya mendapat sedikit memar-memar. “Siapa yang datang?” tanya laki-laki tua itu kembali.
“Entahlah, Eyang. Kami tidak mengenalinya. Orang itu memakai topeng merah terbuat dari kayu. Dia datang tiba-tiba saja, lalu membunuhi orang-orang kita,” jelas Sri Dewi.
“Hanya seorang?”
Kedua anak muda itu mengangguk.
“Dia tidak meninggalkan pesan apa-apa?” kejar Ki Jayeng Rono.
“Ada. Tapi, kami tak percaya!” sahut Sri Dewi.
“Apa katanya?”
“Katanya, Eyang berhutang padanya. Dan oleh sebab itu, dia hendak menagihnya!” sahut Sri Dewi, polos.
Ki Jayeng Rono terdiam untuk sesaat.
“Bukankah itu mengada-ada? Kita tidak kurang suatu apa pun. Maka, mana mungkin Eyang berhutang padanya! Benarkah, Eyang?!” lanjut gadis itu masih dengan wajah kesal.
“Tentu saja! Eyang tidak pernah berhutang pada siapa pun.”
“Dasar orang gila tak tahu diri! Kalau saja dia datang baik-baik meminta makanan atau uang, pasti akan kuberikan. Tapi orang ini mungkin sinting atau sengaja cari permusuhan!” rutuk Sri Dewi bersungut-sungut.
“Sudahlah. Biar nanti cari tahu soal orang ini. Sekarang kalian bantu mereka untuk membereskan tempat ini!”
Sukasrana dan Sri Dewi menjura hormat, lalu berbaur dengan para pelayan untuk membereskan tempat yang berantakan ini. Sementara para pelayan yang lain telah menggotong mayat-mayat kawan mereka, untuk dikebumikan secara layak.
Kini Ki Jayeng Rono masih terpaku di tempatnya dengan wajah kusut. Pikirannya saat ini dihantui sesuatu yang mulai membayanginya belakangan ini.
********************
TIGA
Sebuah rombongan berkuda yang mengawal tiga buah kereta kuda menghentikan perjalanan mereka ketika tiba-tiba di depan berdiri menghadang satu sosok tubuh dalam jarak sepuluh tombak. Salah satu dari sepuluh penunggang kuda terdepan yang berpakaian seragam segera bergerak menghampiri.
Rombongan berkuda itu sendiri terdiri dari sepuluh orang berpakaian hijau yang dipadu celana hitam yang berada di depan. Sementara sepuluh lainnya yang berpakaian sama, berada di belakang kereta-kereta kuda itu. Pada masing-masing pinggang terselip sebilah golok. Agaknya, mereka adalah sepasukan pengawal tiga kereta kuda itu.
“Apa maksudmu menghadang kami, Kisanak?” tegur penunggang kuda yang menghampiri sosok laki-laki bertopeng merah.
“Apakah kau mengawal Ki Sendrogowo?” Bukannya menjawab, laki-laki bertopeng itu malah mengajukan pertanyaan dengan nada merendahkan.
“Ya! Kami hendak menuju perkampungan milik Ki Jayeng Rono!” sahut pengawal berpakaian seragam ini.
“Bagus! Jadi kehadiranku tak sia-sia!” kata orang bertopeng itu.
“Apa maksudmu, Kisanak?”
“Maksudku? Ketahuilah. Aku adalah saudara angkat Ki Jayeng Rono yang hendak menyambut Ki Sendrogowo dengan..., ini...!” Saat itu juga orang bertopeng ini mengebutkan tangannya ke depan.
Set! Set!
“Heh?!” Betapa terkejutnya pengawal itu ketika mendadak melesat beberapa sinar putih kearahnya dengan kecepatan bagai kilat.
“Hup!” Untung saja, pengawal itu cepat melenting dari kudanya. Tapi akibatnya....
Crab! Cras!
“Aaakh...! Aaa...!”
Dua orang pengawal kontan terjengkang disertai jerit kematian, begitu sinar-sinar putih keperakan yang ternyata senjata rahasia berbentuk payung menancap di leher dan dada mereka. Begitu ambruk di tanah, kedua pengawal itu tak berkutik lagi dengan wajah membiru. Jelas, ruyung-ruyung itu mengandung racun ganas.
Sementara itu, mendengar jerit kematian, dari salah satu kereta kuda keluar seorang laki-laki tua bertubuh agak gemuk. Dia langsung berjalan ke depan, melihat apa yang terjadi.
“Ada apa, Bakil?!” tanya laki-laki tua itu, begitu tiba di samping pengawal yang tadi diserang.
“Maaf, Ki Sendrogowo. Tiba-tiba saja orang ini menyerang kita!” sahut pengawal yang dipanggil Bakil.
Laki-laki tua yang tak lain Ki Sendrogowo ini menatap tajam pada orang bertopeng itu. “Siapa kau, Kisanak?! Mengapa kau menyerang kami?!” tanya Ki Sendrogowo dengan suara keras.
“Ha ha ha...! Sendrogowo alias Srigala Berbulu Hitam, tidak kusangka kita akan bertemu di sini!”
“Jangan berbelit-belit. Katakan saja, apa maumu?!” dengus laki-laki bertubuh agak gemuk yang selalu memakai jubah hitam panjang sampai ke mata kaki ini.
“Kau tentu kenal topeng yang kukenakan ini, bukan?!” sahut orang bertopeng itu seraya mendesis sinis.
“Melihat ciri-cirimu, kau pasti salah satu dari Gerombolan Topeng Merah!” desis Ki Sendrogowo.
Memang, Gerombolan Topeng Merah belakangan ini memang amat diperhitungkan kalangan persilatan. Dalam waktu singkat saja, gerombolan itu menjadi momok yang menakutkan! Anggota-anggotanya rata-rata memiliki kepandaian tinggi dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Maka ketika mengetahui bahwa penghadangnya adalah salah satu dari Gerombolan Topeng Merah, laki-laki tua itu sedikit kecut.
“Apa yang kau inginkan dari kami?” tanya Ki Sendrogowo.
Bagaimanapun sebagai tokoh yang cukup dikenal dalam rimba persilatan, mana mau Ki Sendrogowo yang berjuluk Serigala Berbulu Hitam menunjukkan kelemahan menghadapi anggota Gerombolan Topeng Merah ini. Apalagi, dia merasa tidak ada permusuhan di antara mereka.
“Kalian hendak mendatangi si Jayeng Rono?” tanya orang bertopeng merah itu, datar.
“Betul.”
“Ha ha ha...! Bagus. Kalau begitu, kalian tidak bisa ke sana!” kata orang bertopeng itu, seenaknya. Seolah-olah dia seorang hakim yang menentukan segalanya.
Mendengar hal itu tentu saja Serigala Berbulu Hitam jadi kurang senang. Tapi belum lagi dia bicara....
“Kisanak!” selak seseorang dari belakang Ki Sendrogowo.
Hampir saja semua orang menoleh ke arah seorang laki-laki berusia sekitar lima puluh lima tahun yang tahu-tahu telah berada dibelakang Ki Sendrogowo.
“Kau boleh saja tidak menyukai Ki Jayeng Rono. Tapi, kau tidak punya hak untuk menghalangi kami. Apalagi coba-coba mengganggu jalan kami!” lanjut laki-laki itu.
“Ha ha ha...! Aku bisa berbuat apa saja, meski di daerah kekuasaan si Jayeng Rono! Apa yang bisa diperbuat? Dia bahkan tidak mampu berkata apa-apa di depanku!” sahut orang bertopeng ini, pongah.
“Hati-hati, Praja! Kita tak boleh gegabah!” ujar Ki Sendrogowo.
“Ayah, kita tidak perlu mengurusinya! Lebih baik lanjutkan perjalanan!” sahut laki-laki setengah baya itu pada Ki Sendrogowo. Rupanya, dia putra Ki Sendrogowo.
Kemudian laki-laki berusia sekitar setengah abad lebih bernama Praja itu memberi perintah pada yang lain seraya mengajak Ki Sendrogowo untuk kembali masuk ke dalam kereta. Tapi baru saja mereka berbalik....
“Aaa...!” Mendadak terdengar pekik kesakitan. Ki Sendrogowo dan Ki Praja kembali berbalik, menghadap ke arah sumber suara teriakan tadi. Tampak dua penunggang kuda yang paling depan roboh dan langsung tewas dengan ruyung beracun menancap di jidat.
“Kau...?! Apa yang kau lakukan pada mereka, Pengecut?!” bentak Ki Praja seraya melotot garang dengan muka merah karena marah.
“Sudah kukatakan, aku bisa berbuat apa saja yang kusukai. Dan kau terlalu sombong untuk mempercayai. Dua orang tadi adalah korban kesombonganmu,” sahut orang bertopeng itu tenang.
“Keparat!” desis Ki Praja, tidak dapat lagi menahan amarahnya. Saat itu juga, laki-laki setengah baya ini melompat menerjang sambil menghentakkan kedua tangannya.
Wesss...!
Serangkum angin kencang langsung melesat dari kedua telapak tangan Ki Praja, menuju orang bertopeng itu.
“Uts...!” Sambil memperdengarkan tawa dingin, orang bertopeng itu melompat ke atas, sehingga serangan itu lewat.
Tapi Ki Praja tidak berhenti sampai di situ. Tidak percuma dia menjadi putra seorang tokoh silat terkenal seperti Ki Sendrogowo. Tubuhnya terus meluruk dengan sebelah kaki menyambar pinggang orang bertopeng yang baru saja mendarat ditanah. Dengan gerakan cepat orang bertopeng itu menangkis dengan tangan kiri.
Plak!
Begitu habis terjadi benturan, orang bertopeng ini berputar. Tangan kanannya yang membentuk cakar cepat berkelebat.
Wuttt!
“Uts...!” Hampir saja muka Ki Sendrogowo robek kalau saja tidak melompat ke belakang sambil menjatuhkan diri. Untuk sesaat dia terpana, tak mampu berbuat apa-apa.
Sementara orang bertopeng tidak melanjutkan serangan. Tiba-tiba tubuhnya berbalik dan berkelebat meninggalkan tempat ini. Cepat sekali kelebatannya, sehingga sebentar saja dia sudah menghilang di balik pepohonan di pinggir jalan menuju Gunung Arjuna itu.
“Ha ha ha...! Kalian boleh melanjutkan perjalanan lagi. Tapi, ingat-ingatlah! Keluarga Ki Sendrogowo tidak bisa pamer kekuatan di daerah ini. Meski kalian bergabung dengan keluarga Jayeng Rono, tidak akan membuat Gerombolan Topeng Merah gentar. Kalau saja kami mau, maka dalam sekejap kalian akan hancur!”
Terdengar suara orang bertopeng itu, yang dikeluarkan lewat ilmu mengirimkan suara jarak jauh.
********************
Meski keluarga Ki Jayeng Rono masih diliputi kedukaan karena peristiwa yang menimpa kemarin, namun penyambutan kepada keluarga Ki Sendrogowo cukup meriah. Seolah-olah mereka hendak menunjukkan kesan bahwa hajatan yang akan berlangsung berjalan dengan wajar.
Malam ini, Ki Jayeng Rono mengundang Ki Sendrogowo untuk minum teh bersama. Hal itu wajar saja dilakukan sebagai kawan lama yang telah sekian belas tahun tidak bertemu. Keadaan ini bukan saja sekadar menghormati calon besannya, tapi juga digunakan untuk mengenang peristiwa-peristiwa manis yang dulu pernah dialami. Dengan begitu akan tercipta persahabatan yang semakin akrab.
Namun, Ki Sendrogowo agaknya tidak bisa melupakan peristiwa yang belum lama dialami menjelang tiba di tempat ini. Bisa saja ketika membawa mayat anak buahnya, dia mengatakan kalau telah tertimpa malapetaka. Tapi agaknya hal itu tidak bisa ditutup-tutupi terus. Hatinya masih tidak enak dan sedikit dendam. Maka ketika ada kesempatan, hal itu diungkapkannya pada tuan rumah.
“Apakah Ki Jayeng pernah merasa bermusuhan dengan Gerombolan Topeng Merah?” tanya Ki Sendrogowo setelah menceritakan yang sebenarnya tentang kematian anak buahnya.
Ki Jayeng Rono tidak langsung menjawab. Dia diam terpaku dengan wajah murung. “Tidak. Aku tidak mengadakan permusuhan dengan mereka...,” sahut Ki Jayeng Rono lirih setelah menghela napas panjang.
“Kelihatannya mereka demikian membencimu.”
“Entahlah. Kukira mereka hanya iri saja pada segala yang kumiliki, lalu mulai mencari gara-gara....”
“Aku tidak habis pikir jadinya. Apa yang mereka kehendaki? Padahal kita tidak bermusuhan dengan mereka,” keluh Ki Sendrogowo seraya menghela napas panjang. “Tapi ini tidak bisa dibiarkan terus, Ki Jayeng!”
“Ya. Aku pun mulai berpikir begitu. Mereka sungguh keterlaluan sekali!” desis Ki Jayeng Rono, mulai marah.
“Kalau didiamkan terus, mereka akan besar kepala dan semakin leluasa mengganggu kita!” sambut Ki Sendrogowo.
Ki Jayeng Rono kembali mengangguk-angguk membenarkan.
“Aku hanya heran, siapa sebenarnya orang-orang di balik topeng merah itu? Dan, siapa pula pemimpinnya? Kelihatannya mereka bernafsu sekali untuk menguasai dunia persilatan.”
“Tidak ada yang aneh, Ki Sendro!” sahut Ki Jayeng Rono. “Di dunia ini segalanya serba mungkin. Orang kaya itu tidak puas dengan kekayaannya, dan ingin lebih kaya lagi. Demikian pula orang yang berkuasa yang tidak puas dengan kekuasaannya. Dia ingin lebih berkuasa lagi. Kurasa itu pula yang terpikir oleh pimpinan Gerombolan Topeng Merah itu.”
“Iya. Mungkin juga begitu. Tapi, mereka kelihatannya banyak berkeliaran di Kadipaten Lawang ini. Meski korbannya belum banyak, namun nama mereka telah cukup menggetarkan daerah-daerah di sekitar sini. Aku sendiri tidak yakin bahwa markas mereka di sini,” tukas Ki Sendrogowo.
“Aku yakin markas mereka bukan di sim. Sebab kalau betul, tentu aku yang lebih dulu tahu,” tandas Ki Jayeng Rono.
“Tapi, kenapa kelihatannya mereka mengincarmu, Ki?”
“Tidak. Orang-orang seperti mereka mengincar siapa pun yang dikehendakinya,” tangkis Ki Jayeng Rono cepat.
“Menurut para pegawaimu, orang bertopeng itu pernah pula mengacau di sini. Benarkah itu?”
Ki Jayeng Rono mengutuk pegawainya dalam hati. Kenapa mesti cerita pada orang luar segala? Padahal dia berusaha menutupinya, karena akan menjatuhkan pamornya saja di depan calon besannya.
“Memang begitu, Ki Sendrogowo. Tapi para pegawaiku telah mengusir mereka. Dan kurasa, mereka akan berpikir dua kali untuk kembali mengacau di sini,” sahut Ki Jayeng Rono, sedikit membanggakan diri.
“Keluarga Ki Jayeng Rono amat terkenal. Dan mereka sungguh berani menyatroni tempat ini. Maka sudah pasti ada sesuatu yang tengah diincarnya di tempatmu ini, Ki.”
“He he he...! Kau ini bisa saja, Sobat!” sahut Ki Jayeng Rono sambil tersenyum. “Apa yang diincarnya dariku? Harta yang tidak seberapa ini? Hm.... Keluarga Ki Sendrogowo memiliki harta sepuluh kali lipat dibanding denganku. Atau, barangkali dia mengincar cucu perempuanku? He he he...! Jangan khawatir. Rajapadmi akan kujaga baik-baik agar tidak digondol mereka.”
Ki Sendrogowo ikut-ikutan tersenyum. Namun begitu, hatinya jelas masih belum bisa tenang memikirkan soal ulah Gerombolan Topeng Merah. “Entah kenapa, tapi sepertinya aku punya firasat bahwa mereka hendak mengobarkan perang terbuka kepada kita...,” desah Ki Sendrogowo.
Ki Jayeng Rono yang saat ini tengah mengangkat cawan dan hendak mengajak tamunya minum bersama, sesaat membatalkannya. Dia berusaha bersikap sewajar mungkin, untuk tidak membuat calon besannya tenang.
“Percayalah, Sobat. Keluargaku memang kecil dan tidak terkenal. Tapi bagaimanapun hebatnya, mereka akan berpikir sepuluh kali untuk mengacau ke sini!” tandas Ki Jayeng meyakinkan.
“Bukan hal itu yang kurisaukan. Karena aku sadar, tempat ini tidak bisa dibuat main-main. Tapi....”
“Tapi apa, Sobat?” potong Ki Jayeng Rono.
“Aku hanya tidak habis pikir, kenapa hal itu terjadi di keluarga kita pada saat minggu bahagia ini....”
Ki Jayeng Rono terdiam. Dengan ucapannya itu, terasa bahwa Ki Sendrogowo tidak tenang. Bahkan mungkin masih merasa kacau pikirannya, soal orang bertopeng merah tadi.
********************
EMPAT
Untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan Ki Jayeng Rono bermaksud menyewa jago-jago tangguh untuk menghadapi Gerombolan Topeng Merah. Meskipun, dia mesti mengeluarkan uang cukup banyak. Dan niatnya segera diutarakan pada Dilaga, anaknya.
“Ayah! Kita tidak perlu takut menghadapi Gerombolan Topeng Merah!” tukas Dilaga merasa tidak senang mendengar niat ayahnya itu.
“Bukannya takut. Tapi, aku tidak mau repot-repot mengurusi mereka. Kita tengah menghadapi hajat perkawinan Rajapadmi. Maka, segala sesuatunya harus berlangsung aman dan tenteram,” kilah Ki Jayeng Rono.
“Tapi dengan begitu Ayah mengeluarkan banyak uang. Bukankah itu pemborosan? Serahkan saja padaku! Dengan dibantu lima pegawai, aku akan menghancurkan mereka. Jadi, Ayah tidak perlu menyewa orang segala!” sahut Dilaga, mantap.
Ki Jayeng Rono tersenyum. Dia tahu, anaknya memiliki keberanian yang cukup. Tapi lawan yang dihadapi adalah anggota Gerombolan Topeng Merah yang rata-rata berilmu tinggi. Sedangkan menghadapi seorang dari mereka saja sudah kewalahan. Apalagi kalau mereka seluruhnya. Tapi, Ki Jayeng Rono tidak sampai hati menolak terang-terangan.
“Dilaga! Ayah mengakui, kau mampu menghadapi mereka. Tapi tugasmu banyak dan tidak terus menerus mengurusi hal itu. Banyak hal lebih penting yang mesti dikerjakan. Maka, biarlah yang satu ini dikerjakan orang lain. Lagi pula, Ayah tak ingin mengotori tangan-tangan keluarga kita hanya untuk mengurusi para begundal yang menamakan diri Gerombolan Topeng Merah...,” bujuk Ki Jayeng Rono.
Entah karena bujukan dengan kata-kata manis, entah juga karena sebetulnya ciut nyalinya menghadapi Gerombolan Topeng Merah, tapi yang jelas akhirnya Dilaga tidak banyak bicara lagi, meski tidak mengangguk dengan usul ayahnya.
Sementara itu, tepat di depan jendela ruangan Ki Jayeng Rono, seorang pemuda berusia enam belas tahun berwajah bulat, berlari-lari menuju ke belakang rumah yang sangat megah ini. Dihampirinya seorang gadis cantik yang saat itu tengah duduk di taman belakang perkampungan ini.
“Sri Dewi! Kau tidak akan percaya dengan apa yang kubawa?!” teriak pemuda itu sambil berlari-lari kecil.
“Apa yang kau bawa, Sukasrana. Kue apem atau kue cucur?” tanya gadis yang tak lain Sri Dewi sambil tertawa kecil memperlihatkan barisan giginya yang bagai biji mentimun.
“Hush! Kau ini menggoda aku terus. Mentang-mentang aku suka mencuri makanan dari dapur! Aku membawa berita penting,” sahut pemuda yang ternyata Sukasrana.
“Berita apa?” tanya Sri Dewi acuh tak acuh.
“Eyang hendak menyewa jago-jago silat untuk menghadapi Gerombolan Topeng Merah!” jelas Sukasrana.
“Dari mana kau tahu?”
“Aku mencuri dengar pembicaraan mereka tadi.”
“Kenapa eyang melakukan itu? Apa orang-orang kita tidak cukup untuk menghajar mereka?” tanya gadis itu, seperti untuk diri sendiri.
“Ayahmu pun tadi sudah berkata begitu. Tapi, eyang katanya tidak mau mengotori keluarga kita sekadar untuk mengurusi orang-orang bertopeng merah itu.”
“Hem.... Aku tidak bisa menerimanya! Kita harus berbuat sesuatu!” dengus Sri Dewi. “Eyang telah merendahkan kemampuan kita, apa pun alasannya! Kita harus buktikan bahwa kita mampu menghajar mereka!”
“Iya, iya...!” timpal Sukasrana dengan bersemangat. “Tapi apa yang mesti kita lakukan?”
“Kita harus keluar dari perkampungan ini, mencari Gerombolan Topeng Merah!”
Sukasrana terkejut mendengar niat saudara sepupunya. “Mencari mereka?”
“Iya, kenapa? Kau takut?” tanya Sri Dewi.
“Eh, tidak! Tentu saja tidak!” sahut Sukasrana cepat sambil menggeleng.
“Bagus! Kalau begitu, sekarang juga kita berangkat!”
“Sekarang? Eh, apa kita perlu untuk minta izin pada eyang, atau ayah dan ibu?” kilah Sukasrana.
“Dasar tolol! Mana mungkin mereka memberi izin. Eyang telah menegaskan bahwa keluarganya tidak boleh keluar perkampungan sembarangan, tanpa izin beliau. Jadi kita harus menyelinap. Ayo! Kalau kau tidak berani, biar aku sendiri saja!” umpat Sri Dewi, kesal.
Sri Dewi telah bersiap-siap melangkah dengan pedang tersandang di pinggang ketika melihat Sukasrana masih menunjukkan sikap ragu.
“Aku pergi dulu!” lanjut Sri Dewi.
“Baiklah. Tapi, tunggu dulu. Aku mesti mengambil pedangku terlebih dulu. Tunggu sebentar!” sahut pemuda tampan itu seraya berlari ke rumahnya.
Sri Dewi tidak peduli dengan ocehan saudara sepupunya. Begitu melihat Sukasrana menghilang dari pandangan, maka secepat itu pula tubuhnya berkelebat meninggalkannya.
Memang, Sri Dewi mendapat pelajaran ilmu olah kanuragan bukan dari orangtuanya, melainkan langsung dari kakeknya. Lagi pula, dia amat tekun dan rajin. Sehingga meski usianya tergolong muda, tapi boleh dikata kemampuannya lebih tinggi dibanding saudara-saudaranya. Sehingga hatinya panas betul ketika mengetahui kalau kakeknya melarang untuk memburu Gerombolan Topeng Merah yang telah mengacau. Apalagi kini kakeknya membayar orang lain untuk menghadapinya. Gadis itu merasa dianggap angin dan dipandang sebelah mata.
Adapun halnya Sukasrana, anak itu penakut dan suka ragu-ragu. Itu bisa menghambat maksud Sri Dewi. Kalau menunggu, mungkin saja Sukasrana akan mengadu pada orangtuanya. Atau bahkan pada Ki Jayeng Rono. Maka bisa-bisa rencananya batal, sehingga terpaksa gadis itu meninggalkannya.
Sri Dewi tidak sempat mengeluarkan kuda, karena takut kepergok. Maka terpaksa dia harus berjalan kaki. Dan perjalanan ini amat melelahkan, karena selama ini dia terbiasa ke mana-mana dengan berkuda.
Sudah cukup jauh gadis itu melewati jalan yang jarang dilalui orang-orang perkampungan bila hendak ke kota Kadipaten Lawang. Sengaja dia memilih jalan ini, untuk menghindari pengejaran pegawai-pegawai kakeknya bila Sukasrana sampai mengadu. Namun sampai sejauh ini, belum terlihat tanda-tanda bahwa para pegawai kakeknya akan menyusul.
Matahari telah tergelincir dari atas kepala ketika Sri Dewi tiba di sebuah desa kecil. Penduduknya jarang. Dan jarak antara satu rumah dengan rumah lain cukup jauh. Tubuhnya telah letih dan penat, sehingga diputuskannya untuk mencari rumah penduduk untuk menumpang beristirahat.
Tapi belum lagi hal itu dilakukan, mendadak dari arah belakang terasa terdengar langkah seseorang. Gadis itu cepat berbalik. Dan wajahnya seketika terkejut begitu melihat satu sosok tubuh dengan topeng merah di depannya. Sebenarnya, orang inilah yang dicari-carinya. Tapi entah kenapa, ketika berhadapan justru semangatnya perlahan-lahan terbang melayang.
“Hei?!” Kembali gadis itu dibuat terkejut ketika dari belakangnya, terdengar suara orang melompat Dan wajahnya semakin pucat ketika melihat satu sosok lain yang mengenakan topeng merah. Ternyata dua dari Gerombolan Topeng Merah telah berada di sini. Apa yang bisa dilakukannya.
“He he he...! Siapa sangka di tempat ini kita bertemu gadis cantik yang tengah kesasar!” kata orang bertopeng merah yang di pinggangnya terselip sebatang kapak sambil terkekeh buas.
“Bukan cuma kebetulan, Janang Uwung!” sahut orang bertopeng yang bersenjata kipas di pinggang. “Tapi gadis ini benar-benar istimewa. Tidakkah kau mengenalinya bahwa dia berasal dari perkampungan si Jayeng Rono?”
“Benarkah, Kakang Tunggul Wetu?!” sambut laki-laki bersenjata kapak yang dipanggil Janang Uwung dengan sikap girang.
“Kuyakin gadis ini cucunya!” tandas laki-laki bernama Tunggul Wetu.
“Ah, sungguh kebetulan! Enaknya akan kita apakan bocah manis ini?” leceh Janang Uwung.
“Apalagi? Adakah sesuatu yang lebih menyakitkan bagi si Jayeng Rono ketimbang membunuh cucunya ini?” sahut Tunggul Wetu, seenaknya.
“Aku mengerti! Ya, apalagi yang harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan?! He he he...!”
Sri Dewi terkesiap mendengar ocehan kedua orang bertopeng itu. Dan tak terasa jantungnya berdegup kencang. Sebagai gadis yang beranjak dewasa, dia mengerti apa yang tengah bercokol di kepala dua orang bertopeng itu. Dan tanpa terasa tangannya mulai memegang gagang pedang di pinggang.
“He he he...! Kau hendak melawan, Cah Ayu? Bagus! Ketika di perkampungan kakekmu, kau cukup hebat. Tapi bukan berarti aku tidak mampu meringkusmu!” seru Tunggul Wetu sambil tertawa mengejek.
“Kakang, tidak usah repot-repot! Biar kuringkus dia untukmu!” sahut Janang Uwung. Baru saja berkata begitu, secepat kilat Janang Uwung melangkah menghampiri dan siap menerkam Sri Dewi.
“Hati-hati, Janang! Salah-salah kau akan dipecundangi bocah itu!” teriak Tunggul Wetu memperingatkan.
“Ha ha ha...! Kau meremehkan aku, Kakang? Apa hebatnya keturunan si Jayeng? Kalau dulu dia boleh menepuk dada, tapi sekarang?! Huh! Bila dia ada di sini, akan kuremukkan kepalanya!” desis Janang Uwung.
Sring!
Mendengar kakeknya diremehkan begitu, mendadak semangat Sri Dewi pelan kembali merasuk dan membesar. Maka seketika pedangnya dicabut Pada saat yang sama Janang Uwung telah melompat, dengan kedua tangan terjulur ke depan.
“Keparat busuk, mampuslah kau!” bentak Sri Dewi seraya mengibaskan pedang.
Ayunan pedang Sri Dewi bertenaga kuat, dan rasanya sulit bagi Janang Uwung untuk menghindar. Apalagi dalam keadaan mengapung di udara. Seolah-olah, Janang Uwung memberikan dadanya untuk ditembus pedang.
Sementara gadis itu lupa bahwa lawannya bukanlah tokoh sembarangan. Buktinya Janang Uwung yang tidak berusaha menghindar cepat menggerakkan kedua telapak tangannya.
Tap!
Saat itu juga, pedang Sri Dewi terjepit ketat pada kedua telapak tangan Janang Uwung. Sri Dewi terkejut Pedangnya tidak bisa maju, tertahan oleh kedua telapak tangan Janang Uwung. Ini membuktikan bahwa tenaga dalam laki-laki ini sangat tinggi.
Gadis itu segera mengerahkan tenaga dalamnya. Namun, tetap juga tidak menunjukkan hasil. Dahinya mulai bercucuran keringat. Wajahnya berkerut geram ketika mulai menarik pedangnya. Tapi pedangnya tidak bergeser seujung rambut pun!
“Keparat!” dengus Sri Dewi, seraya mengayunkan sebelah kakinya.
Janang Uwung cepat menaikkan sebelah kaki, sehingga tendangan gadis itu hanya menghantam ke lutut.
Plak!
Dan tiba-tiba secepat kilat Janang Uwung melepaskan tendangan ke perut.
Desss...!
“Aaakh...!” Tak ampun lagi, Sri Dewi terpental ke belakang beberapa langkah. Pedangnya kini bertukar tempat di tangan Janang Uwung. Namun sebagai orang yang telah terdidik ilmu silat, hantaman begitu tidak langsung membuatnya kecut dan jeri. Gadis itu cepat menggulung tubuhnya ke belakang, menjauh. Lalu dia melompat, bermaksud tegak berdiri. Dan baru saja mengatur keseimbangan, mendadak Janang Uwung telah berkelebat dengan kedua tangan bergerak cepat. Dan....
Tuk! Tuk!
“Uhhh...!” Gadis itu kontan terduduk lemas begitu dua totokan Janang Uwung mendarat di dadanya. Tubuhnya seperti tidak bertenaga, tulang-belulangnya bagai dilolosi saja. Matanya hanya bisa menatap laki-laki itu dengan tajam.
“Keparat busuk! Jangan main gila kau! Aku masih mampu menghadapi sampai ribuan jurus. Lepaskan totokanmu!” bentak Sri Dewi garang.
“He he he...! Cah Ayu.... Tentu saja aku percaya. Tapi untuk apa bersusah-payah meladenimu kalau ternyata dengan jalan mudah aku bisa meringkusmu?” ejek Janang Uwung.
“Kau memang hebat, Janang Uwung! Luar bisa. Kemajuanmu sungguh pesat sekali!” puji Tunggul Wetu, sambil menghampiri Sri Dewi.
“He he he...! Kakang bisa saja. Tapi saat ini bukan pujian yang kita harapkan. Tapi ini...,” sahut Janang Uwung, seraya menunjuk ke bagian bawah perutnya.
“He he he...! Kau memang pintar sekali. Tapi kita tidak bisa di sini. Jangan-jangan yang lain muncul dan minta bagian,” tukas Tunggul Wetu.
“Aku tahu tempat yang aman, Kang! Di sebelah sana ada pondok kosong. Kita bisa leluasa!” sambar Janang Uwung.
“Tunggu apa lagi? Ayolah cepat!” desak Tunggul Wetu.
Maka dengan serta-merta Janang Uwung langsung menyambar tubuh Sri Dewi. Tubuhnya langsung berkelebat, membopong Sri Dewi. Sedang Tunggul Wetu mengikuti dari belakang.
Bret!
“Aouw...!”
Janang Uwung agaknya tidak tahan lagi sekadar membayangkan apa yang ada di balik baju Sri Dewi. Maka dengan sekali sambar baju gadis itu langsung robek lebar. Seketika dua buah bukit berkulit putih mulus yang menjadi salah satu kebanggaan kaum wanita terlihat jelas di depan mata Janang Uwung.
“Ck ck ck...! Sempurna dan bagus sekali. Tidak sangka turunan si Jayeng Rono bisa menciptakan bidadari sepertimu, Anak Manis!” puji Janang Uwung yang kali ini telah membuka topengnya. Tampak wajahnya yang seram, memperlihatkan seringai penuh nafsu dengan air liur hampir menetes.
Mata laki-laki yang ternyata telah berusia lanjut itu melotot penuh nafsu. Tubuhnya gemetar menahan hasrat kelelakiannya tanpa mempedulikan teriakan serta makian gadis itu. Seolah-olah telinganya tertutup oleh pemandangan indah didepan mata. Dan tidak terasa tubuhnya mulai panas dingin.
Nyaris saja sebelah tangan Janang Uwung bergulir ke dada gadis itu, kalau saja Tunggul Wetu tidak menangkapnya. “Kau sudah berjanji menangkapnya untukku! Maka aku yang berhak lebih dulu mencicipinya,” sergah Tunggul Wetu.
Janang Uwung terpaksa menelan ludah. Namun, tubuhnya tidak beranjak dari duduknya. “Tapi, Kakang....”
“Tidak ada tapi-tapian!” tukas Tunggul Wetu. “Nah, tunggulah di luar. Tidak lama. Dan setelah itu, kau akan menikmatinya sepuas hati!”
Janang Uwung terpaksa mematuhinya. Kelihatannya, dia bukan takut. Tapi, menghormati. Sebab, Tunggul Wetu telah dianggapnya sebagai saudara tuanya.
Sepeninggal Janang Uwung, Tunggul Wetu yang juga telah melepas topengnya mengunci pintu dari dalam, lalu duduk di sisi pembaringan. Mata laki-laki yang juga sudah berusia lanjut ini melotot tajam. Wajahnya menyeringai buas seperti harimau hendak menerkam kelinci. Dia sudah tidak peduli pada Sri Dewi yang hanya mampu menangis pasrah, karena sudah tak ada gunanya lagi berteriak.
Sri Dewi hanya menggigil ketakutan. Wajahnya semakin pucat ketika hela napas orang bertopeng ini terasa menyapu wajahnya. Semangatnya terbang sejak tadi. Yang ada hanya sikap pasrah.
Pada saat itu, ketika Tunggul Wetu hendak mencopot pakaiannya, mendadak pundaknya dicekal dari belakang. Cepat laki-laki tua ini menoleh dan hendak mendamprat. Namun....
Des!
“Aaakh...!” Tunggul Wetu sama sekali tidak menyangka akan mendapat hajaran telak pada perutnya begitu berbalik. Keruan saja, tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang disertai jerit kesakitan. Dia segera bangkit, dan melihat satu tubuh telah berdiri dengan sikap tenang.
LIMA
“Kurang ajar! Manusia tidak tahu diri. Berani betul kau mencampuri urusanku!” bentak Tunggul Wetu garang pada seorang pemuda tampan berbaju rompi putih dengan pedang bergagang kepala burung di punggung.
Entah dari mana datangnya, Tunggul Wetu sendiri tak tahu. Lagi pula, ke mana perginya Janang Uwung, sehingga tidak melihat pemuda ini masuk lalu mengganggu acaranya? Tapi Tunggul Wetu tidak sempat memikirkan, karena amarahnya lebih kuat merasuki benaknya. Tanpa banyak bicara lagi, laki-laki ini melompat menerjang pemuda berbaju rompi putih itu.
“Rasakan hajaranku, Bocah!”
Sementara pemuda berbaju rompi putih tidak berusaha menghindar. Namun sebelah tangannya bergerak mengibas menyampok tendangan.
Plak!
“Uhhh...!” Tunggul Wetu geram bukan main. Kakinya terasa bergetar hebat saat berbenturan dengan tangan pemuda itu. Tapi mana mau kekurangannya ditunjukkan? Padahal sebagai orang persilatan seharusnya dia mengerti, dari benturan tadi saja bisa diduga kalau tenaga dalam pemuda berbaju rompi putih itu jauh di atasnya.
“Heaat...!” Kini Tunggul Wetu menerjang. Tubuhnya langsung meluruk sambil bergulungan dengan kepala yang akan jadi sasaran.
Namun dengan gerakan ringan sekali pemuda berbaju rompi putih itu memiringkan kepala. Kemudian tubuhnya berputar sambil mengayunkan tangannya yang mengancam ke dada Tunggul Wetu. Dan....
Desss...!
“Aaakh...!” Tunggul Wetu terkesiap dan kontan menjerit tertahan. Gerakan pemuda berbaju rompi putih itu cepat bukan main. Sampai-sampai dia tidak mampu berkelit. Dan akibatnya, hantaman itu telak menghajar dadanya.
“Keparat! Kau akan menyesal seumur hidup!” bentak Tunggul Wetu garang.
Cepat laki-laki anggota Gerombolan Topeng Merah ini bangkit. Tangannya cepat bergerak kepinggang, menggenggam kipasnya.
Set! Bet!
Dengan sekali sentak, kipas dari lempengan-lempengan besi tipis telah terkembang di tangan Tunggul Wetu. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, dia melompat menerjang.
“Yeaaa...!”
Pemuda berbaju rompi putih itu hanya tenang-tenang saja. Namun ketika ujung kipas menyambar, tubuhnya mengegos ke samping. Dan tiba-tiba sebelah kakinya menghantam perut Tunggul Wetu.
Begkh...!
“Hekh...!” Tubuh Tunggul Wetu kontan tertekuk, tidak sempat menghindari tendangan pemuda berbaju rompi putih itu. Tubuhnya ambruk tak tertahankan. Perut terasa mual bukan main mendapat hajaran yang cukup keras itu. Saat itu juga, Tunggul Wetu merasa tak mampu bangkit lagi. Isi perutnya bagaikan diaduk-aduk. Lalu....
“Hoekh...!” Begitu kuatnya dorongan dari dalam, membuat Tunggul Wetu tak mampu lagi menahan keluar isi perutnya yang disertai onggokan darah.
“Pergilah.... Dan jangan membuat keonaran lagi!” ujar pemuda berbaju rompi putih, mengandung ketegasan.
Tunggul Wetu berusaha bangkit sambil memungut kipasnya yang terjatuh. Diselipkannya kipas itu ke pinggang. Tangan kirinya mengusap mulut yang dikotori muntahan bercampur darah. Sementara sepasang matanya memandang dengan sorot dendam penuh amarah.
“Kau akan berurusan dengan kami, Bocah! Persoalan ini belum selesai. Ingat Ketua Gerombolan Topeng Merah akan datang membuat perhitungan denganmu!” dengus Tunggul Wetu.
Agaknya Tunggul Wetu sadar tidak ada gunanya lagi melawan pemuda berbaju rompi putih ini. Bukan saja dia demikian mudah menangkis serangannya, tapi juga cepat mampu membalas. Dari sini jelas kalau kepandaian pemuda itu berada beberapa tingkat di atasnya.
“Musuh tidak kucari. Tapi kalau datang, aku tidak akan lari. Pergilah. Dan bawa serta kawanmu yang ada di depan!” sahut pemuda berbaju rompi putih itu.
Tunggul Wetu terkesiap mendengar kalimat terakhir yang diucapkan pemuda itu. Kawannya di luar? Jelas, pasti telah terjadi sesuatu pada Janang Uwung sehingga tidak masuk membantunya melawan pemuda ini.
Cepat Tunggul Wetu berkelebat keluar. Ketika keluar, benar saja. Didapatinya Janang Uwung duduk terdiam seperti patung. Agaknya tubuhnya telah tertotok. Tanpa banyak bicara lagi, dipanggulnya tubuh Janang Uwung dan segera pergi dari tempat itu.
Sri Dewi masih menangis terisak. Buru-buru dia bangkit, duduk di tepi ranjang sambil membelakangi pemuda yang menolongnya dari aib.
“Sudahlah, jangan menangis. Kau harus menganggap bahwa itu pengalaman yang harus selalu diingat. Hidup di luaran tidak mudah. Banyak kejadian tak terduga akan menimpa kita...,” bujuk pemuda berbaju rompi putih itu.
Sejenak Sri Dewi menoleh. Dan baru disadari bahwa penolongnya masih berada di ruangan ini. Berdiri tegak membelakanginya. “Te..., terima kasih atas pertolonganmu, Kisanak. Aku Sri Dewi...,” ucap gadis itu.
“Namaku Rangga...,” sahut pemuda berbaju rompi putih yang ternyata Rangga alias Pendekar Rajawali Sakti. “Kulihat kau tidak biasa bepergian. Tentunya kau anak seorang hartawan yang kabur dari rumah....”
“Ya. Aku tinggal di....”
Sesaat gadis itu ragu melanjutkan kata-katanya. Sebab, kakeknya dulu pernah berpesan agar tidak mudah percaya begitu saja kepada orang asing meskipun baik dan telah berjasa. Sebab bisa saja kebaikan itu ternyata kedok yang menutupi hati yang sebenarnya culas, jahat, menyimpan maksud busuk. Dan sebenarnya, Sri Dewi tidak tahu apa kaitannya antara menunjukkan tempat kediamannya dengan pemuda itu. Apakah kakeknya takut dirampok? Rasanya sulit. Sebab di perkampungannya bercokol jago-jago silat yang tidak bisa dikalahkan begitu saja oleh para perampok.
“Keadaan sudah aman. Dan kau boleh melanjutkan perjalanan kembali,” kata Rangga tak mempedulikan apa yang tengah dipikir gadis itu.
Setelah berkata begitu, Pendekar Rajawali Sakti beranjak keluar dengan tenang. Sehingga tanpa sadar Sri Dewi bangkit dan menguntitnya dari belakang dengan perasaan bersalah.
“Ma..., maaf. Aku tidak bermaksud menyembunyikan diriku...,” ucap gadis ini lirih.
Rangga menoleh dan tersenyum manis. “Aku tidak merasa bahwa kau menyembunyikan sesuatu. Lagi pula, meski kau menyembunyikan sesuatu, aku tidak hendak memaksamu untuk menceritakannya padaku,” sahut Rangga, datar.
“Kau..., eh! Tidak marah?” tanya Sri Dewi, agak canggung juga. Gadis ini menaksir, usia pemuda ini beberapa tahun di atasnya. Bahkan di atas Kamajaya, yang mesti dipanggilnya kakang.
“Tidak...,” sahut Rangga seperti tidak merasakan kecanggungan gadis itu.
“Sungguh?”
Rangga tertawa. “Kenapa aku mesti marah? Kenal denganmu pun baru sekarang ini. Dan kenapa aku mesti marah, kalau kau menyembunyikan sesuatu? Tidak. Aku tidak marah. Tugasku menyelamatkan kau dari kebuasan mereka telah selesai. Nah, pulanglah. Orangtuamu mungkin kelabakan mencari-carimu.”
Pendekar Rajawali Sakti kembali melangkah dan kini berada di halaman pondok kecil yang dijadikan anggota Gerombolan Topeng Merah untuk memperkosa Sri Dewi. Sementara itu, Sri Dewi mengikuti dari belakang.
“Eh, rumahku jauh sekali dari sini! Maukah kau mengantarku...?” usik Sri Dewi ketika pemuda itu terus melangkah pergi.
Sebenarnya gadis ini agak canggung meminta seperti tadi. Tapi ketakutannya masih banyak tersisa di hati. Dia khawatir kedua orang bertopeng itu akan kembali, lalu melanjutkan niat busuknya. Dan kalau sudah begitu, siapa lagi yang akan menolong?
“Di mana?” tanya Rangga.
“Lawang! Eh, maksudku tidak persis di kotanya. Sebuah perkampungan yang ada di kaki Gunung Arjuna.”
Rangga mengerutkan dahi sebentar. “Tempat itu tidak terlalu jauh....”
“Ya, tapi....”
Sri Dewi tidak melanjutkan kata-katanya. Dia berusaha mencari alasan agar pemuda ini bersedia mengantarnya. Tapi syukur, akhirnya Rangga tersenyum dengan kepala mengangguk.
********************
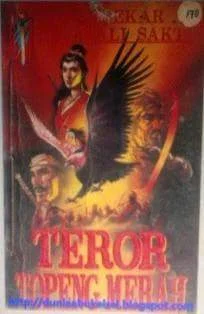
Senja baru saja berlalu. Sebagian rombongan yang ditugaskan Ki Jayeng Rono untuk mencari Sri Dewi, telah kembali. Namun rombongan yang lain terus melakukan perjalanan untuk mencarinya sampai bertemu.
Dilaga sejak tadi sibuk mendiamkan istrinya yang terus menangis dengan perasaan cemas dan takut. Bukan cuma istrinya saja yang mengalami hal itu. Tapi, dia juga merasakannya. Bahkan bercampur amarah.
Dan amarah laki-laki setengah baya itu semakin bertambah ketika melihat jago-jago bayaran yang disewa ayahnya berdatangan satu persatu ke perkampungan ini. Jumlah mereka tidak kurang dari dua puluh orang dengan senjata lengkap. Menilik dari tindak-tanduknya paling tidak mereka memiliki kepandaian lumayan. Tengah Ki Dilaga duduk di ruang depan setelah gagal membujuk istrinya, terdengar ketukan dari pintu.
“Masuk!” kata Dilaga, agak keras.
Wajar saja kalau Dilaga tadi bersuara cukup keras. Karena, hatinya memang masih kesal. Tapi begitu tahu siapa yang muncul, dia berusaha mempermanis sikap dan wajahnya. Ternyata yang datang adalah Ki Jayeng Rono, ayahnya.
“Sudah kau bujuk istrimu?” tanya Ki Jayeng Rono tanpa dipersilakan langsung duduk di depan putranya.
“Sudah,” sahut Dilaga.
“Tidak usah khawatir. Sebentar lagi Sri Dewi pasti akan ditemukan,” lanjut orang tua itu.
“Tapi, mereka yang baru datang mengatakan gagal mencarinya....”
“Ah! Mereka cuma malas saja!” tepis Ki Jayeng Rono. “Yang lainnya tengah mencari lebih cermat.”
“Aku khawatir dia kepergok Gerombolan Topeng Merah...,” desah Dilaga cemas.
“Kita semua mengkhawatirkan hal yang sama. Tapi, Sri Dewi tidak bodoh untuk menjerumuskan dirinya memancing serta menantang orang-orang itu.”
“Tapi, Sukasrana mengatakan sendiri bahwa kepergiannya sengaja untuk mencari Gerombolan Topeng Merah, Ayah!”
“Sukasrana terkadang suka melebih-lebihkan cerita. Kau tidak perlu terlalu mempercayainya. Sudah lama Sri Dewi ingin bertamasya ke tempat-tempat indah. Dan aku selalu saja belum sempat mengajaknya. Kurasa dia kesal. Dan akhirnya nekat untuk pergi sendiri,” tangkis Ki Jayeng Rono, coba mengusir kegelisahan di hati putranya.
Dilaga terdiam. Dia tahu banyak putrinya. Kalau sekadar kakeknya tidak sempat mengantarnya bertamasya, dia pasti akan pergi sendiri. Atau, bersama beberapa pengawal dan pasti akan minta izin. Tapi kalau Sri Dewi sampai nekat kabur tanpa pamit, itu pasti karena niatnya dihalangi. Dan jelas, soal orang-orang bertopeng merah yang membuat Ki Jayeng Rono tidak mengizinkan putrinya keluar dari perkampungan.
Dan belum ada yang sempat bicara lagi, terdengar suara ribut-ribut dari arah luar. Keduanya bergegas melihat ke pintu. Tampak beberapa pekerja di keluarga Ki Jayeng Rono berlarian ke satu arah.
“Keparat! Pengacau itu muncul lagi di sini!” desis Ki Jayeng Rono geram.
Tanpa banyak mulut lagi, Dilaga segera masuk ke kamar. Begitu keluar kembali, dia telah menggenggam sebilah pedang. “Akan kubinasakan mereka hari ini!” desis Dilaga geram.
Apa yang diperkirakan Ki Jayeng Rono dan Dilaga memang benar. Dua pengacau yang telah berada di dalam perkampungan tengah menghajar para pegawai mereka. Dan ciri-ciri khusus yang berupa topeng merah, telah membuat kedua orang itu naik darah.
Kedua orang bertopeng merah itu terlihat ganas sekali. Yang seorang bersenjata caping bambu yang ujung-ujungnya tajam. Sekali senjatanya terbang berputar-putar, maka nyawa dua atau tiga orang pegawai Ki Jayeng Rono melayang. Sedangkan yang bersenjata tongkat baja berujung runcing, bergerak amat cepat. Gerakan tongkatnya langsung menebas leher serta perut lawan tanpa ampun.
“Kurang ajar! Aku tidak bisa membiarkan mereka berbuat seenaknya saja!” desis Dilaga geram seraya melompat menghadapi laki-laki bercaping yang lebih banyak menimbulkan korban.
Sikap Dilaga memang tidak salah. Para pegawai keluarganya yang rata-rata memiliki kemampuan rendah, tidak bisa menandingi kedua orang bertopeng merah ini. Padahal mereka dibantu jago-jago bayaran yang didatangkan Ki Jayeng Rono.
Baru saja Dilaga melompat beberapa tindak, laki-laki bercaping telah melepaskan senjatanya. Senjata caping itu langsung melesat kencang berputaran. Dengan gerakan yang disertai tenaga dalam tinggi, Dilaga langsung mengebutkan pedangnya yang telah terhunus.
Wuttt...! Trak!
“Heh?!” Betapa terkejutnya Dilaga. Dalam perhitungannya, mestinya caping bambu itu akan terkoyak disambar pedangnya. Tapi yang terjadi, malah pedang Dilaga yang bergetar. Tangannya kontan terasa kesemutan sampai ke jantung akibat benturan barusan. Sementara caping bambunya tidak rusak sedikit pun. Sadarlah dia, bahwa tenaga laki-laki bertopeng ini tidak di bawahnya. Bahkan mungkin saja di atasnya.
“He he he...! Jadi kau keturunan si Jayeng? Boleh juga! Tapi, sebaiknya suruh saja ayahmu yang melawanku. Dan kau pergilah menetek pada ibumu!” ejek laki-laki bercaping dengan tawa lebar.
Mendengar ejekan, bukan main geramnya Dilaga. Bahkan dengan seenaknya menyuruhnya menetek pada ibunya yang telah almarhumah.
“Tutup mulutmu, Keparat! Dan lihat pedangku!” bentak Dilaga seraya menyerang dengan ganas.
Tapi laki-laki bercaping tampak tenang-tenang saja meladeninya. Tubuhnya bergerak gesit, menghindari tebasan pedang laki-laki setengah baya itu. Padahal, Ki Dilaga sudah memperhebat serangan. Pedangnya berkelebat seperti baling-baling dan mengurung ruang gerak laki-laki bercaping dengan ketat.
“Apa hebatnya ilmu silat keluarga Jayeng Rono? Huh! Sepuluh kali lebih hebat dari ini pun tak berarti bagiku!”
Begitu selesai kata-katanya, laki-laki bercaping seperti ingin membuktikannya. Tangannya yang sudah memegang caping langsung dikebutkan.
Wuttt...!
Caping bambu itu langsung bergerak menyambar. Saat itu juga pedang Dilaga berusaha memapak!
Trak!
Tubuh Dilaga kontan terjajar mundur, tak mampu menahan kekuatan tenaga dalam yang terkandung dalam caping itu. Dan belum sempat dia memperbaiki keseimbangannya, mendadak laki-laki bercaping itu telah meluruk melepaskan tendangan. Begitu cepat gerakannya, sehingga....
Desss...!
“Aaakh...!” Dilaga menjerit kesakitan begitu tendangan orang bercaping mendarat di dadanya. Tubuhnya terjungkal beberapa langkah ke belakang.
ENAM
Melihat itu Ki Jayeng Rono gusar bukan main. Namun sebelum dia turun tangan, mendadak....
“Keparat busuk, lihat serangan!”
Ki Jayeng Rono menoleh, melihat satu sosok tubuh berkelebat menerjang orang bertopeng. Ternyata, dia tak lain dari Ki Sabda Kalaka yang merupakan saudara tua istri Dilaga. Kepandaian Ki Sabda Kalaka yang berjuluk si Kelelawar Hitam itu tidak rendah. Buktinya, Ki Jayeng Rono pun menyeganinya. Senjatanya adalah sepasang tongkat hitam yang di ujungnya terdapat pisau kecil.
“He he he...! Kukira siapa. Ternyata, hanya kelelawar buduk!” ejek laki-laki bercaping sambil tertawa mengejek.
Dipandang rendah demikian, si Kelelawar Hitam yang selalu memakai jubah hitam itu tidak mempedulikannya. Langsung dia menyerang ganas.
“Yeaaa...!”
Kepalan tangan Ki Sabda Kalaka yang berisi tenaga dalam tinggi ditangkis dengan mudah oleh telapak tangan kiri laki-laki bertopeng.
Plak!
“Uhhh...!” Kakak ipar Dilaga itu mengeluh tertahan, merasakan dorongan tenaga yang lebih kuat menghantamnya. Seperti tidak mempedulikan kekuatan laki-laki bercaping itu, dia terus melenting ke atas. Setelah membuat gerakan jungkir balik dua kali, tubuhnya meluruk sambil menyambar batok kepala lawannya.
“Hup!”
Orang bertopeng dan bercaping hanya terkekeh dingin. Dalam keadaan masih berdiri tegak, sepertinya dia tidak berusaha menghindar. Namun sedikit lagi serangan Ki Sabda Kalaka akan menghantam, dengan gerakan sangat mengagumkan, tubuhnya melenting ke belakang. Begitu mendarat, kaki kanannya langsung melepas tendangan maut. Dalam keadaan melayang di udara, mana mungkin si Kelelawar Hitam mampu menghindar. Akibatnya....
Desss!
“Aaakh...!” Ki Sabda Kalaka kontan berteriak kesakitan. Tubuhnya terjerembab ke depan sejauh tujuh langkah dengan dada dan perut serasa remuk.
“He he he...! Ayo bangun, Kelelawar Buduk! Apa kau hendak bertelor di situ?!” ejek laki-laki bercaping itu.
“Keparat!” bentak si Kelelawar Hitam, geram bukan main.
Saat itu juga, Ki Sabda Kalaka mencabut sepasang tongkat hitamnya. Lalu dia melompat menyerang. “Sekarang kau boleh tertawa di akherat sana!” desis Ki Sabda Kalaka.
Pada saat itu juga Dilaga telah ikut siap membantu. “Kakang! Biar aku membantumu merencanakan batok kepalanya!”
Si Kelelawar Hitam agaknya tidak berusaha menolak bantuan. Karena disadari, menghadapi orang bercaping itu seorang diri belum mampu menjatuhkannya. Maka dibantu beberapa pegawai kedua orang itu segera mengeroyok laki-laki bercaping.
Sementara, laki-laki bertopeng dan bercaping kelihatan tenang-tenang saja, meski tidak sebebas tadi ketika menghadapi keroco-keroco. Dua lawan utama yang dihadapi tidak bisa dipandang sebelah mata.
Di arena pertarungan lain, laki-laki bertopeng bersenjata tongkat baja sudah berusaha menahan gempuran dua orang lawan yang ternyata Ki Joyologo dan Ki Sukatan Jember. Permainan tongkatnya memang masih berada di atas Ki Sukatan Jember. Namun gerakannya sering dikacaukan oleh pedang Ki Joyologo. Sehingga semakin lama, dia betul-betul tak berdaya.
Trak!
Terjadi benturan ketika tongkat orang bertopeng merah itu menangkis tongkat Ki Sukatan Jember. Sebelum dia sempat melakukan serangan balasan, sodokan pedang Ki Joyologo telah mengincar jantungnya dari samping. Secepat kilat, orang bertopeng merah ini menggerakkan tongkatnya.
Trang!
Begitu berhasil menangkis, serangan Ki Sukatan Jember telah menanti orang bertopeng ini dari belakang. Tidak ada waktu lagi untuk menangkis. Dan....
Duk!
“Aaakh...!” Orang bertopeng merah dan bersenjata tongkat itu menjerit kesakitan ketika pinggangnya kena gebuk Ki Sukatan Jember. Sesaat tubuhnya sempoyongan.
“Hei?!” Melihat kawannya terdesak, laki-laki bertopeng merah yang mengenakan caping menoleh. Pada saat itu juga mereka saling menoleh mengangguk seperti memberi isyarat. Lalu....
“Suiiittt..!”
Sesaat orang-orang di perkampungan kecil ini terkejut mendengar suitan dari salah satu orang bertopeng merah. Meski tidak tahu maksudnya, namun sedikit-sedikit mereka mengerti apa yang diperbuat kedua orang bertopeng itu. Kalau tidak melarikan diri, tentu mencari bantuan. Sementara kedua orang bertopeng ini kembali melanjutkan pertarungan. Itu berarti, suitan barusan mengisyaratkan permintaan bantuan.
Ternyata benar saja. Sebentar saja telah berlompatan dua orang bertopeng merah lain, masuk ke arena pertarungan. Yang seorang bertubuh tinggi besar. Sepasang lengannya panjang kokoh dan kelihatan kuat. Yang seorang lagi tidak terlalu tinggi, namun rambutnya panjang riap-riapan. Di pinggangnya terlihat sepasang senjata tongkat pendek yang salah satu ujungnya berbentuk cakar dari besi. Kedua orang itu langsung mengamuk sejadi-jadinya. Dalam waktu singkat mereka telah membuat banyak korban.
“Kurang ajar! Ini tidak bisa dibiarkan! Danang Rejo! Kau bisa meladeni yang seorang lagi!” ujar Ki Jayeng Rono seraya menyongsong orang bertopeng yang bersenjata sepasang tongkat berujung cakar besi.
Laki-laki berusia enam puluh tahun yang dipanggil Ki Danang Rejo, adalah kawan Ki Jayeng Rono. Tokoh yang juga Ketua Perguruan Tapak Buana ini memang sejak tadi belum turun tangan. Maka begitu mendapat isyarat dari Ki Jayeng Rono, dia segera berkelebat, menghadang orang bertopeng yang bertubuh tinggi besar tanpa senjata sebuah pun.
“He he he...! Jadi, ini Jayeng Rono yang kesohor itu? Sayang sekali. Kau dan seluruh keluargamu akan musnah hari ini!” ejek orang bertopeng yang bersenjata sepasang tongkat berujung cakar besi sambil tertawa, ketika Ki Jayeng Rono mendarat satu tombak di depannya.
“Siapa pun kalian, jangan harap bermimpi bisa berbuat seenaknya di tempatku!” dengus Ki Jayeng.
“He he he...! Kau hendak menunjukkan kegaranganmu, Orang Tua Busuk?! Kalau dulu boleh saja. Tapi sekarang, jangan harap! Gerombolan Topeng Merah akan menghancurkanmu!”
“Apa sebenarnya yang kalian inginkan dariku?” tanya laki-laki tua itu heran dengan dahi berkerut.
“Aku tidak bermusuhan dengan kalian. Tapi, tiba-tiba saja Gerombolan Topeng Merah mencari gara-gara.”
“Sebenarnya ini bukan urusan pribadiku, tapi dua kawanku. Kau pasti mengenal mereka. Dan kemudian, ketua kami menemukan hal lain yang menarik sehingga menjadi urusan kami semua,” jelas orang bertopeng merah itu.
“Tidak usah banyak omong! Katakan saja apa mau kalian?!” bentak Ki Jayeng Rono.
“Gulungan kulit itu. Lalu, semua hartamu! Serahkan, atau kau tidak akan selamat! Kau dan seluruh keluargamu akan disapu bersih!”
“Apa maksudmu? Gulungan kulit yang mana yang dimaksudkan?” tanya Ki Jayeng Rono pura-pura tidak mengerti.
“Tidak usah berpura-pura, Bangsat! Serahkan saja cepat kalau mau selamat!”
“Huh! Aku tidak mengerti alasan kalian. Gulungan kulit yang mana yang kalian inginkan? Seingatku, memang aku punya gulungan kulit Tapi itu sudah dijadikan hiasan atau lukisan,” kilah Ki Jayeng Rono.
“Kau terlalu banyak berpura-pura, Orang Tua Busuk! Kau kira kami ke sini dengan niat kosong, he?! Kenalkah kau dengan kedua saudara angkatmu?”
“Aku semakin tidak mengerti bicaramu. Seumur hidup, aku sama sekali tidak mempunyai saudara angkat!” bantah orang tua itu.
“Bagaimana dengan Tunggul Wetu dan Janang Uwung?”
Ketika disebutkan kedua nama itu, darah Ki Jayeng Rono seketika berdesir. Jantungnya berdetak lebih kencang. Wajahnya separo pucat Kedua nama yang disebutkan itu memang saudara angkatnya. Pikirannya langsung melayang pada peristiwa puluhan tahun lalu pada masa mudanya. Saat itu mereka sering melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti merampok, membunuh, serta memperkosa para wanita. Ketiganya mulai terkenal sebagai Tiga Perampok Bukit Tunggul, karena wilayah kekuasaan mereka memang di sekitar Bukit Tunggul.
“Kau kenal mereka, bukan?” sindir orang bertopeng itu, terdengar sinis.
Sesaat Ki Jayeng Rono melirik ke arah lain, khawatir ada orang yang mendengar pembicaraan itu. Karena, perbuatan-perbuatan dimasa mudanya dulu tentu saja bisa meruntuhkan wibawanya didepan keluarganya. Padahal, mereka sudah kepalang menganggapnya sebagai orang terhormat.
“Huh! Kau salah duga. Aku sama sekali tidak kenal nama-nama yang kau sebutkan!” sergah Ki Jayeng Rono.
“He he he...! Bagi seorang terhormat sepertimu, terang saja membantahnya. Tapi siapa peduli? Kami tetap meminta gulungan kulit itu dan seluruh harta kekayaanmu. Atau, kau dan semua keluargamu mati sia-sia!” ancam orang bertopeng ini.
“Tidak perlu mengancam kami. Sebab kalian tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan!” dengus Ki Jayeng Rono. “Hiaaat...!”
Bersamaan dengan itu Ki Jayeng Rono meluruk menyerang ganas. Kelihatannya, dia hendak membunuh laki-laki bertopeng itu secepatnya. Paling tidak, untuk membungkam orang yang mungkin tahu banyak tentang dirinya semasa muda.
Bet! Wut!
Dengan jurus-jurus andalan yang dipadu permainan pedang, gerakan Ki Jayeng Rono jadi amat berbahaya sekaligus sulit dihindari. Tangan kiri mencakar dan tangan kanan memainkan jurus ilmu pedang. Itulah jurus yang dibanggakannya, jurus ‘Macan Terbang’.
Tapi orang bertopeng merah yang dihadapi Ki Jayeng Rono bukanlah sembarangan orang. Saat itu juga senjata tongkatnya bergerak menangkis pedang orang tua ini.
Trang!
Pada saat yang sama, orang bertopeng itu juga mengebutkan tongkat bercakar besinya ke arah tangan kiri Ki Jayeng Rono.
Wuttt...!
“Uts...!” Dengan sebisanya, Ki Jayeng Rono melompat ke belakang. Sehingga sambaran itu hanya mengenai tempat kosong.
Ki Jayeng Rono menyadari. Dari beberapa kali benturan senjata ternyata, tenaga dalam orang bertopeng itu tidak berada di bawahnya. Maka bila tadi memapak, akibatnya akan parah. Senjata cakar besi yang disalurkan tenaga dalam tinggi, bukan tidak mungkin akan membuat tangannya remuk.
Pada saat itu di tempat yang lain, Ki Danang Rejo tampak mulai terdesak. Ketua Perguruan Tapak Buana itu betul-betul kewalahan menghadapi tenaga dalam orang bertopeng yang laksana gabungan lima ekor singa jantan. Beberapa kali dalam benturan pukulan, Ki Danang Rejo mesti meringis.
Melihat itu beberapa pegawai keluarga Jayeng Rono yang sejak tadi masih berdiri di pinggir arena pertarungan, langsung membantu.
“Ayo, semuanya boleh maju bersamaan! Biar lebih mudah aku mengirim kalian ke neraka!” tantang orang bertopeng itu dengan sikap jumawa.
Mendengar sesumbar orang bertopeng, darah muda Sukasrana mendidih. Saat itu juga tubuhnya meluruk ke arena pertarungan.
“Paman! Biar aku membantumu membereskannya!” teriak anak muda belia itu, lantang.
Meski sudah cukup tua, namun Ki Danang Rejo sering bertandang ke sini dan akrab dengan bocah itu. Sehingga, Sukasrana tidak canggung-canggung lagi menyebutnya paman. Meski masih muda, namun tenaga Sukasrana cukup besar. Gerakannya pun lumayan gesit. Bersama Ki Danang Rejo, dia cukup merepotkan orang bertopeng itu.
Secara keseluruhan, empat orang bertopeng merah itu memang telah memporak-porandakan keluarga Ki Jayeng Rono. Mereka mampu menghadapi lawan yang jumlahnya sepuluh kali lipat tanpa kesulitan berarti. Tidak terbayangkan, apa jadinya bila hal itu berlangsung beberapa lama lagi. Keluarga Ki Jayeng Rono mungkin akan musnah.
“Suiiittt...!”
Mendadak dalam keadaan demikian, kembali terdengar suitan panjang dari arah lain. Salah seorang dari keempat kawanan bertopeng merah ini membalas suitan itu.
Belum juga gema suitan itu hilang, telah berkelebat dua orang bertopeng yang lain. Yang seorang bersenjata kipas, dan seorang lagi bersenjata kapak.
“Ha ha ha...! Bagus kalian cepat datang. Tua bangka busuk ini coba-coba hendak mengelabuiku!” sambut orang bertopeng yang tengah bertarung melawan Ki Jayeng Rono.
“Keparat! Serahkan pada kami!” dengus orang bertopeng yang bersenjata kapak.
“He he he...! Boleh saja kalian cincang dia. Tapi jangan lupa, gulungan kulit itu mesti didapatkan!”
“Jangan khawatir, Singodimejo! Kami akan dapatkan gulungan kulit itu untuk ketua kita!” sahut orang bertopeng yang bersenjata kipas.
“Baiklah. Kalau begitu, kalian boleh bereskan orang tua busuk ini. Biar aku membereskan yang lain!” sahut orang bertopeng merah yang tadi dipanggil Singodimejo.
Dan sebenarnya Ki Jayeng Rono agak terkejut mendengar nama Singodimejo disebut-sebut. Laki-laki tua ini tahu, Ki Singodimejo adalah berjuluk Singa Bermuka Merah yang terkenal bengis dan kejam.
“Jayeng Rono! Kali ini kau tidak lagi bisa menghindar dari kami!” bentak salah seorang dari dua orang bertopeng yang baru datang.
“Siapa kalian?!” balas orang tua itu.
“Kau tentu tahu dua adik angkatmu yang kau lemparkan ke dalam jurang, bukan?” sahut orang bertopeng yang bersenjata kipas.
“Huh! Jangan coba-coba mengelabuiku! Kalian hanya keroco-keroco licik. Aku tidak bisa kalian tipu begitu saja!” dengus Ki Jayeng Rono.
“Terserah apa katamu, Jayeng Rono. Tapi perlu kau tahu, sesungguhnya kami tidak mati saat itu. Ketua Gerombolan Topeng Merah telah menyelamatkan dan mendidik kami dengan baik. Saat itu, mungkin saja ilmu silatmu di atas kami. Tapi sekarang jangan harap kau bisa lolos dari kematianmu!” dengus orang bertopeng yang bersenjata kapak.
Ki Jayeng Rono tercekat. Kini jelas sudah, siapa orang-orang yang mengaku saudara angkatnya. Mereka tak lain Tunggul Wetu dan Janang Uwung. Yang pernah bergabung dengannya dalam suatu gerombolan bernama Tiga Perampok Bukit Tunggul, sebuah keserakahan telah membuat Ki Jayeng Rono gelap mata. Setelah berhasil merampok sebuah istana kecil di Kadipaten Tegalwungu, dia berkeinginan untuk memiliki seluruh harta, dan sepotong kulit kambing yang berisi peta harta. Maka tanpa ragu-ragu lagi, Ki Jayeng Rono memerangi kedua saudara angkatnya yang bernama Tunggul Wetu dan Janang Uwung.
Ki Jayeng Rono yang menduga kalau dua saudara angkatnya telah tewas, segera membuang mereka ke dalam jurang. Namun sayang, dugaan itu keliru. Ternyata Tunggul Wetu dan Janang Uwung belum tewas, dan akhirnya malah berhasil diselamatkan Ketua Gerombolan Topeng Merah.
Dan sebenarnya, Ki Jayeng Rono sudah mendengar kabar itu. Hanya saja, dia belum yakin. Dan kini, dia telah membuktikannya sendiri. Kendati demikian, dia masih tetap berkilah kalau kedua orang itu bukan saudara angkatnya. Sebab, mana mau dia mengakui mereka. Kalau hal itu dilakukannya, sama artinya membongkar aibnya sendiri yang selama ini selalu ditutup-tutupi di depan anak serta cucu dan kaum kerabatnya yang lain.
“Phuih! Siapa pun adanya kalian yang mengaku-ngaku sebagai saudara angkatku, jangan harap lepas dari pedangku!” bentak Ki Jayeng Rono.
Saat itu juga, orang tua ini memasang kuda-kuda sambil memainkan pedangnya dengan jurus-jurus ‘Macan Terbang’ yang diandalkannya.
“Ha ha ha...! Kau hendak menghadapi kami dengan jurus-jurus ‘Macan Terbang’, Jayeng Rono? Ketahuilah. Sudah lama kau hidup dalam kemewahan. Sehingga, kegaranganmu yang dulu terhapus. Kini kau tidak lebih dari macan ompong!” ejek Tunggul Wetu.
“Sudahlah, Kakang Tunggul Wetu! Buat apa berdebat segala dengannya? Tanganku sudah gatal ingin memberi pelajaran padanya!” timpal Janang Uwung.
“Kau benar, Janang Uwung. Orang busuk ini mesti merasakan penderitaan yang kita alami bertahun-tahun. Dia akan mengalami dalam waktu singkat, tapi amat perih!”
Setelah berkata demikian, kedua orang bertopeng itu bergerak menyambut serangan Ki Jayeng Rono yang sudah meluncur tiba. Puluhan tahun mereka berlatih dibawah bimbingan Ketua Gerombolan Topeng Merah, maka kemajuan yang diperoleh pun amat pesat.
Apalagi setelah sekian puluh tahun berlalu, ternyata ilmu silat yang dimiliki Ki Jayeng Rono tidak bertambah. Maka dengan mudah kedua orang bertopeng merah itu mendesaknya. Saat ujung pedang Ki Jayeng Rono menikam tajam, Tunggul Wetu mengembangkan kipasnya untuk menangkis.
Trakkk!
Pada saat yang hampir bersamaan, kapak Janang Uwung melesat menyambar pinggang.
“Uhhh...!” Ki Jayeng Rono melenguh, merasa tidak mungkin menghindari serangan yang demikian cepat. Jalan satu-satunya, dia mesti mundur ke belakang. Cepat kakinya melangkah mundur. Namun baru saja bergerak, Tunggul Wetu sudah maju selangkah. Kemudian sebelah kakinya mengirim tendangan keras ke perut.
Desss...!
“Aaakh...!” Ki Jayeng Rono menjerit kesakitan. Namun begitu dia masih mampu berjumpalitan, lalu tegak berdiri meski agak sempoyongan.
“Kau boleh mampus sekarang juga!” desis Janang Uwung, langsung berkelebat sambil mengibaskan kapak.
Sebisa-bisanya Ki Jayeng Rono mengibaskan pedang untuk menangkis.
Trang!
Pada saat hampir bersamaan, serangan Tunggul Wetu telah berkelebat mengancamnya. Dengan gerakan mengagumkan, Ki Jayeng Rono menangkis kipas Tunggul Wetu.
Trang!
Begitu habis terjadi benturan senjata, Ki Jayeng Rono balas menyerang lewat tendangan ke ulu hati. Dengan demikian tubuhnya sedikit maju ke depan. Agaknya hal itu telah diperhitungkan.
TUJUH
Namun, Ki Jayeng Rono agaknya salah perhitungan. Meski kelihatan gerakan Tunggul Wetu agak lambat, namun mendadak bisa berubah secepat kilat. Tiba-tiba saja tubuhnya mengegos ke kiri dengan sikut bergerak ke wajah. Begitu cepat gerakannya, sehingga....
Diekh!
“Aaakh...!” Ujung sikut Tunggul Wetu menghantam ke wajah Ki Jayeng Rono. Lalu kipasnya mendadak terkembang, dan menyabet ke samping kanan.
Wuttt!
Crasss...!
“Aaakh...!” Ki Jayeng Rono terpekik, ketika tangan kanannya putus setengah jengkal dari pergelangan disabet ujung kipas Tunggul Wetu yang runcing. Sementara hidungnya berdarah, terhantam sikut Orang tua itu kontan mundur beberapa langkah, sambil memegangi tangannya yang buntung.
“Sebaiknya serahkan gulungan kulit itu pada kami. Dan pergilah kau serta keluargamu dari sini. Kalau tidak, kau tidak akan selamat!” ancam Tunggul Wetu sinis.
“Huh! Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan!” tukas Ki Jayeng Rono.
“Kau masih berusaha menghindar dan mengelak dari kami?!” bentak Janang Uwung.
Ki Jayeng Rono meringis kesakitan. “Aku tidak kenal kalian. Dan, jangan coba-coba memaksaku!” dengus laki-laki tua ini geram.
“Ha ha ha...! Kalau memang kau ingin melihat kematian keluargamu satu persatu, maka pertahankan saja benda itu. Lihatlah ke sekelilingmu! Mereka tidak punya harapan hidup lagi!”
Ki Jayeng Rono langsung mengedarkan pandangan ke sekeliling. Benar apa yang dikatakan Tunggul Wetu. Satu persatu pembantu orang tua itu telah dibantai habis. Sedang yang lainnya masih bertahan. Namun agaknya tidak akan lama, sebab luka-luka di sekujur tubuh mereka semakin mempersulit gerakan. Padahal saat itu, laki-laki bertopeng yang bernama Singodimejo tengah mengamuk pula, menimbulkan korban yang tidak kalah banyak.
“Bagaimana, Jayeng Rono? Kau masih tetap ngotot ingin mempertahankan gulungan kulit itu?” desak Tunggul Wetu.
Ki Jayeng Rono jadi bimbang. Sesaat pikirannya berkecamuk. Apakah mesti menuruti permintaan mereka? Dengan begitu, dia akan terhina. Bahkan seluruh harta kekayaannya akan dirampas. Tapi kalau terus bertahan, maka keluarganya pasti akan disapu bersih. Ini pilihan yang betul-betul sulit! Tapi...
“Iblis-iblis bertopeng, enyahlah kalian dari sini!”
Mendadak terdengar seseorang berteriak marah. Dan tahu-tahu seorang gadis yang baru meningkat remaja mendadak muncul di ambang pintu gerbang. Dia langsung mencelat menyerang Ki Singodimejo yang berjuluk si Singa Bermuka Merah.
“Yeaaa...!”
Gadis ini langsung melepaskan tendangan terbang bertenaga kuat. Namun orang yang dihadapi telah kenyang makan asam garam dunia persilatan. Ki Singodimejo segera mengetahui kalau serangan itu sama sekali tidak membahayakannya. Maka segera disiapkan sebuah hantaman bertenaga dalam tinggi.
Sedikit lagi hantaman si Singa Bermuka Merah itu menghantam kaki gadis yang menyerangnya, mendadak berkelebat satu sosok yang langsung mengebutkan tangannya.
Plak!
“Heh?!” Ki Singodimejo terkejut merasakan pukulannya seperti membentur batu karang. Padahal tenaga dalamnya yang disalurkan di tangan telah dikerahkan begitu tinggi. Dia bisa merasakan tenaga dalam sosok bayangan putih itu hebat luar biasa. Buktinya tangannya terasa nyeri bukan main.
Ki Singodimejo mundur beberapa langkah seraya memandang kepada sosok pemuda tampan berbaju rompi putih dengan pedang bergagang burung rajawali menyembul dibalik punggung yang menghadang serangannya.
Sementara itu gadis yang menyerang Ki Singodimejo tadi tak kalah kagetnya. Dia sudah melangkah mundur sambil mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi.
“Sri Dewi...!” Tiba-tiba sebuah suara terdengar menggigil.
Gadis yang tak lain memang Sri Dewi menoleh. “Ibu...!”
Sambil berteriak, Sri Dewi menghambur ke arah seorang wanita setengah baya yang memang ibunya. Sesaat ibu dan anak itu saling berpelukan haru.
“Siapa kau, Bocah Edan?!”
Pelukan ibu dan anak itu langsung terlepas, begitu terdengar suara bentakan.
“Aku Rangga...!” sahut sosok pemuda berbaju rompi putih yang memang Rangga alias Pendekar Rajawali Sakti. Rupanya, Sri Dewi datang tadi bersama Rangga.
“Ki Singodimejo, hati-hati! Bocah itu bisa menghajarmu!” teriak Tunggul Wetu yang melihat kehadiran Pendekar Rajawali Sakti di tempat ini.
“Huh! Segala bocah ingusan kenapa dibuat takut segala?!” dengus Ki Singodimejo, memandang enteng.
Tunggul Wetu menyesalkan sikap sahabatnya. Bukan tanpa sebab dia berkata begitu. Karena dia sendiri pernah mencicipi sendiri hajaran Pendekar Rajawali Sakti. Padahal, ilmu silatnya tidak terpaut jauh dengan si Singa Bermuka Merah. Dan di samping itu pula hatinya ketar-ketir menyadari bahwa pemuda itu berada disini. Tapi hatinya sedikit tenteram mengetahui bahwa kini mereka berenam.
“Memang tak ada yang perlu ditakutkan. Toh kedatanganku kesini hanya untuk mencegah kalian agar jangan terlalu mengumbar keangkaramurkaan..." kata Rangga, halus.
“Bocah tengik, apa kehebatanmu sehingga bertingkah didepanku?!” bentak Ki Singodimejo. “Hiaaat..!”
Seketika si Singa Bermuka Merah menerjang sambil menggerakkan kedua tangannya, seperti mencakar.
“Uts!” Namun dengan mengerahkan jurus ‘Sembilan Langkah Ajaib’, Pendekar Rajawali Sakti mampu menghindarinya. Tubuhnya meliuk-liuk seperti orang mabuk. Sehingga serangan kedua tangan berbentuk cakar itu tak satu pun yang berhasil mendarat tepat.
Mendapati serangannya gagal, Ki Singodimejo meningkatkan serangannya. Tangan kanannya, yang membentuk cakar, kembali berkelebat disertai tenaga dalam tinggi.
Namun kali ini Pendekar Rajawali Sakti tidak berusaha menghindar. Bahkan tiba-tiba tangannya yang membentuk paruh rajawali berkelebat memapak.
Plak!
“Aaakh...!” Si Singa Bermuka Merah itu menjerit kesakitan begitu tangannya terpapak. Terdengar suara berderak menandakan tulang-tulang jari yang patah. Wajahnya meringis kesakitan.
Ki Singodimejo kelihatan penasaran sekali. Saat itu juga sebelah tangannya yang masih utuh langsung mencabut senjata andalannya. Dan seketika kembali diserangnya Pendekar Rajawali Sakti.
“Yeaaa...!”
Rangga bersiap-siap menghadapi sambaran senjata tongkat berujung cakar dari baja. Dua kali sabetan ke perut dan lehernya dapat dihindari dengan melompat kesamping sambil merendahkan tubuh. Tangan kirinya kemudian bergerak cepat menangkap pergelangan tangan Ki Singodimejo.
Tap!
“Hih!” Seketika Pendekar Rajawali Sakti menarik tangan si Singa Bermuka Merah dengan kaki kanan bergerak menggedor dada.
Begkh!
“Aaakh...!” Kembali si Singa Bermuka Merah terpekik kesakitan. Senjatanya langsung lepas dari genggaman. Tubuhnya terjungkal beberapa langkah ke belakang. Wajahnya pucat dan berkerut kesakitan. Tangannya yang tak cedera menyeka darah yang meleleh di ujung bibirnya.
Melihat keadaan demikian agaknya orang bertopeng yang tadi bertarung melawan Ki Danang Rejo dan Sukasrana tidak tinggal diam, segera ditinggalkannya kedua lawannya. Langsung diterjangnya Pendekar Rajawali Sakti.
“Bocah usil! Rasakan pukulanku! Heaaat...!” bentak orang bertopeng itu sambil menghantamkan tangan ke batok kepala Pendekar Rajawali Sakti.
Tapi, Rangga dengan seenaknya membuka tangan kiri. Langsung disambutnya kepalan itu dengan kibasan telapak tangannya.
Plak! Plak!
Orang bertopeng itu kontan persendiannya bergetar dan terasa linu. Meski begitu dia kembali melanjutkan serangan dengan sebuah hantaman kepalan tangan kiri. Sekali lagi, dengan tangkas Rangga menangkis. Namun kali ini dibarengi tendangan keras ke arah perut.
Plak! Des!
“Aaakh...!” Orang bertopeng itu kontan terpental ke belakang sambil menjerit kesakitan. Namun dia cepat bangkit Pada saat yang sama, Ki Singodimejo sudah bangkit berdiri. Kini kedua orang bertopeng itu siap mengeroyok Pendekar Rajawali Sakti. Namun belum sempat mereka bergerak....
Sriiing!
Seketika Pendekar Rajawali Sakti mencabut Pedang Pusaka Rajawali Sakti. Tujuannya jelas untuk sekadar menakut-nakuti. Dan ternyata, kedua orang bertopeng itu terkejut setengah mati dan langsung menghentikan serangan. Mereka hanya terpaku, memandang perbawa pedang yang memancarkan sinar biru berkilauan.
“Hei? Dia Pendekar Rajawali Sakti?!” teriak Ki Singodimejo, begitu berhasil menguasai keterkejutannya.
“Celaka! Pantas saja kita tidak mampu melawannya!” timpal orang bertopeng satunya.
Mendengar teriakan itu, seluruh orang bertopeng menghentikan pertarungan. Mereka kini tahu betul, siapa yang dihadapi. Seorang pendekar besar yang namanya menggetarkan rimba persilatan.
“Kenapa berhenti, Kisanak? Apa yang aneh pada diriku?” tanya Rangga, dingin.
“Pendekar Rajawali Sakti! Masalah yang ada disini bukan urusanmu. Maka, sebaiknya jangan mencampurinya!” dengus Ki Singodimejo.
“Kalian membantai manusia seenaknya. Maka itu sudah menjadi urusanku!” sahut Rangga, tegas.
“Ini urusan pribadi kami dengan mereka!” sambung laki-laki bertopeng di samping Ki Singodimejo.
“Menjadi urusan pribadiku pula, bila kalian tidak bisa menjelaskan kenapa melakukan pembantaian di sini.”
“Si Jayeng Rono itu manusia durjana. Untuk apa kau membelanya?!” bentak Ki Singodimejo.
“Yang kulihat durjana malah kalian. Maka jangan bersilat lidah di depanku! Pergilah. Dan, bawa anak buahmu sejauh-jauhnya. Jangan sampai pikiranku berubah!” ancam Pendekar Rajawali Sakti.
Ki Singodimejo dan orang bertopeng di sampingnya menggeram marah. Namun keduanya hanya bisa saling pandang, tanpa bisa berbuat apa-apa. Karena mereka tahu, bila melawan sama artinya mencari penyakit.
“Kau telah berurusan dengan Gerombolan Topeng Merah. Maka, jangan anggap urusan ini selesai begitu saja. Ketua kami tentu akan membuat perhitungan denganmu!” ancam Ki Singodimejo seraya berbalik. Segera kawan-kawannya diajak untuk angkat kaki.
Bagi Tunggul Wetu dan Janang Uwung yang sudah tahu kehebatan Pendekar Rajawali Sakti tentu memilih angkat kaki daripada bertahan disini. Demikian pula yang lainnya. Rata-rata mereka kenal, siapa Pendekar Rajawali Sakti.
“Katakan pada ketuamu. Jangan terlalu mengumbar nafsu, bila tidak ingin berhadapan denganku!” ujar Rangga kalem.
Orang-orang bertopeng itu segera berkelebat cepat dari tempat ini. Begitu cepatnya, sehingga mereka cepat lenyap dari pandangan.
Ki Jayeng Rono yang merasa lepas dari lubang jarum, bernapas lega. Buru-buru dihampirinya Pendekar Rajawali Sakti.
“Pendekar Rajawali Sakti.... Namamu menjulang tinggi di rimba persilatan. Dan, telah banyak orang tertindas yang merasakan pertolonganmu. Tidak sangka bahwa hari ini akulah yang mendapat anugerah pertolonganmu...,” ucap Ki Jayeng Rono, sambil meringis menahan sakit pada tangan kirinya yang buntung. Tubuhnya membungkuk sedikit, saat membuka suara.
“Jangan terlalu memuji, Ki. Aku hanya manusia biasa yang hanya sedikit mempunyai kepandaian untuk membantu orang lemah. Aku tidak beda dengan kalian semua,” sahut Rangga merendahkan diri.
“Ah! Kau terlalu merendahkan diri, Pendekar Rajawali Sakti. Aku Ki Jayeng Rono, pemimpin perkampungan ini. Kalau kau tidak keberatan, sudilah bertamu ke gubuk kami.”
“Aku Rangga. Jadi panggil saja aku dengan namaku. Jangan menyebut gelarku!” ujar Pendekar Rajawali Sakti.
“Baiklah, Pendekar Rajawali Sakti..., eh! Rangga! Sudilah menginap di tempat ini!”
Ki Jayeng Rono setengah memaksakan keinginannya untuk mengundang Pendekar Rajawali Sakti ke tempatnya. Ini suatu kebetulan yang amat diharapkannya. Kepandaian pemuda ini bisa digunakannya untuk menakut-nakuti Gerombolan Topeng Merah yang tengah menekannya belakangan ini.
Dan Rangga tidak bisa menolak ketika yang lain pun seperti mendesaknya untuk bermalam di tempat itu. Sehingga mau tidak mau terpaksa menyetujuinya.
DELAPAN
Malam telah larut dan suasana di perkampungan itu terlihat sunyi. Bukan saja karena semua penghuninya tengah berkabung karena kehilangan banyak anggota, tapi juga karena terlalu letih akibat pertarungan tadi. Tenaga mereka seperti terkuras habis.
Pembicaraan antara Pendekar Rajawali Sakti dengan tuan rumah pun berlangsung tidak lama. Mereka hanya mengulang-ulang pernyataan terima kasih atas pertolongan Pendekar Rajawali Sakti yang telah menyelamatkan Sri Dewi, sekaligus keluarga ini dari serbuan Gerombolan Topeng Merah.
Rangga menghela napas. Dia yang terlebih dulu mengundurkan diri karena merasa jemu mendengar puja-puji Ki Jayeng Rono yang setinggi langit Orang tua itu kelewat ramah, sehingga membuatnya jengah. Telinganya sumpek mendengar puji-pujian dan sikap manis yang seperti dibuat-buat.
Ruangan yang dihuni Pendekar Rajawali Sakti, tidak luas namun rapi. Sebuah ranjang yang beralas sutera halus, membuat Pendekar Rajawali Sakti seperti ingin menikmatinya. Tapi entah kenapa, matanya tak mau terpejam. Dan tiba-tiba....
“Kebakaran...! Kebakaran...!”
“Aaa...!” “Aaakh...!”
Pendekar Rajawali Sakti langsung melompat dari tempat tidur begitu terdengar teriakan kebakaran dan jerit kematian yang saling sambung-menyambung. Ketika berada di luar terlihat malam yang pekat tiba-tiba dikejutkan cahaya merah menyala. Tampak asap hitam mengepul-ngepul di udara.
Api menyala dengan garangnya, membakar apa saja pada bangunan rumah milik Ki Jayeng Rono. Dan itu pun masih ditingkahi pekik kematian dari segala arah.
“Kurang ajar!” umpat Pendekar Rajawali Sakti geram.
Secepat kilat, Rangga berkelebat ke belakang bangunan rumah ini, tempat asal jeritan. Begitu tiba di belakang, Pendekar Rajawali Sakti melihat seorang bertopeng merah tengah membantai anak buah serta para pegawai Ki Jayeng Rono yang berusaha memadamkan api.
Jumlah mereka ternyata cukup banyak. Karena dibeberapa sudut terlihat orang-orang bertopeng merah lain yang melakukan sepak terjangnya dengan beringas. Tanpa membuang waktu lagi, Pendekar Rajawali Sakti berkelebat ke arah orang bertopeng yang bersenjata sepasang trisula.
Plak!
“Aaakh...!” Orang bertopeng itu terkejut, ketika tahu-tahu trisulanya terpental, terpapak sambaran tangan Rangga. Tanpa berpikir panjang lagi trisulanya yang satu lagi langsung berkelebat menyerang.
Tapi dengan liukan tubuh yang manis, Pendekar Rajawali Sakti berhasil menghindarinya. Bahkan tiba-tiba tangannya bergerak mengibas dengan jurus ‘Pukulan Maut Paruh Rajawali’ yang berisi tenaga dalam tinggi ke arah kepala.
Prak!
“Aaakh...!” Orang bertopeng itu kontan terjengkang dengan kepala retak. Dari sela-sela kedua telapak tangannya yang memegangi kepala, tampak mengalir darah segar. Sebentar orang itu kelojotan, lalu diam tidak berkutik lagi.
Tanpa peduli lagi Rangga terus berkelebat menghampiri orang bertopeng yang lain. Memang kali ini dia tidak mau bertindak tanggung-tanggung. Dia merasa orang-orang bertopeng merah ini tidak mengindahkan ancamannya. Terbukti mereka datang dengan jumlah yang berkali lipat lebih banyak.
Baru saja Pendekar Rajawali Sakti tiba di depan sosok orang bertopeng yang akan jadi sasarannya, mendadak berkelebat satu bayangan merah yang langsung menghadang gerakannya pada jarak dua tombak.
Rangga kini berhadapan dengan seorang laki-laki tua renta berambut panjang digelung ke atas. Dia memakai jubah merah yang berkibar-kibar ditiup angin. Jenggotnya panjang berwarna putih, seperti warna rambutnya. Demikian pula kumisnya. Wajahnya dingin, mengandung hawa maut!
“Kaukah orang yang berjuluk Pendekar Rajawali Sakti?” desis laki-laki tua ini.
“Benar! Dan kau sendiri siapa, Kisanak?”
“Kau kini berhadapan dengan Ketua Gerombolan Topeng Merah, Orang Usilan! Heaaat..!”
Tanpa memberi kesempatan pada Rangga, laki-laki tua yang mengaku sebagai Ketua Gerombolan Topeng Merah meluruk, melepaskan pukulan maut bertenaga dalam tinggi.
“Hiiih!”
“Wesss!”
Seketika selarik cahaya merah menyambar ke arah Pendekar Rajawali Sakti. Seketika, Rangga melompat ke samping seraya mengerahkan jurus ‘Sembilan Langkah Ajaib’ untuk menghindarinya.
“Huh...! Kurang ajar!” Laki-laki tua berjubah merah yang merupakan Ketua Gerombolan Topeng Merah itu mendengus geram, melihat serangannya yang tiba-tiba tidak mengenai sasaran. Padahal, bila orang biasa, sudah pasti tak akan bisa lolos.
Kini Ketua Gerombolan Topeng Merah menatap tajam Pendekar Rajawali Sakti, sinar matanya menyiratkan kebencian. Bibirnya tertarik, mengembangkan senyum sinis.
“Bagus! Pantas saja kau berani petantang-petenteng. Rupanya kau punya kepandaian lumayan!” leceh Ketua Gerombolan Topeng Merah.
“Aku tidak bermaksud petantang-petenteng. Tapi, sekadar memperingatkan kalau kalian tidak bisa seenaknya saja main bunuh tanpa alasan kuat,” kilah Rangga, berusaha membela diri.
“Tahu apa kau tentang si Jayeng Rono, Bocah?!”
“Aku memang tidak tahu banyak. Tapi, itu tidak penting. Yang terpenting adalah, aku tahu orang seperti apa kalian ini!”
“Banyak mulut! Sudah waktunya kau mampus!” bentak Ketua Gerombolan Topeng Merah.
Begitu habis kata-katanya, laki-laki tua itu mencelat ke atas melepaskan pukulan bertubi-tubi yang berisi tenaga dalam tinggi. Agaknya, dia bermaksud membuat pemuda ini repot.
Tapi, perkiraan Ketua Gerombolan Topeng Merah ini terlalu gegabah. Sebab, dengan masih menggunakan jurus ‘Sembilan Langkah Ajaib’ Rangga mampu menghindari. Tubuhnya terus meliuk-liuk. Bahkan kadang condong hampir jatuh. Hingga tak satu serangan pun yang berhasil menyentuh tubuhnya.
“Hup!” Tiba-tiba saja Pendekar Rajawali Sakti melenting ke atas. Jurusnya langsung berubah menjadi ‘Sayap Rajawali Membelah Mega’. Kedua tangannya bergerak mengebut-ngebut, bagaikan sayap rajawali.
“Yeaaa...!”
Pada saat yang sama, laki-laki Ketua Gerombolan Topeng Merah tidak menyia-nyiakan kesempatan. Secepat kilat kedua tangannya dihentak, ke arah Pendekar Rajawali Sakti.
Wesss...!
Seketika selarik cahaya merah menderu dahsyat ke arah Rangga. Namun agaknya Pendekar Rajawali Sakti memang telah memperhitungkan. Sengaja tubuhnya melenting, agar Ketua Gerombolan Topeng Merah menyerangnya. Dan ternyata pancingannya mengena. Maka begitu satu tombak lagi serangan itu menghantam, tubuhnya berkelit dengan bergulingan di udara. Dan begitu cahaya merah itu lewat, Rangga cepat merubah jurusnya menjadi ‘Rajawali Menukik Menyambar Mangsa’.
“Heaaa...!” Pendekar Rajawali Sakti langsung meluruk cepat, ke arah Ketua Gerombolan Topeng Merah yang tersirap kaget. Laki-laki tua ini benar-benar tak menduga gerakan Pendekar Rajawali Sakti yang cepat bukan main. Dan sebelum dia sempat berbuat apa-apa....
Sring!
Dengan gerakan cepat luar biasa, Pendekar Rajawali Sakti mencabut Pedang Pusaka Rajawali Sakti. Lalu secepat kilat pula, pedang yang mengeluarkan sinar biru berkilauan ini berkelebat ke arah leher. Dan....
Crasss...!
“Aaa...!” Disertai pekik kematian Ketua Gerombolan Topeng Merah ambruk di tanah dengan leher buntung. Tubuhnya kontan merejang-rejang dijemput ajal. Kepalanya menggelinding terpisah beberapa tombak dari lehernya yang terus mengucurkan darah.
“Hhh...!” Rangga menghela napas lega. Dipandangnya mayat Ketua Gerombolan Topeng Merah. Lalu perhatiannya beralih pada pertarungan yang belum selesai. Orang-orang bertopeng itu agaknya belum menyadari kalau ketua mereka telah tewas, sehingga mereka terus menyerang.
“Hentikan pertarungan kalian. Dan, menyerahlah! Pemimpin kalian telah binasa di tanganku...!” teriak Pendekar Rajawali Sakti, lantang.
Suara Rangga langsung bergema di sekitar tempat itu, karena dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam cukup hebat.
“Heh?!” Orang-orang bertopeng merah itu terkesiap. Sesaat mereka berusaha meyakinkan penglihatan kalau pemimpin mereka telah tewas.
“Aku tidak mau cari penyakit dengan mati konyol!” desis salah satu orang bertopeng. Saat itu juga, tubuhnya berbalik dan berkelebat kabur dari tempat itu.
Tindakan orang bertopeng itu segera diikuti beberapa kawannya, yang kemudian segera mengajak yang lain untuk kabur. Tidak lama, seluruh orang bertopeng telah kabur dari tempat itu.
Sementara suasana di perkampungan Ki Jayeng Rono kelihatan berkabung. Semua orang berkumpul di halaman paling besar dan diantara halaman-halaman rumah yang ada di perkampungan ini. Tampak mayat-mayat korban keganasan Gerombolan Topeng Merah telah dikumpulkan di tempat ini. Hal yang paling mengenaskan adalah, tewasnya Ki Jayeng Rono, Sukasrana, dan Ki Danang Rejo.
Tak seorang pun yang tahu kalau sebelum pertempuran tadi, Ketua Gerombolan Topeng Merah telah bersembunyi di ruangan khusus yang biasa digunakan Ki Jayeng Rono. Di sinilah, sesepuh perkampungan itu terbantai, setelah tak bersedia menyebutkan tempat disembunyikannya kulit binatang yang menyimpan peta harta.
Secara kebetulan, Sukasrana pada saat itu juga hendak menemui kakeknya. Maka, pemuda itu pun menjadi korban pula. Sementara Ki Danang Rejo yang kamarnya berdekatan, begitu mendengar jeritan segera berusaha membalas kematian sahabatnya. Namun dengan mudah dia tewas di tangan Ketua Gerombolan Topeng Merah.
Semua orang termasuk tamu-tamu telah berkumpul untuk menghormati jenazah almarhum. Namun, bola mata gadis bernama Sri Dewi mencari-cari seseorang. Rasanya ada yang kurang. Ternyata pemuda berbaju rompi putih berjuluk Pendekar Rajawali Sakti tidak ada dalam kerumunan orang-orang.
“Kau mencarinya, Sri Dewi...?”
Terdengar suara teguran, membuat Sri Dewi menoleh. “Eh, Ibu..., kukira siapa.”
“Kau tengah mencari Rangga?” ulang wanita setengah baya yang memang ibu dari Sri Dewi.
“Benar, Ibu.... Apakah Ibu melihatnya?”
“Sayang sekali. Dia sudah pergi sejak tadi...,” sahut wanita setengah baya itu.
“Pergi? Tanpa pamit?” tanya Sri Dewi.
Wanita itu mengangguk pelan. Dan terlihat Sri Dewi terpaku untuk beberapa saat. “Dia pergi setelah melihat orang-orang bertopeng merah itu kabur. Aku sendiri tak tahu kenapa dia tidak mau pamit. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya sungkan. Atau... entahlah. Mungkin juga ada persoalan mendesak yang mesti diselesaikannya. Tapi dia kirim salam untukmu...,” lanjut wanita setengah baya ini.
Gadis yang baru beranjak besar itu masih terpaku ditempatnya. Sepertinya dia tak percaya kalau penolongnya, sekaligus tokoh yang dikagumi, pergi meninggalkannya begitu saja. Padahal dia ingin sekali berbincang-bincang tentang berbagai hal dalam waktu yang cukup lama. Tapi....
“Kau menyukainya...?” usik wanita setengah baya istri Dilaga ini dengan bibir tersenyum.
Sri Dewi tidak menjawab. Kepalanya langsung melengos, lalu melangkah pergi. Dia kembali bergabung di antara kerumunan orang. Dan diam terpaku seperti patung...!
S E L E S A I
EPISODE BERIKUTNYA: SEPASANG TAJI IBLIS

