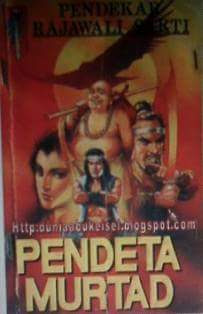PENDETA MURTAD
SATU
Ctar! Ctar!
“Heaaa...!” Lecutan cambuk terdengar berkali-kali membelah, ditingkahi teriakan membahana. Kemudian terdengar derap seekor kuda berwarna coklat yang melesat sejadi-jadinya bagaikan sedang dikejar setan.
Penunggangnya seorang laki-laki berusia lima puluhan, tapi masih tampak gagah dan berwibawa. Entah ada urusan apa, sampai dia mengendarai kuda secepat itu. Begitu sampai di tepi sebuah hutan kecil yang cukup gelap, mendadak laki-laki setengah baya menarik tali kekang kudanya, ketika di depannya pada jarak sepuluh tombak berdiri satu sosok tubuh berpakaian serba merah.
Setelah berhasil mengendalikan kudanya, laki-laki setengah baya itu melompat dengan gerakan ringan. Dan setelah beberapa kali berjumpalitan di udara, kakinya mendarat dengan mulus di tanah. Langsung diawasinya manusia bercadar itu dari kepala sampai ke kaki.
“Siapa kau, Kisanak...? Mengapa kau menghadang perjalananku...?” tegur laki-laki setengah baya itu dengan wajah tak senang.
“Ha ha ha...! Masih ingatkah kau pada seorang perampok yang bernama Sampuraga, Giras Lawa? Kalian telah menghina dan mengeroyok, sehingga dia melarikan diri dari tanah Jawa?” sahut sosok berpakaian serba merah dan bercadar merah yang jelas seorang laki-laki.
“Hah...?! Siapa kau...? Apa hubunganmu dengan perampok kejam dan telengas itu...?” laki-laki setengah baya bernama Ki Giras Lawa ini balik bertanya, terkejut. Wajahnya sedikit pucat. Tetapi, dia berusaha tenang dan mengatasi rasa terkejutnya.
“Ha ha ha...! Kau tak perlu tahu, siapa aku. Yang jelas, aku utusan Sang Pendeta yang akan menghukummu! Heaaa...!” sahut sosok bercadar merah tenang, sambil meluruk dengan golok di tangan berkelebat mengarah tenggorokan.
“Hiaaa...!” Tetapi sambil berteriak keras Ki Giras Lawa menangkis dengan pedangnya.
Trang!
Terjadi benturan dua senjata, membuat masing-masing terjajar beberapa langkah. Namun Ki Giras Lawa telah memutar pedangnya setengah lingkaran, dan langsung meluncur ke tenggorokan sosok yang mengaku sebagai utusan Sang Pendeta.
“Hiih...!” Laki-laki bercadar merah ini menangkis.
Namun pedang Ki Giras Lawa membeset ke bawah, mengancam ulu hati. Maka dengan tidak kalah cepatnya, golok utusan Sang Pendeta membabat pinggang Ki Giras Lawa. Kalau dilanjutkan, tentu keduanya akan mati bersama. Dan tentu saja Ki Giras Lawa tidak mau mati secara demikian. Maka sambil menarik pedangnya, laki-laki setengah baya ini meloncat mundur.
Melihat Ki Giras Lawa tidak berani mengadu jiwa, laki-laki bercadar tertawa mengejek. Dan dia terus mendesak dengan serangan-serangan keras disertai tenaga dalam tinggi. Ki Giras Lawa terpaksa meladeni. Tubuhnya seketika melompat ke sana kemari bagaikan gerakan seekor belalang. Sambil bergerak, pedangnya berputar-putar melindungi diri. Sesekali, dikirimkannya serangan balasan.
“Hm...! Hanya begini saja kemampuan manusia sombong Ketua Padepokan Walang Wesi yang mengeroyok Sampuraga! Sekarang, terimalah ajalmu. Heaaa...!”
Disertai teriakan keras, utusan Sang Pendeta menerjang maju. Tenaga dalam penuh dikerahkan. Tulang tangannya sampai terdengar berkerotokan. Begitu berada dua setengah tombak di hadapan Ki Giras Lawa, kedua tangannya dihentakkan.
Zeb! Zeb!
Angin pukulan keras terdengar nyata, ketika utusan Sang Pendeta melepas pukulan jarak jauh. Pasir dan daun kering sampai berterbangan ke atas. Merasa terdesak, Ki Giras Lawa menyambuti. Kedua tangannya cepat dihentakkan disertai tenaga dalam tinggi.
Blarrr...!
Terdengar ledakan keras ketika dua tenaga dalam tinggi beradu pada satu titik. Sementara Ki Giras Lawa terhuyung-huyung ke belakang dengan tangan terasa sakit. Pedang yang digenggamnya hampir terlepas.
Melihat ada kesempatan, laki-laki bercadar ini tanpa pikir panjang segera memanfatkannya. Segera dia melompat sambi! menebas Ki Giras Lawa dengan goloknya. Ki Giras Lawa yang dalam keadaan tak menguntungkan cepat menaikkan pedang ke atas untuk menahan serangan.
Trang!
“Uhhh...!” Begitu pedangnya bertemu golok, kembali telapak tangan Ketua Padepokan Walang Wesi itu terasa perih bukan main. Kulitnya tampak mengelotok. Tidak dapat dipertahankan lagi, pedangnya terlepas dari pegangan setelah terjajar tiga langkah. Belum hilang rasa sakitnya, sebuah tendangan telak menghantam dadanya.
Buk!
“Aaakh...!” Ki Giras Lawa kontan terlempar disertai semburan darah dari sudut bibirnya. Sebagai seorang ketua padepokan, dia tidak mau menunjukkan kelemahan. Cepat tubuhnya melenting bangkit. Tetapi karena sedang terluka, gerakannya jadi tersendat dan kaku.
Hal itu tidak lepas dari pandangan utusan Sang Pendeta. Seketika tangan kanannya dihentakkan. Sebuah pukulan jarak jauh kembali dilancarkan.
Wer...! Jblarrr...!
“Waaa...!” Pukulan itu tepat menghantam perut Ki Giras Lawa yang kontan terlempar. Begitu jatuh di tanah, seluruh isi perutnya bagai terbalik. Matanya terasa gelap. Dia tidak sadarkan diri. Dari mulut, hidung, dan telinga mengucur darah segar. Agaknya laki-laki ini mendapat luka dalam yang parah, dan tinggal menunggu waktu saja. Tetapi laki-laki bercadar ini seperti tidak puas bertindak. Golok besarnya segera diangkat tinggi-tinggi. Dan sekali tebas....
Crasss...!
Tanpa bersuara lagi kepala Ki Giras Lawa tanggal dari tubuhnya. Darah menyembur dari lubang bekas lukanya.
“Hm.... aku akan membawa mayatnya ke Padepokan Walang Wesi,” gumam utusan Sang Pendeta.
********************
Padepokan Walang Wesi gempar, dengan ditemukannya mayat Ki Giras Lawa di halaman depan. Para murid padepokan begitu geram melihat keadaan mayat yang mengenaskan. Ketua Padepokan Walang Wesi ini terbunuh dengan kepala terpisah. Yang lebih menggeramkan, di dada mayat terdapat secarik kain berisi tulisan dari darah.
Yang bertanggung jawab atas kematian ini adalah si Cadar Merah, utusan Sang Pendeta. Ki Giras Lawa telah membayar lunas hutang lamanya pada Sampuraga. Sekarang semuanya telah selesai. Si Cadar Merah.
Seminggu setengah penguburan mayat Ki Giras Lawa, kain yang ditulis dari tinta darah itu masih tergenggam erat di tangan pemuda tampan dengan wajah persegi. Badannya kekar, dengan otot-otot bertonjolan. Pakaiannya ketat berwarna merah. Rambutnya selalu berwarna hitam pekat.
“Ayah! Aku bersumpah akan menuntut balas atas perlakuan dan penghinaan ini terhadapmu. Akan kucari orang yang berjuluk si Cadar Merah itu...,” desis pemuda yang tak lain anak tunggal Ki Giras Lawa.
Sambil berkata demikian, pemuda ini meremas kain yang digenggamnya. Dengan amarah meluap, tanpa sadar dia mengerahkan tenaga dalam tinggi. Akibatnya, kain itu jadi hancur bagai tepung!
“Sudahlah, Mudrika. Relakan kepergian ayahmu...,” hibur seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun yang selalu setia menemani pemuda anak tunggal Ki Giras Lawa yang bernama Mudrika.
“Tidak, Kakang Maharata! Sekarang juga aku harus berangkat!” tandas Mudrika.
“Bukan begitu, Mudrika. Biarlah aku yang akan berangkat mencari si Cadar Merah. Kalau kau berangkat, siapa yang mengurus padepokan ini?” kilah laki-laki bernama Maharata.
“Sebagai pengganti ayah, aku menugaskanmu mengurus padepokan ini. Kau murid utama, Kakang Maharata. Dan lagi, aku ingin membunuh si Cadar Merah dengan tanganku sendiri!” Maharata hanya mendesah.
Tak bisa lagi dia menghadapi tekad putra gurunya ini. Malah sejak kemarin, Mudrika telah membereskan perbekalan yang hendak dibawa. Dia telah bertekad tak akan kembali, sebelum berhasil membalaskan dendam ayahnya. Semua urusan dalam Padepokan Walang Wesi, tadi telah diserahkan pada Maharata. Mudrika memang sudah tidak mempunyai ibu, sehingga kepergian ayahnya merupakan pukulan berat yang tak terhingga.
********************
Berita kematian Ketua Padepokan Walang Wesi, telah mengejutkan kalangan persilatan. Apalagi dalam peristiwa itu disebut-sebut nama Sampuraga, dan si Cadar Merah yang mengaku sebagai utusan Sang Pendeta. Soal Sang Pendeta dan si Cadar Merah, masih asing bagi kalangan persilatan. Tapi nama Sampuraga?
Tokoh itu ternyata memang pernah membuat ulah yang menghebohkan. Para tokoh persilatan tahu, Sampuraga dulu bekas seorang tokoh aliran hitam yang ditakuti. Membunuh, memperkosa, dan merampok sudah merupakan pekerjaan sehari-harinya. Kepandaiannya tinggi dan pengikutnya banyak.
Siapa pun akan berpikir panjang kalau harus berurusan dengannya. Sampai suatu saat, amarah para tokoh golongan putih pun meledak. Mereka bertindak, mengeroyok Sampuraga yang merupakan biang penyakit yang tidak berperikemanusiaan. Akhirnya, Sampuraga berhasil dikalahkan.
Namun sayang, dia berhasil melarikan diri entah ke mana. Kalau melihat luka-lukanya para tokoh golongan putih berpendapat, Sampuraga telah binasa. Apalagi setelah sepuluh tahun lamanya, manusia berjiwa iblis itu tidak pernah muncul lagi dalam dunia persilatan.
Lalu, siapa yang telah muncul saat ini...? Apakah Sampuraga yang sekarang muncul sama dengan Sampuraga yang dulu...?! Kalau benar, tentu akan muncul kembali peristiwa besar dan berdarah!
********************
Walaupun saat ini matahari bersinar penuh, namun tak juga mampu mengusir kabut di puncak Gunung Saka ini. Sebagian sinar matahari, memberi suasana cerah di sebuah padepokan yang di kalangan persilatan dikenal sebagai Padepokan Kijang Kencana. Padepokan ini memang sudah terkenal sejak puluhan tahun yang lalu, karena sering menelurkan pendekar-pendekar digdaya pembela kebenaran dan ketidakadilan.
Bahkan para tokoh persilatan mengenal betul, siapa ketua padepokan itu. Dia tak lain dari Ki Burisrawa, seorang tokoh tua berkepandaian tinggi. Saat ini beberapa orang murid Padepokan Kijang Kencana sedang beristirahat sehabis bekerja di sawah yang terletak didepan pagar padepokan.
Padi yang ditanam di sawah tampak tumbuh subur. Pada saat mereka melepaskan lelah sambil makan dan minum, terlihat serombongan orang yang memikul tandu. Dua dari empat orang yang menggotong tandu, memakai cadar merah dan biru.
Sementara yang berada di depan, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, mirip raksasa. Di belakangnya, dua orang laki-laki bermata sipit dan berkulit putih bersih. Dengan seenaknya rombongan itu menginjak-injak tanaman sawah milik Padepokan Kijang Kencana. Melihat kejadian yang tak mengenakan ini, para murid menjadi gusar.
“Hei...! Berhenti dulu...! Itu bukan jalanan umum! Apa kalian sengaja mencari gara-gara...?!” tegur murid-murid Padepokan Kijang Kencana.
Mereka marah karena melihat tanaman padi menjadi rusak terinjak-injak para penggotong tandu. Rombongan ini berhenti. Namun, orang berbadan paling besar yang melebihi ukuran manusia bisa maju ke depan. Dihampirinya murid-murid Padepokan Kijang Kencana yang sudah bersiaga.
“Apa katamu?!” bentak laki-laki tinggi besar berwajah penuh bekas luka, begitu berdiri setengah tombak di hadapan murid-murid padepokan itu.
“Ini hasil jerih payah kami, Kisanak. Hormatilah pekerjaan kami,” sahut pemuda murid Padepokan Kijang Kencana yang berdiri paling depan bersama seorang murid lain.
“Hmm.... Di depan Kaladewa kalian jangan jual lagak. Hiih...!” Begitu habis kata-katanya, laki-laki bertubuh besar bernama Kaladewa ini menyambarkan tangannya, seperti menepuk lalat. Begitu cepat gerakannya, sehingga....
Prokkk!
“Aaa...!” Dengan teriakan menyayat, kedua murid itu binasa dengan kepala pecah. Mereka ambruk tak berkutik, dengan darah menggenangi tanah. Melihat kekejaman para pendatang ini, beberapa murid langsung menerjang dengan cangkul dan arit.
“Ghrrr...!”
Kaladewa menggerung marah. Dengan menggunakan tangan dan kaki, laki-laki ini meladeni serangan murid-murid Kijang Kencana. Agaknya tenaga Kaladewa sangat luar biasa dan kuat. Dengan sekali tangkis, cangkul, dan arit berterbangan dari genggaman pemiliknya. Melihat kekuatan tenaga lawan, murid-murid Kijang Kencana mundur dengan muka pucat.
Tetapi tindakan mereka terlambat sudah. Karena Kaladewa telah menghampiri dengan langkah lebar.
“Huh...! Rupanya masih ada tikus sawah yang berani melawanku. Sudah bosan hidup rupanya...!” dengus Kaladewa sambil menghantamkan tinjunya.
“Hait!”
Krak...!
“Aaakh...!” Dua orang murid berusaha menangkis. Tetapi begitu terjadi benturan, terdengar suara tulang berderak patah disertai jeritan kesakitan. Kedua murid ini melompat mundur sambil menyeringai menahan sakit. Tangan mereka terkulai, karena tulang-tulang patah.
“Chiaaat...!”
Salah seorang murid yang bertubuh gempal mencoba menyerang dari belakang. Sementara yang seorang lagi menusuk perut dengan pisau pendek. Namun, Kaladewa, membiarkan saja, seolah hendak pamer kehebatan.
Dug!
Murid yang menyerang dengan tinju tersentak kaget, ketika tangannya patah begitu menghantam punggung. Sementara Kaladewa cepat mengayunkan tangan ke belakang.
Prak!
Kepala murid bertubuh gempal itu langsung pecah terhantam tangan Kaladewa. Pada saat yang sama pisau murid Padepokan Kijang Kencana mengenai perut. Namun begitu menyentuh bagaikan menusuk karet yang keras dan kenyal. Akibatnya, tangan murid ini tertolak balik. Melihat serangannya tidak mempan, pemuda yang memegang pisau ini mendelik dengan perasaan tak mengerti. Namun keterkejutannya harus dibayar mahal, karena tangan Kaladewa telah mengibas cepat. Dan....
Prak!
“Aaakh...!” Pemuda naas ini langsung ambruk dengan kepala retak. Sebentar tubuhnya meregang nyawa, lalu diam tak berkutik lagi.
Merasa tidak unggul menghadapi Kaladewa, murid-murid Padepokan Kijang Kencana ini segera berlari memasuki padepokan. Mereka segera memberi laporan pada Ki Burisrawa.
“Huh...! Kutu busuk-kutu busuk yang mencari mati!” dengus Kaladewa. Kemudian laki-laki bertubuh besar ini memberi aba-aba, untuk memasuki padepokan.
DUA
“Keparat...! Kalian benar-benar iblis jahanam...! Kalau ada urusan, langsung saja dengan aku. Mengapa harus membunuh orang yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa...?!” bentak Ki Burisrawa, begitu berhadapan dengan Kaladewa.
Mendengar bentakan ini, Kaladewa menggeram keras. Otot di tubuhnya bertonjolan. Tampak jelas kalau dia memiliki tenaga yang besar. Dengan mengandalkan kelebihannya, Kaladewa menyerang Ketua Padepokan Kijang Kencana yang berusia sekitar tujuh puluh tahun itu. Namun, Ki Burisrawa yang berjubah coklat ini tidak tinggal diam, tangannya cepat bergerak memapak.
Plak!
“Aaakh...!” Terdengar suara benturan keras. Tangan Kaladewa kontan bergetar. Malah, kuda-kudanya juga tergeser. Mau tak mau, dia terpaksa mundur dua tindak sambil menggosok-gosok tangannya yang terasa sakit. Ki Burisrawa sendiri merasa heran.
Biasanya, jarang ada yang sanggup menandingi tenaga dalamnya. Tapi bila melihat tokoh persilatan yang menjadi lawannya, hal ini masih dapat dimengerti. Karena selain memiliki tenaga besar, tenaga dalam Kaladewa bisa jadi sudah sangat tinggi.
“Haaat...!” Ketua Padepokan Kijang Kencana kali ini menghentakkan tangan kanannya, melancarkan serangan jarak jauh sampai menimbulkan angin keras.
Sementara Kaladewa agaknya kembali ingin memamerkan kekebalan tubuhnya. Dadanya langsung dikembangkan sambil menyalurkan tenaga dalam untuk menahan pukulan itu. Dan....
Dugk!
“Hoagk...!” Sambil berteriak tertahan, tubuh Kaladewa yang seperti raksasa jatuh telentang disertai lelehan darah dari sudut bibir. Ki Burisrawa yang sedang murka karena beberapa muridnya terbantai, bermaksud menghabisi sekaligus. Tetapi....
Wusss...!
Mendadak meluncur angin keras yang berbau harum, Ki Burisrawa membatalkan serangannya. Dia cepat melompat mundur dengan wajah sedikit pucat. Matanya langsung terarah pada tandu, asal angin pukulan tadi. Ketua Padepokan Kijang Kencana ini tahu betul, pukulan berbau harum yang tadi dihindarinya adalah milik datuk sesat yang telah lama menghilang. Pukulan ini tak lain milik Sampuraga yang sepuluh tahun lalu telah membuat petaka.
“Hm.... Apakah dia masih hidup? Dan kini, kedatangannya hendak membalas dendam, karena aku telah ikut mengusirnya sepuluh tahun yang lalu...,” pikir Ki Burisrawa dalam hati.
Tapi, laki-laki tua berjubah coklat ini tidak dapat berpikir terlalu jauh. Karena, dari dalam tandu telah muncul seorang laki-laki setengah baya bertubuh tegap terbungkus pakaian bagai pendeta. Kepalanya gundul, wajahnya ramah penuh senyum, berminyak dan bersinar kekuningan. Tangannya memegang tasbih besar dari emas murni. Semua itu pas dengan pakaian pendetanya yang warna kuning keemasan.
“Selamat jumpa lagi, Burisrawa.... Apa kabarmu selama ini? Apakah baik-baik saja...?” sapa laki-laki setengah baya berpakaian pendeta dengan senyuman yang tak pernah lepas dari bibir.
“Huh...! Kiranya benar kau yang muncul, Sampuraga. Kukira kau sudah mati. Ternyata kemunculanmu kali ini bukan membawa berkah, malah menimbulkan petaka di mana-mana. Apa pula maksudmu dengan berpakaian seperti pendeta...?!” tanya Ki Burisrawa, bernada dingin.
“Hei...! Sopanlah kalau bicara dengan Sang Pendeta, Kalau tidak ingin mati dengan tubuh hancur tidak berbentuk lagi...!” bentak Kaladewa sambil menyusut darah yang masih menetes dari sudut bibir.
“Sang Pendeta...? Kau telah melampaui batas, Sampuraga...! Sebaiknya sadarlah sebelum yang lain datang memusuhi seperti waktu yang lalu...,” ujar Ki Burisrawa sedikit memberi nasihat.
“Terima kasih, Sahabat! Rupanya kau masih baik hati padaku...! Inilah sebagai rasa terima kasihku, Hup...!” Begitu selesai dengan kata-katanya, laki-laki berpakaian pendeta yang ternyata Sampuraga mengibaskan tangan kanannya perlahan saja.
Zeb!
Pukulan berbau harum langsung berdesir lembut ke arah Ki Burisrawa. Namun dengan mengerahkan tenaga sekuatnya, Ketua Padepokan Kijang Kencana itu menyambuti dengan menghentakkan tangannya.
Blarrr!
“Hugkh...!” Dua tenaga berkekuatan tinggi beradu. Tampak Ki Burisrawa tersentak mundur. Dadanya kontan terasa sakit dan napas sesak. Padahal, dia melihat Sang Pendeta hanya mengebutkan tangan secara perlahan, seolah tidak mengerahkan tenaga sama sekali.
“Hiaaa...!” Disertai teriakan keras, Ki Burisrawa menerjang sambil mencabut golok yang langsung disabetkan ke pinggang dan leher Sampuraga. Walaupun bertubuh agak gemuk, Ki Burisrawa memiliki gerakan gesit bagaikan kijang. Goloknya tampak berkelebat mencari lubang kelemahan lawan. Namun dengan gerakan biasa saja, Sampuraga berhasil menghalau serangan.
“He he he...! Kepandaianmu kini telah maju pesat, Burisrawa...! Coba tahan ilmuku ini. Heaaat..!” Kaki Sang Pendeta menjejak tanah tiga kali.
“Heh?!” Ki Burisrawa tersentak kaget begitu merasakan tanah yang diinjaknya terguncang keras bagaikan ada lindu. Tubuhnya terhuyung-huyung. Pada saat itu, tasbih emas milik Sampuraga berkelebat.
Cprattt!
“Aaakh...!” Tak ampun lagi, tulang pundak Ki Burisrawa remuk. Goloknya terlepas dari tangan. Sebagai seorang tokoh persilatan, laki-laki tua ini tidak mau menunjukkan rasa sakitnya. Dengan nekat tenaga dalamnya dikerahkan. Kembali diterjangnya Sampuraga dengan maksud mengajak adu jiwa.
Dug! Krek...!
Tetapi ketika serangan itu mengena, tangan Ki Burisrawa seperti memukul tembok besi yang kokoh. Tangan laki-laki tua ini kontan patah menjadi tiga bagian. Sakitnya terasa menusuk ulu hati.
“Hiaaa...!” Kali ini Ki Burisrawa sudah bertindak nekat. Sambil berteriak keras Ketua Padepokan Kijang Kencana melenting ke udara, lalu melakukan tendangan ke arah kepala.
“Balik...!” teriak Sang Pendeta sambil mendorong dengan telapak tangan terbuka.
Bet!
“Aaa...!” Bagaikan sehelai daun kering, tubuh Ki Burisrawa terpental kembali ke belakang. Ketika menyentuh tanah, tubuhnya berkelojotan sejenak lalu diam untuk selama-lamanya.
Setelah menatap dingin mayat Ki Burisrawa, Sampuraga berbalik dan melangkah masuk kembali ke dalam tandu. Sementara para murid utama Ki Burisrawa tak ada yang berani bertindak lagi. Di samping merasa ngeri, mereka juga yakin tak akan menang menghadapi orang-orang telengas ini. Tak lama laki-laki bercadar merah maju beberapa tindak. Matanya tajam mengawasi satu persatu murid-murid Padepokan Kijang Kencana.
“Hm...! Kalian tidak perlu takut. Lihatlah! Apa yang kalian harap dari seorang guru yang tidak memiliki kepandaian apa-apa...? Bila kalian mau menurut dan mengikuti kami, maka di samping mendapat ilmu olah kanuragan tinggi, juga akan mendapat kekayaan dan kesenangan.... Bagaimana? Pilih mati, atau ikut pada kami?”
Laki-laki berpakaian serba merah dan bercadar merah yang tadi mengusung tandu memberi penawaran pada murid-murid Padepokan Kijang Kencana yang masih terpaku. Para murid ini saling pandang dan berpikir sejenak. Tetapi dasar manusia, mereka kemudian mengangguk.
“Kami semua ikut pada ketua baru...!” seru mereka, serempak.
“Hidup Sang Pendeta...! Hidup Maha Guru Sampuraga...!”
“Hidup Maha Guru, Sampuragaaa...!” mereka berteriak-teriak sekuat tenaga. Suara mereka menggema keempat penjuru lereng Gunung Saka.
********************
Sejak Sampuraga dan para pengikutnya menguasai Padepokan Kijang Kencana berikut sisa murid-murid Ki Burisrawa, keadaan di sekitar Gunung Saka berubah kacau balau. Perkosaan dan perampokan merajalela. Tidak hanya dilakukan oleh anak buah Sampuraga, tapi juga oleh bekas murid-murid Ki Burisrawa yang membelot. Dan sejak itu pula, beberapa tokoh persilatan mulai melirik untuk menghambakan diri pada Sampuraga yang berjuluk Sang Pendeta.
Malah, konon sudah ada seorang tokoh hitam yang telah menjadi pengikut Sampuraga. Namanya, Dewi Kencana Wungu. Dia adalah seorang tokoh wanita berpakaian tipis tembus pandang. Menurut kabar, wanita cantik ini sangat telengas. Apalagi kalau sudah menggunakan senjata rahasianya yang bernama Duri Bunga Beracun. Sedangkan senjata yang menjadi ciri-ciri utamanya adalah senjata pedang bercabang dua.
Akibat semua itu, para penduduk desa di sekitar Gunung Saka, mulai pergi mengungsi ke desa lain yang jauh letaknya. Mereka takut jadi bulan-bulanan pengikut Sampuraga. Siapa yang berani melawan, tentu akan binasa dengan keadaan menyedihkan.
Waktu terus bergulir tanpa ada yang dapat menahan. Sementara jerit tangis penduduk yang jadi korban anak buah Sampuraga, seolah tidak berhenti. Sampai saat ini belum ada yang peduli. Terutama, dari tokoh persilatan golongan putih. Entah, mereka tidak mau peduli, atau pura-pura tidak tahu....
Kabar tentang Sepak terjang Sampuraga dan para pengikutnya jelas merebak ke mana-mana. Tak urung, sampai pula di Padepokan Wesi Kuning yang berada di pantai selatan tanah Jawa. Namun padepokan yang terkenal sebagai padepokan khusus wanita ini belum menanggapi secara sungguh-sungguh. Kendati demikian, bukannya mereka meninggalkan kewaspadaan.
Ketua padepokan ini yang di kalangan persilatan dikenal bernama Nyai Pohaci tak henti-hentinya mengingatkan anak-anak muridnya untuk selalu waspada, di samping memberi jurus-jurus baru untuk bekal menghadapi Sampuraga dan begundal-begundalnya. Senja baru saja menyapa, ketika murid-murid Padepokan Wesi Kuning yang seluruhnya wanita ini selesai berlatih.
Namun ketika mereka hendak istirahat melepas penat, dari luar pagar padepokan berlompatan tiga sosok tubuh dengan gerakan-gerakan indah. Setelah berputaran beberapa kali, mantap sekali mereka mendarat di tanah. Para murid padepokan tersentak. Mata mereka menyipit melihat seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, didampingi dua orang laki-laki bermata sipit dengan kulit putih bersih.
“Siapakah Kisanak bertiga...? Ada perlu apa datang ke padepokan kami...?” tanya salah satu gadis murid Padepokan Wesi Kuning.
“Aku Awyang Seng. Dan adikku bernama Awyang Hok. Sedangkan yang bertubuh seperti raksasa adalah Kaladewa.... Kami datang hendak menagih hutang lama...,” kata salah satu laki-laki bermata sipit yang mengaku bernama Awyang Seng.
“Hutang lama...? Kami tidak mengerti? Lagi pula, kami tidak merasa punya hutang pada siapa pun...!” jawab seorang murid wanita lainnya.
“Jelas kalian tidak mengerti.... Maka, suruh saja Nyai Pohaci keluar dan menemui kami. Katakan, teman lamanya Sampuraga ingin bertemu dengannya...,” potong adik Awyang Seng, yang bernama Awyang Hok.
Sebenarnya, mendengar nama Sampuraga disebut, para murid padepokan itu hampir tercekat. Namun sebagai orang persilatan mereka tak sudi menampakkan rasa takut. Bagi mereka, cerita Nyai Pohaci tentang Sampuraga hanya isapan jempol sebelum ada buktinya.
“Hei...! Sopanlah sedikit kalau bicara. Atau kuusir kalian dengan kasar?!” bentak murid lain, yang memegang cambuk.
“Sebenarnya aku merasa sayang kalau harus membunuh wanita-wanita cantik seperti kalian.... Tetapi kalau kalian membandel dan banyak tingkah, kami tidak akan berlaku sungkan lagi...,” tandas Awyang Hok.
“Ucapanmu semakin tidak sopan! Cepat tinggalkan tempat ini! Kami tidak ada waktu main-main dengan kalian...!” hardik wanita itu.
“He he he...! Sombongnya kalian ini. Hmm.... Sebaiknya rasakan dulu sentuhanku ini...!” seru Awyang Seng sambil mengulurkan tangannya ke arah dada wanita itu.
Mendapat serangan yang bersifat kurang ajar dan memandang rendah, wanita itu jadi murka. “Serang...!” teriak wanita ini seketika.
Tanpa pikir panjang lagi para wanita ini segera menerjang Awyang Seng dan Awyang Hok. Senjata khas mereka yang berupa cambuk langsung menyentak-nyentak mencari sasaran. Suaranya seperti hendak membelah angkasa.
Ctar...!
Sebuah cambuk mendadak menjilat ke arah tangan Awyang Seng. Namun dengan cepat, laki-laki dari Tiongkok itu menarik tangannya. Tubuhnya cepat berbalik, langsung mencolek pipi.
“Kurang ajar.... Rupanya kalian ini bajingan yang tidak perlu dikasihani. Mampuslah kalian semua...!”
Pertarungan sengit segera terjadi. Suara lecutan cambuk terdengar berkali-kali. Para wanita itu mengeroyok tiga anak buah Sampuraga karena yakin kalau mereka hanyalah pengacau yang hendak mengganggu padepokan.
“Hiyaaat!”
Tap!
Laki-laki bertubuh tinggi besar yang tak lain Kaladewa menangkap tali cambuk, lalu menariknya sekaligus. Dengan tenaganya yang kuat, salah satu wanita yang cambuknya tertangkap langsung terseret dan jatuh dalam pelukan Kaladewa.
“Auuuwww...!” Kontan wanita itu menjerit-jerit kalap. Namun sambil tertawa-tawa, Kaladewa meraba dan menggerayangi tubuhnya.
TIGA
Setelah puas mempermainkan, Kaladewa membunuh wanita murid Padepokan Wesi Kuning itu. Sementara Awyang Seng dan Awyang Hok lebih gila lagi. Mereka merobek-robek pakaian lawannya tanpa rasa kasihan. Jelas, para murid Padepokan Wesi Kuning bukan tandingan walaupun wanita-wanita itu menggunakan cambuk, tapi menghadapi ketiga tokoh sesat yang berilmu tinggi ini, tak ada artinya sama sekali.
Keadaan Padepokan Wesi Kuning jadi kacau. Para murid wanita yang bajunya disobek-sobek berlarian masuk ke dalam bangunan padepokan. Dalam keadaan yang kacau balau itu, dari dalam bangunan padepokan berkelebat satu bayangan kuning tua ke arah Kaladewa.
Ctarrr...!
Tanpa banyak kata lagi, dengan kemarahan luar biasa bayangan kuning itu langsung mengebutkan senjatanya yang berupa cambuk di tangannya.
“Hiih...!” Kaladewa yang tengah memeluki seorang murid Padepokan Wesi Kuning tidak mau dirinya terhajar cambuk. Dengan cepat didorongnya wanita dalam pelukannya ke depan. Dan bayangan kuning itu juga tidak mau wanita itu terhajar. Maka cepat sekali ditariknya serangan maut tadi. Tetapi tanpa terduga, Kaladewa menarik kembali dan membenturkan kepala wanita itu pada kepalanya sendiri.
Prok!
Tanpa dapat bersuara lagi, wanita itu ambruk binasa dengan kepala pecah. Pada saat yang sama, cambuk sosok ramping berpakaian kuning tua telah menggeliat ke arah punggung Kaladewa.
Jtarrr!
“Aaagkh...!” Punggung Kaladewa robek tersengat cambuk, membuatnya mengeluh tertahan.
Laki-laki tinggi besar ini heran. Ternyata, ilmu kebalnya tidak berarti bagi sosok berpakaian kuning tua yang ternyata adalah seorang perempuan tua. Baru disadari kalau kepandaian wanita ini tinggi, sehingga dapat menembus ilmu kebal yang dibanggakan. Maka tak bisa dipungkiri kalau wanita tua itu tak lain dari Nyai Pohaci.
Dengan meringis menahan sakit Kaladewa meloncat mundur. Tangannya cepat mengambil sebongkah batu, lalu dilemparkan pada Nyai Pohaci. Awyang Seng dan Awyang Hok melihat Kaladewa tidak mungkin dapat mengalahkan Nyai Pohaci. Maka dengan cepat mereka melompat menghadang sambil menghunus senjata masing-masing.
“Siapakah kalian...?! Kudengar kalian mengaku ada hubungan dengan orang yang bernama Sampuraga. Apa benar begitu...?” tanya Nyai Pohaci sambil memutar-mutar cambuknya.
“Benar...! Kami datang kemari diutus Sampuraga untuk menagih hutang lama...,” tukas Awyang Seng.
“Kau jangan mengada-ada! Sampuraga telah binasa sepuluh tahun yang lalu...! Katakan saja terus terang, apa maksud kalian...?” tukas Nyai Pohaci dengan suara keras. Baru saja suara Nyai Pohaci hilang....
“Ha ha ha...!”
Mendadak dari atas genteng terdengar suara tawa menggetarkan disusul berkelebatnya sesosok bayangan. Beberapa kali bayangan itu berputar, lalu mendarat dua tombak di hadapan Nyai Pohaci. Perempuan tua ini bisa melihat laki-laki setengah baya berpakaian pendeta membawa tasbih besar terbuat dari emas. Sambil melangkah lebar, dihampirinya Nyai Pohaci.
“He he he...! Pohaci! Masih ingatkah kau padaku...? Apa kabarmu selama ini...? Semoga kau baik-baik saja...,” sapa laki-laki berpakaian pendeta yang tak lain Sampuraga.
“Eh...?! Kiranya kau masih hidup, Sampuraga.... Kukira kau sudah mati dimakan cacing tanah.... Hm.... Kemunculanmu telah menebar kematian di sini. Rupanya iblis telah menjelma dalam dirimu!” gumam Nyai Pohaci dingin sambil memandang tajam pada Sampuraga.
“Sang Pendeta! Izinkanlah kami membereskan nenek tua yang bawel dan tidak tahu diri ini...!” seru Awyang Seng sambil memutar-mutar pedang berbentuk bulan sabitnya.
“Ssst...!”
“Ada apa, Sang Pendeta...?” tanya Awyang Seng.
“Sopanlah terhadap orang yang lebih tua. Jangan menghina dan kurang ajar seperti itu...,” sergah Sang Pendeta, bernada menasihati.
“Kau tidak perlu berpura-pura baik, Sampuraga...! Apa pula maksudmu dengan panggilan Sang Pendeta itu...?!” tukas Nyai Pohaci.
“Aku belajar di daratan Cina, karena telah mencapai ilmu tertinggi dan memiliki kepandaian melebihi para pendeta lain. Maka, mereka memanggilku Sang Pendeta...,” papar Sampuraga.
“Sombong...! Manusia macam dirimu tidak pantas memakai gelar itu. Pantasnya Pendeta Murtad...!” desis Nyai Pohaci.
“Bagus! Kau telah membuatku berbuat seperti julukan yang kau berikan padaku...!” jawab Sampuraga tenang sambil mengibaskan tangannya pelan saja.
“Haaap...!”
Zeb! Zeb!
Merasakan ada angin serangan menyambar, Nyai Pohaci juga menghentakkan tangannya berusaha memapak. “Yeaaat...!”
Blarrr!
Dua tenaga dalam kuat bertemu. Nyatanya, Nyai Pohaci tergetar mundur beberapa langkah.
“Gila! Tenaganya semakin kuat. Kesaktiannya maju pesat sekali...!” desis Nyai Pohaci. Mengetahui lawannya sangat tangguh. Nyai Pohaci mendahului dengan serangan cambuknya yang berwarna kuning.
“Uts...!” Sang Pendeta alias Sampuraga menggeser kakinya ke samping. Lalu dengan gerakan aneh, tubuhnya meliuk ke arah perempuan tua itu. Dua jari telunjuk dan tengahnya, tiba-tiba bergerak menotok ke arah pergelangan tangan. Nyai Pohaci pun tidak mau menjadi sasaran. Seketika tubuhnya berjumpalitan, sehingga berhasil menghindari serangan.
“Bagus! Ternyata kepandaianmu tidak lenyap dimakan usia tua. Terimalah serangan yang berikut ini...!” puji Sang Pendeta. Dengan langkah-langkah aneh, si Pendeta Murtad memutar tasbih emasnya sampai mengeluarkan suara mengaung. Begitu tubuhnya meluruk, tasbihnya cepat dikebutkan ke kepala Nyai Pohaci.
“Hiih!” Cepat wanita tua itu menangkis dengan lecutan cambuknya.
“Shaat!”
Jdarrr!
Kembali senjata mereka beradu. Untuk kesekian kalinya Nyai Pohaci mundur dengan telapak tangan terasa sakit. Memang sejak dulu, kepandaian wanita itu di bawah Sampuraga. Sehingga lambat laun, keadaannya terdesak. Apa pun usahanya untuk mengatasi si Pendeta Murtad, tetap saja tidak berhasil. Semua geraknya seolah tertutup.
Keadaan yang paling mengenaskan adalah para murid Padepokan Wesi Kuning. Mereka dipermainkan secara tak senonoh oleh para pengikut Sampuraga yang rata-rata bekas kaum sesat. Tidak memakan waktu lama, wanita-wanita bertekad mengadu jiwa. Mereka tidak tahan menanggung malu. Lebih baik mati mengadu jiwa daripada hidup menanggung malu. Sementara, Nyai Pohaci sendiri tinggal menunggu waktu saja.
“Yaaat...!”
Sambil berteriak keras, wanita tua itu menerjang dengan jurus andalannya yang dahsyat. Cambuknya menggeliat-geliat, mengincar daerah kematian di tubuh Sampuraga. Ke mana pun laki-laki itu menghindar, ujung cambuk selalu mengikutinya. Namun dengan jurus-jurus anehnya, kembali Sampuraga berhasil mengelakkan semua serangan.
“Ha ha ha...! Cukup sudah kita bermain-main, Pohaci! Sekarang terimalah kematianmu...!” dengus Sang Pendeta.
Begitu habis kata-katanya, Sampuraga melancarkan serangan jarak jauh. Namun sampai sejauh itu, Nyai Pohaci berhasil mengelakkan serangan dengan menggulingkan dirinya ke tanah.
“Hmm.... Boleh juga jurus menghindarmu. Tapi sekarang, kau akan kujadikan kelinci percobaan dari ilmu baruku... Huaeeet...!”
Sang Pendeta berteriak dengan suara nyaring. Mendadak, tubuh Sampuraga mengembang perlahan-lahan. Makin lama, makin tinggi. Badannya membesar. Demikian pula kaki dan tangannya. Wajahnya pun berubah mengerikan, matanya melotot hampir keluar. Pada mulanya tumbuh dua taring pada masing-masing sudut bibirnya. Begitu melangkah menghampiri Nyai Pohaci saat itu juga, bumi seakan berguncang. Sulit sekali untuk berdiri tetap. Sampuraga, kini telah berubah menjadi sosok raksasa yang mengerikan!
“Gila! Ilmu sihir apa yang dipakainya?!” desis Nyai Pohaci seraya melangkah mundur.
Sambil menggeram, tangan raksasa ini terulur dengan maksud mencengkeram kepala wanita tua ini. Tetapi, cepat bagai kilat Nyai Pohaci mengayunkan cambuknya.
Tap!
Enak sekali raksasa ini menangkap lidah cambuk. Dan dengan sekali tarik, cambuk itu telah terlepas dari tangan Nyai Pohaci. Bahkan tubuh wanita itu ikut tertarik sampai tersuruk ke tanah. Raksasa ini bergerak mendekati. Dan hanya sekali injak....
Jrottt..!
“Aaa...!” Saat itu juga nyawa Nyai Pohaci putus dari raga. Teriakannya menggema setinggi langit. Tubuhnya hancur bagai terinjak-injak ratusan gajah. Darah langsung menggenangi sekitar tubuhnya. Dengan binasanya Nyai Pohaci, habislah riwayat Padepokan Wesi Kuning.
********************
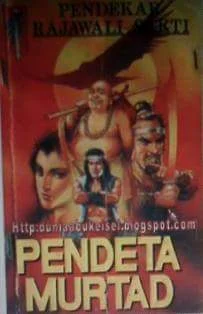
Satu sosok bayangan berkelebat menembus kegelapan pagi buta. Sosok yang bagaikan bayangan setan yang sedang mencari mangsa. Kemudian, bayangan itu mendekati jendela sebuah rumah dan langsung masuk ke dalamnya.
“Kukira kau tidak datang, Mundinglaya....” Terdengar suara begitu sosok itu menutup jendela kembali. Dia melihat seorang laki-laki setengah baya tengah duduk di bangku kamar rumah ini sambil menenggak tuak.
“Maaf, Balad Kabrang. Aku tadi siang mengikuti seorang pemuda. Setelah kuselidiki, namanya Mudrika. Dia mempunyai tujuan dan maksud yang sama seperti kita. Itulah sebabnya aku datang terlambat...,” sahut sosok yang ternyata laki-laki setengah baya bernama Mundinglaya.
“Mudrika...? Siapakah dia? Awas, kita jangan sampai terpancing dan masuk perangkap iblis yang mengaku bernama Sampuraga itu...,” ingat laki-laki setengah baya bernama Balad Kabrang.
“Kau tidak perlu khawatir, Balad Kabrang.... Aku bukan anak kemarin sore. Dia telah kuikuti sejak beberapa hari yang lalu...,” jawab Mundinglaya.
“Syukurlah.... Semakin banyak yang memusuhi iblis itu, akan semakin baik bagi kita. Tapi, apakah kau tahu asal usul pemuda itu...?” tanya Balad Kabrang, kembali meneguk tuaknya.
“Tentu saja aku tahu. Mudrika adalah anak Ki Giras Lawa, Ketua Padepokan Walang Wesi. Dia sangat dendam, karena ayahnya binasa di tangan anak buah Sampuraga beberapa waktu lalu,” papar Mundinglaya sambil mengambil tuak, dan minum sedikit untuk menghangatkan tubuh.
“Baguslah kalau begitu...,” desah Balad Kabrang sambil menganggukkan kepalanya. Dan baru saja mereka hendak mengatur siasat untuk menyerang Sampuraga di Gunung Saka....
“Chiaaa...!”
“Heh?!” Kedua orang ini tersentak, ketika terdengar teriakan keras yang menyiratkan terjadinya sebuah pertarungan. Tanpa banyak kata lagi, keduanya menerobos jendela, keluar dari rumah ini.
Balad Kabrang dan Mundinglaya tiba di tempat asal suara pertarungan. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian ketat warna merah tengah bertarung melawan seorang laki-laki tinggi besar yang dibantu dua orang laki-laki bertampang seram.
“Lihat, Balad Kabrang! Pemuda berbaju merah itulah yang bernama Mudrika...!” tunjuk Mundinglaya.
“Dan dia tengah dikeroyok oleh begundal-begundalnya Sampuraga. Kalau yang bertubuh seperti raksasa, namanya Kaladewa. Entah yang dua lagi...,” sahut Balad Kabrang.
“Berarti si Mudrika benar-benar ingin membalaskan kematian orang-tuanya....”
“Lalu, bagaimana kita, Balad Kabrang....”
“Kita lihat dulu saja...!” Pemuda berbaju merah yang memang Mudrika. Dia tahu, laki-laki bertubuh besar itu pasti memiliki tenaga kuat. Maka dia tidak mengadu tenaga, melainkan bergerak mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya saja. Sesekali dikirimkannya tusukan atau tebasan pedangnya.
“Ciaaat!” Bleng...!”
Sebuah babatan mendarat tepat di dada Kaladewa. Tapi ternyata tak menimbulkan bekas sama sekali!
“Hah...?! Setan ini memiliki ilmu kebal...,” sentak Mudrika dalam hati. Tetapi pemuda tampan ini segera merubah serangannya. Kini sasarannya adalah bagian yang lemah, dan tak mungkin dilatih menjadi kebal. Pedangnya dengan gerakan kilat menyerang mata, tenggorokan, ulu hati dan daerah bawah perut Kaladewa.
“Sialan! Bocah gila! Mengapa seranganmu tidak karuan seperti ini...?!” teriak Kaladewa sambil berloncatan menghindari serangan gencar yang membahayakan.
Melihat Kaladewa terdesak, dua laki-laki bertampang seram segera maju membantu. Tapi, baru saja mencabut senjata, Mundinglaya dan Balad Kabrang telah melompat ke dalam kancah pertarungan.
“Hei! Jangan main curang. Biarkan saja mereka bertarung. Kalau tangan kalian gatal biar kami temani, agar jadi seimbang...,” seru Mundinglaya. Segera kedua laki-laki setengah baya itu menggebrak dua teman Kaladewa.
Perkelahian satu lawan satu berlangsung seru. Kedua belah pihak sama-sama secepatnya ingin menghabisi. Tanpa disadari oleh orang bertarung, tidak jauh dari mereka tampak dua orang laki-laki tua sedang bermain catur diterangi sebuah lampu dari jarak. Mereka seakan tidak mau peduli pada orang-orang yang sedang bertarung mati-matian. Yang berbaju dan berambut putih, sebentar-bentar menggaruk kepalanya.
“Keparat kau, Demong! Kalau jalan jangan yang sulit-sulit seperti ini...!” maki laki-laki tua satunya dengan pandangan tak bergeser dari biji catur.
“He he he...! Sudah kukatakan, hari ini kau akan kalah bila melawanku Sabda Gendeng...! Bagaimana? Menyerah...?!” tukas laki-laki tua yang ternyata Ki Demong dengan wajah berseri. Guci tuaknya selalu menempel di bibirnya.
“Siapa yang mau menyerah? Tidak ada sejarahnya aku kalah darimu pemabuk butut...!” bentak laki-laki satunya yang tak lain Ki Sabda Gendeng.
Kedua kakek ini memang selalu ribut dan tarik urat bila main catur. Tingkahnya seperti anak-anak saja. Pada saat yang sama, Balad Kabrang berhasil menghantam lawannya dengan sebuah pukulan keras. Hantaman itu disusul dengan tendangan ke arah dada.
Bugk!
Tubuh orang itu terpental, dan jatuh tepat ke arah Ki Demong. Dengan cepat laki-laki tua yang berjuluk Pemabuk Dari Gunung Kidul mengeluarkan tangannya.
“Hush...! Pergi sana! Mengganggu orang main saja kau...,” seru Ki Demong sambil mengibaskan telapak tangan terbuka.
Wuuuttt!
Tubuh itu kontan melayang ke tengah, tepatnya ke arah Ki Sabda Gendeng. Tetapi....
“Eh, malah kemari.... Pergi sana...!” teriak Ki Sabda Gendeng sambil menampar dengan tangan terbuka.
Wuuutt!
Kontan tubuh itu melayang kembali ke arah Balad Kabrang. Langsung saja laki-laki setengah baya ini menyambutnya dengan tusukan pedang.
Crap!
Orang itu kontan jatuh binasa tanpa mengeluarkan teriakan sedikit pun. Rupanya ketika ditepuk-tepuk Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng, nyawanya memang telah melayang. Begitu juga dengan Mundinglaya. Ketika lawannya membabat leher, dia menunduk sambil mengirimkan tendangan ke perut. Tapi orang itu juga tidak tinggal diam. Segera lututnya dinaikkan untuk melindungi perut. Dan memang itu yang dikehendaki Mundinglaya. Tiba-tiba kakinya bergerak ke atas. Dan....
Desss...!
“Aaakh...!” Tubuh teman Kaladewa kontan terdorong ke arah Ki Sabda Gendeng begitu dadanya terhantam tendangan Mundinglaya. Dan tanpa menoleh, kakek itu melemparkan biji catur.
Seeet! Taks! Brug!
Orang itu jatuh dengan kening berlubang. Di keningnya telah tertancap biji catur berbentuk kuda. Setelah bergelimpangan sejenak, dia menghembuskan napas terakhir.
“Kampret! Mengganggu yang sedang main saja, tahu rasa kalian!” gerutu Ki Sabda Gendeng.
Kini Kaladewa kena batunya. Dia dikeroyok tiga orang. Walaupun kebal dan memiliki tenaga dalam kuat, menghadapi Mudrika yang dibantu Mundinglaya dan Balad Kabrang dia jadi mati kutu! Sebelas jurus kemudian, Baladewa telah pontang panting. Nafasnya telah memburu keras. Walau kebal, tetapi merasa sakit dipukuli terus-menerus. Bahkan tiba-tiba, Mudrika menusukkan pedangnya ke arah mata....
Cras! Cras!
“Wuaaa...!” Kontan Kaladewa memekik keras. Dia merasakan sakit luar biasa pada dua kelopak matanya. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan Ki Sabda Gendeng dan Ki Demong. Cepat mereka melemparkan biji-biji catur.
Set! Set! Crap! Crap!
“Aaa...!” Seketika biji-biji catur itu menghantam daerah terlarang milik Kaladewa. Kontan mulutnya meringis sambil memegangi kebanggaannya yang pecah terhantam biji catur. Tubuh raksasa itu ambruk dengan jiwa melayang. Ketika Mudrika, Balad Kabrang, dan Mundinglaya menoleh, dua pemain catur itu sudah tak ada di tempatnya lagi.
********************
EMPAT
Betapa murkanya Sampuraga mendengar kematian Kaladewa di tangan Ki Sabda Gendeng dan Ki Demong. Bahkan laki-laki yang mengaku sebagai Sang Pendeta ini telah mengirim beberapa pengikutnya untuk mencari Ki Sabda Gendeng dan Ki Demong. Orang kepercayaan Sampuraga yang diutus mencari kedua tokoh putih berkepandaian tinggi adalah Awyang Seng dan Awyang Hok.
Tapi, mencari Ki Sabda Gendeng dan Ki Demong sama saja mencari jarum di tengah lautan. Walau begitu, mereka tidak berputus asa. Sementara lima orang yang menemani telah merasa kelelahan. Apalagi, malam sebentar lagi telah jatuh. Berjalan sejak pagi memang membuat badan terasa penat.
“Tuan Awyang Seng.... Bagaimana kalau kita beristirahat dulu...?” usul salah satu dari lima orang yang menemani, begitu tiba di pinggiran sebuah desa.
“Baiklah.... Aku pun sudah merasa lelah...,” sahut Awyang Seng.
“Apakah boleh kami berbuat seperti biasa, Ketua..?!” tanya yang lain sambil tersenyum penuh arti.
“Tentu saja boleh. Siapa yang melarang...? Tapi setelah itu, kalian harus bekerja lebih giat lagi...,” ujar Awyang Hok.
“Jangan lupa, bawa makanan serta wanita muda kemari.... Tetapi, ingat! Cukup dua saja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kalian tidak boleh sembrono. Jangan sampai membuat ketua marah...,” ingat Awyang Seng kalem.
Sambil tersenyum penuh suka cita, mereka kembali bergerak menuju tengah desa. Kebetulan, di situ terdapat rumah kecil yang sudah tidak terpakai lagi. Walau begitu masih terdapat balai-balai tempat beristirahat orang yang sedang melakukan perjalanan jauh.
“Kalian pergilah. Biar aku dan Awyang Hok menunggu di gubuk ini,” ujar Awyang Seng seraya duduk di balai-balai bambu.
Demikian pula Awyang Hok. Begitu mendapat isyarat, kelima orang ini segera bergerak memasuki desa lebih dalam lagi. Namun tanpa disadari, tiga pasang mata tampak bergerak mengikuti.
“Setan! Ke mana mereka semua. Edan! Sampai sekian lama mereka belum kembali...?!” rutuk Awyang Hok, setelah sekian lama menunggu kelima bawahannya belum juga kembali.
“Kurasa mereka bersenang-senang dulu. Huh! Rupanya mereka ingin merasakan bagaimana enaknya dihukum...!” seru Awyang Seng, kesal.
“Biar kususul saja ke sana...,” kata Awyang Hok.
“Tidak perlu! Sebaiknya kita tunggu saja di sini...!” cegah Awyang Seng menyabarkan adiknya.
Kini keduanya merebahkan diri sambil memejamkan mata. Mungkin karena kelelahan, keduanya segera tertidur lelap. Kalau tadi mereka duduk-duduk di balai-balai bambu di depan rumah ini, kini berbaring di ranjang papan di dalam kamar. Namun baru beberapa kejap terbuai dalam tidur, tiba-tiba telinga mereka menangkap suara ribut-ribut di luar rumah ini. Cepat mereka beringsut dan loncat keluar rumah.
Wut! Wut!
Pada saat itu, melayang lima buah karung berisi benda besar ke arah mereka. Kedua kakak beradik itu langsung menyambuti dengan pukulan keras.
“Haiiit!”
Bug! Begkh!
Kelima karung terpental balik. Tetapi begitu menyentuh tanah, pengikatnya terbuka. Maka dari dalamnya keluar lima sosok tubuh tidak bergerak lagi. Ketika kedua laki-laki dari Tiongkok ini menegasi, ternyata kelima orang itu adalah anak buah mereka sendiri yang tadi hendak mencari hiburan di dalam desa.
“Bedebah! Siapa yang berani macam-macam dengan pengikut Sampuraga?!” bentak Awyang Seng seraya memandang ke sekeliling. Dia jadi heran, karena suara berisik tadi mendadak lenyap. Bahkan suasana di depan rumah ini terlihat gelap dan sunyi. Namun....
Wesss...!
“Heh...?!” Betapa terkejutnya kedua laki-laki dari daratan Tiongkok ini ketika dari samping melesat angin serangan yang begitu cepat. Namun sebagai tokoh berkepandaian lumayan, mereka berusaha menghindari dengan melompat ke depan. Ketika mendarat, mata mereka langsung tertuju ke arah serangan tadi berasal.
Ternyata yang menyerang adalah dua laki-laki setengah baya. Merasa tidak mengenal, kedua kakak beradik dari daratan Cina ini memandang penuh keheranan.
“Hei?! Siapa kalian, Orang Tua?! Mengapa membokong kami secara licik?! Apa tidak malu...?” tegur Awyang Seng geram, seraya bersiaga.
“Ha ha ha...! Aku Mundinglaya. Dan temanku, Balad Kabrang. Terhadap para iblis pengikut Sampuraga, kami tidak perlu main sopan.... Kalian orang asing, mengapa ikut campur dalam urusan ini...? Bukankah kalian sendiri yang tidak tahu malu...?!” tukas sosok penyerang yang ternyata Mundinglaya.
“Perbuatan kami ini tidak seberapa bila dibandingkan tindakan Sampuraga terhadap tokoh rimba persilatan. Dan siapa pun pasti akan berusaha membunuhnya.... Dari dulu, dia selalu membuat kacau dan menimbulkan petaka dalam dunia persilatan. Hmm.... Kalian yang berpihak padanya, pasti setali tiga uang.... Maka bersiaplah untuk mampus...!” sambung laki-laki setengah baya satunya yang tak lain Balad Kabrang.
“Bajingan Sampuraga telah berhutang jiwa padaku...! Kalian sebagai anak buahnya terpaksa kusingkirkan dulu...!” Mendadak terdengar suara lain, yang disusul munculnya seorang pemuda berbaju merah dari belakang Mundinglaya dan Balad Kabrang.
“Hmm.... Siapa pula kau ini...?!” tanya Awyang Seng.
“Namaku Mudrika. Aku anak Ki Giras Lawa, Ketua Padepokan Walang Wesi. Belum lama ayahku telah dibantai anak buah Sampuraga. Dan kalian sebagai anak buahnya kalian harus turut bertanggung jawab...!” desis Mudrika.
Merasa telah terkurung dan tidak ada gunanya banyak bicara, kedua tokoh dari Cina itu segera mencabut senjatanya. Awyang Seng bersenjata pedang bulan sabit. Sedangkan adiknya sebilah pedang biasa.
“Heaaa...!” Sambil berteriak keras kakak adik itu masing-masing menerjang Mundinglaya dan Balad Kabrang.
“Sheaaat!” “Hait!”
Menghadapi jurus-jurus dari tanah Tiongkok, Mundinglaya dan Balad Kabrang masih tampak kebingungan. Sehingga untuk sementara, mereka hanya berusaha mengimbangi sambil mencari titik kelemahan dari jurus-jurus itu. Lagi pula kerja sama kedua tokoh asing itu sangat baik.
Awyang Seng yang bersenjata pedang berbentuk bulan sabit membabati Mundinglaya dengan gerakan tidak terduga. Sebentar ke atas dan ke bawah bagaikan naga yang sedang mengamuk. Langkah kakinya tidak sama dengan langkah ilmu silat yang terdapat di tanah Jawa ini. Kadang kala tubuhnya diam bagai patung, lalu bergerak menyambar-nyambar bagaikan patukan ular.
Sedang Awyang Hok yang berhadapan dengan Balad Kabrang selalu menjaga setiap serangan yang datang dengan kelincahan tubuhnya. Untuk mengacaukan pertahanan kedua tokoh dari Cina itu, Mudrika seketika meluruk maju sambil membabatkan pedangnya.
Semakin lama pertarungan jadi bertambah seru. Tampaknya mereka berimbang dan sulit mendapat kemenangan dalam waktu singkat. Walau begitu, Mudrika yang mempunyai dendam sedalam lautan terus mengacaukan pertahanan lawan tanpa memikirkan keselamatan dirinya lagi.
Pedang di tangannya menusuk dan menyabet cepat. Inilah jurus pedang andalan Padepokan Walang Wesi yang memiliki gerakan cepat dan gesit.
Trang! Tring!
“Yaiik...!”
Awyang Hok yang bertugas melindungi selalu bentrok dengan pedang Mudrika. Dalam hal tenaga dalam, laki-laki Cina itu berada di atasnya. Tetapi sayang, dua laki-laki setengah baya yang ikut mengeroyok memiliki kepandaian berimbang dengan kedua tokoh dari Cina itu. Maka bila ditambah Mudrika, Awyang Hok dan Awyang Seng makin terdesak saja.
“Heaaa...!” Disertai teriakan keras, Awyang Seng menyabetkan pedang bulan sabitnya pada leher Mundinglaya. Namun orang tua itu cepat berjongkok sambil meraup pasir bercampur debu yang ada di tanah. Dan ketika berdiri, tangan yang memegang debu dan pasir itu ditaburkan pada mata Awyang Seng.
Wuurrr...!
“Aaakh...!” Karena tidak menyangka, tokoh daratan Cina itu jadi kelabakan. Pasir dan debu yang masuk matanya telah membuatnya jadi kalang kabut. Dalam keadaan begitu, mendadak sebuah tendangan keras menghantam iganya.
Desss...!
“Aaakh...!” Awyang Seng hanya dapat berteriak tertahan, begitu iga tulangnya patah dan nyerinya bukan kepalang. Tubuhnya pun terhuyung ke sana kemari sambil menekap tulangnya yang patah.
“Ciaaat!” Balad Kabrang yang melihat kesempatan baik cepat meluruk sambil menebaskan goloknya. Dan....
Cras!
“Aaa...!” Golok di tangan Balad Kabrang berhasil menebas leher tokoh dari Cina itu. Kontan Awyang Seng terguling, dengan darah menggenangi. Sebentar dia meregang nyawa, lalu diam tak berkutik lagi.
“Awyang Seng...! Keparat! Kalian akan menunggu balasanku nanti!” Awyang Hok merutuk-rutuk setinggi langit. Dan tiba-tiba tubuhnya berbalik, lalu melesat kabur dari tempat ini.
Begitu cepat gerakannya, sehingga Mundinglaya, Balad Kabrang, dan Mudrika hanya sempat terperangah. Tentu saja, mereka tak ingin membiarkan begundal itu melarikan diri. Cepat mereka berkelebat mengejar.
********************
“Ada apa Awyang Hok...? Apa yang telah terjadi. Dan, mana kakakmu Awyang Seng...?” tanya Sampuraga, melihat kehadiran Awyang Hok di ruang utama tempat tinggalnya, bekas Padepokan Kijang Kencana di Gunung Saka.
Dengan tersendat-sendat dan napas memburu dibakar dendam, Awyang Hok menceritakan apa yang telah terjadi.
“Edan!” Si Pendeta Murtad Sampuraga terperangah dan membentak saking marahnya setelah Awyang Hok selesai bercerita. Wajahnya berubah merah membara terbakar amarah. Yang berada dalam ruangan ini tidak ada yang berani membuka suara. Suasana jadi berubah hening dan sepi. Tarikan napas para tokoh hitam yang berada dalam ruangan ini terdengar jelas.
“Keparat! Hancurkan saja siapa yang berani menentang kita! Hm.... Jadi anak si Giras Lawa hendak menuntut balas padaku? Kalau jumpa lagi, bunuh saja.... Kalian lihat saja! Akan kubuat banjir darah dalam rimba persilatan ini! Siapa saja yang menghalangi, singkirkan! Yang mendukung rencana kita, ajak bergabung!” ujar Sampuraga tegas dengan suara keras menggelegar.
“Bagaimana dengan rencana kita yang satu lagi...?” tanya Dewi Kencana Wungu, yang juga hadir di tempat ini.
“Oh.... Soal itu harus tetap kita utamakan...! Tetapi, harus hati-hati. Jangan sampai tercium orang luar sebelum terlaksana dan matang! Oleh karena itu, kita harus mencari pengikut sebanyak mungkin, untuk mendukung rencana pemberontakan ini.... Kalau aku telah menjadi raja, kalian semua akan kuberi pangkat dan hadiah...!” tandas Sampuraga.
Rupanya mereka tengah menyusun rencana untuk memberontak terhadap Kerajaan Lemah Abang, yang menguasai daerah ini.
“Dan kalau....” Si Pendeta Murtad tiba-tiba menghentikan kata-katanya. Matanya sedikit melirik ke langit-langit. Kegeraman semakin tersirat di wajahnya. “Ada apa...?” tanya Awyang Hok.
“Hiih...!” Tanpa menjawab, tangan Sampuraga mendorong ke atas.
Wuuttt...!
Selarik sinar merah berhawa panas kontan melesat ke atas dengan kecepatan kilat. Dan....
Bruak!
Wuwungan rumah hancur berikut gentengnya. Pada saat yang hampir bersamaan dari atas meluruk dua sosok tubuh. Lalu ringan sekali mereka berhasil mendarat di lantai. Keduanya saling pandang sebentar dengan senyum menjengkelkan.
“Hm...! Kukira siapa yang datang berkunjung. Tidak tahunya si Pemabuk Dari Gunung Kidul dan Ki Sabda Gendeng. Apa maksud kalian datang ke gubukku yang reot ini...?” sambut Sampuraga tersenyum ramah.
Rupanya, setelah mengetahui ciri-ciri dua sosok yang baru datang, Sampuraga langsung mengenali kalau yang ada di depannya adalah Pemabuk Dari Gunung Kidul dan Ki Sabda Gendeng.
“He he he...! Tidak perlu bersikap ramah. Semua pembicaraanmu telah kudengar.... Tidak sangka, kemunculan Sampuraga kali ini malah hendak memberontak pada Kerajaan Lemah Abang yang syah. Sungguh suatu perbuatan dan rencana gila...!” desah Ki Sabda Gendeng.
“Lalu kalian mau apa...? Tentu kalian mau bergabung dengan kami dan mencari kesenangan di hari tua, bukan...? Masa, kalian ingin mencari kematian dengan datang ke tempat ini...?!” tukas si Pendeta Murtad.
“Hua ha ha...! Kalian mengancamku secara halus. Sungguh lucu! Apa kau pikir aku ini anak kecil? Soal mati, bagi kami tidak masuk hitungan. Tapi yang penting, dapat memberi pelajaran pada kalian...!” desis Ki Demong, memandang tajam pada Sampuraga.
“Ketua! Biar kuberi mereka pelajaran agar tahu sopan sedikit kalau berbicara dengan Sang Pendeta...,” timpal Dewi Kencana Wungu tenang.
Namun begitu ucapan wanita berpakaian merangsang itu habis, kedua kakek urakan itu telah menyerang ke arah Sang Pendeta. Ki Demong menyemburkan tuak merahnya, sedangkan Ki Sabda Gendeng menyabetkan tongkat hitamnya.
“Pruhhh...!” Bragk!
Bangku tempat duduk Sampuraga hancur berantakan. Tetapi laki-laki itu telah melenting dan mendarat tepat di belakang kedua laki-laki tua ini.
“He he he...! Segala orang tua pikun mau menantangku. Lucunya kalian ini...,” ejek Sampuraga, tetap tersenyum.
Kedua kakek itu saling berpandang. Sadarlah mereka kalau kali ini masuk ke sarang macan. Rasanya, sedikit harapan untuk dapat keluar dari ruangan ini dalam keadaan selamat. Kedua tokoh ini sama-sama tersenyum, pertanda telah siap mengadu jiwa.
LIMA
Setelah saling memberi tanda, Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng menerjang serentak. Tapi anak buah Sampuraga yang berada di ruangan ini cepat menghadang dengan senjata terhunus.
“Pruhhh...!” Seketika Pemabuk Dari Gunung Kidul menyemburkan tuak merahnya. Butir-butir tuak yang disertai kobaran api langsung melesat.
Crasss!
“Aaa...!”
“Hust! Minggir kalian...!” Ki Sabda Gendeng tak mau kalah. Tongkat hitamnya disabetkan ke sana kemari.
Bletak!
“Aaakh...!”
Beberapa anak buah Sampuraga yang berkepandaian rendah langsung ambruk tersembur tuak Ki Demong dan terhantam tongkat Ki Sabda Gendeng. Tetapi, di kandangnya sendiri mereka tidak kenal takut. Apalagi, di situ terdapat si Pendeta Murtad dan para bawahannya yang berilmu tinggi.
Trang! Tring!
Beberapa kali terdengar bentrokan senjata. Walau bagaimanapun kedua tokoh urakan yang tangguh itu mempunyai tenaga dan tangan terbatas. Lambat laun, mereka jadi kewalahan dan terdesak. Apalagi setelah dua laki-laki yang bercadar merah dan biru turun tangan. Belum lagi serangan senjata rahasia Duri Bunga Beracun dari Dewi Kencana Wungu.
Semakin lama pertarungan jadi semakin berat sebelah. Walau berusaha semampu mungkin, tetap saja kedua kakek sableng ini terdesak. Bahkan, sebuah tendangan keras dan telak telah menghantam punggung Ki Demong. Lalu, disusul terpukulnya perut Ki Sabda Gendeng. Keduanya terpelanting, namun cepat bangkit kembali dengan mulut meringis menahan sakit.
“Chiaaat!”
Desss...! Desss...!
Kembali kedua laki-laki tua ini terkena pukulan keras dari dua laki-laki yang dikenal berjuluk si Cadar Merah dan si Cadar Biru. Sehingga, kedua tubuh tua itu tersungkur kembali mencium lantai. Pada saat yang sama, Duri Bunga Beracun di tangan Dewi Kencana Wungu berhamburan ke arah Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng yang masih tergolek di lantai. Dan di luar dugaan, keduanya melenting ke atas dengan gerakan udang. Tubuh mereka berjumpalitan tujuh kali ke udara.
Pyarrr...!
“Aaakh...!”
Tidak ampun lagi seorang pengepungnya berteriak menyayat terkena Duri Bunga Beracun yang salah sasaran. Orang itu kontan berteriak sambil menggaruk-garuk seluruh tubuhnya yang terasa gatal. Dia sudah tidak peduli lagi pada ketua dan atasannya. Bisa dibayangkan, betapa jahatnya racun ini.
Begitu mendarat Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng, sampai bergidik ngeri melihat kejadian itu. Keduanya tak menyangka Duri Bunga Beracun begitu jahat. Namun sebelum hilang keterkejutan mereka, serangkum angin berbau harum tiba-tiba meluruk. Secara bersamaan kedua laki-laki tua sableng ini menghentakkan kedua tangan, menangkis. Dan....
Blarrr!
“Hoaakh!” “Aaagkh...!”
Tak dapat tertahan lagi, tubuh Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng terlempar disertai muntahan darah. Kedua tokoh itu tidak dapat bangkit kembali. Mereka hanya dapat telentang tanpa dapat bergerak.
“He he he...! Demong! Tidak sangka pada hari ini kita akan mati bersama-sama...,” ujar Ki Sabda Gendeng.
“Ho ho ho...! Asyik sekali, Sabda Gendeng! Kita dapat mati bersama.... Mereka, belum tentu dapat seperti kita...,” sahut Ki Demong sambil mengerjap-ngerjapkan matanya. Begitu habis berkata, Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng jatuh pingsan.
Melihat hal ini si Cadar Merah telah mengayunkan senjatanya. Agaknya, kedua tokoh konyol ini akan menemui ajal secara mengenaskan.
Wesss...!
Namun, pada saat yang gawat berkelebat sebuah bayangan putih yang kecepatannya bagaikan kilat.
“Awaaas...!” Kedua orang bercadar itu sampai berteriak saking terkejut, seraya membuang diri ke lantai. Sementara bayangan itu terus melesat, setelah menyambar tubuh Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng.
Melihat itu, si Pendeta Murtad segera menghentakkan tangannya ke arah bayangan itu.
Wusss...!
Namun, bayangan putih itu telah lebih cepat keluar dari balairung ini, dan terus melesat keluar membawa Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng. Si Pendeta Murtad dan anak buahnya berusaha mengejar. Namun, mereka telah kehilangan jejak. Bayangan itu sudah tak tampak lagi, lenyap di antara pepohonan lebat.
“Gila...! Ilmu meringankan tubuhnya tinggi sekali. Siapakah bayangan itu...?” gumam Sampuraga dalam hati.
Tokoh lain pun hanya dapat mengawasi, tanpa dapat berbuat sesuatu si Pendeta Murtad memberi perintah agar lebih berhati-hati. Karena dengan lolosnya mereka, berarti ancaman besar tengah menanti!
********************
Gerakan bayangan yang membawa lari Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng memang cepat bukan main. Kedua kakinya seakan tidak menyentuh tanah. Sehingga dalam waktu sepenanakan nasi saja, dia telah jauh dari tempat tinggal Sampuraga. Pada sebuah gua yang cukup luas dan jarang didatangi manusia, sosok bayangan putih itu berhenti.
Kini baru jelas, siapa sosok itu. Ternyata, dia adalah seorang pemuda tampan berbaju rompi putih. Sebuah pedang bergagang kepala burung rajawali tampak bersandar di punggung. Pemuda tampan ini segera memasuki gua. Kemudian kedua orang tua ini diturunkan, langsung dijejali obat pulung pada mulut Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng.
Beberapa saat kemudian kedua tokoh tua itu mulai sadar dari pingsannya. Kendati demikian, di perut masing-masing seperti ada sesuatu yang bergolak, berputar-putar. Lalu....
“Hoeeekh...!”
Hampir berbarengan, Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng membuang muntah darahnya yang berwarna kehitaman ke samping sambil berbaring. Kini wajah mereka mulai cerah sedikit demi sedikit.
Sementara, pemuda tampan berbaju rompi putih ini segera membalikkan tubuh kedua orang tua ini. Setelah menyingkap baju mereka, pemuda ini segera menempelkan kedua telapak tangannya ke masing-masing punggung yang telah keriput itu. Tampaknya dia tengah menyalurkan hawa murni. Setelah merasa cukup, pemuda ini membalikkan kembali tubuh Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng yang telah membuka matanya. Dan saat itulah mereka pulih, tahu kalau yang menolong dari kematian adalah....
“Rangga....! Rupanya kau yang menyelamatkan kami. Terima kasih... terima kasih...,” ucap Ki Sabda Gendeng.
“Aku juga berterima kasih padamu, Rangga. Kalau tidak kau tolong, aku pasti telah jadi makanan cacing tanah.... Tetapi, bagaimana caranya kau menolong kami?! Padahal pada saat itu, semua pentolan tokoh sesat tengah berkumpul.... Aku merasakan sendiri, kalau mereka semua memiliki ilmu olah kanuragan tinggi...?!” tanya Ki Demong sambil menatap heran Pendekar Rajawali Sakti.
“Jangan memandangku terlalu tinggi, Ki.... Mereka saja yang lengah, sehingga aku berhasil menyelinap masuk dan dapat menolong tepat pada waktunya...,” ujar Rangga merendah.
“He he he...! Terserah kaulah. Sekarang yang penting perut sangat lapar.... Dapatkah kau membawakan aku makanan...?” tanya Ki Demong sambil menenggak tuak merah dari guci yang selalu dibawanya.
Pendekar Rajawali Sakti mengangguk sambil tersenyum. Dia cukup maklum melihat tingkah laku kedua orang tua yang sableng ini.
Setelah selesai menyantap daging kelinci panggang dan berunding, Rangga mohon diri. Dan tanpa menunggu jawaban lagi, Pendekar Rajawali Sakti berkelebat pergi. Sementara kedua tokoh tua itu sama menggelengkan kepala. Mereka merasa tidak ada apa-apanya bila dibandingkan pendekar dari Karang Setra ini.
“Demong! Pemuda itu hebat sekali...,” kata Ki Sabda Gendeng.
“Tentu saja! Tidak seperti kau! Dari dulu, tetap saja gendeng....”
“Apa bedanya? Kau pun selalu mabuk-mabukan saja! Dasar tidak punya masa depan...,” balas Ki Sabda Gendeng, melotot.
“Wah...! Kau menantangku...?” tanya Ki Demong.
“Boleh saja!” jawab Ki Sabda Gendeng.
Keduanya segera berdiri sambil bersiap hendak saling terjang. Namun baru saja hendak bergerak, di luar gua terdengar suara orang yang tengah bercakap-cakap. Dengan cepat, keduanya bergerak mengintip keluar. Dan wajah mereka segera berubah merah, menahan amarah. Ternyata yang muncul adalah si Cadar Merah dan si Cadar Biru. Tanpa kenal takut Pemabuk Dari Gunung Kidul dan Ki Sabda Gendeng keluar dari gua.
“Hei! Kalian mencari kami, ya...!” seru Pemabuk Dari Gunung Kidul, sambil melangkah mendekati bersama Ki Sabda Gendeng. Si Cadar Merah dan si Cadar Biru langsung menoleh. Dan mendadak, mereka memberi isyarat dengan tepukan.
Plok! Plok!
Saat itu juga, dari balik semak-semak berlompatan beberapa orang, langsung mengurung kedua orang tua ini. Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng terperangah, karena, tak menyangka kedua orang bercadar itu ternyata ditemani sepuluh orang bertampang bengis.
“Mana orang yang menolong kalian?! Kebetulan sekali, kalian menghampiri kami. Mau cari mati, ya?! Dasar kalian ditakdirkan untuk mati di tangan kami...! Bersiaplah kalian...!” seru si Cadar Merah.
“Ho ho ho...! Kalian tak perlu takut pada orang yang menolongku. Dia tidak ada di sini.... Manusia brengsek! Ayo kita tentukan, siapa yang bertahan hidup...?” tantang Ki Demong, setengah mengejek.
“Bedebah! Siapa yang takut pada orang itu...?! Suruh kemari, biar kuhabisi sekalian...!” bentak si Cadar Merah sambil mencabut senjatanya.
Seketika diterjangnya Ki Demong. Sedangkan si Cadar Biru menyerang Ki Sabda Gendeng.
“Sheaaat!”
Trang! Trang!
Benturan senjata tak dapat dihindari lagi. Suaranya keras memekakkan telinga. Bahkan menimbulkan pijaran api. Sementara Ki Sabda Gendeng dan Ki Demong mengamuk sejadi-jadinya. Pertarungan berlangsung seru dan menegangkan. Ki Demong dengan semburan tuak merah yang disertai semburan api cukup merepotkan si Cadar Merah.
Sementara tongkat Ki Sabda Gendeng juga membuat sibuk si Cadar Biru. Ujung tongkat yang bergetar keras, merubahnya menjadi puluhan jumlahnya. Namun, dua laki-laki bercadar itu juga bukan orang lemah. Dengan pedang mereka mengadakan serangan balasan yang bertubi-tubi, sambil mengatur pertahanan kokoh. Sehingga untuk sementara, sulit bagi kedua belah pihak untuk saling cepat menjatuhkan.
“Pruhhh...!”
Pada satu kesempatan Pemabuk Dari Gunung Kidul meluruk maju, setelah menyemburkan tuak merahnya. Dengan gerakan cepat, si Cadar Merah berhasil menghindari mencondongkan tubuhnya ke belakang. Maka semburan itu lewat di atas wajahnya. Tetapi pada saat yang sama Ki Demong lewat di atasnya sambil menjambret cadar merah orang itu.
Bret!
“Keparat!” dengus si Cadar Merah. Sambil menyabetkan pedang, si Cadar Merah memalingkan mukanya. Maka, tampaklah seraut wajah yang menyeramkan. Mata kirinya bolong tanpa biji. Bibir atas dan bawahnya terbuka tanpa daging, sehingga tampak sangat menyeramkan. Ki Demong sendiri sampai melompat mundur, begitu mendarat di tanah.
“Kalau tidak salah, kau Kebo Lanang. Dan temanmu itu Rangkawi. Kalian jelas bekas tangan kanan Sampuraga pada sepuluh tahun yang lalu...?!” seru Ki Demong sambil menunjuk pada si Cadar Biru yang sedang bertarung dengan Ki Sabda Gendeng.
“Huh...! Bagus kalau kau sudah tahu. Jadi, sekarang kau tidak akan mati penasaran lagi.... Mampuslah kau...!” seru si Cadar Merah yang ternyata bernama Kebo Lanang sambil menerjang kembali. “Yeaaat!”
“Pruhhh...!” Ki Demong terus menenggak dan menyemburkan tuak merahnya. Tapi Kebo Lanang menyambuti dengan mendorongkan kedua tangan disertai tenaga dalam tinggi. Sehingga, semburan disertai api meleset arahnya. Kumis dan janggut Ki Demong sampai berkibaran terserempet angin pukulan dahsyat dari si Cadar Merah.
Sementara keadaan Ki Sabda Gendeng sama saja dengan sahabatnya. Dan dia juga mendapat lawan tangguh yang memiliki kepandaian tidak jauh darinya. Melihat kedua manusia bercadar itu sulit memperoleh kemenangan, kesepuluh orang pengikutnya meluruk ke arah Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng. Maka kini perkelahian tak seimbang segera terjadi.
“Chiaaat!”
Trang! Cring!
Berkali-kali tongkat Ki Sabda Gendeng dan guci tuak Ki Demong, berhasil menghalau serangan. Tapi, serangan kesepuluh orang itu tidak berhenti sampai di situ. Bagaikan ombak di lautan serangan mereka terus mengalun bertubi-tubi ke arah kedua orang tua urakan itu.
“Shaaat...!”
Seorang penyerang, membacok dari belakang. Namun Ki Sabda Gendeng cepat melangkah ke samping. Seketika tangan kirinya menangkap pergelangan tangan lawan. Sedang tangan kanan menusukkan tongkat hitamnya ke belakang. Gerakannya cepat bukan main. Sehingga....
Blesss!
“Hegkh...!”
Tongkat hitam Ki Sabda Gendeng tepat menancap di dada orang itu sampai tembus di punggung. Ketika dicabut, dia jatuh dengan darah menyembur dari lubang bekas lukanya. Orang itu mati dalam kubangan darahnya sendiri. Sementara seorang pengeroyok yang terpaku melihat hal itu jadi lengah. Dan tahu-tahu....
Bret!
“Aaakh...! Orang ini kontan ambruk tersabet tongkat. Perutnya robek dengan usus terburai keluar dari kulit perut.
“Bangsat...!” Rangkawi alias si Cadar Biru segera memutar pedangnya dengan cepat. Langsung diterjangnya Ki Sabda Gendeng. Dengan demikian kembali orang tua itu dikeroyok empat. Untuk menghadapi mereka, Ki Sabda Gendeng harus mengganti jurusnya. Disertai pengerahan tenaga tinggi, ujung tongkatnya segera berubah jadi puluhan. Menghadapi jurus itu, para pengeroyok jadi kebingungan. Akibatnya....
Jres! Cres! Crep!
“Wuaaa...!” Tiga teriakan terdengar saling susul, disusul ambruknya tiga sosok tubuh berlumur darah dengan tenggorokan, ulu hati, dan perut seolah robek. Sedangkan Rangkawi berhasil menyelamatkan diri. Kalau kurang cepat niscaya tenggorokannya berlubang tertusuk tongkat. Tetapi, tanpa terduga Rangkawi memutar tubuhnya. Kakinya cepat menyapu kaki Ki Sabda Gendeng.
Buk!
“Ukh...!” Ki Sabda Gendeng jatuh ke tanah. Pantatnya yang membentur batu terasa nyeri. Sambil mengelus-ngelus pantatnya orang tua ini meloncat bangun. “Setan keparat! Kuhajar kau nanti...!” hardik laki-laki tua yang doyan main catur ini geram.
Namun, Rangkawi tidak mau memberi kesempatan. Dengan mengerahkan tenaga dalam, tubuhnya terus meluruk sambil menyabetkan pedang.
Bret!
“Aaakh!” Ki Sabda Gendeng terserempet pedang pada pundaknya. Dengan memaki kalang kabut, dia balik menyerang.
Sementara itu Ki Demong sedang diserang tiga orang bawahan si Cadar Merah. Mendapat serangan seperti ini Pemabuk Dari Gunung Kidul malah menenggak tuak merahnya banyak-banyak. Lalu dengan gerakan terhuyung-huyung tubuhnya menyelinap ke sana kemari di antara hujan senjata. “Aiiit...!” Anehnya, semua serangan pengeroyok tidak ada yang mengenai sasaran. Bahkan tiba-tiba Ki Demong menyemburkan tuak dari mulutnya dengan gerakan cepat sekali. “Pruhhh...!”
“Wuaaa...!” Tiga pengeroyok kontan menjerit dengan tubuh terbakar. Mereka jatuh bergulingan, lalu diam untuk selamanya. Dua orang lagi segera menerjang Pemabuk Dari Gunung Kidul dengan tenaga dalam penuh. Sambil menggeliatkan tubuh bagaikan orang bermalasan, Ki Demong menghindari. Dan begitu serangan itu lewat, guci tuaknya berkelebat cepat menghantam kepala mereka.
Prok! Prok!
Kontan kepala kedua orang itu pecah. Isinya berantakan keluar. Mereka ambruk, tak bangun-bangun lagi. Kini pertarungan berlangsung satu lawan satu. Kebo Lanang yang wajahnya rusak menakutkan tampak berkerut-kerut menahan amarah meluap. Sehingga makin seram saja dilihatnya.
“He he he...! Waduh..., waduh...! Mukamu jadi mirip setan sungguhan, Kebo Lanang...,” ledek Ki Demong sambil meminum tuaknya.
Dengan tenaga dalam penuh, si Cadar Merah menerjang. Tetapi baru bergerak beberapa tindak, dia telah disambut semburan tuak Ki Demong. Terpaksa Kebo Lanang membuang diri ke samping seraya mengirimkan tusukan ke lambung.
“Uts!” Dengan langkah limbung bagaikan orang mabuk, tubuh Pemabuk Dari Gunung Kidul meliuk-liuk ke sana kemari. Maka, serangan itu lewat begitu saja.
“Sheap!” Bahkan tiba-tiba, Ki Demong mengebutkan gucinya dengan gerakan begitu cepat. Dan....
Bugk! Krek!
“Aaakh...!” Pundak Kebo Lanang patah terhajar guci tuak. Sambil memekik kesakitan, dia mundur beberapa langkah. Sementara itu Ki Sabda Gendeng terus memainkan jurus tongkat yang menjadi andalannya. Sehingga, Rangkawi terpaksa bermain mundur dan bertahan saja. “Hiih!” Tiba-tiba, tongkat Ki Sabda Gendeng menusuk perut.
Namun serangan itu dapat dihindari si Cadar Biru dengan jalan berjumpalitan di udara. Dan memang itu yang diharapkan, mendadak tongkat itu bergerak ke atas. Lalu....
Bret!
“Hakh...!” Cadar berwarna biru kontan terlepas dari wajah Rangkawi. Dan, tampaklah seraut wajah yang tak kalah menyeramkan dari Kebo Lanang. Hidungnya grumpung. Mata kirinya berlubang besar tanpa biji mata. Mulutnya tidak bergigi sebuah pun. Merasa tidak unggulan menghadapi kedua orang tua urakan ini. Kedua orang bercadar ini saling memberi tanda. Tiba-tiba mereka berbalik, langsung melarikan diri.
Tentu saja Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng tidak mau kehilangan buruannya. Dengan gerak cepat mereka mengejar.
ENAM
Setelah sekian lama mengejar namun tak ada hasil, Ki Sabda Gendeng dan Ki Demong menghentikan larinya. Dua sosok manusia bercadar telah lenyap entah ke mana. Dan baru saja kedua orang tua sableng ini hendak berbalik....
“Heh?!”
“Tunggu dulu! Apa kau mendengar suara pertarungan?” tanya Ki Demong sambil menajamkan pendengarannya.
“He... eeh, iya! Mari kita lihat. Cepat! Suaranya seperti kedua manusia telengas yang kita kejar tadi...!” sahut Ki Sabda Gendeng.
Saat itu juga kedua orang tua urakan ini berkelebat ke arah datangnya suara pertarungan yang tak begitu jauh. Sebentar saja, mereka telah tiba di pinggiran kancah pertarungan. Ternyata, yang sedang mengadu jiwa adalah benar-benar dua manusia bercadar!
Sementara yang menjadi lawan mereka adalah dua laki-laki setengah baya dan seorang pemuda tampan berbaju merah. Mereka tak lain dari, Mundinglaya, Balad Kabrang, dan Mudrika.
Wuuus!
Mundinglaya lancarkan serangan dengan menghentakkan tangan kanannya. Sementara Kebo Lanang segera mengangkat tangan kirinya. Tak terelakkan lagi....
Blarrr...!
Dan tenaga dalam tinggi bertemu. Dan Kebo Lanang tampak terjajar lima langkah ke belakang. Mulutnya mengeluarkan darah, pertanda mendapat luka dalam. Ketika menyemburkan nafasnya yang menyesakkan dada, darah segar ikut terlontar dari mulutnya. Berdirinya mulai limbung dan terhuyung-huyung.
Melihat kesempatan baik, Mudrika cepat memasang pedangnya di depan dada. Lalu disertai teriakan menggeledek ujung pedangnya meluncur ke tenggorokan. Orang bercadar merah ini bermaksud menghindar. Tapi dari belakang, telapak tangan Balad Kabrang tahu-tahu telah mendorong punggungnya dengan keras. Akibatnya....
Blesss!
“Aaagkh...!” Tak terhindari lagi, pedang Mudrika menembus tenggorokan si Cadar Merah. Ketika pedang dicabut, tubuhnya jatuh berkubang darahnya sendiri. Melihat si Cadar Biru yang masih bertahan, Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng segera ikut maju....
“Hei...! Ajak aku kalau ada hiburan! Kalian tinggal terima enaknya saja.... Curang...,” gerutu Ki Sabda Gendeng sambil menyabetkan tongkatnya ke arah kaki Rangkawi.
“Wheii...! Jangan mau menang sendiri, Sabda Gendeng! Dia ini bagianku.... Kalian semua minggirlah...!” ujar Ki Demong, seraya menyemburkan tuak merahnya.
“He he he...! Enak saja kalau bicara! Kami bertiga yang menemukan kedua orang ini.... Jadi, kamilah yang berhak menentukan hukuman untuk mereka...!” sergah Mundinglaya sambil membabatkan pedangnya ke leher si Cadar Biru.
Sementara itu menghadapi keroyokan orang-orang tangguh seperti mereka itu, Rangkawi hanya dapat menangkis dan main mundur saja. Tapi, hal itu tidak bertahan lama. Karena tiba-tiba pedang Mudrika yang datang bagaikan air hujan, menerjang ke arah lehernya. Dan....
Crasss!
“Aaakh...!” Si Cadar Biru memekik ketika pedang Mudrika membabat lehernya hingga hampir buntung. Darah langsung merembes dari lukanya. Sejenak dia sempoyongan, lalu ambruk tak berkutik lagi.
“Hi hi hi...! Enak saja kalian membunuh teman-temanku. Hadapi dulu Dewi Kencana Wungu, baru boleh berbuat sekehendak hati....”
Sebuah suara merdu menyentak kesadaran semua para tokoh persilatan yang baru saja membantai dua manusia bercadar. Begitu semua berpaling, tampak seorang wanita cantik berpakaian tembus pandang. Mereka tahu, pasti wanita ini adalah salah seorang anak buah Sampuraga. Memang, dia tak lain dari Dewi Kencana Wungu.
“Heaaat...!” Tanpa basa-basi lagi, Balad Kabrang menerjang. Tapi dengan memasang tubuhnya yang molek dan sintal, Dewi Kencana Wungu berhasil membatalkan serangan Balad Kabrang. Serangan itu ditarik kembali. Sementara pandangan Balad Kabrang jadi melotot lebar melihat lekuk-lekuk tubuh yang begitu indah. Dia jadi terkesima. Dan itu harus dibayar mahal. Karena tiba-tiba Dewi Kencana Wungu menghentakkan kedua tangannya.
“Yeaaa!” Blugk! “Aaakh...!”
Akibat kesalahan itu, sebuah pukulan keras menghantam dada Balad Kabrang. Tanpa mampu ditahan lagi, laki-laki setengah baya ini jatuh telentang. Ketika bangkit kembali, Dewi Kencana Wungu telah mengebutkan tangannya, melepas Duri Bunga Beracun yang langsung meluruk cepat.
Pyurrr...! “Aaakh...!”
Tak ampun lagi, Balad Kabrang jatuh bergulingan sambil menggaruk-garuk ke sana kemari. Rasa gatal dan perih tak terhingga menyerang tubuhnya. Rasanya bagaikan ditusuki ribuan jarum dan digigiti semut merah. Tak pelak lagi tubuhnya hancur tercakar oleh garukan tangannya sendiri.
“Aaakh.... Aadhuuuh...! Sheeeht.... Hsseeeh..., gatal..., adhuuuh..., gataaal...! Toolooong..., gataaal...!” teriak Balad Kabrang sambil terus menggaruki seluruh tubuhnya.
Merasa tidak sampai hati melihat penderitaan Balad Kabrang yang diyakini tidak akan tertolong lagi, Mundinglaya bergerak maju seraya memejamkan matanya.
“Maaf, Balad Kabrang. Kalau kudiamkan, justru penderitaanmu makin menggiriskan hatiku.... Jadi...,”
Crap!
Begitu habis kata-katanya, Mundinglaya menusukkan pedangnya sampai menembus ke punggung. Balad Kabrang mengeluh tertahan sambil menatap redup kawannya.
“Tolong balaskan sakit hatiku ini...,” desah Balad Kabrang, lalu terkulai lemah dengan hembusan napas yang terakhir.
“Bangsat!” Dengan kemarahan meluap Mundinglaya langsung menerjang Dewi Kencana Wungu sekuat tenaga. Suara sambaran pedangnya terdengar menusuk telinga.
Serangannya bahkan diikuti serangan Mudrika. Maka Dewi Kencana Wungu pun terjepit di antara dua serangan dahsyat. Tapi dengan senjata pedang bercabangnya, wanita cantik itu berhasil mematahkannya. Ketika Mundinglaya dan Mudrika baru dua jurus berlaga....
Wesss...!
Mendadak dari sisi kiri berdesir angin keras. Maka dengan sebisanya, mereka menyelamatkan diri masing-masing dengan jalan melompat ke belakang sambil bersalto. Begitu mendarat, mereka langsung melihat satu sosok laki-laki bermata sipit. Ternyata serangan itu memang berasal dari Awyang Hok. Dengan ilmu pedangnya, laki-laki Cina ini bergerak menusuk. Gerakannya sulit diduga, karena masih terasa asing bagi mata para tokoh persilatan tanah Jawa.
“Hiaaat!”
Trang! Tring!
Beberapa bentrokan senjata terjadi menimbulkan suara keras dan pijaran bunga api. Dan ini ternyata membuat tangan Mundinglaya dan Mudrika tergetar. Mereka sama-sama menyadari kalau tenaga dalam laki-laki asing itu, tidak dapat dianggap ringan.
Pada saat yang sama, Dewi Kencana Wungu ikut membantu serangan. Maka keadaan Mundinglaya dan Mudrika pun jadi terdesak. Terutama, menghadapi serangan Dewi Kencana Wungu. Karena sambil menyerang, wanita ini sering memperlihatkan bagian tubuhnya yang terlarang.
Tentu saja hal ini membuat lawan-lawannya tidak dapat memusatkan perhatian secara penuh pada pertarungan. Dan baru beberapa jurus pertarungan berlangsung....
“Keparat...! Wanita jalang! Terimalah kematianmu. Pruhhh...!” bentak Ki Demong sambil menyemburkan tuak merahnya.
Cepat Dewi Kencana Wungu bergerak ke samping sambil mengebutkan lengan bajunya, membuat semburan tuak jadi menyerong ke samping. Berbarengan dengan serangan itu, kakinya menendang ke arah kepala Ki Demong. Dengan sendirinya, kain tipis yang dikenakan terkuak lebar. Akibatnya mata orang tua urakan itu jadi melotot. Biji matanya nyaris loncat keluar.
“Sialan, Wanita Busuk...! Mengapa main-main dengan barang pusaka...? Sekali lagi, kusembur punyamu itu dengan tuakku...!” dengus Ki Demong sambil membuang diri ke belakang.
“Hi hi hi...! Dasar orang tua celamitan! Salah sendiri, mengapa matamu melihat ke arah sini...? Kau yang salah, malah aku yang disalahkan.... Dasar orang tua peyot tidak tahu malu...!” ledek Dewi Kencana Wungu seenaknya.
“Huh...! Mengapa jadi ngobrol tidak karuan...? Sini, biar aku yang memberesi wanita jalang itu...!” hardik Ki Sabda Gendeng, sambil menyabetkan tongkatnya.
“Hast!”
Serangan Ki Sabda Gendeng disambut Dewi Kencana Wungu lewat lemparan Duri Bunga Beracun. Terpaksa serangannya dibatalkan. Dan dengan berjumpalitan ke belakang, orang tua ini melemparkan biji catur ke arah Awyang Hok.
Set! Set!
Tokoh dari daratan Cina ini segera memutar pedangnya bagai kitiran. Maka gulungan pedang itu berhasil menahan biji-biji catur Ki Sabda Gendeng. Pertempuran jadi bertambah sengit.
Mudrika yang masih muda tidak tahan menghadapi serangan Dewi Kencana Wungu. Bukan saja wanita ini berkepandaian tinggi. Dengan gerakan merangsang yang banyak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya, membuat Mudrika dalam waktu singkat saja jadi pontang-panting.
“Bedebah...! Wanita iblis! Aku akan mengadu jiwa denganmu...,” teriak Mudrika berusaha mengusir rangsangan birahinya yang mendadak menggeliat. Seketika pemuda ini menusukkan pedangnya ke arah perut.
“Haes!” Dewi Kencana Wungu cepat mengegos ke samping. Tubuhnya seketika berputar seraya melepas tendangan setengah lingkaran. Dan....
Desss...!
“Aaakh...!” Perut Mudrika mendapat tendangan telak. Tubuhnya terjajar ke belakang tiga langkah. Pemuda itu menekap perutnya yang terasa sakit bagai diaduk-aduk.
Pyur!
Saat itulah Duri Bunga Beracun milik Dewi Kencana Wungu meluruk ke arah pemuda itu. Untung saja ada Ki Demong selalu waspada.
“Pruhhh...!”
Dengan semburan tuak merah, Pemabuk Dari Gunung Kidul berhasil memunahkan terjangan Duri Bunga Beracun.
“Ha ha ha...!” Mendadak terdengar suara tawa menggelegar, membuat masing-masing pihak menghentikan pertarungan.
“Heh...?! Tawa siapa itu. Suaranya bagaikan iblis..!” seru Mundinglaya sambil menekap telinganya dan disertai pengerahan tenaga dalam untuk membendung tawa yang juga berisi tenaga dalam.
“Hoi...! Keluarlah kau...! Jangan jadi pengecut!” teriak Mudrika.
“Ha ha ha...! Bagus..., bagus...! Ternyata kalian semua pendekar hebat! Baik, aku akan keluar....”
Belum juga gema suara itu lenyap, mendadak meluncur satu sosok bayangan kuning dari atas sebuah pohon.
“Hup!” Ringan sekali bayangan kuning itu mendarat. Kini tampak jelas, siapa yang muncul. Di tengah kancah pertarungan tadi berciri sesosok tubuh tinggi besar berkepala botak. Pakaiannya serba kuning. Di lehernya tergantung tasbih besar terbuat dari emas juga. Penampilan yang seperti itu, membuat tubuhnya bersinar kuning. Memang yang muncul adalah Sampuraga. Laki-laki ini berdandan sebagai seorang pendeta, dan mengaku dirinya sebagai Sang Pendeta.
“Hormat kami pada Sang Pendeta....” Para anak buah Sampuraga langsung menjura memberi hormat.
“Ammitabhaaa...! Syukurlah kalian masih selamat. Biar mereka kuberi pelajaran sedikit...,” ucap Sampuraga sambil tersenyum.
“Hei...! Kau yang dulu dikeroyok beramai-ramai dan diusir dari tanah Jawa ini, mestinya bisa membuka hati kecilmu! Apalagi, kau telah mengaku dirimu sebagai Sang Pendeta? Apakah kau sudah cuci tangan dari segala perbuatanmu yang buruk di masa lampau...? Tapi, yang terlihat kini, kau malah semakin busuk dan kejam luar biasa...!” desis Ki Sabda Gendeng.
“Ammitabhaaa.... Mungkin kalian mendengar dari sumber yang membenci diriku. Sehingga, mereka menjelek-jelekkan segala yang kulakukan. Hal itu sudah wajar bukan...?” jawab si Pendeta Murtad, enteng.
“Huh! Kali ini dosamu tidak terampunkan lagi, Keparat! Segala bajingan besar mengaku dirinya Sang Pendeta. Kau benar-benar manusia terkutuk, Sampuraga...!” dengus Ki Demong.
“Hua ha ha...! Hebat kau, Demong. Tapi di mataku, kau tak lebih seekor tikus yang ketakutan melihat kucing!” ejek Sang Pendeta.
“Keparat! Sejak dulu aku belum pernah takut pada orang. Kecuali, yang mempunyai kepala tiga dan bertangan enam. Kalau itu, barangkali aku agak ngeri...!” tukas Pemabuk Dari Gunung Kidul sambil menenggak tuak merahnya dari guci.
“Glug! Glug! Ceglug!” “Pruhhh...!” Seketika Ki Demong menyemburkan tuaknya. Sambaran tuak yang disertai nyala api mengancam Sang Pendeta.
“Uts!” Tapi sekali mengibaskan lengan baju Sampuraga, membuat serangan itu melenceng ke samping. Bahkan sekali dorong dengan telapak tangan terbuka, tubuh Ki Demong terjajar mundur empat langkah ke belakang.
“Gila...! Tenaga dalam yang dipergunakannya hebat luar biasa!” rutuk Ki Demong dalam hati.
“Ha ha ha...! Ki Demong! Aku ingin membuktikan kata-katamu kalau kau takut pada orang berkepala tiga dan bertangan enam..., lihat...!” kata Sang Pendeta dengan suara besar.
Ketika Ki Demong memperhatikan, tubuh Sampuraga telah terselubung asap. Ketika perlahan-lahan asap menghilang, tahu-tahu tubuh Sang Pendeta berubah jadi besar. Kepalanya telah bertambah tiga. Sedangkan tangannya menjadi enam.
“Ha ha ha...!” Sang Pendeta yang kini bertubuh mengerikan, tertawa terbahak-bahak sampai daun-daun kering berjatuhan dari tangkainya.
“Hah...? Ilmu iblis...!” seru Ki Demong.
“Gila...! Dia kini telah menguasai ilmu sihir jahat...!” desah Ki Sabda Gendeng terkejut.
Wuuut...!
Sang Pendeta tertawa-tawa sambil mengebutkan lengan bajunya pada kedua tokoh tua yang urakan ini. Cepat Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng mendorongkan telapak tangannya ke depan.
Blammm!
Dua tenaga dalam tinggi beradu di udara. Ki Sabda Gendeng dan Ki Demong terjajar mundur tiga langkah. Tangan mereka terasa kaku dan tidak dapat digerakkan lagi. Namun dengan penasaran mereka menerjang kembali. Kali ini, mereka menggunakan tenaga dalam penuh. Tetapi....
“Hua ha ha...! Balik...!” teriak Sang Pendeta dengan suara berpengaruh.
“Wuaaa...!” “Aaa...!”
Bagaikan didorong tenaga raksasa, kedua orang tua urakan itu tertolak balik sebelum menyentuh lawannya. Bagaikan nangka busuk, mereka jatuh telentang. Mundinglaya dan Mudrika tak mau ketinggalan. Mereka segera mati-matian. Tetapi tangan Sampuraga yang berjumlah enam telah bergerak bagaikan setan.
Tap! Tap!
Pedang Mundinglaya dan Mudrika entah bagaikan dapat ditangkap dan dirampas Sampuraga. Lalu dengan sekali tekuk pedang-pedang dipatahkan jadi dua. Bahkan mendadak, dua tangan Sampuraga berkelebat mengancam.
“Uts...!” Cepat keduanya menggulingkan diri, menjauhi Sang Pendeta. Tetapi baru saja bangkit, Awyang Hok telah melesat dengan sambaran pedang. Kembali Mundinglaya dan Mudrika bergulingan, bergabung dengan Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng.
Setelah saling memberi isyarat, mereka berempat menerjang ke arah Sang Pendeta secara serempak dengan serangan dahsyat bukan main. Angin pukulan gabungan ini menimbulkan suara bergemuruh. Bahkan batu kecil serta dedaunan terangkat naik ke udara.
Wuuuus...! Werrr...!
Batu pasir dan dedaunan yang terangkat naik kini berputar-putar, lalu tiba-tiba meluruk ke arah Sang Pendeta. Sambil tetap tertawa, Sampuraga yang telah berubah wujud ini mementang kedua kakinya sampai melesak ke tanah. Dan seketika keenam tangannya mendorong ke depan.
“Heaaa...!” Wuuut!
serangkum angin keras berhawa panas dari tangan-tangan Sampuraga menyambar ke arah pusaran batu dan dedaunan. Blammm! Terdengar ledakan keras yang disusul terciptanya satu asap tebal yang menghalangi pandangan.
Wesssht!
Ketika asap itu lenyap, keempat pengeroyok Sampuraga sudah tidak tampak lagi di tempat itu.
“Sialan! Awas, kalian! Bila bertemu lagi, jangan harap dapat meloloskan diri!” maki Sang Pendeta geram bukan main.
********************
TUJUH
Hari ini matahari bersinar sangat terik. Namun keadaan itu tak membuat empat orang yang tengah berlari menghentikan langkah. Peluh mereka telah membanjir di sekujur tubuh. Mereka tampak tidak ada tanda-tanda hendak menyerah.
“Ki Demong! Bagaimana di depan sana kita beristirahat sejenak untuk melepaskan lelah...?” tanya salah satu laki-laki tua yang berlari.
Mereka memang Ki Demong, Ki Sabda Gendeng, dan Mundinglaya, dan Murdika yang baru saja terbebas dari ancaman maut yang ditebarkan Sampuraga.
“Baiklah.... Aku juga sudah lelah.... Kasihan Mudrika dan Mundinglaya...,” jawab Ki Demong sambil mempercepat larinya.
Sesampai di tempat yang banyak ditumbuhi pohon besar dan berdaun lebat, mereka berhenti dan beristirahat sambil melepas lelah. Mungkin karena terlalu lelah, Mudrika dan Mundinglaya tertidur di bawah pohon.
“Mereka tak akan mengejar sampai kemari. Kini, apa yang akan kita lakukan...?” tanya Ki Demong.
“Saat ini kita belum tahu harus berbuat apa. Sebaiknya kita tunggu beberapa waktu lagi.... Siapa tahu, kita mendapat akal dan jalan keluarnya...,” sahut Ki Sabda Gendeng sambil minum tuak dari bumbung bambu yang selalu tersampir di pundaknya.
“He he he...! Buat apa kita susah-susah. Kau benar, Sobat.... Mari kutantang kau main catur...,” kata Ki Demong.
“Berani kau menantang aku main catur...? Mari buktikan, siapa yang lebih unggul di antara kita...?” tukas Ki Sabda Gendeng sambil mengeluarkan permainan caturnya dari balik baju.
Sebentar saja, kedua orang yang sama bodohnya dalam hal main catur ini sudah terlibat permainan ulet. Keduanya sama-sama diam tak ada yang bersuara, seolah-olah tengah menghadapi persoalan pelik dan tak terpecahkan. Untuk menjalankan sebuah bidak saja, memerlukan waktu lama!
Di tengah keheningan itu, tak ada yang menyadari kalau pemuda berbaju rompi putih dengan rambut panjang telah berdiri di tempat ini. Pada punggungnya tersampir sebilah pedang berhulu kepala burung rajawali. Siapa lagi pemuda itu kalau bukan Pendekar Rajawali Sakti?
“Hm.... Kalian sudah meninggalkan kewaspadaan rupanya. Sampai-sampai kehadiranku tak ditanggapi,” tegur Pendekar Rajawali Sakti.
“Hua ha ha...! Rangga...! Kebetulan kau datang! Kami semua sedang mendapat kesulitan,” sambut Ki Demong sambil melompat bangun, setelah menoleh ke arah Rangga.
“Apa yang telah terjadi terhadap kalian...?” Rangga balik bertanya.
Dengan singkat tetapi jelas, Ki Demong menceritakan segala yang terjadi beberapa waktu berselang. Dan Mundinglaya serta Mudrika yang sudah terbangun ketika mendengar tawa Ki Demong membenarkan cerita itu. Bagi Mudrika, dia pernah mendengar nama besar Pendekar Rajawali Sakti. Maka dipandanginya Rangga dengan perasaan kagum.
“Aku juga sering mendengar tentang kekejaman mereka. Tapi, aku tak mengira kalau yang menamakan dirinya Sang Pendeta memiliki kepandaian setinggi itu.... Beberapa waktu yang lalu, aku bertemu ketua Pesanggrahan Pondok Ungu. Mereka bermaksud membantu kita dalam menghadapi Sang Pendeta...,” jelas Rangga.
“Siapakah nama besar...?” potong Mundinglaya.
“Dia keponakan muridku. Namanya, Bima Sena dan istrinya yang tidak dapat bicara. Puspita Dewi namanya...,” jelas Ki Demong, mewakili Rangga menjawab pertanyaan itu.
“Oh...?! Kiranya kau berasal dari Padepokan Pondok Ungu,” seru Mundinglaya dan Mudrika hampir bersamaan.
“Syukurlah kalau mereka mau membantu. Murid-murid padepokan itu cukup banyak dan terlatih. Kedudukan kita akan bertambah kuat,” sambut Ki Sabda Gendeng sambil garuk-garuk kepala yang tak gatal.
“Benar! Di samping itu, masih banyak pendekar yang bersedia membantu kita. Oh, iya! Masih ada dua padepokan silat yang dulu terlibat dengan Sampuraga. Dan mereka bersedia bergabung dengan kita. Tapi, kita harus ingat...! Jangan sampai mengorbankan mereka yang berkepandaian tidak memadai. Pertempuran kali ini sangat berbahaya dan pasti memakan banyak korban...,” papar Pendekar Rajawali Sakti.
“Lalu, apa rencanamu. Rangga...?” tanya Ki Sabda Gendeng.
“Kudengar, mereka akan mengadakan gerakan pada hari kelima, setelah purnama mendatang.... Jumlah mereka cukup lumayan. Apalagi, mereka rata-rata berkepandaian tinggi dan terlatih baik. Jadi kita menggempur, karena mereka berniat berontak pada Kerajaan Lemah Abang. Ditambah, sepak terjang mereka yang sangat meresahkan masyarakat. Di samping itu bila mereka dibiarkan, darah akan selalu mengalir dari orang-orang lemah yang tidak bersalah...,” jelas Rangga kembali.
“Lalu kapan kita harus bergerak...?” tanya Mudrika, tidak sabar.
“Para pendekar yang lain bergerak sehari, sebelum mereka turun gunung.... Kita semua berkumpul di Gunung Saka dalam sikap mengurung. Kemudian, bergerak serentak tatkala melihat tanda panah api melesat ke udara.... Saat itulah kita tidak perlu sungkan dan banyak pikir lagi. Pokoknya, yang tidak memakai tanda kain merah di tangan babat saja...! Bukannya kejam, tapi demi mengurangi bencana dalam dunia persilatan...,” kembali Pendekar Rajawali Sakti membeberkan rencananya.
“Jadi sebagai tanda kalau mereka teman kita adalah, kain merah yang diikat pada pergelangan tangan...?” tanya Mudrika kembali.
“Benar...!” jawab Rangga, tegas.
Rupanya, selama ini Pendekar Rajawali Sakti bergerak secara diam-diam menghubungi beberapa padepokan silat. Rangga memang mendengar kalau kekuatan Sampuraga terdiri dari para tokoh hitam. Makanya, Rangga juga tak ingin menghubungi pihak Kerajaan Lemah Abang. Karena baginya akan menambah korban saja. Pendekar Rajawali Sakti lantas memutuskan untuk menghubungi para tokoh persilatan, sekalian mengatur siasat. Dan kemudian semua rencana itu dipaparkan pada Ki Demong, Ki Sabda Gendeng, Mundinglaya, dan Murdika.
********************
Saat ini Gunung Saka telah dikelilingi para tokoh persilatan di tempat-tempat tersembunyi. Di antara mereka juga terdapat Ki Sabda Gendeng dan kawan-kawannya. Mereka bergerombol di suatu tempat. Mereka semua adalah para tokoh persilatan yang tidak suka terhadap sepak terjang Sampuraga. Mereka berkumpul, menanti tanda panah api dilepaskan Pendekar Rajawali Sakti. Keseluruhan memakai ikat kain merah pada pergelangan tangan agar tidak salah serang.
Sementara di puncak sana, terjadi kesibukan untuk mengadakan persiapan pemberontakan bila saatnya diperlukan nanti. Dewi Kencana Wungu dan Awyang Hok tampak sibuk pula mengatur siasat yang akan dipakai dalam pemberontakan nanti.
Di saat semuanya sibuk, Sampuraga mengajak Dewi Kencana Wungu meninggalkan tempat pertemuan. Mereka langsung menuju kamar yang tak jauh dari tempat ini. Setelah kamar terkunci, mereka segera menuju tempat tidur yang besar dan empuk itu. Selanjutnya hanya seekor cecak yang tahu apa yang dilakukan dua insan berlainan jenis yang ada hanya suara tertawa cekikikan dan dengus napas memburu.
Pada ruangan lain terdengar suara tangis dan makian. Semua suara itu berasal dari wanita yang dikurung dalam kamar. Mereka diculik dari beberapa desa dengan maksud sebagai puas nafsu sebelum hari pemberontak tiba. Si Pendeta Murtad ingin para anak buahnya jadi bersemangat, tatkala melakukan pemberontak nanti.
Puncak Gunung Saka terselimut gelap malam. Rayapan kabut membawa hawa dingin, memaksa siapa saja yang berada di luar harus memeluk tangannya sendiri. Namun, suasana itu tidak berlaku bagi satu sosok tubuh yang mengendap-endap memasuki bangunan tempat tinggal Sampuraga, tanpa seorang pun yang mengetahui. Jelas, sosok ini memiliki kepandaian tinggi.
“Hup...!” Ringan sekali gerakan sosok itu saat tubuhnya melayang, dan hinggap di atas bangunan. Dengan berjingkat-jingkat, sosok ini segera mencari kamar Sampuraga. Setelah diketemukan, dibukanya sebuah genting. Langsung diawasinya suasana dalam ruangan kamar ini. Tampak Sang Pendeta tengah tertidur pulas, suara dengkurnya terdengar nyata. Dengan perlahan dan gerakan halus, sosok itu mengeluarkan beberapa benda kecil yang bergerak-gerak dari balik bajunya. Lalu, dilemparkannya ke arah Sang Pendeta.
Wer! Siet!
Benda-benda kecil yang tak lain binatang berbisa itu cepat meluncur ke bawah, ke arah sasaran yang dituju. Sebagai tokoh tingkat tinggi, Sampuraga bisa menangkap desir halus yang meluncur ke arahnya. Maka seketika dengan telapak tangan terbuka dipapaknya binatang-binatang berbisa itu.
“Shaaat!” Bres!
Binatang-binatang berbisa itu kontan berjatuhan dalam keadaan hangus. Bahkan kemudian, dengan gerakan cepat tangannya menghentak kembali ke arah sosok tadi berada.
Bruagk!
“Ah...!” Atap genteng kontan hancur berantakan. Selang beberapa kejap, dari atas melayang satu sosok tubuh dengan gerakan seringan kapas. Dan dengan mulus, dalam kamar Sang Pendeta telah mendarat satu sosok laki-laki berbadan cebol. Pakaiannya panjang berwarna hitam. Wajahnya bulat dengan hidung bulat seperti tomat.
“Boleh juga kau dapat menyelinap masuk kemari. Tapi, siapakah kau ini...?” tanya Sampuraga sambil menatap tajam.
“Aku Tabib Beracun. Segala rencana dan perbuatan busukmu telah kuketahui.... Hari ini terimalah kebinasaanmu...!” desis laki-laki cebol berjuluk Tabib Beracun.
“Heh...?! Bukankah kau dari aliran sesat?” tukas Sampuraga, agak heran juga ada tokoh sesat malah menentang tokoh sesat pula.
“Terserah orang mau menilai aku dari golongan apa. Dan aku juga tidak mau peduli dengan segala tindak tanduk orang lain.... tapi terhadap kau yang seperti iblis, aku tak dapat tinggal diam...!” desis Tabib Beracun.
“Hua ha ha...! Apa dipikir kau sudah hebat? Hm.... Sekarang, terimalah ini. Heaaa...!” kata Sampuraga, seraya menghentakkan tangannya.
Sebuah serangan berupa terjangan angin dahsyat meluruk ke arah Tabib Beracun. Tapi dengan gerakan memutar, dia berhasil menghindarinya. Bahkan tiba-tiba tubuhnya meluruk, seraya melepas hantaman.
Bugk! Blugk!
“Hekh!” Serangan tak terduga itu memang mengenai sasaran. Tapi ketika Tabib Beracun hendak menarik telapak tangannya, ternyata sudah melekat erat tak dapat dilepaskan kembali. Wajah laki-laki cebol ini jadi berubah pucat. Dengan sekuat tenaga kedua tangannya berusaha dilepaskan dari tubuh si Pendeta Murtad. Tetapi, tangannya seolah telah bersatu dengan tubuh Sampuraga. Malah kepalanya sampai mengeluarkan asap putih, karena terlalu deras mengerahkan tenaga dalam.
“Hekh...! Eeekh...!” Tabib Beracun tetap berusaha sekuat tenaga. Dari sudut bibirnya sudah mengeluarkan darah. Semakin lama, darah yang keluar semakin banyak. Dirasakannya satu sedotan kuat pada telapak tangannya dan dia tak kuasa lagi untuk dilepaskan.
“Hua ha ha...! Segala tikus dapur sok mau jadi pahlawan! Lebih baik kau jadi raja cacing saja di tanah...,” ejek Sang Pendeta.
“Hoekh...!”
Ketika Tabib Beracun hendak menjawab, darah tumpah dari mulutnya. Sambil tertawa-tawa, Sang Pendeta Sampuraga membuka tangannya kiri dan kanan. Kemudian dipukulkan pada pelipis kiri dan kanan Tabib Beracun.
Prak!
“Aaa...!” Kepala Tabib Beracun pecah seketika. Darah merah bercampur putih muncrat menjadi satu. Ketika jatuh ke tanah, laki-laki cebol ini telah dalam keadaan binasa.
********************
DELAPAN
Malam ini, adalah malam ketiga bagi para tokoh persilatan menanti datangnya aba-aba panah api, untuk menyerang tempat tinggal Sampuraga! Dan tepat malam ini, di tempat itu terdengar gaduh sekali. Beberapa kali terdengar teriakan minta tolong dari wanita-wanita yang diculik anak buah si Pendeta Murtad. Ini berarti, para penghuni rumah itu tengah bersuka ria sambil menikmati perempuan-perempuan hasil culikan.
Tentu saja keadaan ini membuat geram para tokoh persilatan yang mengepung. Mereka hendak bergerak, tapi teringat pesan Pendekar Rajawali Sakti yang menekankan agar mereka jangan bergerak dulu sebelum ada tanda.
“Huh! Kalian ciumlah! Bau tuak sudah merebah kemari.... Berarti mereka telah mulai mengadakan acara gila-gilaan. Lantas, mengapa tanda panah api belum dilepaskan...?” tanya Mundinglaya tak sabar.
“Tunggu dan sabar. Mungkin Pendekar Rajawali Sakti mempunyai perhitungan lain dan sedang menunggu saat yang tepat...,” tukas Ki Demong.
Tapi, tampak Mudrika telah mencabut pedangnya. Rupanya, pemuda yang mempunyai dendam sedalam lautan ini tak sabar lagi menunggu panah api diluncurkan. Matanya selalu mengawasi ke atas, untuk melihat panah api.
“Huh...! Mengapa lama sekali...,” desah tokoh lain, mulai tak sabar.
Di saat ketegangan mulai memuncak, terdengarlah desis keras diiringi nyala api yang meluncur ke angkasa malam. Panah api itu bersinar terang sejenak, kemudian lenyap kembali. Begitu melihat tanda itu, para pengepung mulai meluruk ke atas.
“Serang...!”
“Bunuh...! Hancurkan pemberontak hina...!”
“Ayo majuuu.... Serbuuu...!”
Bagaikan air bah, mereka menyerbu bangunan tempat tinggal Sang Pendeta disertai teriakan merobek angkasa. Berbagai senjata tajam tampak berkeredep di malam itu. Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng mendahului membuka jalan. Yang menghalangi, disembur tuak dan ditusuk tongkat. Mudrika memutar pedangnya secepat baling-baling. Maka korban pun mulai berjatuhan.
“Wuayaaa...!” “Aaa...!”
Karena sedang terlena dan sibuk berbuat mesum, para anak buah Sampuraga tak dapat bersiaga. Sehingga mudah saja nyawa mereka dihabisi. Pintu yang terkunci didobrak sampai berantakan. Ada juga yang berhasil meraih senjata, walaupun belum berpakaian. Tapi, mereka malah menjadi korban kemarahan para tokoh persilatan yang memang telah muak terhadap Sang Pendeta.
Dengan sekali sabet, pedang Mudrika berhasil membantai para anak buah Sang Pendeta yang kebanyakan tengah sibuk mencari pakaian. Sehingga, mereka menjadi korban dengan mudah. Apalagi Ki Demong. Dengan nakal dia menyemburkan tuak berapi pada barang kebanggaan laki-laki milik orang-orang itu. Kontan mereka kelabakan karena barang berharganya terbakar.
“Aduuuh..., duhhh...! Panas, ampun mati aku...!”
Pada saat itu masuk pula ke ruangan Sampuraga pendekar yang dikenal bernama Bima Sena dan Puspita Dewi. Mereka berasal dari Padepokan Pondok Ungu (Untuk mengetahui nama Bima Sena dan Puspita Dewi baca Satria Pondok Ungu). Begitu berjumpa musuh mereka segera membunuhi gerombolan ini. Gerakan mereka disusul munculnya para pendekar dari golongan putih, yang rata-rata berkepandaian tinggi. Tentu saja hal itu telah membuat anak buah si Pendeta Murtad bertambah kalang kabut.
“Tolooong...! Ampuunnn! Jangan bunuh kami.... Wuaakh...!” teriak para pengikut si Pendeta Murtad saling sambung menyambung.
Darah telah menganak sungai di ruangan itu. Potongan tangan dan kaki berserakan tak teratur, membuat mual perut. Hanya satu dua orang yang berhasil merapikan pakaian dan meraih senjatanya. Tapi, semua itu sia-sia belaka. Karena jumlah penyerbu cukup banyak. Lagi pula, mereka dalam keadaan mabuk dan lemas.
“Ciaaat!” “Heaaa...!” Bret! “Aaa...!”
Kembali beberapa tubuh berjatuhan dalam keadaan binasa. Awyang Hok mulai keluar dengan perasaan heran. Keadaannya juga dalam keadaan mabuk. Dan kemunculannya disambut Ki Demong. Dalam keadaan demikian, kemampuan tokoh dari Cina ini tidak berkembang. Tak heran kalau dalam waktu singkat dia telah terdesak hebat, oleh serangan Ki Demong.
Sementara para pendekar yang memang telah membenci, ikut membantu Ki Demong tanpa kenal ampun. Akhirnya, tanpa dapat ditahan lagi tubuh Awyang Hok habis dihujani senjata tajam. Dia binasa dalam keadaan tak berbentuk lagi!
Namun yang membuat para tokoh persilatan rikuh adalah para wanita yang berteriak-teriak sambil berlarian, tanpa memakai pakaian sehelai benang pun. Dan Puspita Dewi mendapat tugas untuk memimpin mereka keluar, lalu mencari pakaian seadanya.
Dalam keadaan yang hiruk pikuk dari dalam berkelebat satu sosok bayangan kuning. Begitu cepat gerakannya, sehingga sulit diikuti pandangan mata biasa. Dan tahu-tahu, bayangan kuning itu telah meluruk ke arah Mundinglaya dengan serangan berbahaya. Untung saja, laki-laki itu dapat menyadari. Langsung ditangkisnya serangan itu.
Blarrr!
Dua tenaga dalam dahsyat bertemu. Akibatnya Mundinglaya terjajar beberapa tindak dengan kaki tampak gemetar. Lalu dia jatuh duduk dengan darah meleleh dari sudut bibir. Sebelum sempat berbuat sesuatu, kaki bayangan kuning itu telah menendang kepala Mundinglaya.
Prak!
“Aaakh...!” Dengan teriakan menyayat Mundinglaya roboh. Kepalanya retak mengeluarkan darah. Dia binasa di saat itu juga.
“Sampuraga...!” teriak beberapa tokoh persilatan, begitu mengenali bayangan kuning yang membantai Mundinglaya.
“Hua ha ha...! Bangsat kecil! Kalian berani masuk ke sarang macan, berarti sudah bersiap tidak kembali lagi...!” desis sosok yang memang Sang Pendeta.
“Bagus! Akhirnya kau muncul Sampuraga! Kami telah bertekad untuk melenyapkanmu dari permukaan bumi ini...!” seru para pendekar, serentak.
Kemudian secara beramai-ramai mereka mengeroyok Sang Pendeta. Agaknya mereka telah lupa pesan Pendekar Rajawali Sakti, kalau Sampuraga adalah bagiannya. Walau dikeroyok beramai-ramai dengan berbagai senjata, tampaknya Sang Pendeta tak gentar. Bahkan tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan asap tebal. Asap itu terus membubung tinggi, lalu perlahan-lahan menghilang.
Namun bersamaan itu sosok Sang Pendeta telah berubah menjadi makhluk raksasa yang besar. Makhluk itu langsung membantingi para pengeroyok satu persatu. Bagaikan daun kering dan layangan putus, tubuh mereka terpelanting dan terseret-seret sampai binasa. Darah berhamburan memenuhi ruangan. Yang membandel, mati dengan kepala pecah. Atau, kaki dan tangan terlepas dari tubuh. Sungguh suatu ilmu sesat yang dahsyat!
Sementara itu Bima Sena dari Padepokan Pondok Ungu maju menerjang Dewi Kencana Wungu. Ilmu-ilmu tingkat tinggi telah dikerahkan, namun belum juga mampu menyudahi wanita telengas itu. Dewi Kencana Wungu terus melempar Duri Bunga Beracun yang sangat beracun. Namun Bima Sena menghindarinya dengan melenting ke belakang.
Ki Demong dan Ki Sabda Gendeng beserta Mudrika tak ingin berpangku tangan lebih lama. Maka mereka segera mengeroyok wanita jalang yang sangat berbahaya itu. Belum lagi keroyokan dari para pendekar yang rata-rata berkepandaian tangguh.
“Chiaaat...!”
Mendapat serangan dari segala arah, membuat Dewi Kencana Wungu kebingungan sendiri. Yang lebih sialnya, setiap sambaran Duri Bunga Beracunnya berhasil dipatahkan semburan Ki Demong. Dan ketika wanita itu hendak menebar senjata rahasianya kembali, Ki Demong telah meluruk cepat sambil menyabetkan guci tuaknya.
“Hiih...!” Dengan sebisanya, Dewi Kencana Wungu mengegos ke kiri. Namun pada saat yang sama Ki Sabda Gendeng telah menyambutnya dengan tongkat. Dan....
Diegkh...!
“Aaakh...!” Dewi Kencana Wungu terjajar beberapa langkah disertai keluhan tertahan. Dan sebelum dia sempat berbuat apa-apa, dari belakang Bima Sena meluruk maju dengan tendangan menggeledek.
Dugkh!
“Ohhh...!” Wanita ini terdorong ke muka dengan tubuh sedikit merunduk, kesempatan ini tidak disia-siakan salah seorang tokoh persilatan. Seketika pedangnya berkelebat. Lalu....
Crasss...!
“Aaa...!” Diiringi terdengar jeritan menyayat, tubuh Dewi Kencana Wungu ambruk dengan kepala terpisah, ketika pedang itu menyambar lehernya. Sebentar Dewi Kencana Wungu meregang nyawa, lalu diam tak bergerak lagi.
“Kisanak semua, minggirlah...! Biar Sang Pendeta bagianku!” teriak Pendekar Rajawali Sakti yang kini telah berdiri di tengah kancah pertarungan.
Sebelum Pendekar Rajawali Sakti sempat menyerang, raksasa jelmaan itu mencengkeram dengan tangannya yang berbentuk cakar. Namun dengan kelincahan dan jurus ‘Sembilan Langkah Ajaib’. Rangga bisa menghindar. Tubuhnya meliuk-liuk bagai hendak jatuh.
“Ciaaat!” Tiba-tiba Pendekar Rajawali Sakti berkelebat. Lalu dengan sisi telapak tangan, disabetnya tangan raksasa itu.
Tak!
Rangga terpaksa meringis sendiri karena tangannya terasa sakit sekali. Pendekar Rajawali Sakti segera mengatur kuda-kudanya, siap mengerahkan jurus-jurus gabungan dari lima rangkaian jurus ‘Rajawali Sakti’.
“Heaaa...!” teriak Pendekar Rajawali Sakti, seraya meluruk dengan jurus ‘Sayap Rajawali Membelah Mega’. Setelah berputaran beberapa kali, dihantamnya kepala raksasa itu dengan jurus ‘Pukulan Maut Paruh Iblis’.
Diegkh! Blash!
“Heh?!” Pendekar Rajawali Sakti tersentak kaget, ketika tubuh raksasa itu tahu-tahu lenyap menjadi asap kembali. Keanehan terjadi. Kini yang berdiri di depan Rangga adalah Sampuraga yang mengaku sebagai Sang Pendeta.
“Heaaat!” Begitu kembali ke aslinya. Sampuraga meluruk menyerang Pendekar Rajawali Sakti yang masih terkesiap. Karena semula sosok raksasa ini adalah wujud sebenarnya dari Sampuraga.
Desss...!
“Aaakh...!” Tak ampun lagi Pendekar Rajawali Sakti terjajar ke belakang, terhantam pukulan dahsyat bertenaga dalam tinggi. Darah tampak menetes dari sudut bibirnya. Namun, secepat itu pula Rangga bangkit, bersiap kembali.
“Keparat! Hmm.... Dari pedang yang tersandang, tentu kau yang bergelar Pendekar Rajawali Sakti...,” desis Sampuraga seraya menatap tajam pada Pendekar Rajawali Sakti.
“Hentikan sepak terjangmu, Kisanak! Masih ada waktu untuk bertobat,” ujar Pendekar Rajawali Sakti, tenang penuh perbawa.
“Bangsat! Bocah kemarin sore berani berkhotbah di depanku?!” bentak Sampuraga, untuk menutupi kegentarannya melihat tatapan Pendekar Rajawali Sakti yang dingin menggetarkan.
“Kalau begitu, jangan salahkan aku bila bertindak keras padamu. Kau sudah kuperingatkan. Dan itu cukup sekali saja, bagi orang sepertimu...!” desis Rangga.
“Pendekar Rajawali Sakti! Kau memang batu sandunganku yang paling besar. Tapi bukan berarti aku gentar. Tak ada yang dapat menandingiku setelah aku berguru di tanah Tiongkok...!”
“Terserah kau berguru di mana. Itu bukan urusanku. Yang menjadi urusanku adalah, melenyapkan orang telengas sepertimu...!”
“Keparat busuk! Terima seranganku.... Heaaa...!” Begitu habis kata-katanya, si Pendeta Murtad mengebutkan tasbih emasnya disertai pengerahan tenaga dalam tinggi. Maka saat itu juga, melesat sinar kuning keemasan mengancam keselamatan Rangga.
“Uts.... Terpaksa...!” Rangga cepat melenting ke atas sambil menggosok kedua telapak tangannya, hingga mengeluarkan sinar biru berkilauan sebesar kepala bayi yang menyelubungi pergelangan tangan. Tepat ketika sinar kuning telah melintas, kedua kakinya mendarat di tanah dalam keadaan kuda-kuda kokoh.
“Rasakan seranganku ini...!” Di tengah kemarahan yang membludak, Sang Pendeta mengerahkan tenaga dalamnya yang paling tinggi saat menyabetkan tasbih emasnya.
Wuuusss...!
Seketika sinar keemasan berkilau ini melesat. Pada saat yang sama Rangga yang telah bersiap, menghentakkan kedua tangannya ke depan.
“Aji Cakra Buana Sukma...! Heaaa...!”
Wuuuttt...!
Sinar biru berkilau meluncur, memapak sinar kuning keemasan. Dan...
Blarrr...!
Terdengar ledakan dahsyat disertai pijaran bunga api ke segala arah. Tak lama, sinar kuning keemasan itu terpecah pula ke segala arah. Sementara, sinar biru berkilau milik Rangga terus menerobos. Dan...
Jderrr...!
“Aaa...!” Ajian Cakra Buana Sukma yang disertai tenaga dalam tingkat tinggi menghantam Sang Pendeta hingga hancur tak berbentuk lagi. Tamat sudah riwayat Sampuraga.
Sementara itu, Pendekar Rajawali Sakti jatuh terduduk. Tampak peluh telah membasahi wajahnya. Nafasnya memburu, dengan dada berdebar kencang.
“Hentikan pertarungan... Sang Pendeta telah tewas...!” teriak Ki Demong.
Seketika, anak buah Sampuraga yang tersisa langsung menjatuhkan senjata. Dan mereka segera diringkus tokoh-tokoh persilatan yang mengenakan pita merah di lengan.
Sedangkan beberapa tokoh lain segera memapah Pendekar Rajawali Sakti untuk dibawa ke dalam. Karena tadi Rangga bilang kalau dia ingin bersemadi untuk memulihkan tenaganya. Hanya karena tenaganya telah terkuras seluruhnya, untuk berdiri saja rasanya tak mampu...
S E L E S A I
EPISODE BERIKUTNYA: DEWI MAWAR SELATAN