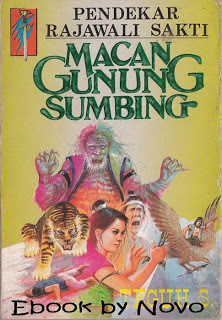Pendekar Rajawali Sakti
Karya Teguh S
MACAN GUNUNG SUMBING
SATU
“Auuum...!”
Suatu auman keras telah memecah keheningan malam. Siapa saja yang mendengar pasti jantungnya bergetar serasa akan copot. Belum lagi hilang suara mengaum itu, mendadak...
“Aaa...!”
Terdengar jeritan melengking yang menyayat hati. Sesaat kemudian, suasana malam menjadi sunyi sepi. Tak terdengar satu suara, kecuali desiran angin malam yang mengusik, membawa embun. Udara malam ini terasa begitu dingin membekukan. Sedangkan suara-suara tadi terdengar bagaikan alunan mimpi buruk yang mengerikan. Hanya sesaat, tapi mampu mencekam seluruh penduduk Desa Weru.
Malam itu terasa begitu lambat berjalan. Fajar seakan-akan enggan menyingsing. Kesunyian menyelimuti seluruh sudut desa yang dipenuhi rumah-rumah penduduk yang terbuat dari kayu dan beratapkan daun-daun rumbia. Pelita-pelita kecil tak sanggup menghalau gelapnya sang malam. Apinya yang redup seperti menari-nari tertiup angin, seakan-akan hendak padam.
Namun kesunyian itu tidaklah menghalangi langkah dua orang berkerudung kain pekat yang melintasi jalan berdebu membelah desa itu. Mereka berjalan cepat-cepat, seperti tengah memburu sesuatu. Namun sesekali mereka menoleh ke belakang. Tampak raut wajah yang pucat terlindung kain yang menutupi kepala dan tubuhnya.
Mereka baru berhenti melangkah setelah tiba di depan sebuah rumah yang tidak begitu besar, namun memiliki halaman luas yang dihiasi rumput dan pepohonan tertata apik. Sesaat mereka saling berpandangan, tapi tidak juga meneruskan langkahnya. Perlahan-lahan dibukanya kain yang menyelubungi kepala mereka.
Dalam keremangan cahaya pelita dan bulan, terlihat wajah agak tua, namun memiliki tatapan mata tajam memancarkan kewibawaan. Sedangkan seorang lagi masih tampak muda. Mungkin usianya sekitar dua puluh lima tahun. Gagang golok menyembul keluar dari balik kain yang belum tersingkap penuh.
“Kau yakin suara itu terdengar dari rumah ini, Argayuda?” tanya laki-laki yang lebih tua. Tatapan matanya tak berkedip ke arah rumah di depannya yang tampak sepi.
“Tidak salah, Ki. Rumahku di sebelah sana...,” laki-laki muda yang dipanggil Argayuda menunjuk rumah kecil tidak jauh dari sini. “Bahkan kulihat, harimau itu keluar dari rumah ini. Tak lama kemudian, seseorang juga melompat keluar sambil membawa buntalan,” jelas Argayuda.
“Baiklah, kau tunggu di sini saja. Aku akan lihat ke dalam,” kata laki-laki tua itu seraya melangkah.
“Ki....”
Argayuda bergegas mengikuti. Laki-laki tua itu terus saja melangkah, tidak menghiraukan panggilan Argayuda. Terpaksa pemuda itu mengikuti dari belakang. Mereka berhenti kembali setelah sampai di depan pintu rumah yang tertutup tak sempurna. Ada sedikit rongga yang cukup untuk mengintip ke dalam. Laki-laki tua itu mendekati pintu, kemudian mendo-rongnya perlahan-lahan. Derit daun pintu terdengar saat terkuak.
“Akh...!” tiba-tiba saja Argayuda memekik perlahan.
“Dewata Yang Agung...,” desis laki-laki tua itu se-raya memalingkan wajahnya ke arah lain.
Apa yang mereka lihat di dalam rumah itu sungguh mengerikan. Tampak seonggok mayat tergeletak di lantai dengan kepala remuk dan tubuh tercabik. Tidak jauh dari mayat itu, terlihat satu mayat lagi yang tergantung seutas tambang ijuk. Tangan dan kakinya buntung. Darah segar masih menetes ke lantai.
Tampak di atas dipan kayu, juga masih terdapat satu mayat lagi. Mayat seorang anak perempuan ber-usia sekitar sembilan tahun. Lebih mengerikan lagi, tubuh mayat itu hampir setengahnya hilang. Tinggal bagian dada ke atas saja yang tersisa.
“Ki..., Ki Gedag...,” suara Argayuda terdengar bergetar.
“Pukul kentongan! Beri tanda kematian,” perintah Ki Gedag, agak bergetar nada suaranya.
“Bb... baik..., baik, Ki,” sahut Argayuda gugup.
Bergegas anak muda itu berlari menuju kentongan yang ada di bagian kanan depan rumah itu. Sesaat kemudian, terdengar kentongan dipukul bertalu-talu yang memiliki nada tersendiri. Suara kentongan itu terdengar menyelusup sampai ke sudut-sudut Desa Weru. Tidak lama kemudian terdengar suara kentongan balasan, yang semakin lama semakin banyak terdengar dari segala penjuru.
Rumah-rumah yang semula remang-remang, kini terang benderang. Dan beberapa orang mulai bermunculan dari dalam rumahnya. Mereka setengah berlari menuju ke rumah yang tertimpa musibah. Terdengar suara langkah-langkah kaki mendekati rumah itu. Begitu tiba, mereka langsung memekik penuh kengerian saat melihat ke dalam. Sementara Argayuda jadi terpaku memegangi kentongan bambu yang tergantung di beranda samping rumah itu.
********************
Wajah mendung terlihat dari orang-orang yang melangkah perlahan meninggalkan areal pekuburan di luar perbatasan Desa Weru. Tampak Ki Gedag masih berdiri di samping gundukan tanah merah. Di sam-pingnya berdiri Argayuda. Kepala mereka tertunduk dalam. Tidak sedikit pun menghiraukan penduduk Desa Weru lainnya yang sudah meninggalkan pusara itu. Empat pusara baru berjajar di depan kedua laki-laki itu.
“Aku tak percaya kalau Macan Gunung Sumbing sampai ke sini,” desah Ki Gedag pelan bernada mengeluh.
“Aku juga tidak percaya, Ki. Tapi benar-benar harimau itu kulihat keluar dari rumah Paman Waku,” tegas Argayuda seraya mengangkat kepalanya. “Hhh..., kasihan Paman Waku. Kalau saja dia tahu keluarganya terbantai begini....”
Ki Gedag menepuk pundak anak muda itu, kemudian mengajaknya berjalan meninggalkan pemakaman. Mereka berjalan perlahan-lahan berdampingan. Sesekali Argayuda menoleh ke belakang, melihat empat pusara yang baru terbentuk sekaligus hari ini.
Kedua laki-laki itu terus berjalan berdampingan tanpa bicara lagi. Langkah mereka pelan tanpa me-noleh sedikit pun, sehingga sampai tidak menyadari ada seorang pemuda duduk di bawah pohon yang sejak tadi memperhatikan mereka ketika keluar dari areal kuburan itu. Seekor kuda hitam pekat dan bertubuh tinggi tegap, terlihat merumput tenang tidak jauh dari pemuda itu.
“Ki...,” agak ragu-ragu nada suara Argayuda.
“Hm...,” gumam Ki Gedag seraya menghentikan langkahnya. Dia menoleh sedikit memandang pemuda yang berjalan di sampingnya itu.
Argayuda ikut berhenti setelah lewat dua langkah di depan Ki Gedag. Pemuda itu berbalik, menghadap pada laki-laki tua dengan gagang golok menyembul di pinggang.
“Ada apa?” tanya Ki Gedag melihat Argayuda nampak ragu-ragu untuk berkata.
“Apa ini tidak ada hubungannya dengan kejadian di Desa Ilir...?” tanya Argayuda ragu-ragu.
“Maksudmu?” Ki Gedag malah balik bertanya.
“Pembunuhan beruntun itu, Ki.”
Ki Gedag terdiam. Tatapan matanya tajam ke arah pemuda itu. Memang bisa dimengerti maksud pembicaraan Argayuda. Sebab, sebulan yang lalu, pernah terjadi peristiwa mengerikan di Desa Ilir. Desa itu memang tidak seberapa jauh letaknya dari Desa Weru ini. Peristiwa yang sangat menggemparkan, dan hampir tidak bisa dipercaya kebenarannya. Beberapa keluarga terbunuh dalam keadaan mengerikan. Tubuh mereka terpotong, tercabik, bahkan banyak yang sudah tidak berbentuk lagi.
Ki Gedag juga tahu kalau mereka yang tewas masih satu darah. Tidak kurang dari dua belas orang tewas. Tidak peduli apakah orang tua, anak muda, atau anak-anak kecil. Bahkan bayi berusia enam bulan pun ikut menjadi korban. Ki Gedag tahu betul dengan keluarga yang terbantai itu.
“Ciri-cirinya sama persis, Ki,” kata Argayuda pelan.
“Terus terang, Argayuda. Aku juga sudah berpikir ke situ. Tapi rasanya tidak ada hubungan keluarga antara Paman Waku dengan mereka yang terbunuh di Desa Ilir. Aku juga belum yakin kalau ini perbuatan si Macan Gunung Sumbing...,” kata-kata Ki Gedag terdengar ragu-ragu.
“Kalau ternyata benar, Ki...?” bergetar juga suara Argayuda.
“Mudah-mudahan saja tidak,” desah Ki Gedag. “Ayo...!”
Kedua laki-laki itu kembali berjalan tanpa bicara lagi. Namun dari kepala yang tertunduk, dapat ditebak kalau mereka masih memikirkan semua yang telah terjadi pada keluarga Paman Waku semalam. Suatu peristiwa yang mengerikan. Pembantaian satu keluarga, tanpa seorang pun dibiarkan hidup.
Sementara itu, di bawah pohon yang cukup rindang, pemuda berwajah tampan dan berbaju rompi putih masih menatap kedua laki-laki yang kini sudah jauh. Kening pemuda itu nampak berkerut dalam dan matanya agak menyipit. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri, dan tangannya menyangga di batang pohon. Pandangannya masih tertuju pada Desa Weru.
“Macan Gunung Sumbing...,” desisnya perlahan.
********************
Suasana duka menyelimuti seluruh Desa Weru. Tidak tergambar wajah-wajah cerah. Kematian satu keluarga Paman Waku membuat hati seluruh penduduk terasa teriris. Terlebih lagi melihat cara kematian yang begitu mengerikan. Hati siapa tidak akan tergiris melihat tubuh terpotong, kepala pecah, darah berceceran di mana-mana. Pembantaian malam itu benar-benar mengguncang seluruh Desa Weru yang selama ini selalu damai dan tenteram.
Di setiap sudut, wajah-wajah mendung selalu terlihat nyata. Demikian juga di sebuah kedai makan yang tidak begitu besar. Tidak banyak orang datang ke situ. Meskipun pemilik kedai selalu tersenyum menyambut tamu, tapi tidak bisa menghilangkan kemurungan wajahnya. Laki-laki tua pemilik kedai itu tersenyum manis menyambut seorang pemuda tampan memakai baju rompi putih yang masuk ke kedainya.
“Pesan apa, Den?” tanya pemilik kedai itu.
“Tuak, dan makanan kecil,” sahut pemuda itu seraya duduk di bangku yang langsung menghadap ke luar lewat jendela.
“Sebentar, Den.”
Laki-laki tua pemilik kedai itu bergegas pergi saat datang lagi seorang laki-laki berwajah aneh dan bertubuh tinggi tegap. Dia langsung duduk di sudut yang agak terlindung. Sempat diliriknya pemuda yang memakai baju rompi putih. Terdengar dengusan pendek.
Sementara pemilik kedai sibuk melayani tamu-tamunya, pemuda berbaju rompi putih itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Perhatiannya langsung terpaku pada salah satu meja di sudut, tempat laki-laki berwajah penuh brewok tebal dengan mata bulat merah duduk di sana. Pada saat yang sama, laki-laki itu juga menatap pemuda berbaju rompi putih itu. Mereka saling pandang beberapa saat, kemudian perhatiannya beralih pada seorang wanita berbaju putih yang bersenjata pedang di punggung. Wanita itu baru saja masuk, dan langsung duduk di tengah-tengah kedai. Dipesannya arak dan beberapa macam makanan.
Pemuda berbaju rompi putih yang duduk dekat jendela, menggapaikan tangannya memanggil pemilik kedai. Laki-laki tua dengan tangan membawa baki, bergegas menghampiri. Tubuhnya setengah membungkuk begitu sampai di depan pemuda itu. Disorongkan tubuhnya lebih ke depan begitu jari telunjuk pemuda berbaju rompi itu bergerak.
“Ada apa, Den?” tanya laki-laki tua pemilik kedai itu
“Apakah mereka penduduk desa ini?” pemuda berbaju rompi putih itu bertanya.
“Siapa?”
“Yang di sudut dan di tengah-tengah itu.”
Pemilik kedai itu menolehkan kepalanya sedikit, kemudian menatap pemuda itu dalam-dalam.
“Mereka juga pendatang seperti Raden,” kata pemilik kedai.
“Terima kasih,” ucap pemuda itu seraya bangkit berdiri.
Pemuda itu meletakkan beberapa keping uang untuk membayar pesanannya, kemudian melangkah ke luar. Matanya sempat melirik dua orang yang sejak tadi diperhatikannya. Laki-laki berwajah penuh brewok dan bermata bulat merah seperti mata kucing itu membalas tajam tatapan pemuda itu. Bibirnya yang hampir tertutup brewok, menyunggingkan senyuman tipis.
Pemuda berbaju rompi putih itu langsung melompat ke atas punggung kuda hitamnya yang tinggi tegap. Otot-otot kuda itu bersembulan, mencerminkan kegagahan dan kejantanan. Suara decakan terdengar, maka kuda hitam itu melangkah perlahan-lahan meninggalkan kedai. Beberapa penduduk yang terlewati sempat memperhatikannya. Namun pemuda itu tetap mengendarai kudanya perlahan-lahan.
Kuda hitam itu berhenti tepat di depan rumah yang tidak begitu besar, namun berhalaman luas dan ditumbuhi rerumputan. Pemuda berbaju rompi putih itu memandang ke arah rumah yang tampak sepi. Pintu depannya terbuka lebar. Pada bagian atas palang pintu terdapat hiasan dari daun kelapa muda. Tidak jauh dari situ terdapat bangunan batu berbentuk puri kecil yang diselubungi kain hitam dan dihiasi rangkaian bunga.
“Ada yang menarik, Den?” tiba-tiba terdengar teguran ramah.
“Oh!” pemuda itu terkejut, dan langsung berpaling.
Seorang laki-laki tua tahu-tahu sudah berdiri di depannya. Di sampingnya tampak seorang pemuda berusia sekitar dua puluh lima tahun. Gagang golok tersembul di pinggang mereka. Pemuda berbaju rompi putih itu turun dari kudanya.
“Baru ada musibah di rumah itu rupanya...,” ujar pemuda itu setengah bergumam.
“Benar,” sahut laki-laki tua yang ternyata adalah Ki Gedag.
“Hm... kalau tidak salah, kau yang berada di dekat kuburan tadi. Benar...?” celetuk pemuda di samping Ki Gedag. Dia tidak lain dari Argayuda.
“Betul sekali. Aku juga sempat melihat upacara pemakaman tadi,” sahut pemuda itu. “Apakah pemilik rumah itu yang meninggal?”
“Benar,” sahut Argayuda. “Kenapa kau tanyakan itu?”
Pemuda berbaju rompi putih menatap Argayuda. Jelas suara Argayuda bernada kecurigaan. Kasarnya, nada itu bersifat menuduh. Tapi pemuda berbaju rompi putih itu malah tersenyum.
“Permisi,” ucap pemuda itu seraya melangkah menuntun kudanya.
Ki Gedag bergeser ke samping memberi jalan. Sedangkan Argayuda tetap berdiri dengan tatapan mata penuh kecurigaan. Kedua laki-laki itu memutar tubuhnya, dan sama-sama memandangi pemuda berbaju rompi putih yang pedangnya tersampir di punggung. Argayuda menggeser kakinya mendekati Ki Gedag.
“Aku jadi curiga, Ki,” bisik Argayuda hampir tidak terdengar.
Ki Gedag tidak menyahut, namun pandangannya tetap tertuju pada pemuda yang berjalan semakin jauh menuntun kudanya. Perlahan dia menoleh memandang Argayuda.
“Jangan cepat menaruh kecurigaan, Argayuda,” ujar Ki Gedag.
“Kecurigaanku beralasan, Ki,” sergah Argayuda.
“Hm...,” Ki Gedag hanya menggumam tidak jelas.
“Pertama dia ada di kuburan. Sekarang ada di sini, lalu menanyakan rumah itu. Apa maksud pertanyaannya tentang orang yang tertimpa musibah ini? Bukankah itu sangat mencurigakan, Ki. Jangan-jangan...,” kata-kata Argayuda terputus.
“Kau sudah mulai menuduh, Argayuda. Tidak baik menuduh orang tanpa bukti,” celetuk Ki Gedag memperingatkan.
“Bukan menuduh, Ki. Tapi kita perlu menyelidiki siapa dia, dan apa keperluannya datang ke Desa Weru ini. Aku merasakan ada sesuatu yang lain, Ki,” kata-kata Argayuda seperti untuk dirinya sendiri.
“Ah! Sudahlah, Argayuda. Sebaiknya kita cepat ke rumah Eyang Ganjur. Paman Waku sudah ada di sana,” sergah Ki Gedag seraya berbalik dan terus melangkah.
Argayuda mengangkat bahunya sedikit, kemudian ikut memutar tubuhnya dan berjalan di samping Ki Gedag. Mereka sempat menoleh ketika tiba di depan kedai. Tampak seorang wanita muda berparas cantik dan memakai baju putih keluar dari dalam kedai itu. Tidak lama kemudian seorang laki-laki berwajah penuh brewok menyusul ke luar. Tapi arah mereka berlawanan. Ki Gedag dan Argayuda terus saja berjalan tanpa berbicara lagi.
********************
DUA
Malam mulai menyelimuti seluruh Desa Weru. Bulan bersinar penuh. Namun awan hitam yang menggantung lebat di langit telah menghalangi cahaya bulan untuk menerangi mayapada ini. Angin bertiup sedikit keras membawa hawa dingin yang menggigilkan. Desa Weru sudah tenggelam terselimut kabut yang semakin menebal. Tak terlihat ada orang di luar rumah, kecuali dua laki-laki yang tengah duduk di beranda.
Mereka adalah Eyang Ganjur bersama cucunya yang bernama Paman Waku. Laki-laki berusia lima puluh tahun itu baru saja tertimpa musibah di saat dirinya sedang melaksanakan tugas ke Bukit Opak membawa pesan kakeknya ini. Walaupun tidak muda lagi, namun masih terlihat gagah dan tegap. Rambutnya memang mulai berwarna dua. Sedangkan Eyang Ganjur sudah demikian lanjut. Usianya mungkin sudah mencapai sembilan puluh tahun lebih. Tapi laki-laki tua itu masih tetap terlihat gagah meskipun tubuhnya kurus tertutup jubah panjang berwarna putih bersih.
“Rasanya aku tidak pernah punya musuh selama dua puluh tahun ini, Eyang. Tapi mengapa ada orang yang begitu tega membantai keluargaku...?” desah Paman Waku lirih.
“Mungkin saja salah seorang lawanmu dulu yang masih menyimpan dendam, Waku,” ujar Eyang Ganjur lembut.
“Ya..., mungkin juga. Tapi siapa...?”
“Memang terlalu mudah untuk menuduh si pelaku, tapi sukar untuk membuktikannya. Masa mudamu kau habiskan dalam dunia persilatan. Tak sedikit orang yang menyimpan dendam di hatinya. Kau tidak akan mampu mengingatnya satu persatu,” kata Eyang Ganjur bijaksana.
“Lalu, apa yang harus kulakukan, Eyang?” tanya Paman Waku meminta pendapat.
“Diam,” sahut Eyang Ganjur mantap.
“Diam...?!” Paman Waku terkejut juga mendengar jawaban itu. Ditatapnya dalam-dalam laki-laki tua yang duduk di seberang meja bundar beralaskan batu pualam putih itu.
Sedangkan yang ditatap hanya diam saja. Pandangannya malah lurus ke depan. Dagunya ditopangkan ke punggung tangan yang menggenggam tongkat berkepala ular.
“Apa yang akan kau lakukan, Waku? Mencari pembunuh keluargamu? Mengumbar amarah dan dendam buta tanpa petunjuk sedikit pun? Kau sudah tidak muda lagi, Waku. Sadarilah keadaan dirimu sendiri,” lembut namun terdengar tegas kata-kata Eyang Ganjur.
Paman Waku hanya diam saja. Dia sendiri tidak tahu, apa yang akan dilakukannya sekarang ini. Sampai saat ini memang belum jelas, siapa pembunuh keluarganya. Meskipun siang tadi Ki Gedag dan Argayuda sudah menceritakan secara jelas, tapi masih belum bisa diyakini kalau yang melakukan semua itu adalah si Macan Gunung Sumbing.
Paman Waku memang pernah bentrok dengan seorang tokoh yang berjuluk Macan Gunung Sumbing. Tokoh itu memang berhasil dikalahkannya. Pertarungan waktu itu memang cukup adil dan disaksikan Eyang Ganjur, kakeknya sendiri yang kini menjadi ketua sebuah padepokan di Bukit Opak. Bahkan istrinya yang saat itu baru dinikahinya ikut menyaksikan, ditambah beberapa tokoh lain yang sulit untuk diingat lagi.
Permasalahannya sangat sepele. Waktu itu Paman Waku menikahi seorang gadis yang juga diinginkan Macan Gunung Sumbing. Macan Gunung Sumbing tidak rela, dan mengajak bertarung sampai salah satu ada yang mati. Tapi Paman Waku tidak berusaha menewaskannya, meskipun saat itu Macan Gunung Sumbing sudah pasrah saat dikalahkan. Paman Waku membiarkannya pergi, hingga sampai sekarang tidak pernah terdengar lagi beritanya.
Dan baru kali ini didengarnya nama Macan Gunung Sumbing disebut, malah kebetulan pula bersamaan dengan terjadinya musibah besar ini. Benarkah yang dilihat Argayuda saat terjadinya pembantaian malam itu? Pertanyaan ini yang selalu mengganggu benak Paman Waku.
“Mungkin yang dikatakan Argayuda benar, Eyang. Rasanya tidak ada lagi yang...,” ucapan Paman Waku terputus.
“Mustahil!” sentak Eyang Ganjur cepat.
“Macan Gunung Sumbing tidak memelihara seekor harimau. Itu hanya sekedar julukan saja. Tidak ingatkah kau sewaktu bertarung dengannya?”
“Tidak akan kulupakan, Eyang.”
“Nah! Apa mungkin Macan Gunung Sumbing memiliki seekor harimau? Bodoh sekali kalau kau termakan omongan bocah kemarin sore itu!” agak keras suara Eyang Ganjur.
“Mungkin hal itu tidak akan kupikirkan kalau saja tidak ada peristiwa serupa sebulan lalu di Desa Ilir, Eyang. Aku kenal betul dengan keluarga yang terbantai habis tanpa sisa itu. Mereka adalah teman-teman baikku, yang juga pernah berurusan dengan si Macan Gunung Sumbing. Demikian pula peristiwa pembantaian yang hampir sama di Gunung Anjar, di Kampung Bulam dan di tempat-tempat lain. Pembantaian satu keluarga. Bahkan sanak familinya pun ikut terbantai dengan cara mengerikan. Dari semua itu Macan Gunung Sumbing selalu disebut-sebut sebagai pelakunya, meskipun sampai saat ini belum terbukti sama sekali,” ujar Paman Waku panjang lebar.
Eyang Ganjur terdiam. Memang benar apa yang dikatakan cucunya barusan. Semua peristiwa itu hampir serupa bentuknya. Brutal dan mengerikan. Dan yang terpenting, korbannya adalah anggota keluarga yang pernah punya urusan dengan si Macan Gunung Sumbing. Kini satu keluarga telah terbantai. Apakah peristiwa-peristiwa itu akan terulang kembali? Kalau memang benar, tidak sedikit yang akan menjadi korban. Masalahnya, hampir semua penduduk Desa Weru ini bertalian darah.
“Aku akan mengirim utusan ke Bukit Opak secepatnya, Eyang,” kata Paman Waku.
“Untuk apa?” tanya Eyang Ganjur.
“Mengabarkan hal ini pada Kakang Bakor. Mereka semua harus waspada sebelum telanjur, Eyang.”
“Belum perlu, Waku. Kita belum bisa mengambil kesimpulan secepat itu.”
“Meskipun Eyang tidak setuju, aku tetap akan memberitahu seluruh sanak keluarga agar waspada. Aku yakin persoalan ini bukan persoalan sepele, Eyang. Ini menyangkut nyawa orang banyak,” tegas kata-kata Paman Waku.
“Pikirkan dulu, Waku,” saran Eyang Ganjur.
“Sudah!” sahut Paman Waku mantap.
“Hhh...!” Eyang Ganjur menarik napas panjang.
********************
Malam terus merayap semakin larut. Udara pun semakin dingin menusuk kulit. Di dalam sebuah kamar berdinding bilik bambu, terlihat sepasang insan tengah mereguk kenikmatan. Tak ada yang terdengar selain dengus napas memburu disertai erangan lirih mengusik telinga. Mereka adalah pasangan muda yang baru melangsungkan pernikahan beberapa hari.
“Oh! Kakang...!” terdengar pekikan lirih tertahan.
“Ahhh...!” disusul satu desahan panjang.
Satu tubuh menggelimpang ke samping bermandikan keringat yang mengucur deras, berkilat tertimpa cahaya pelita yang menempel di dinding. Sebuah kepala dengan rambut terurai kusut menyembul terangkat naik. Terdengar bunyi suara gemerisik dari kain yang dililitkan ke tubuh ramping berkulit kuning langsat.
“Mau ke mana?” sapa laki-laki muda yang masih menggeletak bersimbah keringat. Tangannya menjulur memeluk pinggang istrinya.
“Ambil air,” sahut wanita itu seraya mengecup pipi suaminya.
“Jangan lama-lama, di luar gelap.”
“He-eh.”
Wanita itu beranjak turun dari pembaringan. Terdengar bunyi bergerik. Sebentar wanita itu menoleh dan memberikan senyum menawan, kemudian jalan melenggang. Tubuhnya hanya dililit selembar kain. Dia melangkah keluar dari kamar, dan terus melintasi satu ruangan.
Tangannya yang kecil dan halus, mengangkat palang pintu. Dibukanya pintu itu perlahan-lahan, namun masih juga terdengar suara bergerit. Angin malam yang dingin langsung menerpa kulit wajahnya. Wanita itu membungkuk mengambil tempayan air dari tanah liat. Dan pada saat berdiri tegak...
“Akh...!” wanita itu memekik kaget agak tertahan.
Seketika wajahnya pucat pasi, dan matanya membeliak lebar. Tubuhnya bergetar hebat, sehingga tempayan itu jatuh dan pecah di ujung kakinya. Belum lagi wanita itu bisa bersuara, mendadak satu bayangan besar berkelebat disertai auman keras menggetarkan.
“Aaaum...!”
“Aaa...!”
Satu jeritan melengking terdengar. Tubuh wanita itu terguling ke lantai. Hanya sesaat jeritan melengking itu terdengar, kemudian tidak terdengar lagi suara dari bibir wanita itu.
“Senah...!”
Jeritan melengking itu membuat laki-laki yang berada di dalam kamar kontan memburu keluar. Betapa terkesiap hatinya begitu melihat pemandangan yang mengerikan sekali. Tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya pucat pasi seketika. Tapi segera disambarnya golok yang menggantung di dinding di sampingnya.
Sret! Baru saja dicabut goloknya, mendadak satu bayangan berkelebat cepat mengarah padanya. Sejenak dia terkesiap, dan buru-buru melompat ke samping sambil menjatuhkan tubuhnya bergulingan di lantai. Tapi mendadak saja bayangan itu berbalik dan langsung menerjangnya demikian kuat.
“Akh!” laki-laki muda itu memekik tertahan.
Dan belum lagi menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba terasa ada beberapa tusukan benda kecil mengoyak dadanya. Itu pun masih disusul suatu hentakan keras pada kepalanya ke lantai.
“Aaa...!” laki-laki itu menjerit melengking tinggi.
Jeritan yang begitu keras menyayat, membelah keheningan malam yang dingin ini. Sesaat kemudian keadaan menjadi sunyi sepi kembali, namun masih tampak dua bayangan berkelebat cepat keluar dari bagian belakang rumah itu. Mereka meninggalkan dua sosok tubuh yang koyak tak berbentuk lagi. Kepala laki-laki muda itu hancur. Leher dan dadanya berlubang besar. Sedangkan yang wanita lebih mengerikan lagi. Sebagian besar tubuhnya hilang. Yang ada tinggal kepala, sebagian dada, sebelah tangan, dan potongan perut yang tercecer. Darah menggenangi lantai.
“Grauuugh...!” terdengar raungan panjang yang semakin lama semakin mengecil, lalu hilang sama sekali.
Sementara malam terus merambat semakin larut. Tak ada seorang pun yang menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Memang begitu cepat terjadi, dan sukar sekali dipahami.
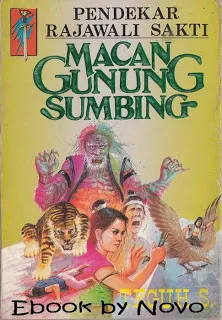
Paman Waku tidak sanggup lagi melihat, dan langsung melangkah keluar. Wajahnya merah padam menahan geram. Betapa tidak? Wanita yang tewas bersama suaminya itu adalah keponakannya yang baru beberapa hari melangsungkan pernikahan. Rumah yang kecil dengan halaman tidak seberapa besar itu kini dipadati penduduk yang berdatangan ingin melihat.
Semua orang yang melihat pasti akan mendesis kengerian. Hanya murid-murid Eyang Ganjur yang mampu bertahan lama. Itu pun terpaksa karena mendapat perintah gurunya untuk mengurus mayat-mayat itu. Sementara Paman Waku sendiri tidak sanggup lagi menyaksikannya. Eyang Ganjur yang semula berada di dalam mengawasi muridnya yang berjumlah empat orang, melangkah ke luar begitu melihat cucunya ke luar dengan wajah merah padam menahan geram.
“Waku...,” panggil Eyang Ganjur begitu berada di samping cucunya.
“Eyang masih juga berdiam diri?!” dengus Paman Waku langsung menyelak.
“Tahan amarahmu, Waku. Bisa kurasakan apa yang kau rasakan sekarang. Kau pikir aku...,” Eyang Ganjur mendesah panjang seraya mengangkat kepalanya sedikit ke atas. “Hhh...! Tidak seharusnya aku kasar padamu, Waku.”
“Maafkan aku, Eyang. Aku terbawa kata hatiku,” ucap Paman Waku perlahan.
“Ah, sudahlah.”
Kakek dan cucu itu terdiam. Saat itu Ki Gedag dan Argayuda muncul dan langsung menghampiri. Mereka baru saja keluar dari dalam rumah duka. Eyang Ganjur menoleh pada kedua orang itu. Sesaat mereka hanya berdiam diri saja dengan sinar mata yang sulit diartikan.
“Eyang, bukannya aku hendak menambah keruh suasana. Tapi sejak tadi kuperhatikan ada tiga orang yang....”
“Di mana?” sentak Paman Waku langsung memotong ucapan Argayuda.
“Mereka sendiri-sendiri. Yang dua orang memang sudah tidak terlihat. Tapi yang seorang masih ada di bawah pohon kenanga. Itu, di samping kuda hitamnya,” sahut Argayuda menunjuk dengan ekor matanya.
Paman Waku dan Eyang Ganjur langsung mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Argayuda. Di bawah pohon kenanga memang terlihat seorang pemuda berwajah tampan memakai baju rompi putih. Sebilah gagang pedang berbentuk kepala burung, tersembul dari balik punggungnya. Seekor kuda tegap berwarna hitam pekat tengah merumput di sampingnya.
“Waku...,” Eyang Ganjur menangkap tangan cucunya yang hendak melangkah menghampiri pemuda itu.
Paman Waku menatap kakeknya tajam.
“Apa yang akan kau lakukan?” tanya Eyang Ganjur.
“Hanya ingin bertanya saja, Eyang,” sahut Paman Waku.
“Hatimu sedang panas! Biar aku saja,” ujar Eyang Ganjur.
Semula Paman Waku akan membantah, tapi Eyang Ganjur sudah melangkah begitu melepaskan cekalannya. Ki Gedag menghampiri Paman Waku dan berdiri di samping kanannya. Mereka memperhatikan Eyang Ganjur yang menghampiri pemuda berbaju rompi putih itu.
Eyang Ganjur memberi salam ramah begitu sampai di depan pemuda itu, yang kemudian langsung disambut ramah pula. Sejenak Eyang Ganjur memperhatikan pemuda itu dari ujung rambut hingga ke ujung kaki
“Maaf, boleh aku tahu siapa Kisanak ini?” tanya Eyang Ganjur ramah.
“Apakah kehadiranku mengganggu, Eyang?” pemuda itu malah balik bertanya. Dia langsung memanggil Eyang karena melihat laki-laki itu usianya sudah lanjut dan memakai jubah putih bagai seorang pertapa.
“Oh, bukan begitu maksudku. Hanya saja, aku harus tahu setiap orang asing yang berada di desa ini,” sahut Eyang Ganjur.
“Namaku Rangga. Aku memang sedang singgah di sini dalam perjalananku,” jelas pemuda itu memperkenalkan diri.
“Kau seorang pengembara?” tanya Eyang Ganjur lagi.
“Benar, Eyang.”
“Hm.... Begini Kisanak. Bukannya aku tidak suka akan kehadiranmu di sini. Tapi demi kebaikanmu, sebaiknya segeralah pergi setelah istirahatmu selesai,” lembut dan sopan kata-kata Eyang Ganjur, namun bernada tegas penuh kewibawaan.
“Oh...! Kenapa?” tanya Rangga agak terkejut juga.
“Sayang sekali tidak bisa kujelaskan. Yang jelas, terlalu berbahaya bagimu berada di sini terlalu lama. Bukan hanya dirimu, tapi juga bagi semua orang asing. Desa ini terpaksa kututup dari kunjungan orang luar. Kuharap, kau bisa memakluminya, Kisanak,” kata Eyang Ganjur tetap ramah.
“Baiklah, aku akan pergi sekarang,” kata Rangga mengalah.
“Aku ucapkan terima kasih atas pengertianmu, Kisanak,” ucap Eyang Ganjur.
“Tidak mengapa, Eyang. Aku bisa mengerti.”
Rangga berbalik dan melangkah pergi seraya menuntun kudanya. Eyang Ganjur masih berdiri memandang kepergian pemuda yang lebih dikenal berjuluk Pendekar Rajawali Sakti itu. Eyang Ganjur masih menatap kepergian Rangga, sehingga tidak menyadari kalau Paman Waku, Ki Gedag, dan Argayuda sudah berdiri di sampingnya. Laki-laki tua itu menarik napas panjang setelah mengetahui kehadiran ketiga orang itu.
“Apa yang Eyang katakan padanya?” tanya Paman Waku seraya menatap punggung Rangga yang semakin jauh berjalan.
“Hanya meminta pengertiannya,” sahut Eyang Ganjur tanpa berpaling. “Hhh...! Pemuda yang sopan."
“Eyang tidak menanyakan maksud kedatangannya ke sini?” desak Paman Waku.
“Dia hanya singgah sebentar. Ah! Sudahlah, Waku. Tidak pantas mencurigai orang yang begitu sopan dan bersedia mengerti tanpa harus dijelaskan lebih banyak.”
“Eyang, sejak kemarin dia ada di sini,” celetuk Argayuda.
“Argayuda!” sentak Ki Gedag.
Tapi Paman Waku sudah menanggapinya dengan serius. “Menginap di mana dia, Argayuda?” tanya Paman Waku.
“Aku tidak tahu. Tapi, dia selalu muncul setiap ada korban jatuh,” sahut Argayuda tidak menghiraukan delikan mata Ki Gedag. “Bahkan juga muncul di kuburan, menatap rumah Paman, dan menanyakan....”
“Argayuda!” sentak Ki Gedag memotong ucapan pemuda itu. “Jangan tanggapi kata-kata cucuku, Paman Waku. Argayuda sendiri sedang tegang,” sambung Ki Gedag melihat tatapan tajam Paman Waku.
Paman Waku semakin tajam menatap laki-laki setengah baya itu. Sedangkan Argayuda jadi kikuk. Argayuda tidak menolak ketika Ki Gedag menariknya dan membawanya pergi. Sedangkan Paman Waku kelihatan tidak puas terhadap sikap Ki Gedag.
“Keterlaluan kau, Argayuda!” rungut Ki Gedag setelah cukup jauh.
“Aku mengatakan yang sebenarnya, Ki,” bela Argayuda.
“Itu namanya membuat keruh suasana. Berapa kali kukatakan, jangan banyak bicara di depan Paman Waku. Kalau terjadi apa-apa, kau bersedia bertanggung jawab? Bisa-bisa malah kau sendiri yang dicurigai kalau ternyata pemuda itu tidak bersalah!” dengus Ki Gedag menggerutu menyesali kecerobohan cucunya itu.
“Tapi, Ki....”
“Sudah!” bentak Ki Gedag.
Argayuda langsung diam. Mereka terus melangkah pergi tanpa bicara lagi. Ki Gedag benar-benar menyesali kelancangan cucunya ini. Dia tahu persis watak Paman Waku yang mudah bangkit amarahnya. Terlebih lagi, pada saat-saat seperti ini. Argayuda memang masih terlalu muda dan tidak bisa berpikir panjang. Darah muda yang selalu menuruti kata hati tanpa mengenal kompromi.
********************
TIGA
Kuda hitam pekat itu melangkah perlahan. Ayunan kakinya begitu teratur seperti tahu keinginan majikannya. Di punggungnya duduk seorang pemuda berwajah tampan dan berkulit kuning langsat. Baju rompi putih yang bagian dadanya terbuka lebar, meriap dipermainkan angin senja. Rambutnya hitam panjang tergelung ke atas. Sebagian meriap melambai-lambai mengikuti irama derap langkah kaki kuda itu.
“Berhenti...!” tiba-tiba terdengar bentakan keras.
Belum lagi hilang suara bentakan itu, mendadak di depan muncul seorang gadis cantik. Bajunya putih ketat, dan pedangnya tersampir di punggung. Gadis itu berdiri bertolak pinggang sambil menatap tajam. Pemuda di atas punggung kuda hitam itu langsung menghentikan langkah kudanya, dan tetap duduk dengan sikap tenang.
“Nisanak, apa maksudmu menghalangi jalanku?” tanya pemuda itu sopan dan lembut.
“Jangan berlagak bodoh, Pendekar Rajawali Sakti! Apa maksudmu datang ke Desa Weru!” dengus wanita itu ketus.
“He...! Kau tahu namaku...?!” pemuda yang berada di punggung kuda hitam itu terkejut, karena wanita itu tahu nama julukannya. Pemuda itu memang Pendekar Rajawali Sakti yang bernama asli Rangga.
“Hhh! Hanya orang bodoh saja yang tidak tahu siapa dirimu!” kembali wanita itu mendengus.
“Nisanak, aku tidak kenal dirimu. Dan rasanya di antara kita tidak pernah ada persoalan apa-apa. Kenapa kau menghadang jalanku dengan sikap permusuhan?” Rangga mencoba lembut.
“Di antara kita memang belum pernah punya persoalan. Aku hanya ingin memberi peringatan saja padamu, Pendekar Rajawali Sakti!” tetap ketus nada suara wanita itu.
“Peringatan? Peringatan apa, Nisanak? Hm..., kalau boleh tahu, siapa namamu?” Rangga masih tetap lembut meskipun wanita itu tetap ketus.
“Mungkin kau sudah mendengar julukan Bidadari Pencabut Nyawa! Itulah diriku. Dewi Tanjung atau si Bidadari Pencabut Nyawa. Jelas...!?”
“Hm...,” Rangga menggumam pelan. Sama sekali belum pernah didengar nama wanita itu.
Pendekar Rajawali Sakti melompat turun dari punggung kudanya. Dilangkahkan kakinya dua tindak ke depan, dan dibiarkan kuda hitamnya melenggang ke tepi, mendekati segerumbul rumput hijau yang subur di bawah pohon kamboja.
“Kuperingatkan sekali lagi, Pendekar Rajawali Sakti. Tinggalkan segera Desa Weru, atau kau berhadapan denganku!” dingin nada suara Dewi Tanjung.
“Ha ha ha...!” Rangga tidak dapat lagi menahan tawanya. Seketika itu juga tawanya meledak mendengar peringatan wanita yang mengaku bernama Dewi Tanjung atau berjuluk Bidadari Pencabut Nyawa. Memang satu hari ini sudah dua orang memperingatkannya untuk pergi dari Desa Weru. Hatinya benar-benar terasa tergelitik, sehingga tidak bisa menahan tawanya.
“Diam! Tidak lucu...!” merah padam wajah Dewi Tanjung..
Rangga langsung diam, tapi bibirnya tetap menyunggingkan senyum menahan tawa. Sedangkan Dewi Tanjung semakin merah wajahnya. Dirasakan kalau Rangga telah meremehkan peringatannya.
“Aku tidak main-main, Pendekar Rajawali Sakti! Aku tidak ingin melihat mukamu lagi di desa ini!” tegas kata-kata Dewi Tanjung.
“Baik, aku akan pergi secepatnya. Tapi tolong jelaskan, mengapa kau menginginkan aku pergi dari Desa Weru?”
“Kau tidak perlu tahu, Kisanak!” dengus Dewi Tanjung ketus.
“Kalau aku mencari tahu sendiri?”
“Heh...?!” Dewi Tanjung terkejut setengah mati.
Rangga mengangkat bahunya, kemudian melangkah ringan mendekati kudanya. Ditepuk-tepuknya leher kuda hitam yang bernama Dewa Bayu itu. Kemudian dia duduk di atas akar pohon yang menyembul dari dalam tanah. Sebatang rumput dicabut, kemudian diselipkan di sudut bibirnya.
Dewi Tanjung semakin geram melihat sikap Pendekar Rajawali Sakti itu. Dengan ujung jari kakinya dikutiknya sebatang ranting kering, lalu disentilnya ke arah Pendekar Rajawali Sakti. Sentilan yang mengandung pengerahan tenaga dalam itu sungguh luar biasa. Ranting kering itu meluruk deras bagai sebatang anak panah lepas dari busur.
“Uts!”
Rangga mengegoskan kepalanya sedikit ke samping. Ranting kering yang rapuh itu menancap sampai setengahnya di batang pohon di belakang Pendekar Rajawali Sakti. Rangga berdecak kagum melihat tenaga dalam yang dimiliki gadis itu. Memang boleh juga. Ranting kering yang rapuh itu bagai sebatang baja kuat, dan sanggup menembus batang kayu yang cukup besar dan kokoh.
“Sudahlah, Nini Dewi. Aku tidak ada waktu bermain-main denganmu,” ujar Rangga sengit.
“Aku tidak minta kau bermain denganku, yang kuminta, enyahlah dari sini!” dengus Dewi Tanjung.
Rangga bangkit berdiri. Sebentar ditatapnya gadis berbaju putih itu. Meskipun masih kesal, tapi dia melompat juga ke punggung kudanya. Rangga benar-benar tidak ingin berurusan dengan gadis yang begitu galak. Dia berdecak dan menghentakkan tali kekang kudanya. Dewa Bayu segera melenggang setelah meringkik satu kali.
Dewi Tanjung memandangi kepergian Rangga. Bibirnya menyunggingkan senyuman tipis karena berhasil mengusir Pendekar Rajawali Sakti. Bidadari Pencabut Nyawa itu masih berdiri tegak meskipun Rangga sudah jauh, dan menghilang di dalam hutan, tubuhnya baru berbalik setelah bayangan Pendekar Rajawali Sakti itu tidak terlihat lagi. Namun baru saja berbalik, mendadak sebuah bayangan melesat.
“Kau...!?” Dewi Tanjung terkesiap begitu melihat jelas bayangan itu.
Dan belum lagi hilang rasa terkejutnya, bayangan itu sudah kembali melesat menerjangnya. Dewi Tanjung langsung melentingkan tubuhnya ke belakang, dan berputaran beberapa kali di udara. Namun sosok bayangan itu terus mencecarnya, dan tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk bernapas.
“Hiyaaat...!”
Sambil berteriak nyaring, Dewi Tanjung melentingkan tubuhnya ke atas. Dengan manis sekali kakinya hinggap di atas dahan pohon yang cukup tinggi. Sepasang bola matanya yang bulat bening, membeliak mendapati sesosok tubuh menyeramkan berdiri di bawah pohon itu.
“Ha ha ha...!” tiba-tiba terdengar tawa menggelegar.
“Huh!” Dewi Tanjung mendengus berat.
Dewi Tanjung meluruk turun. Begitu kakinya menjejak tanah, muncul seorang laki-laki tinggi tegap penuh brewok. Laki-laki itu menghampiri seekor harimau sebesar anak kerbau yang tadi sempat menyerang Dewi Tanjung. Binatang buas itu mendekam sambil menggerung-gerung perlahan.
“He he he...! Hebat...! Hebat, kau bisa mengusir Pendekar Rajawali Sakti tanpa mengadu tenaga. He he he...!” laki-laki itu memuji sambil terkekeh.
“Aku tidak perlu pujianmu, Macan Gunung Sumbing! Aku datang ke sini untuk membuat perhitungan denganmu!” dengus Dewi Tanjung ketus.
“Perhitungan...? Ha ha ha...!” Laki-laki yang wajahnya penuh brewok itu tertawa terbahak-bahak. Perutnya yang sedikit buncit terguncang-guncang.
Dewi Tanjung menggeram melihat tingkah manusia seperti harimau itu. Wajahnya memang hampir menyerupai harimau peliharaannya itu. Matanya bulat merah, dan seluruh mukanya hampir tertutup brewok lebat. Kuku jari-jari tangannya runcing dan berwarna hitam. Lengannya kokoh dan dihiasi bulu tebal. Perawakan Macan Gunung Sumbing memang sungguh menyeramkan, membuat siapa saja yang melihatnya bakal merinding ketakutan!
“Ghraugh...!” harimau itu menggerung seraya membuka mulutnya lebar-lebar.
Tampak barisan giginya yang tajam bertaring. Seluruh mulutnya berwarna merah darah. Tatapan matanya begitu tajam menusuk ke arah Bidadari Pencabut Nyawa. Tapi dia tetap mendekam di samping si Macan Gunung Sumbing.
“Telah lama kutunggu kesempatan ini, Macan Gu-nung Sumbing! Sekarang saatnya menagih hutang padamu!” dingin sekali nada suara Dewi Tanjung.
“Dewi Tanjung! Apakah kau sudah punya nyawa rangkap sehingga berani menantangku, heh?! Dengar, bocah! Aku tidak pernah punya hutang nyawa pada siapa pun juga. Kalau aku membunuh, itu karena mereka patut dibunuh!” keras suara Macan Gunung Sumbing.
“Dan aku akan membunuhmu, karena kau juga patut dibunuh!” sambut Dewi Tanjung dingin.
“Bocah setan! Rupanya kau benar-benar cari mampus, heh?!” geram Macan Gunung Sumbing.
“Kita lihat, siapa di antara kita yang lebih dahulu ke neraka!” tantang Dewi Tanjung tegas.
“Phuih! Baru kali ini aku ditantang bocah ingusan!” dengus Macan Gunung Sumbing sinis.
“Tantanganku yang akan mengirimmu ke neraka, Macan Gunung Sumbing!”
“Bocah gendeng! Kupatahkan batang lehermu. Hiyaaat...!” Mendapat tantangan terbuka itu, Macan Gunung Sumbing tidak bisa lagi menahan luapan amarahnya.
Cepat sekali tubuhnya melompat sambil menjulurkan tangannya ke depan. Kuku-kukunya yang hitam runcing, mengembang siap mengoyak tubuh indah Bidadari Pencabut Nyawa. Namun terjangan yang cepat itu manis sekali dielakkan wanita itu. Dewi Tanjung menggeser kakinya ke kanan sambil memiringkan tubuhnya sedikit. Dan dengan kecepatan kilat, dilayangkan tendangan ke arah perut Macan Gunung Sumbing.
“Phuah!”
Macan Gunung Sumbing menyumpah serapah. Buru-buru ditarik tubuhnya ke belakang, sehingga tendangan bertenaga dalam cukup tinggi itu luput dari sasaran. Laki-laki berwajah mirip harimau itu kembali menyerang ganas. Kedua tangannya selalu merentang dan jari-jarinya terbuka lebar. Kebutan tangannya begitu cepat dan kuat. Angin kebutannya mengandung hawa panas yang menyengat.
Dewi Tanjung menyadari betul kalau saat ini tengah berhadapan dengan tokoh sakti yang berkepandaian tinggi dan sukar dicari tandingannya. Wanita itu berkelit dan berlompatan menghindari setiap serangan yang datang sambil sesekali mengirimkan serangan balasan. Bidadari Pencabut Nyawa itu juga tidak tanggung-tanggung lagi, langsung dipergunakanlah jurus-jurus yang dahsyat dan diandalkan. Pertarungan terus berlangsung semakin sengit. Masing-masing berusaha untuk merobohkan lawannya. Tidak terasa, mereka sudah mengeluarkan sepuluh jurus.
Namun pertarungan nampaknya masih terus berlangsung. Tempat di sekitar pertarungan itu sudah tidak karuan lagi. Porak-poranda bagai diterjang amukan dua manusia raksasa. Pohon-pohon besar dan kecil bertumbangan. Batu-batu pecah berantakan. Debu mengepul di udara, menambah pekatnya suasana. Namun pertarungan masih saja berlangsung. Bahkan semakin sengit.
“Yeaaah...!”
Tiba-tiba saja Macan Gunung Sumbing berteriak keras. Dan tahu-tahu tubuhnya sudah berputar cepat mengelilingi Dewi Tanjung. Sesaat Bidadari Pencabut Nyawa itu jadi kelabakan, karena tidak tahu lagi di mana lawannya berada. Yang terlihat hanya bayangan berkelebat cepat mengelilingi tubuhnya. Dan belum lagi gadis itu menyadari apa yang terjadi, tahu-tahu Macan Gunung Sumbing melepaskan satu pukulan keras yang tidak terduga sama sekali.
“Akh...!” Dewi Tanjung memekik keras tertahan.
Tubuhnya limbung terhuyung-huyung. Satu pukulan keras bertenaga dalam sangat tinggi berhasil mendarat di punggungnya. Dan selagi tubuhnya terhuyung, kembali Macan Gunung Sumbing melepaskan satu pukulan disertai teriakan menggelegar.
“Hiyaaa...!”
“Aaakh...!”
Pukulan itu tidak bisa dielakkan lagi. Dewi Tanjung memekik keras, dan tubuhnya terlontar sejauh beberapa tombak. Dua batang pohon langsung hancur berantakan terlanda tubuh ramping gadis itu. Namun Dewi Tanjung masih berusaha bangkit berdiri. Pukulan Macan Gunung Sumbing yang telah menghantam dadanya, membuatnya jadi sukar bernapas. Dan selagi mencoba bangkit berdiri, darah segar termuntahkan dari mulutnya.
“Ha ha ha...!” Macan Gunung Sumbing tertawa terbahak-bahak.
“Setan...!” dengus Dewi Tanjung menggeram.
Cepat Bidadari Pencabut Nyawa itu menggerak-gerakkan tangannya di depan dada, kemudian mencabut pedangnya. Sret...! Pedang berwarna hitam pekat itu telah tergenggam erat di tangan kanan, melintang di depan dada. Disekanya darah yang masih tersisa di mulut dengan punggung tangan kiri. Sepasang bola matanya menatap tajam penuh kemarahan.
“Ghraugh...!” tiba-tiba harimau yang sejak tadi mendekam diam, bangkit berdiri sambil menggerung keras.
“He he he.... Rupanya kau ingin mendapat bagian juga, Belang. Baiklah! Aku serahkan dia untukmu,” ujar Macan Gunung Sumbing terkekeh.
“Phuih!” Dewi Tanjung menyemburkan ludahnya.
Bidadari Pencabut Nyawa itu menggeser kakinya ke samping beberapa langkah. Sedangkan Macan Gunung Sumbing melangkah mundur, memberi kesempatan harimau peliharaannya untuk maju. Dari bibirnya yang tipis tertutup brewok, masih terdengar tawa terkekeh. Sementara Dewi Tanjung kembali menggeser kakinya. Pandangannya tajam tertuju pada binatang buas sebesar anak kerbau itu.
“Auuum...!” Harimau itu mengaum keras.
Dan belum lagi hilang suara aumannya, binatang buas itu sudah melompat cepat menerkam. Dewi Tanjung melompat ke samping sambil membabatkan pedangnya ke tubuh binatang mengerikan itu. Tapi sungguh di luar dugaan, ternyata binatang itu mampu berkelit dengan memutar tubuhnya di udara. Tebasan Dewi Tanjung hanya mengenai angin. Dan secepat itu pula, harimau belang itu berbalik. Langsung diterkamnya kembali tubuh ramping itu dengan kecepatan yang sukar diikuti mata biasa.
“Haaait..!”
Dewi Tanjung melompat ke belakang seraya mengibaskan pedangnya. Tapi harimau itu tetap maju menerjang, dan....
Dug!
“Heh...!”
“Ha ha ha...!”
Dewi Tanjung terkejut bukan main begitu pedangnya membabat bagian perut harimau sebesar anak kerbau itu. Rasanya seperti menghantam sekarung kapuk saja. Pedangnya terpental balik, sedangkan harimau itu tidak mengalami luka sedikit pun. Dewi Tanjung bergegas melompat mundur. Diperiksa mata pedangnya, ternyata tak ada yang gompal. Kemudian, dipandangi tajam-tajam harimau yang menggerung-gerung memamerkan taringnya.
“Gila! Binatang apa ini...?” dengus Dewi Tanjung.
“Graugh...!” harimau itu menggeram.
Binatang itu merendahkan tubuhnya sedikit, dan tiba-tiba melompat hendak menerkam Dewi Tanjung. Sesaat, Bidadari Pencabut Nyawa itu terperangah, sehingga tidak sempat lagi menghindar. Namun pada saat yang sangat kritis, mendadak sebuah bayangan putih berkelebat menghajar harimau itu.
“Grrraaaugh...!” harimau itu meraung keras.
Tubuh binatang itu terpental cukup jauh ke belakang, menghantam sebongkah batu hingga hancur berantakan. Sebelum ada yang sempat menyadari, bayangan putih itu sudah berkelebat lagi. Langsung saja disambarnya tubuh Dewi Tanjung, dan seketika itu juga lenyap tak berbekas.
“Setan keparat....!” geram Macan Gunung Sumbing begitu tersadar.
Tapi Dewi Tanjung sudah lenyap, bersama lenyapnya bayangan putih itu. Macan Gunung Sumbing menggerutu dan memaki-maki geram. Sedangkan harimau belang yang sangat besar itu menggerung-gerung sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia melangkah menghampiri si Macan Gunung Sumbing, lalu mendekam di depan laki-laki berwajah kasar penuh brewok itu. Geramannya terdengar lirih, dan kepalanya terkulai rata dengan tanah.
“Bukan hanya kau yang kecewa, Belang. Huh! Siapa pun orangnya yang berani usil, akan kurobek-robek tubuhnya!” dengus Macan Gunung Sumbing geram.
“Grrr...!” Harimau itu menggerung pelan, seakan menyetujui ucapan majikannya.
“Ayo, Belang. Masih banyak yang harus dikerjakan,” ajak Macan Gunung Sumbing.
Harimau itu bangkit berdiri dan melangkah lenggang mengikuti Macan Gunung Sumbing. Sepertinya mereka melangkah biasa saja, tapi kecepatannya melebihi orang berlari sekuat tenaga. Bahkan sebentar saja sudah lenyap tertelan lebatnya pepohonan di sekitar perbatasan utara Desa Weru.
Saat itu, tidak berapa jauh dari tempat pertarungan tadi, tampak Dewi Tanjung bergulir jatuh bergelimpangan di tanah. Tidak jauh darinya berdiri seorang pemuda berwajah tampan. Baju rompi putihnya berkibar-kibar tertiup angin. Dewi Tanjung bergegas bangkit berdiri. Dikibaskan debu yang melekat di bajunya, kemudian dimasukkan pedangnya kembali ke dalam sarungnya di punggung. Tatapannya langsung tertuju pada pemuda tampan yang menolongnya dari maut.
“Huh! Kau lagi...!” rungut Dewi Tanjung begitu mengenali pemuda itu. Memang dewa penolongnya itu tidak lain dari Rangga si Pendekar Rajawali Sakti.
“Kenapa kau sampai bentrok dengan Macan Gunung Sumbing?” tanya Rangga tidak menghiraukan gerutuan gadis itu.
“Bukan urusanmu!” dengus Dewi Tanjung seraya melangkah ingin pergi.
“Hey...! Tunggu...!” Rangga melompat, dan tahu-tahu sudah berdiri menghadang.
“Terima kasih atas pertolonganmu,” ucap Dewi Tanjung ketus.
“Bukan itu yang kuinginkan,” kata Rangga.
“Oh..., jadi kau meminta imbalan?” sinis sekali nada suara Dewi Tanjung.
Rangga mendengus kesal juga terhadap sikap ketus gadis ini, tapi masih bisa ditahan kekesalannya. Dia hanya ingin tahu, kenapa gadis ini bisa bentrok dengan Macan Gunung Sumbing. Sementara hampir seluruh penduduk Desa Weru sedang dicekam perasaan takut. Dan tidak jarang mereka menyebut-nyebut nama Macan Gunung Sumbing sebagai pelaku utama pembantaian di Desa Weru.
Bukannya ingin tahu urusan orang lain, tapi Rangga merasa perlu ikut campur. Apalagi dia pernah bentrok dengan Macan Gunung Sumbing. Rangga tahu betul kalau tokoh sakti itu sukar ditandingi. Terutama binatang peliharaannya yang sangat kebal dan kuat luar biasa. Sepertinya memang bukan harimau sungguhan. Rangga juga sempat mendengar beberapa pembicaraan yang membuatnya harus berpikir keras mencari kebenaran. Kalau saja apa yang didengar dari beberapa penduduk Desa Weru itu benar, sudah menjadi kewajibannya untuk menghentikan sepak terjang Macan Gunung Sumbing. Dan tadi, Macan Gunung Sumbing hampir menewaskan seorang gadis yang ketus, angkuh, dan keras kepala.
“Tunggu apa lagi? Imbalan apa yang kau inginkan?” sinis nada suara Dewi Tanjung.
“Pergilah!” dengus Rangga jadi muak.
“Ha ha ha...!” Dewi Tanjung tertawa terbahak-bahak melihat wajah Pendekar Rajawali Sakti itu jadi bersemu merah.
Gadis itu memang sengaja membuka sedikit bagian atas dadanya, sehingga tampak sedikit dua bukit kembar yang putih dan mulus. Sambil memperdengarkan suara tawanya, gadis itu cepat melangkah pergi.
Rangga bersungut-sungut sendirian. “Dasar...!”
********************
EMPAT
Dewi Tanjung tampak gelisah. Beberapa kali tubuhnya menggelimpang di atas pembaringan kamar penginapan ini. Sebentar bangkit duduk, kemudian menghenyakkan lagi tubuhnya. Sementara malam terus beranjak semakin larut. Keheningan menyelimuti seluruh Desa Weru ini. Desahan panjang terdengar diiringi bangkitnya tubuh ramping dari pembaringan.
“Huh! Kenapa dia tidak mau hilang dari bayanganku...?” gerutu Dewi Tanjung.
Gadis itu melangkah menghampiri jendela yang masih terbuka lebar. Sebentar memandang ke luar, tapi hanya kegelapan yang terlihat. Perlahan tangannya menutup jendela itu, lalu berbalik seraya menghembuskan napas panjang. Terasa berat hembusan napasnya. Kembali kakinya terayun menghampiri pembaringan yang beralas kain merah muda, lalu duduk di tepinya.
“Rangga.... Hhh...!” Dewi Tanjung mendesah pelan menyebut nama Pendekar Rajawali Sakti.
Sejak peristiwa siang tadi, Dewi Tanjung menjadi gelisah. Entah kenapa, bayang-bayang wajah tampan Pendekar Rajawali Sakti selalu menghantui pelupuk matanya. Sukar sekali untuk mengenyahkannya. Meskipun pertemuan yang tidak bersuasana baik, tapi ketampanan dan kegagahan Pendekar Rajawali Sakti sempat juga menggetarkan hati gadis itu.
Dan Dewi Tanjung tidak mampu mengelaknya meskipun sudah berusaha keras mengusir bayang-bayang itu dari pelupuk matanya. Terbayang kembali ketika Rangga memeluk, dan membawanya kabur dari hadapan harimau besar peliharaan Macan Gunung Sumbing. Entah kenapa, saat itu Dewi Tanjung tidak berusaha berontak. Bahkan hatinya begitu kesal saat Rangga melepaskannya, sehingga tubuhnya jatuh bergulingan di tanah. Ada perasaan tenteram ketika tubuhnya dipeluk pemuda pendekar itu.
“Huh! Kenapa aku memikirkannya? Apa sih kelebihannya? Banyak pemuda yang lebih tampan dan lebih gagah darinya...!” Dewi Tanjung menggumam sendiri membantah segala bayangan di dalam hatinya.
Dewi Tanjung jadi tersenyum begitu membayangkan wajah Rangga bersemu merah ketika bagian atas dadanya terbuka sedikit. Dan Pendekar Rajawali Sakti langsung menyuruhnya pergi.
Senyum di bibir mungil yang selalu merah menantang itu, mendadak sirna. Dewi Tanjung mendongakkan kepalanya ke atas. Telinganya yang setajam mata pisau mendengar suara halus di atas atap kamar penginapannya. Walaupun suara itu langsung menghilang, tapi Dewi Tanjung masih juga mendengar tarikan napas yang demikian halus, dan hampir tidak terdengar.
“Hm.. Ada tamu rupanya...,” gumam Dewi Tanjung dalam hati.
Dewi Tanjung melompat ke sudut dekat jendela ketika atap kamarnya perlahan-lahan terbuka. Gadis itu melirik pembaringan yang kosong, kemudian menatap atap yang semakin terbuka lebar. Lalu....
“Hup! Hiyaaa...!”
Secepat kilat gadis itu melentingkan tubuhnya ke atas, menembus atap yang sudah cukup lebar terbuka, tubuh ramping itu langsung menerobos keluar, dan tahu-tahu sudah hinggap di atas atap. Tampak seorang laki-laki muda di atas atap terkejut setengah mati. Buru-buru laki-laki itu melompat turun. Tapi Dewi Tanjung lebih cepat lagi bertindak. Dia langsung melesat, lalu mengirimkan satu pukulan bertenaga dalam penuh.
Dug!
“Ughk...!” laki-laki itu mengeluh pendek.
Seketika tubuhnya terjerembab ke tanah, namun masih mampu bangkit berdiri. Seleret cahaya keperakan terlihat begitu tangannya bergerak. Ternyata laki-laki muda yang hanya terlihat wajahnya itu mencabut sebilah golok. Dewi Tanjung tersenyum sinis, berdiri tegak sambil bertolak pinggang.
“Maling kecil, ingin berlagak di depanku. Phuih!” dengus Dewi Tanjung mengejek.
“Aku bukan maling, perusuh keparat!” bentak laki-laki muda yang ternyata adalah Argayuda.
“Perusuh...? Kau bilang aku perusuh? Ha ha ha...!” Dewi Tanjung tertawa tergelak.
“Orang lain boleh tidak peduli dan takut padamu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu membantai seluruh penduduk Desa Weru seenak udel!” geram Argayuda.
Dewi Tanjung terkejut. Tawanya berhenti seketika. Ditatapnya tajam-tajam wajah Argayuda yang sudah menggeser kakinya dengan golok melintang di depan dada.
“Dengar, bocah edan! Aku tak pernah membantai orang-orang di sini. Jelas ini perbuatan Macan Gunung Sumbing! Sebagian besar penduduk di sini bisa mampus di tangannya! Kau terlalu gegabah menuduh sembarangan tanpa bukti!” tegas kata-kata Dewi Tanjung.
“Heh! Tidak semudah itu mengelabuiku, iblis betina! Kau pikir aku tidak tahu perbuatanmu yang keji itu? Kau kulihat keluar dari rumah korban, lalu kuikuti sampai ke sini!” dengus Argayuda dingin.
“Korban...?!” Dewi Tanjung kelihatan terkejut.
“Jangan berlagak bodoh, iblis! Kau baru saja membantai satu keluarga. Hm..., mana binatang peliharaanmu itu? Keluarkan sekalian, biar kukirim ke neraka bersamamu!”
Jelas raut wajah Dewi Tanjung terlihat sangat terkejut. Ternyata malam ini kembali terjadi pembantaian serupa pada satu keluarga. Dan Argayuda melihat, dan mengikutinya sampai ke sini. Apakah orang yang melakukan semua itu benar-benar Dewi Tanjung? Atau ada orang lain yang juga menginap di rumah penginapan ini?
Dan belum lagi rasa terkejut Dewi Tanjung hilang, Argayuda sudah melompat cepat sambil mengibaskan goloknya ke arah leher. “Mampus kau, Iblis! Hiyaaa...!”
“Uts!”
Dewi Tanjung cepat merundukkan kepalanya. Satu desingan keras terdengar melewati atas kepala gadis itu. Dan kembali Argayuda memutar goloknya menyimpang turun mengarah dada. Dewi Tanjung bergegas melompat mundur, tapi Argayuda tidak memberi kesempatan lagi. Dicecarnya wanita itu dengan kebutan golok ke kiri dan ke kanan. Dewi Tanjung terpaksa berjumpalitan berputaran menghindari kibasan golok yang beruntun itu.
“Hup! Hiyaaa...!”
Sambil berteriak keras, Dewi Tanjung melentingkan tubuhnya ke atas ketika satu babatan golok mengarah ke kakinya. Dua kali tubuhnya berputar di udara, lalu cepat meluruk turun, tepat di belakang Argayuda. Dewi Tanjung mengibaskan tangannya, langsung menghantam punggung pemuda itu.
“Akh...!” Argayuda terpekik tertahan.
Pemuda itu tersuruk jatuh mencium tanah. Dan belum lagi mampu berdiri, Dewi Tanjung sudah melompat cepat. Kakinya menyambar pergelangan tangan yang memegang golok. Kembali Argayuda memekik keras. Goloknya terlempar jauh, dan menancap di pohon. Sebelah kaki Dewi Tanjung langsung menginjak dada pemuda itu.
“Ugh!” Argayuda mengeluh seraya meringis menahan sakit pada dadanya.
Injakan kaki Bidadari Pencabut Nyawa itu demikian keras, sehingga membuat Argayuda jadi tersengal napasnya. Dadanya juga terasa nyeri, seolah-olah tulang-tulang dadanya remuk. Bahkan Dewi Tanjung semakin menekan kuat saat Argayuda mencoba menggelinjang berusaha melepaskan diri.
“Punya kepandaian mentah saja coba-coba menantangku, hih!” dengus Dewi Tanjung seraya mendupak tubuh Argayuda.
Pemuda itu bergelimpangan beberapa tombak jauhnya. Dia berusaha bangkit, tapi dadanya terasa sesak sekali. Argayuda hanya mampu duduk dan bernapas tersengal, namun sinar matanya bersorot tajam penuh kebencian pada gadis cantik yang mempecundanginya. Sedangkan Dewi Tanjung hanya berdiri tegak, lalu berbalik. Gadis itu melesat cepat ke atas atap, dan menghilang di sana.
********************
Ki Gedag begitu terkejut saat melihat Argayuda pulang. Tubuhnya limbung, kotor, dan mulut berdarah. Buru-buru laki-laki tua itu menyongsong. Dipapahnya pemuda itu dan dibawanya masuk ke dalam. Argayuda menurut saja saat didudukkan di kursi. Ki Gedag segera membersihkan darah di mulut Argayuda dengan kain basah.
“Ada apa? Apa yang terjadi denganmu, Argayuda?” tanya Ki Gedag seraya memeriksa tubuh cucunya ini.
“Dia menyerangku, Ki,” sahut Argayuda sambil meringis.
“Dia.... Dia siapa?” desak Ki Gedag. “Iblis pembantai itu.”
Ki Gedag terhenyak mendengar jawaban yang tidak diduga-duganya itu. Dipandanginya Argayuda dalam-dalam, seakan-akan hendak mencari kebenaran pada jawaban yang mengejutkan itu. Ki Gedag menoleh ketika mendengar langkah kaki memasuki ruangan depan rumahnya. Tampak Paman Waku dan Eyang Ganjur mendekati. Mereka datang dari ruangan dalam. Argayuda terkejut karena tidak menyangka kalau ada tamu di rumah kakeknya ini.
“Bagaimana kejadiannya, Argayuda?” tanya Paman Waku langsung.
Argayuda memandang Ki Gedag yang hanya mengangguk saja. Rupanya Paman Waku dan Eyang Ganjur sudah mendengar pembicaraan mereka tadi dari dalam. Argayuda menarik napas panjang, lalu segera menceritakan pengalamannya malam ini. Kejadiannya memang berawal dari rasa penasarannya. Kebetulan saat itu dia berada di depan rumah salah satu keluarga Paman Waku. Dari situ terdengar raungan keras yang disusul jeritan melengking saling susul. Argayuda menunggu beberapa saat, kemudian melihat dua bayangan berkelebat keluar dari dalam rumah itu.
Paman Waku diam tertunduk. Eyang Ganjur menarik kursi dan duduk di sebelah Argayuda. Sedangkan Ki Gedag hanya diam dengan kepala tertunduk. Argayuda kembali melanjutkan ceritanya. Waktu itu dibuntutinya kedua makhluk tadi sampai hilang di penginapan Ki Raga. Dia mengintai penginapan itu sesaat, lalu melihat salah satu kamar penginapan masih terang. Dicobanya masuk dari atap, tapi pemilik penginapan itu mengetahuinya. Maka terjadilah pertarungan. Argayuda menghentikan ceritanya. Dipandangi wajah-wajah yang tampak menegang penuh keseriusan.
“Maafkan aku, Paman. Aku hanya ingin...,” ucap Argayuda di akhir ceritanya.
“Sudahlah, Argayuda. Kuhargai keberanianmu. Tapi aku minta jangan diulangi lagi. Terlalu berbahaya bagi dirimu sendiri,” tegas Paman Waku pelan.
“Argayuda, kau lihat jelas wajahnya?” tanya Eyang Ganjur.
“Tentu. Dia seorang wanita yang masih muda dan cantik. Memakai baju putih, dan pedangnya tersampir di punggung,” sahut Argayuda.
“Wanita...,” desis Paman Waku lirih.
Eyang Ganjur menatap cucunya itu, kemudian beralih pada Argayuda. Pemuda ini nampak kebingungan melihat perubahan wajah Paman Waku saat mendengar ciri-ciri orang yang tadi bertarung dengannya, dan dicurigai sebagai pelaku pembantaian sadis di desa itu. Tampak kepala Paman Waku menggeleng-geleng beberapa kali. Terdengar tarikan napas panjang dan berat.
“Ada apa, Paman?” tanya Argayuda kebingungan.
“Hhh...!” Paman Waku menarik napas panjang. “Benarkah dia seorang wanita, Argayuda?” Paman Waku malah bertanya.
“Benar, Paman,” sahut Argayuda mantap.
Kepala Paman Waku menggeleng-geleng beberapa kali. Kakinya melangkah mendekati jendela. Sambil bertopang di sana, matanya memandang lurus ke depan. Tubuhnya lalu berbalik seraya menghembuskan napas panjang.
“Dugaan kita selama ini ternyata keliru, Eyang,” ujar Paman Waku disertai desahan napas panjang.
“Kau tahu siapa wanita itu, Waku?” tanya Eyang Ganjur. “Entahlah! Aku memang tidak mengenalnya. Tapi apa maksudnya membantai keluarga kita...?” Paman Waku seperti bertanya pada dirinya sendiri
Tidak ada yang membuka suara sedikit pun. Masing-masing sibuk dengan pikirannya. Pertanyaan Paman Waku masih menggantung. Di samping itu, mereka jadi khawatir karena sudah tiga keluarga yang terbantai sampai malam itu. Tidak ada yang hidup dari ketiga keluarga itu. Semuanya tewas mengerikan. Tubuh terpotong, atau tercabik. Bahkan ada beberapa yang hilang sebagian tubuhnya. Mungkinkah ini perbuatan Macan Gunung Sumbing atau si Bidadari Pencabut Nyawa?
********************
Desa Weru semakin dicekam perasaan takut. Mereka kembali digemparkan oleh terbantainya satu keluarga semalam. Tak ada lagi yang berkomentar. Semuanya diliputi perasaan cemas dan kekhawatiran yang dalam. Setiap malam satu keluarga terbantai tanpa ada sisa seorang pun. Segala bentuk dugaan dan cerita-cerita mengerikan bergema dari setiap mulut. Namun semua itu terlukiskan dari perasaan takut yang amat sangat.
Jauh di perbatasan Desa Weru sebelah barat, tampak Pendekar Rajawali Sakti tengah duduk bersimpuh menyatukan jiwa dan raga pada alam semesta. Tidak jauh di sampingnya, seekor kuda hitam asyik merumput. Seakan-akan tidak peduli terhadap majikannya yang sedang bersemadi. Tampak seorang wanita berbaju putih berlari cepat menembus semak belukar.
“Hup...!”
Rangga bergegas melompat, langsung menghadang gadis yang ternyata adalah Dewi Tanjung. Gadis itu terkejut, dan langsung berlindung di balik punggung Pendekar Rajawali Sakti. Napasnya tersengal tidak teratur. Bajunya tampak kusut dan koyak di beberapa bagian perut dan punggung. Dari sudut bibirnya mengalir darah.
“Ada apa?” tanya Rangga.
“Mereka..., mereka hendak membunuhku. Mereka masih mengejarku...,” sahut Dewi Tanjung masih terengah.
Rangga memalingkan mukanya ke arah datangnya Dewi Tanjung tadi. Terdengar suara-suara kaki yang berian cepat dalam jumlah banyak, disertai suara hiruk-pikuk. Sebentar Rangga memandang berkeliling, kemudian menarik tangan Dewi Tanjung. Seketika tubuh Pendekar Rajawali Sakti itu melesat ke udara sambil menarik tangan Dewi Tanjung. Kaki mereka hinggap di atas dahan pohon yang cukup tinggi dan rimbun. Rangga berdecak perlahan yang disertai pengerahan tenaga dalam, dan disalurkan melalui suara. Kuda hitam yang sedang merumput itu meringkik keras, lalu berlari menjauh.
Tidak berapa lama kemudian muncul beberapa orang dari dalam semak belukar. Mereka terus bergerak memasuki hutan. Tampak di antara sekitar tiga puluh orang bersenjata golok dan tombak itu terlihat Eyang Ganjur, Argayuda, Ki Gedag, dan Paman Waku. Ternyata, di situ juga ada seorang laki-laki setengah baya yang mengenakan jubah hijau tua. Tangannya menggenggam tombak bermata yang memiliki keluk tiga seperti keris. Mereka terus bergerak menjauh, tapi tidak berapa lama kemudian kembali lagi.
Dari atas pohon, Rangga mengamati semua itu. Tubuhnya baru meluruk turun setelah orang-orang tadi tidak terlihat lagi, sudah jauh kembali ke Desa Weru. Pendekar Rajawali Sakti itu segera melepaskan cekalannya pada tangan Dewi Tanjung begitu kakinya mendarat di tanah. Sedangkan kuda hitam itu kembali muncul, dan langsung menghampiri Pendekar Rajawali Sakti.
“Kenapa mereka mengejarmu?” tanya Rangga.
Dewi Tanjung tidak langsung menjawab. Dibersihkan debu dan darah yang melekat di tubuhnya. Bajunya yang sobek segera dibenahi, tapi tetap tidak bisa menyembunyikan sebagian kulit tubuhnya yang putih mulus.
“Kau tanya apa tadi...?” Dewi Tanjung baru membuka suara setelah dirasa dirinya sedikit rapi.
“Kadal!” rungut Rangga seraya menghampiri Dewa Bayu, lalu menepuk-nepuk leher kuda hitam itu.
“Jangan marah dulu, Kakang...,” rajuk Dewi Tanjung seraya memberikan senyuman yang termanis dimiliki.
“Kakang...?!” Rangga tersentak kaget. Seketika wajahnya bersemu merah mendengar sebutan itu.
“Tidak bolehkah aku memanggilmu begitu?” Dewi Tanjung malah semakin melebarkan senyumnya. “Kalau tidak boleh, ya tidak apa-apa. Tapi..., terima kasih kau telah menolongku. Sudah dua kali, ya...?”
“Kampret! Masih bisa bercanda juga...!” rungut Rangga dalam hati.
Tapi di balik itu, Rangga juga heran akan perubahan sikap Dewi Tanjung. Kemarin begitu ketus, galak, dan keras kepala. Tapi sekarang sungguh jauh berbeda! Bahkan dalam keadaan nyawa terancam masih juga bisa bergurau.
“Hhh.... Rupanya kau masih marah tentang kejadian kemarin. Aku minta maaf,” ujar Dewi Tanjung melihat Rangga memberengut saja tidak segera bicara.
“Untuk apa?” pelan suara Rangga, seakan enggan berbicara.
“Mungkin aku terlalu angkuh, keras kepala, dan cepat menuduh buruk pada setiap orang. Aku sadar kalau tidak bisa hidup sendiri di dunia yang kejam ini. Aku perlu seseorang yang bisa mengatasi segala kesulitanku...,” Dewi Tanjung mengangkat bahunya. “Yah.... Saat kesadaran itu muncul, mereka malah hendak membunuhku, mengeroyokku, bahkan tidak memberi kesempatan padaku untuk menjelaskan persoalan sebenarnya. Aku dituduh telah membantai beberapa keluarga secara keji. Padahal aku tahu siapa yang berbuat semua itu.”
“Siapa?” tanya Rangga cepat
“Macan Gunung Sumbing,” sahut Dewi Tanjung. “Dialah yang menjadi biang keladinya. Bukan hanya di Desa Weru ini, tapi juga di desa-desa lain sebelumnya. Tidak terhitung lagi, berapa orang yang menjadi korban kebiadabannya.”
“Dan kau memburunya untuk menghentikan perbuatannya?”
“Bukan hanya itu.”
“Oh..., lantas?”
Dewi Tanjung diam sesaat. Ditariknya napas panjang-panjang. Wajahnya berubah mendung seketika. Rangga mendekati gadis itu dan memegang pundaknya. Dibawanya Dewi Tanjung duduk di bawah pohon agar terlindung dari sengatan matahari. Raut wajah gadis itu masih terlihat mendung, seperti ada satu kenangan pahit yang tiba-tiba melintas dalam benaknya.
“Maaf, seharusnya aku tidak menyinggung masalah pribadimu,” ujar Rangga pelan.
“Tidak apa-apa. Kau memang harus tahu masalahnya. Aku sadar betul kalau kemampuanku belum apa-apa untuk menghadapi Macan Gunung Sumbing. Modalku hanya nekad. Tapi kematian orang tua dan saudara-saudaraku harus dibalas,” sebentar Dewi Tanjung terdiam. Kembali ditarik napas panjang, seakan-akan ingin dilonggarkan rongga dadanya. “Peristiwa itu terjadi kira-kira sebulan yang lalu. Waktu itu aku masih berada di padepokan milik kakekku. Aku tidak tahu lagi, apa yang harus kulakukan selain dendam dan ingin membunuh si keparat Macan Gunung Sumbing itu!”
Rangga diam sambil terangguk-angguk. Baru dimengerti, mengapa gadis ini bersikap aneh, keras kepala, dan angkuh. Rupanya di dalam hatinya menyimpan bara api dendam yang luar biasa. Dendam yang sulit dipadamkan sampai kapan pun, sebelum terlaksana niatnya!
Tapi sekarang persoalannya menjadi semakin rumit. Semua orang sudah menuduh, Dewi Tanjung lah yang melakukan semua pembantaian keji itu. Memang tidak mudah untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, kecuali Macan Gunung Sumbing sendiri yang mengakui. Itu pun kalau bisa bertemu, atau paling tidak memergokinya saat beraksi. Tapi tidak mudah untuk melaksanakannya. Sedangkan Rangga sendiri tidak tahu, apa maksud sebenarnya Macan Gunung Sumbing melakukan pembantaian keji itu. Dan lagi memang tidak ada yang tahu, siapa korban-korban berikutnya.
“Aku akan membantumu, Dewi Tanjung. Bukan karena aku punya persoalan dengan Macan Gunung Sumbing. Tapi yang jelas, aku tidak bisa melihat kekejaman berlangsung di depan mataku,” kata Rangga berjanji.
“Aku percaya, Kakang. Eyang Guru sering bercerita tentang dirimu. Itu sebabnya kau langsung kukenali saat pertama kali bertemu. Juga ketika di kedai itu. Aku pun sudah bisa mengenalimu. Bahkan si keparat itu juga ada di sana,” sahut Dewi Tanjung mulai cerah kembali wajahnya. Gadis ini memang selalu periang, meski dalam keadaan yang teramat sulit sekalipun.
“Kenapa waktu itu tidak bertindak?” tanya Rangga ingin tahu.
“Aku tidak ingin membuat keributan. Yang kuinginkan hanya pertarungan yang adil antara aku dengan dia saja.”
Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam hatinya dikagumi juga keberanian dan sifat Dewi Tanjung yang satria itu. Tapi sayangnya, semua itu tidak didukung oleh kemampuan ilmu olah kanuragan. Dan Rangga sendiri belum yakin, apakah mampu mengatasi semuanya itu. Dia memang sudah pernah bentrok satu kali dengan si Macan Gunung Sumbing itu. Waktu itu Pendekar Rajawali Sakti memang sudah bisa mengukur, sampai di mana tingkat kepandaiannya.
********************
LIMA
Malam itu udara terasa pekat sekali. Awan hitam bergulung-gulung di angkasa. Udara dingin terbawa angin yang berhembus kencang terasa begitu menusuk. Namun tidak ada tanda-tanda kalau malam itu akan terguyur hujan. Desa Weru tampak sunyi senyap. Dan malam itu tidak seperti pada malam-malam sebelumnya. Di beberapa tempat terlihat sekelompok orang bersenjata golok berjaga-jaga. Mereka adalah murid Padepokan Gunung Opak.
Paman Waku memang sudah mengirim utusan ke Gunung Opak. Dalam suratnya, diceritakan semua kejadian di desa itu pada kakaknya. Bakor sendiri langsung datang bersama tiga puluh orang murid utamanya, karena tahu siapa yang bakal dihadapi. Seorang tokoh rimba persilatan yang sangat tangguh dan sukar dicari tandingannya! Tokoh yang berhati iblis, dan tidak segan-segan melenyapkan nyawa lawan, atau siapa saja yang dikehendaki.
Tapi di tempat lain, tepatnya tidak jauh dari rumah penginapan milik Ki Raga, terlihat Pendekar Rajawali Sakti dan Bidadari Pencabut Nyawa tengah mengawasi rumah penginapan itu dari tempat yang cukup tersembunyi. Di rumah itu Bidadari Pencabut Nyawa menginap beberapa hari. Dan di situ pula nyawanya hampir melayang akibat kesalahpahaman.
“Aku ragu-ragu dengan dugaanmu, Dewi Tanjung,” kata Rangga setengah berbisik.
“Mungkin bisa juga salah, Kakang. Tapi aku yakin betul kalau Macan Gunung Sumbing menginap di situ juga,” sahut Dewi Tanjung.
“Bagaimana kau bisa yakin?”
“Tidak ada rumah penginapan lain di desa ini, selain rumah itu.”
“Kau pernah melihat dia di sana?”
“Belum. Tapi dari kejadian siang tadi, keyakinanku semakin bertambah. Mana mungkin mereka langsung menuduhku sebagai pelaku, dan tahu kalau aku menginap di sana? Sedangkan malamnya ada seseorang yang hendak membunuhku secara licik.”
Rangga terdiam. Pandangannya tidak berkedip ke arah rumah penginapan di depan itu. Keningnya agak sedikit berkerut, pertanda tengah berpikir keras.
“Kau tunggu saja di sini,” kata Rangga seraya beringsut ke luar dari tempat persembunyiannya.
“Mau ke mana?” tanya Dewi Tanjung.
“Sebentar aku kembali. Kau jangan ke mana-mana,” sahut Rangga.
Pendekar Rajawali Sakti langsung melompat cepat ke arah hutan. Begitu sempurnanya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki, sehingga dalam waktu singkat saja sudah jauh di luar perbatasan Desa Weru. Rangga berdiri tegak di tengah-tengah padang rumput yang cukup terbuka lebar.
“Suiiit...!”
Rangga bersiul nyaring dan panjang dengan nada aneh tanpa irama yang pasti. Siulan itu menggema, terpantul oleh bukit dan gunung, terbawa angin, merambat sampai jauh. Sebentar Pendekar Rajawali Sakti itu menunggu, kemudian bersiul kembali lebih panjang.
Agak lama juga Rangga menatap langit yang kelam. Tapi sesaat kemudian bibirnya menyunggingkan senyuman. Jauh di angkasa, tampak sebuah titik hitam keperakan. Titik itu semakin lama semakin membesar, dan terlihat jelas bentuknya.
“Khraghk...!”
“Rajawali, ke sini...!” seru Rangga keras.
Titik yang ternyata adalah burung rajawali raksasa, langsung menukik dan mendarat tepat di depan Pendekar Rajawali Sakti. Rangga langsung melompat naik ke punggung rajawali raksasa itu. Sebentar ditepuk-tepuknya leher burung itu.
“Khraghk...!”
“Aku mencari seseorang, Rajawali Putih. Tapi aku tidak tahu, di mana dia sekarang. Tapi yang jelas masih berada di Desa Weru. Kita terbang rendah di atas desa itu, tapi jangan sampai mengejutkan penduduk,” perintah Rangga.
“Khraghkkk...!”
“Iya, kau juga jangan bersuara.”
“Khraghk...!”
Rajawali Putih langsung melesat membumbung ke angkasa. Sebentar saja sudah melayang cukup rendah di atas puncak pepohonan. Burung raksasa itu terus menuju Desa Weru yang ditunjuk Rangga. Malam yang pekat ini memang membantu Rajawali Putih untuk tidak terlihat penduduk, meskipun terbang cukup rendah. Dia berputar-putar begitu sampai di Desa Weru.
Dari atas, Rangga dapat melihat lebih jelas. Bahkan bibirnya tersenyum begitu mendapati Dewi Tanjung masih berada di tempatnya semula, tanpa bergerak sedikit pun. Pendekar Rajawali Sakti itu juga bisa mengetahui tempat-tempat yang dijaga murid-murid Padepokan Gunung Opak.
“Hhh...! Jangan-jangan dia tahu kalau malam ini ada penjagaan yang cukup ketat juga,” gumam Rangga dalam hati. Sudah cukup lama juga Rangga berada di angkasa bersama Rajawali Putih, tapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun kalau Macan Gunung Sumbing bakal keluar malam ini. Akhirnya Rangga memutuskan untuk menghentikan saja usahanya malam ini. Dia yakin kalau Macan Gunung Sumbing tidak bodoh, nekad ke luar dari persembunyian dalam suasana tidak menguntungkan bagi dirinya ini.
Pendekar Rajawali Sakti meminta Rajawali Putih untuk kembali ke hutan. Burung itu langsung melesat tepat ke arah semula, dan mendarat mulus di tanah berumput tebal. Rangga berpesan agar Rajawali Putih tidak pergi jauh-jauh, karena masih dibutuhkan kelak. Kemudian Pendekar Rajawali Sakti langsung kembali menemui Dewi Tanjung yang masih berada di tempat persembunyiannya.
********************
Tiga malam berturut-turut Rangga memutari Desa Weru bersama Rajawali Putih. Tapi selama itu tidak terlihat Macan Gunung Sumbing keluar dari persembunyiannya. Juga tidak ada lagi korban yang jatuh. Lain yang dilakukan Rangga, lain pula yang terjadi pada Paman Waku. Kakaknya yang bernama Bakor merasa kalau Macan Gunung Sumbing tidak akan muncul lagi. Makanya dia kini kembali ke padepokannya di Gunung Opak.
Tapi Paman Waku tetap yakin kalau Macan Gunung Sumbing masih berada di sekitar Desa Weru ini. Sedangkan lain lagi yang ada di benak Eyang Ganjur. Orang tua ini malah tidak percaya kalau itu perbuatan Macan Gunung Sumbing. Dugaannya,
semua itu adalah perbuatan seorang wanita yang berhasil lolos saat digerebek. Lolosnya wanita itu waktunya bersamaan dengan ketidakmunculan Macan Gunung Sumbing lagi. Bukan hanya Eyang Ganjur yang menduga seperti itu, Ki Gedag dan Argayuda pun juga yakin wanita yang menginap di rumah penginapan Ki Raga adalah pelaku dari semua pembantaian keji ini.
Ini adalah malam keempat, pelaku pembantaian keji itu belum menampakkan diri lagi. Sedangkan Bakor dan murid-muridnya sudah kembali ke Gunung Opak. Desa Weru kembali terselimut kesunyian dan kecemasan akan munculnya pembunuh berdarah dingin itu. Malam juga demikian larut, tapi Paman Waku belum juga bisa memejamkan matanya. Dia masih memikirkan pelaku pembantaian keji yang sekarang menghilang entah ke mana.
“Hhh...! Tidak ada yang bisa kulakukan di kamar ini. Aku harus mencari keterangan, siapa sebenarnya pelaku berdarah dingin itu. Apakah Macan Gunung Sumbing, atau orang lain? Hhh! Keluargaku bisa habis kalau didiamkan terus begini,” bisik kata hati Paman Waku.
“Aummm...!”
“Heh...!”
Tiba-tiba Paman Waku tersentak kaget ketika mendengar auman harimau. Dia langsung melompat bangkit dari pembaringannya. Auman itu demikian jelas terdengar, seakan-akan begitu dekat berada di dalam rumah ini.
“Aaakh...!”
Belum lagi Paman Waku bisa berpikir, terdengar jeritan panjang melengking disusul suara geraman harimau.
“Eyang...!”
Paman Waku langsung melompat menerjang pintu hingga hancur berantakan, dan terus berlari menuju kamar kakeknya. Hampir-hampir tidak dipercaya dengan apa yang dilihatnya, begitu sampai di kamar itu keadaannya sudah berantakan seperti baru saja terjadi pertempuran. Paman Waku tersentak. Telinganya mendengar suara-suara ribut di bagian belakang rumah ini. Dia langsung memburu cepat ke arah suara yang didengarnya.
“Eyang...!” pekik Paman Waku begitu sampai di depan pintu halaman belakang rumah.
Tampaklah di situ, Eyang Ganjur tengah bertarung melawan seekor harimau sebesar anak kerbau! Paman Waku langsung melompat hendak membantu, tapi pada saat itu satu sampokan cakar harimau merobek leher Eyang Ganjur.
“Aaakh...!” Eyang Ganjur memekik keras. Tubuhnya langsung limbung. Sekujur tubuhnya telah berlumuran darah, dan bajunya cabik-cabik tercakar binatang buas itu. Paman Waku cepat menghantamkan kakinya ke tubuh harimau yang tengah mengangkangi Eyang Ganjur.
Duk!
Satu tendangan keras disertai pengerahan tenaga dalam tinggi, membuat harimau itu terpental. Namun begitu kakinya menyentuh tanah, binatang itu langsung melompat menerkam Paman Waku.
“Hait..!”
Paman Waku berkelit mengegoskan tubuhnya ke samping, dan cepat mengirimkan satu pukulan keras bertenaga dalam penuh. Pukulan itu menghunjam tepat di bagian perut binatang buas itu. Namun Paman Waku jadi terperanjat, karena dirasakan seperti memukul segumpal kapuk yang membal. Pukulannya terpental dan berbalik
Paman Waku langsung melompat mundur, dan masih sempat melirik Eyang Ganjur yang menggeletak tidak bergerak. Seluruh tubuh laki-laki tua itu sudah tercabik dan berlumuran darah. Sementara harimau besar itu sudah menerkam kembali sambil mengaum keras.
“Hup! Hiya...! Hiyaaa...!”
Laki-laki setengah baya itu cepat melentingkan tubuhnya ke udara, dan langsung menukik menghantamkan tiga kali pukulan beruntun ke tubuh harimau itu. Satu pun pukulannya tidak ada yang meleset, tapi harimau itu malah semakin liar dan ganas. Binatang itu cepat berbalik begitu menyentuh tanah, dan kembali menyerang lebih ganas lagi. Paman Waku terpaksa berjumpalitan menghindari serangan yang cepat dan tidak kenal menyerah itu. Beberapa pukulan dan tendangan bersarang di tubuh harimau itu, tapi tak ada satu pun yang berarti.
Memang hampir tidak dapat dipercaya. Bahkan Paman Waku sendiri sampai tidak habis pikir terhadap binatang itu. Padahal sudah dikerahkan seluruh tenaga dalamnya setiap kali memukul atau menendang. Tapi harimau itu sama sekali tidak menderita luka, bahkan semakin bertambah ganas saja.
“Graugh...!”
Sambil meraung keras, harimau itu melompat seraya mengibaskan kaki depannya. Paman Waku ber-usaha menghindar dengan membanting tubuhnya ke tanah. Tapi kibasan cakar harimau itu masih sempat menyambar bahu kirinya.
“Akh!” Paman Waku terpekik tertahan.
Sambil melompat bangkit, laki-laki setengah baya itu memegangi pundak kirinya. Darah merembes seperti anak sungai. Luka cakaran itu cukup dalam dan terasa pedih. Belum lagi Paman Waku bisa menghilangkan rasa perih pada bahu kirinya, harimau itu kembali menerjang ganas.
“Uh, mati aku...!” dengus Paman Waku dalam hati.
Dan pada saat yang kritis itu, tiba-tiba sebuah bayangan putih berkelebat cepat memapak terjangan harimau itu. Satu raungan keras terdengar, dan harimau itu terpental balik ke belakang. Tubuhnya menghantam tembok hingga hancur berantakan. Hebatnya, harimau itu masih juga mampu bangkit dan menggerung-gerung marah. Matanya merah menatap tajam pemuda tampan berbaju rompi putih yang tahu-tahu sudah berdiri di depan Paman Waku.
“Auuummm...!”
Tiba-tiba terdengar suara mengaum yang keras. Kelihatannya binatang buas itu akan membalas. Tiba-tiba dia meloncat tinggi hingga melewati kepala pemuda itu dan Paman Waku. Lompatannya begitu cepat, sehingga lenyap seketika di balik pagar tembok yang cukup tinggi di bagian belakang. Paman Waku langsung berlari menghampiri Eyang Ganjur.
“Eyang...,” lirih suara Paman Waku.
Tapi Eyang Ganjur tidak bisa bergerak lagi. Luka-luka akibat cakaran harimau membuat nyawanya melayang. Darah menggenang di sekitar tubuhnya. Paman Waku tidak bisa lagi berbuat banyak. Dia hanya mampu berdiri sambil menahan kesedihan dan rasa amarahnya. Diangkat kepalanya, maka terlihatlah seraut wajah tampan yang tahu-tahu sudah berada di depannya. Entah kapan pemuda itu berpindah tempat.
********************
Paman Waku masih berdiri mematung di samping pusara Eyang Ganjur. Sebagian besar orang yang mengantar ke pemakaman segera pulang ke rumahnya masing-masing begitu pemakaman selesai. Di situ tinggal Paman Waku, Ki Gedag, Argayuda, dan Rangga yang lebih dikenal sebagai Pendekar Rajawali Sakti. Paman Waku baru mengangkat kepalanya begitu dirasakan tepukan halus pada bahu kanannya. Balutan merah bernoda darah masih melekat di bahu kirinya.
“Ayo, kita pulang,” ajak Ki Gedag pelan.
“Hhh...!” Paman Waku menarik napas panjang.
Laki-laki setengah baya itu menatap Rangga yang berada tepat di depannya. Kakinya melangkah memutari pusara itu, dan segera menghampiri Pendekar Rajawali Sakti. Sebentar ditatapnya pemuda itu dan diulurkan tangannya. Rangga menerimanya dengan bibir menyunggingkan senyuman.
“Maaf, aku telah menduga buruk padamu,” ucap Paman Waku lirih.
“Lupakan,” sahut Rangga.
Paman Waku melangkah pergi diiringi Pendekar Rajawali Sakti yang mensejajarkan langkahnya di samping kanan laki-laki tua itu. Di belakang mereka berjalan Ki Gedag dan Argayuda. Mereka tidak ada yang berbicara sampai memasuki Desa Weru yang kini semakin terasa sunyi senyap.
“Bagaimana kau bisa tahu kalau aku tengah diserang semalam?” tanya Paman Waku setelah sekian lama membisu.
“Hanya kebetulan saja aku lewat,” sahut Rangga. Tentu saja tidak mungkin dikatakan yang sebenarnya. Padahal semalam Rangga berada di udara bersama Rajawali Putih. Tiap malam dia memang meronda di atas Desa Weru, dan baru semalam bisa bertemu binatang peliharaan Macan Gunung Sumbing. Itu pun kedatangannya sudah terlambat, sehingga nyawa Eyang Ganjur tidak bisa tertolong lagi.
“Sulit kupercaya kalau dia masih menyimpan dendam,” desah Paman Waku lirih.
“Maaf. Dendam apa, Paman?” tanya Rangga ingin tahu.
“Dulu antara aku dan Macan Gunung Sumbing pernah bertarung. Dia berhasil kukalahkan. Hhh..., waktu memang bisa merubah segalanya. Begitu cepat dan pesatnya kemajuan yang dimiliki. Dan harimau itu.... Padahal dulu belum memilikinya, atau mungkin sudah. Aku sendiri tidak mengerti.”
“Kapan itu terjadi?” tanya Rangga.
“Dua puluh tahun yang lalu.”
“Dua puluh tahun..., waktu yang cukup panjang untuk meningkatkan ilmu,” gumam Rangga.
“Kudengar, kau juga pernah bentrok dengannya. Benar?” tanya Paman Waku.
“Ya, beberapa purnama yang lalu,” sahut Rangga.
Pendekar Rajawali Sakti itu memang sudah menceritakan pengalaman dirinya yang pernah bentrok dengan Macan Gunung Sumbing pada Ki Gedag (Baca: Serial Pendekar Rajawali Sakti, dalam kisah Kemelut Pusaka Leluhur). Dan mungkin Ki Gedag sudah bercerita kembali pada Paman Waku.
“Bagaimana kau bisa mengalahkannya?” tanya Paman Waku lagi ingin tahu.
“Aku tidak mengalahkannya. Hanya bentrokan kecil saja,” sahut Rangga jujur.
“Hhh...! Sepertinya dia tidak ingin bentrok lagi denganmu, Pendekar Rajawali Sakti.”
“Panggil saja aku Rangga,” pinta Rangga. Dia memang lebih senang dipanggil namanya saja, daripada dipanggil julukannya.
Paman Waku tersenyum. Kakinya berhenti melangkah dan berbalik menghadap pada Ki Gedag dan Argayuda yang ikut berhenti melangkah. Rangga juga ikut berhenti. Sesaat tidak ada yang bicara lagi.
“Ki Gedag, bagaimana dengan pengungsian keluargaku yang lain?” tanya Paman Waku.
“Semua berjalan lancar, dan sekarang sudah ada di Padepokan Gunung Opak,” sahut Ki Gedag.
“Mudah-mudahan Macan Gunung Sumbing tidak sampai ke sana,” desah Paman Waku.
“Sebaiknya kau juga segera ke sana, Waku,” usul Ki Gedag menyarankan.
“Tidak, Ki. Aku harus tetap di sini. Apa pun yang terjadi, akan kuhadapi. Macan Gunung Sumbing hanya memerlukan diriku, bukan yang lain. Dia membantai sanak saudaraku hanya untuk membuat jiwaku goncang dan melemahkan semangatku. Hm, rencana yang keji!”
“Kau akan menghadapinya?” tanya Ki Gedag bernada khawatir.
“Tentu! Akan kutantang dia seperti dua puluh tahun yang lalu,” sahut Paman Waku tegas.
“Ha ha ha...!”
Tiba-tiba saja terdengar suara tawa keras menggelegar. Dan belum lagi hilang suara tawa itu, muncul sesosok tubuh tinggi tegap berwajah penuh brewok. Di sampingnya, berdiri tegak seekor harimau besar.
Paman Waku, Ki Gedag, dan Argayuda terkejut bukan main. Tapi Rangga kelihatan tenang, bahkan malah mendongak ke atas sedikit. Bibirnya tersenyum melihat Rajawali Putih masih melayang di angkasa hampir tertutup awan.
“Macan Gunung Sumbing...,” desis Paman Waku.
“Kau masih mengenalku, Waku?” sinis nada suara Macan Gunung Sumbing.
“Perbuatanmu sudah kelewat batas, Macan Gunung Sumbing!” dengus Paman Waku menggeram.
“Ha ha ha...! Tidakkah kau ingat sumpahku, Waku? Atau sengaja melupakannya? Bukan hanya padamu, tapi seluruh lawan-lawanku. Dan sebagian sudah binasa!”
“Kejam...!” desis Paman Waku.
Tentu saja laki-laki setengah baya itu tidak bisa melupakan sumpah Macan Gunung Sumbing, sesaat setelah dikalahkan dua puluh tahun yang lalu. Macan Gunung Sumbing bersumpah akan datang lagi menuntut kekalahannya. Bukan saja pada mereka yang pernah berurusan dengannya, tapi seluruh keluarga, dan sanak saudara harus mati. Dan sumpah itu diucapkan juga pada lawan-lawannya yang pernah mengalahkannya dalam pertarungan.
“Dan kau juga, Pendekar Rajawali Sakti,” Macan Gunung Sumbing menuding Rangga dengan jari telunjuknya yang berkuku hitam dan runcing. “Pertarungan kita belum selesai, dan tunggulah giliranmu. Tapi karena kau sudah berada di sini, maka nyawamu sudah sampai di tenggorokan!”
“Kita lihat, siapa yang lebih dahulu terbang ke neraka!” tantang Rangga dingin.
“Ha ha ha...! Bagus...! Aku senang mendengar tantangan itu, Pendekar Rajawali Sakti. Tapi tunggulah, akan datang saatnya untukmu!” sambut Macan Gunung Sumbing. “Hm..., mana satu lagi?! Gadis sombong yang coba-coba ingin menantangku!”
“Tidak perlu kau tanyakan! Aku sanggup mewakili semuanya!” ujar Rangga tegas.
“Grrr...! Kau terlalu angkuh, Pendekar Rajawali Sakti. Baiklah, aku ingin lihat, sampai di mana kesombonganmu itu!”
Setelah berkata demikian, Macan Gunung Sumbing langsung melompat cepat bagaikan kilat. Dan tahu-tahu sudah lenyap dari pandangan mata. Harimau belang itu juga langsung melesat cepat. Rangga menarik napas panjang. Sedangkan Paman Waku, Ki Gedag, dan Argayuda, berpaling memandang ke arahnya.
********************
ENAM
Hari-hari terus berlalu seirama peredaran matahari dan bulan. Setiap malam selalu terjadi pembantaian di Desa Weru. Bukan saja keluarga dan sanak saudara Paman Waku. Bahkan juga penduduk yang tidak ada sangkut pautnya dalam urusan ini. Tindakan Macan Gunung Sumbing seperti hantu saja. Datang menyebar bencana, dan pergi tanpa diketahui jejaknya. Tidak mudah untuk mencari tahu di mana Macan Gunung Sumbing bersembunyi pada siang hari.
Sementara itu saat matahari bersinar penuh, Rangga tengah melayang di angkasa bersama Rajawali Putih. Sudah tiga kali Desa Weru dikitari, tapi tidak ditemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Siang dan malam Pendekar Rajawali Sakti itu meronda ke seluruh pelosok desa dari angkasa, tapi tetap saja kecolongan.
“Kira-kira di mana dia bersembunyi, Rajawali Putih?” tanya Rangga bernada agak putus asa.
“Khrrr...!” Rajawali Putih mengkirik perlahan.
“Ya, dia memang seperti hantu saja.”
“Khraghk...!” tiba-tiba Rajawali Putih berseru nyaring.
Seketika itu juga burung itu meluruk deras ke arah utara Desa Weru. Rangga langsung mengarahkan pandangannya ke sana. Tampak Dewi Tanjung tengah bertarung sengit melawan seekor harimau besar. Tidak jauh dari tempat pertarungan itu, terlihat Macan Gunung Sumbing tengah tertawa terbahak-bahak.
“Khraghk...!”
“Hiyaaa...!”
Rangga segera melompat turun sebelum Rajawali Putih sampai ke tanah, dan langsung terjun ke kancah pertempuran. Satu tendangan keras bertenaga dalam sempurna dilepaskan, dan telak menghantam bagian perut harimau.
“Ghraaaugh...!” harimau itu menggerung keras. Tubuhnya terlontar jauh sekitar dua batang tombak.
Belum juga harimau itu bisa bangkit berdiri, Rangga sudah melompat lagi. Langsung saja dikirimkan dua pukulan beruntun dari jurus ‘Pukulan Maut Paruh Rajawali’ tingkat terakhir. Kedua tangan Pendekar Rajawali Sakti itu jadi merah bagai terbakar. Kembali harimau itu terpelanting terhantam pukulan maut secara beruntun itu. Dan Rangga memang sudah menduga kalau harimau itu kebal, tidak terpengaruh pukulannya. Pendekar Rajawali Sakti itu kembali menerjang dahsyat. Tapi pada terjangannya kali ini, pukulannya tertahan karena sebuah bayangan melesat cepat menyampok serangannya pada harimau itu. “Hup!”
Rangga melentingkan tubuhnya ke belakang, dan manis sekali mendaratkan kakinya di tanah. Tampak Macan Gunung Sumbing sudah berdiri tegak membelakangi harimaunya yang menggerung-gerung dengan kaki depan menggaruk-garuk tanah. Sementara Rangga menggeser kakinya mendekati Dewi Tanjung.
“Kau tidak apa-apa, Dewi?” tanya Rangga setelah dekat.
“Tidak, untung kau cepat datang,” jawab Dewi Tanjung. Napasnya sedikit tersengal.
“Kau terluka...?”
“Hanya sedikit cakaran di punggung.”
Rangga melirik punggung Dewi Tanjung. Tampak darah merembes keluar dari luka gores yang cukup dalam. Jelas, itu berasal dari goresan cakar harimau. Ada tiga goresan yang cukup panjang. Rangga mengalihkan perhatiannya kembali pada Macan Gunung Sumbing dan binatang peliharaannya yang mulai bergerak mendekati. Macan itu menggerung-gerung sambil menatap liar penuh hawa nafsu membunuh.
“Menyingkirlah, Dewi. Biar aku yang menghadapinya,” perintah Rangga setengah berbisik.
“Hati-hati, Kakang.”
Dewi Tanjung menggeser kakinya menyingkir. Sedangkan Rangga mengayunkan kakinya dua tindak ke depan. Nampaknya memang sudah bersiap-siap menghadapi serangan Macan Gunung Sumbing dan binatang peliharaannya itu. Rangga sempat melirik ke atas, tampak Rajawali Putih masih melayang-layang cukup tinggi.
“Suiiit...!” Rangga bersiul nyaring.
“Khraghk...!” Dewi Tanjung dan Macan Gunung Sumbing terkejut, dan sama-sama mendongak ke atas. Tampak seekor burung rajawali raksasa menukik deras, dan langsung hinggap di tanah di samping Pendekar Rajawali Sakti. Bukan main besarnya burung itu. Seperti bukit saja layaknya. Tegar, besar, dan menyeramkan!
“Rajawali! Buat harimau itu kapok untuk tinggal di dunia,” perintah Rangga seraya menepuk-nepuk leher Rajawali Putih.
“Khraghk...!”
“Ayo, Macan Gunung Sumbing! Kita selesaikan urusan kita!” tantang Rangga keras.
Macan Gunung Sumbing tidak menjawab. Matanya menatap lurus pada rajawali raksasa yang berada di samping Rangga. Sedangkan harimaunya hanya menggerung-gerung sambil menggaruk-garuk tanah.
“Bagaimana, Macan Gunung Sumbing?” sinis nada suara Rangga.
“Phuih!” Macan Gunung Sumbing menyemburkan ludahnya.
Laki-laki berwajah penuh brewok itu menggeser kakinya ke samping. Dan Rangga pun mengikuti sambil menatap tajam tanpa berkedip. Tapi tiba-tiba saja harimau belang sebesar anak kerbau itu menggerung keras, dan langsung melompat ke arah Pendekar Rajawali Sakti. Cakar mengembang mengancam tubuhnya! Cepat Rangga melompat ke samping menghindari terjangan itu. Tapi belum juga tubuhnya bisa menyentuh tanah, Macan Gunung Sumbing sudah melompat cepat bagai kilat sambil mengirimkan dua pukulan dahsyat secara beruntun.
“Curang!” maki Rangga seraya melentingkan
tubuhnya berputaran di udara menghindari serangan yang mendadak itu.
“Khraghk...!”
Saat itu Rajawali Putih melesat ke angkasa. Langsung saja ditangkapnya tubuh Rangga yang kewalahan, berpelantingan di udara menghindari serangan-serangan beruntun Macan Gunung Sumbing dan binatang peliharaannya. Rajawali Putih menurunkan Rangga di tempat yang tidak berapa jauh, dan kembali membumbung ke angkasa. Kini burung itu menukik deras ke arah harimau belang sebesar anak kerbau itu!
Pada saat yang sama, Rangga kembali melompat menerjang Macan Gunung Sumbing. Kali ini laki-laki penuh brewok itu terpaksa bertarung sendirian melawan Pendekar Rajawali Sakti. Ternyata harimau peliharaannya tengah sibuk menghalau gempuran rajawali raksasa yang bertarung cepat tanpa menyentuh tanah sedikit pun.
Harimau belang itu kelihatan geram menghadapi lawan yang selalu berada di udara. Memang, pola serangan Rajawali Putih sangat aneh. Melambung tinggi ke angkasa, lalu menukik deras dengan sambaran keras dan mematikan. Hal ini membuat harimau itu kelabakan dan tidak mampu membalas. Beberapa kali sabetan sayap Rajawali Putih membuat harimau itu berpelantingan sambil menggerung marah. Tapi harimau itu memang cukup alot, dan gerakannya lincah luar biasa. Tidak mudah bagi Rajawali Putih untuk menghunjamkan cakar atau memukul dengan paruhnya yang lebih tajam daripada senjata apa pun di dunia ini!
Sementara di tempat lain, Rangga dan Macan Gunung Sumbing juga bertarung tidak kalah sengitnya. Masing-masing berusaha untuk saling menjatuhkan. Kini tempat pertarungan itu sudah sulit dikenali lagi. Pohon-pohon bertumbangan. Batu-batu pecah berantakan. Tanah berlubang, debu mengepul menambah kepekatan udara. Hanya dua orang tokoh sakti dan dua binatang bertarung, tapi keadaan sekitarnya seperti diamuk ratusan ekor gajah.
Sementara tidak jauh dari pertarungan itu, Dewi Tanjung tetap memperhatikan tanpa berkedip. Dia berharap Rangga memenangkan pertarungan ini. Sama sekali tidak diinginkan kalau Rangga kalah. Kalau saja Pendekar Rajawali Sakti sampai kalah, apa jadinya dunia ini? Tidak ada seorang pendekar pun yang mampu membendung kekuatan Macan Gunung Sumbing!
Pertarungan masih terus berlangsung sengit. Entah sudah berapa jurus terlampaui. Masing-masing sudah mengeluarkan jurus andalannya. Bahkan Rangga sendiri sudah sampai pada jurus-jurus yang didapatkan dari Satria Naga Emas, salah seorang pendekar yang hidup seratus tahun lalu, dan menjadi sahabat karib Pendekar Rajawali, guru Pendekar Rajawali Sakti. Tapi sampai sejauh ini Macan Gunung Sumbing masih mampu melayaninya.
Pertarungan meningkat menjadi adu kesaktian. Udara bukan saja dipenuhi debu, tapi juga suara-suara ledakan dahsyat menggemuruh, disertai percikan bunga api dan sinar-sinar yang berkilatan. Tapi kedua tokoh sakti itu tampaknya masih sama-sama tangguh. Belum ada tanda-tanda bakal ada yang terdesak.
“Ha ha ha...! Keluarkan semua kesaktianmu, Pendekar Rajawali Sakti!” Macan Gunung Sumbing tertawa terbahak-bahak.
“Hm..., tinggal satu lagi ajian yang belum kukeluarkan,” gumam Rangga dalam hati.
Sesaat mereka saling berdiam diri dan berdiri tegak menatap tajam. Jarak antara mereka hanya sekitar satu batang tombak saja. Perlahan-lahan Rangga mencabut pedangnya. Seketika itu juga cahaya biru menyemburat menerangi sekitarnya. Rangga mengangkat pedang itu tinggi-tinggi di atas kepala, lalu perlahan-lahan turun ke bawah sampai mencapai dada. Kemudian, disilangkan pedang itu di depan dada. Dengan tangan kirinya, digosoknya pedang itu dari ujung ke pangkalnya.
Pada saat yang sama, Macan Gunung Sumbing juga sudah mempersiapkan satu ajiannya. Dia berdiri dengan kaki terpentang lebar ke samping. Kedua lututnya agak tertekuk. Dengan cepat digerakkan tangannya di depan dada. Dari bibirnya terdengar suara menggerung kecil yang semakin lama semakin terdengar keras bagai raungan harimau. Kedua telapak tangannya terbuka mengembang, dan menyorong ke depan.
“Hait...!”
“Aji ‘Cakra Buana Sukma’...!”
“Yaaah...!”
“Yeaaah...!”
Kedua tokoh sakti itu sama-sama melompat ke depan. Dan pada satu titik tengah, mereka bertemu. Satu ledakan keras terdengar menggelegar membuat telinga jadi tuli. Bunga api memercik ke segala arah, bercampur cahaya biru yang memancar menyelubungi sekitarnya. Telapak tangan Macan Gunung Sumbing menempel erat pada mata pedang Pendekar Rajawali Sakti yang tergenggam antara pangkal dan ujungnya.
Tampak keduanya tengah mengadu tenaga kesaktian. Masing-masing wajah sudah memerah, dan titik-titik keringat membasahi wajah dan tubuhnya. Mereka saling berdiri berhadapan dengan tangan menyatu pada pedang yang memancarkan cahaya biru membentuk bulatan seperti bola.
“Ukh! Ini tidak bisa didiamkan! Tenagaku tersedot!” dengus Macan Gunung Sumbing, langsung merasakan akibat dari aji ‘Cakra Buana Sukma’.
Sedangkan yang dirasakan Rangga lain lagi. Saat itu dia sedikit mengeluh, karena penyaluran ajiannya terasa mengalami hambatan. Ajian yang dimiliki Macan Gunung Sumbing sungguh luar biasa, sehingga mampu menghambat aliran tenaga aji ‘Cakra Buana Sukma’. Bulatan biru yang terbentuk dari pedang di tangan Rangga, berubah-ubah. Sebentar mengecil, sebentar kemudian membesar. Bahkan cahayanya kadang kala redup dan kembali berubah jadi terang menyilaukan.
“Hup...! Hiyaaa...!”
Tiba-tiba saja Macan Gunung Sumbing berteriak keras. Dan seketika itu juga didorongkan tubuhnya ke depan sedikit, lalu ditariknya kuat-kuat ke belakang. Tepat pada saat tangannya terlepas dari pedang Rangga, kakinya mendupak cepat ke dada Pendekar Rajawali Sakti. Rangga terkejut setengah mati, dan berubah melentingkan tubuhnya ke belakang. Tapi hantaman kaki Macan Gunung Sumbing tidak mungkin dihindari lagi.
“Akh...!” Rangga memekik keras.
Dan sebelum tubuh Pendekar Rajawali Sakti itu terlontar ke belakang, pedangnya sempat berkelebat cepat membabat perut Macan Gunung Sumbing. Satu raungan keras terdengar. Kedua tokoh sakti itu sama-sama terpental ke belakang, dan jatuh bergulingan di tanah. Tapi masing-masing masih mampu bangkit berdiri meskipun tubuhnya limbung.
Tampak darah mengucur deras dari perut Macan Gunung Sumbing yang koyak terbabat ujung pedang Pendekar Rajawali Sakti. Sedangkan mulut Rangga juga mengeluarkan darah. Pemuda berbaju rompi putih itu berusaha mengatur jalan napasnya yang terasa sesak seketika. Sepertinya tulang-tulang dadanya remuk.
“Graugh...!”
Tiba-tiba saja terdengar suara raungan keras dari arah lain. Tampak harimau belang sebesar anak kerbau, terjungkal bergulingan di tanah. Sedangkan Rajawali Putih terhempas membentur sebatang pohon yang sangat besar hingga hancur berantakan! Namun Rajawali Putih langsung melesat tinggi ke udara, dan segera menukik deras menyambar tubuh harimau itu yang baru saja bisa bangkit berdiri.
“Khraghk...!” Rajawali Putih memekik keras.
“Grauuughk...!”
Sungguh sukar diikuti mata biasa. Begitu cepatnya Rajawali Putih menukik, tahu-tahu cakarnya sudah menyambar harimau besar itu. Harimau itu menggerung keras, menggeliat berusaha melepaskan diri. Tapi Rajawali Putih sudah lebih dahulu melesat terbang. Dan pada saat yang baik, Macan Gunung Sumbing mengibaskan tangannya ke arah burung raksasa itu.
Sebuah pisau kecil melesat terbang dengan kecepatan bagai kilat ke arah Rajawali Putih. Sedangkan di cakarnya menggantung harimau besar yang meronta-ronta mencoba melepaskan diri sambil menggerung-gerung.
“Rajawali, awas...!” teriak Rangga memperingatkan. “Khraghk...!”
Rajawali Putih melepaskan harimau itu, dan langsung berputar di udara. Untunglah lontaran pisau kecil Macan Gunung Sumbing luput dari sasaran. Sementara itu harimau sebesar anak kerbau itu meluncur deras ke bawah. Binatang itu menggerung-gerung keras dengan kaki bergerak-gerak. Dan saat yang hampir bersamaan, Macan Gunung Sumbing melompat cepat bagaikan kilat. Langsung ditopangnya tubuh harimau belang itu, dan dibawanya turun dengan lunak.
“Khraghk!”
Rajawali Putih menukik deras hendak menyambar harimau itu kembali. Tapi belum juga maksudnya tersampaikan, Macan Gunung Sumbing sudah melompat naik ke punggung harimau itu, dan langsung berlari cepat bagaikan kilat. Cakar Rajawali Putih hanya menyambar tanah berumput hingga bergetar dan berlubang cukup besar. Rajawali Putih berkaokan marah, karena lawannya berhasil kabur dengan cepat. Sementara itu Rangga sudah duduk bersila, bersikap semadi. Rajawali Putih menghampiri sambil mengkirik perlahan.
Hanya sebentar Rangga bersemadi untuk memulihkan keadaan tubuhnya, kemudian bangkit berdiri dan memeluk kepala burung raksasa itu. Pedangnya sudah sejak tadi tersimpan di dalam warangka di balik punggung. Rangga melepaskan pelukannya pada leher burung itu ketika menangkap sosok tubuh ramping yang berdiri agak jauh di bawah pohon.
“Dewi Tanjung...,” desah Rangga.
“Kau tidak apa-apa, Kakang?” tanya Dewi Tanjung seraya berlari menghampiri Pendekar Rajawali Sakti.
“Tidak,” sahut Rangga.
Dewi Tanjung menatap burung rajawali raksasa yang berada di belakang Rangga. Dan Pendekar Rajawali Sakti itu tersenyum, lalu memperkenalkan Dewi Tanjung pada Rajawali Putih. Burung raksasa itu mengkirik perlahan sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Dewi Tanjung kembali menatap Rangga yang keadaannya tampak kusut, kotor, dan berdebu, tapi sesekali masih juga dilirik burung raksasa itu. Seumur hidupnya, baru kali ini melihat seekor burung sebesar itu.
“Bagaimana lukamu?” tanya Rangga.
“Darahnya sudah berhenti mengalir. Hanya luka biasa,” sahut Dewi Tanjung.
“Hm.... Bagaimana dia bisa tahu tempat ini, Dewi?” tanya Rangga lagi.
“Entahlah. Tahu-tahu dia muncul dan langsung menyerangku,” sahut Dewi Tanjung pelan.
“Sebaiknya kau ke Desa Weru lagi,” usul Rangga.
“Mau apa ke sana? Apa kau suka kalau aku dikeroyok, lalu dibunuh mereka?” Dewi Tanjung mendelik berang.
Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menyunggingkan senyum tipis. Wanita itu memang belum diberitahu perubahan di Desa Weru. Sekarang tidak ada lagi yang menuduh Dewi Tanjung sebagai pelaku pembantaian keji selama ini. Mereka semua sudah tahu kalau Macan Gunung Sumbing-lah pelaku utamanya. Tidak heran kalau Dewi Tanjung begitu berang mendengar usul Rangga tadi.
“Tidak ada yang menuduhmu lagi, Dewi. Mereka semua sudah tahu, kalau bukan kau yang melakukan semua pembantaian itu,” bujuk Rangga lembut
“Huh! Sudah terlambat!” dengus Dewi Tanjung memberengut.
“Tidak ada yang terlambat, Dewi.”
“Jangan paksa aku, Kakang!” sentak Dewi Tanjung cepat.
Rangga mengangkat bahunya sedikit. Gadis ini memang keras, dan tidak mudah melunakkan hatinya. Rangga bisa memahami kalau Dewi Tanjung masih kesal terhadap perbuatan penduduk Desa Weru yang main tuduh tanpa diselidiki dulu kebenarannya.
Sementara itu hari telah senja. Matahari sudah condong ke arah barat, sehingga sinarnya tidak lagi terik. Angin pun terasa sejuk membelai kulit. Rangga mengumpulkan ranting kering, dan menumpuknya di bawah pohon. Sementara Dewi Tanjung hanya duduk saja bersandar di pohon lain. Tidak jauh dari gadis itu, Rajawali Putih mendekam dengan kepala hampir menyentuh tanah. Sesekali Dewi Tanjung melirik burung rajawali raksasa itu. Meskipun sudah kenal, tapi masih juga ada perasaan takut. Betapa tidak? Meskipun Rajawali Putih hanya seekor burung, tapi perawakannya yang tinggi dan besar sungguh menakutkan orang yang baru melihatnya. Tidak terkecuali Dewi Tanjung yang baru kali ini melihat ada seekor burung raksasa sebesar itu.
“Khrrr...,” Rajawali Putih mengkirik perlahan sambil menyorongkan kepalanya pada Dewi Tanjung.
“Eh...!” Dewi Tanjung terpekik kaget, dan langsung melompat.
Rangga yang melihat kejadian itu jadi tertawa terpingkal-pingkal. Rajawali Putih mengangguk-anggukkan kepalanya dengan suara mengkirik perlahan. Pendekar Rajawali Sakti itu menghampiri Rajawali Putih, lalu memeluk mesra lehernya. Dewi Tanjung memperhatikan, namun wajahnya sedikit pucat.
“Rajawali Putih ingin lebih kenal denganmu, Dewi,” jelas Rangga lembut. “Bukankah begitu, Rajawali Putih?”
“Khrrrk...!” Rajawali Putih menganggukkan kepalanya.
Rangga menghampiri Dewi Tanjung, dan menggamit lengan gadis itu. Dengan diliputi perasaan takut dan ragu-ragu, Dewi Tanjung mengikuti Rangga yang membawanya mendekati Rajawali Putih. Gadis itu masih takut-takut juga ketika kepala burung raksasa itu menyorong ke arahnya, dan mendesak-desak tubuhnya.
Perlahan-lahan perasaan takut di hati Dewi Tanjung memudar. Dibelai-belainya kepala burung itu meskipun masih bersikap ragu-ragu. Tapi sebentar kemudian sudah terdengar tawanya yang mengikik lembut. Rangga memperhatikan sambil tersenyum. Memang tidak mudah untuk mengakrabkan diri dengan Rajawali Putih. Dan biasanya, Rajawali Putih enggan untuk bercanda dengan orang lain selain Rangga. Tapi dengan Dewi Tanjung, Rajawali Putih menjadi cepat akrab. Hal ini membuat Rangga heran juga. Tapi hal itu tidak ingin dipikirkan lebih jauh lagi.
Sementara malam mulai merayap dan diliputi kegelapan. Rangga menyalakan api dari ranting-ranting kering yang dikumpulkannya. Dewi Tanjung duduk bersandar pada tubuh Rajawali Putih, sedangkan Rangga membalik-balik kelinci panggang yang telah ditangkapnya. Ada enam ekor kelinci, dan yang dua sudah masuk ke perut Rajawali Putih.
“Khraghk...!” Rajawali Putih berkaokan, dan berdiri.
Dewi Tanjung menggeser duduknya. Rajawali Putih itu menggaruk paruhnya ke tanah, kemudian
membumbung tinggi ke atas. Dewi Tanjung memperhatikan sebentar, sedangkan Rangga tetap asyik dengan kelinci-kelinci panggangnya. Gadis itu segera menggeser mendekati Pendekar Rajawali Sakti itu.
“Mau ke mana dia?” tanya Dewi Tanjung setengah berbisik.
“Meronda,” sahut Rangga kalem.
“Meronda...?”
“Iya. Kalau terjadi apa-apa di Desa Weru, dia pasti ke sini memberitahu.”
Dewi Tanjung terdiam. Diambilnya satu kelinci panggang yang sudah matang, dan disantapnya dengan nikmat. Tapi sebentar kemudian kembali ditatapnya Rangga yang juga mulai menikmati santapannya. Santapan yang sudah tidak asing lagi, dan selalu dinikmati di setiap pengembaraannya. Rangga memang suka sekali daging kelinci. Makanya selalu diburunya binatang itu untuk dijadikan santapan.
“Kau beruntung punya piaraan rajawali,” kata Dewi Tanjung.
“Rajawali Putih bukan peliharaanku. Dia adalah guruku, orang tuaku, teman sekaligus saudaraku,” Rangga menjelaskan tanpa ada perasaan tersinggung. Rajawali Putih memang tidak pernah dianggap hanya sebagai seekor binatang.
“Sudah berapa lama kau bersamanya?”
“Sejak kecil. Dialah yang membimbingku dan memberiku ilmu-ilmu kepandaian. Yaaah..., memang terlalu banyak yang diberikannya padaku. Dan aku sendiri tidak akan bisa berpisah dengannya. Bagiku, Rajawali Putih adalah segala-galanya. Bahkan lebih berharga daripada nyawaku sendiri.”
“Aku kagum padamu, Kakang,” puji Dewi Tanjung tulus.
“Simpan saja rasa kagummu itu. Dewi,” desah Rangga pelan.
Mereka tidak bicara lagi, dan terus menikmati santapan kelinci panggang. Rangga memang lebih senang diam, tapi otaknya terus bekerja mencari jalan untuk dapat melenyapkan Macan Gunung Sumbing. Masalahnya, dunia akan hancur kalau tokoh hitam itu lebih lama lagi hidup di dunia. Saat ini, mungkin hanya Pendekar Rajawali Sakti saja yang mampu menandingi kepandaiannya. Dan itu pun kelihatannya seimbang. Rangga sendiri tidak bisa meramalkan, apakah mampu membinasakan manusia iblis itu atau malah dirinya sendiri yang akan binasa?
********************
TUJUH
Malam terus merambat semakin larut. Di sebuah tempat yang tidak berapa jauh dari Desa Weru, tampak Macan Gunung Sumbing duduk bersila bersikap semadi di atas sebongkah batu besar yang pipih. Di sampingnya mendekam harimau belang yang luar biasa besarnya. Luka di perut Macan Gunung Sumbing masih membekas, meskipun tidak lagi mengeluarkan darah.
Perlahan-lahan kelopak mata Macan Gunung Sumbing terbuka, dan langsung menoleh ke arah sepasang mata merah di sampingnya. Harimau itu menjulurkan kepala, dan menjilati wajah majikannya. Macan Gunung Sumbing menepuk-nepuk leher binatang itu, kemudian memandang lurus ke arah Desa Weru. Dari tempat yang cukup tinggi ini, bisa terlihat jelas desa itu.
“Malam ini kita bantai semua penduduk Desa Weru! Jangan ada yang tersisakan satu pun juga. Setelah itu kita cepat ke Gunung Opak. Hm..., Ki Raga harus mampus setelah adiknya. Setelah itu baru kita hadapi kembali si Jahanam Rajawali Sakti!” gumam Macan Gunung Sumbing menggeram.
“Grrrh...!” harimau belang itu menggerung perlahan, seakan menyetujui rencana majikannya.
“Kita akan menguasai dunia persilatan, Belang. Kalau Pendekar Rajawali Sakti sudah mampus, tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Huh! Hanya dia satu-satunya penghalangku, dan harus mampus secepatnya. Bagaimana, Belang?”
“Grrrh...!” harimau yang dipanggil Belang itu hanya menggerung saja.
“Ya! Memang dialah satu-satunya penghalang kita. Kau punya saran, Belang?”
Harimau belang itu diam dan pandangannya luruh ke depan. Sepasang bola matanya menyala. Terdengar gerungan yang perlahan dan panjang. Macan Gunung Sumbing melompat turun dari batu yang didudukinya. Diarahkan pandangannya ke arah yang sama dengan pandangan si Belang.
“Ayo, Belang. Kita hancurkan seluruh penduduk Desa Weru,” ajak Macan Gunung Sumbing. “Malam ini, Desa Weru harus musnah!”
“Grauuugh...!”
“Ha ha ha...! Ayo kita berlomba membantai mereka, Belang!”
“Aaauuum...!” Macan Gunung Sumbing langsung melompat ke punggung harimau belang itu. Seketika itu juga binatang itu langsung melesat cepat bagai kilat. Begitu cepatnya melompat, sehingga dalam waktu sebentar saja sudah lenyap ditelan kegelapan malam. Tujuan mereka jelas, Desa Weru yang saat ini dicekam ketakutan. Desa yang kini bagaikan desa mati tanpa penduduk.
Tidak ada yang tahu kalau Macan Gunung Sumbing akan menghancurkan desa itu. Bahkan tidak ada yang tahu kalau di angkasa, Rajawali Putih melayang-layang mengawasi keadaan. Pandangan mata Rajawali Putih langsung tertuju ke arah selatan. Di situ terlihat satu bayangan bergerak cepat menuju ke arah Desa Weru. Bayangan yang tidak lain dari si Belang yang ditunggangi Macan Gunung Sumbing.
“Khraaaghk...!”
Rajawali Putih langsung melesat ke arah utara. Cepat sekali melesat, bagaikan kilat saja. Sebentar saja burung itu sudah tiba di tempat Rangga dan Dewi Tanjung berada. Rajawali Putih langsung menukik turun sambil memperdengarkan suaranya yang serak dan keras. Rangga menggerinjang bangkit berdiri. Diikuti Dewi Tanjung. Mereka langsung menghampiri Rajawali Putih yang sudah mendarat di tanah.
“Ada apa, Rajawali?” tanya Rangga.
“Khraghk...!” Rajawali Putih mengepakkan sayapnya, dan kepalanya menoleh ke arah Desa Weru.
“Dewi! Matikan api, dan kita langsung ke Desa Weru,” kata Rangga.
Belum lagi Dewi Tanjung sempat bertanya, Rangga sudah melompat naik ke punggung Rajawali Putih. Dan seketika itu juga....
“Khraghk...!”
Rajawali Putih langsung melesat membumbung tinggi ke angkasa. Begitu cepat lesatannya, tahu-tahu sudah lenyap dari pandangan. Dewi Tanjung masih terpaku sesaat, kemudian bergegas mematikan api, dan segera menuju ke Desa Weru.
********************
Saat itu Macan Gunung Sumbing sudah tiba di Desa Weru. Langsung dipilihnya rumah yang kelihatan gelap. Hanya sebuah pelita kecil yang menyala di bagian ruangan depan rumah itu. Cahayanya yang redup menyemburat melalui lubang-lubang di atas pintu dan jendela. Macan Gunung Sumbing melompat turun dari punggung harimaunya. Perlahan-lahan kakinya melangkah mendekati rumah itu. Harimau besar perlahan-lahan mengikuti dari belakang. Langkah kaki mereka begitu ringan, sehingga tidak menimbulkan suara sedikit pun.
Macan Gunung Sumbing menghentakkan tangannya secara tiba-tiba ke depan. Satu angin dorongan yang kuat mendobrak pintu rumah itu. Seketika terdengar jeritan dari dalam rumah yang saling susul. Macan Gunung Sumbing langsung lompat masuk ke dalam rumah, disusul harimau peliharaannya.
“Ghrauuugh...!”
“Aaa...!”
“Ha ha ha...!”
Macan Gunung Sumbing tertawa terbahak-bahak. Jari-jari tangannya mengembang kaku, dan bergerak cepat mencabik-cabik penghuni rumah. Harimau belang juga tidak ketinggalan. Dia berpesta mengoyak tubuh-tubuh yang tidak berdaya. Jeritan-jeritan melengking semakin sering terdengar.
Tidak lama peristiwa itu berlangsung. Sebentar saja telah senyap kembali. Yang terdengar kini hanya raungan harimau disertai tawa terbahak-bahak. Suara itu membuat rumah-rumah di sekitarnya langsung menyalakan lampu. Dan pada saat itu, Macan Gunung Sumbing melompat keluar dari dalam rumah, disusul si Belang. Mereka terus menerobos sebuah rumah lagi yang berada tidak jauh dari situ.
Kembali terdengar jeritan-jeritan melengking menyayat hati, bercampur baur suara tawa bergelak dan raungan harimau. Macan Gunung Sumbing benar-benar melaksanakan niatnya, membantai habis seluruh penduduk Desa Weru. Dendamnya pada Paman Waku dilampiaskan pada orang-orang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Pelampiasan dendamnya benar-benar brutal.
Dan semua itu terjadi karena mendapat hambatan dari Pendekar Rajawali Sakti. Suatu kemarahan berlumur dendam yang tidak terbendung lagi. Jerit-jerit menyayat terus terdengar dari rumah ke rumah. Dalam waktu yang tidak lama, sudah lima rumah didatangi Macan Gunung Sumbing. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Semuanya tewas dengan tubuh tercabik cakar-cakar harimau.
“He he he...!” Macan Gunung Sumbing terkekeh melihat korban pada rumah yang keenam.
“Graughk...!”
Sekali lagi Macan Gunung Sumbing memandangi mayat-mayat yang tergeletak dengan tubuh hancur tercabik, kemudian tertawa terkekeh. Dengan langkah tenang, dia berjalan keluar dari rumah itu. Tapi mendadak suara tawanya terhenti. Di depan rumah itu ternyata sudah berdiri puluhan orang yang membawa senjata seadanya. Mereka adalah penduduk Desa We-ru. Tampak di depan berdiri Paman Waku yang bersenjatakan golok panjang terhunus.
Tempat sekitarnya sudah terang benderang oleh obor yang dipancangkan di beberapa sudut. Beberapa penduduk juga ada yang membawa obor dari bambu. Paman Waku melangkah beberapa tindak, didampingi Bakor yang memimpin Padepokan Gunung Opak. Kakak dari Paman Waku itu menimbang-nimbang senjatanya yang berbentuk tombak dengan mata berkeluk seperti keris.
“Lihat, Belang. Mereka sudah siap menjemput ajal. He he he...,” ujar Macan Gunung Sumbing kembali terkekeh.
“Bukan mereka, tapi kau!” bentak Paman Waku.
“Ha ha ha...!” Macan Gunung Sumbing tertawa terbahak-bahak.
“Aku tahu, kau dendam padaku. Tapi mengapa kau bantai mereka yang tidak tahu apa-apa?! Perbuatanmu sungguh keji! Dewata akan mengutukmu, Macan Gunung Sumbing!” geram Paman Waku.
“Sebenarnya aku enggan mengotori tangan dengan darah mereka. Tapi, bukankah kau sendiri yang menginginkan demikian, Waku?” dingin nada suara Macan Gunung Sumbing.
“Jangan banyak omong! Ayo, kita selesaikan persoalan ini! Kau atau aku yang mampus!” bentak Paman Waku seraya menyilangkan goloknya di depan dada.
“He he he...,” Macan Gunung Sumbing terkekeh. Ditepuk-tepuknya harimau yang berdiri di sampingnya.
Si Belang menggeram perlahan. Dia bergerak maju seperti binatang malas karena kekenyangan. Namun tatapan matanya begitu tajam menusuk langsung ke bola mata Paman Waku. Laki-laki setengah baya itu menggeser kakinya selangkah ke samping kanan. Sedangkan si Belang mendekam.
“Auuummm...!”
Tiba-tiba saja si Belang mengaum keras, dan langsung melompat cepat bagaikan kilat. Kedua kaki depannya terentang lurus ke depan. Kuku-kuku yang tajam berkilat siap merobek tubuh Paman Waku. Untuk sesaat, Paman Waku terkesiap. Namun, dengan cepat dibanting dirinya ke samping, dan bergulingan beberapa kali.
Gagal serangan pertama, si Belang langsung berbalik dan kembali melompat menerjang. Saat itu Paman Waku baru saja bisa berdiri. Buru-buru dikibaskan goloknya yang panjang sambil melompat ke kanan. Kibasan golok itu tepat menghantam perut si Belang. Namun harimau itu hanya menggerung kecil.
“Gila...!” dengus Paman Waku.
“Ha ha ha...!” Macan Gunung Sumbing tertawa terbahak-bahak.
Harimau itu berdiri tegak di atas keempat kakinya. Sedikit pun tidak terdapat luka di tubuhnya. Padahal, jelas sekali kalau golok Paman Waku menghantam perut binatang itu.
“Kau tidak akan mampu mengalahkannya, Waku! Temanku ini kebal,” kata Macan Gunung Sumbing diiringi suara tawanya.
Paman Waku mendengus berat. Kakinya bergerak perlahan menggeser menyusur tanah. Tatapannya tidak berkedip pada binatang buas itu.
“Dua puluh tahun lalu kau boleh bangga karena dapat mengalahkanku, Waku. Memang itu semua kesalahanku, tidak membawa sahabat saktiku ini. Tapi sekarang, jangan harap kau dapat mengalahkanku. Aku bukan lagi yang dulu. Kau akan mati, Waku! Ha ha ha...!” Macan Gunung Sumbing terus mengejek.
“Persetan! Hiyaaa...!”
Paman Waku geram bukan main. Telinganya panas mendengar ejekan itu. Dia langsung melompat ke arah Macan Gunung Sumbing yang masih terkekeh. Tapi sebelum laki-laki setengah baya itu bisa mengibaskan goloknya, si Belang sudah lebih dulu melompat cepat menerjangnya.
“Graugh!”
“Akh...!”
Paman Waku terhuyung-huyung sambil mendekap lambung kanannya. Kuku-kuku si Belang telah merobek cukup dalam dan panjang pada lambung kanannya. Darah mengucur deras tak tertahankan lagi. Dan pada saat Paman Waku limbung, si Belang sudah melompat lagi hendak menerkam.
“Aaauuum...!”
“Mati aku...!” desah Paman Waku dalam hati.
Tapi sebelum harimau itu mencapai tubuh Paman Waku, tiba-tiba Bakor melemparkan tombaknya ke arah harimau itu. Ujung tombak yang berbentuk seperti keris itu tepat menghunjam dada si Belang. Tapi sungguh menakjubkan, tombak itu malah terpental balik tanpa melukai harimau itu sedikit pun.
Bakor melompat menangkap tombaknya yang terpental kembali, dan langsung mendarat di depan adiknya yang terluka di bagian lambungnya. Macan Gunung Sumbing menggeram marah melihat musuh bebuyutannya masih terlindungi. Dia tahu betul siapa orang yang kini berdiri di depan Paman Waku.
“Aku paling benci melihat kelicikan. Membunuh orang yang sudah tidak berdaya!” dingin, kata-kata Bakor.
“Menyingkirlah, Bakor! Giliranmu nanti!” dengus Macan Gunung Sumbing. Sementara si Belang mendekam kembali di sampingnya.
“Nanti atau sekarang sama saja! Sengaja aku datang agar kau tidak mengotori tempat suciku!” sahut Bakor semakin dingin. “Akulah lawanmu, iblis!”
Setelah berkata demikian, Bakor langsung melompat seraya menusukkan tombaknya ke arah dada Macan Gunung Sumbing. Tapi serangan yang cepat disertai pengerahan tenaga dalam itu, manis sekali dielakkan Macan Gunung Sumbing. Bahkan laki-laki yang wajahnya sudah mirip harimau itu mampu memberikan serangan balasan yang juga luput dari sasaran.
Sementara Paman Waku bergerak mundur. Darah semakin banyak keluar dari lukanya. Dan pertarungan antara Bakor melawan Macan Gunung Sumbing tidak dapat dihentikan lagi. Harimau belang itu juga menyingkir. Tapi tatapannya tertuju pada pertarungan itu.
Tidak jauh dari tempat itu, terlihat Argayuda dan Ki Gedag. Mereka juga tampaknya sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Macan Gunung Sumbing memang tokoh hitam yang sangat tinggi tingkat kepandaiannya. Tidak mudah menaklukkan laki-laki berwajah seperti harimau itu.
“Hiyaaa...!”
“Yeaaah...!”
Pertarungan antar Bakor melawan Macan Gunung Sumbing sudah mencapai tingkat yang tinggi. Mulai kelihatan kalau Bakor sudah terdesak. Beberapa kali pukulan dan tendangan Macan Gunung Sumbing mendarat di tubuhnya. Tapi Bakor masih juga mampu melawan.
“Jebol dadamu! Hiyaaa...!”
Sambil berteriak keras, Macan Gunung Sumbing melompat cepat, dan tangan kanannya menggedor dada Bakor.
“Aaakh...!” Bakor menjerit keras.
Seketika tubuhnya terpental ke belakang. Dan belum lagi mencapai tanah, Macan Gunung Sumbing kembali menerjang seraya mengibaskan tangan kanannya. Tak pelak lagi, jari yang berkuku hitam dan runcing itu merobek dada Bakor. Kembali laki-laki setengah baya itu menjerit keras. Darah langsung menyembur keluar dari dada yang sobek panjang!
Dan belum sempat ada yang menyadari, kembali Macan Gunung Sumbing mengibaskan tangan kanannya. Kali ini sasarannya adalah bagian leher. Bakor yang sudah tidak berdaya, tidak mampu berkelit lagi. Tanpa bersuara sedikit pun, tubuh laki-laki setengah baya itu ambruk ke tanah dengan leher terpenggal!
“Iblis...!” geram Paman Waku menyaksikan kematian kakaknya yang sangat tragis.
“Ha ha ha...!” Macan Gunung Sumbing tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan.
“Kubunuh kau, keparat!” geram Paman Waku.
Tanpa menghiraukan luka di tubuhnya, Paman Waku segera melompat menyerang sambil mengibaskan goloknya yang panjang. Tapi pada saat itu, si Belang juga sudah lebih cepat melompat. Cakarnya pun menyampok cepat bagaikan kilat. Paman Waku terperanjat, namun tidak bisa menghindar lagi.
“Akh...!” Paman Waku memekik tertahan.
Sampokan cakar harimau itu merobek wajahnya. Darah langsung menyembur. Paman Waku terhuyung-huyung sambil menutupi wajahnya dengan tangan kiri. Pada saat itu, harimau besar peliharaan Macan Gunung Sumbing sudah kembali melompat hendak menerjangnya.
“Ghraaaughk...!”
“Hiyaaa...!”
Dug!
********************
DELAPAN
Tepat pada saat yang sangat kritis itu, tiba-tiba sebuah bayangan putih berkelebat cepat bagaikan kilat, dan langsung menyambar tubuh si Belang. Harimau besar itu meraung keras, lalu terpelanting ke tanah. Tampak seorang gadis muda dan cantik tahu-tahu sudah berdiri tegak melindungi Paman Waku.
“Dewi Tanjung...!” desis Macan Gunung Sumbing geram saat mengenali gadis cantik berbaju putih yang sedikit koyak itu.
“Hm.... Saatnya kau terbang ke neraka. Macan Iblis!” dengus Dewi Tanjung dingin.
Saat itu dua orang penduduk menghampiri Paman Waku dan membawanya menyingkir. Darah masih mengucur di tubuh dan wajah laki-laki tua itu. Dewi Tanjung sempat melirik Paman Waku yang sudah berada di tempat aman bersama beberapa penduduk yang merawat luka-lukanya.
Pada saat itu Ki Gedag dan Argayuda melompat mendekati Dewi Tanjung. Kedua laki-laki itu langsung menghunus senjatanya. Macan Gunung Sumbing tersenyum sinis melihat ketiga orang penantangnya, kemudian tertawa terbahak-bahak sambil mengegoskan tangannya ke depan.
“Auuummm...!”
Sambil mengaum keras, si Belang langsung melompat menerjang ketiga orang itu. Ki Gedag dan Argayuda berlompatan ke samping, sedangkan Dewi Tanjung malah diam berdiri tegak. Dan begitu harimau sebesar anak kerbau itu berada dalam jangkauan, dengan cepat dikibaskan pedangnya.
Harimau itu hanya meraung kecil begitu pedang Dewi Tanjung menghantam tubuhnya. Binatang itu terjajar sedikit, lalu kembali menerjang lebih ganas. Dewi Tanjung berlompatan menghindari terjangan binatang buas itu. Beberapa kali pedangnya dihantamkan ke tubuh si Belang, tapi harimau itu tidak terluka sedikit pun. Kulitnya sungguh kebal, tidak mempan senjata apa pun juga!
Sementara Argayuda dan Ki Gedag sudah bertarung mengeroyok Macan Gunung Sumbing. Golok mereka berkelebatan cepat mengurung tubuh Macan Gunung Sumbing, tapi tokoh sakti itu tidak mudah didesak. Bahkan satu ketika dia berhasil menyarangkan cakarnya pada dada Ki Gedag, sehingga laki-laki tua itu menjerit keras terhuyung-huyung ke belakang. Darah mengucur deras dari dadanya yang koyak.
“Ki...!” seru Argayuda cemas.
Keterkejutan Argayuda tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja telah menjerit melengking. Macan Gunung Sumbing telah menyampok kepalanya, sehingga pemuda itu terpental jauh. Tubuhnya terus meluncur, lalu menabrak dinding rumah hingga jebol berantakan. Namun Argayuda bergegas bangkit dan melompat menerjang manusia berwajah harimau itu.
“Nekad...!” dengus Macan Gunung Sumbing.
Cepat sekali Macan Gunung Sumbing mengibaskan tangannya, langsung mengoyak leher Argayuda hingga hampir buntung. Argayuda memekik melengking tinggi. Sebentar tubuhnya bergetar, lalu ambruk berkelojotan di tanah. Darah mengucur deras membasahi tanah. Tidak berapa lama berkelojotan, sebentar kemudian diam tidak bergerak-gerak lagi!
“Setan keparat! Kubunuh kau!” geram Ki Gedag.
“He he he.... Orang tua bodoh! Sebaiknya kupercepat kematianmu. Hih...!”
Macan Gunung Sumbing melompat ke atas, lalu menukik keras menuju ke kepala Ki Gedag. Hanya sekali Ki Gedag mampu mengibaskan pedangnya ke atas. Namun, saat-saat berikut, tubuhnya sudah terangkat, dan kembali jatuh dengan kepala terpisah. Tubuh tanpa kepala itu bergerak-gerak sebentar, lalu diam tanpa nyawa lagi. Macan Gunung Sumbing mendarat manis sambil menenteng kepala Ki Gedag. Dilemparkannya kepala itu seperti kelapa busuk yang tidak berguna ke arah penduduk Desa Weru.
Melihat tetua-tetua desa bergelimpangan jadi mayat, para penduduk itu berlarian menyelamatkan diri. Tapi Macan Gunung Sumbing tidak membiarkan begitu saja. Dia memang sudah terlalu membenci mereka yang berusaha mengeroyoknya. Dengan cepat tubuhnya melesat sambil mengibaskan tangannya. Dua orang penduduk menjerit melengking, lalu ambruk bersimbah darah.
“Jangan lari kalian! Hiyaaat...!”
Macan Gunung Sumbing melompat mengejar penduduk yang berlarian tak tentu arah sambil berteriak-teriak minta tolong. Dan pada saat tangannya hampir menjangkau salah seorang penduduk, mendadak dari angkasa meluruk deras sebuah bayangan besar. Bayangan itu langsung menyampok Macan Gunung Sumbing hingga terpelanting bergulingan di tanah.
“Keparat! Monyet buduk...!” Macan Gunung Sumbing menyumpah serapah seraya bangkit berdiri.
“Tidak ada gunanya kau membantai mereka, Macan Gunung Sumbing!” terdengar suara dingin dan datar.
“Pendekar Rajawali Sakti.... Phuih!” Macan Gunung Sumbing mendesis geram.
Sementara itu di tempat lain, Dewi Tanjung masih berusaha menghadapi harimau yang besar dan kebal. Gadis itu nampak kewalahan, tapi terus berusaha keras mempertahankan nyawanya. Rangga sempat melirik ke arah pertarungan ganjil dan tidak seimbang itu. Dewi Tanjung memang sudah jatuh bangun dan tubuhnya berlumuran darah. Entah sudah berapa kali kulitnya tersayat cakaran binatang buas itu.
“Dewi Tanjung, mundur...!” seru Rangga keras.
Tepat ketika Dewi Tanjung melompat mundur, dari angkasa meluruk seekor burung rajawali raksasa berbulu putih agak keperakan. Cakar rajawali itu langsung menyambar harimau belang yang terus menggeram. Namun harimau itu dengan gesit mengelak, lalu mengaum keras sambil menggaruk-garuk tanah di depannya.
“Rajawali, hadapi dia! Kau lebih tahu caranya!” seru Rangga keras.
“Khraghk...!”
Sementara itu Macan Gunung Sumbing mengumpat, menyumpah serapah atas munculnya Pendekar Rajawali Sakti bersama burung raksasa tunggangannya.
“Phuih! Orang lain boleh takut padamu, Pendekar Rajawali Sakti.”
Sambil terus menyumpah, Macan Gunung Sumbing langsung menyerang. Dia memang baru dua kali bentrok dengan pendekar yang selalu memakai baju rompi putih itu. Makanya, kini dia tidak mau tanggung-tanggung lagi. Laki-laki yang wajahnya penuh brewok itu melompat sambil mengerahkan jurus andalannya.
Dan Rangga yang juga sudah mengukur kepandaian lawannya, langsung mencabut Pedang Rajawali Sakti. Seketika malam yang hanya diterangi beberapa obor, menjadi terang benderang begitu Pedang Rajawali Sakti keluar dari warangkanya.
Secepat Macan Gunung Sumbing menerjang, secepat itu pula Pendekar Rajawali Sakti melompat dibarengi pengerahan jurus ‘Pedang Pemecah Sukma’. Gerakan pedangnya sungguh cepat luar biasa, sehingga sulit diikuti pandangan mata. Dan sabetan pedang itu hampir saja memenggal leher Macan Gunung Sumbing, kalau tidak cepat-cepat membanting tubuhnya ke tanah dan bergulingan menjauh.
“Keparat!” geram Macan Gunung Sumbing seraya bangkit berdiri.
Sedangkan Rangga berdiri tegak, dan pedangnya tersilang di depan dada. Tatapan matanya begitu tajam menusuk dengan bibir terkatup rapat.
“Hhh! Rupanya kau takut mati juga, macan ompong!” ejek Rangga sinis.
“Phuih!” Macan Gunung Sumbing menyemburkan ludahnya. Wajahnya merah padam menahan amarah mendengar ejekan yang membuat panas telinganya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Macan Gunung Sumbing mempersiapkan ajian pamungkasnya. Dan Rangga yang melihat lawannya tidak main-main lagi, segera mempersiapkan aji ‘Cakra Buana Sukma’. Kedua ajian itu pernah dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Saat itu kekuatan ajian mereka seimbang. Tapi entah untuk kali ini. Hanya merekalah yang bisa menentukan dari pertarungan antara hidup dan mati!
Sesaat mereka saling berdiri dengan tatapan kosong, seakan tengah mengukur ajian yang tinggal dilepaskan saja. Cahaya biru sudah mulai menggulung di ujung pedang, sedangkan kedua telapak tangan Macan Gunung Sumbing sudah merah membara bagai terbakar. Hawa panas menyebar dari telapak tangan yang memerah itu.
“Bersiaplah untuk mati, Pendekar Rajawali Sakti!” dingin nada suara Macan Gunung Sumbing.
“Bertobatlah sebelum terbang ke neraka, macan ompong!” sambut Rangga tidak kalah dinginnya.
“Hih! Hiyaaat..!”
“Yeaaah...!”
Macan Gunung Sumbing berlari kencang dengan kedua tangan menjulur ke depan. Sedangkan Rangga menyilangkan pedangnya, dan telapak tangan kiri ditempelkan pada ujung pedangnya. Sedikit pun dia tidak bergerak. Memang aji ‘Cakra Buana Sukma’ bersifat menyerang, tapi menunggu untuk diserang. Suatu benturan keras tak dapat dihindari lagi, sehingga menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat! Itu pun masih disertai percikan bunga api yang dipadu dengan menggumpalnya dua sinar yang menjadi satu.
“Ukh!”
Meskipun sudah pernah bertarung sebelumnya, tapi Macan Gunung Sumbing masih terperanjat juga ketika kedua telapak tangannya menempel erat pada mata pedang Pendekar Rajawali Sakti. Padahal pedang itu tidak digenggamnya. Macan Gunung Sumbing berusaha melepaskan tangannya, tapi dirasakan adanya satu kekuatan yang menyedot tenaganya. Semakin kuat dikerahkan tenaganya, semakin kuat pula aliran itu menguasai dirinya.
“Hih! Hiyaaa...!”
Macan Gunung Sumbing meliukkan tubuhnya, dan kakinya melayang deras disertai pengerahan tenaga dalam penuh ke arah perut Pendekar Rajawali Sakti. Namun tanpa diduga sama sekali, Rangga menyentakkan tangannya cepat-cepat. Seketika tubuh Macan Gunung Sumbing terlontar jauh, sehingga tendangannya hanya sia-sia saja.
Dan selagi tubuh laki-laki berwajah penuh brewok itu terlontar, dengan cepat Rangga melompat memburunya. Langsung saja dikerahkan jurus ‘Pedang Pemecah Sukma’. Pedang bercahaya biru itu dikibaskan dengan cepat ke arah leher Macan Gunung Sumbing.
“Hiyaaat...!”
“Uts!”
Macan Gunung Sumbing buru-buru melentingkan tubuhnya berputar di udara, sehingga tebasan pedang Pendekar Rajawali Sakti tidak mencapai sasaran. Namun pada saat yang sama, Rangga telah lebih cepat menghunjamkan satu pukulan tangan kiri disertai pengerahan tenaga dalam sempurna.
Dug!
Pukulan itu tidak terbendung lagi, dan telak menghantam bagian lambung Macan Gunung Sumbing.
“Ughk..!” keluh Macan Gunung Sumbing. Keras sekali tubuhnya mencelat menghantam sebatang pohon beringin hingga tumbang. Tapi hebatnya, Macan Gunung Sumbing langsung bangkit berdiri meskipun bibirnya meringis merasakan sakit pada lambung.
“Saatmu sudah tiba, Macan Gunung Sumbing!” desis Rangga dingin.
Seketika itu juga Rangga menghentakkan tangan kirinya. Maka secercah cahaya biru meluncur deras dari telapak tangan kiri yang terbuka. Begitu cepatnya cahaya itu meluruk, sehingga Macan Gunung Sumbing yang baru saja mampu berdiri, tidak dapat mengelak lagi. Tubuhnya langsung terselubung cahaya biru berkilauan itu.
Laki-laki mirip harimau itu menggeliat-geliat sambil berteriak-teriak keras. Dan pada suatu ketika, teriakannya berubah menjadi raungan dahsyat bagai raungan harimau. Tampak dalam selubung cahaya biru itu, tubuh Macan Gunung Sumbing berkelojotan. Sesaat kemudian seluruh tubuhnya tumbuh bulu kuning belang hitam kecoklatan. Kedua bola matanya membulat dan berwarna merah bagai sepasang bola api.
“Ghraaagh...!”
Sambil meraung keras, Macan Gunung Sumbing menghentakkan tangannya ke atas. Seketika itu juga cahaya biru yang menyelubungi tubuhnya, lenyap disertai ledakan dahsyat menggelegar. Rangga melompat mundur begitu melihat Macan Gunung Sumbing berubah jadi manusia setengah harimau!
“Ghraaaghk...!” Macan Gunung Sumbing meraung dahsyat sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas kepala.
Kemudian tangannya memukul-mukul dadanya sendiri yang ditumbuhi bulu lebat, bagai bulu harimau. Seluruh tenaga, kaki, wajah dan tubuhnya telah berbulu. Macan Gunung Sumbing benar-benar telah berubah menjadi makhluk setengah harimau!
Pada saat itu, dalam waktu yang bersamaan, keanehan juga terjadi pada harimau yang tengah bertarung melawan Rajawali Putih. Harimau besar itu meraung keras, kemudian langsung melompat mendekati Macan Gunung Sumbing. Sungguh sukar dipercaya! Harimau itu mengangkat kedua kaki depannya, dan perlahan-lahan tubuhnya menyatu dengan tubuh Macan Gunung Sumbing. Harimau itu lenyap. Dan kini Macan Gunung Sumbing benar-benar berubah menjadi seekor harimau yang sangat besar luar biasa! Meskipun tidak berdiri dengan empat kakinya, tapi bentuk tubuhnya benar-benar berubah menjadi harimau. Hanya bagian tangannya saja yang masih berbentuk tangan manusia, meskipun berbulu lebat.
“Gila! Ilmu apa yang dipakainya...!?” desis Rangga tidak percaya dengan penglihatannya sendiri.
“Ghraughk...! Kau harus mampus, Pendekar Rajawali Sakti! Tidak ada yang mampu menandingi ilmu ‘Siluman Harimau’ku!” suara Macan Gunung Sumbing terdengar serak dan agak parau.
Sambil menggerung dahsyat, Macan Gunung Sumbing yang sudah berubah ujud itu langsung melompat menerjang Pendekar Rajawali Sakti. Sejenak Rangga masih terpana setengah tidak percaya, tapi buru-buru melompat ke samping menghindari terjangan itu. Namun tanpa diduga sama sekali, Macan Gunung Sumbing mampu berputar meskipun dalam keadaan tubuh di udara, dan langsung menerjang Rangga.
“Akh!” Rangga memekik tertahan.
Terjangan Macan Gunung Sumbing tidak dapat dielakkan lagi. Tangannya yang berbulu lebat, dahsyat sekali menyampok tubuh Rangga. Akibatnya, Pendekar Rajawali Sakti itu mental, melayang tinggi ke angkasa. Dan pada saat itu, Rajawali Putih melesat mengejar. Dengan manisnya Rangga hinggap di punggung Rajawali Putih itu.
“Khraghk...!”
“Aku tidak apa-apa, hanya sedikit sesak,” jelas Rangga seraya mengebutkan pedangnya tiga kali di depan wajahnya.
Rajawali Putih menukik deras ke arah Macan Gunung Sumbing yang menggerung-gerung dahsyat. Dengan sayapnya, burung itu menyampok tubuh berwujud harimau itu. Kibasan yang cepat dan bertenaga luar biasa itu membuat Macan Gunung Sumbing terpental ke belakang. Dan pada saat tubuhnya menghantam tembok batu, Rangga melompat bagaikan kilat seraya mengibaskan pedang pusakanya.
“Hiyaaat...!”
“Graughk...!”
Tebasan yang disertai pengerahan tenaga dalam sempurna itu tidak dapat dihindari lagi. Mata pedang yang berwarna biru menghantam dada Macan Gunung Sumbing. Suara raungan keras terdengar menggelegar. Dan tubuh Macan Gunung Sumbing kembali terpental ke belakang hingga menghantam rumah. Rumah itu hancur berantakan mengubur manusia harimau itu!
“Aaarghk...!”
“Gila...!”
Rangga terkesiap melihat Macan Gunung Sumbing kembali bangkit menyibakkan reruntuhan rumah yang menimbunnya. Tidak ada luka sedikit pun pada tubuhnya. Padahal tadi jelas terlihat kalau pedang Pendekar Rajawali Sakti yang terkenal dahsyat telah menghantam dadanya.
“Hhh! Aku tidak tahu lagi, bagaimana harus mengalahkannya,” desah Rangga dalam hati.
Pendekar Rajawali Sakti itu menggeser kakinya ke kanan dua tindak. Dan Macan Gunung Sumbing pun sudah melangkah menghampiri sambil menggerung-gerung menahan marah. Sepasang bola matanya merah menyala bagai bola api.
“Ayo! Maju kau, iblis!” dengus Rangga seraya menggerak-gerakkan pedangnya.
“Ghraughk...!”
Macan Gunung Sumbing menggerung dahsyat, dan tiba-tiba saja menerjang cepat bagaikan kilat ke arah Pendekar Rajawali Sakti. Rangga yang sudah siap sejak tadi, langsung melompat ke atas melewati kepala manusia harimau itu. Dengan cepat dibabatkan pedangnya ke kepala manusia harimau itu.
Tebasan itu tepat menghantam kepala Macan Gunung Sumbing, tapi tidak mencederai sedikit pun. Bahkan dalam keadaan masih di udara, Macan Gunung Sumbing berbalik, dan langsung menyerang kembali. Buru-buru Rangga meluruk turun disertai kibasan pedangnya. Kali ini dibabatkannya ke arah kaki, tapi juga tidak membawa hasil.
Dua kali Rangga bergulingan di tanah, dan bergegas bangkit berdiri. Pada saat itu Macan Gunung Sumbing sudah menyerang kembali lebih ganas. Rangga berdiri tegak, dan segera memasukkan Pedang Rajawali Sakti ke dalam warangka di punggung. Rasanya memang tidak ada gunanya lagi menggunakan pedang itu. Kini ditunggunya serangan harimau itu.
Semua orang yang melihat, pasti akan menduga kalau Rangga sudah pasrah menerima kematiannya. Pendekar Rajawali Sakti itu tidak bergeming sedikit pun. Padahal si Macan Gunung Sumbing sudah demikian dekat, dan sesaat lagi pasti akan menerkamnya.
“Ghrauk!”
“Hiyaaat..!”
Tepat ketika jangkauan tangan Macan Gunung Sumbing hampir menyentuh tubuhnya, tiba-tiba saja Rangga melompat ke udara. Seketika tubuhnya cepat meluruk turun sambil mengirimkan satu pukulan keras bertenaga dalam penuh dan sempurna.
Duk!
Pukulan Pendekar Rajawali Sakti tepat menghantam ubun-ubun manusia harimau itu.
“Aaarghk...!” Macan Gunung Sumbing meraung keras.
Dan belum lagi manusia harimau itu mampu melakukan sesuatu, cepat-cepat Rangga menghunjamkan dua jarinya ke bola mata Macan Gunung Sumbing. Kembali manusia setengah harimau itu meraung keras. Ditutupi mukanya dengan kedua tangannya.
“Rajawali! Bawa dia ke atas...!” seru Rangga keras seraya menjejakkan kakinya di tanah.
“Khraghk...!”
Rajawali Putih yang sejak tadi melayang-layang di angkasa, langsung meluruk turun. Disambarnya kepala Macan Gunung Sumbing dengan cakarnya, dan langsung dibawanya ke angkasa. Pada saat itu, Rangga melesat tinggi dan kemudian hinggap di punggung Rajawali Putih. Sret!
Cahaya biru kembali berpijar begitu Rangga mencabut pedang pusakanya. Tepat pada ketinggian tertentu, Rangga nekad melompat turun, dan langsung menghunjamkan pedangnya ke mulut Macan Gunung Sumbing. Dan begitu pedangnya ditarik, Rangga kembali menghunjamkan ke arah jantung.
“Lepaskan, Rajawali...!” teriak Rangga yang saat itu keseimbangan tubuhnya mulai kendur.
Rajawali Putih melepaskan cengkeramannya, sehingga Macan Gunung Sumbing meluruk jatuh ke bawah tanpa dapat dicegah lagi. Dan Rajawali Putih segera menukik menghampiri Rangga yang saat itu juga sudah turun deras. Pendekar Rajawali Sakti itu jatuh tepat di punggung Rajawali Putih.
Tampak Macan Gunung Sumbing terjatuh keras menghantam tanah. Pada saat yang sama, Rajawali Putih menukik turun dan cakarnya langsung menyambar tubuh manusia harimau itu. Kembali tubuh Macan Gunung Sumbing dibawa tinggi ke angkasa, lalu dijatuhkan lagi. Tiga kali Rajawali Putih melakukan hal itu, sehingga Macan Gunung Sumbing tidak berdaya lagi. Pada jatuhnya yang ketiga kali, tubuh Macan Gunung Sumbing menggelepar sambil menggerung-gerung kesakitan. Rangga cepat melompat, dan segera membabatkan pedangnya ke leher si manusia harimau itu.
Cras!
“Aaargh...!” Macan Gunung Sumbing meraung keras.
Leher Macan Gunung Sumbing langsung putus terbabat pedang Pendekar Rajawali Sakti. Rangga segera melompat mundur, dan menyarungkan pedangnya kembali di balik punggung. Hanya sebentar Macan Gunung Sumbing mampu bergerak, sesaat kemudian tidak berkutik lagi. Darah mengucur deras dari kepala yang buntung.
Kembali perubahan terjadi. Tubuh yang tadinya penuh bulu itu, perlahan-lahan kembali berubah menjadi manusia, menjadi si Macan Gunung Sumbing yang kini tanpa kepala. Rangga menarik napas panjang, kemudian menoleh saat mendengar suara-suara langkah kaki mendekati. Tampak Dewi Tanjung dan Paman Waku serta beberapa penduduk menghampirinya.
“Kau tidak apa-apa, Kakang?” nada suara Dewi Tanjung terdengar cemas, namun juga gembira.
“Tidak,” sahut Rangga pelan.
“Rangga, bagaimana kau mengetahui kelemahannya?” tanya Paman Waku.
“Otak,” sahut Rangga singkat.
“Otak...?!”
Rangga hanya tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak Paman Waku. Pendekar Rajawali Sakti itu kemudian menatap Dewi Tanjung lekat-lekat, lalu melompat naik ke punggung Rajawali Putih. Dewi Tanjung berlari menghampiri.
“Kau akan pergi juga, Kakang?” tanya Dewi Tanjung agak tersendat.
“Ya,” sahut Rangga mendesah, namun terdengar mantap. “Kembalilah ke padepokanmu. Kau belum siap untuk terjun dalam dunia persilatan. Masih banyak yang harus dipelajari, terutama menyempurnakan ilmu yang sudah kau miliki.”
“Kita akan bertemu lagi, Kakang?”
“Ya, kita akan bertemu lagi jika kau sudah menyempurnakan ilmu yang kau miliki,” jawab Rangga sambil tersenyum. Lalu dia segera memerintahkan Rajawali Putih untuk pergi. Burung rajawali raksasa itu berkaokan, seakan-akan mengucapkan selamat tinggal. Sebentar kemudian burung itu sudah membumbung tinggi ke angkasa. Sementara saat itu matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Paman Waku menghampiri Dewi Tanjung, lalu menepuk pundak gadis itu.
“Maafkan. Seharusnya aku tahu bahwa kau putri sahabatku,” ucap Paman Waku pelan. “Sungguh aku tidak tahu kalau si Raja Obat punya putri yang tangguh dan cantik.”
“Dari mana Paman tahu?” tanya Dewi Tanjung terkejut.
“Jurus ‘Bidadari Penyebar Maut’ yang kau mainkan tadi.”
“Ohhh...,” Dewi Tanjung menarik napas panjang.
Dewi Tanjung tidak mampu menolak tawaran Paman Waku untuk singgah di rumahnya. Mereka berjalan menuju ke rumah Paman Waku, sementara para penduduk Desa Weru mulai sibuk mengurus mayat yang bergelimpangan akibat pertarungan sepanjang malam tadi.
SELESAI
EPISODE SELANJUTNYA: MUTIARA DARI SELATAN