Cerita Silat Pendekar Rajawali Sakti
Karya Teguh S
Penerbit Cintamedia, Jakarta
Episode
Jago Dari Mongol
Karya Teguh S
Penerbit Cintamedia, Jakarta
Episode
Jago Dari Mongol
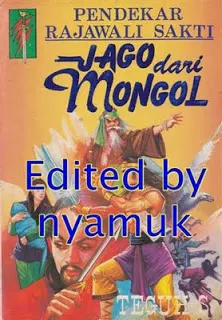
SATU
Sebuah kapal layar berukuran besar merapat di dermaga Pelabuhan Timur Kerajaan Jiwanala. Tidak seperti biasanya, kali ini pelabuhan itu tampak ramai disinggahi kapal besar dan kecil. Dari dalam kapal besar itu keluar orang-orang berpakaian aneh dari bulu binatang. Kulit mereka kuning dan mata agak sipit. Jumlahnya tidak kurang dari sepuluh orang, rata-rata menyandang senjata golok besar dan bergagang panjang.
Dari bendera yang berkibar di tiang, dapat diketahui kalau mereka berasal dari daratan Mongol. Hampir semua orang yang memadati pelabuhan itu memperhatikan mereka. Sebuah tandu indah diusung oleh empat orang bertubuh kekar dengan otot-otot bersembulan keluar. Di dalam tandu itu duduk seorang laki-laki berkumis panjang, dan berbaju indah dari bahan sutra halus. Di pinggangnya tersandang sebilah pedang panjang yang gagangnya bertaburkan batu mutiara.
Rombongan dari Mongol itu terus bergerak menuju ke ibukota Kerajaan Jiwanala. Seorang punggawa kerajaan yang kebetulan melihat rombongan asing itu, bergegas memacu kudanya menuju istana kerajaan yang tidak jauh dari situ. Dia sempat berpesan kepada empat orang prajurit penjaga pintu gerbang, kemudian memacu kudanya dengan cepat memasuki benteng istana. Kerajaan Jiwanala merupakan kerajaan megah yang kaya. Tidak heran kalau istananya begitu megah dan indah.
Punggawa itu bergegas turun dari kudanya begitu sampai di depan istana. Langkahnya tergesa-gesa memasuki istana. Beberapa prajurit penjaga membung-kukkan badan memberi hormat. Laki-laki berpakaian pembesar kerajaan itu terus melangkah lebar menuju ruangan singgasana kerajaan, dan langsung menjatuhkan diri berlutut di depan Raja Jiwanala.
“Ampunkan hamba, Gusti Prabu Duta Nitiyasa. Hamba menghadap tanpa diperintah,” ucap punggawa itu.
“Ada apa, Punggawa Narayama?” tanya Prabu Duta Nitiyasa lembut.
“Ampun, Gusti. Hamba melihat serombongan orang asing menuju ke Kotaraja. Mereka datang dengan kapal yang cukup besar dan peralatan lengkap,” lapor Punggawa Narayama.
Belum lagi Prabu Duta Nitiyasa mengatakan sesuatu, seorang prajurit penjaga pintu gerbang istana muncul dan menghampiri. Prajurit itu membungkuk, kemudian berlutut memberi hormat. Para patih, panglima, dan pembesar kerajaan yang kebetulan berada di ruangan itu, memandang pada prajurit penjaga pintu gerbang yang baru datang.
“Ada apa, prajurit?” tanya Prabu Duta Nitiyasa.
“Ampun, Gusti Prabu. Ada beberapa orang asing hendak bertemu Gusti Prabu,” lapor prajurit penjaga itu.
“Hm..., perintahkan mereka masuk.”
“Hamba, Gusti.”
Prajurit penjaga itu memberi hormat, lalu melangkah ke luar. Punggawa Narayama bermaksud meninggalkan ruangan itu, tapi Prabu Duta Nitiyasa cepat melarangnya. Punggawa itu menyingkir, dan duduk pada deretan pung-gawa lainnya. Tidak lama berselang, seorang laki-laki bertubuh tinggi kekar dan berkumis hitam panjang melangkah masuk. Sepuluh orang berpakaian seragam aneh yang terbuat dari bulu binatang ikut mengiringnya.
Mereka serentak membungkukkan badan sambil meletakkan tangan kanannya di depan dada. Prabu Duta Nitiyasa pun segera membalasnya dengan mengangkat tangannya ke depan. Orang-orang dari Daratan Mongol itu duduk bersila den-gan sikap hormat.
“Apakah maksud kalian datang jauh-jauh ke negeri kami?” tanya Prabu Duta Nitiyasa.
Laki-laki bertubuh tinggi besar dan berbaju sutra halus itu bangkit berdiri. Semua orang yang berada di ruangan itu terkejut. Bagi mereka, sikap orang Mongol itu sudah melampaui batas! Berani berdiri tegak di hadapan junjungan mereka adalah melanggar tatakrama. Tapi Prabu Duta Nitiyasa segera mengangkat tangannya, sehingga para pembantunya bisa mengendalikan diri.
“Aku bernama Ogodai Leng, dan mereka adalah pengawal khusus Yang Mulia Jengis Khan. Kami datang untuk meminta tanda takluk negeri ini,” lantang suara laki-laki tinggi besar itu.
“Gila! Setan apa yang membawa kalian kemari?” bentak Panglima Sembada berang.
“Panglima Sembada...,” tetap tenang suara Prabu Duta Nitiyasa.
“Hamba, Gusti Prabu,” Panglima Sembada memberi hormat.
“Hm..., katakan pada rajamu. Kami semua di sini cinta damai, dan tidak akan pernah takluk pada siapa pun. Dengan tegas aku menolak permintaan rajamu,” kata Prabu Duta Nitiyasa tegas.
Ogodai Leng merebut tombak dari tangan salah seorang pengawalnya, lalu ditancapkan tepat di depan Prabu Duta Nitiyasa. Para panglima Kerajaan Jiwanala langsung bangkit berdiri, tapi Prabu Duta Nitiyasa cepat mengangkat tangannya kembali. Maka, kemarahan panglima-panglima itu masih dapat teredakan.
“Silakan kalian tinggalkan istana ini,” tegas Prabu Duta Nitiyasa.
Orang-orang Mongol itu tidak berkata-kata lagi. Mereka langsung berbalik dan melangkah pergi. Tombak yang ditinggalkan menandakan tantangan untuk berperang, dan ini sangat disadari Prabu Duta Nitiyasa maupun para panglimanya.
********************
Orang-orang Mongol itu tidak langsung kembali ke kapalnya, dan singgah di sebuah kedai minum yang tidak begitu ramai. Dengan sikap dan gaya bagai penguasa, mereka bertindak semaunya di kedai itu. Tentu saja hal ini membuat pengunjung lain merasa tidak senang, tapi tidak bisa berbuat banyak. Seorang pemuda yang coba-coba mengusir, tewas di ujung golok salah seorang Mongol itu.
Tapi dari sebelas orang itu, terlihat seorang pemuda berwajah tampan yang duduk tenang, tak menghiraukan keramaian itu. Sebilah pedang panjang bertengger di punggungnya. Kelihatannya pemuda itu tidak begitu suka melihat tingkah laku teman-temannya yang brutal dan membuat kekacauan di kedai ini. Sejak masuk tadi, pemuda berbaju putih bersih bagai seorang pelajar itu tidak membuka suara sedikit pun. Bahkan dia duduk tenang tidak menghiraukan tingkah teman-temannya. Di depan pemuda itu duduk Ogodai Leng, seorang panglima kepercayaan yang memimpin utusan dari Jengis Khan ini.
“Sejak turun dari kapal tadi, kau diam saja, Hulagu Leng. Ada apa?” tegur Ogodai Leng.
“Tidak ada apa-apa, Kak Ogodai Leng,” sahut pemuda yang dipanggil Hulagu Leng ini.
Pemuda itu memang adik dari Ogodai Leng, dan dalam rombongan itu bertugas sebagai wakil kakaknya. Memang tidak ada yang bisa menyangka kalau mereka kakak beradik. Ogodai Leng berwajah kasar dan berwatak keras serta berangasan. Sedangkan Hulagu Leng berwajah tampan, dan berperilaku halus lembut bagai seorang wanita. Namun tingkat kepandaian mereka bisa dikatakan seimbang. Hanya saja, mereka saling menyayangi meskipun mempunyai watak yang saling bertolak belakang.
“Baru kali ini kau keluar dari Mongol, Hulagu Leng. Kau harus banyak belajar. Ingat, kita berada di negeri asing, jangan samakan dengan negeri sendiri. Sikap lemah akan membuat dirimu sengsara. Kau harus mengerti itu, Hulagu Leng,” jelas Ogodai Leng seperti bisa menduga jalan pikiran adiknya.
“Selalu dengan cara seperti inikah kita memperoleh daerah kekuasaan, Kak Ogodai Leng?” tanya Hulagu Leng.
“Ingat, Adikku. Kekuatan adalah segala-galanya. Kita harus tunjukkan kekuatan untuk menurunkan mental mereka. Ini baru sebagian kecil yang dapat kau saksikan. Ah...! Sudahlah, Hulagu Leng. Kau nanti akan tahu sendiri, bagaimana caranya memperoleh daerah kekuasaan.”
Hulagu Leng diam membisu. Memang baru kali ini dia ikut dalam rombongan mencari daerah kekuasaan baru bagi negerinya. Tapi justru pengalaman pertama ini membuat hatinya terasa teriris. Betapa tidak, baru beberapa saat saja mereka mendarat di negeri asing, sudah lima orang tewas.
“Mau ke mana kau?” tanya Ogodai Leng melihat adiknya bangkit dari duduknya.
“Kembali ke kapal,” sahut Hulagu Leng seraya melangkah ke luar kedai.
“Kau tahu jalannya, Hulagu Leng?”
“Aku rasa tidak jauh dari sini.”
“Hati-hatilah. Semua orang di negeri ini adalah musuh.”
Hulagu Leng hanya tersenyum tipis, dan terus saja berjalan keluar dari kedai minum ini. Sementara teman-temannya masih terus berpesta. Hulagu Leng agak terkejut juga melihat banyak orang berdiri berjajar di sepanjang jalan depan kedai. Mereka semua membawa parang atau senjata lain yang sangat sederhana. Dari sinar matanya, dapat diketahui kalau orang-orang itu menyimpan kebencian yang amat sangat.
Hulagu Leng terus berjalan pelahan-lahan, namun sikapnya jadi waspada juga. Berpuluh-puluh pasang mata mena-tapnya penuh kebencian. Tapi, tidak seorang pun yang bergerak mendekatinya.
Sampai mendekati pelabuhan, tidak ada seorang pun yang mendekati orang Mongol itu. Sedangkan Hulagu Leng masih terus bersikap waspada. Dan begitu kakinya menginjak lantai dermaga, tiba-tiba terdengar bentakan keras dari belakang.
“Orang asing! Berhenti...!”
Hulagu Leng langsung menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan dibalikkan tubuhnya. Tampak seorang laki-laki berusia sekitar tiga puluh tahun berdiri tegak, bersikap menantang. Dari pakaiannya dapat diketahui kalau dia seorang panglima perang Kerajaan Jiwanala. Di belakangnya berdiri sepuluh orang berpakaian prajurit. Mereka semua membawa sebatang tombak panjang dan pedang tergantung di pinggang.
“Panglima Sembada, ada keperluan pentingkah sehingga Tuan bersusah payah datang menemuiku?” tanya Hulagu Leng mengenali panglima itu.
“Aku datang untuk meminta tanggung jawabmu, orang asing!” sahut Panglima Sembada ketus.
“Tanggung jawabku...?!” Hulagu Leng mengerutkan keningnya.
“Jangan berpura-pura bodoh, orang asing! Kau datang membuat keributan dan membunuh lima orang rakyat tak berdosa. Kau tahu, apa hukumannya bagi seorang pembunuh?! Mati...!”
Hulagu Leng mengerti sekarang. Dia kini tidak terkejut lagi. Memang, sejak keluar dari kedai tadi sudah diduga kalau hal ini pasti bakal terjadi. Dan kejadian ini memang disesalkan sekali. Hanya saja dirinya tidak bisa berbuat banyak. Semua pengawal hanya tunduk pada perintah kakaknya.
“Tangkap dia...!” perintah Panglima Sembada.
“Tunggu!” sentak Hulagu Leng.
Tapi sepuluh orang prajurit Jiwanala itu tidak mengindahkan bentakan itu. Mereka langsung bergerak cepat menyerang. Mau tidak mau Hulagu Leng melayaninya, namun berusaha untuk tidak balas menyerang. Yang dilakukannya hanya berkelit menghindari setiap serangan sepuluh orang prajurit itu.
“Tahan! Kalian salah jika menyerangku. Nanti akan kujelaskan!” seru Hulagu Leng keras.
Tapi seruan itu tidak didengar sama sekali. Bahkan sebatang tombak hampir saja merobek perutnya, kalau saja orang dari Mongol itu tidak cepat-cepat berkelit dengan memiringkan tubuhnya. Dan belum lagi sempat menarik kembali tubuhnya, satu tusukan tombak mengarah ke dadanya.
“Eit..!”
Hulagu Leng terpaksa mengangkat tangannya, lalu menangkap tombak itu. Dengan cepat tangan kirinya mengibas ke arah perut penyerangnya. Prajurit Kerajaan Jiwanala itu mengeluh pendek, dan tubuhnya terjajar ke belakang beberapa langkah. Tombaknya berhasil dirampas Hulagu Leng yang langsung digunakan sebagai senjata untuk menahan gempuran para prajurit lainnya.
“Mundur...!” tiba-tiba Panglima Sembada berteriak nyaring.
Para prajurit itu segera berlompatan mundur begitu mendengar perintah pemimpinnya. Panglima Sembada langsung melompat ke depan. Di tangannya telah tergenggam sebilah pedang yang berkilat tertimpa cahaya matahari. Hulagu Leng menggeser kakinya sedikit ke kiri.
“Tahan...!” tiba-tiba terdengar bentakan keras. “Kakang Raksajunta...,” desis Panglima Sembada begitu menoleh ke arah sumber suara tadi.
Seorang laki-laki berusia hampir tujuh puluh tahun melompat ringan, dan langsung mendarat di samping Panglima Sembada. Raksajunta adalah seorang patih tertua di Kerajaan Jiwanala saat ini. Semua panglima, patih, dan para pembesar sangat menghormatinya.
“Ada apa ini, Sembada?” tanya Patih Raksajunta.
“Orang Mongol itu telah membuat keributan dan membunuh lima orang penduduk, Kakang,” sahut Panglima Sembada.
“Hm..., benar apa yang dikatakan Panglima Sembada?” Patih Raksajunta bertanya penuh bijaksana pada Hulagu Leng.
“Sama sekali tidak kusangkal. Tapi semua itu bukan aku yang melakukan,” sahut Hulagu Leng.
“Siapa pun yang berbuat, harus bertanggung jawab, Kakang!” sergah Panglima Sembada.
“Hm..., siapa namamu?” tanya Patih Raksajunta tidak menghiraukan kata-kata Panglima Sembada.
“Hulagu Leng. Aku adik kandung Panglima Ogodai Leng.”
“Kuminta dengan hormat, sebaiknya kau ikut ke istana untuk ikut bertanggung jawab akibat perbuatan teman-temanmu. Aku yakin, kau seorang ksatria yang bersedia bertanggung jawab atas perbuatan teman-temanmu,” tegas Patih Raksajunta.
Hulagu Leng terdiam beberapa saat. Tampaknya sedang menimbang keputusan Patih Raksajunta barusan. Di negerinya, dia memang seorang ksatria tangguh yang sukar dicari tandingannya. Tapi persoalan yang dihadapinya sekarang bukanlah persoalan kecil. Apalagi ini di negeri orang lain yang belum jelas tatacara kehidupan dan peraturan hukumnya.
“Kau tidak perlu khawatir, Tuan Hulagu Leng. Akan kujamin keselamatanmu, jika kau benar-benar tidak bersalah,” kata Patih Raksajunta seperti mengetahui jalan pikiran orang Mongol itu.
“Bisa kupercaya kata-kata Tuan?” Hulagu Leng ingin kepastian.
“Nyawaku taruhannya,” sahut Patih Raksajunta tegas.
“Baiklah! Sumpah seorang satria telah kupegang.”
Hulagu Leng menyerahkan tombak yang dirampasnya dari tangan prajurit. Seorang prajurit menerimanya, dan segera menggiring laki-laki Mongol itu. Panglima Sembada memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya, kemudian berjalan di samping Hulagu Leng. Sedangkan Patih Raksajunta berjalan di depan. Sepuluh orang prajurit mengiringi di belakang mereka
********************
Kecemasan merayapi hati Ogodai Leng yang tidak mendapatkan adiknya di kapal. Semua awak kapal dan prajuritnya ditanyai, tapi tidak ada seorang pun yang melihat Hulagu Leng kembali ke kapal. Berbagai macam pikiran dan dugaan berkecamuk di benaknya. Sudah beberapa negeri didatangi, berbagai macam bahaya dilalui, namun baru kali ini hatinya merasa gelisah. Menghilangnya Hulagu Leng membuat panglima dari Mongol itu diliputi kecemasan.
“Mungkin Hulagu Leng tersasar, Tuan Panglima,” kata salah seorang pengawal khusus Panglima Ogodai Leng.
“Tidak mungkin!” bantah panglima itu.
“Tapi sudah malam begini belum juga kembali,” kata seorang pengawal lagi.
“Temujin...,” panggil Panglima Ogodai Leng.
“Hamba, Panglima...,” sahut seorang laki-laki bertubuh kekar memakai baju dari kulit harimau.
“Bawa beberapa orang. Cari Hulagu Leng sampai dapat,” perintah Ogodai Leng.
Temujin membungkuk memberi hormat, lalu bergegas meninggalkan kapal itu diiringi enam orang berpakaian prajurit. Saat itu malam sudah demikian larut. Udara laut yang dingin berhembus kencang menggigilkan. Tapi semua itu tidak dipedulikan Temujin dan enam orang prajuritnya. Mereka terus bergerak menyusuri jalan yang tadi siang telah dilalui.
Sepanjang jalan yang dilalui hanya kesunyian dan kegelapan saja ditemui. Mereka berhenti di depan kedai yang disinggahi siang tadi. Suasana di dalam kedai masih tetap sunyi, namun masih terlihat ada seseorang duduk di sana. Pintu kedai yang terbuka lebar dengan cahaya pelita yang terang-benderang, menampakkan suasana di dalam kedai itu.
“Hm...!” Temujin memberi isyarat.
Enam orang prajurit Mongol yang ikut bersamanya segera bergerak mendekati kedai itu. Laki-laki muda berambut gondrong terikat, menoleh begitu mendengar langkah-langkah kaki yang berat memasuki kedai. Alisnya berkerenyit melihat orang-orang Mongol masuk ke dalam kedai yang lantas membuat kegaduhan.
Temujin melangkah tegap memasuki kedai itu, langsung menghampiri pemuda yang masih duduk tenang di kursinya. Seguci arak terhidang di atas meja itu. Temujin berdiri menatap tajam pada pemuda itu. Seorang laki-laki tua pemilik kedai mengintip dari balik dinding bagian belakang.
“Gusti..., bencana apa lagi yang akan terjadi.... Hancur sudah seluruh kedaiku...,” rintih laki-laki tua pemilik kedai ini.
Sementara itu Temujin mengambil guci arak dari meja pemuda tampan yang tetap duduk tenang di kursinya. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, pengawal pribadi panglima dari Mongol itu menuangkan arak dalam guci itu ke atas meja. Pemuda itu mengangkat kepalanya, menatap tajam ke bola mata orang di depannya.
“Arak itu belum dibayar,” kata pemuda itu kalem. Namun suaranya terdengar bernada datar dan agak tertekan.
“Akan kubayar sepuluh kali lipat kalau kau jawab pertanyaanku!” ujar Temujin kasar.
“Hm...,” pemuda tampan berbaju rompi putih itu hanya menggumam saja.
“Kau tahu, di mana Tuan Muda Hulagu Leng?” tanya Temujin.
“Maaf, aku tidak kenal dengan orang yang Tuan tanyakan,” sahut pemuda itu datar.
Brak!
Temujin menggebrak meja hingga hancur berantakan. Tapi pemuda berbaju rompi putih itu tetap tenang di kursinya. Sedikit pun tidak bergeming, bahkan tatapan matanya begitu tajam menusuk langsung ke bola mata orang Mongol itu.
“Maaf, aku masih ada urusan lain,” ucap pemuda itu seraya bangkit dari duduknya.
“Setan...!” Temujin menggeram marah. Pemuda berbaju rompi putih itu terus berbalik dan melangkah pergi tanpa mempedulikan umpatan Temujin. Tapi baru beberapa langkah dia berjalan, Temujin menghentakkan tangannya melayangkan pukulan jarak jauh. Desiran angin yang sangat kuat membuat pemuda tampan itu melesat ke atas, dan hinggap di palang atap kedai.
“Grrr...!” Temujin menggeram hebat karena pukulannya luput dari sasaran.
Sambil berteriak keras, Temujin melompat ke atas sambil mencabut senjatanya. Dengan mengerahkan tenaga yang sangat luar biasa, dikibaskan senjatanya ke arah pemuda itu. Tapi lagi-lagi serangan Temujin hanya menghantam tempat kosong. Entah kapan dimulainya, tahu-tahu pemuda itu sudah berada di bawah.
“Hyaaat..!”
Temujin semakin berang karena merasa dipermainkan di depan anak buahnya. Dengan ganas, kembali diserangnya pemuda itu. Namun manis sekali pemuda tampan berbaju rompi putih itu menghindari setiap serangan Temujin. Dan hal itu membuat pengawal khusus Panglima Ogodai Leng itu marah luar biasa, sehingga tidak dipedulikan lagi kesatriaan. Sambil menyerang, diperintahkan enam orang prajuritnya untuk menyerang.
“Hm..., kedai ini bisa hancur kalau aku tidak keluar,” gumam pemuda itu dalam hati.
Seketika itu juga pemuda itu melesat cepat ke luar kedai. Temujin berseru nyaring, dan tubuhnya langsung melompat ke luar mengejar. Enam orang prajuritnya pun bergegas berlarian mengikuti. Kini pertarungan berlangsung di halaman kedai, terselimut kegelapan dan desiran angin laut yang dingin.
DUA
Malam yang semula sepi, kini pecah oleh suara pertarungan di depan kedai. Seorang pemuda tampan memakai baju rompi putih harus menghadapi seorang pengawal khusus Panglima Mongol yang dibantu enam orang prajuritnya. Meskipun dikeroyok tujuh orang, tapi kelihatannya pemuda itu tidak mengalami kesulitan dalam menghadapinya.
Gerakan-gerakan tubuhnya cepat luar biasa. Bahkan serangannya tidak terduga, selalu tepat mengenai sasaran. Orang-orang Mongol itu rupanya bukan lawan tanding pemuda berbaju rompi putih. Mereka dibuat jungkir balik bergulingan di tanah. Hanya Temujin yang kelihatan tangguh, mampu sedikit mengimbangi serangan pemuda itu.
“Hiyaaat..!”
Tiba-tiba saja pemuda itu berteriak keras melengking. Secepat kilat tubuhnya melesat ke atas, lalu secepat itu pula menukik ke bawah. Tangannya merentang lebar dan kaki bergerak cepat.
“Aaa...!”
Jeritan-jeritan melengking terdengar saling sahut. Sesaat kemudian terlihat empat orang asing itu roboh terjungkal bersimbah darah. Pemuda itu berdiri tegak sambil melipat tangannya di depan dada. Tatapan matanya tajam menusuk.
Melihat empat orangnya tewas, Temujin jadi gentar juga.
“Lari...!” seru Temujin keras.
Pengawal khusus Panglima Ogodai Leng itu langsung berlari kencang diikuti dua orangnya yang tersisa. Sedangkan pemuda itu tidak berkedip memandanginya. Temujin terus berlari cepat menuju ke dermaga.
Laki-laki tua pemilik kedai yang sejak tadi melihat pertarungan itu dari tempat yang tersembunyi, langsung keluar begitu Temujin dan dua orang sisa prajuritnya melarikan diri. Segera dihampirinya pemuda itu, lalu dibungkukkan tubuhnya.
“Oh, terima kasih.... Terima kasih, Den.... Aden telah menyelamatkan kedaiku dari kehancuran,” ucap laki-laki tua itu sambil membungkukkan tubuhnya beberapa kali.
“Hm.... Banyak yang rusak, Pak Tua?” tanya pemuda itu.
“Tidak, Den. Hanya meja dan kursi. Tapi bisa diperbaiki,” jawab laki-laki tua pemilik kedai itu. “Ah, sebaiknya kita bicara di dalam saja, Den. Mari....”
Pemuda itu tidak menolak. Dia berjalan memasuki kedai mengikuti Pak Tua pemilik kedai yang sudah berjalan lebih dahulu. Matanya sempat melihat empat mayat yang masih menggeletak di luar.
“Biar pembantuku yang mengurus dan membuangnya ke laut. Biar jadi santapan ikan-ikan liar,” ujar Pak Tua seperti mengetahui jalan pikiran pemuda itu.
Laki-laki tua pemilik kedai itu menyediakan seguci arak manis pilihan di meja yang masih utuh. Pemuda itu duduk menghadapi meja, dan tidak menolak ketika laki-laki tua itu menuangkan arak ke dalam gelasnya. Sebentar Pak Tua itu masuk ke dalam bagian belakang setelah menuangkan arak. Pemuda tampan berbaju rompi putih itu sempat melihat beberapa orang laki-laki muda menggotong mayat-mayat orang asing di halaman, lalu membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, pemilik kedai itu sudah kembali lagi membawa sepiring makanan kecil.
“Hanya ini yang bisa kusediakan. Maklum, sudah larut malam,” kata laki-laki tua itu.
“Terima kasih, Pak...,” ucap pemuda itu.
“Jantar...! Panggil saja Ki Jantar. Semua orang di sini memanggilku begitu,” pemilik kedai ini memperkenalkan diri. “Aden sendiri siapa...?”
“Rangga.”
“Den Rangga sepertinya bukan orang sini. Tampaknya seperti..., pengembara,” Ki Jantar menebak-nebak
“Tidak salah, Ki,” sahut Rangga.
“Wah, Den. Pada saat seperti ini, semua orang malah mengungsi. Eeeh..., kok Aden malah datang ke sini,” kata Ki Jantar.
“Mengungsi...?! Ada apa?” tanya Rangga agak terkejut juga.
Pendekar Rajawali Sakti itu bertanya-tanya dalam hati. Dugaannya pasti ada hubungan dengan orang-orang asing yang sempat bertarung dengannya. Dari bentuk wajah maupun pakaiannya, sepertinya mereka dari seberang lautan.
Rangga memang sudah melihat adanya keanehan ketika datang ke Kerajaan Jiwanala sore tadi. Sepanjang jalan yang dilalui, banyak ditemui orang-orang yang pergi memakai kereta kuda ataupun berjalan kaki. Dan kelihatannya memang bermaksud meninggalkan kerajaan di pesisir pantai ini. Sempat juga Rangga melihat-lihat keadaan pelabuhan yang tampak sepi. Banyak kapal besar dan kecil telah bertolak meninggalkan dermaga.
“Mereka memang baru siang tadi datang, Den. Tapi kedatangannya yang baru beberapa saat saja sudah membuat penduduk negeri ini meninggalkan kampung halamannya sendiri. Mereka sangat kejam! Bahkan menurut para punggawa atau prajurit kerajaan, mereka datang untuk merebut Kerajaan Jiwanala ini, Den,” tutur Ki Jantar tanpa diminta.
“Maksud Ki Jantar, orang-orang tadi itu?” Rangga ingin menegaskan.
“Benar, Den. Mereka datang dari Daratan Mongol. Menurut kabar, mereka adalah utusan Jengis Khan. Ah..., aku sendiri kurang tahu siapa itu Jengis Khan. Tapi memang begitulah yang kudengar. Maklum, Den, Jiwanala hanya sebuah kerajaan kecil di pesisir pantai ini. Jadi setiap ada berita, cepat tersebar dalam waktu singkat.”
“Hm...,” Rangga bergumam tidak jelas.
“Sudah larut malam, Den. Kalau Raden ingin beristirahat, ada kamar kosong yang bisa ditempati. Tapi agak berantakan, Den. Maklum, sudah lama tidak dipakai,” kata Ki Jantar.
“Terima kasih, Ki,” ucap Rangga.
********************
Pagi-pagi sekali Rangga sudah keluar dari kamar yang disediakan Ki Jantar. Dia berjalan-jalan menghirup udara segar di pagi hari ini. Dalam hati, Pendekar Rajawali Sakti itu semakin sering bertanya-tanya melihat setiap pelosok terdapat sekelompok prajurit yang dipimpin seorang punggawa.
Di pagi ini sudah terlihat beberapa keluarga meninggalkan rumahnya masing-masing. Arah yang ditempuh bukan menuju ke dermaga, melainkan masuk ke pedalaman yang berupa hutan dan perbukitan kecil. Suasana di pagi hari ini membuat Rangga tidak mengerti. Dia teringat kejadian semalam dan cerita Ki Jantar. Rangga jadi ingin tahu, apa benar orang-orang Mongol itu datang untuk merebut kerajaan kecil di pesisir pantai ini?
"Dari mana, Den? Pagi-pagi sudah keliling,” tegur Ki Jantar ketika melihat Rangga baru saja melangkahkan kakinya memasuki kedai.
“Melihat-lihat suasana saja, Ki,” sahut Rangga seraya menghenyakkan tubuhnya di kursi bambu panjang.
“Tadi ada Panglima Sembada, Den,” lapor Ki Jantar. “Gusti Panglima menanyakan tentang keributan semalam.”
“Kok bisa tahu?” tanya Rangga heran juga.
“Jangan heran, Den. Setiap kejadian di sini, dalam waktu sebentar saja akan tersebar cepat. Katanya ada beberapa orang prajurit yang melihat pertarungan semalam.”
“Oh, ya...? Kenapa mereka tidak muncul?”
“Raden ini seperti yang tidak tahu saja. Semua orang sudah tahu kalau orang-orang Mongol itu kejam-kejam. Dan lagi, rata-rata sangat kuat dan tangguh. Kalau baru berpangkat prajurit saja, mana berani menghadapi mereka, Den.”
Rangga diam membisu. Sama sekali tidak diduga kalau prajurit-prajurit Kerajaan Jiwanala memiliki nyali kecil. Padahal kelihatannya gagah-gagah. Tapi Rangga tidak bisa menyalahkan begitu saja. Dia juga pernah dengar tentang kehebatan pasukan Mongol. Sudah tak terhitung lagi berapa jumlah negara taklukannya. Dan kini mereka rupanya tertarik untuk menyeberang, meluaskan daerah kekuasaan.
Rasanya pilihan orang Mongol itu memang tepat. Kerajaan Jiwanala merupakan negeri yang sangat kecil. Kekuatan prajuritnya sangat lemah dan mudah untuk ditaklukkan. Kerajaan pelabuhan ini memang sangat penting. Banyak kapal niaga yang singgah, sehingga kehidupan rakyat di sini boleh dikatakan makmur berkat hasil berniaga. Belum lagi kekayaan akan tambang emas dan batu permata di Kerajaan Jiwanala ini. Tidak heran kalau banyak kerajaan besar yang menginginkannya.
“Ki Jantar tidak mengungsi?” tanya Rangga iseng.
“Untuk apa mengungsi, Den? Kehidupan di mana saja sama. Puluhan tahun aku hidup cukup di sini. Dan sekarang dalam masa genting begini, harus mencari kehidupan lain di tempat pengasingan. Hhh! Hanya orang yang bodoh dan berjiwa kerdil saja yang menyingkir,” sahut Ki Jantar bernada mengeluh atas sikap rakyat Jiwanala yang pengecut.
“Memang sayang sekali! Seharusnya orang-orang sepertimulah yang pantas hidup di negeri kaya ini, Ki,” ujar Rangga memuji.
“Tapi aku ini sudah jompo, tidak bisa berbuat apa-apa. Yaaah..., memang seharusnya yang muda-muda harus mempertahankan negeri ini dari rongrongan pihak luar.”
Rangga mengagumi jiwa kesetiaan laki-laki tua ini. Sulit mencari orang yang mempunyai pendirian kuat seperti Ki Jantar pada masa sekarang ini. Banyak orang yang selalu mementingkan diri sendiri, tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Kalau saja semua orang di kerajaan ini mempunyai sikap seperti Ki Jantar, kecil kemungkinan orang-orang dari Daratan Mongol itu berani datang.
Tapi semua sudah terlambat. Api sudah tersulut, dan hanya menunggu waktu saja untuk berkobar lebih besar lagi. Dari beberapa orang penduduk dan prajurit yang ditemui, Rangga telah mencuri dengar pembicaraan mereka. Pendekar Rajawali Sakti itu sudah bisa menebak kalau orang-orang Mongol itu tidak akan pergi sebelum maksudnya terlaksana.
Lebih-lebih sekarang ini mereka telah kehilangan empat orang prajurit, dan seorang adik panglimanya yang hilang tidak jelas kabarnya. Tapi dari kabar yang didengar Rangga, adik kandung Panglima Mongol yang bernama Hulagu Leng itu, tertangkap oleh Panglima Sembada dan Patih Raksajunta. Hal itu terjadi setelah ada keributan di kedai ini yang meminta korban nyawa lima orang rakyat.
Pendekar Rajawali Sakti itu menolehkan kepala ketika telinganya menangkap derap langkah kaki kuda di kejauhan. Tampak satu pasukan Kerajaan Jiwanala menuju ke dermaga. Paling depan terlihat Panglima Sembada yang didampingi dua orang panglima lainnya, dan Patih Raksajunta. Di belakang mereka sepasukan prajurit berkuda bersenjata lengkap mengiringi. Jumlahnya tidak kurang dari lima puluh orang.
“Mereka pasti akan menyerang kapal orang Mongol itu,” kata Ki Jantar setengah bergumam.
“Hm...,” Rangga hanya bergumam tidak jelas.
Dugaan Ki Jantar ternyata memang tepat. Prajurit Jiwanala yang dipimpin langsung Panglima Sembada dan Patih Raksajunta memang menuju ke pelabuhan. Tapi belum juga tiba di pelabuhan, mereka sudah disambut prajurit-prajurit Mongol. Pertempuran pun tak terelakkan lagi.
Para penduduk di sekitar pelabuhan itu berlarian, berusaha menyelamatkan diri. Prajurit-prajurit Mongol bertarung bagai kesetanan. Bukan hanya prajurit Jiwanala saja yang mereka hantam, bahkan penduduk yang berusaha melarikan diri pun dibantai. Jerit dan pekik peperangan berbaur menjadi satu dengan jerit kematian. Pagi yang seharusnya tenang ini berubah menjadi ajang pembantaian.
Prajurit-prajurit Mongol memang terkenal tangguh dalam pertempuran. Mereka sudah berpengalaman dalam hal ini, sehingga dalam menghadapi serbuan prajurit Kerajaan Jiwanala tidak gentar sedikit pun. Bahkan bertarung dengan penuh semangat. Panglima Ogodai Leng seperti seekor singa gurun yang bertarung bagai kesetanan. Senjatanya yang berupa golok besar dan bertangkai panjang, berkelebatan cepat. Setiap gerakan senjatanya, satu atau dua nyawa melayang.
Saat itu Panglima Sembada dan Patih Raksajunta belum terjun dalam pertempuran. Mereka cukup cemas melihat para prajuritnya terus terdesak. Tidak terhitung lagi, berapa prajurit yang menggeletak bersimbah darah. Sedangkan dari pihak Mongol, hanya beberapa orang saja terluka.
“Mundur...!” seru Patih Raksajunta tiba-tiba.
Prajurit-prajurit Jiwanala yang masih hidup segera berlompatan mundur sambil bertahan menghadapi gempuran dahsyat prajurit Mongol. Mereka terus mundur sampai keluar dari daerah pelabuhan. Patih Raksajunta kelihatan sedih menyaksikan lebih dari separuh prajuritnya tewas.
“Kau lihat, Sembada. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi mereka sangat tangguh. Mereka sudah berpengalaman dalam peperangan,” kata Patih Raksajunta pelan.
Panglima Sembada hanya diam saja. Hatinya geram melihat banyak prajuritnya tewas. Belum lagi yang luka-luka. Tinggal beberapa orang saja masih kelihatan segar. Itu pun tampaknya terlalu kelelahan.
“Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Gusti Prabu pasti tidak suka melihat kekalahan ini,” keluh Patih Raksajunta.
“Bagaimanapun juga, orang asing itu harus kita usir dari tanah ini, Kakang,” tekad Panglima Sembada.
“Benar! Mereka memang harus enyah dari sini. Tapi jangan lupa, Sembada. Prajurit kita tidak akan mampu menghadapinya.”
“Hanya ada satu jalan, Kakang,” pelan suara Panglima Sembada.
Patih Raksajunta menatap tajam pada panglima muda itu.
“Minta bantuan orang-orang persilatan, atau mengundang tokoh asing untuk menghadapi mereka,” usul Panglima Sembada.
“Kau gila, Sembada!” sentak Patih Raksajunta terkejut.
“Kerajaan Jiwanala di ambang kehancuran, Kakang. Cara apa pun harus ditempuh untuk menyelamatkannya.”
“Tapi itu tidak mungkin, Sembada. Apa yang akan kita pertaruhkan...?”
“Dengan bayaran tinggi.”
“Edan!” rungut Patih Raksajunta.
“Akan kuajukan hal ini pada Gusti Prabu. Aku yakin beliau setuju dengan usulku ini, Kakang,” tekad Panglima Sembada.
“Percuma saja, Sembada. Aku tahu betul watak Gusti Prabu. Beliau lebih baik mati membela tanah air daripada berlindung di balik punggung orang asing, meskipun harus mengeluarkan biaya banyak.”
“Setiap usaha harus dicoba, Kakang.”
“Terserahlah. Yang penting kau sudah kuperingatkan,” Patih Raksajunta mengalah.
Panglima Sembada melangkah menghampiri kudanya. Dengan gerakan indah dia melompat ke atas punggung kuda putih itu, kemudian menggebahnya dengan kencang. Debu berkepul begitu kuda putih itu berlari cepat menuju ke Kotaraja Jiwanala. Patih Raksajunta hanya memandangi saja sambil menggeleng-geleng beberapa kali.
Dalam beberapa hal, diakui kalau usul Panglima Sembada memang benar. Tapi dia sangsi kalau Prabu Duta Nitiyasa bersedia menerima usulan itu. Beliau bukanlah raja yang lemah, yang hanya duduk di singgasana saja. Tingkat kepandaiannya cukup tinggi dan sukar ditandingi. Prabu Duta Nitiyasa tidak pernah meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut dalam negerinya.
“Hhh...!” Patih Raksajunta menarik napas panjang dan berat.
Perlahan-lahan dihampiri kudanya, lalu naik ke punggung kuda itu. Beberapa prajurit yang masih tersisa hanya memandangi dengan mata sayu. Patih Raksajunta terpaku sesaat, kemudian turun lagi dari punggung kudanya. Rasanya tidak tega meninggalkan prajurit yang tengah keletihan akibat pertempuran tadi. Bagaimanapun juga dia harus menahan orang-orang Mongol itu untuk tidak menjarah negeri ini.
“Gusti Patih! Mereka menyerang...!” tiba-tiba seorang prajurit berteriak keras.
“Jagat Dewa Batara...!” desah Patih Raksajunta ketika melihat tidak kurang tiga puluh orang Mongol berlarian dengan senjata terhunus.
Sementara itu prajurit Jiwanala yang masih tersisa hanya sekitar sebelas orang saja. Tapi mental mereka sudah turun akibat kekalahan dalam pertempuran tadi. Patih Raksajunta tidak tahu lagi, apa yang harus dilakukannya. Orang-orang Mongol itu sudah semakin dekat saja. Mereka berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjatanya ke atas.
“Dengar! Kalian harus bertahan sampai bantuan datang!” seru Patih Raksajunta keras.
Patih Raksajunta melompat ke depan. Pedangnya terhunus di depan dada. Para prajurit yang semula sudah gentar, mendadak bangkit semangatnya melihat Patih Raksajunta berdiri menyongsong di depan mereka. Sementara orang-orang Mongol itu sudah demikian dekatnya.
Pekik peperangan terdengar menggemuruh ditambah derap kaki-kaki berat yang berlarian kencang. Suasana seperti itu pasti bisa membuat ciut hati orang yang melihatnya. Tapi Patih Raksajunta kelihatan tenang dan tegar. Pedang kebanggaannya tetap menyilang di depan dada.
TIGA
Sudah dapat diduga kalau Patih Raksajunta dan prajurit-prajuritnya tidak akan mampu membendung serangan orang-orang Mongol itu. Di samping saat ini berjumlah jauh lebih besar, rata-rata mereka pun memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Dalam waktu tidak lama empat orang prajurit Patih Raksajunta sudah roboh berlumuran darah.
Satu per satu prajurit Jiwanala roboh berguguran. Sedangkan Patih Raksajunta tidak dapat membantu banyak. Meskipun sudah bertarung penuh semangat, namun lawan yang dihadapinya cukup tangguh. Saat ini yang harus dihadapi adalah lima orang lawan. Sudah tidak terhitung lagi, berapa pukulan dan tendangan bersarang di tubuhnya.
“Akh!” tiba-tiba saja Patih Rak-sajunta memekik tertahan.
Satu sabetan golok lawannya berhasil merobek bahunya. Darah mengucur deras dari luka yang cukup panjang dan dalam itu. Patih Raksajunta terhuyung-huyung ke belakang. Dan pada saat itu satu tendangan keras telah menghantam punggungnya. Tak pelak lagi, laki-laki tua itu terjerembab mencium tanah.
“Yaaah...!”
“Matilah aku...,” desah Patih Raksajunta melihat seorang lawannya mengibaskan goloknya dengan cepat.
Dan pada saat yang kritis itu, tiba-tiba sebuah bayangan putih berkelebat cepat menyambar tubuh Patih Raksajunta. Tebasan golok orang Mongol itu hanya menghantam tanah kosong. Hal ini membuatnya bengong terheran-heran. Tapi belum lagi rasa herannya hilang, bayangan putih itu kembali datang berkelebat cepat.
“Akh...!” orang itu memekik keras, tubuhnya terpental jauh ke belakang.
Empat orang lainnya yang melihat kejadian itu terperanjat kaget. Namun tanpa diduga sama sekali bayangan putih itu sudah kembali berkelebat cepat ke arah empat orang itu. Mereka berlompatan mundur dengan cepat. Tapi dua orang yang terlambat menyelamatkan diri, harus menerima nasib naas dan hanya mampu menjerit keras. Tubuh mereka ambruk ke tanah dengan dada hancur melesak ke dalam.
Saat itu terdengar satu seruan keras dari arah belakang. Maka orang-orang Mongol itu pun segera berlarian mundur. Pada saat itu, seluruh prajurit Kerajaan Jiwanala sudah tergeletak tak bernyawa lagi. Sementara bayangan putih yang telah merobohkan tiga orang prajurit Mongol itu pun langsung lenyap tidak ketahuan arahnya. Orang-orang Mongol itu bergegas kembali ke kapalnya yang bersandar dekat dermaga.
********************
Sementara itu di dalam Istana Kerajaan Jiwanala, Prabu Duta Nitiyasa tengah berbincang-bincang dengan para panglima perang, para patih, dan pembesar istana lainnya. Di antara mereka tampak Panglima Sembada yang baru saja melaporkan keadaan pasukannya di pelabuhan. Prabu Duta Nitiyasa tampak diam membisu menerima laporan kekalahan itu.
Yang membuat Prabu Duta Nitiyasa terdiam bukan laporan kekalahan prajurit, tapi usulan Panglima Sembada yang menyarankan untuk mengundang tokoh-tokoh sakti dunia persilatan atau prajurit asing lainnya. Suasana di Balai Sema Agung itu jadi hening. Tidak ada seorang pun yang membuka suaranya.
“Kekuatan prajurit yang kita miliki memang tidak sebanding dengan mereka. Tapi itu bukan alasan yang tepat untuk berlindung di balik punggung orang lain. Kerajaan Jiwanala berdiri berkat darah dan keringat leluhur, dan wajib dipertahankan dengan darah juga,” tegas Prabu Duta Nitiyasa.
“Gusti Prabu, menurut hamba, saran yang diajukan Panglima Sembada patut dipertimbangkan,” seorang laki-laki tua berjubah kuning gading membuka suara.
Prabu Duta Nitiyasa menatap laki-laki berjubah kuning gading yang berkepala gundul itu. Laki-laki itu adalah Pendeta Naraboga, seorang penasehat pribadi Prabu Duta Nitiyasa.
“Paman Pendeta, sebaiknya Paman jangan berjiwa kerdil dan pengecut,” dingin suara Prabu Duta Nitiyasa.
“Ampun, Gusti Prabu. Bukannya hamba takut menghadapi mereka. Tapi menurut hemat hamba, tidak ada salahnya jika mencoba mengundang beberapa tokoh rimba persilatan untuk memperkuat barisan pertahanan,” kilah Pendeta Naraboga seraya memberi hormat.
“Hm...,” gumam Prabu Duta Nitiyasa pelan.
Saat itu seorang prajurit memasuki ruangan Balai Sema Agung. Prajurit itu segera membungkukkan tubuhnya, memberi hormat. Semua orang yang ada di ruangan itu memandangnya. Mereka tahu kalau prajurit yang tidak mengenakan seragam itu telah ditugaskan untuk memata-matai orang-orang Mongol di pelabuhan.
“Ampun, Gusti Prabu. Ada yang hendak hamba laporkan,” ucap prajurit mata-mata itu.
“Katakan,” perintah Prabu Duta Nitiyasa.
“Seluruh prajurit yang berada di Pelabuhan Timur tewas, sedangkan Patih Raksajunta menghilang,” lapor prajurit itu.
“Apa...?!” semua orang yang ada di Balai Sema Agung itu terperanjat kaget.
Terlebih lagi Panglima Sembada. Waktu meninggalkan prajuritnya, Patih Raksajunta tidak jauh dari pelabuhan. Dan baru beberapa saat dia berada di istana ini, telah datang laporan bahwa semua prajuritnya tewas. Yang lebih mengejutkan lagi, hilangnya Patih Raksajunta.
Prabu Duta Nitiyasa bangkit dari singgasananya, lalu melangkah ke depan. Dia berjalan mondar-mandir dengan wajah tertunduk. Keheningan kembali menyelimuti ruangan besar dan indah itu. Laporan prajurit tadi benar-benar mengejutkan semua orang.
“Panglima, siapkan seluruh prajurit!” perintah Prabu Duta Nitiyasa.
“Gusti...!” Panglima Sembada tersentak kaget.
“Ini perintah! Laksanakan segera!” bentak Prabu Duta Nitiyasa tegas.
“Hamba laksanakan, Gusti,” Panglima Sembada membungkuk hormat.
Dengan mengajak seluruh panglima perang lainnya, Panglima Sembada bergegas meninggalkan Balai Sema Agung. Prabu Duta Nitiyasa melangkah meninggalkan ruangan itu. Sedangkan Pendeta Naraboga mengikuti dari belakang bersama beberapa pembesar kerajaan lainnya.
“Gusti, apakah ini bukan tindakan yang merugikan? Pikirkanlah lebih matang lagi, Gusti,” Pendeta Naraboga berusaha mencegah maksud rajanya itu.
“Tidak ada jalan lain, Paman Pendeta. Orang-orang asing itu harus enyah secepatnya,” jawab Prabu Duta Nitiyasa mantap.
“Dengan mengerahkan seluruh prajurit, sama saja bunuh diri, Gusti.”
“Mati dalam pertempuran lebih terhormat daripada menjadi pengecut, Paman.”
“Hamba yakin masih ada jalan lain yang lebih baik, Gusti.”
Prabu Duta Nitiyasa menghentikan langkahnya. Ditatapnya tajam pendeta gundul itu. Pendeta Naraboga buru-buru membungkuk sambil merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada.
“Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya menyampaikan saran. Bukankah kita memiliki satu tawanan orang Mongol. Tawanan itu bisa dimanfaatkan untuk mengusir mereka, Gusti,” ujar Pendeta Naraboga.
“Tidak ada gunanya, Paman Pendeta. Mereka pun menawan Paman Patih Raksajunta. Aku tahu betul watak orang-orang Mongol itu. Bagi mereka, kehilangan satu nyawa bukan berarti apa-apa bila berhasil merebut satu daerah kekuasaan.”
“Memang benar, Gusti. Tapi...."
“Sudahlah, Paman Pendeta. Aku akan bersiap-siap. Katakan pada seluruh panglima untuk bergerak lebih dahulu ke pelabuhan. Nanti aku menyusul dan memimpin langsung seluruh pasukan!” sergah Prabu Duta Nitiyasa.
Setelah berkata demikian, Prabu Duta Nitiyasa membuka pintu sebuah kamar yang dijaga dua prajurit bersenjata tombak. Pendeta Naraboga hanya bisa membungkuk hormat, kemudian melangkah pergi setelah pintu kamar itu tertutup rapat. Jelas sekali kalau raut wajah pendeta gundul itu diliputi kecemasan. Dia sudah berusaha untuk melunakkan hati junjungannya, tapi dasarnya Prabu Duta Nitiyasa memang seorang raja yang keras. Segala keputusannya tidak bisa dirubah lagi.
Prabu Duta Nitiyasa mengganti bajunya dengan pakaian perang. Sebilah pedang panjang tergantung di pinggang-nya. Sebentar dipandangi tombak pusaka peninggalan leluhurnya. Tombak yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Jiwanala. Dengan tombak pusaka itu kerajaan ini terlindungi dari serangan bangsa lain.
“Kanda...,” satu suara halus terdengar dari arah belakang.
Prabu Duta Nitiyasa membalikkan tubuhnya. Pandangannya langsung tertumbuk pada seorang wanita cantik yang memakai baju biru indah dari kain sutra halus. Tatapan wanita itu kosong dan matanya agak berkaca-kaca, tertuju pada selendang putih yang mengikat leher Prabu Duta Nitiyasa. Selendang putih yang melambangkan satu tekad untuk mempertahankan negara sampai titik darah yang penghabisan.
Prabu Duta Nitiyasa melangkah menghampiri permaisurinya itu. Dipegangnya bahu Permaisuri Dita Wardhani dengan kedua tangannya. Wanita berwajah cantik itu mengangkat kepalanya, langsung menatap ke bola mata yang juga tengah menatapnya. Bibirnya yang merah bergetar, namun tidak ada satu kata pun yang terucapkan. Prabu Duta Nitiyasa mendekatkan wajahnya, dan mengecup lembut bibir itu.
“Urungkan niat Kanda untuk berperang. Lihat anak kita...,” ucap Permaisuri Dita Wardhani seraya memalingkan mukanya, menatap pada wajah mungil yang tergolek di pembaringan. “Dia membutuhkanmu, Kanda.”
“Negara ini juga membutuhkan sumbangan tenagaku, Dinda,” sahut Prabu Duta Nitiyasa.
“Tapi....”
“Ssst.... Percayalah! Aku pasti akan kembali dengan selamat,” potong Prabu Duta Nitiyasa cepat.
“Kanda, tidakkah sebaiknya Kanda meminta bantuan pada Ayah. Pasti Ayahanda Resi bersedia membantu mengusir orang-orang asing itu,” usul Permaisuri Dita Wardhani.
Prabu Duta Nitiyasa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Dia tahu kalau ayah istrinya ini memiliki murid-murid yang cukup handal dan berkemampuan tinggi. Sebagai seorang resi beraliran lurus, tentu saja bersedia membantu mengusir orang asing yang berniat buruk. Tapi itu tidak dilakukannya, karena hanya mengusir satu pasukan asing saja. Terlalu riskan rasanya. Lagi pula, kelihatannya dia masih mampu menghadapi mereka.
“Kenapa? Apakah Kanda ingin melihat kehancuran kerajaan ini? Membiarkan para prajurit dibantai orang-orang Mongol itu? Apa Kanda sudah tidak bisa lagi melihat kenyataan? Sadarlah, Kanda. Carilah jalan keluar lain. Jangan mengorbankan banyak orang hanya untuk mengusir segelintir orang asing,” Permaisuri Dita Wardhani mencoba menyadarkan suaminya.
Prabu Duta Nitiyasa langsung terdiam. Kata-kata permaisurinya sungguh menyentuh sanubarinya yang paling dalam. Keputusan yang diambil tadi memang karena luapan rasa amarah setelah mendengar satu pasukan prajuritnya tewas, dan Patih Raksajunta menghilang entah ke mana. Tapi untuk meminta bantuan, keangkuhannya selalu mengalahkan kenyataan yang dihadapi saat ini.
“Gusti...! Gusti Prabu...!”
Tiba-tiba saja terdengar suara memanggil dari luar pintu, disertai ketukan yang beruntun. Prabu Duta Nitiyasa bergegas melangkah ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Tampak seorang punggawa bersama enam orang prajurit telah berdiri di depan pintu dan segera membungkuk memberi hormat
“Ada apa?” tanya Prabu Duta Ni-tiyasa.
“Ampun, Gusti. Mereka..., mereka...,” punggawa itu tergagap.
“Punggawa, katakan yang jelas!” bentak Prabu Duta Nitiyasa.
“Mereka telah mengepung istana, Gusti,” lapor punggawa itu.
“Apa...?!” Prabu Duta Nitiyasa tersentak kaget.
“Seluruh gerbang masuk sudah ditutup, Gusti. Seluruh prajurit mereka pun sudah disiagakan,” punggawa itu kembali melaporkan.
“Bagaimana dengan Panglima Sembada?”
“Panglima Sembada dan dua orang panglima lainnya sudah bergerak ke pelabuhan membawa seratus prajurit, Gusti.”
“Seratus...?!”
“Benar, Gusti.”
Prabu Duta Nitiyasa jadi bingung juga. Seratus prajurit telah meninggalkan istana, artinya tinggal lima puluh prajurit lagi yang tersisa. Kerajaan Jiwanala memang kecil, sehingga jumlah prajuritnya hanya sedikit. Hanya beberapa ratus orang saja jumlahnya. Jelas saja Prabu Duta Nitiyasa kini kelabakan.
“Ada lagi yang hendak hamba laporkan, Gusti. Panglima Sembada juga membawa tawanan orang Mongol itu.”
“Jagat Dewa Batara...!” keluh Prabu Duta Nitiyasa. “Untuk apa dia membawa tawanan orang Mongol segala?!”
“Hamba tidak tahu pasti, Gusti.”
“Punggawa, panggil Punggawa Narayama ke sini,” perintah Prabu Duta Nitiyasa.
“Hamba, Gusti Prabu.”
Punggawa itu bergegas pergi setelah memberi hormat lebih dahulu. Dua orang prajurit mendampinginya, sedangkan sisanya menjaga di depan pintu. Prabu Duta Nitiyasa melangkah menghampiri permaisurinya yang telah menggendong bayi tunggalnya. Seorang bayi laki-laki yang montok dan sehat.
“Bereskan barang-barangmu seperlunya. Bawa beberapa dayang. Tidak ada waktu lagi, Dinda. Kau dan anak kita harus selamat dari kehancuran ini,” kata Prabu Nitiyasa.
“Kanda....”
“Pergilah ke padepokan ayahmu, dan ceritakan apa yang terjadi semuanya di sini.”
Setelah berkata demikian, Prabu Duta Nitiyasa melangkah keluar dari kamar ini. Tapi baru saja kakinya menjejak ambang pintu, Punggawa Narayama datang tergesa-gesa bersama punggawa yang tadi telah melaporkan keadaan.
“Hamba datang memenuhi panggilan, Gusti Prabu,” ucap Punggawa Narayama seraya menghaturkan sembah.
“Punggawa Narayama, kau kutugaskan untuk menyelamatkan anak dan permaisuriku. Bawa mereka ke Padepokan Arang Watu. Bawa juga beberapa prajurit pengawal,” perintah Prabu Duta Nitiyasa.
“Segala titah Gusti Prabu hamba laksanakan,” sahut Punggawa Narayama hormat.
“Bergegaslah, tidak ada waktu lagi. Gunakan lorong rahasia. Kau tahu letaknya, bukan?”
“Hamba, Gusti.”
“Nah, berangkatlah. Keselamatan keluargaku ada di tanganmu.”
Punggawa Narayama memberi hormat. Prabu Duta Nitiyasa melangkah keluar melalui lorong istana yang panjang, diiringi pengawal khusus yang sangat terlatih. Punggawa Narayama bergegas menunjuk prajurit-prajurit pilihannya dan menyerahkan sisa prajurit lain pada punggawa yang ada. Tugas yang diembannya kali ini tidak ringan. Permaisuri dan putra mahkota harus diselamatkan keluar dari Kerajaan Jiwanala.
********************
Sementara itu jauh di batas Kerajaan Jiwanala, tampak seorang laki-laki tua duduk tepekur di atas bata sambil memandang ke arah kerajaan yang tampak sepi lengang. Di bagian timur terlihat tiang-tiang kapal dan layar perahu yang tertutup, terombang-ambing dipermainkan ombak laut. Laki-laki tua itu hampir satu harian duduk diam dengan pandangan ke satu arah.
“Paman Raksajunta....”
“Kau Rangga...?” laki-laki tua yang ternyata memang Patih Raksajunta mengangkat kepalanya seraya mendesah panjang.
Seorang pemuda tampan berbaju rompi putih duduk di sampingnya. Patih Raksajunta tidak bergeming sedikit pun. Pandangannya tetap lurus ke depan.
“Hampir satu harian kau duduk di sini, Paman,” kata Rangga pelan. Pandangannya juga mengarah pada Kerajaan Jiwanala.
“Hhh...!” Patih Raksajunta hanya menarik napas panjang.
“Aku bisa merasakan kecemasanmu, Paman...,” kata Rangga pelan. “Hm.... Oh ya, tadi aku sempat jalan-jalan ke kota.”
“Apa yang kau lihat di sana?” tanya Patih Raksajunta.
Rangga tidak langsung menjawab, tapi malah bangkit dari duduknya dan melangkah tiga tindak ke depan. Patih Raksajunta ikut berdiri dan mendekati Pendekar Rajawali Sakti itu.
“Aku berhutang budi padamu karena kau telah menyelamatkan nyawaku, Rangga. Tapi kerajaanku juga terancam kehancuran saat ini. Sebagai seorang pendekar tangguh dan digdaya, aku yakin kau tidak akan membiarkan kehancuran dan penindasan merajalela di depan matamu,” kata Patih Raksajunta menggugah hati Pendekar Rajawali Sakti itu.
“Paman, aku juga pernah menghadapi hal seperti ini. Bukan hanya satu atau dua kali saja, bahkan sering kutemukan dalam pengembaraanku. Tidak mudah memang. Tapi perlu pemikiran yang matang, di samping kekuatan dan semangat,” kata Rangga mencoba menjelaskan.
“Bisa kumengerti, Rangga.”
“Aku harap, Prabu Duta Nitiyasa juga tidak terpancing. Tindakan gegabah akan membuat keadaan semakin hancur tak terkendali.”
“Memang. Tapi itu jika dikatakan dalam satu atau dua hari yang lalu, Rangga. Rasanya saat ini sudah terlambat. Kulihat ada serombongan pasukan berkuda memasuki kota. Juga sepasukan lainnya keluar dari kota melalui jalan lain. Aku rasa hal itu satu pertanda buruk.”
Rangga diam sambil menatap laki-laki tua di sampingnya. Yang dikatakan Patih Raksajunta barusan memang benar. Waktu berjalan-jalan ke kota tadi, dia melihat orang-orang asing bergerak memasuki kota. Bersamaan dengan itu, satu pasukan yang berjumlah seratus prajurit juga bergerak keluar dari jalan lain menuju pelabuhan.
Tiba-tiba terdengar satu ledakan keras, disusul dengan berkobarnya api yang sangat besar dari arah pelabuhan. Rangga dan Patih Raksajunta langsung berpaling memandang ke arah kobaran api itu. Tampak sebuah kapal berukuran sangat besar tengah dilalap api yang berkobar dahsyat. Juga terlihat banyak prajurit membawa lambang Kerajaan Jiwanala di sekitar pelabuhan itu. Dari tempat ketinggian seperti ini, memang cukup jelas melihat seluruh pelosok kerajaan itu.
“Kapal Mongol...,” desis Patih Raksajunta.
“Gegabah!” gumam Rangga mendesis karena menahan gusar melihat kapal dari Daratan Mongol itu terbakar.
“Api sudah tersulut. Peperangan tidak mungkin dihindarkan lagi,” gumam Patih Raksajunta.
Rangga diam saja.
“Tidak ada waktu lagi, Rangga. Atas nama Prabu Duta Nitiyasa, aku mohon bantuanmu untuk mengusir orang-orang Mongol itu,” pinta Patih Raksajunta penuh harap.
“Hhh...!” Rangga menarik napas berat.
Patih Raksajunta tidak sempat lagi menunggu sabar. Dia bergegas berlari menggunakan ilmu lari cepatnya menuruni bukit ini.
“Paman, tunggu!” seru Rangga keras.
“Mereka membutuhkanku, Rangga!” sahut Patih Raksajunta tanpa menghentikan larinya.
Rangga tidak punya pilihan lain lagi dan segera melompat cepat mengejar laki-laki tua itu. Hanya tiga kali lompatan saja, Pendekar Rajawali Sakti itu sudah mengejar Patih Raksajunta, dan langsung mencegatnya. Patih Raksajunta menghentikan larinya.
“Jangan menghalangiku, Rangga. Walaupun Kerajaan Jiwanala terpaksa hancur, aku berkewajiban menyelamatkan keluarga Gusti Prabu,” kata Patih Raksajunta dengan napas terengah.
“Percuma saja, Paman. Kulihat mereka telah mengepung istana. Tidak ada celah untuk menerobos kepungan mereka,” kata Rangga.
“Aku bisa melalui jalan rahasia.”
“Jalan rahasia...?”
“Ya, jalan menuju istana melalui lorong. Hanya beberapa orang saja mengetahuinya, terutama yang dekat dengan Gusti Prabu, termasuk aku.”
“Hm.... Kalau begitu, marilah kita segera kesana,” ajak Rangga.
“Lebih cepat, lebih baik.”
Kedua orang itu bergegas berlari menuruni bukit. Rangga mengikuti saja ke mana Patih Raksajunta pergi. Mereka berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Kalau mau, sebenarnya Pendekar Rajawali Sakti bisa meninggalkan Patih Raksajunta. Hanya saja dia belum tahu jalan yang akan ditempuh.
EMPAT
Patih Raksajunta menghentikan larinya ketika tiba di sebuah celuk yang tidak begitu dalam. Pada dinding celuk itu terdapat sebuah mulut goa buatan yang tidak begitu besar ukurannya. Di sekitar celuk itu banyak terdapat semak kering dan ranting-ranting. Juga terdapat rangkaian bambu selebar celuk itu.
“Jagat Dewa Batara...!” desis Patih Raksajunta terperangah di pinggir celuk.
“Ada apa, Paman Patih?” tanya Rangga.
“Kau lihat tangga bambu ini?”
Rangga memperhatikan tangga bambu yang ditunjuk Patih Raksajunta. Tangga bambu itu sudah hancur. Dan kelihatannya, di dasar celuk juga terdapat banyak jejak kaki manusia.
“Ada orang yang telah melewati jalan rahasia ini. Aku tidak tahu siapa mereka,” gumam Patih Raksajunta.
“Banyak jejak di sekitar sini. Bagaimana kalau kita ikuti jejaknya, Paman?” usul Rangga.
“Mana yang akan kau pilih?” Patih Raksajunta memberikan pilihan pada Pendekar Rajawali Sakti itu.
“Hm...,” Rangga tidak segera menjawab. Dipandangi semua jejak kaki yang terdapat di sekitarnya. Tidak mudah mengambil satu keputusan tepat.
Perlahan-lahan Pendekar Rajawali Sakti itu mengikuti jejak-jejak kaki yang kelihatannya masih baru, lalu tidak berapa lama berhenti. Jejak-jejak kaki itu berkumpul dan menuju ke satu arah. “Paman, kemari!” seru Rangga seraya berlutut.
Patih Raksajunta menghampiri. Saat itu Rangga menjumput sesuatu di ujung jari kakinya. Dia berdiri dan berbalik menghadap Patih Raksajunta.
“Aku temukan ini, mungkin kau mengenalinya,” Rangga menunjukkan sebuah arnel yang terbuat dari emas, berhias baru permata.
“Arnel ini milik Gusti Permaisuri,” Patih Raksajunta mengenali tusuk rambut itu.
“Itu berarti keluarga Prabu Duta Nitiyasa sudah selamat, Paman.”
“Belum.”
“Belum...?!” Rangga mengerutkan keningnya.
Baru saja Patih Raksajunta akan membuka mulut, tiba-tiba sebatang tombak melesat cepat menuju ke arah mereka. Tak lama kemudian, disusul puluhan anak panah yang meluncur.
“Paman, awas...!” seru Rangga keras.
“Akh...!” Patih Raksajunta memekik keras tertahan.
Sebatang anak panah menancap dalam di bahu kanan laki-laki tua itu. Rangga cepat melompat ke arahnya, tapi serbuan anak panah itu demikian cepat. Niatnya untuk menolong Patih Raksajunta pun terhambat. Pendekar Rajawali Sakti itu berjumpalitan di udara menghindari serbuan anak panah yang datang bagai hujan.
Sementara itu Patih Raksajunta menarik tubuhnya menjauh. Sesekali dikibaskan pedangnya dengan tangan kiri untuk menghalau anak panah yang terarah padanya. Sedangkan Rangga sendiri masih sibuk menghindari serbuan anak panah yang mengancam dirinya. Namun Pendekar Rajawali Sakti itu tetap berusaha mendekati Patih Raksajunta.
“Hiyaaat..!”
Sambil berteriak keras, Rangga melentingkan tubuhnya tinggi-tinggi ke udara, lalu dengan cepat menukik ke bawah. Bagaikan seekor rajawali, Rangga menyambar tubuh Patih Raksajunta, dan langsung membawanya pergi. Hujan anak panah itu terus menyerbu ke arah mereka. Namun gerakan Pendekar Rajawali Sakti itu demikian cepat, sehingga dalam sekejap saja sudah lenyap di balik lebatnya pepohonan.
Rangga terus berlompatan disertai pengerahan ilmu meringankan tubuhnya yang telah mencapai taraf kesempurnaan. Sebentar saja dia sudah jauh dari situ. Rangga berhenti, lalu menurunkan Patih Raksajunta dari pondongannya. Sebatang anak panah masih menancap dalam di bahu kanan laki-laki tua itu.
“Untung panah ini tidak beracun,” gumam Rangga setelah memeriksa sekitar bahu kanan Patih Raksajunta.
“Terima kasih. Dua kali aku telah berhutang nyawa padamu,” ucap Patih Raksajunta.
“Ah, sudahlah. Yang penting sekarang anak panah ini harus dicabut.”
“Lakukan saja, Rangga.”
“Tahan sedikit, Paman.”
“Lakukan.”
Rangga menggenggam batang anak panah itu. Dengan sekuat tenaga ditekannya anak panah itu sampai menembus bahu. Patih Raksajunta memekik tertahan. Pendekar Rajawali Sakti itu mematahkan ujung panah, lalu menarik batangnya hingga ke luar. Kembali Patih Raksajunta memekik keras tertahan. Darah langsung keluar dari luka di bahu itu. Rangga segera menotok jalan darah di sekitar bahu Patih Raksajunta, sehingga darah seketika berhenti mengalir. Kemudian disobeknya ujung baju laki-laki tua itu, dan dibalutnya luka yang cukup dalam itu.
“Kau tidak apa-apa, Paman?” tanya Rangga ketika melihat keadaan laki-laki tua itu yang nampaknya lemas.
“Tidak. Aku tidak apa-apa,” sahut Patih Raksajunta pelan.
“Telah kububuhkan bubuk obat, mudah-mudahan luka itu cepat mengering,” kata Rangga seraya menghenyakkan tubuhnya di samping Patih Raksajunta.
“Terima kasih,” ucap Patih Raksajunta singkat.
Patih Raksajunta berusaha bangkit berdiri. Pedangnya dijadikan penopang tubuh, sehingga dia mampu berdiri meskipun agak limbung. Sedangkan Rangga masih tetap duduk memandanginya. Tampak raut wajah laki-laki tua itu terlihat mendung. Tatapannya tidak lepas ke arah bangunan istana yang terlihat jelas dari tempat ini. Mereka memang tidak berapa jauh di belakang bangunan istana itu.
“Mereka pasti sudah menguasai Istana Jiwanala,” gumam Patih Raksajunta lirih.
Rangga hanya bisa menarik napas panjang, tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Bisa dirasakan, apa yang tengah melanda hati laki-laki tua itu. Seumur hidupnya Patih Raksajunta telah mengabdikan diri pada Kerajaan Jiwanala. Dan kini di masa sisa-sisa hidupnya, dia harus melihat kehancuran kerajaan kecil ini. Terlalu sukar untuk dilukiskan perasaannya saat ini. Yang jelas, Rangga melihat bola mata Patih Raksajunta merembang berkaca-kaca.
********************
Malam ini angin berhembus agak keras membawa udara dingin yang meng-gigilkan tulang. Langit tampak kelam tanpa satu bintang pun berkelap-kelip. Seakan-akan alam turut berduka dengan kehancuran Kerajaan Jiwanala di pesisir pantai ini. Seluruh kota tampak sepi bagaikan mati. Tidak ada seorang pun yang terlihat berkeliaran seperti hari-hari sebelumnya.
Bahkan rumah-rumah penduduk pun tampak gelap gulita. Hanya beberapa saja yang masih kelihatan terang oleh pelita kecil yang menyala redup. Malam yang hening dan dingin ini rupanya tidak menghalangi kelebatan sesosok bayangan putih dari atap rumah yang satu ke atap lainnya.
“Hup...!”
Bayangan putih itu langsung menuju ke Istana Jiwanala. Gerakannya begitu ringan tanpa suara sedikit pun. Kecepatannya sukar diikuti pandangan mata biasa. Bayangan itu melenting indah dengan cepat ke atas atap bangu-nan istana itu. Sebentar berhenti merapatkan tubuhnya pada atap, kemudian melesat lagi meluruk ke bawah.
Dengan merapatkan dirinya ke dinding, bayangan itu bergerak cepat menghampiri sebuah jendela besar yang tampak terang benderang. Dari jendela itu dapat terlihat suasana dalam istana. Tampak orang-orang Mongol tengah berpesta pora merayakan kemenangannya merebut istana ini.
“Hai...!”
Tiba-tiba saja terdengar bentakan keras. Orang yang tengah mengamati riuhnya pesta pora dari jendela itu tampak terkejut. Dan belum lagi hilang rasa terkejutnya, mendadak sebatang tombak melesat cepat ke arahnya.
“Hup!”
Tangkas sekali tubuhnya melenting ke atas, dengan menggunakan ujung jari kaki untuk menjejak batang tombak di bawahnya. Dengan satu gerakan manis, dia berputar di udara, lalu meluruk cepat ke arah seorang prajurit Mongol yang memergokinya. Gerakan orang itu demikian cepat, sehingga prajurit Mongol itu tidak sempat lagi berbuat sesuatu.
Des...!
“Heghk!”
Tanpa bersuara sedikit pun orang itu berhasil menyarangkan pukulannya ke leher prajurit Mongol itu. Buru-buru disangganya tubuh orang Mongol yang besar dan berat itu, lalu diseretnya masuk ke dalam semak rumpun bunga mawar. Orang berbaju putih tanpa lengan itu kembali bergerak cepat mendekati jendela. Sebentar mengamati keadaan dalam, lalu tubuhnya kembali melenting ke atas dan hinggap di atap.
“Hm..., di mana ruang penjara yang mereka maksudkan?” terdengar gumaman pelan yang sangat halus.
Orang itu kembali bergerak lincah, berlompatan di atas atap bangunan istana itu. Gerakannya begitu ringan, seolah-olah tidak menapak pada atap. Sampai di bagian belakang istana, dia langsung meluruk turun. Ringan sekali kakinya menjejak tanah. Sepasang matanya yang tajam langsung melihat seorang prajurit Mongol tengah memaksa seorang wanita di antara rumpun pohon perdu.
“Binatang...!” orang itu bergumam menggeram.
Slap!
Hanya satu lompatan saja, tubuhnya telah mencapai prajurit Mongol yang tengah dirasuki nafsu iblis itu. Satu pukulan telak telah mendarat di tengkuk prajurit Mongol itu, yang kemudian hanya mengeluh sedikit, lalu ambruk tak berkutik. Tulang lehernya patah seketika. Wanita muda yang pakaiannya sudah tidak karuan itu bergegas beringsut seraya merapikan bajunya.
“Oh...!”
“Ssst...!” orang berpakaian putih tanpa lengan itu menekap mulut wanita itu, lalu menyeretnya masuk lebih ke dalam semak perdu. Kemudian diseretnya juga mayat prajurit Mongol itu hingga tidak tampak dari luar.
“Siapa kau?” tanya wanita itu berbisik pelan. Nampaknya sudah agak tenang begitu menyadari laki-laki muda tampan ini tidak bermaksud buruk, bahkan akan menolongnya keluar dari neraka ini.
“Di mana Prabu Duta Nitiyasa dipenjarakan?” laki-laki berbaju putih tanpa lengan itu malah balik bertanya.
“Tidak tahu,” sahut wanita itu menggeleng lemah. “Hanya mereka yang tahu.”
“Hm..., kau siapa? Mengapa bisa sampai jatuh ke tangan mereka?”
“Aku seorang dayang yang tidak ikut mengungsi bersama Gusti Permaisuri. Masih banyak dayang dan pelayan lain di dalam istana. Bahkan pengurus istana juga ada di dalam. Mereka semua tidak dapat keluar. Seluruh istana ini sudah dikuasai orang-orang asing itu,” jelas wanita itu.
“Siapa namamu?”
“Parti. Raden siapa?”
“Hm...,” laki-laki berbaju putih itu tidak menjawab, tapi hanya menggumam saja tidak jelas. “Sebaiknya kau cepat tinggalkan tempat ini.”
“Tidak mungkin, mereka sudah menjaga ketat istana ini.”
“Kalau begitu...,” laki-laki muda itu tidak melanjutkan ucapannya.
Pada saat itu dua orang prajurit Mongol lewat. Dua orang dari Daratan Mongol itu menyeret seorang wanita yang meronta-ronta sambil menjerit histeris. Tapi kedua orang Mongol itu terus menyeretnya sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara dari tempat persembunyian, pemuda itu menggeram muak melihatnya.
“Iblis...!” geramnya murka. “Kalian harus mampus! Hih...!”
Pemuda tampan berbaju putih tanpa lengan itu langsung melompat cepat, dan...
Bug! Bug!
“Heg!”
Dua orang prajurit Mongol itu kontan ambruk ke tanah begitu mendapat dua pukulan keras di punggungnya. Wanita yang berada di dalam semak belukar segera keluar dan berlari menghampiri wanita yang menangis begitu terlepas dari cengkeraman tangan kotor orang asing itu.
Kedua wanita itu saling berpelukan. Sedangkan pemuda yang berdiri di antara kedua mayat orang Mongol itu tidak punya waktu lagi. Keberadaan dua wanita itu bisa menyulitkannya. Dengan cepat dia melompat sambil menyambar mereka. Begitu cepatnya melesat, tahu-tahu sudah melewati pagar tembok benteng istana dan mendarat di luar benteng. Kedua wanita itu terperangah, sehingga tidak mampu berkata-kata. Mulut mereka hanya mampu terbuka lebar.
“Cepat kalian pergi ke arah barat. Ada seseorang yang menunggu di sana,” kata pemuda itu setengah berbisik.
“Raden...,” salah seorang wanita itu ingin berkata.
“Cepat! Aku akan membebaskan yang lainnya,” potong pemuda itu cepat.
Kedua wanita itu tidak bisa lagi membantah. Mereka segera berlari sekuat mungkin ke arah yang ditunjuk pemuda yang menolongnya tadi. Setelah kedua wanita itu tidak kelihatan lagi, pemuda berbaju putih tanpa lengan itu bergegas melompat melewati pagar benteng yang tinggi dan kokoh itu. Cepat sekali gerakannya, sehingga dalam sekejap saja sudah lenyap di balik pagar.
Malam ini terasa begitu lambat berlalu. Di dalam istana masih terdengar suara-suara orang berpesta. Suara tawa terbahak-bahak ditingkahi jerit dan pekik wanita yang ketakutan. Itupun masih ditambah suara cambuk yang menggeletar memecah keheningan malam ini. Pemuda tampan berbaju putih dengan bagian depan terbuka itu mengendap-endap mendekati satu bangunan batu yang kasar dan berlumut tebal. Bangunan batu itu mirip sebuah tungku api raksasa. Hanya ada satu pintu terbuat dari baja tebal, yang dikawal empat orang prajurit Mongol. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa yang sukar dimengerti. Pemuda berbaju putih itu semakin mendekati, lalu menyelinap di balik pepohonan.
“Uts...!”
Tiba-tiba saja dia berhenti begitu merasakan kakinya membentur sesuatu. Jantungnya serasa berhenti berdetak begitu melihat sesosok tubuh wanita hampir polos terbujur di depannya. Seluruh tubuhnya banyak terdapat luka goresan yang cukup dalam. Darah masih mengalir membasahi kulit tubuhnya yang putih mulus itu.
Tidak jauh dari mayat wanita itu, terdapat beberapa mayat lagi. Dari pakaiannya dapat diketahui kalau itu adalah mayat para prajurit. Namun jika dilihat dari luka-luka yang ada, mereka seperti bukan tewas dalam pertarungan, melainkan karena mendapat siksaan yang kejam.
Pemuda berbaju rompi putih itu menggeretakkan rahangnya menahan geram. Kepalanya terdongak ketika tiba-tiba terdengar jeritan seorang wanita yang melengking tinggi. Sepertinya tidak begitu jauh dari tempatnya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, pemuda tampan itu melompat ke arah sumber jeritan tadi. Tubuhnya melambung tinggi ke udara, lalu hinggap pada atap belakang istana ini.
“Iblis...!” pemuda itu menggeram.
Rasanya dia tidak sanggup melihat pemandangan yang berada di bagian sayap halaman istana ini. Tampak enam orang prajurit Mongol sibuk mempermainkan seorang wanita yang pakaiannya sudah tak menentu lagi. Wanita itu lari ke sana kemari sambil menjerit-jerit ketakutan. Tapi enam orang asing itu selalu dapat menangkapnya. Setiap kali tertangkap, satu sayatan pisau merobek kulit wanita itu. Dan setiap kali itu pula, terdengar jerit keras kesakitan.
“Yang Maha Agung..., bencana apa yang sedang Kau timpakan pada kerajaan ini...?” keluh pemuda itu dalam hati.
Dipalingkan mukanya, karena tidak sanggup melihat kekejaman yang berlangsung di depan matanya. Wanita malang itu benar-benar tidak berdaya lagi. Dia tersuruk jatuh. Maka, seorang prajurit yang sudah tidak berpakaian lagi langsung menubruknya. Sedangkan yang lainnya melihat sambil tertawa-tawa. Wanita itu berusaha memberontak sekuat tenaga. Namun dalam keadaan tubuh terluka, rasanya tak ada daya sama sekali.
Prajurit Mongol itu begitu buas memperkosanya. Belum lagi hilang penderitaan wanita itu, seorang lagi menggumulinya dengan paksa. Wanita itu hanya bisa merintih, tidak mampu lagi melakukan perlawanan. Enam orang Mongol itu benar-benar bagai binatang liar kelaparan. Setelah puas, wanita itu ditebas lehernya hingga tewas. Sementara pemuda berbaju rompi putih di atas atap hanya mampu menggeram menahan amarah.
Sambil tertawa-tawa, enam orang asing itu melangkah meninggalkan wanita yang malang itu. Beberapa kali pemuda berbaju rompi putih di atas atap menarik napas dalam-dalam berusaha untuk menenangkan dirinya. Memang, dia mudah saja membantai enam orang itu. Tapi jumlah yang lainnya tidak sedikit, sehingga mustahil bisa menghadapi semuanya seorang diri. Bagaimanapun juga harus dicari kesempatan yang baik dan perencanaan yang matang.
“Prabu Duta Nitiyasa harus kubebaskan lebih dahulu. Aku yakin dia dikurung dalam penjara itu,” bisiknya dalam hati.
Pemuda tampan berbaju rompi putih itu segera melentingkan tubuhnya mendekati bangunan yang diduga sebagai penjara bawah tanah. Dia paham betul tentang seluk-beluk sebuah istana. Meskipun di kerajaan lain dengan bentuk bangunan yang berbeda, tapi pada dasarnya setiap bangunan istana mempunyai ciri yang sama.
“Hait...!”
Pemuda itu langsung bergerak cepat mengibaskan tangannya ke arah empat orang prajurit yang menjaga pintu bangunan batu itu. Serangan yang tiba-tiba dan bagaikan kilat itu tidak sempat lagi diketahui. Empat prajurit Mongol itu kontan ambruk tanpa menimbulkan suara sedikit pun.
“Hhh! Terkunci...!” dengus pemuda itu saat berusaha membuka pintu baja itu.
Didekati satu persatu mayat prajurit penjaga itu dan diperiksanya. Pada salah seorang prajurit, ditemukan serangkaian kunci. Pemuda itu bergegas kembali menghampiri pintu dan mencoba semua kunci yang ditemukannya. Beruntung, salah satu kunci itu pas. Maka pintu baja itupun berhasil dibukanya.
“Siapa itu...?” terdengar suara dari dalam.
“Prabu Duta Nitiyasa...?” pemuda itu bertanya ingin meyakinkan.
Ruangan yang semula gelap gulita mendadak jadi terang benderang oleh pelita yang dinyalakan. Tampak seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun berdiri di tengah-tengah ruangan yang tidak begitu besar dan berdinding batu. Laki-laki itu mengenakan pakaian perang dan selendang putih yang melilit lehernya. Sebuah sarung pedang yang kosong tergantung di pinggangnya.
“Cepatlah keluar sebelum mereka mengetahuinya, Gusti Prabu,” ajak pemuda itu.
“Siapa kau?” tanya Prabu Duta Nitiyasa.
“Tidak ada waktu menjelaskannya, Gusti. Maaf.... Hup!”
“Hey...!”
Prabu Duta Nitiyasa terperanjat begitu tiba-tiba pemuda berbaju rompi putih itu menyergap, lalu menotok tubuhnya. Akibatnya Prabu Duta Nitiyasa lemas seketika. Sebelum kesadarannya hilang, Raja Jiwanala itu masih sempat melihat kalau pemuda itu membawanya keluar dari dalam penjara khusus ini. Dan selanjutnya tidak ingat lagi. Kesadarannya langsung lenyap bersamaan dengan melesatnya tubuh pemuda itu melewati pagar tembok benteng sebelah barat.
LIMA
“Gusti Prabu...!” Patih Raksajunta terperanjat begitu melihat Prabu Duta Nitiyasa tiba-tiba berada di depannya.
Di samping Prabu Duta Nitiyasa berdiri seorang pemuda berwajah tampan berbaju rompi putih. Gagang pedang berbentuk kepala burung menyembul dari balik punggungnya. Patih Raksajunta langsung menjatuhkan diri berlutut. Dua orang wanita yang diselamatkan dari Istana Jiwanala turut berlutut memberi sembah.
“Bangunlah kalian,” kata Prabu Duta Nitiyasa berwibawa.
“Ampun, Gusti,” ucap Patih Raksajunta.
Patih Raksajunta bangkit berdiri diikuti dua orang wanita di belakangnya. Prabu Duta Nitiyasa menoleh pada pemuda di sampingnya. Ditepuknya pundak pemuda itu disertai senyuman.
“Kisanak, kuucapkan banyak terima kasih. Kau telah menyelamatkanku,” ucap Prabu Duta Nitiyasa.
“Ah. Ini semua berkat Paman Patih, Gusti,” sahut pemuda itu merendah.
“Hm...,” Prabu Duta Nitiyasa memandang Patih Raksajunta.
“Ampun, Gusti. Pemuda ini bernama Rangga, seorang pendekar kelana yang juga menyelamatkan nyawa hamba. Dia bergelar Pendekar Rajawali Sakti,” ujar Patih Raksajunta seraya memberi hormat.
“Ah..., tidak kusangka. Pendekar besar dan digdaya ternyata masih begitu muda,” ungkap Prabu Duta Nitiyasa.
“Gusti, sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Rasanya masih kurang aman dan terlalu dekat dengan istana,” Rangga membelokkan arah pembicaraan.
Baru saja Rangga berkata demikian, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut, disusul munculnya beberapa orang prajurit Mongol.
“Cepat, tinggalkan tempat ini!” seru Rangga seraya melompat.
“Mari, Gusti,” ajak Patih Raksajunta.
“Tunggu sebentar! Kita tidak bisa meninggalkan dia sendirian.”
“Gusti, Rangga pasti bisa menghadapi mereka sendirian. Mari tinggalkan tempat ini,” bujuk Patih Raksajunta.
Sebentar Prabu Duta Nitiyasa berpikir, kemudian melangkah meninggalkan tempat ini. Sementara orang-orang Mongol yang muncul sudah dihadang Pendekar Rajawali Sakti. Pendekar muda itu memancing perhatian orang-orang asing itu agar tertumpah padanya. Tapi sempat juga diperhatikan Prabu Duta Nitiyasa, Patih Raksajunta, dan dua orang dayang yang telah meninggalkan tempat ini.
Rangga tidak bisa lagi menghindari pertempuran. Orang-orang dari Daratan Mongol itu langsung menyerang ganas. Mereka bagaikan binatang liar yang menemukan mangsa di tengah padang. Sepuluh orang itu menyerang tanpa memberi kesempatan bernapas sedikit pun pada Rangga.
Tapi Pendekar Rajawali Sakti itu kelihatannya memang sengaja memperlambat pertempuran. Tidak satu pun dilontarkan pukulan balasan. Rangga hanya menggunakan jurus Sembilan Langkah Ajaib. Jurus ini memang mengandalkan kecepatan gerak kaki dan kelenturan tubuh untuk menghindari setiap seran-gan yang datang. Jadi tidak heran jika setiap serangan orang Mongol itu sulit untuk menyentuh tubuhnya sedikit pun.
“Hm..., mereka sudah jauh. Aku harus menyelesaikan pertarungan menjemukan ini,” gumam Rangga dalam hati.
Seketika itu juga dirubah jurusnya. Rangga mengerahkan jurus ‘Pukulan Maut Paruh Rajawali’. Dengan jurus itu kedua tangannya bagaikan sepasang palu godam yang siap menghancurkan apa saja. Satu persatu orang Mongol itu dibuat ambruk tidak berkutik lagi. Setiap pukulannya mengandung hawa panas yang membuat lawan merasa sesak dan tidak mampu lagi menghindar.
“Hiya! Hiya! Hiyaaa...!”
Sambil berteriak nyaring, Pendekar Rajawali Sakti itu berlompatan cepat sambil mengirimkan beberapa pukulan mautnya. Dan orang-orang Mongol itu memang tidak bisa lagi berbuat banyak. Mereka menjerit dan bergelimpangan. Tubuh orang-orang Mongol itu remuk bagaikan tertimpa bongkahan batu cadas yang besar dan tajam. Dalam waktu singkat, tidak ada seorang pun yang bergerak lagi.
“Hhh...!” Rangga mendengus berat.
Saat itu dia mendengar langkah-langkah kaki menuju ke arahnya. Sebentar ditolehkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, lalu dilentingkan tubuhnya ke atas. Begitu kakinya menjejak dahan pohon, kembali digenjot tubuhnya ke arah Prabu Duta Nitiyasa pergi bersama Patih Raksajunta dan dua orang dayang.
Pada saat bayangan tubuh Pendekar Rajawali Sakti lenyap, dari arah Istana Jiwanala muncul dua puluh orang prajurit Mongol yang dipimpin langsung Panglima Ogodai Leng. Mereka begitu terkejut begitu melihat teman-temannya terbujur tak karuan jadi mayat. Panglima Ogodai Leng menghentak-hentakkan kakinya. Gerahamnya bergemeletuk menahan amarah. Dia berbicara keras pada pengawalnya yang bernama Temujin dengan bahasa yang sukar dimengerti.
Temujin membungkuk, kemudian memberikan isyarat tangannya. Dengan membawa lima belas orang prajuritnya, dia bergerak menelusuri hutan itu. Sedangkan Panglima Ogodai Leng kembali ke istana bersama sisa prajuritnya. Sementara malam terus merayap semakin tinggi. Udara di sekitarnya pun bertambah dingin menggigilkan. Namun Temujin dan lima belas prajuritnya terus bergerak menyusuri hutan mencari orang yang telah membunuh banyak prajuritnya, dan yang telah membebaskan tawanan pentingnya.
********************
Sementara itu Prabu Duta Nitiyasa dan Panglima Raksajunta serta dua orang dayang telah jauh meninggalkan perbatasan hutan yang masih termasuk wilayah Kerajaan Jiwanala. Mereka terus berjalan cepat tanpa berhenti sejenak pun. Saat itu fajar sudah mulai menyingsing. Cahaya merah jingga menyemburat dari ufuk timur. Mereka baru berhenti setelah tiba di tepi sebuah sungai yang cukup besar dan deras arusnya.
“Rangga...,” desis Patih Raksajunta begitu melihat seorang pemuda berbaju rompi putih duduk di atas batu di tepi sungai.
Pemuda yang memang adalah Rangga itu menoleh dan tersenyum menyambut kedatangan rombongan kecil itu. Tidak jauh darinya terdapat seonggok api unggun kecil yang di atasnya terdapat seekor kijang panggang. Bau harum daging kijang panggang itu menggugah selera empat orang yang baru tiba.
“Silakan. Maaf aku sudah mendahului,” kata Rangga mempersilakan.
Dua orang dayang menghampiri kijang panggang itu. Dengan selembar daun waru, salah seorang mengambil sekerat dan memberikannya pada Prabu Duta Nitiyasa yang sudah duduk di bawah pohon rindang. Dayang itu memberikannya sambil bersikap hormat. Prabu Duta Nitiyasa menerimanya disertai senyuman di bibir.
“Aku kagum padamu, Kisanak. Kau bisa lebih cepat sampai ke sini,” kata Prabu Duta Nitiyasa.
“Ah, tadi aku memotong jalan,” sahut Rangga merendah.
“Rangga, bagaimana dengan orang-orang Mongol itu?” tanya Patih Raksajunta.
“Masih mengejar. Tapi aku yakin mereka tidak akan sampai ke sini dalam waktu singkat.”
Mereka kemudian menikmati kijang panggang tanpa bicara lagi. Tapi Prabu Duta Nitiyasa sesekali bertanya juga tentang diri Pendekar Rajawali Sakti. Tentu saja Rangga menjawabnya tidak berterus terang. Ditutupi jati dirinya yang sebenarnya. Bahkan ketika Prabu Duta Nitiyasa menanyakan pertemuannya dengan Patih Raksajunta, bukan Rangga yang menjawab. Tapi patih itu sendiri yang menjawabnya.
Mereka saling mengenal diri masing-masing dalam suasana yang akrab. Meskipun Patih Raksajunta dan kedua dayang itu selalu bersikap hormat, tapi Prabu Duta Nitiyasa memperlakukannya seperti sahabat. Dan ini sangat menarik simpati Pendekar Rajawali Sakti. Seorang raja yang tidak angkuh dan bisa menyadari keadaan dirinya.
“Oh, ya. Apa rencana selanjutnya?” tanya Rangga setelah lama terdiam.
“Aku tidak tahu. Hanya yang pasti, aku akan menyusun kekuatan untuk merebut kembali istanaku,” ujar Prabu Duta Nitiyasa.
“Tentu saja, Gusti. Hamba akan mengumpulkan prajurit yang tercecer secepat mungkin. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kita dapat mengusir mereka untuk selamanya,” sambut Patih Raksajunta.
“Memang harus cepat, sebelum mereka mengirim utusan ke negerinya dan membentuk kekuatan di sini.”
“Tapi, Gusti. Kita harus punya tempat yang aman untuk menyusun kekuatan,” usul Patih Raksajunta.
“Hm.... Bagaimana menurutmu, Anak Muda?” Prabu Duta Nitiyasa meminta pendapat Rangga yang diam saja.
“Sayang sekali, aku tidak punya pendapat. Mungkin aku hanya bisa membantu jika diperlukan,” sahut Rangga tetap merendah.
“Kisanak, namamu begitu masyhur. Aku percaya kau punya kemampuan lebih daripada orang biasa. Terus terang, kami butuh bantuan pikiran dan tenagamu untuk mengusir orang asing itu dari tanah ini,” kata Prabu Duta Nitiyasa.
“Ah, Gusti Prabu melebih-lebihkan,” Rangga masih merendah.
“Tidak! Sering kudengar nama dan sepak terjangmu dalam menumpas keangkaramurkaan. Meskipun bukan berasal dari negeri ini, tapi aku percaya kau bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiranmu,” kata Prabu Duta Nitiyasa penuh wibawa.
“Rangga, kami yakin dengan bantuanmu mereka bisa cepat terusir sebelum keadaan lebih parah lagi,” sambung Patih Raksajunta mendesak.
Rangga terdiam beberapa saat. Sebenarnya dia tidak ingin mencampuri urusan pemerintahan suatu negara. Tapi melihat kebrutalan dan kekejaman orang-orang Mongol itu, jiwa kependekarannya tidak mungkin diam saja. Tugas pentingnya sebagai seorang pendekar beraliran lurus memang harus menumpas segala jenis keangkaramurkaan.
“Baiklah,” ucap Rangga akhirnya. “Tapi bantuanku ini jangan diartikan lebih. Bantuanku hanya sekedar mengusir mereka dari negeri ini, tidak lebih!”
“Aku mengerti, Rangga. Dan untuk ini, kuucapkan banyak terima kasih,” ucap Prabu Duta Nitiyasa.
“Matahari semakin tinggi. Sebaiknya, jangan terlalu lama berada di sini,” kata Rangga mengingatkan.
“Gusti, apa tidak sebaiknya kita pergi ke Padepokan Arang Watu? Hamba yakin, Gusti Resi Kamuka bersedia membantu untuk mengirimkan murid-muridnya,” usul Patih Raksajunta.
“Terus terang, semula aku enggan meminta bantuan ayah mertuaku itu. Tapi..., yah! Mungkin memang harus kulakukan. Aku yakin Dinda Dita Wardhani juga sudah menceritakan hal ini pada ayahnya,” sahut Prabu Duta Nitiyasa.
“Jadi..., Gusti Permaisuri sudah berada di sana?” ada kegembiraan pada nada suara Patih Raksajunta.
“Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan sudah tiba dengan selamat.”
“Oh, syukurlah kalau begitu. Sebelumnya hamba sangat cemas, Gusti.”
“Paman Patih, sebaiknya kita berangkat segera,” ajak Prabu Duta Nitiyasa seraya beranjak berdiri.
“Baik, Gusti,” sahut Patih Raksajunta juga bangkit berdiri.
“Untuk lebih cepat, bagaimana kalau kita menunggang kuda,” kata Rangga yang sudah bangkit lebih dahulu.
“Kuda...?!” Prabu Duta Nitiyasa memandang pendekar muda itu dalam-dalam. “Dari mana kita akan mendapatkannya?"
“Tidak terlalu sulit,” sahut Rangga.
Setelah berkata demikian, Rangga bersiul tiga kali. Dan tidak berapa lama kemudian, dari balik hutan muncul seorang punggawa dan tiga puluh orang prajurit berkuda. Mereka juga membawa kuda-kuda kosong tanpa penunggang. Prabu Duta Nitiyasa dan Patih Raksajunta hanya memandang setengah tidak percaya.
“Punggawa Parian...,” desis Prabu Duta Nitiyasa.
“Gusti Prabu, terimalah salam dan rasa hormat hamba,” ucap Punggawa Parian begitu turun dari kudanya seraya berlutut memberi sembah.
“Bangunlah, Punggawa,” ujar Prabu Duta Nitiyasa.
Punggawa Parian bangkit berdiri setelah menyembah sekali lagi. Tiga puluh orang prajurit yang juga telah turun dari kuda dan memberi sembah, ikut bangkit berdiri. Prabu Duta Nitiyasa memandangi dengan mata berbinar-binar.
“Rangga, bagaimana kau bisa kumpulkan mereka?” tanya Prabu Duta Nitiyasa seraya berpaling pada Pendekar Rajawali Sakti.
“Bukan aku, Gusti Prabu. Mereka memang sudah berada di sini sejak semalam. Maaf, aku memang sengaja meminta mereka untuk sembunyi beberapa saat,” sahut Rangga kalem.
“Punggawa...,” Prabu Duta Nitiyasa mengalihkan pandangannya kembali pada Punggawa Parian.
“Hamba, Gusti Prabu,” Punggawa Parian memberi hormat.
“Kalau tidak salah, kau ikut bersama Panglima Sembada. Bagaimana kalian semua bisa berpencar?” tanya Prabu Duta Nitiyasa ingin tahu.
“Ampun, Gusti Prabu, Hamba memang bersama-sama Panglima Sembada dan prajurit lainnya. Hamba dan Gusti Panglima sempat membakar perahu orang Mongol itu dan membunuhi awak kapalnya. Tapi malang, Gusti. Pada saat kembali ke istana, kami diserang mereka. Sungguh kami tidak tahu kalau mereka telah menguasai istana. Panglima Sembada bersama beberapa punggawa dan puluhan prajurit tewas dalam pertempuran. Sedangkan hamba dan tiga puluh prajurit berhasil meloloskan diri dan sampai di sini,” jelas Punggawa Parian secara rinci dan singkat.
“Hm..., kalian bertemu prajurit-prajurit lainnya?” tanya Patih Raksajunta.
“Tidak, Gusti Patih. Hamba hanya bertemu Tuan Pendekar ini. Kalau tidak ada Tuan Pendekar ini, mungkin hamba juga sudah tewas,” Punggawa Parian menunjuk Rangga dengan ibu jarinya.
“Bagaimana kejadiannya?” tanya Prabu Duta Nitiyasa.
“Semalam hamba dan prajurit bermaksud menyerang istana. Tapi sebelum sampai di istana, kami telah diserang mereka. Kami berusaha bertahan, tapi mereka terlalu tangguh, Gusti. Akhirnya kami terdesak sampai ke hutan. Untung saja Tuan Pendekar ini membantu dan memukul mundur mereka. Kemudian hamba mencari prajurit lain yang masih bertebaran di dalam hutan dan berhasil dikumpulkan kembali di tempat ini.”
“Kau hebat, Rangga. Padahal semalam kau ke istana menyelamatkanku. Hm.... Sukar bagiku untuk mengerti, bagaimana caranya kau bisa melakukan begitu banyak pekerjaan dalam satu malam saja,” ujar Prabu Duta Nitiyasa memuji tulus.
“Ah. Itu hanya kebetulan saja, Gusti Prabu,” sahut Rangga tetap merendah.
“Apa pun yang kau lakukan dan kau katakan, aku tetap kagum padamu.”
Rangga hanya tersenyum saja, kemudian mempersilakan Prabu Duta Nitiyasa untuk naik ke punggung kuda. Patih Raksajunta dan dua dayang juga naik ke punggung kuda yang memang sudah disiapkan. Punggawa Parian dan tiga puluh orang prajurit yang tersisa, bergegas melompat naik ke punggung kudanya masing-masing. Tinggal empat ekor kuda yang belum ada penunggangnya, tapi mereka berangkat juga meninggalkan tepian sungai di dalam hutan itu.
Sepanjang perjalanan, Prabu Duta Nitiyasa selalu meminta Rangga untuk berada di sampingnya. Raja Jiwanala itu terus menanyakan tentang kejadian yang dialami Pendekar Rajawali Sakti semalam. Hanya saja semua itu dijawab Rangga secara merendah, bahkan tidak diceritakan secara persis. Dia tidak ingin membanggakan diri meskipun Prabu Duta Nitiyasa secara jujur mengaguminya. Raja Jiwanala itu semakin kagum akan kerendahan hati Pendekar Rajawali Sakti.
********************
Perjalanan ke Gunung Waja dengan berkuda memang tidak begitu lama. Saat matahari condong ke barat, mereka sudah tiba. Resi Kamuka tidak lagi terkejut menerima kedatangan menantunya yang diiringi tiga puluh prajurit, seorang punggawa, dan seorang patih. Bahkan laki-laki tua renta berjubah putih itu gembira manakala diberitahu kalau pemuda tampan yang menyertai menantunya adalah Pendekar Rajawali Sakti.
“Sudah kudengar banyak tentang dirimu, Pendekar Rajawali Sakti,” ucap Resi Kamuka saat punya kesempatan berbincang-bincang berdua di balai latihan.
“Rangga.... Panggil saja aku Rangga, Resi,” ucap Rangga meminta.
“Baiklah. Rupanya kau lebih suka dipanggil namamu sendiri. Tidak seperti kebanyakan orang rimba persilatan yang lebih suka menyembunyikan namanya dan selalu memamerkan julukannya,” sahut Resi Kamuka.
“Malah sebaliknya, Resi. Nama pemberian orang tua patut dijunjung tinggi.”
“Ha ha ha...!” Resi Kamuka tertawa terbahak-bahak.
Rangga jadi terdiam. Dia heran juga, mengapa Resi Kamuka tertawa? Apakah ada yang salah pada perkataannya! Rangga mengingat-ingat apa yang diucapkannya tadi. Rasanya tidak ada yang salah! Ucapannya seadanya, tidak dilebih-lebihkan.
“Rasanya sukar mencari pendekar digdaya sepertimu, Rangga,” kata Resi Kamuka setelah berhenti tertawa.
“Tidak, Resi. Masih banyak pendekar yang lebih tangguh dan memiliki kepandaian yang sukar diukur tingkatannya. Aku hanya segelintir saja dari mereka,” Rangga merendah.
Saat itu Prabu Duta Nitiyasa masuk ke dalam balai latihan ini. Pakaiannya telah berganti dengan yang bersih. Meskipun terbuat dari bahan yang tidak mahal, tapi cukup enak dipandang. Memang, Prabu Duta Nitiyasa sudah tidak bisa dikatakan muda lagi. Tapi bentuk tubuh dan wajahnya masih terlihat tampan dan gagah. Dengan mengenakan baju kependekaran berwarna biru langit, Prabu Duta Nitiyasa tampak lebih gagah! Bahkan pamornya sebagai raja agung tidak pudar sama sekali. Kewibawaannya semakin bertambah saja.
“Ayahanda Resi, ananda mohon pamit,” ucap Prabu Duta Nitiyasa.
“Eee...! Mau ke mana, Nanda Prabu?” Resi Kamuka terkejut. “Belum ada satu hari kau datang, sekarang akan pergi lagi. Apa tidak salah pendenga-ranku?”
“Tidak, Ayahanda Resi.”
“Ke mana kau akan pergi?”
“Mengusir orang-orang asing itu,” tegas jawaban Prabu Duta Nitiyasa.
“Ck ck ck...!” Resi Kamuka menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berdecak bagai cicak.
Sementara Rangga yang berada di samping Resi Kamuka, hanya diam. Baginya tidak baik mencampuri urusan keluarga ini jika tidak diminta terlebih dahulu. Lagi pula, bantuannya sudah cukup banyak. Bahkan masih ada satu lagi yang harus dikerjakannya. Dia sudah berjanji untuk membantu mengusir orang-orang Mongol itu sampai tuntas.
“Ananda Prabu, bukannya aku hendak mencampuri urusan pemerintahanmu. Tapi, tidakkah keberangkatanmu terlalu terburu-buru? Niatmu itu membutuhkan waktu dan persiapan yang tidak pendek. Mereka telah menguasai istanamu, dan mereka lebih kuat dari prajuritmu. Pikirkanlah itu, Ananda Prabu,” Resi Kamuka memberikan pertimbangan.
“Ayahanda Resi, semua ini sudah ananda pikirkan masak-masak. Dalam perjalanan nanti, ananda akan mengumpulkan sisa-sisa prajurit yang ada. Lagi pula, dengan bantuan Pendekar Rajawali Sakti, mereka pasti dapat dikalahkan,” sahut Prabu Duta Nitiyasa.
“Memang tidak kuragukan kemampuan Pendekar Rajawali Sakti. Tapi kau jangan hanya mengandalkannya saja. Aku rasa jumlah mereka tidak sedikit, bahkan sudah terkenal kehebatannya dalam bertempur di negeri orang. Mereka juga memiliki ilmu keprajuritan yang tangguh. Kusarankan, sebaiknya pertimbangkanlah lebih dahulu barang dua atau tiga hari lagi. Kasihan anak dan istrimu. Mereka pasti masih merindukanmu untuk beberapa hari ini,” bujuk Resi Kamuka.
Prabu Duta Nitiyasa diam membisu. Dalam hatinya, dibenarkan juga bapak mertuanya ini. Memang tidak bisa gegabah menghadapi orang-orang Mongol itu yang sudah bisa dilihat ketangguhan dan kekejamannya. Perlu satu pasukan terlatih untuk menghadapi dan mengusirnya dari tanah ini. Dan itu tidak dimilikinya sekarang. Prajurit yang tersisa kini tidak lebih dari lima puluh orang jumlahnya. Itu pun bukan prajurit terlatih dan pilihan.
“Sebaiknya Ananda beristirahat dulu. Keletihan belum lagi hilang. Jangan paksakan diri meskipun niatmu suci,” kata Resi Kamuka bijaksana.
“Baiklah, Ayahanda Resi,” ucap Prabu Duta Nitiyasa menurut.
Resi Kamuka tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Prabu Duta Nitiyasa berbalik dan melangkah pergi. Tinggal Resi Kamuka dan Rangga yang masih diam di bangsal latihan ini. Kemudian Resi Kamuka mengajak Rangga untuk melihat-lihat sekitar padepokannya, lalu memperkenalkannya pada murid-muridnya.
Dia merasa bangga dan gembira karena padepokan terpencil ini telah kedatangan seorang pendekar besar yang sudah ternama dalam rimba persilatan. Resi Kamuka merasa seperti mendapat anugrah besar dengan kedatangan Pendekar Rajawali Sakti ini.
********************
ENAM
Tiga hari Rangga berada di lingkungan Padepokan Arang Watu. Dan selama itu pula dia tidak bisa menolak keinginan Resi Kamuka untuk memberikan sedikit ilmu yang dimiliki pada murid-murid padepokan itu. Rangga juga tidak bisa menolak ketika diminta untuk melatih prajurit-prajurit Jiwanala yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya.
Waktu tiga hari memang tidak bisa berharap banyak dalam peningkatan kemampuan tempur para prajurit itu. Tapi Prabu Duta Nitiyasa sudah cukup senang melihat ikut sertanya Pendekar Rajawali Sakti menempa prajurit-prajuritnya. Dan apa yang dilakukan Rangga hanya sekedar untuk membantu. Sama sekali tidak punya niatan untuk menyombongkan diri. Memang hanya itulah yang bisa dilakukannya untuk membantu rakyat Kerajaan Jiwanala yang saat ini tengah tertekan oleh kekuasaan orang-orang dari Daratan Mongol.
“Sepertinya dia datang memang diutus Dewata...,” Resi Kamuka bergumam pelan, seolah-olah bicara untuk dirinya sendiri. Tatapan matanya tidak lepas ke arah Rangga yang tengah memberikan beberapa jurus ilmu olah kanuragan pada para prajurit yang kini semakin membengkak saja jumlahnya.
“Maksud Ayahanda Resi?” tanya Prabu Duta Nitiyasa.
“Apa tidak bisa kau lihat cara dia datang, Ananda Prabu? Juga keberadaannya di sini, seperti sudah ditunjukkan oleh Hyang Widi untuk membebaskan rakyatmu dari tekanan orang asing.”
“Dia seorang pengembara, Ayahanda Resi. Tidak aneh kalau tiba-tiba muncul dan membantu perjuangan ini,” bantah Prabu Duta Nitiyasa tidak sependapat.
“Hm.... Apa pun yang kau katakan, aku merasa ada sesuatu yang lain pada diri anak muda itu. Baik sikap, caranya bertutur, dan kerendahan hatinya.... Aku tidak pernah menemukan pribadi seperti itu pada diri orang lain. Aku merasakan ada sesuatu yang lain pada dirinya. Entah apa namanya...,” kata Resi Kamuka setengah bergumam.
Saat itu Rangga berlari-lari kecil menghampiri Resi Kamuka yang berdiri memperhatikan latihan itu bersama Prabu Duta Nitiyasa. Rangga membungkuk sedikit memberi hormat setelah tiba di depan dua orang terkemuka di Kerajaan Jiwanala ini.
“Ah. Kau terlalu merendahkan diri, anakku Rangga,” ucap Resi Kamuka yang menganggap Rangga adalah putranya. Memang sejak Rangga berada di padepokan ini, Resi Kamuka sudah tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai anak.
Keinginannya ini memang dikemukakan langsung pada Pendekar Rajawali Sakti itu. Dan betapa gembiranya dia begitu melihat Rangga menyambut keinginannya dengan tangan terbuka. Memupuk tali persaudaraan memang tidak mudah. Lain halnya jika mencari musuh, yang dalam waktu singkat saja bisa didapat. Rangga selalu menyambut baik jika ada seseorang yang menginginkan persaudaraan dengannya.
“Gusti Prabu, Resi, rasanya kemampuan para prajurit sudah lebih maju. Jumlahnya pun semakin bertambah. Banyak pemuda yang bergabung dengan sukarela,” Rangga memberitahukan perkembangan kemajuan para prajurit yang ditempanya.
“Hm..., apakah itu berarti sudah waktunya merebut kembali Kerajaan Jiwanala?” gumam Resi Kamuka.
Rangga tidak menjawab, tapi hanya memandang Prabu Duta Nitiyasa. Sedangkan yang ditatap malah memandang pada ayah mertuanya.
“Sebaiknya kita tunggu dulu laporan dari telik sandi,” kata Prabu Duta Nitiyasa bijaksana.
“Itu lebih baik,” sambut Resi Kamuka.
Mereka hampir berbarengan menoleh ketika Punggawa Narayama datang menghampiri. Punggawa itu melangkah tergopoh-gopoh. Napasnya tersengal ketika memberi hormat dengan membungkukkan tubuhnya di depan Prabu Duta Nitiyasa.
“Ada apa, Punggawa? Apakah ada seorang telik sandi yang datang?” tanya Prabu Duta Nitiyasa.
“Benar, Gusti Prabu. Seorang telik sandi melaporkan kalau suasana di sekitar kerajaan sedang kacau,” lapor Punggawa Narayama.
“Kacau...!? Apa yang terjadi?” tanya Prabu Duta Nitiyasa.
“Maksud hamba, bukan kekacauan antar mereka sendiri. Tapi tindakan mereka yang semakin brutal, tidak lagi mengindahkan peri kemanusiaan. Banyak rakyat yang tewas terbunuh. Tidak sedikit gadis-gadis yang dijadikan permainan. Mereka memperlakukan rakyat seperti hewan buruan,” lapor Punggawa Narayama lagi.
“Biadab!” desis Prabu Duta Nitiyasa menggeram.
“Kendalikan dirimu, Ananda Prabu,” Resi Kamuka mencoba mendinginkan hati Prabu Duta Nitiyasa yang mendidih seketika.
“Tidak, Ayahanda Resi. Kekejaman ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Mereka harus enyah, atau mati di sini!” tegas Prabu Duta Nitiyasa.
“Tapi kekuatan yang kau miliki belum cukup.”
“Jumlah mereka hanya sepertiganya saja, Ayahanda Resi. Mereka pasti bisa dikalahkan!”
Resi Kamuka merasa sukar untuk meredakan amarah anak menantunya ini. Dia menoleh ke arah Rangga tadi berdiri, tapi Pendekar Rajawali Sakti itu sudah tidak terlihat lagi. Resi Kamuka melayangkan pandangannya ke sekeliling. Tetap saja Pendekar Rajawali Sakti itu tak nampak.
“Heh...! Ke mana dia...?” seru Resi Kamuka tetap mengedarkan pandangannya kesekeliling.
“Siapa?” tanya Prabu Duta Nitiyasa belum menyadari.
“Rangga....”
Prabu Duta Nitiyasa terperanjat begitu menyadari kalau Pendekar Rajawali Sakti tidak ada lagi. Dia juga melayangkan pandangannya ke sekeliling. Tapi sepanjang mata memandang, yang terlihat hanya para prajurit dan murid-murid padepokan ini.
“Dia pasti sudah ke sana, Ayahanda Resi,” kata Prabu Duta Nitiyasa setengah bergumam.
“Mustahil!” bantah Resi Kamuka.
“Punggawa! Siapkan seluruh prajurit! Sekarang juga kita berangkat ke Jiwanala!” perintah Prabu Duta Nitiyasa.
“Tunggu!” cegah Resi Kamuka.
“Tidak ada waktu lagi, Ayahanda Resi!” sergah Prabu Duta Nitiyasa cepat.
Prabu Duta Nitiyasa bergegas meninggalkan balai latihan itu. Punggawa Narayama pun bergegas menghubungi punggawa lain, untuk mempersiapkan para prajurit. Tidak ada lagi panglima di sini. Semua panglima telah tewas dalam pertempuran. Sedangkan para patih tidak sedikit yang gugur. Ada juga yang melarikan diri begitu Istana Jiwanala terenggut. Prajurit yang kembali bergabung juga belum seluruhnya. Masih banyak yang belum jelas nasibnya.
Resi Kamuka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka dipanggillah semua muridnya yang berjumlah hampir lima puluh orang. Seluruh muridnya diminta untuk bersiap-siap membantu Prabu Duta Nitiyasa merebut kembali kejayaan kerajaannya dari tangan orang asing. Bagaimanapun juga anak menantunya harus dibela. Apalagi dalam perjuangan yang suci merebut negeri dari jajahan orang asing.
********************
Sementara seluruh prajurit Jiwanala tengah bersiap-siap di Padepokan Arang Watu, saat yang sama Rangga yang diam-diam meninggalkan padepokan itu sudah tiba di depan Istana Jiwanala. Saat itu keadaan istana tampak sepi tenang. Terlihat beberapa prajurit Mongol berjaga-jaga di depan pintu gerbang istana. Beberapa prajurit lainnya terlihat di atas benteng yang mengelilingi istana ini.
Rangga mengawasi sekitarnya dari balik pohon yang cukup rindang untuk melindungi dirinya dari penglihatan para prajurit Mongol itu. Tidak ada seorang penduduk kota yang terlihat. Rumah-rumah kelihatan begitu sepi, bahkan beberapa di antaranya hancur berantakan. Ada juga yang hangus bekas terbakar. Tidak sedikit bangkai binatang bercampur dengan mayat manusia yang bergelimpangan di jalan-jalan atau emperan rumah. Bau busuk terasa mengganggu pernapasan.
“Hei! Siapa itu...?”
Tiba-tiba terdengar satu bentakan keras. Rangga terkejut juga, namun segera dapat menarik napas panjang begitu melihat seorang laki-laki tua terbungkuk-bungkuk melintasi jalan yang sepi. Dua orang prajurit Mongol yang menjaga pintu gerbang menghampirinya. Laki-laki tua berpakaian kumal itu tetap melangkah tertatih-tatih dibantu sebatang tongkat yang kelihatan rapuh.
“Berhenti...!” bentak salah seorang prajurit Mongol itu.
“Oh..., ada apakah, Tuan?” tanya kakek tua yang kelihatan seperti pengemis itu.
“Mau ke mana kau?” tanya prajurit itu yang tadi membentak.
“Hanya lewat,” sahut kakek tua itu.
“Kau tahu, ini daerah terlarang! Siapa saja yang berani lewat sini harus bayar upeti!”
“Upeti...?! Oh, maaf. Aku tidak tahu kalau ada peraturan baru di sini. Maaf, Tuan. Aku tidak punya uang barang sepeser pun. Maklumlah, hanya seorang pengemis tua yang mencari hidup dari belas kasihan orang.”
“Phuih!”
Rangga yang menyaksikan kejadian itu dari tempat persembunyiannya jadi terkejut ketika tiba-tiba salah seorang prajurit mengayunkan tangannya ke wajah laki-laki tua itu. Tamparan yang cukup keras itu membuat laki-laki tua berpakaian kumal itu terpental ke tanah.
Belum lagi kakek tua itu sempat bangun, satu tendangan keras mendarat di tubuhnya yang kurus renta. Tidak pelak lagi, laki-laki tua itu menggelimpang beberapa depa jauhnya. Dua orang prajurit itu tertawa terbahak-bahak. Mereka menghampiri kakek tua itu, dan kembali mendaratkan tendangan keras. Tampak beberapa prajurit lain yang berada di atas benteng menyaksikan sambil tertawa-tawa. Seperti tengah melihat satu tontonan menarik yang menggelitik tenggorokan.
“Biadab...!” desis Rangga dari tempat persembunyiannya.
Rangga hampir-hampir tidak bisa menahan diri lagi. Tapi tiba-tiba saja satu kejadian yang mengejutkan terlihat. Hampir tidak dipercaya dengan apa yang baru saja terjadi, dua orang prajurit Mongol itu tiba-tiba saja menjerit keras, lalu menggelepar di tanah. Tampak dada mereka sobek, mengucurkan darah segar. Suara tawa yang semula terdengar, mendadak saja hilang.
Sementara, laki-laki tua renta berbaju kumal itu bangkit berdiri dengan bantuan tongkatnya. Sebentar dipandangi dua orang prajurit yang tadi menyiksanya. Sangat jelas terlihat kalau kakek tua renta itu tidak kekurangan satu apa pun. Padahal tubuhnya telah menerima pukulan dan tendangan yang sangat keras dari dua orang prajurit itu.
“Hhh! Kalian bisa seenaknya di negeri sendiri. Tapi di sini...,” laki-laki tua renta itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Kata-katanya begitu sinis.
Saat itu, tiba-tiba saja puluhan anak panah meluncur deras bagai hujan ke arah laki-laki tua itu. Rangga yang berada di tempat persembunyiannya sempat menarik napas dalam-dalam. Namun yang terjadi di luar dugaannya sama sekali. Kakek tua renta itu dengan sigap memutar tongkatnya yang kelihatan rapuh. Putaran yang begitu cepat mampu memayungi dirinya dari hujan anak panah.
“Yeaaah...!”
Puluhan, bahkan ratusan anak panah yang meluncur bagai hujan itu rontok terkena sapuan tongkat yang berputar cepat bagai baling-baling. Bahkan kakek tua renta itu melangkah perlahan-lahan mendekati pintu gerbang istana. Hujan anak panah itu tidak juga berhenti, meskipun tidak satu pun yang berhasil menemui sasaran.
“Ya, ya, yaaah...!”
Sambil berteriak keras, kakek tua renta itu melompat dan langsung hendak menerobos gerbang yang terbuka lebar itu. Tapi belum juga sampai, mendadak datang serbuan tombak yang begitu gencar.
“Haaait...!”
Laki-laki tua kumal itu cepat melentingkan tubuhnya berputaran di udara seraya mengibaskan tongkatnya dengan cepat. Sungguh luar biasa! Tongkat yang kelihatan rapuh itu mampu membabat hancur tombak-tombak yang mengancam nyawanya! Dan begitu serbuan tombak berakhir, disusul dengan munculnya sekitar sepuluh orang berpakaian prajurit Mongol.
Sepuluh orang Mongol itu serentak menyerang dengan ganas. Mereka semua menggunakan senjata golok besar dan panjang. Tangkai golok hampir menyamai panjang golok itu sendiri. Namun kelihatannya kakek tua itu mudah saja menghadapi mereka. Tongkatnya berkelebatan cepat diimbangi gerakan tubuh dan kaki yang lincah. Tongkat yang kelihatan rapuh itu ternyata mampu menahan gempuran senjata lawan yang berkilat tajam.
“Hiyat..!”
Trak! Ting!
Hebat! Dua golok terpotong jadi dua bagian begitu berbenturan dengan tongkat kakek tua itu. Dan belum lagi pemiliknya menyadari apa yang terjadi, kakek tua itu mengibaskan tongkatnya tepat ke arah dada. Dua suara jeritan panjang terdengar melengking, disusul robohnya dua tubuh bersimbah darah. Dada mereka sobek sangat lebar dan dalam.
Tapi belum juga dua orang Mongol itu menyentuh tanah, mendadak satu bayangan berkelebat cepat menyambar punggung kakek tua itu. Sambaran yang begitu cepat dan tidak terduga, membuat kakek tua itu jatuh terguling-guling. Punggungnya terasa nyeri, seolah-olah tulang punggungnya patah.
“Phuih! Kunyuk busuk...!” umpat kakek tua itu geram.
“He he he...!” seorang laki-laki Mongol tahu-tahu sudah berdiri bertolak pinggang. Dia tidak lain dari Temujin, salah seorang pengawal pribadi Panglima Ogodai Leng.
Delapan orang prajurit yang tersisa, bergegas mengundurkan diri. Tapi mereka tetap bersiaga penuh menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Sedangkan Temujin melangkah mendekati laki-laki tua itu.
“Kau punya nyali besar juga, Kakek Tua!” ketus kata-kata Temujin.
“Siapa pun akan berbuat yang sama denganku untuk mengenyahkan kalian!” dengus kakek tua itu tidak kalah ketusnya.
“Rupanya kau sudah tidak sabar lagi menanti kematian, Kakek Tua!”
“Kematian yang terhormat, bukan sebagai anjing busuk sepertimu!”
“Setan...!”
Temujin tidak dapat lagi menahan kemarahannya. Dengan cepat dicabut pedangnya, dan langsung dirangsek laki-laki tua renta itu. Namun terjangan yang cepat itu dengan manis dapat dielakkan. Hal ini membuat Temujin semakin geram, dan terus mencecar dengan serangan-serangan yang dahsyat.
Sementara itu, Rangga yang berada di tempat persembunyiannya serius memperhatikan jalannya pertarungan. Sepasang matanya tidak berkedip mengamati setiap gerakan yang dilakukan dua orang itu. Dalam hatinya diakui kehebatan kakek tua yang mampu menandingi Temujin sampai dua puluh jurus.
“Hm..., orang Mongol itu tangguh juga. Jurus-jurusnya aneh,” gumam Rangga dalam hati.
Pendekar Rajawali Sakti itu juga menebak-nebak sambil tidak lepas memperhatikan pertarungan itu. Dan dugaannya hampir mendekati kenyataan. Temujin tampaknya dapat menguasai jalannya pertarungan. Memasuki jurus yang ke tiga puluh, sudah kelihatan kalau kakek tua itu mulai kehabisan napas. Usianya yang sudah lanjut tidak memungkinkan lagi untuk bertarung dalam jangka waktu lama.
Meskipun gerakan-gerakannya masih cepat dan lincah, namun tidak lagi seampuh semula. Kesalahan terlalu sering dilakukan, sehingga membahayakan dirinya sendiri. Kalau saja tidak ditunjang dengan gerakan kaki yang lincah, mungkin sudah sejak tadi Temujin dapat menghentikan perlawanan kakek tua itu. Dugaan Rangga semakin tepat saat memasuki jurus ke empat puluh.
“Akh...!”
Satu tendangan keras mendarat telak di dada laki-laki tua itu. Sehingga membuat tubuhnya terjengkang ke belakang beberapa langkah. Belum lagi sempat menguasai tubuhnya, Temujin sudah melompat sambil mengibaskan pedangnya ke arah leher.
“Awas...!” Rangga berteriak keras tiba-tiba.
Dan secepat itu pula, tubuhnya melesat bagai kilat menyampok pedang Temujin dengan sentilan ujung jarinya.
Tring!
“Heh...!” Temujin terperanjat.
Sentilan jari Pendekar Rajawali Sakti itu demikian hebat karena disertai pengerahan tenaga dalam sempurna. Akibatnya, jari-jari tangan Temujin kesemutan. Buru-buru ditarik pulang pedangnya sambil melompat mundur. Sedangkan Rangga membantu kakek tua itu berdiri.
“Terima kasih, Anak Muda,” ucap kakek tua itu.
“Siapa Kakek ini?” tanya Rangga.
“Orang-orang memanggilku Kakek Pengemis dari Utara,” kakek tua itu memperkenalkan diri.
“Aku....”
“Tidak perlu kau perkenalkan diri. Aku sudah tahu siapa dirimu,” potong Kakek Pengemis dari Utara cepat.
“Oh...!” Rangga agak terperanjat juga.
Rupanya nama Pendekar Rajawali Sakti sudah begitu terkenal di daerah pesisir timur ini. Sepertinya hampir semua orang sudah bisa mengenali, meskipun dia sendiri belum pernah bertemu. Mungkin ciri-cirinya yang begitu khas, sehingga orang bisa cepat mengenalinya. Rangga memang selalu mengenakan baju rompi putih dalam setiap pengembaraannya. Dan baju itulah yang menjadi ciri khasnya, di samping pedang pusaka yang bergagang kepala burung rajawali.
“Awas...!” tiba-tiba Kakek Pengemis dari Utara berteriak keras.
“Eits...!”
Rangga menoleh seraya memiringkan tubuhnya ke kanan. Pada saat itu Temujin menusukkan pedangnya ke punggung Pendekar Rajawali Sakti. Tusukan itu melesat di samping tubuh Rangga. Pada saat yang hampir bersamaan, kaki Rangga mendupak ke belakang, dan tepat menghantam perut lawan.
“Hugh!” Temujin mengeluh pendek.
Tubuhnya tersuruk ke belakang beberapa langkah. Cepat sekali Rangga memutar tubuhnya bertumpu pada kaki kiri, sedangkan kaki kanannya melayang cepat ke atas. Temujin yang masih sedikit membungkuk, tidak bisa lagi menghindar sepakan kaki itu. Dia memekik keras sambil memegangi kepalanya.
Darah mengucur deras dari sela-sela jari tangan Temujin. Tendangan menyilang milik Pendekar Rajawali Sakti itu demikian keras disertai pengerahan tenaga dalam yang sangat tinggi. Akibatnya kepala pengawal khusus Panglima Mongol itu pecah.
Selagi Temujin meraung memegangi kepalanya, Rangga sudah melompat cepat bagaikan kilat mengerahkan jurus ‘Sayap Rajawali Membelah Mega’. Tangan kanannya berkelebat cepat ke arah kepala orang Mongol itu. Tak pelak lagi, kibasan tangan Pendekar Rajawali Sakti menghajar kepala yang memang sudah pecah.
“Aaakh...!” Temujin memekik keras.
Hanya sebentar ia mampu bertahan dengan kedua kakinya, kemudian tubuhnya limbung dan ambruk menggelepar di tanah. Darah bercucuran dari kepala yang pecah. Delapan orang prajurit Mongol yang menyaksikan kematian Temujin hanya bengong dengan mulut ternganga lebar.
“Kalian juga harus menyusul! Hiyaaa...!” seru Kakek Pengemis dari Utara keras menggelegar.
Bagaikan seekor kijang, laki-laki tua itu melompat sambil mengibaskan tongkatnya ke arah delapan orang itu. Serangan Kakek Pengemis dari Utara yang tiba-tiba dan cepat tidak dapat dihindarkan lagi. Tongkatnya bagaikan sebuah parang yang tengah menebas jajaran batang pisang. Jerit dan pekik terdengar membahana mengiringi kematian delapan orang prajurit Mongol itu.
Belum lagi kedua tokoh sakti itu menarik napas, ratusan anak panah tiba-tiba meluncur deras menghujani mereka. Rangga berseru nyaring, lalu melompat menjauh seraya menyambar tangan Kakek Pengemis dari Utara itu. Hujan anak panah terus mencecar mereka. Namun, lesatan Pendekar Rajawali Sakti demikian sempurna, sehingga dalam beberapa kali lompatan saja, sudah jauh dari benteng istana itu.
“Huh!” Kakek Pengemis dari Utara menyentakkan cekalan tangan Rangga sambil memberengut.
“Maaf,” ucap Rangga.
Mereka kini sudah berada jauh dari jangkauan anak panah. Kakek Pengemis dari Utara bersungut-sungut tidak jelas. Kakinya dihentak-hentakkan ke tanah. Rangga tahu kalau laki-laki tua itu kesal karena dia dibawa paksa menyingkir dari benteng istana. Tapi kalau tidak menyingkir, jelas mereka akan tercincang dihujani anak panah. Setangguh-tangguhnya seseorang, tidak akan mampu menghindari gempuran anak panah yang tiada habis-habisnya itu.
********************
TUJUH
“Sudah lama kutunggu kesempatan ini, tapi semuanya kau buat berantakan!” rungut Kakek Pengemis dari Utara.
“Maaf, aku tidak bermaksud begitu,” ucap Rangga menyesal.
“Tidak perlu! Kau lihat, mereka sudah keluar!”
Rangga mengalihkan perhatiannya ke istana itu. Memang benar, para prajurit Mongol bermunculan dari dalam benteng istana. Mereka semua menunggang kuda. Terlihat paling depan adalah Panglima Ogodai Leng. Di sampingnya yang menunggang kuda coklat adalah Hulagu Leng. Rupanya adik kandung Panglima Mongol itu sudah kembali bebas dari tawanan.
Cukup banyak juga jumlah mereka. Seluruhnya tidak kurang dari lima puluh orang. Bahkan mungkin bisa lebih. Mereka berkuda tidak tergesa-gesa. Ini membuat Pendekar Rajawali Sakti maupun Kakek Pengemis dari Utara keheranan. Mereka tentu melihat dua orang tokoh sakti itu, tapi tampaknya tidak mempedulikan.
Rangga sengaja menampakkan diri berdiri di pinggir jalan yang bakal dilalui rombongan orang Mongol itu. Kakek Pengemis dari Utara ikut melangkah menghampiri Pendekar Rajawali Sakti itu. Mereka berdiri berdampingan dengan pandangan tidak berkedip pada rombongan berkuda itu.
Panglima Ogodai Leng rupanya melihat juga. Maka diangkat tangannya tinggi-tinggi. Para prajurit berkuda di belakangnya menghentikan langkah kudanya. Panglima Ogodai Leng turun dari kuda, diikuti Hulagu Leng. Mereka berdua melangkah menghampiri dua orang yang telah membunuh banyak orang Mongol. Bahkan pengawal pribadi Panglima Mongol itu pun tewas terbunuh.
“Kalian orang-orang yang pemberani,” kata Ogodai Leng setelah jaraknya tinggal beberapa langkah lagi.
“Kalian juga lebih berani lagi. Menjarah negeri orang dan membuat kekacauan,” sahut Kakek Pengemis dari Utara ketus.
“Kalau saja raja kalian berhati lunak, tentu tidak akan seperti ini,” kata Ogodai Leng kalem.
“Apa pun maksud kalian datang ke sini, kami semua tidak menghendaki. Dan sebaiknya tuan-tuan segera meninggalkan negeri ini, sebelum kami buat kuburan bagi tuan-tuan semua!” kata-kata Kakek Pengemis dari Utara jelas bernada ancaman.
“Kakak Ogodai Leng, memang sebaiknya kita tinggalkan negeri ini,” celetuk Hulagu Leng yang sejak tadi diam saja.
“Diam kau, Hulagu Leng!” bentak Panglima Ogodai Leng.
“Kakak, ingatlah dengan amanat yang dibawa utusan Yang Mulia Jengis Khan!” sentak Hulagu Leng agak keras suaranya.
“Ini urusanku! Kalau kau ingin kembali ke Mongol, silakan! Aku tidak akan ingin melihatmu seumur hidupku!”
“Kak..!”
Panglima Ogodai Leng mendorong adiknya ke belakang. Hulagu Leng berusaha mencegah, tapi kakaknya itu malah memukul keras wajahnya. Hulagu Leng pun terjajar beberapa langkah. Dari sudut bibirnya mengucur darah segar.
“Kak, dengarlah dulu! Utusan itu sudah menunggu di kapal. Yang Mulia membutuhkan kita saat ini!” Hulagu Leng terus mendesak kakaknya.
“Diam...!” bentak Panglima Ogodai Leng sambil menahan kemarahannya.
“Baiklah. Jika Kakak ingin tetap di sini, aku akan ke kapal penjemput bersama seluruh prajurit!” kata Hulagu Leng keras.
“Silakan! Cepat kau pergi, tapi jangan coba-coba membawa satu prajurit pun!”
Hulagu Leng melompat naik ke punggung kudanya. Dipandangi prajurit-prajurit yang berjumlah lebih dari lima puluh orang itu. Tampaknya mereka bimbang. Tapi begitu melihat tatapan mata panglimanya, mereka tidak ada yang berani ikut bersama Hulagu Leng. Dan tetap berada di punggung kudanya masing-masing.
“Kalian akan menyesal! Di sini bukan tempat kalian!” kata Hulagu Leng keras.
“Cepat kau pergi, Hulagu Leng!” bentak Ogodai Leng.
“Ingat kata-kataku! Menjarah negeri orang tidak akan membawa kebaikan. Yang Mulia juga tidak akan menerima tindakan kalian di sini! Dengar itu...!” keras nada suara Hulagu Leng.
Setelah berkata demikian Hulagu Leng segera memacu kudanya menuju ke pelabuhan. Tampak sebuah kapal penjemput yang sangat besar berlabuh di dermaga. Sementara Ogodai Leng memandangi prajurit-prajuritnya yang tengah diliputi kebimbangan. Beberapa prajurit mulai bergerak memisahkan diri, kemudian memacu kudanya dengan cepat menuju ke pelabuhan.
“Kembali kalian!” seru Panglima Ogodai Leng geram.
Tapi prajurit-prajurit yang meninggalkan pemimpinnya itu tidak lagi peduli. Mereka terus memacu kudanya menyusul Hulagu Leng. Hal ini membuat Panglima Mongol itu jadi geram. Amarahnya meluap! Dia berteriak keras seraya menghentakkan kedua tangannya ke depan.
Secercah sinar merah melesat dari kedua telapak tangan Panglima Mongol itu. Sinar merah itu meluruk cepat bagai kilat melanda separuh prajurit yang meninggalkannya. Jerit dan pekik melengking terdengar saling sahut begitu sinar merah itu menerpa tubuh mereka.
“Lihat...! Siapa yang berani membangkang perintahku, maka akan bernasib sama dengan mereka!” seru Ogodai Leng pongah.
“Biadab...!” Rangga menggeram muak melihat kekejaman Panglima Mongol itu.
Lebih dari dua puluh orang tewas dalam seketika terhantam pukulan jarak jauh Panglima Ogodai Leng. Mereka adalah prajurit-prajuritnya sendiri. Sisa prajurit yang masih berada di punggung kudanya tidak berani lagi coba-coba mengkhianati panglimanya.
Tapi lima orang yang mungkin sudah tidak tahan akan kekejaman panglimanya itu, tidak mengindahkan peringatan tadi. Mereka menggebah kudanya agar berlari cepat menuju ke pelabuhan.
“Keparat...!” geram Panglima Ogodai Leng gusar. “Hiyaaa...!”
Ogodai Leng menghentakkan tangannya ke depan, maka sinar merah kembali meluncur cepat bagai kilat dari telapak tangannya. Melihat nyawa lima orang yang kelihatannya terancam, Rangga tidak bisa tinggal diam lagi. Cepat-cepat dikerahkan aji ‘Cakra Buana Sukma’.
“Hiyaaat...!”
Rangga menghentakkan tangannya ke depan, menghadang cahaya merah yang melesat ke arah lima orang penunggang kuda itu. Dari telapak tangannya melesat cahaya biru menggumpal bagai bola sebesar kepala. Cahaya biru itu langsung menghantam cahaya merah.
Glarrr...!
Ledakan dahsyat terdengar bagai letusan gunung berapi. Tampak Panglima Ogodai Leng terpental sejauh lima batang tombak. Begitu pula Pendekar Rajawali Sakti. Punggungnya sampai menghantam dinding sebuah rumah hingga jebol. Dua jenis kesaktian yang bertemu, memang menimbulkan suatu kekuatan dahsyat. Ledakan itu juga menimbulkan pijaran bunga api ke segala arah, sehingga membakar beberapa rumah di sekitar tempat itu.
Rangga melompat keluar dari dalam rumah yang terlanda tubuhnya. Rumah itu sudah terbakar sebagian atapnya. Saat yang sama, Panglima Ogodai Leng pun sudah bisa bangkit berdiri. Mereka berdiri saling berhadapan. Ogodai Leng menggeram marah melihat lima orang prajuritnya telah mencapai dermaga. Bahkan sepuluh orang lagi memacu cepat kudanya memasuki pelabuhan. Tinggal sekitar dua puluh orang lagi yang tersisa.
“Setan! Berani kau menghalangiku, Anak Muda!” geram Ogodai Leng.
“Aku tidak bisa melihat kekejaman berlangsung di depan mataku!” sahut Rangga ketus.
“Kalau begitu, kau harus mampus!”
Setelah berkata demikian, Ogodai Leng segera mencabut senjatanya yang berupa golok besar dan panjang, bergagang sepanjang mata goloknya. Kelihatan berat sekali senjata itu. Tapi di tangan Ogodai Leng, golok itu seperti terbuat dari karet saja. Kini diputar-putar senjatanya dengan cepat, sehingga menimbulkan angin menderu-deru. Siapa saja yang mendengarnya pasti menjadi ciut hatinya.
Tapi Pendekar Rajawali Sakti kelihatan tenang saja. Dia masih berdiri tegak dengan mata tajam mengamati setiap gerakan yang dilakukan Panglima Mongol itu. Sekecil apa pun gerakannya, menjadi perhatian Rangga.
“Hiyaaat...!” Ogodai Leng berteriak keras menggelegar.
Dia berlari kencang sambil mengangkat senjatanya tinggi-tinggi di atas kepala. Kedua tangannya menggenggam gagang golok yang panjang. Sedangkan Rangga masih tetap berdiri tegak tidak bergeming sedikit pun. Semua orang yang melihatnya hanya menahan napas. Demikian pula Kakek Pengemis dari Utara.
“Edan! Apa dia mau bunuh diri...?!” dengus Kakek Pengemis dari Utara.
Panglima Ogodai Leng mengayunkan goloknya dengan keras dan bertenaga penuh. Ayunan golok itu menimbulkan suara menderu disertai desiran angin yang dahsyat. Namun Rangga masih tetap diam tidak bergeming, meskipun golok itu mengancam ke arahnya. Tapi ketika golok itu dekat...
“Yap...!”
Secepat kilat Pendekar Rajawali Sakti itu menarik kakinya ke belakang, lalu tubuhnya melenting ke udara. Hanya sekali berputar di udara, tiba-tiba kakinya mendupak keras ke arah kepala Ogodai Leng. Saat itu Ogodai Leng masih terpusat pada ayunan goloknya yang menghantam tanah, sehingga begitu terperangah setelah merasakan desiran halus di atas kepalanya. Buru-buru dirundukkan kepalanya, maka ayunan kaki Rangga lewat di atas kepala Panglima Mongol itu.
“Yaaa...!”
Sambil berteriak nyaring, Ogodai Leng memutar tubuhnya sambil mengibaskan goloknya. Saat itu Rangga tengah meluruk turun dan tidak sempat lagi menghindar. Dengan manis sekali ujung jari kakinya menotok ujung golok Panglima Ogodai Leng. Dengan meminjam tenaga panglima itu, Rangga melentingkan tubuhnya kembali ke udara.
“Awas kepala...!” teriak Rangga keras.
“Ikh...!” Ogodai Leng terpekik kaget.
Sungguh tidak diduga sama sekali kalau Rangga bisa cepat berbalik arah, bahkan kini menyerangnya dengan tangan kanan mengibas ke arah kepala. Ogodai Leng buru-buru melompat mundur seraya mengibaskan goloknya ke depan.
“Hap!”
Tangkas sekali Rangga menangkap golok lawannya ini. Tapi rupanya Ogodai Leng memiliki tenaga dalam yang tinggi juga. Dengan sekali sentak saja goloknya sudah terlepas dari jepitan tangan Pendekar Rajawali Sakti.
“Bagus!” seru Panglima Ogodai Leng tiba-tiba. Dia kini berdiri tegak dengan senjata tersandang di pundak. Rangga yang sudah menjejakkan kakinya di tanah, juga berdiri tegak dengan tangan melipat di depan dada. Tatapan matanya tajam, menembus langsung ke bola mata Panglima Mongol itu. Bibirnya terkatup rapat.
“Jauh-jauh aku mengelilingi dunia hanya untuk mencari orang tangguh! Ternyata di sinilah aku mendapatkannya. Bagus, Anak Muda! Yang kuinginkan pertarungan yang sungguh-sungguh sampai salah satu di antara kita ada yang mati!” kata Panglima Ogodai Leng, wajahnya tampak berseri-seri.
“Hm...,” Rangga bergumam pelan.
Tidak diduga sama sekali, ternyata Panglima Ogodai Leng datang ke sini hanya untuk mencari seseorang yang bisa menandinginya. Mengelilingi dunia hanya untuk mencari lawan! Namun tindakannya yang kasar dan brutal memberikan kesan buruk padanya. Dan citra buruk Panglima Mongol itu tidak dapat lagi dihilangkan dari hati siapa pun, termasuk pendekar muda itu.
“Siapa namamu, Anak Muda?” tanya Panglima Ogodai Leng.
“Rangga,” sahut Rangga singkat.
“Ingat kata-kataku, Rangga. Jangan menyesal kalau memandangku rendah. Aku tidak segan-segan membunuhmu!” kata Panglima Ogodai Leng tegas dan lantang.
“Majulah!” tantang Rangga.
“He he he...! Kau tidak bersenjata, Rangga,” Panglima Ogodai Leng terkekeh.
“Rasanya belum perlu mengeluarkan senjata,” sahut Rangga tenang.
“Oh.... Begitu? Baiklah. Jangan menyesal kalau kau mampus tanpa senjata. Kau sudah kuperingatkan, Anak Muda.”
Setelah berkata demikian, Panglima Ogodai Leng melompat menyerang menggunakan jurusnya yang dahsyat. Rangga menarik kakinya ke belakang seraya mengegoskan tubuhnya ke kiri. Terjangan senjata Ogodai Leng hanya lewat di samping tubuhnya. Dan dengan cepat, kaki kanan Pendekar Rajawali Sakti itu melayang ke arah iga. Tapi manis sekali berhasil dielakkan Panglima Mongol itu.
DELAPAN
Sementara Rangga bertarung melawan Panglima Ogodai Leng, Kakek Pengemis dari Utara terus mengawasi prajurit-prajurit Mongol yang masih berada di punggung kudanya masing-masing. Kakek tua renta itu berjaga-jaga seandainya salah seorang dari mereka melakukan kecurangan. Pertarungan Pendekar Rajawali Sakti dengan Panglima Ogodai Leng adalah suatu pertarungan dua orang jantan sejati.
Pada saat pertarungan mencapai taraf yang sangat tinggi, dari arah selatan muncul Prabu Duta Nitiyasa yang didampingi Resi Kamuka. Di belakang mereka berbaris para prajurit dan murid-murid Padepokan Arang Watu. Pada saat yang sama, dari arah pelabuhan juga datang Hulagu Leng.
Resi Kamuka memberi aba-aba lewat tangannya agar prajurit-prajurit lain tidak ikut campur dalam pertarungan ksatria itu. Dia turun dari kudanya diikuti Prabu Duta Nitiyasa. Resi Kamuka mendekati Kakek Pengemis dari Utara. Laki-laki tua kumal itu hanya melirik sedikit. Sepertinya tidak ingin kenikmatannya terganggu sedikit pun dalam menyaksikan pertarungan yang dahsyat dan menarik ini.
“Bagaimana ini bisa terjadi?” tanya Resi Kamuka.
“Kejantanan,” sahut Kakek Pengemis dari Utara singkat.
“Lalu mereka?” Resi Kamuka melirik para prajurit Mongol yang menonton di atas punggung kudanya masing-masing.
“Mereka akan pergi kalau panglimanya kalah,” sahut Kakek Pengemis dari Utara tidak menoleh sedikit pun.
Kakek Pengemis dari Utara tidak mempedulikan para prajurit Mongol lagi. Perhatiannya terus tertuang pada pertarungan dua satria itu, karena merasa yakin ada orang lain lagi yang mengawasi para prajurit itu. Dan ini satu kesempatan yang tidak disia-siakannya. Masalahnya, jarang bisa menyaksikan dua orang berilmu tinggi bertarung.
Sementara itu pertarungan antara Pendekar Rajawali Sakti melawan Panglima Ogodai Leng sudah mencapai taraf yang tinggi. Masing-masing mengeluarkan jurus andalannya. Bahkan kini Rangga mengeluarkan senjata pusakanya, Pedang Rajawali Sakti. Cahaya biru langsung menyemburat menerangi sekitarnya, membuat mata silau.
Tampak Panglima Ogodai Leng terkesiap juga melihat pamor pedang di tangan lawannya yang begitu dahsyat. Ada sedikit kegentaran di hatinya, namun cepat-cepat dibuang perasaan itu. Dengan tangan kosong saja Rangga mampu menandingi sampai lebih dari lima puluh jurus, apalagi kini dia memegang senjata yang memiliki pamor demikian dahsyat!
Sesaat pertarungan terhenti. Dua orang itu saling berhadapan dalam jarak yang tidak begitu jauh. Mereka saling menatap tajam, seolah-olah tengah mengukur tingkat kepandaian lawan.
“Kakak Ogodai Leng...,” terdengar suara Hulagu Leng yang sudah kembali berada di tempat itu.
“Jangan ikut campur, Hulagu Leng. Pergilah! Bawa seluruh prajurit kembali ke Mongol!” kata Ogodai Leng tanpa memalingkan mukanya.
“Kak, mengapa kau masih juga mencari lawan? Bertahun-tahun mengelilingi dunia hanya untuk memuaskan ambisimu untuk menjadi orang terkuat di dunia. Sadarlah, Kak! Itu tidak akan terjadi. Tidak sedikit orang kuat dan tangguh di dunia ini. Kau tidak akan bisa menandingi mereka semuanya,” Hulagu Leng masih mencoba menyadarkan kakaknya.
“Pergi kataku, Hulagu Leng!” dengus Ogodai Leng geram.
“Kak....”
“Pergi...! Hiyaaa...!”
Ogodai Leng tidak mendengar lagi kata-kata adiknya. Dan segera diterjangnya Rangga dengan golok terangkat ke atas. Pada saat itu, Rangga sudah siap dengan jurus ‘Pedang Pemecah Sukma’. Jurus yang sangat diandalkan jika menggunakan Pedang Pusaka Rajawali Sakti.
Trang!
Rangga sengaja menghantamkan pedangnya ke senjata Panglima Ogodai Leng. Bunga api memercik begitu dua senjata beradu keras. Pada saat yang sama, kaki Pendekar Rajawali Sakti melayang ke arah perut. Tendangan yang tidak terduga itu tak terhindarkan lagi.
“Hug...!” Panglima Ogodai Leng mengeluh pendek.
Tubuhnya terjajar beberapa langkah ke belakang. Belum lagi sempat mengatur napasnya yang mendadak sesak, Rangga sudah melompat sambil mengayunkan pedangnya ke arah kepala. Ogodai Leng cepat-cepat mengangkat goloknya melindungi kepalanya dari tebasan pedang itu.
Tring!
“Akh...!” Panglima Ogodai Leng memekik tertahan.
Semua orang yang berada di situ jadi terbeliak melihat senjata Panglima Ogodai Leng terpenggal jadi dua bagian. Dan belum lagi rasa heran itu hilang, tiba-tiba saja Rangga berteriak keras. Tubuhnya melesat sambil mengibaskan pedangnya beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Ogodai Leng.
“Aaa...!” Panglima Ogodai Leng menjerit keras.
Meskipun sudah berusaha menghindari serangan itu, namun satu tebasan pedang berwarna biru itu berhasil membuntungkan tangan kiri Ogodai Leng sebatas pangkal lengan. Dan ketika tubuhnya limbung, Rangga kembali mengibaskan pedangnya ke arah leher. Kali ini Panglima Ogodai Leng tidak bisa bersuara lagi.
Sebentar tubuhnya masih mampu berdiri tegak, kemudian limbung dan ambruk ke tanah. Lehernya putus terbabat pedang Pendekar Rajawali Sakti. Darah mengucur deras dari pangkal lengan dan leher yang buntung.
“Kak..!” pekik Hulagu Leng histeris.
Hulagu Leng berlari menubruk mayat kakaknya yang menggeletak tidak bergerak-gerak lagi. Pemuda berwajah tampan bagai wanita itu meratapi kematian kakaknya. Disesali sikap kakaknya yang begitu keras dan merasa terhebat di jagad ini. Sudah tidak terhitung berapa negeri yang dimasukinya, berapa nyawa melayang di tangannya. Hari ini dia menemui kematiannya di tangan seorang pendekar muda yang tangguh.
Rangga berdiri tegak memandangi Hulagu Leng yang meratapi dan menyesali kematian kakaknya. Dimasukkan kembali Pedang Rajawali Sakti ke dalam warangkanya di balik punggung. Seketika keheningan mencekam sekitar tempat ini. Hanya ratapan Hulagu Leng saja yang terdengar lirih. Kata-kata yang diucapkannya sangat sukar untuk dimengerti. Hanya mereka yang dari Mongol saja bisa memahami.
Hulagu Leng bangkit berdiri perlahan-lahan, dan langsung menatap pada Pendekar Rajawali Sakti yang masih berdiri di tempatnya. Sesaat mereka hanya saling tatap tanpa berkata-kata. Entah apa yang ada dalam hati masing-masing.
“Aku tidak akan dendam padamu. Memang inilah yang diinginkan kakakku. Mati di tangan seorang yang tangguh dan sakti melebihi kemampuannya,” kata Hulagu Leng agak tersendat.
“Maafkan aku,” ucap Rangga pelan.
“Tidak. Kau tidak perlu meminta maaf. Hanya kematianlah yang dapat menghentikan sepak terjang kakakku. Seandainya kau tadi kalah, entah berapa nyawa lagi akan melayang melalui tangannya. Terus terang, aku sendiri tidak setuju dengan segala tindakannya. Yang Mulia Jengis Khan sengaja menempatkan aku pada pasukan ini untuk mengontrol tindakan kakakku. Tapi Kak Ogodai Leng memang keras dan sulit untuk menghentikannya...,” semakin lirih suara Hulagu Leng.
Semua orang terdiam. Hati mereka tersentuh dengan kata-kata yang diucapkan adik panglima itu. Terlebih lagi Pendekar Rajawali Sakti. Sebenarnya dia sangat menyesal telah menewaskan Ogodai Leng. Kalau saja dia tahu, mungkin hanya membuatnya kalah tanpa harus membunuhnya. Ternyata selama ini segala tindakan Ogodai Leng dan prajurit-prajuritnya memang disengaja untuk memancing keluarnya tokoh-tokoh sakti agar bisa bertarung dengannya. Itulah yang menjadi tujuan utamanya.
Tapi jika Rangga tidak menewaskannya, Ogodai Leng akan tertekan sepanjang hidupnya. Bahkan mungkin akan menyimpan dendam yang semakin berkobar. Tindakannya pun akan bertambah brutal lagi. Memang hanya kematian sajalah yang dapat menghentikan ambisinya itu, seperti yang dikatakan adiknya, Hulagu Leng.
Hulagu Leng memerintahkan para prajurit yang masih ada di tempat itu untuk mengangkat mayat panglima mereka dan meletakkannya di punggung kuda. Hulagu Leng menghampiri Rangga dan menyodorkan tangannya. Sebentar Rangga menatap, lalu menerima uluran tangan itu.
“Kuharap kita bisa bertemu lagi. Bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sahabat,” ucap Hulagu Leng.
“Mudah-mudahan,” sahut Rangga terharu akan kebesaran jiwa orang Mongol ini.
Hulagu Leng menghampiri Prabu Duta Nitiyasa. “Aku berharap Tuan rela memaafkan atas segala kerusakan dan penderitaan yang terjadi selama kami berada di sini,” ucap Hulagu Leng seraya menjabat tangan Prabu Duta Nitiyasa.
“Yah...,” hanya itu yang bisa keluar dari mulut Prabu Duta Nitiyasa. Dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Semuanya sudah terjadi.
Hulagu Leng memerintahkan praju-ritnya menuju ke pelabuhan. Sedangkan dia sendiri masih berdiri menghadap Prabu Duta Nitiyasa. Para Prajurit Mongol itu sudah bergerak membawa mayat panglimanya.
“Terima kasih atas kebaikan hati Tuan dan seluruh rakyat di sini,” ucap Hulagu Leng.
Prabu Duta Nitiyasa mengangkat bahunya, sepertinya masih sulit untuk mengucapkan kata-kata.
“Aku berharap Tuan sudi datang ke Kerajaan Mongol. Tuan bisa melihat bahwa sebenarnya bangsa kami cinta damai. Dan antara bangsa Tuan dan bangsa kami bisa saling mengikat tali persahabatan,” kata Hulagu Leng lagi.
“Dengan senang hati kuterima undangan ini,” sahut Prabu Nitiyasa.
“Terima kasih.”
Hulagu Leng menjabat tangan Prabu Duta Nitiyasa sekali lagi, kemudian menghampiri kudanya dan melompat naik. Sebentar dipandangi semua orang yang berada di tempat ini, kemudian menggebah kudanya meninggalkan tempat itu.
Prabu Duta Nitiyasa melangkah perlahan-lahan menuju ke pelabuhan. Resi Kamuka, Kakek Pengemis dari Utara, dan beberapa prajurit mengikuti dari belakang. Sementara itu orang-orang Mongol yang sudah berada di atas kapal, datang menjemput Hulagu Leng dan prajurit lain. Saat semuanya sudah berada di atas kapal, Prabu Duta Nitiyasa dan yang lainnya sudah sampai di dermaga.
Kini, perlahan-lahan kapal besar itu bergerak meninggalkan dermaga. Tampak di anjungan, Hulagu Leng melambai-lambaikan tangannya. Prabu Duta Nitiyasa membalas dengan lambaian tangan juga. Kapal itu terus bergerak ke tengah laut lepas. Semakin lama semakin jauh menuju cakrawala. Saat itu senja mulai merayap turun. Keremangan pelahan menyelimuti sekitarnya. Prabu Duta Nitiyasa masih berdiri di dermaga memandang ke laut lepas.
“Hhh..., ternyata masih ada orang Mongol yang berbudi luhur,” desah Prabu Duta Nitiyasa.
“Di mana pun tempatnya, pasti ada yang baik dan ada yang buruk,” jelas Resi Kamuka.
“Ya..., ini satu pelajaran untuk kita semua,” desah Prabu Duta Nitiyasa kembali.
“Marilah, Ananda Prabu. Hari semakin gelap,” ajak Resi Kamuka.
“Tunggu dulu, Ayahanda Resi...!” sentak Prabu Duta Nitiyasa tiba-tiba, lalu berbalik.
Raja Jiwanala itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Resi Kamuka tahu apa yang dicari anak menantunya ini. Ditepuknya bahu Prabu Duta Nitiyasa sambil tersenyum dikulum.
“Dia sudah pergi,” kata Resi Kamuka.
“Pergi...!? Ke mana?” tanya Prabu Duta Nitiyasa.
“Untuk apa kau tanyakan itu, Ananda Prabu?” Resi Kamuka balik bertanya.
Prabu Duta Nitiyasa bungkam. Ya..., untuk apa bertanya begitu? Bukankah Rangga seorang pendekar kelana yang tidak pernah menetap dan tidak tentu tujuannya? Tapi Prabu Duta Nitiyasa tidak peduli. Dia begitu mengagumi Pendekar Rajawali Sakti itu, dan ingin mengundangnya tinggal di istana barang beberapa hari. Rasanya tidak pantas kalau tidak memberi kesan apa-apa, setelah Rangga mempertaruhkan nyawanya untuk memulihkan kembali Kerajaan Jiwanala.
“Ananda Prabu, mau ke mana...?” seru Resi Kamuka melihat Prabu Duta Nitiyasa berlari cepat dan melompat ke punggung kudanya yang dipegangi salah seorang punggawa.
Prabu Duta Nitiyasa tidak menjawab, tapi langsung menggebah kudanya dengan cepat. Resi Kamuka bergegas menghampiri kudanya. Kuda itu belum digebah meskipun laki-laki tua itu sudah naik ke punggung kuda. Dipandangi para prajurit dan murid-muridnya.
“Hm..., ayo kembali ke istana!” ajak Resi Kamuka.
********************
Ke mana sebenarnya Rangga pergi? Pendekar Rajawali Sakti itu memang belum meninggalkan Kerajaan Jiwanala. Dia berada di kedai milik Ki Jantar. Kedai itu memang tidak pernah tutup. Meskipun orang-orang Mongol menguasai istana kerajaan, Ki Jantar tidak berniat untuk mengungsi. Laki-laki tua pemilik kedai itu gembira sekali melihat kedatangan Rangga.
“He he he.... Den Rangga memang hebat!” puji Ki Jantar menyambut kedatangan Pendekar Rajawali Sakti itu.
“Hebat bagaimana, Ki?” tanya Rangga pura-pura bodoh.
“Aku tahu apa yang Den Rangga lakukan. Wah..., kalau saja tidak ada Den Rangga, apa jadinya kerajaan ini...? Untung Raden bisa mengalahkan Panglima Mongol itu,” Ki Jantar mengoceh.
“Minta araknya, Ki,” sela Rangga mengalihkan ocehan itu.
“Tidak perlu dibayar, Den,” kata Ki Jantar sambil menyediakan arak yang diminta Rangga. Bahkan juga disediakan makanan istimewa.
“Kenapa?” tanya Rangga.
“Jasa Raden tidak akan terbayar hanya dengan seguci arak dan makanan ini,” sahut Ki Jantar.
“Ah! Sudahlah, Ki. Aku hanya melakukan semampuku saja. Selebihnya..., aku angkat bahu saja,” kata Rangga tidak ingin membicarakan hal itu lagi.
“Pendekar sejati memang begitu, selalu merendahkan diri! Seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. He he he...,” Ki Jantar terkekeh.
Rangga hanya tersenyum saja mendengar celoteh itu. Dituang araknya ke dalam gelas, dan diteguknya hingga tandas. Pertarungannya melawan Panglima Ogodai Leng sangat menguras tenaganya. Baru kali ini didapatkan lawan yang begitu tangguh, hingga semua kemampuannya hampir terkuras.
Tapi dalam hati diakui jiwa ksatria yang dimiliki Panglima Ogodai Leng meskipun tindakannya salah. Dan yang membuat hatinya merasa tersentuh adalah sikap Hulagu Leng. Meskipun kakak kandungnya terbunuh, tapi tidak mendendam. Bahkan memintakan maaf untuk kakaknya yang telah bertindak keliru selama ini. Sungguh besar jiwanya!
“Kok melamun, Den...?” tegur Ki Jantar yang masih duduk di depan Rangga.
“Ah, tidak...,” desah Rangga terbangun dari lamunannya.
Rangga menatap laki-laki tua pemilik kedai ini. Selama berada di Kerajaan Jiwanala ini, banyak yang dapat didengar dan diketahuinya. Kerajaan ini boleh dikatakan seumur jagung! Tidak lebih tua dari usia Rangga sendiri sekarang. Dan lagi kebanyakan penduduknya berasal dari Karang Setra, tempat kelahiran Pendekar Rajawali Sakti. Bahkan Prabu Duta Nitiyasa sendiri masih saudara sepupu Adipati Arya Permadi, ketika Karang Setra masih berupa kadipaten. Jelas dia masih ada ikatan darah dengan Rangga. Jadi, Rangga harus memanggil Prabu Duta Nitiyasa dengan sebutan paman.
“Ada apa, Den?” tanya Ki Jantar merasa jengah dipandangi terus.
“Ada yang ingin kutanyakan padamu, Ki,” kata Rangga.
“Tentang apa?”
“Ki Jantar berasal dari Karang Setra, bukan?” tanya Rangga ingin membuktikan kebenaran cerita yang didapatnya.
“Benar,” sahut Ki Jantar, agak heran juga dengan pertanyaan itu.
“Kapan Ki Jantar meninggalkan Karang Setra?”
“Kira-kira lima belas atau dua puluh tahun yang lalu. Tepatnya ketika Gusti Adipati mendapat musibah,” sahut Ki Jantar.
“Ki Jantar tahu, apa yang terjadi terhadap keluarga Adipati Karang Setra?”
“Wah, tidak Den. Tapi kalau Raden ingin tahu, bisa tanyakan pada Gusti Prabu Duta Nitiyasa. Soalnya beliau masih sepupu Gusti Adipati Karang Setra. Malah kalau Raden ingin tahu lebih jauh, ada bekas pembesar kadipaten yang tinggal di sini. Sekarang pun jadi pembesar di istana, Den.”
“Siapa namanya, Ki?”
“Patih Raksajunta.”
Rangga tersentak. Tidak diduga kalau Patih Raksajunta dulunya juga seorang pembesar Karang Setra. Rangga memang sengaja datang ke kerajaan ini untuk maksud tertentu. Memang sudah banyak didengarnya kalau rakyat Kerajaan Jiwanala di pesisir pantai ini kebanyakan berasal dari Karang Setra. Mereka yang datang ke sini karena tidak suka dengan kepemimpinan Adipati Wira Permadi yang menggantikan Adipati Arya Permadi, ayahnya Rangga.
“Hm..., apakah bisa kudapatkan di sini?” Rangga bertanya dalam hati.
Apa sebenarnya yang dicari Pendekar Rajawali Sakti itu? Bagaimana sikap Prabu Duta Nitiyasa jika mengetahui Pendekar Rajawali Sakti adalah keponakannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah serial Pendekar Rajawali Sakti selanjutnya dalam episode KEMELUT PUSAKA LELUHUR
SELESAI

