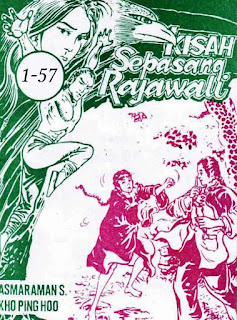TAMBOLON mengeluarkan suara gerengan seperti seekor harimau marah, pedang Ban Tok Kiam menyambar ketika dia menubruk lawan yang sudah roboh di tanah itu. Akan tetapi tiba-tiba kaki Tek Hoat bergerak dan hawa pukulan yang luar biasa dahsyatnya menyambar.
“Bressss...!”
Tambolon memekik kaget dan kesakitan, pedang Ban Tok Kiam terlempar jauh dan dia terdorong sampai bergulingan. Kiranya Tek Hoat yang sengaja menjatuhkan diri itu telah menggunakan kekuatan Inti Bumi yang paling ampuh, yang diambilnya dari tenaga bumi ketika dia rebah, dan kakinya telah menyerang dengan kekuatan luar biasa, yang kiri menendang pergelangan tangan lawan sehingga pedang Ban Tok Kiam terlempar, kaki kanan menendang ke arah dada dan biar pun sudah ditangkis oleh tangan kiri Tambolon, tetap saja tubuh raja yang tinggi besar seperti raksasa itu terlempar dan bergulingan.
Tek Hoat sudah meloncat dan mengejar. Tambolon mengeluarkan senjata jala yang ketika digerakkan berubah seperti uap, akan tetapi Tek Hoat yang sudah mengenal senjata ini tidak menjadi gentar. Bahkan dengan sengaja dia memapaki jala itu dengan pedangnya. Tambolon menjadi girang karena jalanya berhasil menangkap dan membelit pedang.
Dia menyangka bahwa seperti biasa, tentu pemuda itu akan berusaha menarik kembali pedangnya. Akan tetapi Tek Hoat memang sengaja membiarkan pedangnya terampas dan secepat kilat, dia melepaskan gagang pedang dan menggunakan kedua tangannya untuk menyerang dengan pukulan tangan terbuka yang mengandung tenaga Inti Bumi, yang kiri ke arah pusar sedangkan yang kanan ke arah pelipis.
Tambolon terkejut, berusaha menangkis dan memang berhasil menangkis pukulan ke pusarnya, akan tetapi tangan kanan Tek Hoat sudah menyambar pelipisnya.
“Dessss...!”
Tambolon terpelanting dan roboh dengan mata mendelik, tubuhnya kaku dan dia tewas seketika.
Panglima Jayin dan para pembantunya segera bersorak. Panglima ini cepat menyambar pedang, memenggal kepala Tambolon yang dipasangnya di atas tombak dan diangkat tinggi-tinggi ke atas agar kelihatan oleh semua orang dan untuk melenyapkan semangat tentara musuh.
“Tek Hoat, kau bantulah kami!” Puteri Milana berseru.
Tek Hoat memandang dengan terheran-heran melihat betapa Puteri Milana yang dia tahu amat lihai itu dan Ceng Ceng belum juga mampu merobohkan Si Petani Maut dan Si Siucai Maut. Dia memekik keras dan dengan tangan kosong dia menerjang Si Petani Maut Liauw Kui yang memang sudah jeri sekali karena dia bukan tidak tahu betapa Puteri Milana mempermainkannya, menyambut terjangan Tek Hoat dengan pikulannya.
Namun, dengan mudah Tek Hoat menangkap batang pikulan itu. Dengan pengerahan tenaga dia memaksa batang pikulan itu membalik dan robohlah Si Petani Maut, batang pikulan memasuki perutnya menembus ke punggung.
Tek Hoat yang sudah beringas seperti harimau yang haus darah itu lalu menubruk ke arah Siucai Maut sambil berseru, “Ceng Ceng minggirlah!”
Yu Ci Pok menyambut dengan totokan dua senjata siang-koan-pit, akan tetapi Tek Hoat yang sudah melindungi tubuhnya dengan kekuatan tenaga sakti Inti Bumi dan juga menghentikan jalan darah di bagian yang tertotok, menerima dua totokan itu dan membarengi dengan gerakan jari tangannya dipergunakan seperti sebatang pedang menusuk ke depan.
“Craattt!” Jari-jari tangan kanannya memasuki dada Yu Ci Pok seperti sebatang pedang dan robohlah pengawal kedua dari Tambolon ini, berkelojotan dan tewas.
Puteri Milana dan Ceng Ceng bertepuk tangan memuji, kemudian mereka bertiga terus mengamuk sehingga pihak musuh makin kacau dan akhirnya larilah sisa pasukan dari suku-suku bangsa liar itu, apa lagi setelah mereka semua mendengar bahwa Raja Tambolon telah tewas.

Berakhirlah perang itu dengan kemenangan gemilang di pihak Bhutan. Panglima Jayin mengarak Tek Hoat sebagai seorang pahlawan gagah perkasa karena dia sendiri telah menyaksikan betapa pemuda yang gagah perkasa ini sudah berhasil membunuh Tambolon yang demikian lihainya, berarti bahwa pemuda ini memang telah membuat jasa besar sekali dan patut diperlakukan sebagai seorang pahlawan yang dengan setia telah membela Kerajaan Bhutan.
Gak Bun Beng yang telah bertemu dengan Pendekar Super Sakti, cepat berlutut di medan perang itu, memberi hormat dengan hati terharu karena dia tadinya sudah tidak mengira akan dapat bertemu dengan pendekar sakti yang dianggap sebagai gurunya ini.
Sejenak Pendekar Super Sakti juga menunduk dan memandang, lalu mengangguk-angguk dan bertanya, “Bun Beng, aku sudah mendengar bahwa Kerajaan Bhutan dibantu oleh engkau dan Milana. Di mana sekarang dia?”
“Sumoi Milana sedang memimpin pasukan untuk membasmi barisan pemberontak, Suhu. Bagaimana keadaan Suhu dan Subo di Pulau Es? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat.”
“Kami baik-baik saja, Bun Beng. Aku meninggalkan Pulau Es untuk pergi menyusul dan mencari dua orang sute mu. Kian Lee telah kujumpai dan sudah kusuruh pulang, akan tetapi Kian Bu masih kucari-cari. Apakah engkau melihat dia?”
Bun Beng menggeleng kepala. “Teecu pernah bersama dengan Sute Kian Bu ketika membantu pemerintah menghadapi para pemberontak yang dipimpin oleh dua orang Pangeran Liong, akan tetapi setelah itu, Sute Kian Bu pergi meninggalkan kota raja, kemudian terdengar lagi beritanya pada waktu dia menolong Puteri Syanti Dewi dari penghadangan Tambolon dan Durganini, lalu dia pergi lagi tanpa ada yang mengetahui ke mana, Suhu.”
“Hemmm, mari kita mencari Milana, mungkin dia tahu tentang adiknya itu.”
Bun Beng hanya mengangguk, tidak berani menceritakan betapa sejak dari kota raja, kekasihnya itu melakukan perjalanan bersama dia dan tentu saja pengetahuan Milana tentang Kian Bu tidak ada bedanya dengan apa yang telah dia ketahui. Bahkan dia masih merasa sungkan dan khawatir kalau-kalau pendekar sakti ini tidak akan senang hatinya mendengar akan keputusan mereka berdua untuk hidup bersama setelah Milana menjadi janda. Tentu saja orang tua sakti ini tidak tahu bahwa puterinya itu sebetulnya telah menjadi janda yang masih perawan!
Ketika mereka tiba di tempat pertempuran di mana Milana yang dibantu oleh Ceng Ceng dan Tek Hoat mengamuk, pertempuran telah selesai dan musuh telah terbasmi, yang melarikan diri dikejar oleh pasukan-pasukan Bhutan.
“Ayah...!” Milana cepat lari menyambut Pendekar Super Sakti dan di lain saat dia telah memeluk orang tua itu. Air mata puteri yang perkasa ini membasahi baju di dada ayahnya.
Pendekar Super Sakti mengelus rambut puterinya penuh kasih sayang. “Milana..., mana suamimu?”
Mendengar pertanyaan yang seolah-olah merupakan sebatang pedang yang langsung menikam ulu hatinya, Milana mengguguk tangisnya. Akhirnya dapat juga dia menjawab lirih, “...dia... dia telah tewas...”
Pendekar Super Sakti Suma Han adalah seorang manusia yang sudah dapat mengatasi segala perasaan, maka dia biasa saja mendengar berita hebat ini, hanya bertanya, “Bagaimana terjadinya hal itu?”
“Ayah, marilah kita memasuki kota raja dan bicara di sana dengan jelas.”
Pada saat itu, Raja Bhutan sendiri keluar menyambut dan dengan penuh kehormatan semua tamu agung yang sudah berjasa membantu Bhutan, terutama Tek Hoat, diarak masuk ke kota raja. Pendekar Siluman tidak menolak karena dia ingin mendengar cerita Milana tentang Kian Bu dan tentang Han Wi Kong, mantunya yang dikabarkan tewas itu.
Semua orang di kota raja menyambut para tamu agung, terutama sekali mereka menyanjung-nyanjung Puteri Milana dan Tek Hoat. Bahkan Tek Hoat sekaligus telah dikenal oleh mereka sebagai calon mantu raja!
Istana telah cepat sekali mempersiapkan penyambutan yang dipimpin sendiri oleh Puteri Syanti Dewi sehingga ketika rombongan pemenang ini memasuki kota raja dan tiba di depan istana, tempat ini telah dihias dengan meriah dan penari-penari serta musik menyambut mereka.
Pertemuan yang amat menggembirakan, semua orang tersenyum dan tertawa, semua wajah berseri-seri dan semua mata bersinar-sinar. Akan tetapi, suasana menjadi sangat mengharukan ketika tanpa disangka-sangkanya Puteri Syanti Dewi melihat Ceng Ceng di antara rombongan itu. Puteri ini terbelalak seperti mimpi saja dia melihat adik angkatnya, kemudian kedua orang dara cantik itu menjerit dan saling menubruk.
“Candra...!”
“Enci Syanti...!”
Mereka berangkulan dan menangis, saling berciuman karena sejak berpisah di tengah mala petaka ketika perahu mereka terguling, baru satu kali inilah mereka dapat saling bertemu kembali dan pertemuan ini terjadi di Bhutan! Sungguh merupakan hal yang aneh dan tidak tersangka-sangka oleh Syanti Dewi. Betapa hebat pengalaman mereka semenjak saling berpisah. Dan betapa cepatnya waktu berlalu karena begitu saling bertemu dan berpelukan, mereka merasa seolah-olah baru kemarin saja mereka saling berpisah.
Saling bergandeng tangan karena tidak sempat bicara di depan banyak orang, Syanti Dewi dan Ceng Ceng bersama semua rombongan itu memasuki istana di mana Raja Bhutan mengadakan penyambutan dengan pesta untuk merayakan kemenangan yang gemilang itu.
Rakyat dan para prajurit semua juga berpesta pora merayakan kemenangan besar itu. Suasana Kerajaan Bhutan gembira bukan main, sungguh pun harus diakui bahwa banyak pula yang menangis dan dilanda kedukaan hebat karena kematian suami, anak atau ayah yang menjadi prajurit Bhutan dan gugur dalam perang itu. Akan tetapi suara tangis mereka tenggelam dan hanyut oleh arus kegembiraan dari kota raja yang merayakan kemenangan.
Demikianlah adanya perang dan akibat-akibatnya! Di mana pun di bagian dunia ini, dan di jaman apa pun! Para korban perang yang membantu terlaksananya kemenangan, terlupa oleh yang merayakan kemenangan, oleh yang mengecap keuntungan dalam kemenangan perang.
Kalau pun para korban itu diingat oleh mereka, hal ini hanya sekilas saja, sekedar hiburan bagi keluarga si korban, atau lebih tepat, sebagai penonjolan dari yang merayakan kemenangan bahwa mereka itu tidak melupakan para korban, sungguh pun yang dikatakan tidak lupa itu hanya untuk satu kali setahun, dan itu pun hanya beberapa menit saja, lalu tidak dipedulikan lagi sama sekali sampai saatnya diperingati lagi!
Perang merupakan bukti betapa busuknya si aku mementingkan diri pribadi, secara keji mempergunakan manusia-manusia lain, kalau perlu mengorbankan laksaan nyawa manusia lain, demi untuk mencapai cita-cita yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah merupakan pengejaran sesuatu yang menguntungkan diri pribadi lahir mau pun batin. Perang merupakan bukti pula betapa bodohnya manusia, dipermainkan oleh slogan-slogan kosong, seperti sekelompok ikan memperebutkan umpan tidak tahu bahwa di dalam umpan tersembunyi maut!
Di dalam kesempatan berpesta-pora ini, Pendekar Super Sakti mendengar semua penuturan Milana tentang Suma Kian Lee dan Suma Kian Bu. Tanpa menyembunyikan sesuatu, Milana menuturkan tentang kepatahan hati dua orang pemuda Pulau Es itu.
“Aku kasihan sekali kepada mereka, Ayah. Kian Lee jatuh cinta kepada Ceng Ceng, dan ternyata kemudian bahwa Ceng Ceng adalah keponakan sendiri karena gadis itu adalah putera Wan Keng In dan Lu Kim Bwee.”
Pendekar Super Sakti Suma Han memandang ke arah Ceng Ceng yang sedang duduk menyendiri dengan wajah muram. Dia teringat akan pertemuannya dengan gadis itu, mula-mula di rumah makan ketika dia dan isterinya Lulu tiba di tempat itu dalam usaha mereka mencari putera mereka. Kiranya gadis yang kemudian melakukan perjalanan bersamanya itu adalah puteri Wan Keng In! Dengan demikian, Lulu telah menolong cucunya sendiri di dalam rumah makan itu! Lalu dia teringat akan Topeng Setan dan Pendekar Super Sakti menghela napas panjang. Ternyata buah perbuatan Wan Keng In masih terasa sampai sekarang!
“Tidak perlu dikasihani, Milana. Kalau dia melihat kenyataan bahwa gadis itu adalah keponakan sendiri, mengapa dia harus patah hati? Dan bagaimana dengan Kian Bu?”
“Bu-te lebih parah lagi, Ayah. Dia jatuh hati kepada Syanti Dewi, akan tetapi agaknya Puteri Bhutan itu tidak membalas cintanya karena puteri itu agaknya jatuh hati kepada Tek Hoat.” Puteri Milana mengerling dan Suma Han juga melihat betapa mesra puteri itu di dalam pesta melayani Tek Hoat yang duduk di samping Raja Bhutan dan permaisuri!
“Hemm, cinta yang menuntut balasan, kalau tidak dibalas lalu patah hati bukanlah cinta namanya...” Suma Han berkata lirih seperti kepada diri sendiri. “Kepatahan hati itu adalah salahnya sendiri, timbul dari iba diri. Di mana kiranya dia sekarang?”
“Aku tidak tahu, Ayah.”
“Biarlah, aku akan mencarinya. Dan engkau sendiri, Milana. Bagaimana engkau bisa berada di sini tanpa suamimu? Dan apa pula artinya ucapanmu bahwa suamimu telah tewas?”
Puteri Milana menekan perasaannya agar jangan sampai dia menangis di dalam pesta itu. Kemudian, dengan hati-hati dan lirih berceritalah dia tentang keadaannya dengan Han Wi Kong, betapa mereka itu menikah tanpa cinta kasih di pihaknya, hanya untuk memenuhi kehendak Kaisar, dan betapa Han Wi Kong telah bersikap jantan dan tidak memaksa dia memenuhi kewajiban sebagai isteri.
Kemudian tentang perbuatan Han Wi Kong yang membunuh Pangeran Liong Bin Ong sebagai tindakan ‘bunuh diri’ untuk memberi kesempatan kepadanya berkumpul kembali dengan orang yang dicintanya, yaitu Gak Bun Beng, dan tentang surat-surat Han Wi Kong yang sengaja ditinggalkan untuk dia dan Bun Beng.
Mendengarkan semua ini, Suma Han memejamkan kedua matanya dengan alis berkerut. Milana sudah siap untuk mendengar teguran dan kemarahan ayahnya, akan tetapi setelah Suma Han membuka kembali matanya, pendekar bijaksana itu berkata perlahan, “Nasib manusia berada di dalam tangannya sendiri, tergantung dari sepak-terjangnya sendiri dalam kehidupan.
Semua pengalamanmu itu hanya menjadi bukti bahwa apa pun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, Milana, haruslah kita lakukan dengan cinta kasih di dalam hati. Tanpa cinta kasih, maka semua perbuatan itu hanya akan menimbulkan pertentangan dan kedukaan belaka, seperti perbuatanmu menikah dengan Han Wi Kong, dan perbuatanmu bersama Bun Beng yang saling berpisah mematahkan ikatan perasaan antara kalian. Jadi sekarang, engkau dan Bun Beng...”
Milana menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. “Kami telah bersepakat untuk menghadap ke Pulau Es mohon restu dan ijin dari Ayah dan Ibu, dan karena saya telah menjadi buronan di kota raja, maka kami berdua akan pergi mengasingkan diri, entah ke mana, saya hanya akan menurut dan ikut dengan Gak-suheng...”
Suma Han mengangguk-angguk. “Memang sebaiknya jika kalian lebih dulu menghadap ibumu. Nah, biarlah sekarang juga aku pergi, Milana. Aku akan mencari Suma Kian Bu.” Sebelum Puteri Milana menjawab, tampak tubuh ayahnya berkelebat dan lenyaplah pendekar itu dari tempat itu, seolah-olah menghilang begitu saja di tengah-tengah orang banyak yang sedang berpesta.
Milana maklum akan sifat ayahnya yang aneh, maka dia cepat menghadap Raja Bhutan dan mintakan maaf bahwa ayahnya telah pergi tanpa pamit karena ayahnya mempunyai urusan pribadi yang penting. Semua orang terkejut dan kagum, akan tetapi hanya mengangguk-angguk dan merasa seram melihat ada orang dapat lenyap begitu saja di tengah-tengah mereka, seperti siluman!
Tidak lama kemudian, nampak Puteri Milana dan Gak Bun Beng sudah duduk berdua menghadapi meja dan bercakap-cakap dengan mesra, berbisik-bisik karena puteri itu menceritakan kepada kekasihnya tentang reaksi ayahnya ketika tadi mendengar pengakuannya tentang mereka. Legalah hati Bun Beng karena tadi pun, dari meja lain, dia melihat berkelebatnya gurunya itu lenyap, membuat dia khawatir sekali dan menduga bahwa pendekar itu pergi dengan marah. Kiranya tidak demikian, maka tentu saja hatinya merasa lega.
Semua orang di dalam pesta itu bergembira-ria, tenggelam dalam kebahagiaan masing-masing sehingga tentu saja melupakan orang lain. Tek Hoat yang dihujani sanjungan dan kini dilayani dengan mesra dan dengan terbuka oleh Syanti Dewi, di depan Raja dan Permaisuri Bhutan yang memandang sambil tersenyum penuh arti, tentu saja merasa bahagia sekali. Demikian pula Syanti Dewi yang melihat betapa pria yang dicinta dan dipilihnya itu kini telah kembali dalam keadaan selamat, sebagai seorang pahlawan pula, tentu saja menjadi sangat gembira sehingga dia pun lupa akan keadaan orang lain.
Semua orang bergembira-ria, kecuali Ceng Ceng. Sebaliknya, dara ini menjadi sedih sekali karena kebahagiaan orang-orang itu mengingatkan dia akan nasib dirinya. Teringat akan Topeng Setan, satu-satunya manusia yang dicinta, dan teringat akan Kok Cu, satu-satunya manusia yang dibencinya, ternyata kedua orang itu adalah sama, dan kini telah mati!
Padahal, dua orang itulah yang membuat dia tadinya masih ada gairah untuk hidup di dunia yang penuh duka ini. Topeng Setan menghiburnya dan kebaikan hati Topeng Setan membuat dia jatuh cinta kepada orang yang selalu menyembunyikan wajahnya di balik topeng yang amat buruk itu. Dia jatuh cinta bukan karena wajahnya, melainkan karena kebaikan yang banyak dilimpahkan kepadanya oleh pendekar sakti itu sehingga kehadiran Topeng Setan di dalam jalan hidupnya itu menimbulkan gairah hidup yang baru.
Ada pun Kok Cu yang selama ini dimusuhinya dan dibencinya karena pemuda itu telah memperkosanya, merupakan pula suatu dorongan sehingga dia tidak ingin mati dulu sebelum dia dapat membalas dendamnya. Dengan cara yang amat berlainan, bahkan dengan berlawanan, dua nama itu telah membuat dia bersemangat untuk hidup.
Akan tetapi, seperti halilintar datangnya, terbukalah kenyataan bahwa yang amat dicintanya adalah orang yang amat dibencinya, sebaliknya pula yang amat dibencinya itu ternyata adalah orang yang dicintanya, dan kini keduanya, yang sesungguhnya satu orang juga, telah mati! Apa lagi yang menahannya untuk hidup di dunia penuh duka kecewa ini? Lebih baik mati saja dan rasanya mati akan jauh lebih menyenangkan dari pada hidup!
Betapa banyaknya manusia di dunia ini hidup dalam duka dan kesengsaraan batin sehingga dunia ini dianggapnya sebagai tempat yang amat buruk, sebagai neraka yang amat menyiksa. Seperti juga Ceng Ceng, kita manusia selalu dirundung duka yang seribu satu macam sebabnya sehingga kita selalu haus akan kebahagiaan, selalu haus akan kesenangan dan selalu merasa bahwa di dunia ini, hanya kita sendirilah yang paling sengsara sedangkan orang-orang lain semua jauh lebih bahagia dari pada kita.
Benarkah demikian? Sesungguhnya tidaklah demikian kenyataannya. Selama kita memperhatikan keadaan orang lain, membanding-bandingkan dengan keadaan kita, akan timbul rasa kecewa dan iri, memupuk rasa iba diri. Dan kita lupa, seperti juga Ceng Ceng, bahwa justru kekecewaan dan kedukaan itu datang karena keinginan kita mencari yang lebih baik dan lebih menyenangkan itulah! Kita selalu menolak apa yang ada, selalu menolak kenyataan yang terjadi, membutakan mata terhadap kenyataan yang tidak menyenangkan dan mengejar-ngejar bayangan yang dianggap akan dapat menyenangkan.
Padahal, kenyataan seperti apa adanya tidak mengandung suka mau pun duka. Kenyataan apa adanya adalah kebenaran! Ada pun senang atau susah bukanlah bagian dari kenyataan itu, melainkan merupakan permainan dan pikiran kita sendiri, yang selalu menonjolkan dirinya pribadi, yang selalu akan senang kalau diuntungkan lahir maupun batin, dan selalu susah, kalau dirugikan lahir mau pun batin.
Pikiranlah biang keladi susah dan senang. Pikiranlah sumber segala duka dan sengsara! Dan ini merupakan suatu kenyataan, nampak dengan jelas sekali asal kita mau membuka mata dan memandang kenyataan tanpa dipengaruhi oleh segala macam pendapat, prasangka dan kesimpulan yang juga merupakan permainan dari pikiran pula.
Ceng Ceng tenggelam ke dalam lamunan yang menyedihkan. Namun dia hendak merahasiakan semua ini, demi kebahagiaan Syanti Dewi. Dia tidak ingin mengganggu kebahagiaan kakak angkatnya itu, maka ketika Syanti Dewi teringat kepadanya dan mendatanginya, lalu menarik tangannya diajak duduk bersama satu meja dengan keluarga raja, juga bersama Puteri Milana dan Gak Bun Beng yang sudah diminta pula oleh Syanti Dewi, Ceng Ceng tidak menolak dan berusaha menyelimuti kedukaan hatinya dengan senyum manis.
Ketika Raja mengumumkan pertunangan Tek Hoat yang masih mengaku she Ang itu dengan Puteri Syanti Dewi, semua orang menyambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai, juga Ceng Ceng segera menghampiri kakak angkatnya, dipeluknya dan diciuminya Syanti Dewi sambil mengucapkan selamat. Kedua orang wanita cantik ini mengusap air mata keharuan dan Ceng Ceng lalu menghampiri Tek Hoat sambil menjura dan berkata, “Kionghi (selamat), semoga engkau akan menjadi suami kakak angkatku yang baik.”
Tek Hoat tersenyum, menyatakan terima kasihnya dan berkata, “Ceng Ceng, kita adalah saudara seayah, maka kita semua ternyata bukanlah orang-orang lain, bukan? Harap kau maafkan segala kesalahanku yang lalu terhadapmu.”
Ceng Ceng tidak menjawab, hanya di dalam hatinya dia masih mengkhawatirkan apakah kakak angkatnya akan bahagia kelak menjadi isteri Tek Hoat yang dikenalnya sebagai seorang yang licik dan curang, dan jahat. Betapa pun juga, dia tak mengatakan apa-apa karena dia segera teringat akan laki-laki yang tak pernah dapat dilupakannya, biar pun telah mati itu. Topeng Setan atau Kok Cu itu, seperti juga Tek Hoat, baik atau jahatkah?
Kalau dia teringat akan Kok Cu, pemuda yang telah memperkosanya di dalam goa, maka jelas bahwa pemuda itu amat jahat, bahkan merupakan orang yang telah menghancurkan hidupnya, menghancurkan harapannya. Sebaliknya, kalau dia teringat akan Topeng Setan, jelaslah bahwa orang itu amat baik, terlalu baik malah, telah melimpahkan budi kebaikan kepadanya, telah mengorbankan lengannya, bahkan beberapa kali hampir mengorbankan nyawa untuknya. Jadi baikkah orang itu? Atau jahatkah?
Ceng Ceng termenung. Baik atau jahat ternyata tergantung dari pada penilaian kita sendiri, dan penilaian kita pun didasarkan atas kepentingan diri pribadi. Buktinya, kalau dia mengingat Kok Cu yang telah merugikan dia, maka otomatis dia menganggapnya jahat sekali. Dan kalau dia mengingat Topeng Setan yang telah menguntungkan dia, maka otomatis dia menganggapnya baik sekali. Padahal keduanya itu adalah orang yang sama! Tentu demikian pula dengan Tek Hoat. Siapa pun orangnya yang merasa dirugikan oleh Tek Hoat, tentu akan menganggapnya jahat, sebaliknya Syanti Dewi yang tentu telah menerima budi kebaikan dari Tek Hoat seperti dia menerimanya dari Topeng Setan, tentu saja menganggap Tek Hoat sebaik-baiknya manusia!
Ceng Ceng menghela napas panjang. Kenyataan yang membuka matanya lahir batin ini membuat dia menjadi muak akan kepalsuan manusia, akan kepalsuan dirinya sendiri. Setiap orang selalu menginginkan yang menguntungkan dan menyenangkan bagi dirinya sendiri saja, dan menolak yang merugikan atau tidak menyenangkan, maka timbullah suka dan tidak suka, timbullah cinta dan benci, timbullah puas, dan kecewa dan kesemuanya itu tentu saja mendatangkan pertentangan dan kesengsaraan.
Syanti Dewi yang sedang tenggelam dalam kegembiraan itu kini mulai memperhatikan Ceng Ceng. Biar pun adik angkatnya itu kelihatan tersenyum-senyum dan ikut pula berpesta, namun wajahnya pucat dan matanya muram, jelas kelihatan oleh Syanti Dewi betapa kegembiraan Ceng Ceng hanyalah pura-pura belaka untuk menyembunyikan kedukaan yang amat besar.
Perang hebat terjadi di dalam batin Ceng Ceng. Di satu pihak dia menderita pukulan batin yang membuatnya amat berduka teringat kepada Topeng Setan, ditambah menyaksikan kemesraan antara Tek Hoat dan Syanti Dewi, dan pada lahirnya dia memaksa diri untuk ikut bergembira. Arak yang manis diminumnya terasa pahit, semua hidangan yang lezat terasa seperti racun di lidahnya. Dia berusaha menahan-nahan diri, akan tetapi makin diingat makin hebatlah tekanan yang menghimpit batinnya. Akhirnya dia mengeluh dan roboh terguling dari tempat duduknya.
“Adik Candra...!” Syanti Dewi menjerit.
“Ceng Ceng, kau kenapa...?” Tek Hoat juga berseru dan cepat pemuda ini melompat dan memondong tubuh Ceng Ceng yang pingsan, dibawanya masuk bersama Syanti Dewi dan diikuti pula oleh Puteri Milana dan Gak Bun Beng.
Puteri Milana dan Gak Bun Beng cepat memeriksa keadaan Ceng Ceng, dan keduanya saling pandang, lalu Puteri Milana berkata kepada Syanti Dewi, “Biarkan dia beristirahat. Dia mengalami tekanan batin...” lalu dia bersama Bun Beng keluar dari dalam kamar itu, diikuti pula oleh Tek Hoat yang membiarkan Syanti Dewi sendiri menemani Ceng Ceng yang masih rebah pingsan.
Sri Baginda sendiri juga berkenan menengok, dan Sri Baginda lalu bertanya kepada calon mantunya apa yang terjadi dengan diri Ceng Ceng, adik angkat puterinya itu. Dengan halus Tek Hoat melaporkan bahwa Ceng Ceng kelelahan dan perlu beristirahat. Sedangkan Milana sendiri berkata lirih kepada Bun Beng, “Heran sekali, apa yang menyebabkan dia begltu tertekan batinnya?”
“Dan aku pun heran ke mana perginya Topeng Setan yang dulu selalu menemaninya? Sayang Suhu tidak bercerita apa-apa sehingga kita tidak tahu bagaimana Ceng Ceng sampai berpisah dari Topeng Setan dan tahu-tahu datang bersama Suhu.”
Mereka menduga-duga, akan tetapi tidak dapat mengerti apa sebabnya dara itu sampai menderita pukulan batin demikian hebatnya, yang dapat mereka ketahui dari pemeriksaan mereka tadi. Untuk menghormati perayaan kemenangan itu, Milana, Bun Beng, dan Tek Hoat sendiri melanjutkan kehadiran mereka dalam perayaan sungguh pun hati mereka tidak dapat melupakan keadaan Ceng Ceng. Hanya Syanti Dewi saja yang tidak muncul lagi karena puteri ini menjaga sendiri adik angkatnya dengan hati gelisah.
Malam itu pesta dilanjutkan dengan meriah. Beberapa kali secara bergantian, Tek Hoat, Milana, dan Bun Beng menengok keadaan Ceng Ceng yang masih saja rebah seperti tidur pulas dalam keadaan tidak sadar. Bun Beng menyalurkan tenaga sinkang yang kuat dan halus untuk membantu gadis dan memperkuat jantungnya, kemudian dia pun keluar sambil memesan kepada Syanti Dewi bahwa apa bila Ceng Ceng sadar, biarkan gadis itu menangis sepuasnya karena keadaan Ceng Ceng itu hanya akan terbebas dari bencana kalau gadis itu dapat menangis atau menyalurkan beban yang menekan batinnya dengan menceritakan kepada orang lain yang dipercayanya. Syanti Dewi mengangguk dengan air mata berlinang.
Dalam keadaan tidur atau setengah pingsan itu Ceng Ceng mengigau, tubuhnya mulai panas. Syanti Dewi memperhatikan dengan gelisah dan menjadi bingung melihat sikap Ceng Ceng dalam igauannya. Kadang-kadang gadis itu memaki-maki nama ‘Kok Cu’, dan kadang-kadang dia memanggil-manggil ‘Topeng Setan’ dengan mesranya.
Menjelang tengah malam, Ceng Ceng membuka mata dan tiba-tiba meloncat bangun sambil menjerit, “Kau telah mati...!” Akan tetapi karena tubuhnya lemah dan kepalanya pening, hampir saja dia terguling kalau tidak cepat-cepat dirangkul oleh Syanti Dewi.
“Candra... adikku... ingatlah, aku siapa...?” Syanti Dewi yang merangkul itu berbisik dengan suara parau dan air matanya mengalir di kedua pipinya.
Sejenak sepasang mata Ceng Ceng yang muram itu menatap wajah Syanti Dewi seperti yang tidak mengenalnya, tatapan pandang mata yang kosong seolah-olah di balik sinar mata muram itu tidak ada semangatnya lagi. Syanti Dewi merasa seperti ditusuk jantungnya melihat tatapan pandang mata ini.
“Candra Dewi... adikku... kau... kau kenapa...?” Dia merangkul lagi, menciumi pipi yang pucat seperti mayat itu.
Akhirnya Ceng Ceng sadar. “Enci Syanti...!”
Dia merintih dan menangislah Ceng Ceng dalam pelukan Syanti Dewi, menangis sesenggukan akhirnya mengguguk dan air matanya mengalir seperti air bah membobol bendungannya. Syanti Dewi juga menangis, akan tetapi menangis dengan hati lega karena dia teringat akan pesan Bun Beng bahwa tangis akan membebaskan Ceng Ceng dari ancaman bahaya. Maka dia merangkul dan membiarkan Ceng Ceng menangis sepuasnya. Setelah agak reda tangis adik angkatnya itu, dia lalu mengambil sapu tangannya dan menyusuti air mata Ceng Ceng dari pipinya, menyusuti muka yang pucat itu.
“Adikku... adikku yang baik, kenapa kau begini berduka? Ceritakanlah kepada enci-mu ini dan aku bersumpah demi langit dan bumi, aku akan membantumu dengan seluruh kekuasaanku untuk melenyapkan ganjalan hatimu, Candra.”
“Ohh, Enci Syanti...” Ceng Ceng kembali menyembunyikan mukanya di pundak puteri itu. Bagaimana dia akan dapat menceritakan persoalannya itu kepada orang lain?
“Ceritakanlah, Adikku...”
Ceng Ceng tak dapat menjawab, hanya menggelengkan kepala tanpa menghentikan tangisnya.
“Aihh, Candra. Kau kira aku ini siapa? Aku adalah kakakmu, tahukah kau? Lupakah engkau betapa kita bersama-sama meninggalkan Bhutan dan kemudian mengalami segala macam peristiwa hebat? Dan sekarang setelah kita bersama dapat pulang dan berkumpul lagi di sini, engkau menjadi begini. Lebih hebat lagi, agaknya engkau sudah tidak percaya lagi kepada kakakmu ini...”
“Enci Syanti...! Janganlah kau berkata begitu... jangan...” Ceng Ceng terisak, suaranya seperti orang merintih.
“Kalau begitu, kau ceritakanlah semua kedukaanmu itu padaku. Kita ini selain saudara angkat, juga senasib sependeritaan, kalau engkau bahagia, aku pun ikut gembira, kalau engkau sengsara, aku pun ikut berduka. Bagaimana mungkin aku akan dapat menikmati kebahagiaanku sekarang ini kalau melihat engkau sengsara, Adikku?”
Ceng Ceng memejamkan matanya. Memang tidak salah ucapan kakak angkatnya ini. Dahulu dia mempunyai kakeknya akan tetapi kini sudah tidak ada. Kemudian di dunia ini ada Topeng Setan yang dianggapnya satu-satunya orang yang paling baik dan dekat dengannya. Topeng Setan pun sudah tidak ada. Dan Syanti Dewi yang tadinya sudah terpisah dari dia dan disangkanya sudah tewas atau tertawan musuh, sekarang sudah kembali dan berkumpul dengan dia. Memang satu-satunya orang yang paling dekat dengan dia hanya Puteri Bhutan inilah.
Dia menarik napas panjang dan melepaskan rangkulannya. “Baiklah, Enci Syanti. Mari kita duduk dan dengarlah ceritaku.”
Dua orang wanita muda yang cantik jelita itu lalu duduk di atas pembaringan, saling berhadapan dan mulailah Ceng Ceng bercerita. Dia ingin menyingkat ceritanya yang amat panjang itu, hanya mengemukakan hal-hal yang membuat dia merana dan sengsara seperti yang diderita sekarang ini.
“Ketika kita saling terpisah karena perahu kita terguling...” Ceng Ceng berhenti karena teringat betapa peristiwa itu terjadi gara-gara Tek Hoat yang kini menjadi calon suami puteri itu!
Syanti Dewi agaknya dapat meraba perasaan hati adik angkatnya, maka dia tersenyum dan berbisik, “Lanjutkanlah...”
“Aku berjumpa dengan seorang pemuda yang tertawan musuh-musuhnya dan berada dalam sebuah kerangkeng. Karena kasihan kepadanya, aku melarikan dia dengan kerangkengnya, membawanya ke sebuah goa dan di situ aku membuka kerangkeng dan membebaskannya...” Ceng Ceng berhenti lagi. Seperti tampak di depan matanya semua peristiwa itu, betapa pemuda itu dengan berkeras minta agar supaya dia tidak membebaskannya! Agaknya pemuda itu tahu bahwa dia keracunan dan akan terjadi hal yang hebat kalau sampai dia dibebaskan dari dalam kerangkeng!
“Lalu bagaimana, Adikku?” Syanti Dewi mulai tertarik oleh cerita yang dipersingkat ini.
“Setelah aku membebaskan dia... lalu dia itu... dia lihai sekali, dia merobohkan aku dengan totokan...”
“Ahhh...!”
“Kemudian... kemudian... dia memperkosaku...!” Ceng Ceng menutupi mukanya dengan kedua tangannya seolah-olah tidak ingin melihat peristiwa yang kembali membayang di depan matanya.
“Ehhh...!” Syanti Dewi terbelalak, otomatis pandang matanya menjelahi tubuh adiknya. Kemudian dia bangkit berdiri di depan pembaringan, kedua tangannya dikepal dan sepasang matanya bernyala-nyala. “Dia... dia memperkosamu? Adikku, katakan siapa jahanam itu! Aku akan menyuruh Tek Hoat mencarinya sampai dapat dan aku tidak akan mau menikah dengan dia sebelum dia dapat menyeret jahanam itu di depan kakimu! Aku juga akan mohon bantuan Paman Gak Bun Beng! Hayo katakan, siapa jahanam itu!”
Ceng Ceng menurunkan kedua tangannya, memandang puteri yang marah-marah itu dengan muka pucat, kemudian dia memegang kedua tangan puteri itu dengan perasaan berterima kasih sekali. “Enci Syanti, ceritaku belum habis...”
Syanti Dewi duduk kembali di atas pembaringan. “Apakah bukan peristiwa terkutuk itu yang membuatmu berduka? Kalau karena sakit hati itu, biar aku akan mengerahkan segala kemampuanku untuk membantumu membekuk jahanam itu!”
Ceng Ceng menggeleng kepalanya dengan lemas, pandang matanya muram dan sayu, kemudian dia berkata, “Aku akan melanjutkan, dengarlah, Enci Syanti. Seperti dapat kau maklumi, aku menaruh dendam kepada orang itu dan selama ini tiada hentinya aku mencari-cari dia untuk membalas sakit hatiku. Dalam perantauanku ini, aku bertemu dengan seorang lain, yaitu Topeng Setan.”
“Hemm, aku juga sudah mendengar tentang dia, yang kabarnya selalu membantumu dan merupakan seorang manusia ajaib dan lihai sekali yang bersembunyi di balik topengnya.”
“Benar. Dia adalah seorang manusia yang amat baik kepadaku, Enci, telah berulang kali menyelamatkan nyawaku, bahkan dia... dia... telah berkorban dengan lengan kirinya menjadi buntung ketika menolongku. Aku berhutang nyawa kepadanya, berhutang budi dan sudah sepatutnya kalau dia kuanggap sebagai manusia yang paling mulia di dunia ini...”
“Tentu saja! Aku pun tadinya mengalami hal seperti engkau itu dan aku sampai kini selalu menganggap Paman Gak Bun Beng sebagai seorang manusia yang paling mulia di dunia ini, tentu saja sesudah orang tuaku dan... Tek Hoat.”
Ceng Ceng mengangguk-angguk. “Dan kemudian... belum lama ini..., aku mendapat kenyataan yang menghancurkan seluruh perasaanku, yang membuat aku hampir gila, sebuah kenyataan yang amat hebat, Enci Syanti...” dan Ceng Ceng tak dapat menahan air matanya lagi.
Syanti Dewi memegang kedua tangan adik angkatnya. “Kenyataan apakah, Candra? Cepat kau beritahukan kepadaku.”
“Kenyataan bahwa Topeng Setan, orang yang paling kumuliakan dan karenanya paling kucinta... ketika topengnya terbuka... ternyata... ternyata dia... dia... adalah... pemuda yang memperkosa aku dahulu...”
“Aihhhh...!” Syanti Dewi setengah menjerit dan kembali dia meloncat berdiri, mukanya menjadi pucat dan pandang matanya penuh rasa iba, lalu mulutnya komat-kamit seperti berdoa akan tetapi terdengar bisiknya. “...jadi kau... membenci dan sekaligus mencinta orang yang sama...? Dan dia itu... musuhmu dan sekaligus sahabatmu, pemerkosamu dan sekaligus penolongmu...? Aihhh, bagaimana ini...?”
Seperti dalam mimpi, suaranya lirih dan datar, terdengar Ceng Ceng berkata membela, “Akan tetapi... ketika dia memperkosaku... dia... dia dalam keadaan tidak sadar karena keracunan... dan dia sudah berusaha mencegah aku membuka kerangkengnya...”
Mendengar ini, Syanti Dewi mengangguk-angguk, kemudian merangkul adik angkatnya itu dan berkata dengan suara serius, “Dengarlah baik-baik, Candra. Sekarang jawablah aku. Engkau sekarang ini, setelah semua itu terjadi, setelah semua itu lewat dan lupakan semua itu, sekarang jawablah, apakah engkau sekarang ini membencinya ataukah mencintanya?”
Ceng Ceng tertunduk lesu dan sampai lama tidak menjawab.
Syanti Dewi mencium kedua pipinya. “Sadarlah, Adikku. Tak perlu kau membiarkan diri tenggelam dalam peristiwa yang lalu. Katakanlah kepadaku. Bencikah kau kepadanya? Ataukah engkau cinta kepadanya?”
Ceng Ceng menggeleng kepada. “Entahlah, Enci Syanti. Aku tidak tahu. Dia demikian baik kepadaku, mungkin tanpa dia aku sudah mati, dan tidak mungkin lagi bertemu denganmu. Dia mengorbankan segalanya untukku, bahkan lengannya putus sebelah karena aku... akan tetapi... dia... dia yang memperkosaku.”
Syanti Dewi memandang Ceng Ceng sambil tersenyum. Sampai lama dia menatap wajah yang menunduk itu, kemudian dia memegang kedua pundak adik angkatnya, lalu memegang dagu yang meruncing itu dan tersenyum lebarlah Puteri Bhutan itu. “Adikku yang manis, kau cantik sekali! Tahukah kau apa yang tampak olehku? Jelas terbayang di wajahmu, Adikku, dan aku tidak akan salah lihat bahwa engkau cinta kepadanya.”
“Ehhh...?” Ceng Ceng terkejut sekali dan memandang tajam kepada kakak angkatnya itu, akan tetapi dia menundukkan mukanya lagi dan wajahnya makin muram.
“Candra... adikku yang cantik, mengapa kau khawatir? Engkau terlalu memandang rendah kepada kakakmu ini. Apa kau kira aku akan diam saja setelah melihat kenyataan bahwa engkau mencinta pria itu? Jangan kau khawatir, biar kusuruh sekarang juga Tek Hoat, agar dia mencari dia sampai ketemu.”
Ceng Ceng menghela napas panjang, terdengar dia mengeluh. “Aihhh, Enci Syanti, sia-sia saja segala perhatianmu kepadaku, karena dia... dia sudah mati...” Dan air mata mengalir turun lagi dari kedua mata Ceng Ceng.
“Heiiii...?!” Kini Syanti Dewi yang memandang dengan mata terbelalak dan wajahnya pucat. Kemudian dia menubruk, merangkul Ceng Ceng dan sekarang puteri itulah yang menangis tersedu-sedu. Dan anehnya, melihat kakak angkatnya menangis begitu sedih, Ceng Ceng merasa terhibur hatinya, atau setidaknya dia melupakan kesedihannya sendiri, bahkan kini dia yang berusaha menghibur Syanti Dewi!
“Sudahlah, Enci Syanti, sudahlah..., ditangisi pun sia-sia...!”
Memang aneh sekali, akan tetapi telah menjadi kenyataan bahwa kedukaan seseorang akan berkurang, menjadi ringan, atau setidaknya terhibur melihat kedukaan orang lain! Kenyataan ini pahit sekali, membayangkan dengan jelas bahwa kedukaan timbul dari rasa iba kepada diri sendiri, maka rasa iba itu menjadi berkurang kalau melihat orang lain juga menderita, apa lagi kalau penderitaan orang lain itu lebih besar dari pada penderitaannya sendiri. Rasa iba diri ini adalah penonjolan dari pada si aku yang selalu ingin menguasai batin manusia maka terjadilah kesengsaraan dan kedukaan yang memenuhi kehidupan kita.
Perlu sekali untuk disadari benar-benar bahwa kesengsaraan dan kedukaan bersumber kepada pikiran kita sendiri, yang membentuk si aku, karena pikiran kita sendirilah yang menimbulkan pertentangan-pertentangan di dalam batin dengan selalu menginginkan hal-hal lain dari pada kenyataannya yang ada, selalu menginginkan yang dianggapnya menyenangkan sehingga apa yang ada, yaitu kenyataan setiap saat yang dihadapinya, selalu tidak diamatinya benar-benar dan dianggapnya tidak menyenangkan.
Semua ini adalah permainan pikiran kita sendiri setiap saat dan demikianlah pikiran kita menguasai kehidupan kita setiap hari! Mata kita baru akan terbuka, keindahan setiap saat yang terkandung dalam setiap peristiwa baru akan tampak apa bila pikiran atau si aku tidak mencampurinya! Cinta kasih yang murni dan suci, terhadap apa pun juga, baru ada apa bila pikiran atau si aku tidak memegang kendali!
“Adik Candra..., betapa hebat penderitaanmu. Sungguh aku berdosa besar kepadamu, Adikku, aku bergembira, berbahagia, bersenang-senang tanpa memikirkan bahwa kau sesungguhnya sedang menderita kedukaan hebat...”
“Sudahlah, Enci Syanti. Engkau tidak bersalah apa-apa. Engkau tidak mengetahuinya dan tidak perlu pula Enci berduka karena keadaanku. Lanjutkanlah kegembiraanmu, Enci, engkau berhak untuk hidup berbahagia. Setidaknya, mengingat bahwa engkau akan berjodoh dengan seorang yang masih seayah denganku, membuat aku bersyukur. Aku sendiri... ahhh, hidup tidak ada artinya lagi, aku... aku bermaksud... akan pergi lagi dari sini besok...”
“Ehhh... ke mana...?”
“Entahlah. Mungkin kembali ke bekas tempat tinggal Kakek, atau... entah ke mana aku sendiri belum bisa memastikan...”
“Jangan, Candra...! Setidaknya, kau tinggallah di sini sampai hari pernikahanku.”
Ceng Ceng menggelengkan kepalanya dan menghapus sisa air matanya. “Tidak, Enci. Kehadiranku yang penuh kepahitan hanya akan mengganggu kebahagiaanmu saja. Aku sudah mengambil keputusan untuk pergi besok, pagi-pagi dari sini. Kau tidak boleh dan tidak bisa menahanku, Enci Syanti...”
“Candra...!” Syanti Dewi merangkul dan kembali kedua orang kakak beradik yang dipermainkan nasib sehingga keadaan mereka kini seperti bumi dan langlt itu saling bertangis-tangisan.
Malam itu juga Syanti Dewi pergi menemui Tek Hoat yang dimintanya agar sebagai saudara seayah, suka membujuk Ceng Ceng. Tek Hoat terkejut sekali saat mendengar semua penuturan kekasihnya itu tentang Ceng Ceng dan Topeng Setan. Tak pernah disangka seujung rambut pun bahwa Topeng Setan adalah musuh besar yang selalu dicari-cari Ceng Ceng itu, dan baru sekarang dia tahu bahwa adiknya seayah itu, adik tirinya, telah menjadi korban perkosaan Topeng Setan sendiri yang kini kabarnya telah tewas! Tergopoh-gopoh dia menemui Ceng Ceng di kamar gadis itu.
“Kau tidak boleh pergi...!” begitu memasuki kamar itu Tek Hoat berseru.
Ceng Ceng yang tadinya duduk termenung itu, kini meloncat bangun. Mukanya yang tadinya pucat menjadi agak merah karena perasaan marah menyelinap dalam hatinya. Dia berdiri menentang wajah pemuda itu dan menjawab dengan ketus, “Ada hak apa engkau melarang aku pergi?”
“Ada hak apa? Hemm, lupakah kau bahwa aku ini kakakmu, bahwa kita ini seayah? Kau tidak boleh pergi dalam keadaan begini!”
“Dalam keadaan bagaimana?”
“Kau sedang mengalami kedukaan, kau bisa jatuh sakit di jalan. Dan sudah menjadi kewajibanku sebagai saudara untuk menjaga dan melindungimu, aku akan berusaha untuk menggembirakan hatimu, menghiburmu...”
“Dengan sikapmu yang keras dan selalu memusuhiku itu? Hemm, Tek Hoat, agaknya engkau mengandalkan kepandaianmu dan mengandalkan kedudukanmu sekarang, maka kau hendak memaksaku. Kau kira aku mau tunduk begitu saja? Kau boleh bunuh aku sekarang juga, aku tetap hendak pergi besok pagi. Ingin kulihat kau bisa berbuat apa!” Ceng Ceng menantang, berdiri dengan kedua tangan dikepal.
“Kau... kau keras kepala!” Tek Hoat menegur, kedua tangannya juga dikepal.
Mereka berhadapan seperti dua orang musuh bebuyutan (musuh besar turun-temurun) yang hendak mengadu nyawa. Akhirnya setelah beberapa lama mereka saling pandang dengan sinar mata berapi, Tek Hoat menurunkan kembali tangannya dan menarik napas panjang. Kemudian dia berkata lirih setelah menghela napas lagi.
“Ceng Ceng, kau tidak tahu... biarlah selagi masih ada kesempatan aku akan mengaku semuanya kepadamu. Semenjak kita saling berjumpa dahulu, ketika aku menolongmu dari air sungai, timbul rasa suka yang aneh dan mendalam di dalam hatiku terhadap dirimu. Cobalah kau ingat-ingat, kalau tidak begitu, mana mungkin aku membiarkan engkau menguasai aku hanya dengan sumpah dan sapu tangan, bahkan aku rela pula menghambakan diri menjadi pembantumu ketika kau diangkat menjadi bengcu! Andai kata di dunia ini tidak ada Syanti Dewi yang lebih dulu telah menjatuhkan hatiku, yang telah kucinta sejak pertemuan pertama, agaknya... aku tidak akan ragu lagi bahwa aku tentu akan jatuh cinta kepadamu. Sejak dahulu ada getaran perasaan yang mengikat hatiku kepadamu, tidak tahu bahwa sesungguhnya engkau masih sedarah dengan aku. Engkau adikku... di dunia ini hanya ada seorang adik bagiku...”
“Hemm, kakak macam apa engkau ini yang selalu bersikap keras kepadaku.” Akan tetapi suara teguran Ceng Ceng itu mengandung getaran keharuan karena memang dia terharu sekali mendengar pengakuan Tek Hoat itu. Teringat dia betapa dahulu pun hampir saja dia jatuh cinta kepada pemuda ini dan di sudut hatinya memang selalu ada rasa suka terhadap Tek Hoat seperti yang diakui pula oleh pemuda itu. Ternyata pertalian darah itulah yang menimbulkan getaran itu.
“Memang, kita sama-sama keras kepala, Adikku. Agaknya inilah yang diwariskan oleh mendiang ayah kita yang kabarnya amat jahat itu. Kita berdua adalah keturunan orang yang jahat... akan tetapi hanya aku yang mewarisi kejahatannya, sedangkan engkau adalah seorang gadis yang gagah perkasa dan berbudi mulia. Akan tetapi kenapa justru engkau yang menderita kesengsaraan sedangkan aku berenang dalam kebahagiaan? Tidak! Engkau tidak boleh menderita kalau aku berbahagia. Adikku, Ceng Ceng... aku minta, aku mohon kepadamu, jangan kau pergi, Adikku...” Terdorong oleh rasa harunya, Tek Hoat pemuda yang berhati baja itu kini menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Ceng Ceng!
“Tek Hoat...” Ceng Ceng juga berlutut dan seperti digerakkan oleh tenaga gaib, kedua orang saudara tiri seayah ini saling rangkul dan untuk beberapa lamanya Ceng Ceng menangis di atas dada saudaranya.
Akan tetapi kekerasan hatinya timbul pula dan dia lalu bangkit berdiri, menyusut air matanya. “Tek Hoat, aku pun tidak pernah dapat membencimu. Terima kasih atas kebaikanmu kepadaku. Akan tetapi engkau tentu tahu, dalam keadaan seperti sekarang ini, aku membutuhkan ketenangan dan keheningan, aku harus pergi menyendiri, entah ke mana. Percayalah, kalau aku tidak mati, dan kalau luka di hati ini sudah tidak parah lagi, engkaulah satu-satunya orang yang akan kucari sebagai keluargaku.”
Tek Hoat menghela napas panjang dan juga bangkit berdiri. Dia telah mengenal bagai mana sifat Ceng Ceng yang amat keras. Seperti baja yang tak dapat ditekuk lagi. “Kalau begitu, aku hanya dapat ikut prihatin dan akan selalu mendoakan, Adikku.”
Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ceng Ceng berangkat pergi sebelum ada yang bangun dari tidurnya. Tentu saja dengan mudah dara ini keluar dari istana, juga dengan mudah keluar dari pintu gerbang sebelah timur karena para prajurit yang menjaga semua mengenal adik angkat Puteri Bhutan ini.
Dengan muka pucat dan pandang mata kosong Ceng Ceng keluar dari pintu gerbang tanpa menengok lagi. Langsung dia melanjutkan perjalanan dengan langkah-langkah perlahan maju ke depan tanpa tujuan karena pikirannya kosong dan semangatnya seperti telah terbang meninggalkan tubuhnya.
Belum jauh dia meninggalkan pintu gerbang timur, tiba-tiba ada suara memanggilnya, “Sumoi...!”
Ceng Ceng menghentikan langkahnya, berdiri lesu tanpa menoleh karena dia mengenal suara itu, suara Panglima Jayin, yang juga merupakan suheng-nya karena panglima ini pernah berguru kepada kakeknya.
Ketika Jayin tiba di depannya, Ceng Ceng berkata lesu, “Suheng, harap kau jangan ikut-ikut menahanku karena sudah bulat tekadku untuk pergi dan tak seorang pun boleh menahanku.”
“Sumoi, aku sama sekali tidak akan menahan dan mencampuri urusan pribadimu. Aku menyusulmu karena aku diutus oleh Sang Puteri Syanti Dewi. Beliau mengutus aku mengejarmu dan memanggilmu kembali karena tadi malam ada seorang tamu yang datang ke istana mencarimu. Akan tetapi karena hari telah malam, terpaksa kusuruh tamu itu bermalam di gedung tamu dan menunggu sampai pagi. Baru pagi tadi aku dapat menghadap Sang Puteri untuk menyampaikan permintaan tamu yang hendak menjumpai mu itu. Akan tetapi pagi-pagi sekali engkau sudah pergi, maka Sang Puteri mengutus aku untuk menyusul dan memanggilmu kembali ke Istana.”
“Suheng, aku tidak ingin bertemu dengan siapa pun juga. Engkau kembalilah dan katakan kepada Enci Syanti Dewi bahwa aku tidak mau menemui siapa pun.”
“Akan tetapi, Sumoi... engkau belum tahu siapa tamu itu!” Suara panglima ini tergetar karena dia pun sudah mendengar akan keadaan sumoi-nya itu dari Puteri Syanti Dewi. “Dia telah datang menyusul bersamaku. Inilah dia orangnya!”
Akan tetapi Ceng Ceng tidak mempedulikan kata-kata ini dan dia terus melanjutkan langkahnya. Siapa pun orangnya yang datang mencarinya, dia tidak ingin melihat dan menemuinya. Tanpa menoleh sedikit pun, Ceng Ceng melangkah terus, sama sekali tidak mempedulikan.
Baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba terdengar suara, “...bengcu...!”
Ceng Ceng berhenti seperti disambar petir dan dia berdiri tegak, mukanya pucat, kedua kakinya menggigil dan dia tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Dia tidak berani menoleh, karena tentu pendengarannya yang menipunya dan kalau dia menoleh, dia akan kecewa. Tidak mungkin! Tapi suara yang didengarnya tadi amat dikenalnya, terlalu dikenalnya malah, karena suara itu adalah suara Topeng Setan!
“Bengcu...!” Suara itu memanggil lagi, kini terdengar tergetar.
Untuk kedua kalinya Ceng Ceng tersentak kaget. Dia menoleh dan....
“Ouhhhhhh...!” dia menutupi mulut dengan punggung tangan kiri, menahan jeritnya.
Betapa kagetnya ketika dia melihat laki-laki yang berlutut di depannya itu, laki-laki yang melihat pakaian dan lengan kirinya, jelas adalah Topeng Setan, akan tetapi melihat wajahnya yang tidak tertutup topeng itu, wajah yang tampan dan gagah sekali sungguh pun pada saat itu kelihatan pucat dan dicekam perasaan khawatir, adalah wajah Kok Cu, pemuda yang telah memperkosanya.
“Kau...? Kau...?” Hati Ceng Ceng menjerit, akan tetapi bibirnya hanya bergerak-gerak dan mulutnya terbuka tanpa ada suara yang keluar, kemudian terdorong oleh kedua kakinya yang tiba-tiba menjadi lemas seperti lumpuh dan keterkejutan yang meremas hatinya, Ceng Ceng menjatuhkan diri berlutut dan menubruk orang itu sambil merintih dan menangis.
“Kau... kau... masih hidup..., ohhh, kau masih hidup...?” berulang-ulang dia berbisik seperti dalam mimpi ketika dia mendekapkan mukanya di atas dada yang bidang itu.
“Suhu menolong dan menyembuhkan aku...,” bisik Topeng Setan atau Kok Cu itu.
“...ahhh... hu-huuu-huukk... aku... aku girang sekali... aku... aku cinta padamu, Pam...” Ceng Ceng tiba-tiba menghentikan kata-katanya, tidak melanjutkan sebutan ‘paman’ tadi karena dia segera teringat dan cepat dia mengangkat mukanya.
Begitu melihat wajah tampan itu, dia berseru, “Ohhhh...!” dan merenggutkan tubuhnya menjauh.
Sementara itu, begitu Ceng Ceng tadi merangkul ‘tamu’ itu, Panglima Jayin sudah melangkah pergi dan memberi isyarat kepada para penjaga untuk pergi menjauh, lalu memasuki pintu gerbang dan membiarkan kedua orang itu bicara dengan leluasa. Senyum penuh rasa syukur membayang di wajah panglima gagah itu.
“Aku bukan Topeng Setan lagi...” Pemuda itu berkata. “Aku adalah Kao Kok Cu, aku adalah si pemuda laknat dan aku datang untuk menerima hukuman, Ceng Ceng. Semenjak peristiwa terkutuk yang terjadi di goa, aku selalu dikejar oleh dosa dan penyesalan. Apa lagi ketika aku mendengar bahwa engkau adalah penyelamat nyawa Ayah, aku makin menyesal, maka untuk menebus dosa dan untuk membalas budimu terhadap Ayah, aku kemudian menjadi Topeng Setan yang selalu melindungi dan membelamu. Sekarang, rahasiaku telah kau ketahui, maka aku datang untuk menerima hukuman. Kalau kau hendak membunuhku, lakukanlah, aku tidak akan menyesal mati di tanganmu, Ceng Ceng, karena aku akan mati di tangan seorang yang paling kucinta di dunia ini, yang paling kuhormati, kukagumi dan kujunjung tinggi.”
Ceng Ceng yang masih menggigil seluruh tubuhnya itu, mengeluh dan dia kembali menubruk, merangkul karena memang perasaan bahagia melihat ‘Topeng Setan’ masih hidup mengusir semua perasaan lain. “Paman... Paman... melihat engkau masih hidup, aku... ahhh, betapa bahagia rasa hatiku.” Dia berkata dan kembali dia lupa akan wajah tampan itu, merasa bahwa dia berada dalam pelukan Topeng Setan. “Melihat engkau mati, baru aku tahu bahwa aku cinta padamu, Paman, dan aku tidak ingin lagi terpisah darimu...”
“Ceng Ceng, janganlah menyebutku Paman... Engkau isteriku sayang... engkau sudah kuanggap isteriku sejak aku mengenakan topeng... Betapa bahagia hatiku mendapat pengakuan cintamu...”
Ceng Ceng merangkul dan menatap wajah itu, wajah tanpa topeng yang ternyata amat tampan dan gagah. Wajah yang semenjak peristiwa di goa itu tidak pernah dapat dilupakannya! Kok Cu yang melihat wajah jelita basah air mata itu, tergerak hatinya, penuh keharuan, penuh iba dan penuh kemesraan cinta, maka dia menunduk dan di lain saat dia sudah mencium mulut yang setengah terbuka itu, menciumnya dengan seluruh perasaan kasih sayang yang terluap dari lubuk hatinya, melalui bibirnya.
Sejenak Ceng Ceng terlena dan memejamkan mata, otomatis perasaan bahagia dan kasih sayang dari hatinya membuat kedua lengannya melingkari leher pemuda itu dan bibirnya pun bergerak menyambut. Akan tetapi tiba-tiba terbayang peristiwa di dalam goa. Mulutnya yang melekat pada mulut Kok Cu meronta, matanya terbelalak dan dia merenggutkan dirinya.
Kok Cu memandangnya dengan mata terbelalak penuh kekhawatiran.
“Plak! Plakk!”
Dua kali kedua tangan Ceng Ceng bergerak dan nampaklah garis-garis merah di kedua pipi Kok Cu yang pucat. Pemuda itu tersenyum.
“Terima kasih dan pukulan-pukulanmu barusan baik sekali, merupakan obat yang akan menyembuhkan penyesalanku. Kau pukullah lagi, Ceng Ceng. Sudah kukatakan bahwa aku siap menebusnya dengan kematian sekali pun...”
“Ouhhh... tidak... tidak...!” Ceng Ceng kembali merangkul. Kini dia memandangi wajah tampan itu dan jari-jari kedua tangannya mengelus dan membelai bekas tamparannya di kedua pipi pemuda itu. “Tidak... kau... kau adalah orang satu-satunya di dunia ini yang kucinta... kau adalah Topeng Setan yang telah melimpahkan budi kepadaku...”
“Akan tetapi aku juga pemuda laknat yang telah memperkosamu, Ceng Ceng.”
“Tidak... tidak...! Pada waktu itu engkau dalam pengaruh racun... peristiwa itu adalah kesalahanku sendiri. Engkau sudah berusaha mencegah aku membebaskan mu dari kerangkeng... dan engkau sudah berusaha sekuat tenaga mencegah, akan tetapi racun itu lebih kuat... tidak, engkau tidak bersalah...”
Wajah yang tampan dan gagah itu berseri. Tiba-tiba Kok Cu berdiri dan dengan satu tangannya yang luar biasa kuatnya itu, sekali angkat dia sudah mengangkat Ceng Ceng sehingga gadis ini berdiri pula. Wajah yang tampan itu menjadi kemerahan, matanya bersinar-sinar penuh kebahagiaan. “Kalau begitu... kau mengampuni aku...?”
“Tidak ada ampun karena kau tidak bersalah.”
“Aku berdosa dan aku mengharapkan ampunmu, Ceng Ceng.”
“Kalau begitu, aku mengampunimu, Pam... eh, Koko (Kakanda)...”
“Dan kau tidak membenci lagi kepada Kok Cu?”
Sambil merangkul leher pemuda itu, dan matanya masih mengalirkan air mata, Ceng Ceng tersenyum dan menggeleng kepala. “Sebaliknya malah, aku mencinta orang yang bernama Kok Cu.”
“Moi-moi...!”
“Koko...!”
Kembali mereka berdekapan dan sekali ini ketika Kok Cu mencium Ceng Ceng, dara itu menyambut dan membalasnya dengan penuh kemesraan. Dekapan dan ciuman itu seolah-olah menjadi tempat pencurahan seluruh perasaan mereka, rasa cinta, rasa rindu, dan semua kebahagiaan yang terasa di hati masing-masing sehingga mereka seolah-olah tidak ingin saling melepaskan lagi.
“Ceng Ceng, Moi-moi... betapa bahagia hatiku... ketahuilah, aku datang bersama Ayah. Selain menyusulmu, juga Ayah membawa tugas dari Kaisar untuk menyampaikan selamat kepada Kerajaan Bhutan, juga untuk menyatakan keampunan Kaisar terhadap Puteri Milana. Selain itu pula... juga Ayah akan meminangmu secara resmi... marilah, sayang, mari kita kembali ke istana Bhutan...”
Tiba-tiba Ceng Ceng melepaskan dirinya dari rangkulan lengan kanan kekasihnya, dan sambil tersenyum di antara air matanya, dengan kedua pipi merah, dia menggeleng. “Tidak... aku tidak mau kembali...” Dan dia pun membalikkan tubuhnya dan lari.
“Ehh, Ceng Ceng...!” Kok Cu mengejar dan kalau saja dia mau tentu dengan mudah dia dapat menyusul larinya gadis itu. Akan tetapi melihat kekasihnya itu lari sambil tersenyum, dia sengaja mengejar dari belakang dan berteriak, “Kenapa kau tidak mau?”
“Aku malu...!” Ceng Ceng berlari terus, memasuki sebuah hutan kecil.
Akhirnya Ceng Ceng memperlambat larinya dan membiarkan dirinya disusul, ditangkap dan dipeluk di bawah sebatang pohon besar. Dia menyerah dan menyambut ketika pemuda itu kembali menciuminya sampai keduanya gelagapan kehabisan napas. Akhirnya mereka duduk di bawah pohon, di atas rumput tebal dan hijau.
“Ceng-moi, kenapa kau malu?”
“Aku tidak ingin kembali ke sana, tidak ingin... sementara ini menemui orang-orang lain, aku khawatir kebahagiaanku akan terganggu. Aku ingin berdua saja denganmu, Koko, kalau bisa, berdua saja di dunia ini, tidak akan saling terpisah lagi... Koko, ah, Koko... aku masih belum percaya... apakah aku tidak sedang mimpi...?”
“Ceng-moi, kau kekasihku, kau pujaan hatiku, kau isteriku... apakah ini mimpi?” Dia mencium dan menggigit leher Ceng Ceng sampai dara itu terpekik halus. “Aku sendiri pun hampir tidak percaya bahwa engkau dapat mengampuni aku, apa lagi mencintaku! Aku selalu merasa ngeri untuk menghadapi pertemuan ini... tidak ada kengerian yang lebih hebat dari pada melihat engkau membenci aku... bayangkan saja betapa sengsara hatiku sebagai Topeng Setan ketika engkau menyatakan betapa hebatnya kebencianmu kepada Kok Cu...”
Sambil menyandarkan kepalanya di atas dada yang bidang itu, dan memainkan jari-jari tangan kanan Kok Cu yang dia tarik ke atas dadanya, Ceng Ceng berkata, suaranya manja. “Siapa sih yang membenci Kok Cu? Aku membencinya karena dia... menghilang begitu saja setelah peristiwa itu...! Aku benci karena dia tidak muncul lagi, padahal dia kuharap-harapkan... padahal hatiku sudah jatuh cinta begitu aku melihat dia di dalam kerangkeng itu...!”
“Tapi kau... kau mencinta Topeng Setan!” Kok Cu menggoda.
Ceng Ceng menarik lengan baju kiri yang kosong itu dan mencium lengan baju itu. “Mengapa tidak? Topeng Setan telah mengobankan lengannya, bahkan beberapa kali hampir berkorban nyawa untukku. Aku mencinta Topeng Setan karena budinya, tanpa mempedulikan bagaimana macamnya wajah di balik topeng, tanpa mempedulikan usianya, akan tetapi aku mencinta Kok Cu karena pribadinya, karena tatapan sinar matanya, karena... karena memang aku cinta dan sebabnya aku tidak tahu!”
“Hemm..., kalau begitu engkau mencinta dua orang! Hayo, katakan, siapa yang lebih kau cinta, Kok Cu atau Topeng Setan?” pemuda itu menuntut, pura-pura cemberut.
Ceng Ceng membalikkan tubuhnya, tertawa geli. “Kau cemburu? Hi-hik, lucunya! Kau cemburu kepada siapa?”
Dengan muka dibuat seperti marah Kok Cu berkata, “Tentu saja kepada Topeng Setan! Hayo katakan, kau lebih mencinta Kok Cu atau Topeng Setan?”
“Ya ampun... tentu saja aku lebih mencinta Kok Cu!”
Tiba-tiba Kok Cu mengeluarkan sebuah topeng dan sekali bergerak, topeng itu telah dipakai di mukanya dan berubahlah ia menjadi Topeng Setan, suaranya pun agak berubah karena terhalang topeng. “Bagus, Ceng Ceng...! Jadi cintamu kepadaku palsu, ya? Jadi kau lebih cinta kepada pemuda laknat itu dari pada kepadaku?”
Sambil menahan gelinya, Ceng Ceng pun berkata, “Siapa bilang, Paman? Aku cinta padamu, Paman Topeng Setan!”
Kok Cu membuang topengnya dan sambil memegang dagu yang runcing itu, dijepit antara telunjuk dan ibu jarinya, mengangkat muka Ceng Ceng menengadah, dia lalu menghardik, “Perempuan tamak! Sebetulnya kau lebih mencinta yang mana?”
“Aku cinta keduanya, dan cintaku itu kini menjadi satu, tiada bandingannya lagi, dan... ehmmm...” Ceng Ceng tidak dapat melanjutkan kata-katanya lagi karena mulutnya telah ditutup oleh sepasang bibir yang seolah-olah tidak akan ada puas-puasnya itu. Dia memejamkan matanya, menyambut dengan hati terbuka dan penuh penyerahan.
Angin semilir di atas mereka, membuat daun-daun pohon berkeresekan saling sentuh seperti saling berbisik membicarakan pertemuan asyik-masyuk penuh kemesraan di bawah pohon besar itu. Bagi Ceng Ceng dan Kok Cu, waktu dan segala sesuatu lenyap, bahkan diri pribadi juga lenyap, yang ada hanyalah kebahagiaan dan keindahan. Hidup adalah bahagia, hidup adalah indah.
Hanya sayang sekali, hanya sewaktu-waktu saja, hanya selewat saja, dalam keadaan seperti yang dialami oleh Ceng Ceng dan Kok Cu, kita mengenal kebahagiaan dan keindahan itu. Selebihnya, waktu dalam hidup kita penuh dengan pertentangan, penuh dengan kebencian, iri hati, angkara murka yang kesemuanya itu hanya mendatangkan kesengsaraan belaka.
Adakah yang lebih indah dari pada cinta? Sayang, betapa cinta oleh kita telah dipecah-belah, ditafsirkan menurut kecondongan hati yang menyenangkan sehingga timbul bermacam pendapat dan kesimpulan. Cinta bukanlah sex semata, bukanlah kewajiban semata, bukanlah pengorbanan semata, bukanlah pemberian atau permintaan semata.
Kesemuanya itu terdapat dalam cinta dan cinta mencakup segala karena cinta hanya terisi keindahan. Cinta tidak mengenal perbedaan suku, tidak mengenal perbedaan ras, tidak mengenal perbedaan bangsa, tidak mengenal perbedaan usia, tidak mengenal kaya atau miskin, pintar atau bodoh, tidak mengenal tingkat tinggi atau rendah. Cinta tak mengenal kebencian, tak mengenal permusuhan, tidak mementingkan diri pribadi. Cinta adalah kebahagiaan. Tanpa cinta matahari akan kehilangan sinarnya, bunga kehilangan keharumannya, dan manusia kehilangan kemanusiaannya.
Oleh karena itu, segala macam gerak yang kita perbuatan tanpa di dasar cinta kasih adalah palsu belaka. Ada pun yang kita lakukan di dunia ini barulah benar dan suci apabila didasari oleh cinta kasih di dalam hati sanubari kita.
“Bressss...!”
Tambolon memekik kaget dan kesakitan, pedang Ban Tok Kiam terlempar jauh dan dia terdorong sampai bergulingan. Kiranya Tek Hoat yang sengaja menjatuhkan diri itu telah menggunakan kekuatan Inti Bumi yang paling ampuh, yang diambilnya dari tenaga bumi ketika dia rebah, dan kakinya telah menyerang dengan kekuatan luar biasa, yang kiri menendang pergelangan tangan lawan sehingga pedang Ban Tok Kiam terlempar, kaki kanan menendang ke arah dada dan biar pun sudah ditangkis oleh tangan kiri Tambolon, tetap saja tubuh raja yang tinggi besar seperti raksasa itu terlempar dan bergulingan.
Tek Hoat sudah meloncat dan mengejar. Tambolon mengeluarkan senjata jala yang ketika digerakkan berubah seperti uap, akan tetapi Tek Hoat yang sudah mengenal senjata ini tidak menjadi gentar. Bahkan dengan sengaja dia memapaki jala itu dengan pedangnya. Tambolon menjadi girang karena jalanya berhasil menangkap dan membelit pedang.
Dia menyangka bahwa seperti biasa, tentu pemuda itu akan berusaha menarik kembali pedangnya. Akan tetapi Tek Hoat memang sengaja membiarkan pedangnya terampas dan secepat kilat, dia melepaskan gagang pedang dan menggunakan kedua tangannya untuk menyerang dengan pukulan tangan terbuka yang mengandung tenaga Inti Bumi, yang kiri ke arah pusar sedangkan yang kanan ke arah pelipis.
Tambolon terkejut, berusaha menangkis dan memang berhasil menangkis pukulan ke pusarnya, akan tetapi tangan kanan Tek Hoat sudah menyambar pelipisnya.
“Dessss...!”
Tambolon terpelanting dan roboh dengan mata mendelik, tubuhnya kaku dan dia tewas seketika.
Panglima Jayin dan para pembantunya segera bersorak. Panglima ini cepat menyambar pedang, memenggal kepala Tambolon yang dipasangnya di atas tombak dan diangkat tinggi-tinggi ke atas agar kelihatan oleh semua orang dan untuk melenyapkan semangat tentara musuh.
“Tek Hoat, kau bantulah kami!” Puteri Milana berseru.
Tek Hoat memandang dengan terheran-heran melihat betapa Puteri Milana yang dia tahu amat lihai itu dan Ceng Ceng belum juga mampu merobohkan Si Petani Maut dan Si Siucai Maut. Dia memekik keras dan dengan tangan kosong dia menerjang Si Petani Maut Liauw Kui yang memang sudah jeri sekali karena dia bukan tidak tahu betapa Puteri Milana mempermainkannya, menyambut terjangan Tek Hoat dengan pikulannya.
Namun, dengan mudah Tek Hoat menangkap batang pikulan itu. Dengan pengerahan tenaga dia memaksa batang pikulan itu membalik dan robohlah Si Petani Maut, batang pikulan memasuki perutnya menembus ke punggung.
Tek Hoat yang sudah beringas seperti harimau yang haus darah itu lalu menubruk ke arah Siucai Maut sambil berseru, “Ceng Ceng minggirlah!”
Yu Ci Pok menyambut dengan totokan dua senjata siang-koan-pit, akan tetapi Tek Hoat yang sudah melindungi tubuhnya dengan kekuatan tenaga sakti Inti Bumi dan juga menghentikan jalan darah di bagian yang tertotok, menerima dua totokan itu dan membarengi dengan gerakan jari tangannya dipergunakan seperti sebatang pedang menusuk ke depan.
“Craattt!” Jari-jari tangan kanannya memasuki dada Yu Ci Pok seperti sebatang pedang dan robohlah pengawal kedua dari Tambolon ini, berkelojotan dan tewas.
Puteri Milana dan Ceng Ceng bertepuk tangan memuji, kemudian mereka bertiga terus mengamuk sehingga pihak musuh makin kacau dan akhirnya larilah sisa pasukan dari suku-suku bangsa liar itu, apa lagi setelah mereka semua mendengar bahwa Raja Tambolon telah tewas.

Berakhirlah perang itu dengan kemenangan gemilang di pihak Bhutan. Panglima Jayin mengarak Tek Hoat sebagai seorang pahlawan gagah perkasa karena dia sendiri telah menyaksikan betapa pemuda yang gagah perkasa ini sudah berhasil membunuh Tambolon yang demikian lihainya, berarti bahwa pemuda ini memang telah membuat jasa besar sekali dan patut diperlakukan sebagai seorang pahlawan yang dengan setia telah membela Kerajaan Bhutan.
Gak Bun Beng yang telah bertemu dengan Pendekar Super Sakti, cepat berlutut di medan perang itu, memberi hormat dengan hati terharu karena dia tadinya sudah tidak mengira akan dapat bertemu dengan pendekar sakti yang dianggap sebagai gurunya ini.
Sejenak Pendekar Super Sakti juga menunduk dan memandang, lalu mengangguk-angguk dan bertanya, “Bun Beng, aku sudah mendengar bahwa Kerajaan Bhutan dibantu oleh engkau dan Milana. Di mana sekarang dia?”
“Sumoi Milana sedang memimpin pasukan untuk membasmi barisan pemberontak, Suhu. Bagaimana keadaan Suhu dan Subo di Pulau Es? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat.”
“Kami baik-baik saja, Bun Beng. Aku meninggalkan Pulau Es untuk pergi menyusul dan mencari dua orang sute mu. Kian Lee telah kujumpai dan sudah kusuruh pulang, akan tetapi Kian Bu masih kucari-cari. Apakah engkau melihat dia?”
Bun Beng menggeleng kepala. “Teecu pernah bersama dengan Sute Kian Bu ketika membantu pemerintah menghadapi para pemberontak yang dipimpin oleh dua orang Pangeran Liong, akan tetapi setelah itu, Sute Kian Bu pergi meninggalkan kota raja, kemudian terdengar lagi beritanya pada waktu dia menolong Puteri Syanti Dewi dari penghadangan Tambolon dan Durganini, lalu dia pergi lagi tanpa ada yang mengetahui ke mana, Suhu.”
“Hemmm, mari kita mencari Milana, mungkin dia tahu tentang adiknya itu.”
Bun Beng hanya mengangguk, tidak berani menceritakan betapa sejak dari kota raja, kekasihnya itu melakukan perjalanan bersama dia dan tentu saja pengetahuan Milana tentang Kian Bu tidak ada bedanya dengan apa yang telah dia ketahui. Bahkan dia masih merasa sungkan dan khawatir kalau-kalau pendekar sakti ini tidak akan senang hatinya mendengar akan keputusan mereka berdua untuk hidup bersama setelah Milana menjadi janda. Tentu saja orang tua sakti ini tidak tahu bahwa puterinya itu sebetulnya telah menjadi janda yang masih perawan!
Ketika mereka tiba di tempat pertempuran di mana Milana yang dibantu oleh Ceng Ceng dan Tek Hoat mengamuk, pertempuran telah selesai dan musuh telah terbasmi, yang melarikan diri dikejar oleh pasukan-pasukan Bhutan.
“Ayah...!” Milana cepat lari menyambut Pendekar Super Sakti dan di lain saat dia telah memeluk orang tua itu. Air mata puteri yang perkasa ini membasahi baju di dada ayahnya.
Pendekar Super Sakti mengelus rambut puterinya penuh kasih sayang. “Milana..., mana suamimu?”
Mendengar pertanyaan yang seolah-olah merupakan sebatang pedang yang langsung menikam ulu hatinya, Milana mengguguk tangisnya. Akhirnya dapat juga dia menjawab lirih, “...dia... dia telah tewas...”
Pendekar Super Sakti Suma Han adalah seorang manusia yang sudah dapat mengatasi segala perasaan, maka dia biasa saja mendengar berita hebat ini, hanya bertanya, “Bagaimana terjadinya hal itu?”
“Ayah, marilah kita memasuki kota raja dan bicara di sana dengan jelas.”
Pada saat itu, Raja Bhutan sendiri keluar menyambut dan dengan penuh kehormatan semua tamu agung yang sudah berjasa membantu Bhutan, terutama Tek Hoat, diarak masuk ke kota raja. Pendekar Siluman tidak menolak karena dia ingin mendengar cerita Milana tentang Kian Bu dan tentang Han Wi Kong, mantunya yang dikabarkan tewas itu.
Semua orang di kota raja menyambut para tamu agung, terutama sekali mereka menyanjung-nyanjung Puteri Milana dan Tek Hoat. Bahkan Tek Hoat sekaligus telah dikenal oleh mereka sebagai calon mantu raja!
Istana telah cepat sekali mempersiapkan penyambutan yang dipimpin sendiri oleh Puteri Syanti Dewi sehingga ketika rombongan pemenang ini memasuki kota raja dan tiba di depan istana, tempat ini telah dihias dengan meriah dan penari-penari serta musik menyambut mereka.
Pertemuan yang amat menggembirakan, semua orang tersenyum dan tertawa, semua wajah berseri-seri dan semua mata bersinar-sinar. Akan tetapi, suasana menjadi sangat mengharukan ketika tanpa disangka-sangkanya Puteri Syanti Dewi melihat Ceng Ceng di antara rombongan itu. Puteri ini terbelalak seperti mimpi saja dia melihat adik angkatnya, kemudian kedua orang dara cantik itu menjerit dan saling menubruk.
“Candra...!”
“Enci Syanti...!”
Mereka berangkulan dan menangis, saling berciuman karena sejak berpisah di tengah mala petaka ketika perahu mereka terguling, baru satu kali inilah mereka dapat saling bertemu kembali dan pertemuan ini terjadi di Bhutan! Sungguh merupakan hal yang aneh dan tidak tersangka-sangka oleh Syanti Dewi. Betapa hebat pengalaman mereka semenjak saling berpisah. Dan betapa cepatnya waktu berlalu karena begitu saling bertemu dan berpelukan, mereka merasa seolah-olah baru kemarin saja mereka saling berpisah.
Saling bergandeng tangan karena tidak sempat bicara di depan banyak orang, Syanti Dewi dan Ceng Ceng bersama semua rombongan itu memasuki istana di mana Raja Bhutan mengadakan penyambutan dengan pesta untuk merayakan kemenangan yang gemilang itu.
Rakyat dan para prajurit semua juga berpesta pora merayakan kemenangan besar itu. Suasana Kerajaan Bhutan gembira bukan main, sungguh pun harus diakui bahwa banyak pula yang menangis dan dilanda kedukaan hebat karena kematian suami, anak atau ayah yang menjadi prajurit Bhutan dan gugur dalam perang itu. Akan tetapi suara tangis mereka tenggelam dan hanyut oleh arus kegembiraan dari kota raja yang merayakan kemenangan.
Demikianlah adanya perang dan akibat-akibatnya! Di mana pun di bagian dunia ini, dan di jaman apa pun! Para korban perang yang membantu terlaksananya kemenangan, terlupa oleh yang merayakan kemenangan, oleh yang mengecap keuntungan dalam kemenangan perang.
Kalau pun para korban itu diingat oleh mereka, hal ini hanya sekilas saja, sekedar hiburan bagi keluarga si korban, atau lebih tepat, sebagai penonjolan dari yang merayakan kemenangan bahwa mereka itu tidak melupakan para korban, sungguh pun yang dikatakan tidak lupa itu hanya untuk satu kali setahun, dan itu pun hanya beberapa menit saja, lalu tidak dipedulikan lagi sama sekali sampai saatnya diperingati lagi!
Perang merupakan bukti betapa busuknya si aku mementingkan diri pribadi, secara keji mempergunakan manusia-manusia lain, kalau perlu mengorbankan laksaan nyawa manusia lain, demi untuk mencapai cita-cita yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah merupakan pengejaran sesuatu yang menguntungkan diri pribadi lahir mau pun batin. Perang merupakan bukti pula betapa bodohnya manusia, dipermainkan oleh slogan-slogan kosong, seperti sekelompok ikan memperebutkan umpan tidak tahu bahwa di dalam umpan tersembunyi maut!
Di dalam kesempatan berpesta-pora ini, Pendekar Super Sakti mendengar semua penuturan Milana tentang Suma Kian Lee dan Suma Kian Bu. Tanpa menyembunyikan sesuatu, Milana menuturkan tentang kepatahan hati dua orang pemuda Pulau Es itu.
“Aku kasihan sekali kepada mereka, Ayah. Kian Lee jatuh cinta kepada Ceng Ceng, dan ternyata kemudian bahwa Ceng Ceng adalah keponakan sendiri karena gadis itu adalah putera Wan Keng In dan Lu Kim Bwee.”
Pendekar Super Sakti Suma Han memandang ke arah Ceng Ceng yang sedang duduk menyendiri dengan wajah muram. Dia teringat akan pertemuannya dengan gadis itu, mula-mula di rumah makan ketika dia dan isterinya Lulu tiba di tempat itu dalam usaha mereka mencari putera mereka. Kiranya gadis yang kemudian melakukan perjalanan bersamanya itu adalah puteri Wan Keng In! Dengan demikian, Lulu telah menolong cucunya sendiri di dalam rumah makan itu! Lalu dia teringat akan Topeng Setan dan Pendekar Super Sakti menghela napas panjang. Ternyata buah perbuatan Wan Keng In masih terasa sampai sekarang!
“Tidak perlu dikasihani, Milana. Kalau dia melihat kenyataan bahwa gadis itu adalah keponakan sendiri, mengapa dia harus patah hati? Dan bagaimana dengan Kian Bu?”
“Bu-te lebih parah lagi, Ayah. Dia jatuh hati kepada Syanti Dewi, akan tetapi agaknya Puteri Bhutan itu tidak membalas cintanya karena puteri itu agaknya jatuh hati kepada Tek Hoat.” Puteri Milana mengerling dan Suma Han juga melihat betapa mesra puteri itu di dalam pesta melayani Tek Hoat yang duduk di samping Raja Bhutan dan permaisuri!
“Hemm, cinta yang menuntut balasan, kalau tidak dibalas lalu patah hati bukanlah cinta namanya...” Suma Han berkata lirih seperti kepada diri sendiri. “Kepatahan hati itu adalah salahnya sendiri, timbul dari iba diri. Di mana kiranya dia sekarang?”
“Aku tidak tahu, Ayah.”
“Biarlah, aku akan mencarinya. Dan engkau sendiri, Milana. Bagaimana engkau bisa berada di sini tanpa suamimu? Dan apa pula artinya ucapanmu bahwa suamimu telah tewas?”
Puteri Milana menekan perasaannya agar jangan sampai dia menangis di dalam pesta itu. Kemudian, dengan hati-hati dan lirih berceritalah dia tentang keadaannya dengan Han Wi Kong, betapa mereka itu menikah tanpa cinta kasih di pihaknya, hanya untuk memenuhi kehendak Kaisar, dan betapa Han Wi Kong telah bersikap jantan dan tidak memaksa dia memenuhi kewajiban sebagai isteri.
Kemudian tentang perbuatan Han Wi Kong yang membunuh Pangeran Liong Bin Ong sebagai tindakan ‘bunuh diri’ untuk memberi kesempatan kepadanya berkumpul kembali dengan orang yang dicintanya, yaitu Gak Bun Beng, dan tentang surat-surat Han Wi Kong yang sengaja ditinggalkan untuk dia dan Bun Beng.
Mendengarkan semua ini, Suma Han memejamkan kedua matanya dengan alis berkerut. Milana sudah siap untuk mendengar teguran dan kemarahan ayahnya, akan tetapi setelah Suma Han membuka kembali matanya, pendekar bijaksana itu berkata perlahan, “Nasib manusia berada di dalam tangannya sendiri, tergantung dari sepak-terjangnya sendiri dalam kehidupan.
Semua pengalamanmu itu hanya menjadi bukti bahwa apa pun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, Milana, haruslah kita lakukan dengan cinta kasih di dalam hati. Tanpa cinta kasih, maka semua perbuatan itu hanya akan menimbulkan pertentangan dan kedukaan belaka, seperti perbuatanmu menikah dengan Han Wi Kong, dan perbuatanmu bersama Bun Beng yang saling berpisah mematahkan ikatan perasaan antara kalian. Jadi sekarang, engkau dan Bun Beng...”
Milana menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. “Kami telah bersepakat untuk menghadap ke Pulau Es mohon restu dan ijin dari Ayah dan Ibu, dan karena saya telah menjadi buronan di kota raja, maka kami berdua akan pergi mengasingkan diri, entah ke mana, saya hanya akan menurut dan ikut dengan Gak-suheng...”
Suma Han mengangguk-angguk. “Memang sebaiknya jika kalian lebih dulu menghadap ibumu. Nah, biarlah sekarang juga aku pergi, Milana. Aku akan mencari Suma Kian Bu.” Sebelum Puteri Milana menjawab, tampak tubuh ayahnya berkelebat dan lenyaplah pendekar itu dari tempat itu, seolah-olah menghilang begitu saja di tengah-tengah orang banyak yang sedang berpesta.
Milana maklum akan sifat ayahnya yang aneh, maka dia cepat menghadap Raja Bhutan dan mintakan maaf bahwa ayahnya telah pergi tanpa pamit karena ayahnya mempunyai urusan pribadi yang penting. Semua orang terkejut dan kagum, akan tetapi hanya mengangguk-angguk dan merasa seram melihat ada orang dapat lenyap begitu saja di tengah-tengah mereka, seperti siluman!
Tidak lama kemudian, nampak Puteri Milana dan Gak Bun Beng sudah duduk berdua menghadapi meja dan bercakap-cakap dengan mesra, berbisik-bisik karena puteri itu menceritakan kepada kekasihnya tentang reaksi ayahnya ketika tadi mendengar pengakuannya tentang mereka. Legalah hati Bun Beng karena tadi pun, dari meja lain, dia melihat berkelebatnya gurunya itu lenyap, membuat dia khawatir sekali dan menduga bahwa pendekar itu pergi dengan marah. Kiranya tidak demikian, maka tentu saja hatinya merasa lega.
Semua orang di dalam pesta itu bergembira-ria, tenggelam dalam kebahagiaan masing-masing sehingga tentu saja melupakan orang lain. Tek Hoat yang dihujani sanjungan dan kini dilayani dengan mesra dan dengan terbuka oleh Syanti Dewi, di depan Raja dan Permaisuri Bhutan yang memandang sambil tersenyum penuh arti, tentu saja merasa bahagia sekali. Demikian pula Syanti Dewi yang melihat betapa pria yang dicinta dan dipilihnya itu kini telah kembali dalam keadaan selamat, sebagai seorang pahlawan pula, tentu saja menjadi sangat gembira sehingga dia pun lupa akan keadaan orang lain.
Semua orang bergembira-ria, kecuali Ceng Ceng. Sebaliknya, dara ini menjadi sedih sekali karena kebahagiaan orang-orang itu mengingatkan dia akan nasib dirinya. Teringat akan Topeng Setan, satu-satunya manusia yang dicinta, dan teringat akan Kok Cu, satu-satunya manusia yang dibencinya, ternyata kedua orang itu adalah sama, dan kini telah mati!
Padahal, dua orang itulah yang membuat dia tadinya masih ada gairah untuk hidup di dunia yang penuh duka ini. Topeng Setan menghiburnya dan kebaikan hati Topeng Setan membuat dia jatuh cinta kepada orang yang selalu menyembunyikan wajahnya di balik topeng yang amat buruk itu. Dia jatuh cinta bukan karena wajahnya, melainkan karena kebaikan yang banyak dilimpahkan kepadanya oleh pendekar sakti itu sehingga kehadiran Topeng Setan di dalam jalan hidupnya itu menimbulkan gairah hidup yang baru.
Ada pun Kok Cu yang selama ini dimusuhinya dan dibencinya karena pemuda itu telah memperkosanya, merupakan pula suatu dorongan sehingga dia tidak ingin mati dulu sebelum dia dapat membalas dendamnya. Dengan cara yang amat berlainan, bahkan dengan berlawanan, dua nama itu telah membuat dia bersemangat untuk hidup.
Akan tetapi, seperti halilintar datangnya, terbukalah kenyataan bahwa yang amat dicintanya adalah orang yang amat dibencinya, sebaliknya pula yang amat dibencinya itu ternyata adalah orang yang dicintanya, dan kini keduanya, yang sesungguhnya satu orang juga, telah mati! Apa lagi yang menahannya untuk hidup di dunia penuh duka kecewa ini? Lebih baik mati saja dan rasanya mati akan jauh lebih menyenangkan dari pada hidup!
Betapa banyaknya manusia di dunia ini hidup dalam duka dan kesengsaraan batin sehingga dunia ini dianggapnya sebagai tempat yang amat buruk, sebagai neraka yang amat menyiksa. Seperti juga Ceng Ceng, kita manusia selalu dirundung duka yang seribu satu macam sebabnya sehingga kita selalu haus akan kebahagiaan, selalu haus akan kesenangan dan selalu merasa bahwa di dunia ini, hanya kita sendirilah yang paling sengsara sedangkan orang-orang lain semua jauh lebih bahagia dari pada kita.
Benarkah demikian? Sesungguhnya tidaklah demikian kenyataannya. Selama kita memperhatikan keadaan orang lain, membanding-bandingkan dengan keadaan kita, akan timbul rasa kecewa dan iri, memupuk rasa iba diri. Dan kita lupa, seperti juga Ceng Ceng, bahwa justru kekecewaan dan kedukaan itu datang karena keinginan kita mencari yang lebih baik dan lebih menyenangkan itulah! Kita selalu menolak apa yang ada, selalu menolak kenyataan yang terjadi, membutakan mata terhadap kenyataan yang tidak menyenangkan dan mengejar-ngejar bayangan yang dianggap akan dapat menyenangkan.
Padahal, kenyataan seperti apa adanya tidak mengandung suka mau pun duka. Kenyataan apa adanya adalah kebenaran! Ada pun senang atau susah bukanlah bagian dari kenyataan itu, melainkan merupakan permainan dan pikiran kita sendiri, yang selalu menonjolkan dirinya pribadi, yang selalu akan senang kalau diuntungkan lahir maupun batin, dan selalu susah, kalau dirugikan lahir mau pun batin.
Pikiranlah biang keladi susah dan senang. Pikiranlah sumber segala duka dan sengsara! Dan ini merupakan suatu kenyataan, nampak dengan jelas sekali asal kita mau membuka mata dan memandang kenyataan tanpa dipengaruhi oleh segala macam pendapat, prasangka dan kesimpulan yang juga merupakan permainan dari pikiran pula.
Ceng Ceng tenggelam ke dalam lamunan yang menyedihkan. Namun dia hendak merahasiakan semua ini, demi kebahagiaan Syanti Dewi. Dia tidak ingin mengganggu kebahagiaan kakak angkatnya itu, maka ketika Syanti Dewi teringat kepadanya dan mendatanginya, lalu menarik tangannya diajak duduk bersama satu meja dengan keluarga raja, juga bersama Puteri Milana dan Gak Bun Beng yang sudah diminta pula oleh Syanti Dewi, Ceng Ceng tidak menolak dan berusaha menyelimuti kedukaan hatinya dengan senyum manis.
Ketika Raja mengumumkan pertunangan Tek Hoat yang masih mengaku she Ang itu dengan Puteri Syanti Dewi, semua orang menyambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai, juga Ceng Ceng segera menghampiri kakak angkatnya, dipeluknya dan diciuminya Syanti Dewi sambil mengucapkan selamat. Kedua orang wanita cantik ini mengusap air mata keharuan dan Ceng Ceng lalu menghampiri Tek Hoat sambil menjura dan berkata, “Kionghi (selamat), semoga engkau akan menjadi suami kakak angkatku yang baik.”
Tek Hoat tersenyum, menyatakan terima kasihnya dan berkata, “Ceng Ceng, kita adalah saudara seayah, maka kita semua ternyata bukanlah orang-orang lain, bukan? Harap kau maafkan segala kesalahanku yang lalu terhadapmu.”
Ceng Ceng tidak menjawab, hanya di dalam hatinya dia masih mengkhawatirkan apakah kakak angkatnya akan bahagia kelak menjadi isteri Tek Hoat yang dikenalnya sebagai seorang yang licik dan curang, dan jahat. Betapa pun juga, dia tak mengatakan apa-apa karena dia segera teringat akan laki-laki yang tak pernah dapat dilupakannya, biar pun telah mati itu. Topeng Setan atau Kok Cu itu, seperti juga Tek Hoat, baik atau jahatkah?
Kalau dia teringat akan Kok Cu, pemuda yang telah memperkosanya di dalam goa, maka jelas bahwa pemuda itu amat jahat, bahkan merupakan orang yang telah menghancurkan hidupnya, menghancurkan harapannya. Sebaliknya, kalau dia teringat akan Topeng Setan, jelaslah bahwa orang itu amat baik, terlalu baik malah, telah melimpahkan budi kebaikan kepadanya, telah mengorbankan lengannya, bahkan beberapa kali hampir mengorbankan nyawa untuknya. Jadi baikkah orang itu? Atau jahatkah?
Ceng Ceng termenung. Baik atau jahat ternyata tergantung dari pada penilaian kita sendiri, dan penilaian kita pun didasarkan atas kepentingan diri pribadi. Buktinya, kalau dia mengingat Kok Cu yang telah merugikan dia, maka otomatis dia menganggapnya jahat sekali. Dan kalau dia mengingat Topeng Setan yang telah menguntungkan dia, maka otomatis dia menganggapnya baik sekali. Padahal keduanya itu adalah orang yang sama! Tentu demikian pula dengan Tek Hoat. Siapa pun orangnya yang merasa dirugikan oleh Tek Hoat, tentu akan menganggapnya jahat, sebaliknya Syanti Dewi yang tentu telah menerima budi kebaikan dari Tek Hoat seperti dia menerimanya dari Topeng Setan, tentu saja menganggap Tek Hoat sebaik-baiknya manusia!
Ceng Ceng menghela napas panjang. Kenyataan yang membuka matanya lahir batin ini membuat dia menjadi muak akan kepalsuan manusia, akan kepalsuan dirinya sendiri. Setiap orang selalu menginginkan yang menguntungkan dan menyenangkan bagi dirinya sendiri saja, dan menolak yang merugikan atau tidak menyenangkan, maka timbullah suka dan tidak suka, timbullah cinta dan benci, timbullah puas, dan kecewa dan kesemuanya itu tentu saja mendatangkan pertentangan dan kesengsaraan.
Syanti Dewi yang sedang tenggelam dalam kegembiraan itu kini mulai memperhatikan Ceng Ceng. Biar pun adik angkatnya itu kelihatan tersenyum-senyum dan ikut pula berpesta, namun wajahnya pucat dan matanya muram, jelas kelihatan oleh Syanti Dewi betapa kegembiraan Ceng Ceng hanyalah pura-pura belaka untuk menyembunyikan kedukaan yang amat besar.
Perang hebat terjadi di dalam batin Ceng Ceng. Di satu pihak dia menderita pukulan batin yang membuatnya amat berduka teringat kepada Topeng Setan, ditambah menyaksikan kemesraan antara Tek Hoat dan Syanti Dewi, dan pada lahirnya dia memaksa diri untuk ikut bergembira. Arak yang manis diminumnya terasa pahit, semua hidangan yang lezat terasa seperti racun di lidahnya. Dia berusaha menahan-nahan diri, akan tetapi makin diingat makin hebatlah tekanan yang menghimpit batinnya. Akhirnya dia mengeluh dan roboh terguling dari tempat duduknya.
“Adik Candra...!” Syanti Dewi menjerit.
“Ceng Ceng, kau kenapa...?” Tek Hoat juga berseru dan cepat pemuda ini melompat dan memondong tubuh Ceng Ceng yang pingsan, dibawanya masuk bersama Syanti Dewi dan diikuti pula oleh Puteri Milana dan Gak Bun Beng.
Puteri Milana dan Gak Bun Beng cepat memeriksa keadaan Ceng Ceng, dan keduanya saling pandang, lalu Puteri Milana berkata kepada Syanti Dewi, “Biarkan dia beristirahat. Dia mengalami tekanan batin...” lalu dia bersama Bun Beng keluar dari dalam kamar itu, diikuti pula oleh Tek Hoat yang membiarkan Syanti Dewi sendiri menemani Ceng Ceng yang masih rebah pingsan.
Sri Baginda sendiri juga berkenan menengok, dan Sri Baginda lalu bertanya kepada calon mantunya apa yang terjadi dengan diri Ceng Ceng, adik angkat puterinya itu. Dengan halus Tek Hoat melaporkan bahwa Ceng Ceng kelelahan dan perlu beristirahat. Sedangkan Milana sendiri berkata lirih kepada Bun Beng, “Heran sekali, apa yang menyebabkan dia begltu tertekan batinnya?”
“Dan aku pun heran ke mana perginya Topeng Setan yang dulu selalu menemaninya? Sayang Suhu tidak bercerita apa-apa sehingga kita tidak tahu bagaimana Ceng Ceng sampai berpisah dari Topeng Setan dan tahu-tahu datang bersama Suhu.”
Mereka menduga-duga, akan tetapi tidak dapat mengerti apa sebabnya dara itu sampai menderita pukulan batin demikian hebatnya, yang dapat mereka ketahui dari pemeriksaan mereka tadi. Untuk menghormati perayaan kemenangan itu, Milana, Bun Beng, dan Tek Hoat sendiri melanjutkan kehadiran mereka dalam perayaan sungguh pun hati mereka tidak dapat melupakan keadaan Ceng Ceng. Hanya Syanti Dewi saja yang tidak muncul lagi karena puteri ini menjaga sendiri adik angkatnya dengan hati gelisah.
Malam itu pesta dilanjutkan dengan meriah. Beberapa kali secara bergantian, Tek Hoat, Milana, dan Bun Beng menengok keadaan Ceng Ceng yang masih saja rebah seperti tidur pulas dalam keadaan tidak sadar. Bun Beng menyalurkan tenaga sinkang yang kuat dan halus untuk membantu gadis dan memperkuat jantungnya, kemudian dia pun keluar sambil memesan kepada Syanti Dewi bahwa apa bila Ceng Ceng sadar, biarkan gadis itu menangis sepuasnya karena keadaan Ceng Ceng itu hanya akan terbebas dari bencana kalau gadis itu dapat menangis atau menyalurkan beban yang menekan batinnya dengan menceritakan kepada orang lain yang dipercayanya. Syanti Dewi mengangguk dengan air mata berlinang.
Dalam keadaan tidur atau setengah pingsan itu Ceng Ceng mengigau, tubuhnya mulai panas. Syanti Dewi memperhatikan dengan gelisah dan menjadi bingung melihat sikap Ceng Ceng dalam igauannya. Kadang-kadang gadis itu memaki-maki nama ‘Kok Cu’, dan kadang-kadang dia memanggil-manggil ‘Topeng Setan’ dengan mesranya.
Menjelang tengah malam, Ceng Ceng membuka mata dan tiba-tiba meloncat bangun sambil menjerit, “Kau telah mati...!” Akan tetapi karena tubuhnya lemah dan kepalanya pening, hampir saja dia terguling kalau tidak cepat-cepat dirangkul oleh Syanti Dewi.
“Candra... adikku... ingatlah, aku siapa...?” Syanti Dewi yang merangkul itu berbisik dengan suara parau dan air matanya mengalir di kedua pipinya.
Sejenak sepasang mata Ceng Ceng yang muram itu menatap wajah Syanti Dewi seperti yang tidak mengenalnya, tatapan pandang mata yang kosong seolah-olah di balik sinar mata muram itu tidak ada semangatnya lagi. Syanti Dewi merasa seperti ditusuk jantungnya melihat tatapan pandang mata ini.
“Candra Dewi... adikku... kau... kau kenapa...?” Dia merangkul lagi, menciumi pipi yang pucat seperti mayat itu.
Akhirnya Ceng Ceng sadar. “Enci Syanti...!”
Dia merintih dan menangislah Ceng Ceng dalam pelukan Syanti Dewi, menangis sesenggukan akhirnya mengguguk dan air matanya mengalir seperti air bah membobol bendungannya. Syanti Dewi juga menangis, akan tetapi menangis dengan hati lega karena dia teringat akan pesan Bun Beng bahwa tangis akan membebaskan Ceng Ceng dari ancaman bahaya. Maka dia merangkul dan membiarkan Ceng Ceng menangis sepuasnya. Setelah agak reda tangis adik angkatnya itu, dia lalu mengambil sapu tangannya dan menyusuti air mata Ceng Ceng dari pipinya, menyusuti muka yang pucat itu.
“Adikku... adikku yang baik, kenapa kau begini berduka? Ceritakanlah kepada enci-mu ini dan aku bersumpah demi langit dan bumi, aku akan membantumu dengan seluruh kekuasaanku untuk melenyapkan ganjalan hatimu, Candra.”
“Ohh, Enci Syanti...” Ceng Ceng kembali menyembunyikan mukanya di pundak puteri itu. Bagaimana dia akan dapat menceritakan persoalannya itu kepada orang lain?
“Ceritakanlah, Adikku...”
Ceng Ceng tak dapat menjawab, hanya menggelengkan kepala tanpa menghentikan tangisnya.
“Aihh, Candra. Kau kira aku ini siapa? Aku adalah kakakmu, tahukah kau? Lupakah engkau betapa kita bersama-sama meninggalkan Bhutan dan kemudian mengalami segala macam peristiwa hebat? Dan sekarang setelah kita bersama dapat pulang dan berkumpul lagi di sini, engkau menjadi begini. Lebih hebat lagi, agaknya engkau sudah tidak percaya lagi kepada kakakmu ini...”
“Enci Syanti...! Janganlah kau berkata begitu... jangan...” Ceng Ceng terisak, suaranya seperti orang merintih.
“Kalau begitu, kau ceritakanlah semua kedukaanmu itu padaku. Kita ini selain saudara angkat, juga senasib sependeritaan, kalau engkau bahagia, aku pun ikut gembira, kalau engkau sengsara, aku pun ikut berduka. Bagaimana mungkin aku akan dapat menikmati kebahagiaanku sekarang ini kalau melihat engkau sengsara, Adikku?”
Ceng Ceng memejamkan matanya. Memang tidak salah ucapan kakak angkatnya ini. Dahulu dia mempunyai kakeknya akan tetapi kini sudah tidak ada. Kemudian di dunia ini ada Topeng Setan yang dianggapnya satu-satunya orang yang paling baik dan dekat dengannya. Topeng Setan pun sudah tidak ada. Dan Syanti Dewi yang tadinya sudah terpisah dari dia dan disangkanya sudah tewas atau tertawan musuh, sekarang sudah kembali dan berkumpul dengan dia. Memang satu-satunya orang yang paling dekat dengan dia hanya Puteri Bhutan inilah.
Dia menarik napas panjang dan melepaskan rangkulannya. “Baiklah, Enci Syanti. Mari kita duduk dan dengarlah ceritaku.”
Dua orang wanita muda yang cantik jelita itu lalu duduk di atas pembaringan, saling berhadapan dan mulailah Ceng Ceng bercerita. Dia ingin menyingkat ceritanya yang amat panjang itu, hanya mengemukakan hal-hal yang membuat dia merana dan sengsara seperti yang diderita sekarang ini.
“Ketika kita saling terpisah karena perahu kita terguling...” Ceng Ceng berhenti karena teringat betapa peristiwa itu terjadi gara-gara Tek Hoat yang kini menjadi calon suami puteri itu!
Syanti Dewi agaknya dapat meraba perasaan hati adik angkatnya, maka dia tersenyum dan berbisik, “Lanjutkanlah...”
“Aku berjumpa dengan seorang pemuda yang tertawan musuh-musuhnya dan berada dalam sebuah kerangkeng. Karena kasihan kepadanya, aku melarikan dia dengan kerangkengnya, membawanya ke sebuah goa dan di situ aku membuka kerangkeng dan membebaskannya...” Ceng Ceng berhenti lagi. Seperti tampak di depan matanya semua peristiwa itu, betapa pemuda itu dengan berkeras minta agar supaya dia tidak membebaskannya! Agaknya pemuda itu tahu bahwa dia keracunan dan akan terjadi hal yang hebat kalau sampai dia dibebaskan dari dalam kerangkeng!
“Lalu bagaimana, Adikku?” Syanti Dewi mulai tertarik oleh cerita yang dipersingkat ini.
“Setelah aku membebaskan dia... lalu dia itu... dia lihai sekali, dia merobohkan aku dengan totokan...”
“Ahhh...!”
“Kemudian... kemudian... dia memperkosaku...!” Ceng Ceng menutupi mukanya dengan kedua tangannya seolah-olah tidak ingin melihat peristiwa yang kembali membayang di depan matanya.
“Ehhh...!” Syanti Dewi terbelalak, otomatis pandang matanya menjelahi tubuh adiknya. Kemudian dia bangkit berdiri di depan pembaringan, kedua tangannya dikepal dan sepasang matanya bernyala-nyala. “Dia... dia memperkosamu? Adikku, katakan siapa jahanam itu! Aku akan menyuruh Tek Hoat mencarinya sampai dapat dan aku tidak akan mau menikah dengan dia sebelum dia dapat menyeret jahanam itu di depan kakimu! Aku juga akan mohon bantuan Paman Gak Bun Beng! Hayo katakan, siapa jahanam itu!”
Ceng Ceng menurunkan kedua tangannya, memandang puteri yang marah-marah itu dengan muka pucat, kemudian dia memegang kedua tangan puteri itu dengan perasaan berterima kasih sekali. “Enci Syanti, ceritaku belum habis...”
Syanti Dewi duduk kembali di atas pembaringan. “Apakah bukan peristiwa terkutuk itu yang membuatmu berduka? Kalau karena sakit hati itu, biar aku akan mengerahkan segala kemampuanku untuk membantumu membekuk jahanam itu!”
Ceng Ceng menggeleng kepalanya dengan lemas, pandang matanya muram dan sayu, kemudian dia berkata, “Aku akan melanjutkan, dengarlah, Enci Syanti. Seperti dapat kau maklumi, aku menaruh dendam kepada orang itu dan selama ini tiada hentinya aku mencari-cari dia untuk membalas sakit hatiku. Dalam perantauanku ini, aku bertemu dengan seorang lain, yaitu Topeng Setan.”
“Hemm, aku juga sudah mendengar tentang dia, yang kabarnya selalu membantumu dan merupakan seorang manusia ajaib dan lihai sekali yang bersembunyi di balik topengnya.”
“Benar. Dia adalah seorang manusia yang amat baik kepadaku, Enci, telah berulang kali menyelamatkan nyawaku, bahkan dia... dia... telah berkorban dengan lengan kirinya menjadi buntung ketika menolongku. Aku berhutang nyawa kepadanya, berhutang budi dan sudah sepatutnya kalau dia kuanggap sebagai manusia yang paling mulia di dunia ini...”
“Tentu saja! Aku pun tadinya mengalami hal seperti engkau itu dan aku sampai kini selalu menganggap Paman Gak Bun Beng sebagai seorang manusia yang paling mulia di dunia ini, tentu saja sesudah orang tuaku dan... Tek Hoat.”
Ceng Ceng mengangguk-angguk. “Dan kemudian... belum lama ini..., aku mendapat kenyataan yang menghancurkan seluruh perasaanku, yang membuat aku hampir gila, sebuah kenyataan yang amat hebat, Enci Syanti...” dan Ceng Ceng tak dapat menahan air matanya lagi.
Syanti Dewi memegang kedua tangan adik angkatnya. “Kenyataan apakah, Candra? Cepat kau beritahukan kepadaku.”
“Kenyataan bahwa Topeng Setan, orang yang paling kumuliakan dan karenanya paling kucinta... ketika topengnya terbuka... ternyata... ternyata dia... dia... adalah... pemuda yang memperkosa aku dahulu...”
“Aihhhh...!” Syanti Dewi setengah menjerit dan kembali dia meloncat berdiri, mukanya menjadi pucat dan pandang matanya penuh rasa iba, lalu mulutnya komat-kamit seperti berdoa akan tetapi terdengar bisiknya. “...jadi kau... membenci dan sekaligus mencinta orang yang sama...? Dan dia itu... musuhmu dan sekaligus sahabatmu, pemerkosamu dan sekaligus penolongmu...? Aihhh, bagaimana ini...?”
Seperti dalam mimpi, suaranya lirih dan datar, terdengar Ceng Ceng berkata membela, “Akan tetapi... ketika dia memperkosaku... dia... dia dalam keadaan tidak sadar karena keracunan... dan dia sudah berusaha mencegah aku membuka kerangkengnya...”
Mendengar ini, Syanti Dewi mengangguk-angguk, kemudian merangkul adik angkatnya itu dan berkata dengan suara serius, “Dengarlah baik-baik, Candra. Sekarang jawablah aku. Engkau sekarang ini, setelah semua itu terjadi, setelah semua itu lewat dan lupakan semua itu, sekarang jawablah, apakah engkau sekarang ini membencinya ataukah mencintanya?”
Ceng Ceng tertunduk lesu dan sampai lama tidak menjawab.
Syanti Dewi mencium kedua pipinya. “Sadarlah, Adikku. Tak perlu kau membiarkan diri tenggelam dalam peristiwa yang lalu. Katakanlah kepadaku. Bencikah kau kepadanya? Ataukah engkau cinta kepadanya?”
Ceng Ceng menggeleng kepada. “Entahlah, Enci Syanti. Aku tidak tahu. Dia demikian baik kepadaku, mungkin tanpa dia aku sudah mati, dan tidak mungkin lagi bertemu denganmu. Dia mengorbankan segalanya untukku, bahkan lengannya putus sebelah karena aku... akan tetapi... dia... dia yang memperkosaku.”
Syanti Dewi memandang Ceng Ceng sambil tersenyum. Sampai lama dia menatap wajah yang menunduk itu, kemudian dia memegang kedua pundak adik angkatnya, lalu memegang dagu yang meruncing itu dan tersenyum lebarlah Puteri Bhutan itu. “Adikku yang manis, kau cantik sekali! Tahukah kau apa yang tampak olehku? Jelas terbayang di wajahmu, Adikku, dan aku tidak akan salah lihat bahwa engkau cinta kepadanya.”
“Ehhh...?” Ceng Ceng terkejut sekali dan memandang tajam kepada kakak angkatnya itu, akan tetapi dia menundukkan mukanya lagi dan wajahnya makin muram.
“Candra... adikku yang cantik, mengapa kau khawatir? Engkau terlalu memandang rendah kepada kakakmu ini. Apa kau kira aku akan diam saja setelah melihat kenyataan bahwa engkau mencinta pria itu? Jangan kau khawatir, biar kusuruh sekarang juga Tek Hoat, agar dia mencari dia sampai ketemu.”
Ceng Ceng menghela napas panjang, terdengar dia mengeluh. “Aihhh, Enci Syanti, sia-sia saja segala perhatianmu kepadaku, karena dia... dia sudah mati...” Dan air mata mengalir turun lagi dari kedua mata Ceng Ceng.
“Heiiii...?!” Kini Syanti Dewi yang memandang dengan mata terbelalak dan wajahnya pucat. Kemudian dia menubruk, merangkul Ceng Ceng dan sekarang puteri itulah yang menangis tersedu-sedu. Dan anehnya, melihat kakak angkatnya menangis begitu sedih, Ceng Ceng merasa terhibur hatinya, atau setidaknya dia melupakan kesedihannya sendiri, bahkan kini dia yang berusaha menghibur Syanti Dewi!
“Sudahlah, Enci Syanti, sudahlah..., ditangisi pun sia-sia...!”
Memang aneh sekali, akan tetapi telah menjadi kenyataan bahwa kedukaan seseorang akan berkurang, menjadi ringan, atau setidaknya terhibur melihat kedukaan orang lain! Kenyataan ini pahit sekali, membayangkan dengan jelas bahwa kedukaan timbul dari rasa iba kepada diri sendiri, maka rasa iba itu menjadi berkurang kalau melihat orang lain juga menderita, apa lagi kalau penderitaan orang lain itu lebih besar dari pada penderitaannya sendiri. Rasa iba diri ini adalah penonjolan dari pada si aku yang selalu ingin menguasai batin manusia maka terjadilah kesengsaraan dan kedukaan yang memenuhi kehidupan kita.
Perlu sekali untuk disadari benar-benar bahwa kesengsaraan dan kedukaan bersumber kepada pikiran kita sendiri, yang membentuk si aku, karena pikiran kita sendirilah yang menimbulkan pertentangan-pertentangan di dalam batin dengan selalu menginginkan hal-hal lain dari pada kenyataannya yang ada, selalu menginginkan yang dianggapnya menyenangkan sehingga apa yang ada, yaitu kenyataan setiap saat yang dihadapinya, selalu tidak diamatinya benar-benar dan dianggapnya tidak menyenangkan.
Semua ini adalah permainan pikiran kita sendiri setiap saat dan demikianlah pikiran kita menguasai kehidupan kita setiap hari! Mata kita baru akan terbuka, keindahan setiap saat yang terkandung dalam setiap peristiwa baru akan tampak apa bila pikiran atau si aku tidak mencampurinya! Cinta kasih yang murni dan suci, terhadap apa pun juga, baru ada apa bila pikiran atau si aku tidak memegang kendali!
“Adik Candra..., betapa hebat penderitaanmu. Sungguh aku berdosa besar kepadamu, Adikku, aku bergembira, berbahagia, bersenang-senang tanpa memikirkan bahwa kau sesungguhnya sedang menderita kedukaan hebat...”
“Sudahlah, Enci Syanti. Engkau tidak bersalah apa-apa. Engkau tidak mengetahuinya dan tidak perlu pula Enci berduka karena keadaanku. Lanjutkanlah kegembiraanmu, Enci, engkau berhak untuk hidup berbahagia. Setidaknya, mengingat bahwa engkau akan berjodoh dengan seorang yang masih seayah denganku, membuat aku bersyukur. Aku sendiri... ahhh, hidup tidak ada artinya lagi, aku... aku bermaksud... akan pergi lagi dari sini besok...”
“Ehhh... ke mana...?”
“Entahlah. Mungkin kembali ke bekas tempat tinggal Kakek, atau... entah ke mana aku sendiri belum bisa memastikan...”
“Jangan, Candra...! Setidaknya, kau tinggallah di sini sampai hari pernikahanku.”
Ceng Ceng menggelengkan kepalanya dan menghapus sisa air matanya. “Tidak, Enci. Kehadiranku yang penuh kepahitan hanya akan mengganggu kebahagiaanmu saja. Aku sudah mengambil keputusan untuk pergi besok, pagi-pagi dari sini. Kau tidak boleh dan tidak bisa menahanku, Enci Syanti...”
“Candra...!” Syanti Dewi merangkul dan kembali kedua orang kakak beradik yang dipermainkan nasib sehingga keadaan mereka kini seperti bumi dan langlt itu saling bertangis-tangisan.
Malam itu juga Syanti Dewi pergi menemui Tek Hoat yang dimintanya agar sebagai saudara seayah, suka membujuk Ceng Ceng. Tek Hoat terkejut sekali saat mendengar semua penuturan kekasihnya itu tentang Ceng Ceng dan Topeng Setan. Tak pernah disangka seujung rambut pun bahwa Topeng Setan adalah musuh besar yang selalu dicari-cari Ceng Ceng itu, dan baru sekarang dia tahu bahwa adiknya seayah itu, adik tirinya, telah menjadi korban perkosaan Topeng Setan sendiri yang kini kabarnya telah tewas! Tergopoh-gopoh dia menemui Ceng Ceng di kamar gadis itu.
“Kau tidak boleh pergi...!” begitu memasuki kamar itu Tek Hoat berseru.
Ceng Ceng yang tadinya duduk termenung itu, kini meloncat bangun. Mukanya yang tadinya pucat menjadi agak merah karena perasaan marah menyelinap dalam hatinya. Dia berdiri menentang wajah pemuda itu dan menjawab dengan ketus, “Ada hak apa engkau melarang aku pergi?”
“Ada hak apa? Hemm, lupakah kau bahwa aku ini kakakmu, bahwa kita ini seayah? Kau tidak boleh pergi dalam keadaan begini!”
“Dalam keadaan bagaimana?”
“Kau sedang mengalami kedukaan, kau bisa jatuh sakit di jalan. Dan sudah menjadi kewajibanku sebagai saudara untuk menjaga dan melindungimu, aku akan berusaha untuk menggembirakan hatimu, menghiburmu...”
“Dengan sikapmu yang keras dan selalu memusuhiku itu? Hemm, Tek Hoat, agaknya engkau mengandalkan kepandaianmu dan mengandalkan kedudukanmu sekarang, maka kau hendak memaksaku. Kau kira aku mau tunduk begitu saja? Kau boleh bunuh aku sekarang juga, aku tetap hendak pergi besok pagi. Ingin kulihat kau bisa berbuat apa!” Ceng Ceng menantang, berdiri dengan kedua tangan dikepal.
“Kau... kau keras kepala!” Tek Hoat menegur, kedua tangannya juga dikepal.
Mereka berhadapan seperti dua orang musuh bebuyutan (musuh besar turun-temurun) yang hendak mengadu nyawa. Akhirnya setelah beberapa lama mereka saling pandang dengan sinar mata berapi, Tek Hoat menurunkan kembali tangannya dan menarik napas panjang. Kemudian dia berkata lirih setelah menghela napas lagi.
“Ceng Ceng, kau tidak tahu... biarlah selagi masih ada kesempatan aku akan mengaku semuanya kepadamu. Semenjak kita saling berjumpa dahulu, ketika aku menolongmu dari air sungai, timbul rasa suka yang aneh dan mendalam di dalam hatiku terhadap dirimu. Cobalah kau ingat-ingat, kalau tidak begitu, mana mungkin aku membiarkan engkau menguasai aku hanya dengan sumpah dan sapu tangan, bahkan aku rela pula menghambakan diri menjadi pembantumu ketika kau diangkat menjadi bengcu! Andai kata di dunia ini tidak ada Syanti Dewi yang lebih dulu telah menjatuhkan hatiku, yang telah kucinta sejak pertemuan pertama, agaknya... aku tidak akan ragu lagi bahwa aku tentu akan jatuh cinta kepadamu. Sejak dahulu ada getaran perasaan yang mengikat hatiku kepadamu, tidak tahu bahwa sesungguhnya engkau masih sedarah dengan aku. Engkau adikku... di dunia ini hanya ada seorang adik bagiku...”
“Hemm, kakak macam apa engkau ini yang selalu bersikap keras kepadaku.” Akan tetapi suara teguran Ceng Ceng itu mengandung getaran keharuan karena memang dia terharu sekali mendengar pengakuan Tek Hoat itu. Teringat dia betapa dahulu pun hampir saja dia jatuh cinta kepada pemuda ini dan di sudut hatinya memang selalu ada rasa suka terhadap Tek Hoat seperti yang diakui pula oleh pemuda itu. Ternyata pertalian darah itulah yang menimbulkan getaran itu.
“Memang, kita sama-sama keras kepala, Adikku. Agaknya inilah yang diwariskan oleh mendiang ayah kita yang kabarnya amat jahat itu. Kita berdua adalah keturunan orang yang jahat... akan tetapi hanya aku yang mewarisi kejahatannya, sedangkan engkau adalah seorang gadis yang gagah perkasa dan berbudi mulia. Akan tetapi kenapa justru engkau yang menderita kesengsaraan sedangkan aku berenang dalam kebahagiaan? Tidak! Engkau tidak boleh menderita kalau aku berbahagia. Adikku, Ceng Ceng... aku minta, aku mohon kepadamu, jangan kau pergi, Adikku...” Terdorong oleh rasa harunya, Tek Hoat pemuda yang berhati baja itu kini menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Ceng Ceng!
“Tek Hoat...” Ceng Ceng juga berlutut dan seperti digerakkan oleh tenaga gaib, kedua orang saudara tiri seayah ini saling rangkul dan untuk beberapa lamanya Ceng Ceng menangis di atas dada saudaranya.
Akan tetapi kekerasan hatinya timbul pula dan dia lalu bangkit berdiri, menyusut air matanya. “Tek Hoat, aku pun tidak pernah dapat membencimu. Terima kasih atas kebaikanmu kepadaku. Akan tetapi engkau tentu tahu, dalam keadaan seperti sekarang ini, aku membutuhkan ketenangan dan keheningan, aku harus pergi menyendiri, entah ke mana. Percayalah, kalau aku tidak mati, dan kalau luka di hati ini sudah tidak parah lagi, engkaulah satu-satunya orang yang akan kucari sebagai keluargaku.”
Tek Hoat menghela napas panjang dan juga bangkit berdiri. Dia telah mengenal bagai mana sifat Ceng Ceng yang amat keras. Seperti baja yang tak dapat ditekuk lagi. “Kalau begitu, aku hanya dapat ikut prihatin dan akan selalu mendoakan, Adikku.”
Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ceng Ceng berangkat pergi sebelum ada yang bangun dari tidurnya. Tentu saja dengan mudah dara ini keluar dari istana, juga dengan mudah keluar dari pintu gerbang sebelah timur karena para prajurit yang menjaga semua mengenal adik angkat Puteri Bhutan ini.
Dengan muka pucat dan pandang mata kosong Ceng Ceng keluar dari pintu gerbang tanpa menengok lagi. Langsung dia melanjutkan perjalanan dengan langkah-langkah perlahan maju ke depan tanpa tujuan karena pikirannya kosong dan semangatnya seperti telah terbang meninggalkan tubuhnya.
Belum jauh dia meninggalkan pintu gerbang timur, tiba-tiba ada suara memanggilnya, “Sumoi...!”
Ceng Ceng menghentikan langkahnya, berdiri lesu tanpa menoleh karena dia mengenal suara itu, suara Panglima Jayin, yang juga merupakan suheng-nya karena panglima ini pernah berguru kepada kakeknya.
Ketika Jayin tiba di depannya, Ceng Ceng berkata lesu, “Suheng, harap kau jangan ikut-ikut menahanku karena sudah bulat tekadku untuk pergi dan tak seorang pun boleh menahanku.”
“Sumoi, aku sama sekali tidak akan menahan dan mencampuri urusan pribadimu. Aku menyusulmu karena aku diutus oleh Sang Puteri Syanti Dewi. Beliau mengutus aku mengejarmu dan memanggilmu kembali karena tadi malam ada seorang tamu yang datang ke istana mencarimu. Akan tetapi karena hari telah malam, terpaksa kusuruh tamu itu bermalam di gedung tamu dan menunggu sampai pagi. Baru pagi tadi aku dapat menghadap Sang Puteri untuk menyampaikan permintaan tamu yang hendak menjumpai mu itu. Akan tetapi pagi-pagi sekali engkau sudah pergi, maka Sang Puteri mengutus aku untuk menyusul dan memanggilmu kembali ke Istana.”
“Suheng, aku tidak ingin bertemu dengan siapa pun juga. Engkau kembalilah dan katakan kepada Enci Syanti Dewi bahwa aku tidak mau menemui siapa pun.”
“Akan tetapi, Sumoi... engkau belum tahu siapa tamu itu!” Suara panglima ini tergetar karena dia pun sudah mendengar akan keadaan sumoi-nya itu dari Puteri Syanti Dewi. “Dia telah datang menyusul bersamaku. Inilah dia orangnya!”
Akan tetapi Ceng Ceng tidak mempedulikan kata-kata ini dan dia terus melanjutkan langkahnya. Siapa pun orangnya yang datang mencarinya, dia tidak ingin melihat dan menemuinya. Tanpa menoleh sedikit pun, Ceng Ceng melangkah terus, sama sekali tidak mempedulikan.
Baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba terdengar suara, “...bengcu...!”
Ceng Ceng berhenti seperti disambar petir dan dia berdiri tegak, mukanya pucat, kedua kakinya menggigil dan dia tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Dia tidak berani menoleh, karena tentu pendengarannya yang menipunya dan kalau dia menoleh, dia akan kecewa. Tidak mungkin! Tapi suara yang didengarnya tadi amat dikenalnya, terlalu dikenalnya malah, karena suara itu adalah suara Topeng Setan!
“Bengcu...!” Suara itu memanggil lagi, kini terdengar tergetar.
Untuk kedua kalinya Ceng Ceng tersentak kaget. Dia menoleh dan....
“Ouhhhhhh...!” dia menutupi mulut dengan punggung tangan kiri, menahan jeritnya.
Betapa kagetnya ketika dia melihat laki-laki yang berlutut di depannya itu, laki-laki yang melihat pakaian dan lengan kirinya, jelas adalah Topeng Setan, akan tetapi melihat wajahnya yang tidak tertutup topeng itu, wajah yang tampan dan gagah sekali sungguh pun pada saat itu kelihatan pucat dan dicekam perasaan khawatir, adalah wajah Kok Cu, pemuda yang telah memperkosanya.
“Kau...? Kau...?” Hati Ceng Ceng menjerit, akan tetapi bibirnya hanya bergerak-gerak dan mulutnya terbuka tanpa ada suara yang keluar, kemudian terdorong oleh kedua kakinya yang tiba-tiba menjadi lemas seperti lumpuh dan keterkejutan yang meremas hatinya, Ceng Ceng menjatuhkan diri berlutut dan menubruk orang itu sambil merintih dan menangis.
“Kau... kau... masih hidup..., ohhh, kau masih hidup...?” berulang-ulang dia berbisik seperti dalam mimpi ketika dia mendekapkan mukanya di atas dada yang bidang itu.
“Suhu menolong dan menyembuhkan aku...,” bisik Topeng Setan atau Kok Cu itu.
“...ahhh... hu-huuu-huukk... aku... aku girang sekali... aku... aku cinta padamu, Pam...” Ceng Ceng tiba-tiba menghentikan kata-katanya, tidak melanjutkan sebutan ‘paman’ tadi karena dia segera teringat dan cepat dia mengangkat mukanya.
Begitu melihat wajah tampan itu, dia berseru, “Ohhhh...!” dan merenggutkan tubuhnya menjauh.
Sementara itu, begitu Ceng Ceng tadi merangkul ‘tamu’ itu, Panglima Jayin sudah melangkah pergi dan memberi isyarat kepada para penjaga untuk pergi menjauh, lalu memasuki pintu gerbang dan membiarkan kedua orang itu bicara dengan leluasa. Senyum penuh rasa syukur membayang di wajah panglima gagah itu.
“Aku bukan Topeng Setan lagi...” Pemuda itu berkata. “Aku adalah Kao Kok Cu, aku adalah si pemuda laknat dan aku datang untuk menerima hukuman, Ceng Ceng. Semenjak peristiwa terkutuk yang terjadi di goa, aku selalu dikejar oleh dosa dan penyesalan. Apa lagi ketika aku mendengar bahwa engkau adalah penyelamat nyawa Ayah, aku makin menyesal, maka untuk menebus dosa dan untuk membalas budimu terhadap Ayah, aku kemudian menjadi Topeng Setan yang selalu melindungi dan membelamu. Sekarang, rahasiaku telah kau ketahui, maka aku datang untuk menerima hukuman. Kalau kau hendak membunuhku, lakukanlah, aku tidak akan menyesal mati di tanganmu, Ceng Ceng, karena aku akan mati di tangan seorang yang paling kucinta di dunia ini, yang paling kuhormati, kukagumi dan kujunjung tinggi.”
Ceng Ceng yang masih menggigil seluruh tubuhnya itu, mengeluh dan dia kembali menubruk, merangkul karena memang perasaan bahagia melihat ‘Topeng Setan’ masih hidup mengusir semua perasaan lain. “Paman... Paman... melihat engkau masih hidup, aku... ahhh, betapa bahagia rasa hatiku.” Dia berkata dan kembali dia lupa akan wajah tampan itu, merasa bahwa dia berada dalam pelukan Topeng Setan. “Melihat engkau mati, baru aku tahu bahwa aku cinta padamu, Paman, dan aku tidak ingin lagi terpisah darimu...”
“Ceng Ceng, janganlah menyebutku Paman... Engkau isteriku sayang... engkau sudah kuanggap isteriku sejak aku mengenakan topeng... Betapa bahagia hatiku mendapat pengakuan cintamu...”
Ceng Ceng merangkul dan menatap wajah itu, wajah tanpa topeng yang ternyata amat tampan dan gagah. Wajah yang semenjak peristiwa di goa itu tidak pernah dapat dilupakannya! Kok Cu yang melihat wajah jelita basah air mata itu, tergerak hatinya, penuh keharuan, penuh iba dan penuh kemesraan cinta, maka dia menunduk dan di lain saat dia sudah mencium mulut yang setengah terbuka itu, menciumnya dengan seluruh perasaan kasih sayang yang terluap dari lubuk hatinya, melalui bibirnya.
Sejenak Ceng Ceng terlena dan memejamkan mata, otomatis perasaan bahagia dan kasih sayang dari hatinya membuat kedua lengannya melingkari leher pemuda itu dan bibirnya pun bergerak menyambut. Akan tetapi tiba-tiba terbayang peristiwa di dalam goa. Mulutnya yang melekat pada mulut Kok Cu meronta, matanya terbelalak dan dia merenggutkan dirinya.
Kok Cu memandangnya dengan mata terbelalak penuh kekhawatiran.
“Plak! Plakk!”
Dua kali kedua tangan Ceng Ceng bergerak dan nampaklah garis-garis merah di kedua pipi Kok Cu yang pucat. Pemuda itu tersenyum.
“Terima kasih dan pukulan-pukulanmu barusan baik sekali, merupakan obat yang akan menyembuhkan penyesalanku. Kau pukullah lagi, Ceng Ceng. Sudah kukatakan bahwa aku siap menebusnya dengan kematian sekali pun...”
“Ouhhh... tidak... tidak...!” Ceng Ceng kembali merangkul. Kini dia memandangi wajah tampan itu dan jari-jari kedua tangannya mengelus dan membelai bekas tamparannya di kedua pipi pemuda itu. “Tidak... kau... kau adalah orang satu-satunya di dunia ini yang kucinta... kau adalah Topeng Setan yang telah melimpahkan budi kepadaku...”
“Akan tetapi aku juga pemuda laknat yang telah memperkosamu, Ceng Ceng.”
“Tidak... tidak...! Pada waktu itu engkau dalam pengaruh racun... peristiwa itu adalah kesalahanku sendiri. Engkau sudah berusaha mencegah aku membebaskan mu dari kerangkeng... dan engkau sudah berusaha sekuat tenaga mencegah, akan tetapi racun itu lebih kuat... tidak, engkau tidak bersalah...”
Wajah yang tampan dan gagah itu berseri. Tiba-tiba Kok Cu berdiri dan dengan satu tangannya yang luar biasa kuatnya itu, sekali angkat dia sudah mengangkat Ceng Ceng sehingga gadis ini berdiri pula. Wajah yang tampan itu menjadi kemerahan, matanya bersinar-sinar penuh kebahagiaan. “Kalau begitu... kau mengampuni aku...?”
“Tidak ada ampun karena kau tidak bersalah.”
“Aku berdosa dan aku mengharapkan ampunmu, Ceng Ceng.”
“Kalau begitu, aku mengampunimu, Pam... eh, Koko (Kakanda)...”
“Dan kau tidak membenci lagi kepada Kok Cu?”
Sambil merangkul leher pemuda itu, dan matanya masih mengalirkan air mata, Ceng Ceng tersenyum dan menggeleng kepala. “Sebaliknya malah, aku mencinta orang yang bernama Kok Cu.”
“Moi-moi...!”
“Koko...!”
Kembali mereka berdekapan dan sekali ini ketika Kok Cu mencium Ceng Ceng, dara itu menyambut dan membalasnya dengan penuh kemesraan. Dekapan dan ciuman itu seolah-olah menjadi tempat pencurahan seluruh perasaan mereka, rasa cinta, rasa rindu, dan semua kebahagiaan yang terasa di hati masing-masing sehingga mereka seolah-olah tidak ingin saling melepaskan lagi.
“Ceng Ceng, Moi-moi... betapa bahagia hatiku... ketahuilah, aku datang bersama Ayah. Selain menyusulmu, juga Ayah membawa tugas dari Kaisar untuk menyampaikan selamat kepada Kerajaan Bhutan, juga untuk menyatakan keampunan Kaisar terhadap Puteri Milana. Selain itu pula... juga Ayah akan meminangmu secara resmi... marilah, sayang, mari kita kembali ke istana Bhutan...”
Tiba-tiba Ceng Ceng melepaskan dirinya dari rangkulan lengan kanan kekasihnya, dan sambil tersenyum di antara air matanya, dengan kedua pipi merah, dia menggeleng. “Tidak... aku tidak mau kembali...” Dan dia pun membalikkan tubuhnya dan lari.
“Ehh, Ceng Ceng...!” Kok Cu mengejar dan kalau saja dia mau tentu dengan mudah dia dapat menyusul larinya gadis itu. Akan tetapi melihat kekasihnya itu lari sambil tersenyum, dia sengaja mengejar dari belakang dan berteriak, “Kenapa kau tidak mau?”
“Aku malu...!” Ceng Ceng berlari terus, memasuki sebuah hutan kecil.
Akhirnya Ceng Ceng memperlambat larinya dan membiarkan dirinya disusul, ditangkap dan dipeluk di bawah sebatang pohon besar. Dia menyerah dan menyambut ketika pemuda itu kembali menciuminya sampai keduanya gelagapan kehabisan napas. Akhirnya mereka duduk di bawah pohon, di atas rumput tebal dan hijau.
“Ceng-moi, kenapa kau malu?”
“Aku tidak ingin kembali ke sana, tidak ingin... sementara ini menemui orang-orang lain, aku khawatir kebahagiaanku akan terganggu. Aku ingin berdua saja denganmu, Koko, kalau bisa, berdua saja di dunia ini, tidak akan saling terpisah lagi... Koko, ah, Koko... aku masih belum percaya... apakah aku tidak sedang mimpi...?”
“Ceng-moi, kau kekasihku, kau pujaan hatiku, kau isteriku... apakah ini mimpi?” Dia mencium dan menggigit leher Ceng Ceng sampai dara itu terpekik halus. “Aku sendiri pun hampir tidak percaya bahwa engkau dapat mengampuni aku, apa lagi mencintaku! Aku selalu merasa ngeri untuk menghadapi pertemuan ini... tidak ada kengerian yang lebih hebat dari pada melihat engkau membenci aku... bayangkan saja betapa sengsara hatiku sebagai Topeng Setan ketika engkau menyatakan betapa hebatnya kebencianmu kepada Kok Cu...”
Sambil menyandarkan kepalanya di atas dada yang bidang itu, dan memainkan jari-jari tangan kanan Kok Cu yang dia tarik ke atas dadanya, Ceng Ceng berkata, suaranya manja. “Siapa sih yang membenci Kok Cu? Aku membencinya karena dia... menghilang begitu saja setelah peristiwa itu...! Aku benci karena dia tidak muncul lagi, padahal dia kuharap-harapkan... padahal hatiku sudah jatuh cinta begitu aku melihat dia di dalam kerangkeng itu...!”
“Tapi kau... kau mencinta Topeng Setan!” Kok Cu menggoda.
Ceng Ceng menarik lengan baju kiri yang kosong itu dan mencium lengan baju itu. “Mengapa tidak? Topeng Setan telah mengobankan lengannya, bahkan beberapa kali hampir berkorban nyawa untukku. Aku mencinta Topeng Setan karena budinya, tanpa mempedulikan bagaimana macamnya wajah di balik topeng, tanpa mempedulikan usianya, akan tetapi aku mencinta Kok Cu karena pribadinya, karena tatapan sinar matanya, karena... karena memang aku cinta dan sebabnya aku tidak tahu!”
“Hemm..., kalau begitu engkau mencinta dua orang! Hayo, katakan, siapa yang lebih kau cinta, Kok Cu atau Topeng Setan?” pemuda itu menuntut, pura-pura cemberut.
Ceng Ceng membalikkan tubuhnya, tertawa geli. “Kau cemburu? Hi-hik, lucunya! Kau cemburu kepada siapa?”
Dengan muka dibuat seperti marah Kok Cu berkata, “Tentu saja kepada Topeng Setan! Hayo katakan, kau lebih mencinta Kok Cu atau Topeng Setan?”
“Ya ampun... tentu saja aku lebih mencinta Kok Cu!”
Tiba-tiba Kok Cu mengeluarkan sebuah topeng dan sekali bergerak, topeng itu telah dipakai di mukanya dan berubahlah ia menjadi Topeng Setan, suaranya pun agak berubah karena terhalang topeng. “Bagus, Ceng Ceng...! Jadi cintamu kepadaku palsu, ya? Jadi kau lebih cinta kepada pemuda laknat itu dari pada kepadaku?”
Sambil menahan gelinya, Ceng Ceng pun berkata, “Siapa bilang, Paman? Aku cinta padamu, Paman Topeng Setan!”
Kok Cu membuang topengnya dan sambil memegang dagu yang runcing itu, dijepit antara telunjuk dan ibu jarinya, mengangkat muka Ceng Ceng menengadah, dia lalu menghardik, “Perempuan tamak! Sebetulnya kau lebih mencinta yang mana?”
“Aku cinta keduanya, dan cintaku itu kini menjadi satu, tiada bandingannya lagi, dan... ehmmm...” Ceng Ceng tidak dapat melanjutkan kata-katanya lagi karena mulutnya telah ditutup oleh sepasang bibir yang seolah-olah tidak akan ada puas-puasnya itu. Dia memejamkan matanya, menyambut dengan hati terbuka dan penuh penyerahan.
Angin semilir di atas mereka, membuat daun-daun pohon berkeresekan saling sentuh seperti saling berbisik membicarakan pertemuan asyik-masyuk penuh kemesraan di bawah pohon besar itu. Bagi Ceng Ceng dan Kok Cu, waktu dan segala sesuatu lenyap, bahkan diri pribadi juga lenyap, yang ada hanyalah kebahagiaan dan keindahan. Hidup adalah bahagia, hidup adalah indah.
Hanya sayang sekali, hanya sewaktu-waktu saja, hanya selewat saja, dalam keadaan seperti yang dialami oleh Ceng Ceng dan Kok Cu, kita mengenal kebahagiaan dan keindahan itu. Selebihnya, waktu dalam hidup kita penuh dengan pertentangan, penuh dengan kebencian, iri hati, angkara murka yang kesemuanya itu hanya mendatangkan kesengsaraan belaka.
Adakah yang lebih indah dari pada cinta? Sayang, betapa cinta oleh kita telah dipecah-belah, ditafsirkan menurut kecondongan hati yang menyenangkan sehingga timbul bermacam pendapat dan kesimpulan. Cinta bukanlah sex semata, bukanlah kewajiban semata, bukanlah pengorbanan semata, bukanlah pemberian atau permintaan semata.
Kesemuanya itu terdapat dalam cinta dan cinta mencakup segala karena cinta hanya terisi keindahan. Cinta tidak mengenal perbedaan suku, tidak mengenal perbedaan ras, tidak mengenal perbedaan bangsa, tidak mengenal perbedaan usia, tidak mengenal kaya atau miskin, pintar atau bodoh, tidak mengenal tingkat tinggi atau rendah. Cinta tak mengenal kebencian, tak mengenal permusuhan, tidak mementingkan diri pribadi. Cinta adalah kebahagiaan. Tanpa cinta matahari akan kehilangan sinarnya, bunga kehilangan keharumannya, dan manusia kehilangan kemanusiaannya.
Oleh karena itu, segala macam gerak yang kita perbuatan tanpa di dasar cinta kasih adalah palsu belaka. Ada pun yang kita lakukan di dunia ini barulah benar dan suci apabila didasari oleh cinta kasih di dalam hati sanubari kita.
EPISODE SELANJUTNYA JODOH RAJAWALI